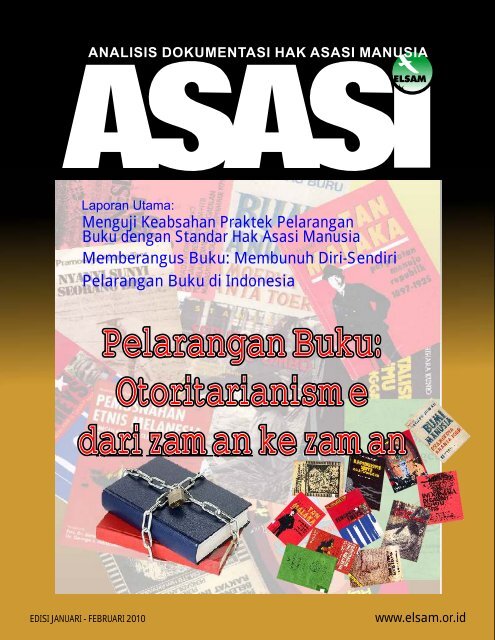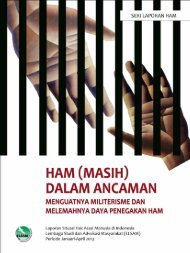Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam
Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam
Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Menguji Keabsahan Praktek Pelarangan<br />
Buku dengan Standar Hak <strong>Asasi</strong> Manusia<br />
Memberangus Buku: Membunuh Diri-Sendiri<br />
Pelarangan Buku di Indonesia<br />
Pelarangan Buku:<br />
Otoritarianisme<br />
dari zaman ke zaman<br />
EDISI JANUARI - FEBRUARI <strong>2010</strong><br />
www.elsam.or.id
daftar isi<br />
editorial 04<br />
Bubur Kertas<br />
Demokrasi pasca Orde Baru belum mengubah hubungan negara<br />
dan masyarakat. Keberagaman budaya dan kecerdasan pikiran<br />
belum jadi sumber kekuatan politik bangsa. Kita pun masih<br />
mendaur ulang kebijakan kolonial.<br />
Pelarangan terbitnya buku-buku merupakan bentuk<br />
pengingkaran terhadap demokrasi,dan pelanggaran<br />
hak asasi manusia (dok elsam).<br />
Kolom<br />
internasional<br />
Komisi HAM ASEAN,<br />
Akhirnya Datang juga!<br />
20-21<br />
ASEAN Intergovernmental Commission on<br />
Human Rights (AICHR) menjadi penting<br />
sebagai salah satu usaha dalam proses<br />
membangun komunitas ASEAN, sebagai<br />
sebuah kendaraan yang progresif dalam<br />
pembangunan sosial dan keadilan,<br />
pemenuhan kehormatan manusia dan<br />
pencapaian kualitas hidup yang lebih tinggi<br />
dari masyarakat ASEAN.<br />
resensi<br />
22-23<br />
Bebas dari Penyiksaan:<br />
Perjalanan Masih Panjang<br />
profil elsam 24<br />
laporan utama 5 - 13<br />
Menguji Keabsahan Praktek Pelarangan<br />
Buku dengan Standar Hak <strong>Asasi</strong> Manusia<br />
Keberlangsungan praktek pelarangan buku setelah sebelas<br />
tahun digulirkannya reformasi membawa sejumlah pertanyaan<br />
kritis atas komitmen penegakan dan perlindungan hak asasi<br />
manusia.<br />
Memberangus Buku: Membunuh Diri-Sendiri<br />
Memusnahkan buku umumnya disandingkan juga dengan<br />
sejenis hasrat totalitarianisme. Suatu hasrat untuk melakukan<br />
monopoli terhadap ruang kosong pemaknaan. Hasrat untuk<br />
meniadakan kontestan lain terhadap suatu tafsir, sehingga bisa<br />
menjadi kebenaran tunggal, dan satu-satunya pandangan hidup<br />
dan pegangan warga.<br />
Pelarangan Buku di Indonesia<br />
Mengapa buku harus dilarang? Apa kesalahan dan alasannya?<br />
Bagaimana prosesnya hingga sebuah buku harus dilarang?<br />
Dan, apakah keputusan pelarangan itu lahir dari proses yang<br />
adil, melalui pengadilan? Sejauh mana hukum dan pengadilan<br />
menjadi acuan dalam seluruh proses pelarangan ini?<br />
perspektif 14-16<br />
Seratus Hari SBY: Mengulang Periode Lalu,<br />
Jaminan HAM Hanya Normatif<br />
Persoalan hak asasi manusia (HAM) hanya mengedepankan<br />
jaminan normatif dengan diproduksinya regulasi yang kaya<br />
dengan perlindungan hak asasi manusia, namun miskin dalam<br />
implementasinya.<br />
daerah 17-19<br />
Perda Gerbang Marhamah Cianjur:<br />
Mengikat Tanpa Tali<br />
Beberapa berita mengejutkan muncul dari salah satu kabupaten di<br />
Propinsi Jawa Barat. Dugaan korupsi, penyimpangan dana bantuan<br />
sosial, perempuan pekerja seksual yang beroperasi di Cianjur yang<br />
berjumlah 1.200 orang, dan jumlah pelanggan PSK yang sekitar<br />
6.000 orang. Semua data tersebut mengemuka justru di saat<br />
kabupaten ini sedang gegap dengan identifikasi dirinya sebagai kota<br />
yang mengedepankan akhlaqul karimah dalam seluruh kehidupan<br />
masyarakatnya.
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
pameran<br />
w w w . e l s a m . o r . i d<br />
Redaksional<br />
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:<br />
Agung Putri<br />
Wakil Pemimpin Redaksi:<br />
Amiruddin al Rahab<br />
Redaktur Pelaksana:<br />
Atnike Nova Sigiro<br />
Para pembaca Buletin ASASI<br />
yang kami hormati,<br />
Dewan Redaksi:<br />
Agung Putri, Amiruddin al Rahab, Atnike<br />
Nova Sigiro, Indriaswati Dyah<br />
Saptaningrun, Otto Adi Yulianto<br />
Redaktur:<br />
Atnike Nova Sigiro, Betty Yolanda,<br />
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana<br />
Dyah, Wahyu Wagiman<br />
Sekretaris Redaksi:<br />
Triana Dyah<br />
Sirkulasi/Distribusi:<br />
Khumaedy<br />
Desain & Tata Letak:<br />
alang-alang<br />
Penerbit:<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat<br />
(ELSAM)<br />
Alamat Redaksi:<br />
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar<br />
Minggu, Jakarta 12510,<br />
Telepon: (021) 7972662, 79192564<br />
Faximile: (021) 79192519<br />
E-mail:<br />
office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id<br />
Website:<br />
www.elsam.or.id.<br />
Redaksi senang menerima tulisan, saran,<br />
kritik dan komentar dari pembaca. Buletin<br />
ASASI bisa diperoleh secara rutin.<br />
Kirimkan nama dan alamat lengkap ke<br />
redaksi. Kami juga menerima pengganti<br />
biaya cetak dan distribusi berapapun<br />
nilainya. Transfer ke rekening<br />
ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar<br />
Minggu No. 127.00.0412864-9<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Pameran akan diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, mural,<br />
pertunjukan musik dll.<br />
ELSAM bekerjasama dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia, Ruang Rupa,<br />
Grafis Sosial Indonesia & Dewan Kesenian Jakarta<br />
Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat<br />
dikirimkan via email di bawah ini:<br />
asasi@elsam.or.id<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
03
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
editorial<br />
eorang teman baik bercerita,<br />
suatu kali di tahun<br />
60-an Pramoedya Ananta<br />
Toer dihibahi satu peti Sdokumen dari seorang pegawai<br />
Dinas Pendidikan yang kala itu<br />
berkantor di Jalan Kimia, Jakarta<br />
Pusat. Peti diusung ke rumah dan<br />
bagai harta karun begitu dibuka,<br />
isinya tumpukan dokumen asli<br />
laporan intelijen pemerintah<br />
kolonial Hindia Belanda (PID).<br />
Terkuaklah rahasia intelijen<br />
memata-matai partai politik dan<br />
gerak kaum Indisch. Sayang<br />
dokumen bersejarah itu dibakar<br />
tanggal 13 Oktober 1965 saat<br />
tentara dan massa menyerbu<br />
rumahnya. Pram benar-benar<br />
terguncang mendengar dokumen<br />
itu lembar demi lembar dijilat api.<br />
Sesungguhnya sejak itu dia tidak<br />
pernah sembuh dari keguncangan<br />
tersebut. Hanya mengandalkan<br />
ingatan atas dokumen dan atas<br />
'jasa baik' Jendral Sumitro tahun<br />
1977 yang meng'hadiah'i Pram<br />
mesin tik -sekalipun mesin itu tak<br />
pernah diterimanya- sekaligus ijin<br />
mengetik, “Bumi Manusia” lahir,<br />
Minke hadir hingga di buku keempat<br />
“Rumah Kaca”.<br />
Naskah ketik beredar dari unit<br />
ke unit di Pulau Buru, berlayar<br />
mengarungi laut Jawa dari Pulau<br />
Buru kembali ke Jawa. Mendarat di<br />
Nusa Kambangan, berpindah ke<br />
Rutan Salemba, naskah selamat<br />
tiba di rumah. Bersama Joesoef<br />
Isak dan Hasjim Rachman,<br />
sahabatnya, Pram mendirikan<br />
penerbit 'Hasta Mitra' dengan versi<br />
Belandanya 'Manus Amici', dan<br />
menerbitkan naskah tersebut<br />
sebagai serial “Karya Pulau Buru”<br />
tahun 1980. Malang tak henti<br />
merundung. Jaksa Agung kembali<br />
hadir dalam kehidupan kepengarangan<br />
Pram. Kali ini dia datang<br />
untuk melarang peredarannya dan<br />
menginterogasi Pram, Joesoef dan<br />
Hasjim. Jejak Pak Jaksa diikuti oleh<br />
komandan Kodim Yogyakarta. Atas<br />
perintahnya, satuan intelijen dan<br />
militer menangkap Bonar Tigor<br />
Naipospos, Bambang Isti dan<br />
Subono, menyiksa dalam interogasi.<br />
Mereka diadili dan diganjar<br />
hingga 8 tahun oleh hakim<br />
Bubur Kertas<br />
Pengadilan Negeri. Kesalahan<br />
mereka adalah melawan larangan<br />
Jaksa Agung menjual buku Pram.<br />
Kisah dokumen intelijen belum<br />
lagi jadi sejarah. Perintah melarang<br />
peredaran buku tetap bergema<br />
hingga hari ini. Soalnya tak berhenti<br />
pada sifat rezim yang lalim. Benar<br />
Yoga Sugama Kepala Staf<br />
Kopkamtib 1978, pernah berkata<br />
“… the position was given to me has<br />
never had any precedent in any<br />
country, not before. The precedent<br />
was during himmler's time and was<br />
given by Himmler (sic) (seharusnya<br />
Hitler, pen)…” (Tapol, 1979). Tetapi<br />
memasuki koridor pembangunan<br />
bangsa dan modernisasi sejak<br />
tahun 50-an, tak pelak buku duduk<br />
di kederajatan politik tinggi. Seruan<br />
“mencerdaskan kehidupan bangsa”<br />
menjadi ambisi mewujudkan apa<br />
yang disebut Partha Chatterjee<br />
(2004) sebagai bangsa yang<br />
homogen, tak berwajah, tak berdimensi<br />
waktu. Kekal, berstandar dan baku.<br />
D e m i p o l i t i k k e b a n g s a a n ,<br />
pelarangan buku berurusan dengan<br />
perang dingin. Putusnya hubungan<br />
diplomatik dengan Cina dilengkapi<br />
rezim Orde Baru dengan melarang<br />
penggunaan aksara Cina dalam<br />
barang cetakan dan non-cetakan.<br />
Selain Jaksa Agung, Departemen<br />
Pendidikan, Departemen Agama,<br />
bahkan Departemen Perdagangan,<br />
Dirjen Pers dan Grafika, dikerahkan<br />
untuk mengawasi buku.<br />
Di sini juga berlangsung<br />
mistifikasi pelarangan buku. Misi<br />
pembersihan dosa, demikian Jaksa<br />
Agung memuliakan kedudukannya,<br />
dengan tugas kebangsaan yang<br />
pamungkas yaitu memusnahkan<br />
buku. Penghancuran candi, penggulingan<br />
ke laut arca-arca pemujaan<br />
yang dipandang berhala, penghancuran<br />
kerajaan Hindu terakhir, hidup<br />
kembali 500 abad kemudian.<br />
Membakar buku. Padahal tak<br />
sebarispun perundangan memaklumkan<br />
kuasa memusnahkan.<br />
Pernah dikerahkan massa untuk<br />
m e m b u m i h a n g u s k a n b u k u .<br />
Mulanya tim penelaah buku<br />
bergerak menelusuri peredaran<br />
buku hingga ke daerah. Hasilnya,<br />
tak lebih dari 1 bulan 2000 buah<br />
b u k u d i m u s n a h k a n d a l a m<br />
pergolakan politik 45 tahun lalu.<br />
Membakar buku menjadi atraksi<br />
publik mencekam, gigantis, ritualistik<br />
yang diliput media. Hukuman mati<br />
bagi kebudayaan.<br />
Penghangusan gagasan menantang<br />
mereka yang berseberangan:<br />
bahwa pelarangan buku<br />
adalah tindakan paripurna, tak bisa<br />
dicabut apapun situasi politik dan<br />
seberapapun tinggi tingkat kecerdasan<br />
masyarakat. Ini lebih dari<br />
yang diatur dalam PNPS No. 4/<br />
1963. Ketika publik mengecam<br />
betapa tidak beradabnya pembakaran<br />
buku, Jaksa Agung segera<br />
membuatnya tampak 'beradab'.<br />
Teknologi daur ulang, ikon generasi<br />
ketiga gerakan hak asasi manusia<br />
dengan ide pembangunan berkelanjutan<br />
dan penyelamatan lingkungan,<br />
menjalankan perintah mendaur.<br />
Para wartawan kembali diundang<br />
bukan untuk melihat tumpukan abu<br />
sisa bakar melainkan bubur kertas.<br />
Tak ada pasalnya penulis atau<br />
penerbit punya hak membela diri.<br />
Entah buku Yoshihara Kunio<br />
,“Kapitalisme Semu di Asia<br />
Tenggara” atau Harry Poeze tentang<br />
Tan Malaka, Jaksa Agung telah<br />
menjadikannya bubur kertas.<br />
Demokrasi pasca Orde Baru<br />
belum mengubah hubungan negara<br />
dan masyarakat. Keberagaman<br />
budaya dan kecerdasan pikiran<br />
belum jadi sumber kekuatan politik<br />
bangsa. Kita pun masih mendaur<br />
ulang kebijakan kolonial. Dari<br />
haatzaai artikelen dalam wetboek<br />
van Strafrecht, persbreidelordonnantie,<br />
staat van oorlog en beleg<br />
ordonnantie menjadi KUHP, PNPS<br />
No 4 1963 dan menjadi UU No<br />
4/PNPS/1963. Demokrasi ini<br />
bertabur pujian dari berbagai<br />
b e l a h a n d u n i a s e m e n t a r a<br />
pengendalian pikiran selangkah<br />
demi selangkah dilakukan. Apa<br />
boleh buat kertas sudah menjadi<br />
bubur.<br />
Agung Putri<br />
Direktur Eksekutif<br />
04<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
Oleh Indri D. Saptaningrum<br />
(Deputi Program ELSAM)<br />
laporan utama<br />
Menguji Keabsahan<br />
Praktek Pelarangan Buku<br />
dengan Standar Hak <strong>Asasi</strong> Manusia<br />
i penghujung tahun<br />
2009, publik kembali<br />
diramaikan dengan<br />
keputusan Kejaksaan DAgung RI yang melarang<br />
peredaran lima buku, di antaranya<br />
buku Dalih Pembunuhan Massal<br />
karya John Rossa yang diterbitkan<br />
oleh Institut Sejarah Sosial<br />
Indonesia (ISSI) dan Enam Jalan<br />
Menuju Tuhan karya Darmawan<br />
MM. Tindakan ini segera<br />
mengundang kecaman dari<br />
masyarakat dan kelompok Ornop,<br />
seperti tampak dalam pernyataan<br />
sikap dan keprihatinan dari<br />
sejumlah besar tokoh masyarakat<br />
seperti Adnan Buyung Nasution,<br />
Ade Rostina Sitompul, dll. Selain<br />
itu, beberapa penulis juga<br />
melakukan perlawanan dengan<br />
mengajukan peninjauan kembali<br />
atas kewenangan Kejaksaan<br />
dalam melakukan pembreidelan<br />
buku, di antaranya Darmawan,<br />
Roma Dwi Aria, dan ISSI sebagai<br />
penerbit buku Dalih Pembunuhan<br />
Massal.<br />
Keberlangsungan praktek<br />
pelarangan buku setelah sebelas<br />
tahun digulirkannya reformasi<br />
membawa sejumlah pertanyaan<br />
kritis atas komitmen penegakan<br />
dan perlindungan hak asasi<br />
manusia. Telah menjadi pengetahuan<br />
publik bahwa reformasi<br />
membuka ruang percepatan<br />
institusionalisasi kerangka<br />
normatif perlindungan hak asasi.<br />
Segera setelah transisi politik<br />
bergulir di tahun 1998, serangkaian<br />
perubahan konstitusional<br />
yang diikuti dengan penerbitan<br />
berbagai ketentuan perundangundangan<br />
menguatkan jaminan<br />
normatif hak asasi manusia. Oleh<br />
karena itu, berlangsungnya<br />
praktek pelarangan buku ini<br />
menjadi semacam ironi atas<br />
komitmen pemajuan hak asasi<br />
tersebut. Pertanyaannya kemudian,<br />
bagaimana hak asasi memandang<br />
praktek semacam ini, dan<br />
seberapa jauh standar penghormatan<br />
dan perlindungan hak<br />
asasi manusia dihormati oleh<br />
Pemerintah (baca: Kejaksaan<br />
Agung) ketika melakukan<br />
pelarangan. Tulisan ini akan<br />
menguraikan lebih jauh bagaimana<br />
hak asasi memandang kebijakan<br />
pelarangan buku tersebut,<br />
termasuk prinsip-prinsip umum<br />
yang terkait dengan perlindungan<br />
hak dan standar hak asasi yang<br />
harus dipertimbangkan dalam<br />
kebijakan pelarangan buku .<br />
Pelarangan Buku sebagai<br />
Pelanggaran Hak <strong>Asasi</strong> Manusia<br />
Kewenangan Kejaksaan untuk<br />
melarang buku memperoleh<br />
dasar hukumnya dari undangundang<br />
(UU) No 16 tahun 2004<br />
tentang Kejaksaan Republik<br />
Indonesia, khususnya Pasal 30<br />
(3) huruf c. Berdasarkan<br />
ketentuan perundang-undangan<br />
tersebut, dalam bidang ketentraman<br />
umum, Kejaksaan memperoleh<br />
kewenangan untuk<br />
melakukan pengawasan terhadap<br />
peredaran barang cetakan.<br />
Dalam ketentuan perundangundangan<br />
lain dapat ditemukan<br />
cakupan barang cetakan, yakni<br />
buku, brosur, bulletin, surat kabar<br />
harian, majalah, penerbitan<br />
berkala, pamflet, poster, dan<br />
surat-surat yang ditujukan untuk<br />
disebarkan atau dipertunjukkan<br />
kepada khalayak ramai (Pasal 2<br />
UU No 4/PNPS/1963). Dalam<br />
perkembangan kemudian, khususnya<br />
di masa Orde Baru,<br />
pengawasan terhadap barang<br />
cetakan berupa surat kabar dan<br />
majalah ataupun bentuk terbitan<br />
berkala lainnya (baca kewenangan<br />
melakukan breidel) dialihkan<br />
kepada Kementrian Penerangan.<br />
Namun setelah tahun 1998,<br />
kewenangan semacam ini tidak<br />
lagi ada seiring dengan dihapusnya<br />
Departemen Penerangan,<br />
digantikan oleh pembentukan<br />
Kementrian Komunikasi dan<br />
Informasi (Kominfo). Dengan<br />
demikian, hanya kewenangan<br />
pengawasan peredaran barang<br />
cetakan berupa buku, pamflet,<br />
poster dan surat yang ada di<br />
Kejaksaan Agung yang sampai<br />
saat ini masih terus berlangsung.<br />
Kebijakan publik semacam ini<br />
memang tidak popular di negaranegara<br />
demokratis karena<br />
dipandang sebagai tindakan<br />
represif yang mencerminkan<br />
watak otoritarian pemegang<br />
kekuasaan. Selain itu, apabila<br />
Ilustrasi. dok.www,kompas.com<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
05
laporan utama<br />
dilakukan secara tidak tepat dan<br />
gegabah, tindakan ini justru<br />
merupakan pelanggaran hak<br />
asasi manusia. Pertama,<br />
kebijakan ini dapat secara<br />
langsung melanggar hak warga<br />
n e g a r a ( p e n u l i s ) u n t u k<br />
menyatakan pendapat dan<br />
kebebasan untuk berekspresi<br />
yang dijamin dalam Pasal 19 Ayat<br />
1 dan 2 Kovenan Hak Sipil dan<br />
Politik yang telah diratifikasi<br />
melalui UU No 12 Tahun 2005.<br />
Kedua, tindakan pelarangan juga<br />
d a p a t s e c a r a l a n g s u n g<br />
menghalangi hak warga negara<br />
(pembaca) untuk mencari dan<br />
memperoleh informasi, yang<br />
dijamin dalam pasal yang sama.<br />
Lantas kapan tepatnya suatu<br />
tindakan pelarangan dapat<br />
dikatakan sebagai tindakan<br />
p e l a n g g a r a n h a k a s a s i<br />
manusia?<br />
Memang seperti diatur lebih lanjut<br />
dalam Pasal 19 (3) Kovenan<br />
tersebut, penikmatan hak ini<br />
membawa kewajiban dan<br />
tanggung jawab khusus. Oleh<br />
karenanya, pemenuhan hak ini<br />
dimungkinkan tunduk pada<br />
pembatasan tertentu. Namun<br />
pembatasan ini hanya dapat<br />
dilakukan apabila:<br />
(1) Diatur dalam undangundang,<br />
(2) Untuk melindungi hak<br />
atau reputasi orang lain,<br />
(3) Untuk perlindungan<br />
keamanan nasional, atau<br />
ketertiban umum, atau<br />
kesehatan masyarakat<br />
atau moral publik.<br />
Lebih lanjut ditegaskan oleh<br />
Komite Hak Sipil dan Politik PBB<br />
bahwa tindakan pembatasan<br />
tersebut, meskipun dimungkinkan,<br />
tidak boleh membahayakan<br />
hak tersebut (Komentar<br />
Umum Komite Hak Sipil dan<br />
Politik paragraf 4) sehingga<br />
menghilangkan jaminan penikmatan<br />
hak tersebut.<br />
Prasyarat dan prosedur<br />
pembatasan seperti diatur dalam<br />
kovenan tersebut memang<br />
dirumuskan dengan bahasa yang<br />
sangat umum yang memungkinkan<br />
adanya variasi pemahaman<br />
dan inteprestasi, misalnya<br />
terkait dengan batasan dan<br />
cakupan ketertiban umum,<br />
keamanan nasional maupun<br />
kesehatan masyarakat ataupun<br />
moral publik. Upaya untuk<br />
merumuskan suatu panduan<br />
yang lebih rigid atas praktek<br />
pembatasan hak-hak sipil dan<br />
politik melahirkan Prinsip-Prinsip<br />
Siracusa yang secara universal<br />
telah dipergunakan oleh badanbadan<br />
PBB dan organisasi<br />
internasional lainnya untuk<br />
menilai tindakan pembatasan hak<br />
oleh negara. Prinsip ini lahir dari<br />
suatu konferensi internasional di<br />
Siracusa Italia di tahun 1984 yang<br />
diprakarsai sejumlah NGOs dan<br />
didukung oleh akademisi serta<br />
praktisi hak asasi dari seluruh<br />
dunia. Serangkaian prinsip ini<br />
kemudian diadopsi badan dunia<br />
PBB di tahun yang sama.<br />
B e r d a s a r k a n p r i n s i p<br />
Siracusa, prasyarat 'diatur dalam<br />
undang-undang' mensyaratkan<br />
lima hal:<br />
1. Pembatasan hanya dapat dilakukan<br />
melalui suatu undangundang<br />
yang secara umum<br />
berlaku yang substansinya<br />
konsisten dengan Kovenan.<br />
Dengan demikian, keberadaan<br />
suatu undang-undang sebagai<br />
suatu alas pembenar pelarangan<br />
tidak secara otomatis bisa<br />
menjadi justifikasi keabsahan<br />
tindakan pelarangan tersebut.<br />
Apabila substansi dari undangundang<br />
tersebut tidak sesuai<br />
a t a u k o n s i s t e n d e n g a n<br />
Kovenan, tindakan pelarangan<br />
justru dapat menjadi suatu<br />
bentuk pelanggaran hak asasi,<br />
2. Selain itu, hukum yang<br />
dipergunakan untuk mendasari<br />
pembatasan haruslah tidak<br />
bersifat semena-mena dan<br />
masuk akal,<br />
3. Aturan hukum yang membatasi<br />
penikmatan hak asasi tersebut<br />
haruslah dirumuskan secara<br />
jelas dan dapat diakses oleh<br />
setiap orang,<br />
4. Perlindungan yang memadai<br />
dan pemulihan yang efektif<br />
harus disediakan oleh hukum<br />
atas penerapan kebijakan<br />
pembatasan yang melawan<br />
hukum dan kejam,<br />
5. Negara memiliki beban untuk<br />
menunjukkan bahwa pembatasan<br />
tersebut tidak merusak fungsi<br />
demokratis masyarakat.<br />
Perumusan prasyarat ini<br />
ditegaskan lebih lanjut melalui<br />
prinsip Johannesburg yang secara<br />
khusus menguraikan prinsipprinsip<br />
utama pembatasan<br />
penikmatan atas kebebasan<br />
berekspresi dan mengeluarkan<br />
pendapat. Berdasarkan prinsip ini,<br />
prasyarat kejelasan substansi<br />
undang-undang yang dipergunakan<br />
untuk melakukan pembatasan<br />
diuraikan dengan lebih mendetail<br />
dengan mensyaratkan keterjangkauan,<br />
batasan dan ketepatan<br />
rumusan sehingga memungkinkan<br />
seseorang menilai sah<br />
tidaknya tindakan pelarangan<br />
yang diterapkan.<br />
Dengan mempertimbangkan<br />
kelima elemen tersebut sebagai<br />
indikator, tampaknya sulit<br />
m e m b e r i k a n p e m b e n a r a n<br />
terhadap praktek pelarangan yang<br />
d i d a s a r k a n p a d a U U N o<br />
4/PNPS/1964. Sebaliknya justru<br />
terlihat absennya beberapa<br />
prasyarat penting, seperti absennya<br />
mekanisme perlindungan dan<br />
pemulihan yang efektif bagi<br />
korban pelarangan. Dengan<br />
demikian, lebih mudah mengidentifikasi<br />
tindakan tersebut sebagai<br />
bentuk pelanggaran daripada<br />
menemukan argumentasi yang<br />
kuat untuk menunjukkan kesesuaiannya<br />
dengan prinsip dan<br />
standar hak asasi manusia<br />
Selain itu, pelarangan buku<br />
paling sering dikaitkan dengan<br />
alasan melindungi ketertiban<br />
umum. Meskipun ketertiban<br />
umum merupakan alasan yang<br />
dapat dibenarkan dalam melakukan<br />
pembatasan, cakupan<br />
pengertian ketertiban umum perlu<br />
diperiksa apakah sesuai dengan<br />
standar hak asasi yang telah<br />
diakui secara universal. Artinya<br />
negara tidak dapat secara<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
06 EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
laporan utama<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
semena-mena atau sepihak<br />
mengintepretasikan rumusan<br />
ketertiban umum tersebut tanpa<br />
d a s a r y a n g k u a t . S u a t u<br />
pertimbangan atau kondisi tertentu<br />
yang menjadi keprihatinan dalam<br />
masyarakat, tidak dengan serta<br />
merta dapat diintepretasikan<br />
sebagai ketertiban umum.<br />
Sebagai contoh, ketertiban umum<br />
dalam tindakan pelarangan buku<br />
dan barang cetakan hampir selalu<br />
dikaitkan dengan kekhawatiran<br />
akan munculnya keresahan di<br />
kalangan masyarakat, atau akan<br />
memicu terjadinya kekerasan dan<br />
gangguan ketertiban umum.<br />
Meskipun tampak masuk<br />
akal, tidak secara otomatis alasan<br />
ini sesuai dengan standar hak<br />
asasi yang berlaku. Berdasarkan<br />
prinsip Siracusa, ketertiban umum<br />
setidaknya harus diintepretasikan<br />
sebagai pertama, serangkaian<br />
norma yang menjamin berfungsinya<br />
masyarakat, atau seperangkat<br />
prinsip-prinsip dasar yang menjadi<br />
dasar pembentukan masyarakat.<br />
Penghormatan atas hak asasi<br />
merupakan bagian yang inheren<br />
dari ketertiban umum tersebut.<br />
Kekhawatiran akan timbulnya<br />
'kerawanan sosial' tampaknya<br />
masih jauh dari memadai untuk<br />
dapat menjelaskan terlanggarnya<br />
prinsip-prinsip dasar yang<br />
membentuk masyarakat. Oleh<br />
karena itu, kecuali terdapat<br />
seperangkat prosedur dan<br />
mekanisme yang sahih untuk<br />
menyangga kesimpulan yang<br />
menjadi alas pelarangan tersebut,<br />
sulit menghindarkan kesimpulan<br />
bahwa tindakan tersebut merupakan<br />
pelanggaran hak asasi.<br />
Apalagi, prinsip Siracusa juga<br />
mensyaratkan adanya mekanisme<br />
kontrol atas kewenangan pemerintah<br />
dalam menjaga ketertiban<br />
umum, baik melalui badan<br />
legislatif, pengadilan ataupun<br />
badan independen lain yang<br />
kompeten (Siracusa Principle B. iii.<br />
Para 24).<br />
Menuju Kebijakan Berbasis<br />
Hak dalam Pengaturan Barang<br />
Cetakan dan Publikasi<br />
Sebagai suatu medium penyampaian<br />
gagasan ataupun ekspresi,<br />
keberadaan barang cetakan<br />
ataupun bentuk publikasi lain<br />
penting untuk mendorong perkembangan<br />
pengetahuan sosial<br />
masyarakat. Oleh karena itu,<br />
suatu kebijakan yang dapat<br />
memungkinkan distribusi pengetahuan<br />
di antara anggota<br />
masyarakat merupakan suatu<br />
keniscayaan. Secara normatif,<br />
perubahan konstitusional yang<br />
mengikuti transisi politik di tahun<br />
1998 telah memperkuat jaminan<br />
perlindungan hak asasi manusia.<br />
Jaminan normatif ini semakin<br />
menguat dengan langkah pemerintah<br />
untuk meratifikasi dua<br />
kovenan utama yakni Kovenan<br />
Internasional untuk Hak Sipil dan<br />
Politik serta Kovenan Internasional<br />
untuk Hak Ekonomi, Sosial dan<br />
Budaya melalui UU No 11 dan 12<br />
tahun 2005.<br />
Untuk dapat merealisasikan<br />
jaminan normatif tersebut,<br />
pemerintah perlu mengambil<br />
beberapa langkah penting yang<br />
tidak dapat ditunda. Salah<br />
satunya adalah menyesuaikan<br />
peraturan perundang-undangan<br />
yang masih berlaku hingga saat<br />
ini agar sesuai dengan standar<br />
dan prinsip hak asasi manusia<br />
yang ada baik dalam konstitusi<br />
maupun ketentuan perundangundangan<br />
yang lain, termasuk UU<br />
No 4/PNPS/1963 ini.<br />
Selain itu, perubahan ini juga<br />
perlu dilakukan sebagai bagian<br />
dari proses transisi agar bisa<br />
ditarik garis tegas antara rezim<br />
yang saat ini sedang berjalan<br />
dengan praktek otoritarian di<br />
masa yang lampau. Selama ini,<br />
gagasan untuk menarik garis<br />
tegas dengan masa lalu hampir<br />
selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban<br />
atas pelanggaran<br />
HAM berat di masa lampau.<br />
Mudah-mudahan publik tidak<br />
lupa, bahwa praktek pelarangan<br />
ini merupakan salah satu praktek<br />
yang tidak pernah terganggu<br />
dengan hiruk pikuk reformasi.<br />
Rezim boleh berganti, namun<br />
praktek pelarangan buku seperti<br />
tak kenal pergantian. Dari tahun<br />
ke tahun terus berlangsung,<br />
dilakukan oleh institusi negara<br />
yang sama, dengan dasar<br />
ketentuan hukum yang sama yang<br />
diwarisi pada masa Soekarno.<br />
Kalau bukan sekarang, kapan<br />
garis tegas dari praktek kesewenangan<br />
di masa lalu itu dapat<br />
dilakukan?<br />
Keterangan<br />
1. Secara umum dalam Kovenan Hak<br />
Sipil dan Politik memang dikenal<br />
dua klasifikasi hak yakni hak yang<br />
dapat dikurangi pemenuhannya<br />
pada situasi tertentu (derogable<br />
rights) dan hak yang tak dapat<br />
dikurangi penikmatannya dalam<br />
situasi apapun (non-derogable<br />
rights). Hak atas kebebasan<br />
berekspreksi dan menyatakan<br />
pendapat termasuk dalam klasifikasi<br />
hak yang pertama, sehingga tunduk<br />
pada kemungkinan pembatasan<br />
tersebut. Alasan yang paling umum<br />
dipergunakan untuk melakukan<br />
pembatasan adalah kondisi<br />
kegentingan/darurat.<br />
2. Prinsip Johannesburg dihasilkan<br />
dalam suatu pertemuan internasional<br />
di Johannesburg, Afrika yang dihadiri<br />
oleh sekelompok ahli dalam hukum<br />
internasional, keamanan nasional,<br />
dan hak asasi pada tanggal 1<br />
Oktober 1995. Prinsip ini dirumuskan<br />
berdasarkan standar hukum<br />
internasional dan regional yang<br />
terkait dengan perlindungan hak<br />
asasi manusia, dan perkembangan<br />
penerapannya seperti tercermin<br />
melalui putusan pengadilan, serta<br />
prinsip-prinsip umum hukum yang<br />
diakui oleh bangsa-bangsa.<br />
Semenjak diadopsi, prinsip ini telah<br />
secara luas dipergunakan terlebih<br />
setelah diadopsi oleh badan PBB<br />
sebagai suatu dokumen resmi meski<br />
tidak memiliki kekuatan hukum<br />
mengikat di tahun 1984.<br />
3. Lihat, siaran pers Kejaksaan Agung<br />
tanggal 28/12/2009, dapat diunduh<br />
di http://www.kejaksaan.go.id/<br />
siaranpers.php?id=244<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
07
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
laporan utama<br />
Memberangus Buku:<br />
Membunuh Diri-Sendiri<br />
Oleh Daniel Hutagalung<br />
(Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)<br />
“Whenever they burn books, they will also, in the end, burn human beings” Heinrich Heine<br />
n t a h m e n g a p a , d i<br />
Indonesia buku menjadi<br />
demikian menakutkan.<br />
Dibandingkan dengan Edunia maya yang aksesnya bisa<br />
lebih luas dan lebih mudah, bisa<br />
jadi sebuah buku lebih terbatas<br />
peredarannya, harus digapai di<br />
toko-toko buku, pun dengan<br />
jumlah yang terbatas. Namun<br />
buku menjadi demikian penting<br />
nilainya hingga ia harus<br />
diberangus dan peredarannya<br />
dilarang. Novel mahsyur The<br />
Name of the Rose karya Umberto<br />
Eco juga mengangkat soal<br />
larangan membaca buku karya<br />
Aristoteles di dalam lingkungan<br />
biara Katolik abad ke-14. Eco<br />
menulis kisah tentang betapa<br />
berkuasanya doktrin kebenaran<br />
absolut sehingga intepretasi<br />
individual atas teks Comedy<br />
karya Aristoteles diharamkan dan<br />
Pembakaran buku-buku oleh pemerintah Nazi di Berlin pada Mei, 1933.<br />
Dok.http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_book_burnings<br />
dilarang, sehingga siapapun yang<br />
membacanya akan mengalami<br />
kematian mengenaskan, karena<br />
buku yang tersimpan di dalam<br />
sebuah bagian terlarang dalam<br />
perpustakaan di biara itu telah<br />
dibubuhi racun.<br />
Karya Eco memberikan<br />
suatu gambaran betapa buku<br />
menjadi suatu hal yang amat<br />
ditakuti. Kadangkala, jauh lebih<br />
ditakuti ketimbang si penulisnya<br />
sendiri. Tidak perlu jauh menarik<br />
ke masa kolonialisme, di masa<br />
Soekarno dan Soeharto pelarangan<br />
buku juga kerap terjadi. Pramoedya<br />
Ananta Toer, merupakan<br />
pengarang yang bukunya<br />
dilarang di dua era pemerintahan<br />
tersebut. Tulisan dan novel-novel<br />
karya Pramoedya dinilai membahayakan<br />
dan bisa menggangu<br />
ketertiban umum. Buku-bukunya<br />
dilarang, namun orangnya bebas<br />
dan tetap menulis (meskipun<br />
hidup dalam pengawasan ketat),<br />
demikian juga dialami buku-buku<br />
lainnya. Kisah pelarangan buku<br />
terus berlanjut sampai di masa<br />
pemerintahan Susilo Bambang<br />
Yudhoyono (SBY). Kisah tragis<br />
paling akhir, salah satunya<br />
menimpa buku Dalih Pembunuhan<br />
Massal karya John Roosa, yang<br />
dilarang peredarannya oleh<br />
Kejaksaan Agung RI.<br />
Tulisan ini mencoba<br />
untuk melihat secara umum<br />
mengapa buku dilarang dan<br />
ditakuti dalam suatu rentang<br />
kepolitikan tertentu, dengan fokus<br />
pelarangan buku di Indonesia.<br />
Biblioclasm: Pemusnahan<br />
Budaya<br />
Buku menjadi amat menakutkan<br />
pada saat ia menjadi intepretasi<br />
lain dari suatu tafsir kebenaran<br />
yang diabsolutkan. Ketakutannya<br />
adalah: intepretasi lain tersebut<br />
akan diyakini banyak orang, dan<br />
perlahan menggerogoti kebenaran<br />
absolut yang diciptakan atas suatu<br />
tafsir, baik peristiwa, kejadian<br />
maupun doktrin tertentu. Dalam<br />
novel Eco yang digerogoti adalah<br />
tafsir kebenaran absolut agama<br />
dan gereja. Dengan itu, buku<br />
(representasi) kerapkali menjadi<br />
jauh lebih ditakuti daripada<br />
penulisnya (presentasi).<br />
Bentuk awal pemusnahan<br />
buku adalah aksi pembakaran<br />
buku dan penghancuran perpustakaan,<br />
atau umumnya dikenal<br />
dengan istilah biblioclasm atau<br />
juga bibliocaust, yang dapat<br />
dirujuk pada aksi perusakan<br />
perpustakaan Alexandria, penghancuran<br />
manuskrip-manuskrip<br />
Indian Maya oleh gereja setelah<br />
pendudukan Spanyol, pembakaran<br />
buku jaman Nazi, penghancuran<br />
perpustakaan Sarajevo, dan<br />
lainnya. Pemusnahan buku<br />
dipandang sebagai suatu wujud<br />
penghancuran kebudayaan<br />
(cultural destruction), bahkan<br />
menjurus pada pemusnahan<br />
kebudayaan (cultural extinction).<br />
Dalam studi Rebecca Knuth<br />
(2006), sejarah biblioclasm<br />
umumnya berjalinan erat dengan<br />
s e j a r a h v a n d a l i s m e d a n<br />
kekerasan politik, di mana pada<br />
08<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
laporan utama<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
masa klasik, penghancuran<br />
perpustakaan merupakan bagian<br />
dari rutinitas peperangan.<br />
Perampasan barang-barang<br />
perpustakaan menjadi simbol<br />
bagi si pemenang perang untuk<br />
menunjukkan kekuasaannya,<br />
s e k a l i g u s m e m u s n a h k a n<br />
rekaman kejayaan dari wilayah<br />
yang ditaklukkan. Penghancuran<br />
perpustakaan dan pemusnahan<br />
buku adalah sekaligus memutus<br />
ingatan masa lalu dan pengikisan<br />
identitas budaya komunitaskomunitas<br />
yang ditaklukkan.<br />
Penghancuran perpustakaan<br />
Alexandria bahkan menghantui<br />
peradaban Eropa sampai hari ini.<br />
Knuth (2003) menamai<br />
aksi-aksi vandal pemberangusan<br />
buku dengan: libricide, yang<br />
artinya kira-kira pembunuhan<br />
buku (Knuth mempersamakannya<br />
dengan istilah “homicide”<br />
dalam artian menghilangkan<br />
nyawa seseorang). Libricide<br />
secara etimologi merefleksikan<br />
keterkaitannya dengan istilah<br />
genosida dan etnosida sekaligus,<br />
yang bagi Knuth merujuk pada,<br />
“specifically to the twentiethcentury,<br />
large-scale, regimesanctioned<br />
destruction of books<br />
a n d l i b r a r i e s , p u r p o s e f u l<br />
initiatives that were designed to<br />
advance short and long term<br />
ideologically driven goals”.<br />
Sebagian contoh yang diuraikan<br />
Knuth di antaranya: Nazi Jerman,<br />
pembakaran perpustakaan di<br />
Kuwait, dan Yugoslavia pada<br />
masa disintegrasi. Ciri utama dari<br />
libricide adalah bahwa aktivitas ini<br />
mendapat dukungan dari rezim<br />
yang berkuasa, jadi bukan<br />
semata-mata suatu tindakan<br />
spontan yang dilakukan oleh<br />
individu atau kelompok. Tujuantujuan<br />
yang ingin dicapai dari aksi<br />
ini di antaranya untuk menggelapkan<br />
atau menghapuskan: sejarah,<br />
ingatan kolektif, sistem<br />
keyakinan, nasionalisme dan<br />
informasi perkembangan masyarakat.<br />
Memusnahkan buku<br />
umumnya disandingkan juga<br />
dengan sejenis hasrat totalitarianisme.<br />
Suatu hasrat untuk<br />
melakukan monopoli terhadap<br />
ruang kosong pemaknaan.<br />
Hasrat untuk meniadakan<br />
kontestan lain terhadap suatu<br />
tafsir, sehingga bisa menjadi<br />
kebenaran tunggal, dan satusatunya<br />
pandangan hidup dan<br />
pegangan warga. Soeharto dan<br />
rezim Orde Baru-nya terbilang<br />
sukses menjalankan ini. Dalam<br />
luapan hasrat totalitarianisme<br />
O r d e B a r u , s e j a r a h d a n<br />
pengetahuan masyarakat secara<br />
paksa dijadikan suatu yang baku<br />
dalam suatu wadah tunggal,<br />
berupa doktrin kebenaran tafsiran<br />
rezim Soeharto. Untuk mencapai<br />
titik itu maka segala sumber<br />
informasi dan pengetahuan yang<br />
berbeda, maupun versi-versi lain<br />
yang bisa dianggap menjadi<br />
kebenaran, atau menjadi ragam<br />
kebenaran (yang tidak tunggal),<br />
s e g e r a d i h a n c u r k a n a t a u<br />
setidaknya dibatasi. Penyeragaman<br />
kebudayaan dijalankan<br />
lewat lajur monopoli kebenaran.<br />
Hasrat totalitarianisme<br />
dan libricide bertaut dalam diri<br />
Orde Baru. Akibatnya budaya<br />
masyarakat mengalami perubahan<br />
drastis: malas berdebat, enggan<br />
mengkritik, menghindari pengemukaan<br />
pandangan lain, dan<br />
terutama terbungkam-erat kala<br />
menyinggung Peristiwa 1965.<br />
Tidak ada keterbukaan dan<br />
perbedaan pandangan, pikiran,<br />
argumen selain yang disediakan<br />
rezim Orde Baru. Pemberangusan<br />
tidak melulu pada isi<br />
buku, melainkan juga pada<br />
penulis tertentu, yang apapun<br />
yang ia tulis harus dilarang dan<br />
diberangus, tidak boleh mendapat<br />
tempat dalam diskursus Orde<br />
Baru. Karena itu, sejumlah<br />
dimensi luruh dari kamus<br />
kehidupan manusia Indonesia<br />
semasa Orde Baru. Orde Baru<br />
berhasil menciptakan budaya<br />
baru dan menyingkirkan sejumlah<br />
budaya yang sebelumnya<br />
melekat dalam kehidupan<br />
manusia Indonesia, yang salah<br />
satunya melalui tindakan<br />
memberangus dan melarang<br />
buku.<br />
Ilustrasi pelarangan buku . dok.koran republika.com<br />
Pelarangan Buku di Era<br />
R e f o r m a s i : V a n d a l i s m e<br />
Pemerintahan SBY<br />
Pembakaran buku-buku Pelajaran<br />
Sejarah untuk SMP dan SMU pada<br />
2007 oleh Kejaksaan Tinggi di<br />
seluruh Indonesia, karena menghilangkan<br />
kata “PKI” dari “G-30-S”,<br />
merupakan upaya memutus<br />
rekaman ingatan orang Indonesia<br />
atas Peristiwa 1965 sebagai ruang<br />
bagi berbagai kemungkinan tafsir.<br />
Bayangkan: Kejaksaan<br />
Tinggi Semarang pada 19 Juni<br />
2007 memusnahkan 14.960 buku<br />
Pelajaran Sejarah untuk SMP dan<br />
SMA yang berdasarkan Kurikulum<br />
2004, dengan mesin penghancur.<br />
Tindakan tersebut disusul<br />
Kejaksaan Tinggi Bandung<br />
bersama Dinas Pendidikan dan<br />
Pemda Kota Bandung dengan<br />
cara membakar 2.258 buku yang<br />
sama pada 26 Juli 2007.<br />
Pembakaran dan penghancuran<br />
buku yang sama juga terjadi di<br />
D e p o k , B o g o r, M a k a s s a r,<br />
Indramayu, Kupang dan Riau.<br />
Pembakaran buku ini merupakan<br />
tindakan yang pertama kali<br />
dilakukan di era reformasi.<br />
Pelarangan buku terakhir kali<br />
dilakukan di era Orde Baru.<br />
Kasus pelarangan yang<br />
berujung pembakaran buku<br />
tersebut berawal dari pengaduan<br />
Yusuf Hasyim, Taufik Ismail dan<br />
Fadli Zon ke Dewan Perwakilan<br />
Rakyat, bahwa di Jawa Timur<br />
ditemukan buku Pelajaran Sejarah<br />
untuk siswa SMP dan SMA yang<br />
tidak mencantumkan keterlibatan<br />
Partai Komunis Indonesia dalam<br />
Peristiwa Madiun 1948 dan<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
09
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
laporan utama<br />
pembunuhan petinggi TNI AD<br />
tahun 1965 (Analisis Mingguan,<br />
No.21/2007)<br />
Dari laporan tersebut<br />
DPR kemudian memanggil<br />
Mendiknas Bambang Sudibyo<br />
dan melakukan rapat koordinasi.<br />
Selepas rapat, Mendiknas<br />
meminta Badan Standar Nasional<br />
Pendidikan (BSNP) untuk<br />
membentuk tim khusus. Tim yang<br />
terbentuk terdiri dari Djoko Suryo<br />
(Sejarawan/Guru Besar UGM),<br />
Hamid Hasan (Pakar Pendidikan<br />
UPI Bandung), Susanto Zuhdi<br />
(Sejarawan/Guru Besar FIB UI),<br />
Wasino (Sejarawan Universitas<br />
Negeri Semarang) dan W.<br />
S o e t o m o ( S e m a r a n g ) .<br />
Rekomendasi yang dihasilkan<br />
oleh tim ini adalah perlunya<br />
dicantumkan kata “PKI” setelah<br />
“Peristiwa G30S 1965” dan<br />
“Peristiwa Madiun 1948”. Dalam<br />
uji publik kurikulum yang<br />
diselenggarakan 1 Desember<br />
2005, Asvi Marwan Adam<br />
mengatakan bahwa mereka yang<br />
terlibat pada Peristiwa 1965<br />
menyebut dirinya sebagai<br />
“Gerakan 30 September”,<br />
sehingga semestinya istilah yang<br />
lebih obyektif ini digunakan,<br />
karena memang ada berbagai<br />
versi tentang dalang peristiwa itu<br />
(Tempo Interaktif, 15/3/2007).<br />
P e m b a k a r a n d a n<br />
pemusnahan buku sebagaimana<br />
dilakukan Kejaksaan Tinggi,<br />
Dinas Pendidikan dan Pemda di<br />
sejumlah wilayah di Indonesia<br />
tersebut, mengingatkan kita<br />
k e m b a l i k e p a d a p e r i l a k u<br />
vandalisme pemusnahan buku<br />
jaman Nazi pada tahun 1933.<br />
Pembakaran maupun pelarangan<br />
buku merupakan wujud kebencian<br />
terhadap pemikiran, dan upaya<br />
membenamkan adanya kemungkinan<br />
kebenaran yang lain ke<br />
dalam sumur gelap, dan kita tak<br />
diijinkan untuk mengoreknya<br />
kembali.<br />
Ada semacam ketakutan<br />
terhadap “argumen”, “pandangan”<br />
atau “perspektif” yang berbeda<br />
dengan yang dibangun Orde Baru<br />
mengenai Persitiwa 1965.<br />
Akademisi, sejarawan dan<br />
ilmuwan yang biasanya bertindak<br />
atas dasar kebebasan mimbar<br />
akademik, rasionalitas, kebenaran,<br />
obyektivitas, validitas dan<br />
nilai etis agaknya enggan atau<br />
mungkin takut, untuk keluar dari<br />
monopoli tafsir kebenaran Orde<br />
Baru, dan lebih memilih untuk<br />
merekomendasikan pelarangan<br />
buku ketimbang menjenguk lebih<br />
dalam mengenai kontroversi<br />
Peristiwa 1965. Rekomendasi itu<br />
merupakan ironi sekaligus<br />
kejahatan terbesar dalam dunia<br />
pendidikan di Indonesia, di mana<br />
para akademisi terkemuka<br />
menganjurkan tindakan yang<br />
sangat diharamkan oleh dunia<br />
akademik: memberangus buku!<br />
Petanda ini menunjukkan<br />
bahwa rezim SBY tetap menerima<br />
begitu saja seluruh argumen<br />
yang diciptakan Orde Baru<br />
mengenai Peristiwa 1965.<br />
Argumen ini pernah coba digoyah<br />
oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman<br />
Wahid, dengan mengusulkan<br />
pencabutan TAP MPRS<br />
No.25/1966, namun kandas dan<br />
gagal. Bagi rezim SBY, tidak<br />
boleh ada argumen lain, seilmiah<br />
apapun, yang boleh menandingi<br />
apa yang sudah dibuat Orde<br />
Baru. Lewat Kejaksaan Agung,<br />
monopoli kebenaran dan tafsir<br />
tunggal ciptaan Soeharto terusmenerus<br />
dipertahankan. Maka,<br />
apapun yang tersimpan di balik<br />
Peristiwa 1965, kalaupun terdapat<br />
kejahatan kemanusiaan yang<br />
menggiriskan, akan tersimpanaman<br />
di dalam laci meja rezim<br />
SBY.<br />
Penutup<br />
Rezim-rezim yang melakukan<br />
pemberangusan buku umumnya<br />
rezim yang berhasil mengkonsolidasikan<br />
kekuasannya, di mana<br />
ideologi menjadi pijakan rasional<br />
bagi totalitarianisme. Buku<br />
menjadi salah satu situs yang<br />
merekam dan menjaga ingatan,<br />
kadang menyajikan kesaksian,<br />
juga menjadi ruang yang<br />
menyediakan bukti-bukti dari<br />
berbagai perspektif dan bersifat<br />
valid, memberikan fasilitas bagi<br />
kebebasan intelektual, dan juga<br />
memberikan dukungan bagi<br />
identitas berbagai kelompok. Buku<br />
menjadi situs sangat penting yang<br />
karenanya kerap menuai rasa<br />
takut bagi rezim-rezim yang berdiri<br />
di atas pusara totalitarian lewat<br />
kekerasan, manipulasi dan<br />
kebohongan. Orde Baru telah<br />
memberikan sajian amat pahit<br />
pada kita mengenai apa itu<br />
totalitarianisme, yang salah satu<br />
gejala dari hasratnya adalah<br />
melarang buku. Rezim SBY hari ini<br />
pun mulai bertingkah dengan<br />
langkah dan gaya Orde Baru:<br />
membakar dan melarang buku!<br />
M e m b e r a n g u s b u k u<br />
berarti kita sedang menghapus<br />
ingatan akan diri kita sendiri. Kita<br />
perlahan-lahan membunuh diri<br />
kita, dan pada suatu saat kita tak<br />
lagi mempu mengenali diri-sendiri,<br />
karena mosaik dan situs-situs<br />
mengenai keberadaan kita, sebagian<br />
besar telah dimusnahkan.<br />
Tindakan vandal dan barbarisme<br />
seperti itu tentu tidak punya<br />
tempat di alam demokrasi. Hanya<br />
rezim-rezim yang tidak beradab<br />
dan berhasrat totaliter saja yang<br />
melakukan pemberangusan buku,<br />
terlebih buku ilmiah. Pelarangan<br />
buku Dalih Pembunuhan Massal<br />
harus kita jadikan monumen, agar<br />
k i t a k e m b a l i b e r s i a p - s i a p<br />
menghadapi gelombang hasrat<br />
totaliter yang mencoba kembali<br />
hadir di dalam diri pemerintahan<br />
yang berkuasa hari ini.<br />
Kepustakaan<br />
Fishburn, Matthew, Burning<br />
Books. London: Macmillan<br />
Palgrave, 2008.<br />
Knuth, Rebecca, Burning Books<br />
a n d L e v e l i n g L i b r a r i e s :<br />
Extremist Violence and Cultural<br />
Destruction. London: Praeger,<br />
2006.<br />
Knuth, Rebecca, Libricide: The<br />
Regime-Sponsored Destruction<br />
of Books and Libraries in the<br />
Twentieth Century. London:<br />
Praeger, 2003.<br />
10<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
laporan utama<br />
Pelarangan Buku di Indonesia<br />
Oleh M. Fauzi<br />
(Sejarawan)<br />
ada 23 Desember 2009,<br />
ketika sebagian masyarakat<br />
tengah bersiap<br />
untuk berlibur atau Pmenyiapkan segala sesuatu<br />
menyambut datangnya perayaan<br />
Natal dan pergantian tahun,<br />
pemerintah melalui Kejaksaan<br />
Agung justru hadir dengan<br />
sebuah pengumuman penting<br />
y a n g c u k u p m e n g e j u t k a n<br />
masyarakat, yakni melarang lima<br />
b u k u . P e n g u m u - m a n i t u<br />
membuat banyak pihak lantas<br />
bertanya-tanya, tak sedikit pula<br />
yang mengkritiknya. Mengapa<br />
buku harus dilarang? Apa kesalahan<br />
dan alasannya? Bagaimana<br />
prosesnya hingga sebuah buku<br />
harus dilarang? Dan, apakah<br />
keputusan pelarangan itu lahir<br />
dari proses yang adil, melalui<br />
penga-dilan? Sejauh mana<br />
hukum dan pengadilan menjadi<br />
acuan dalam seluruh proses<br />
pelarangan ini?<br />
Semua pertanyaan di<br />
atas muncul karena seringkali<br />
d a l a m s e t i a p k e p u t u s a n<br />
pelarangan, alasan yang dipakai<br />
kerapkali seragam: ketertiban<br />
umum. Alasan ini tentu masih bisa<br />
diperdebatkan. Alasan itu pula<br />
yang dipakai oleh penguasa dari<br />
waktu ke waktu untuk melarang<br />
sebuah buku. Seberapa besar<br />
bahayanya sebuah buku bagi<br />
sebuah rezim ataupun penguasa<br />
hingga perlu dilarang? Tak ada<br />
catatan dalam sejarah Indonesia<br />
bahwa sebuah buku mampu<br />
menggerakkan masyarakat untuk<br />
melawan pemerintah ataupun<br />
penguasa. Yang terjadi justru<br />
sebaliknya, sebuah buku mampu<br />
meng-gerakkan pemerintah<br />
untuk melawan atau membatasi<br />
pikiran sang pengarangnya.<br />
Inilah yang acapkali terjadi dalam<br />
setiap pelarangan buku di<br />
sepanjang sejarah negeri ini.<br />
Di era kolonial, misalnya,<br />
pemerintah tidak melarang buku<br />
atau bacaan yang mempersoalkan<br />
kekuasaan kolonial. Pemerintah<br />
justru menangkap, memenjarakan<br />
atau membuang penulisnya<br />
ke tempat pengasingan. Tak<br />
cukup sebatas tindakan itu,<br />
sejumlah tindakan lain bersifat<br />
preventif dilakukan untuk<br />
menghancurkan sumber penerbitan.<br />
Percetakannya dibubarkan<br />
Pramoedya Ananta Toer Karyanya kerap menjadi sasaran<br />
pemerintah Orde Baru dok.http://ibnuanwar.wordpress.com/<br />
2008/05/29/pramoedya-ananta-toer/<br />
dan peralatan cetak disita oleh<br />
negara kolonial. Mungkin<br />
keputusan pembuangan dan<br />
menghancurkan sumber penerbitan<br />
ini lebih efektif ketimbang<br />
melarang sebuah buku. Dengan<br />
begitu, fungsi sosial buku yang<br />
m e n j a d i j e m b a t a n a n t a r a<br />
pengarang dan pembacanya<br />
dihancurkan. Peristiwa yang<br />
sangat terkenal dalam sejarah<br />
adalah ketika negara kolonial<br />
dipersoalkan lewat sebuah<br />
bacaan yang ditulis oleh R.M.<br />
Soewardi Soerjaningrat kemudian<br />
dikenal sebagai Ki Hadjar<br />
Dewantara. Judul karya Soewardi<br />
dalam rangka menyambut<br />
perayaan pembeba-san Belanda<br />
dari kekuasaan Perancis itu<br />
adalah “Als ik een Nederlander<br />
was” yang kemudian di-Melayukan<br />
menjadi “Seandainya Saya<br />
Seorang Belanda”.<br />
Ketika karangan Soewardi<br />
tersebut terbit pertama kali<br />
dalam bahasa Belanda pada 1913<br />
di koran De Expres milik Indische<br />
Partij (IP), bertiras 1.500<br />
eksemplar dan sebagian besar<br />
dibaca oleh kalangan Indo negara<br />
kolonial belum menghitung<br />
dampak dan ongkos politik akibat<br />
tulisan tersebut. Namun, ketika<br />
tulisan itu diterjemahkan ke dalam<br />
bahasa Melayu dan dicetak dalam<br />
bentuk pamflet dan beredar luas<br />
ke berbagai kalangan bumiputera,<br />
barulah negara menyadari<br />
dampak tulisan tersebut terhadap<br />
kaum bumiputera yang lebih luas.<br />
Bahasa Melayu dipahami oleh<br />
sebagian besar penduduk di<br />
Hindia Belanda. Inilah yang<br />
menjadi salah satu alasan<br />
pembuangan tiga tokoh IP yaitu<br />
Soewardi, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo<br />
dan Douwes Dekker ke<br />
negeri Belanda. Meskipun<br />
ketiganya dibuang, tak ada<br />
gerakan massa yang lahir akibat<br />
terbitnya pamflet Soewardi itu.<br />
Negara kolonial dan aparatusnya<br />
masih terlalu kuat dan tangguh<br />
untuk dijatuhkan hanya lewat<br />
sebuah pamflet. Namun, pamflet<br />
Soewardi justru menyadarkan dan<br />
membuka pikiran kaum bumiputera<br />
tentang kolonialisme yang<br />
dipraktikkan di Hindia Belanda.<br />
Nasib serupa seperti<br />
dialami tiga serangkai itu juga<br />
terjadi pada beberapa pengarang<br />
lainnya seperti Darsono, Mas<br />
Marco Kartodikromo dan Semaoen.<br />
Semaoen dijebloskan ke dalam<br />
bui oleh pemerintah kolonial<br />
karena menerjemahkan tulisan<br />
Sneevliet yang kemudian diterbitkan<br />
dalam Sinar Hindia pada<br />
1918 berjudul “Kelaparan dan<br />
Pertoendjoekan Koeasa”. Tampaknya<br />
pemerintah kolonial<br />
sangat takut terhadap dampak pe-<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
11
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
laporan utama<br />
Melayu-an tulisan tersebut<br />
terhadap kaum bumiputera yang<br />
lebih luas. Tulisan tersebut<br />
mewartakan bahwa negara<br />
kolonial lebih mendahulukan<br />
kepentingan kaum modal<br />
daripada menuntaskan masalah<br />
kelaparan. Logika kolonialisme<br />
dalam mengatur tata kehidupan<br />
di Hindia Belanda itulah yang<br />
dikritik oleh kaum pergerakan,<br />
meski harus berujung pada<br />
pemenjaraan atau pengasingan<br />
para aktivisnya.<br />
Kontrol terhadap rakyat<br />
jajahan dalam hal bacaan juga<br />
d i l e g a l k a n d a l a m b e n t u k<br />
pembentukan Kantoor voor de<br />
Volkslectuur/ Balai Poestaka<br />
pada 1917. Peran penting Balai<br />
Poestaka tidak terletak pada<br />
fungsinya sebagai publishing<br />
house semata, tapi justru sebagai<br />
“clearing house” bagi rakyat<br />
Hindia Belanda. Pemilihan<br />
naskah, penyuntingan, dilakukan<br />
secara ketat sesuai prosedur<br />
tatanan kolonial oleh para<br />
redaktur dan editornya. Oleh<br />
karena itu, dalam bahasa kaum<br />
pergerakan, “Ra'jat haroes tidak<br />
menoeroet nasehat-nasehat jang<br />
'baik' dalam boekoe-boekoe dari<br />
volkslectuur itoe, karena 'baik'<br />
disitoe boekan baik boeat klas<br />
jang miskin.” Dari Balai Poestaka<br />
inilah, gagasan tentang Hindia<br />
yang “tertib” dan “apolitis”<br />
b e r u s a h a d i b a n g u n d a n<br />
distandarkan. Reaksi pemerintah<br />
terhadap bacaan yang baik, dan<br />
juga bahasa yang baik, untuk<br />
rakyat muncul sebagai jawaban<br />
t e r h a d a p b e r k e m b a n g n y a<br />
bacaan yang diproduksi oleh<br />
kaum pergerakan, yang juga<br />
mengusung bahasa Melayu<br />
pasar di dalamnya. Atau, menurut<br />
pandangan pemerintah kolonial<br />
sebagai “batjaan liar”. Maka,<br />
julukan terhadap Balai Poestaka<br />
sebagai “serigala kolonial berbulu<br />
domba” melekat pada institusi<br />
budaya ini. Balai Poestaka juga<br />
berupaya menjalankan fungsi<br />
sosial sebagai penghubung<br />
antara pengarang dan pembacanya,<br />
seperti yang dijalankan<br />
oleh kaum pergerakan melalui<br />
“batjaan liar”. Sejumlah kategori<br />
dalam hubungan sosial seperti<br />
yang dikehendaki oleh para<br />
kolonialis di tubuh Balai Poestaka<br />
dicoba diterapkan dalam terbitan<br />
mereka. Upaya pelanggengan<br />
kekuasaan secara budaya ini<br />
terus berlangsung hingga masa<br />
akhir negara kolonial. Dalam<br />
pandangan negara kolonial,<br />
rakyat tetaplah harus mendapat<br />
bacaan yang baik, tentunya<br />
dengan bahasa, logika, tema dan<br />
standar tertentu yang dikehendaki<br />
oleh mereka.<br />
Kebijakan yang ditempuh<br />
pemerintahan militer Jepang<br />
selama tiga setengah tahun<br />
kekuasaannya di Indonesia juga<br />
tak jauh berbeda dari apa yang<br />
dilakukan oleh pemerintah Hindia<br />
Belanda. Kendati penguasa<br />
Jepang mendorong pertumbuhan<br />
bahasa Indonesia dan melarang<br />
bahasa Belanda dalam segala<br />
bentuknya, bacaan tetap saja<br />
menjadi bagian penting dari<br />
“kekuasaan lunak” Jepang di<br />
Indonesia. Terbitan atau bacaan<br />
selama era pemerintahan militer<br />
Jepang juga jauh dari hal-hal<br />
yang bersifat politis. Pengetahuan<br />
praktis dalam hal bercocok<br />
tanam misalnya mendominasi<br />
tema-tema bacaan selama kurun<br />
ini. Kontrol tetap diberlakukan<br />
atas bacaan yang muncul dan<br />
beredar di masyarakat. Pembatasan<br />
jumlah terbitan juga diberlakukan<br />
dengan maksud memudahkan<br />
kontrol atas bacaan. Sendenbu<br />
(Departemen Propaganda) yang<br />
dibentuk pada Agustus 1942 dan<br />
m e m b a w a h k a n b e b e r a p a<br />
organisasi propaganda menjadi<br />
salah satu institusi yang bertanggung<br />
jawab atas propaganda<br />
dan informasi yang beredar.<br />
Pemerintahan militer Jepang<br />
memberi tekanan pada tiga hal<br />
penting yaitu bagaimana menyita<br />
hati rakyat, mengindoktrinasi dan<br />
menjinakkan rakyat. Mobilisasi<br />
dan kontrol menjadi kata kunci<br />
keberhasilan tujuan Jepang<br />
tersebut. Rakyat, dalam hal ini<br />
kaum pergerakan, juga tak kalah<br />
kreatif merespons represi<br />
pemerintahan Jepang. Berbagai<br />
cara pun dilakukan oleh kaum<br />
pergerakan misalnya mengganti<br />
sampul buku dengan hal-hal yang<br />
berbau komersil atau dengan iklan<br />
produk tertentu, sementara isi<br />
buku justru menyangkut pendidikan<br />
politik atau kilasan berita<br />
perjuangan. Strategi seperti itu<br />
dilakukan agar buku tidak mudah<br />
dikenali atau disita oleh kenpeitai.<br />
Pasca proklamasi 17<br />
Agustus 1945, tidak ada berita<br />
yang menonjol menyangkut<br />
pelarangan sebuah buku. Perang<br />
melawan pasukan Sekutu dan<br />
Belanda menjadi fokus semua<br />
pihak. Selama era revolusi itu,<br />
berbagai bacaan tetap terbit<br />
terutama yang diterbitkan atas<br />
nama partai, serikat buruh, atau<br />
organisasi lainnya. Hingga<br />
pertengahan 1950-an tidak ada<br />
catatan ihwal pelarangan buku.<br />
Pelarangan mulai terjadi lagi pada<br />
masa Demokrasi Terpimpin.<br />
Situasi darurat perang membuat<br />
militer menjadi ujung tombak<br />
pelarangan buku. Para korban<br />
pelarangan selama era Demokrasi<br />
Terpimpin antara lain ialah<br />
Pramoedya Ananta Toer (Hoa Kiau<br />
di Indonesia), Mohammad Hatta<br />
(Demokrasi Kita). Keragaman<br />
dalam pelarangan di era ini<br />
menunjukkan bahwa belum ada<br />
suatu kekuatan dominan yang bisa<br />
melakukan tindakan sewenangwenang<br />
dalam pengambilan<br />
keputusan menyangkut nasib<br />
sebuah buku.<br />
Pelarangan buku dalam<br />
jumlah besar tercatat dilakukan<br />
s e l a m a e r a p e m e r i n t a h a n<br />
Soeharto. Masyarakat juga kian<br />
jauh aksesnya untuk mengetahui<br />
secara persis alasan pelarangan<br />
sebuah buku. “Ketertiban umum”<br />
seringkali menjadi alasan umum<br />
yang dipakai negara untuk<br />
melarang sebuah buku. Sifat karet<br />
alasan itu pun menuai kritik.<br />
Protes dalam skala kecil memang<br />
ada, tetapi tetap tidak mampu<br />
mengubah keputusan pemerintah<br />
untuk melarang sebuah buku.<br />
Ada beberapa kriteria<br />
mengapa sebuah buku dilarang<br />
s e l a m a e r a p e m e r i n t a h a n<br />
Soeharto, yaitu merusak persatuan<br />
dan kesatuan bangsa dan<br />
negara; mengandung paham atau<br />
ajaran Marxisme-Leninisme<br />
12<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
laporan utama<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
/komunisme; mengganggu kehidupan<br />
beragama di Indonesia<br />
atau penodaan agama tertentu;<br />
merendahkan martabat kepala<br />
negara atau merongrong kewibawaan<br />
pemerintah; memutarbalikkan<br />
sejarah dan menonjolkan<br />
tokoh tertentu dalam sejarah.<br />
Banyaknya kriteria untuk melarang<br />
sebuah buku di era<br />
pemerintahan Soeharto ini<br />
menunjukkan bahwa betapa<br />
negara tak mau diusik hanya oleh<br />
sebuah buku. Di sisi lain, hal itu<br />
juga menunjukkan bahwa negara<br />
tetap memperlakukan rakyatnya<br />
secara tidak cerdas, dengan cara<br />
memberikan buku yang dianggap<br />
baik setelah melewati “institusi”<br />
bernama clearing house. Jalan<br />
pikiran aparatur pemerintahan<br />
Soeharto dalam hal pelarangan<br />
buku tak berbeda dengan yang<br />
dilakukan oleh negara kolonial<br />
melalui institusi Balai Poestaka<br />
dulu. Kontrol bacaan yang<br />
berujung pada kontrol pikiran<br />
tetaplah penting dan diperlukan<br />
bagi kelangsungan sebuah rezim<br />
dalam mengelola kekuasaannya.<br />
Masyarakat atau kalangan ahli<br />
yang berkompeten di bidangnya<br />
juga tak punya pengaruh apa pun<br />
untuk menghentikan dilarangtidaknya<br />
sebuah buku.<br />
S a l a h s a t u k o r b a n<br />
pelarangan yang buku-bukunya<br />
terbanyak dilarang adalah<br />
Pramoedya Ananta Toer. Aktivitas<br />
kebudayaannya sebagai aktivis<br />
Lekra (Lembaga Kebudajaan<br />
Rakjat) di era pemerintahan<br />
Soekarno menjadi salah satu<br />
alasan pelarangan atas sejumlah<br />
karyanya. Buku karya Toer pula<br />
yang kemudian menyeret mahasiswa<br />
aktivis di Yogyakarta pada<br />
awal 1980-an diajukan ke<br />
pengadilan karena memperdagangkan<br />
buku-buku yang dilarang:<br />
Bumi Manusia dan Anak<br />
Semua Bangsa. Toer memang<br />
fenomenal dalam konteks<br />
pelarangan buku di Indonesia.<br />
Pemberitaan tentang dirinya dan<br />
karya-karyanya di luar negeri<br />
sekaligus pemuatan namanya<br />
dalam daftar para calon penerima<br />
Nobel Sastra setiap tahun berb<br />
a n d i n g t e r b a l i k d e n g a n<br />
perlakuan yang diterimanya di<br />
tanah airnya. Bangsa Indonesia<br />
pun terpaksa harus membaca<br />
k a r y a - k a r y a To e r s e c a r a<br />
sembunyi-sembunyi atau bahkan<br />
tidak pernah sama sekali,<br />
sedangkan berbagai bangsa di<br />
luar Indonesia justru menikmatinya<br />
dalam bahasa mereka sendiri.<br />
Toer adalah salah satu pengarang<br />
Indonesia yang karya-karyanya<br />
paling banyak diterjemahkan ke<br />
dalam berbagai bahasa di dunia.<br />
Pelarangan buku juga<br />
telah menutup rapat-rapat pintu<br />
pengetahuan bagi masyarakat<br />
untuk mengetahui tentang apa<br />
yang dilarang untuk dibaca. Jika<br />
tujuan ini yang dikehendaki oleh<br />
negara sejak era kolonial, maka<br />
hal ini salah perhitungan karena<br />
rakyat bukanlah robot atau<br />
“organisme” yang mati dan tak<br />
bergerak. Rakyat tetap punya daya<br />
kreatif untuk mengatasi berbagai<br />
pembatasan atau akses terhadap<br />
bacaan dan kontrol bacaan dari<br />
negara. Menganggap bahwa<br />
rakyat selalu bodoh juga keliru<br />
karena mereka punya kecerdasan<br />
tersendiri untuk merespons apa<br />
p u n y a n g d a t a n g n y a d a r i<br />
penguasa. Melarang sebuah buku<br />
sama halnya dengan memaksakan<br />
kehendak penguasa atas<br />
sebuah bacaan yang baik bagi<br />
rakyatnya. Rakyat tidak diberi<br />
kesempatan atau mempunyai hak<br />
untuk menentukan pilihan bacaan<br />
yang menurutnya baik-tidaknya,<br />
seperti tercermin dalam pelarangan<br />
lima buku di akhir 2009.<br />
Melarang sebuah buku<br />
dan dampak selanjutnya dari<br />
pelarangan itu tampaknya tidak<br />
sepenuhnya dipahami oleh aparatus<br />
pemerintahan. Pelarangan<br />
buku oleh negara tetap tidak efektif<br />
untuk mengontrol pikiran atau<br />
bacaan bagi rakyatnya, apalagi<br />
menjinakkan pikiran rakyat. Ada<br />
saja kreativitas untuk tidak terjebak<br />
dalam pola atau logika berpikir<br />
yang berusaha diberikan oleh<br />
negara lewat pelarangan buku.<br />
Apa yang dilakukan oleh generasi<br />
pergerakan 1910-20-an dan<br />
sesudahnya terhadap kontrol atas<br />
bacaan justru tidak menyurutkan<br />
langkah mereka untuk tetap<br />
mempersoalkan nasion dan kekuasaan<br />
di dalamnya, sekaligus<br />
membangun hubungan sosial<br />
dengan rakyat melalui bacaan.<br />
Dalam lingkup yang lebih luas, di<br />
era global seperti sekarang,<br />
melarang sebuah buku juga<br />
menjadi tolok ukur bagi penguasa<br />
dalam mengelola kekuasaannya.<br />
Pelarangan buku juga membuat<br />
pertukaran antar gagasan tidak<br />
berkembang, bahkan justru malah<br />
membelenggu. Lalu, tatanan<br />
sosial macam apa yang ingin<br />
dibangun dalam sebuah nasion<br />
seperti Indonesia dengan pelarangan<br />
sebuah buku, berikut<br />
standar dan kriteria di dalamnya.<br />
Dan, seberapa besar kontribusi<br />
rakyat dalam menentukan dan<br />
membangun nasion itu. Proyek<br />
bersama untuk membangun<br />
Indonesia yang lebih baik,<br />
menjunjung konstitusi dan hukum,<br />
demokratis, menghargai perbedaan<br />
pendapat, pluralisme dan<br />
multikulturalisme seharusnya<br />
menjadi syarat dan kesepakatan<br />
bersama semua anak bangsa.<br />
Catatan sejarah pelarangan buku<br />
di Indonesia seharusnya menjadi<br />
pelajaran berharga bagi negara<br />
sebelum mengeluarkan keputusan<br />
pelarangan sebuah buku.<br />
Kepustakaan<br />
Farid, Hilmar. “Kolonialisme dan<br />
Budaya: Balai Poestaka di<br />
Hindia Belanda,” Prisma, No.<br />
10, Oktober 1991.<br />
Jaringan Kerja Budaya.<br />
M e n e n t a n g P e r a d a b a n :<br />
Pelarangan Buku di Indonesia.<br />
Jakarta: <strong>Elsam</strong>, 1999.<br />
Kurasawa, Aiko. Mobilisasi dan<br />
K o n t r o l : S t u d i Te n t a n g<br />
Perubahan Sosial di Pedesaan<br />
Jawa 1942-1945. Jakarta:<br />
Grasindo, 1993.<br />
“Pelarangan Buku,” Media<br />
Kerja Budaya, No. 3, <strong>Februari</strong><br />
1996.<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
13
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
perspektif<br />
Seratus Hari SBY<br />
Mengulang Periode Lalu,<br />
Jaminan HAM Hanya Normatif<br />
Oleh Zainal Abidin, SH<br />
(Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI))<br />
ejak dilantik pada 20<br />
Oktober 2009 silam,<br />
Presiden Susilo Bambang<br />
Yudhoyono (SBY) memulai Speriode keduanya sebagai<br />
presiden bersama Wakil Presiden<br />
Boediono. Selama periode<br />
pemerintahan sebelumnya (2004-<br />
2009 isu hak asasi manusia (HAM)<br />
hanya mengedepankan jaminan<br />
normatif dengan diproduksinya<br />
regulasi tentang perlindungan hak<br />
asasi manusia, namun miskin<br />
dalam implementasi.<br />
Jaminan normatif inipun<br />
masih dicederai dengan gagalnya<br />
implementasi sejumlah instrumen<br />
HAM yang penting seperti<br />
ratifikasi Statuta Roma, ratifikasi<br />
Konvensi Buruh Migran dan terus<br />
munculnya sejumlah kebijakan<br />
daerah yang melanggar HAM.<br />
100 hari SBY menjadi<br />
sorotan penting bagu publik<br />
untuk melihat perspektif SBY<br />
terkait masalah-masalah HAM<br />
yang urgent dan harus menjadi<br />
prioritas.<br />
Keluarga Orang Hilang melakukan Audiensi ke Kejaksaan Agung<br />
dok.http://ikohi.blogspot.com/2009/10/seruan-terbuka-01ikohiistx2009-saudara.html<br />
Janji Indah<br />
Selama pemerintahannya, tidak<br />
banyak yang dikatakan Presiden<br />
SBY tentang HAM. Presiden<br />
menempatkan hak asasi manusia<br />
dalam konteks penegakan<br />
hukum, dengan mengedepankan<br />
konsep rule of law. Pada bulan<br />
April 2008, dalam pembukaan<br />
Konvensi Hukum Nasional tentang<br />
UUD 1945, SBY menegaskan<br />
pentingnya kebebasan (freedom)<br />
yang harus berjalan beriringan<br />
dengan mengindahkan tatanan<br />
hukum dan rule of law.<br />
Dalam Pidato Kenegaraan<br />
serta Keterangan Pemerintah<br />
atas RUU APBN 2009, SBY<br />
menyatakan dalam berdemokrasi<br />
perlu menjalankan kebebasan<br />
dengan menghargai hak-hak dan<br />
kebebasan orang lain serta<br />
dengan menghargai ketertiban<br />
dan pranata hukum (the rule of<br />
law). Presiden menegaskan perlu<br />
ada kemampuan untuk menjaga<br />
keseimbangan antara hak dan<br />
tanggung jawab, antara kebebasan<br />
dan ketertiban yang akan<br />
menentukan kemajuan demokrasi<br />
di Indonesia. SBY menegaskan<br />
tidak ada tempat bagi anarki<br />
karena demokrasi terlalu berharga<br />
untuk dirusak oleh anarki. SBY<br />
tegas menyatakan negara tidak<br />
boleh kalah dan tidak akan kalah<br />
t e r h a d a p a n a r k i s m e d a n<br />
1<br />
kekerasan.<br />
Pandangan lainnya yang<br />
terkait dengan HAM, misalnya<br />
dalam pidato kenegaraan<br />
memperingati Hari Kemerdekaan<br />
pada 2009, SBY menyatakan di<br />
m a s a d e p a n p e m a t a n g a n<br />
demokrasi harus berjalan seiring<br />
14<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
perspektif<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
dengan prinsip-prinsip dasar<br />
konstitusionalisme. Demokrasi<br />
harus semakin egaliter yaitu<br />
demokrasi yang makin meneguhkan<br />
pelaksanaan mekanisme<br />
saling kontrol dan saling imbang<br />
(check and balance) dalam<br />
praktek kehidupan politik kita.<br />
Demokrasi yang berlandaskan<br />
pada penghormatan dan pelaksanaan<br />
penegakan hukum yang<br />
adil dan bermartabat (rule of law).<br />
Demokrasi juga harus menjamin<br />
dan melindungi kebebasan dan<br />
hak-hak asasi manusia. SBY<br />
menyatakan hendak menghadirkan<br />
konstitusionalisme dan<br />
checks and balances dalam kehidupan<br />
bernegara, mewujudkan<br />
negara yang menjunjung tinggi<br />
hak-hak asasi manusia, tanpa<br />
diskriminasi, menjamin hak warga<br />
negara untuk berserikat, berkumpul,<br />
dan menyatakan pendapat,<br />
termasuk hadirnya kebebasan<br />
p e r s . K i t a m e n d a m b a k a n<br />
pemilihan umum yang aman,<br />
damai, jujur dan adil. SBY<br />
mengharapkan hukum dan<br />
keadilan ditegakkan, serta<br />
korupsi, kolusi dan nepotisme<br />
terus diberantas.<br />
Dalam janji kampanyenya<br />
SBY menjawab dua isu<br />
hak asasi manusia; pertama, soal<br />
pelanggaran HAM masa lalu yang<br />
dijawab dengan rekonsiliasi<br />
nasional. SBY tampak tidak<br />
berani secara tegas mengemukakan<br />
soal penegakan hukum dan<br />
pengadilan. Kedua, soal pelanggaran<br />
HAM yang terjadi sebagai<br />
akibat semburan lumpur di<br />
Sidoarjo yang disikapi dengan<br />
perlunya revisi kebijakan soal<br />
penanganannya.<br />
Semua yang menjadi janji<br />
Presiden SBY di atas tampak<br />
sangat indah karena hendak<br />
meletakkan bangunan negara<br />
hukum (rule of law) menjadi<br />
panglima di Indonesia. Dari<br />
komitmen ini, rule of law haruslah<br />
dipahami sebagai implementasi<br />
prinsip-prinsip penting dalam<br />
suatu negara hukum tersebut.<br />
Prinsip-prinsip tersebut di<br />
antaranya adalah supremasi<br />
hukum (supremacy of law),<br />
p e r s a m a a n d a l a m h u k u m<br />
(equality before the law), asas<br />
legalitas (due process of law),<br />
pembatasan kekuasaan, adanya<br />
organ-organ eksekutif yang bersifat<br />
indepen-den, peradilan bebas dan<br />
tidak memihak (independent and<br />
impartial judiciary), perlindungan<br />
hak asasi manusia, hukum berfungsi<br />
sebagai sarana mewujudkan tujuan<br />
kesejahteraan (welfare rechtsstaat),<br />
dan adanya transparansi serta<br />
kontrol Sosial.<br />
Lain Janji, Lain Tindakan: Desakan<br />
Dulu, Baru Ada Program!<br />
Pada November 2009, SBY<br />
kemudian mengeluarkan program<br />
100 hari dengan menempatkan 15<br />
program pilihan di dalamnya. Tidak<br />
ada satu pun dari 15 program<br />
pilihan tersebut yang jelas menunjukkan<br />
pada upaya untuk adanya<br />
perlindungan, pemajuan, penghormatan<br />
dan penegakan HAM.<br />
Satu-satunya yang agak<br />
bisa dipahami adalah adanya program<br />
pemberantasan 'mafia hukum'. Hal<br />
ini dikatakan agak mendekati karena<br />
tujuan besar dari pemberantasan mafia<br />
hukum tersebut adalah membenahi<br />
sektor peradilan yang dianggap<br />
mengalami kerusakan luar biasa<br />
karena merajalelanya para 'makelar<br />
kasus'. Terlebih dari adanya kasus<br />
Bibit-Chandra dengan terkuaknya<br />
dugaan adanya rekayasa kriminalisasi<br />
terhadap mereka.<br />
Program pemberantasan<br />
mafia hukum ini sebetulnya hanya<br />
sebagai respon semata dari SBY<br />
untuk menjawab keresahan publik.<br />
Terbukanya rekaman dugaan<br />
rekayasa kriminalisasi di Mahkamah<br />
Konstitusi membuka mata Presiden<br />
bahwa makelar kasus sedemikian<br />
parahnya. Kemudian publik mengharapkan<br />
adanya tindakan konkrit<br />
dari Presiden. Tanpa adanya<br />
peristiwa ini mustahil Presiden<br />
merespon dengan cepat dan<br />
segara membentuk satuan tugas<br />
mafia hukum.<br />
Tampak bahwa kebijakan<br />
SBY dilakukan tidak didasari oleh<br />
sebuah platform yang jelas, dalam<br />
penegakan hukum dan HAM.<br />
Kebijakan penegakan hukum dan<br />
HAM tampil hanya sebagai katakata<br />
manis.<br />
Lihat misalnya, yang<br />
terjadi dengan kasus penghilangan<br />
paksa 1997-1998, di mana pada<br />
28 September 2009 Dewan<br />
Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan<br />
sejumlah rekomendasi,<br />
yaitu: 1) merekomendasikan<br />
kepada Presiden untuk membentuk<br />
pengadilan hak asasi<br />
manusia (HAM) ad hoc; 2) merekomendasikan<br />
kepada Presiden<br />
serta segenap institusi pemerintah<br />
dan pihak-pihak terkait untuk<br />
segera melakukan pencarian<br />
terhadap 13 orang yang oleh<br />
Komnas HAM masih dinyatakan<br />
hilang; 3) merekomendasikan<br />
kepada Pemerintah untuk merehabilitasi<br />
dan memberikan<br />
kompensasi terhadap keluarga<br />
korban yang hilang; dan 4)<br />
merekomendasikan kepada<br />
Pemerintah agar segera meratifikasi<br />
Konvensi Anti Penghilangan<br />
Paksa sebagai bentuk komitmen<br />
dan dukungan untuk menghentikan<br />
praktek penghilangan paksa di<br />
Indonesia.<br />
Tak ada kata-kata dan<br />
pandangan resmi dari Presiden<br />
tentang rekomendasi DPR<br />
tersebut. Padahal, menilik dari<br />
hukum yang berlaku, rekomendasi<br />
DPR untuk membentuk pengadilan<br />
HAM adalah rekomendasi<br />
yang dibuat berdasarkan hukum.<br />
Seharusnya Presiden kemudian<br />
mengeluarkan Keputusan Presiden<br />
(Keppres) untuk membentuk<br />
pengadilan HAM ad hoc (lihat<br />
Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000<br />
tentang Pengadilan HAM).<br />
Sikap “diam” Presiden<br />
SBY dapat dibaca dalam<br />
beberapa kemungkinan; pertama,<br />
kurangnya desakan publik untuk<br />
pembentukan pengadilan HAM ad<br />
hoc. Kedua, konfigurasi politik dan<br />
situasi politik saat ini yang<br />
membuat SBY ragu untuk memberikan<br />
rekomendasi pembentukan<br />
pengadilan HAM ad hoc. Ketiga,<br />
presiden SBY tidak terlalu<br />
nyaman dengan pengadilan HAM<br />
dan mungkin memilih jalan<br />
rekonsiliasi.<br />
Sikap Presiden yang<br />
cuek dengan rekomendasi DPR<br />
ini bertentangan dengan jargon<br />
yang selalu digaungkan tentang<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
15
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
perspektif<br />
demokrasi yang berlandaskan<br />
pada penghormatan dan pelaksanaan<br />
penegakan hukum yang<br />
adil dan bermartabat (rule of law)<br />
serta menjamin dan melindungi<br />
kebebasan dan hak-hak asasi<br />
manusia. Jika Presiden konsisten<br />
dengan pandangannya, seharusnya<br />
pembentukan pengadilan<br />
HAM ad hoc dalam kasus<br />
penghilangan paksa 1997-1998<br />
ini segera diwujudkan.<br />
Reformasi Institusi Mandeg,<br />
Buruknya Pilihan Pejabat<br />
Publik<br />
Soal lain yang memperburuk<br />
program 100 hari SBY khususnya<br />
di bidang HAM adalah pemilihan<br />
pejabat-pejabat publik yang<br />
“terkesan” sembarangan dan<br />
pembiaran terhadap pejabat<br />
publik yang selama ini gagal<br />
mendorong penegakan HAM,<br />
seperti di institusi kepolisian,<br />
kejaksaan, dan Kementrian<br />
Hukum dan HAM.<br />
Institusi Kepolisian dan<br />
Kejaksaan pada pertengahan<br />
tahun lalu, sedemikian terpuruk<br />
dengan adanya kasus Bibit-<br />
Chandra. Demikian pula sebelumnya<br />
dengan kurang memadainya<br />
penanganan kasus pembunuhan<br />
aktivis HAM Munir. Bahkan<br />
Kejaksaan Agung di bawah<br />
Hendarman Supandji tampak<br />
enggan untuk melanjutkan hasil<br />
penyelidikan Komnas HAM atas<br />
dugaan pelanggaran HAM yang<br />
berat. Serangkaian kegagalan<br />
tersebut seharusnya disikapi SBY<br />
dengan sejumlah pembenahan<br />
dan penggantian pimpinan di<br />
kedua institusi tersebut.<br />
Tidak jelasnya strategi<br />
SBY dibidang hukum dan HAM<br />
terlihat dalam pemilihan pejabat di<br />
dalam Kementrian Hukum dan<br />
HAM Kementrian Hukum dan<br />
HAM membutuhkan keahlian dan<br />
pemahaman dibidang hukum dan<br />
HAM. Hal ini penting untuk<br />
menentukan kebijakan HAM<br />
Pemerintah yang menjadi<br />
tanggung jawab Kementrian ini,<br />
seperti penyusunan Rencana Aksi<br />
Nasional HAM 201-2014 dan<br />
upaya ratifikasi berbagai instrumen<br />
internasional HAM.<br />
Hal ini berimbas juga<br />
pada pemilihan pejabat publik<br />
lainnya. Misalnya, perwakilan<br />
Pemerintah yang diwakili oleh<br />
Kementrian Hukum dan HAM<br />
ternyata melakukan proses<br />
pemilihan Hakim Konstitusi yang<br />
tidak transparan dan tanpa<br />
masukan dari publik. Padahal,<br />
saat ini Mahkamah Konstitusi<br />
merupakan salah satu institusi<br />
yang cukup bisa diharapkan untuk<br />
mewujudkan jaminan hak asasi<br />
manusia yang dijamin oleh<br />
konstitusi.<br />
Niat Baik<br />
Hal yang paling melegakan dari<br />
100 hari pemerintahan SBY<br />
adalah adanya kesepakatan<br />
Pemerintah dan DPR tentang<br />
program Legislasi Nasional<br />
(Prolegnas) <strong>2010</strong>-2014 yang<br />
sebagian di antaranya berkaitan<br />
dengan hak asasi manusia.<br />
Bahkan beberapa program<br />
legislasi tersebut masuk adalah<br />
daftar RUU Prioritas <strong>2010</strong>,<br />
seperti: 1) RUU Perubahan UU<br />
K o m i s i K e b e n a r a n d a n<br />
Rekonsiliasi, 2) RUU Perubahan<br />
UU No. 26 Tahun 2000 tentang<br />
Pengadilan HAM, 3) RUU<br />
Perubahan UU No. 39 Tahun 1999<br />
t e n t a n g H A M , 4 ) R U U<br />
Perlindungan Pekerja HAM, 5)<br />
RUU Bantuan Hukum, 6) RUU<br />
KUHAP, 7) RUU KUHP, 8) RUU<br />
Perlindungan Pekerja Rumah<br />
Tangga, dan RUU Perlindungan<br />
dan Pemberdayaan Petani dan<br />
Nelayan.<br />
Beberapa RUU tersebut<br />
dapat menjadi jawaban dari<br />
sejumlah persoalan mendasar<br />
dalam penegakan hukum dan<br />
HAM. Untuk pelanggaran HAM<br />
berat ia akan memberikan<br />
landasan hukum pembentukan<br />
Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi<br />
dan perbaikan pengadilan HAM.<br />
RUU Bantuan Hukum dan KUHAP<br />
akan memberikan jaminan<br />
peradilan yang adil dan tidak<br />
memihak serta perlindungan<br />
kaum miskin. Untuk itu perlu<br />
pengawalan dari masyarakat<br />
karena pengalaman masa lalu<br />
mengajarkan bagaimana kebijakan<br />
diselewengkan untuk motif politik<br />
yang justru meminggirkan hak<br />
asasi manusia.<br />
Prediksi HAM 5 Tahun ke Depan<br />
Melihat program kerja SBY di<br />
periode kedua ini, tampaknya<br />
bidang HAM kurang mendapatkan<br />
perhatian. Kepemimpinan SBY<br />
yang sibuk dengan pencitraan,<br />
membuat program atau respon<br />
dilakukan jika ada desakan publik.<br />
Misalnya pemberitaan tentang<br />
pengadilan terhadap rakyat kecil<br />
yang mengusik rasa keadilan dan<br />
kasus Prita. Sementara kasus<br />
penghilangan paksa 1997-1998,<br />
meski SBY mempunyai kewajiban<br />
hukum untuk mengeluarkan<br />
Keppres tentang Pengadilan HAM<br />
ad hoc, hal itupun tidak dilakukan.<br />
S B Y m e r a s a c u k u p<br />
dengan memproduksi regulasi<br />
HAM, padahal implementasinya<br />
juga bergantung kepada kebijakan<br />
politik Pemerintah, dukungan institusiinstitusi<br />
negara dan aparatnya.<br />
Dalam periode kepemimpinan<br />
SBY ke depan, jika citranya tidak<br />
“diganggu” dengan soal HAM,<br />
maka penegakan HAM nampaknya<br />
akan tetap menjadi persoalan<br />
kelas dua bagi SBY.<br />
Keterangan<br />
1 . P i d a t o K e n e g a r a a n s e r t a<br />
Keterangan Pemerintah atas RUU<br />
APBN 2009 Beserta Nota<br />
Keuangannya di depan Rapat<br />
Paripurna Dewan Perwakilan<br />
Rakyat (DPR), 15 Agustus 2009.<br />
16<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
daerah<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
Perda Gerbang Marhamah Cianjur:<br />
Mengikat Tanpa Tali<br />
Oleh Miftahus Surur<br />
Kepala Program Tankinaya Institute)<br />
eberapa berita mengejutkan<br />
muncul dari sudut<br />
Cianjur, salah satu<br />
kabupaten di Propinsi BJawa Barat. Pada pertengahan<br />
Desember 2009, dugaan korupsi<br />
ditujukan kepada dua orang<br />
penegak hukum yang bekerja<br />
sebagai staf di Pengadilan Tinggi<br />
Agama. Lalu, <strong>Januari</strong> tahun ini,<br />
salah satu anggota DPRD Cianjur<br />
periode 2009-2014 divonis<br />
penjara dan denda Rp 50 juta<br />
akibat dugaan penyimpangan<br />
dana bantuan sosial. Pada sisi<br />
lain, sebuah laporan mengejutkan<br />
juga datang dari Yayasan Gerakan<br />
Penanggulangan Narkoba dan<br />
AIDS (GNPA) Kabupaten Cianjur<br />
yang menyebutkan bahwa<br />
terhitung September 2008, jumlah<br />
perempuan pekerja seksual yang<br />
beroperasi di Cianjur sekitar 1.200<br />
orang dengan jumlah pelanggan<br />
sekitar 6.000 orang. Semua data<br />
tersebut mengemuka justru di saat<br />
kabupaten ini sedang gegap<br />
dengan identifikasi dirinya sebagai<br />
kota yang mengedepankan<br />
akhlakul karimah dalam seluruh<br />
kehidupan masyarakatnya.<br />
Akhlakul karimah atau<br />
kebaikan tata laku yang diadopsi<br />
dari terminologi agama (Islam) itu<br />
digamit oleh sebagian entitas<br />
masyarakat Cianjur untuk<br />
mendorong terbentuknya kehidupan<br />
masyarakat yang bermoral.<br />
R u m u s a n y a n g k e m u d i a n<br />
disepakati melalui proses politik<br />
dan akhirnya melahirkan Peraturan<br />
Daerah No 03 Tahun 2006 tentang<br />
G e r a k a n P e m b a n g u n a n<br />
Masyarakat Berakhlaqul Karimah<br />
atau yang popular dengan<br />
sebutan Gerbang Marhamah itu<br />
tampak tak berguna, bukan hanya<br />
rumusan normatifnya yang terlihat<br />
ganjil, melainkan juga kondisi<br />
empiris sosialnya yang jauh dari<br />
imajinasi Perda itu.<br />
Paling tidak, Perda itu melalui<br />
klausul-klausulnya mengimajinasi<br />
atau beranjak dari bayangan<br />
tentang ambruknya tata laku<br />
masyarakat untuk kemudian<br />
berusaha diluruskan, dibenahi,<br />
atau ditobatkan. Sayangnya,<br />
Perda itu tidak pernah mengimajinasi<br />
bagaimana sebuah tata<br />
laku sebenarnya tidak cukup<br />
dirumuskan dalam peraturan<br />
tertulis, karena tata laku itu sendiri<br />
merupakan bagian dari sejarah<br />
hidup manusia yang lebih<br />
menyukai menyebarkan nilai atau<br />
tata laku melalui institusi keluarga<br />
atau pendidikan hidup sehari-hari.<br />
Wajar jika kemudian Perda itu<br />
ditafsirkan oleh sebagian<br />
kalangan menyimpan banyak<br />
kepentingan, seperti: upaya<br />
mengerek bendera Islam sebagai<br />
identitas masyarakat atau identitas<br />
negara, membentuk image<br />
penguasa sebagai pihak yang<br />
seolah-olah Islami, atau sekedar<br />
komoditasi ekonomi politik yang<br />
memanfaatkan momentum Otonomi<br />
Daerah untuk memperoleh kursi<br />
kekuasaan.<br />
Sekilas tentang Isi Perda<br />
Jauh sebelum Perda Gerbang<br />
Marhamah itu hadir, sekelompok<br />
orang yang membenamkan diri<br />
dalam Lembaga Pengkajian dan<br />
Pengembangan Islam (LPPI)<br />
Cianjur telah melakukan suatu<br />
telaah dan rencana strategis<br />
pengamalan Syariat Islam di<br />
Cianjur. Lembaga yang dibentuk<br />
melalui Surat Keputusan Bupati<br />
Cianjur No 34/2001 itu paling tidak<br />
menginginkan dua hal, yaitu<br />
m e m b u a t f o r m u l a s i d a s a r<br />
pelaksanaan Syariat Islam dan<br />
membuat rencana strategis<br />
(Renstra) gerakan pembangunan<br />
Monumen Gerbang Marhamah di pusat kota cianjur . Dok.www,wordpress.com<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
17
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
daerah<br />
masyarakat berakhlakul karimah.<br />
Melalui pembentukan berbagai<br />
forum pertemuan (silaturahmi),<br />
disepakatilah untuk menetapkan<br />
Renstra Gerbang Marhamah itu<br />
sebagai pijakan bagi pembentukan<br />
regulasi daerah dan memuncak<br />
dalam bentuk Peraturan Daerah<br />
(Perda).<br />
Tentu, ada yang menggelitik<br />
dari isi Perda itu. Pertama, asumsi<br />
dasar dari Perda tersebut adalah<br />
keinginan untuk menjadikan Islam<br />
sebagai satu-satunya sumber<br />
yang dirujuk. Potret ini terlihat<br />
misalnya dari berbagai istilah<br />
yang dipakai. Kata-kata seperti<br />
“akhlakul karimah”, “Alqur'an dan<br />
Sunnah”, “dakwah Islamiah”<br />
merupakan deret dari wajah yang<br />
Islam itu. Keinginan ini tentu saja<br />
kurang arif mengingat Perda<br />
disusun oleh dan diperuntukkan<br />
serta berlaku bagi seluruh<br />
masyarakat.<br />
Dalam Pasal 1 (6) misalnya,<br />
disebutkan:<br />
Gerakan Pembangunan Masyarakat<br />
B e r a k h l a q u l K a r i m a h , y a n g<br />
selanjutnya disingkat GERBANG<br />
MARHAMAH adalah merupakan<br />
upaya bersama yang di lakukan<br />
secara sistematis dan terus menerus<br />
dalam rangka mengamalkan<br />
nilainilai Akhlaqul Karimah dalam<br />
kehidupan seharihari masyarakat<br />
yang merupakan tahapan sekaligus<br />
bagian tak terpisahkan dari upaya<br />
jangka panjang masyarakat<br />
K a b u p a t e n C i a n j u r u n t u k<br />
melaksanakan serta mewujudkan<br />
Islam sebagai agama yang<br />
rohmatan lil a'lamin.<br />
Lalu, dalam pasal 1 (7)<br />
disebutkan:<br />
Akhlaqul Karimah adalah tabi'at<br />
sifat, sikap dan prilaku atau kebiasaan<br />
sesuai dengan prinsipprinsip<br />
ajaran Islam yakni akhlaq yang<br />
bersumber dari Al Quran dan<br />
Assunah.<br />
Merujuk pada satu agama<br />
sebagai landasan untuk melaksanakan<br />
peraturan daerah yang<br />
bersifat umum dan menjangkau<br />
seluruh masyarakat tentu saja<br />
tidak tepat. Dalam konteks<br />
kebangsaan yang majemuk dan<br />
melandaskan diri pada konstitusi<br />
(hukum), satu agama saja tidak<br />
bisa dijadikan klaim dan satusatunya<br />
ujung tombak dakwah<br />
yang menuntut seluruh warga<br />
masyarakat merealisasikan ajaran<br />
agama sepersis mungkin. Asas<br />
keadilan, asas bhineka tunggal<br />
ika, dan asas kebangsaan yang<br />
telah diamini oleh para pemimpin<br />
bangsa ini sebagai landas-hukum<br />
pendirian negara bangsa dan juga<br />
telah diamanatkan oleh UU No 10<br />
Tahun 2004 tentang Pembentukan<br />
Peraturan Perundang-undangan<br />
itulah yang sepatutnya dirujuk.<br />
Sayangnya, asas dan prinsipprinsip<br />
itu tidak diindahkan.<br />
Kedua, proses pembuatan<br />
Perda Gerbang Marhamah ini<br />
mengisyaratkan tidak adanya<br />
partisipasi publik yang baik.<br />
Dalam sebuah diskusi untuk<br />
membahas Perda ini pada 29<br />
<strong>Januari</strong> <strong>2010</strong> yang lalu di Cipanas,<br />
terkutiplah pernyataan dan<br />
kesaksian dari salah satu pendeta<br />
Katolik yang mengatakan bahwa<br />
orang-orang seperti dirinya tidak<br />
pernah dilibatkan dalam proses<br />
itu. Bahkan istilah 'akhlaqul<br />
karimah' yang menjadi inti dari isi<br />
Perda itu pun tidak pernah ia<br />
mengerti. Partisipasi, sepatutnya<br />
tidak hanya melibatkan orangorang<br />
tertentu secara kuantitatif<br />
b e l a k a , m e l a i n k a n j u g a<br />
representasi. Artinya, partisipasi<br />
dalam konteks pembahasan<br />
Perda ini tidak cukup hanya melibatkan<br />
banyak ulama dan cerdik<br />
pandai, melainkan juga harus<br />
melibatkan kelompok minoritas<br />
agama, bahkan penganut keyakinan<br />
lokal sekalipun.<br />
Ketiga, sebagai peraturan<br />
ternyata Perda ini tidak diiringi<br />
dengan sanksi sehingga ia lebih<br />
tepat diposisikan sebagai himbauan<br />
yang tidak meniscayakan<br />
adanya kepatuhan dan ketaatan<br />
bagi warganya. Akhlaqul karimah<br />
sebagai ruh dari Perda ini,<br />
sebagaimana disebutkan dalam<br />
pasal 3 (3), hanya sebagai<br />
pedoman dan budaya tata<br />
pergaulan hidup dalam kehidupan<br />
pribadi, keluarga, bermasyarakat<br />
dan bernegara. Jika demikian,<br />
ada atau tiadanya Perda ini tidak<br />
bisa dijadikan sebagai suatu<br />
pijakan hukum bagi masyarakat<br />
Cianjur untuk bertindak sesuai<br />
atau bertentangan dengan Perda.<br />
Lalu, apa perlunya keberadaan<br />
Perda yang ingin mengikat<br />
masyarakat tetapi tanpa tali<br />
kepatuhan dan sanksi?<br />
Pluralisme dan Hak <strong>Asasi</strong><br />
Manusia<br />
Kegelisahan yang muncul dari<br />
adanya Perda Gerbang Marhamah<br />
ini adalah ketika potret keagamaan<br />
diwarnai oleh proyek politik. Klaim<br />
para penguasa setempat yang<br />
mengatakan bahwa Kabupaten<br />
Cianjur didomisili oleh 99% warga<br />
muslim kerap menjadi legitimasi<br />
yang ampuh untuk membuat<br />
Perda bernuansa keagamaan. Hal<br />
ini juga terjadi diberbagai propinsi<br />
dan kabupaten/kota lain di mana<br />
Perda-Perda bernuansa syariat<br />
Islam disusun berdasarkan klaim<br />
mayoritas pemeluk agama Islam.<br />
Klaim tersebut seolah-olah berbanding<br />
lurus dengan pengandaian<br />
bahwa seluruh masyarakat<br />
memiliki satu sudut pandang dan<br />
praktik yang sama berkaitan<br />
dengan perilaku keagamaan<br />
ataupun moral publik.<br />
Para penguasa dan juga<br />
Perda itu tidak berusaha untuk<br />
mengerti bahwa pengandaian<br />
tentang “yang sama” itu sesungguhnya<br />
mustahil, bukan hanya<br />
karena persepsi mengenai akhlaqul<br />
karimah di kalangan muslim<br />
sendiri beragam melainkan juga<br />
setiap orang lahir dengan<br />
mengenal standar yang berbedabeda<br />
mengenai baik-buruknya<br />
akhlak. Belum lagi jika kemudian<br />
ia dipertanyakan bagi komunitas<br />
agama lain, pastilah mereka lebih<br />
tidak mengerti atau justru merasa<br />
dipaksa untuk menyetujui segala<br />
sesuatu yang berjudul dan berbau<br />
akhlaqul karimah itu. Mungkin,<br />
persoalannya tidak sekadar<br />
bagaimana merumuskan dan<br />
menjelaskan apa itu akhlaqul<br />
karimah, tokh ia bisa saja diganti<br />
dengan moral, etika, atau apapun<br />
namanya. Persoalannya lebih<br />
terletak pada keinginan kelompok<br />
mayoritas untuk mendesakkan<br />
agenda keagamaannya bagi<br />
18<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
daerah<br />
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
seluruh masyarakat yang majemuk.<br />
Padahal, belum tentu seluruh<br />
masyarakat menghendaki<br />
agama jadi penggerak identitas<br />
politik. Wajar pula jika AE Priyono<br />
(2007) sempat resah ketika<br />
lahirnya Perda semacam ini<br />
hanya sebagai proyek politik<br />
syariahisasi negara dengan<br />
menyemarakkan simbol keagamaan<br />
yang difantasikan dan dimistifikasi,<br />
di mana-mana menggemakan<br />
suara bahwa syariat Islam itu<br />
merupakan keulungan dan<br />
keagungan yang mutlak sehingga<br />
siapapun harus tunduk.<br />
Pemaksaan-pemaksaan<br />
inilah yang kemudian melahirkan<br />
kritik bahwa Perda Gerbang<br />
Marhamah dan yang sejenisnya<br />
menyimpan keinginan untuk<br />
merenggut perbedaan yang<br />
artinya pula membungkam hak<br />
masyarakat untuk bebas memilih,<br />
menentukan, dan mempraktikkan<br />
ajaran agama yang “tidak sama”<br />
dengan ajaran agama yang<br />
mainstream. Perda Gerbang<br />
Marhamah, yang ditujukan bagi<br />
seluruh warga Cianjur itu ternyata<br />
menyimpan benih-benih untuk<br />
mendiskriminasi warga pemeluk<br />
agama lain dengan tidak<br />
menganggap mereka sebagai<br />
warga yang berhak diikutkan<br />
dalam proses perumusan dan<br />
pembahasannya. Hal lain yang<br />
terlupa dari Perda Gerbang Marhamah<br />
ini adalah ketidakbolehannya<br />
untuk bertentangan dengan<br />
peraturan yang lebih tinggi.<br />
Peraturan perundang-undangan<br />
apapun termasuk Perda- juga<br />
harus dibuat melalui mekanisme<br />
pembuatan peraturan perundangundangan,<br />
serta secara substansial<br />
tidak boleh bertentangan dengan<br />
prinsip-prinsip penegakan dan<br />
perlindungan hak asasi manusia<br />
(HAM) seperti kebebasan dalam<br />
konteks hukum dan anti diskriminasi.<br />
Dalam konteks Indonesia,<br />
keberagaman baik secara sosiokultural<br />
maupun pemikiran perlu<br />
dipertimbangkan agar pembuatan<br />
suatu peraturan tidak menyimpangi<br />
kenyataan masyarakat<br />
yang majemuk itu.<br />
Jikalaupun pemerintah<br />
daerah masih ngotot ingin<br />
Pintu gerbang masuk Kota Cianjur dok: asepmuhsin.blogspot.com<br />
menegakkan Gerbang Marhamah<br />
sebagai langkah untuk mengamalkan<br />
Syariat Islam di mana<br />
dengan itu mereka akan terpelihara<br />
dari ambruknya moral,<br />
tidakkah mereka teringat pada<br />
ucapan salah satu pemikir besar<br />
di bidang politik Islam, Ali Abd<br />
Raziq yang mengatakan bahwa<br />
ketika penegakan identitas Islam<br />
itu dilakukan melalui jalur politik<br />
negara, maka justru akan<br />
mengarah pada politisasi agama<br />
atau monopoli negara terhadap<br />
agama. Karena yang muncul<br />
kemudian bukanlah warga<br />
masyarakat yang patuh terhadap<br />
agama, melainkan kelompokkelompok<br />
masyarakat yang saling<br />
tuding, saling kecam, dan<br />
b e r t a r u n g s e h i n g g a a k a n<br />
menghilangkan kemaslahatan<br />
umum itu sendiri.<br />
Tampaknya akan lebih arif jika<br />
perhatian pemerintah daerah<br />
beralih dari gegap-gempita<br />
mengatur cara berakhlaqul<br />
karimah ke arah kinerja lain yang<br />
lebih dibutuhkan oleh masyarakat.<br />
Menghimbau masyarakat untuk<br />
berperilaku yang baik tidak akan<br />
cukup berguna ketika di sisi lain<br />
masyarakat masih kesulitan<br />
memenuhi kebutuhan ekonomi,<br />
sulit mendapatkan pelayanan<br />
pendidikan dan kesehatan yang<br />
baik, atau anak-anak mereka<br />
kurus kering kekurangan gizi<br />
akibat kemiskinan. Temuan di<br />
Rumah Sakit Umum Cianjur Juni<br />
2009 yang menyebutkan bahwa<br />
terdapat 32 penderita gizi buruk<br />
seharusnya tidak perlu ada jika<br />
perhatian Pemerintah Daerah<br />
dimaksimalkan dalam pemenuhan<br />
kesejahteraan masyarakat. Bukankah<br />
memperhatikan kesejahteraan<br />
masyarakat itu lebih bijak ketimbang<br />
memperbesar anggaran pembuatan<br />
portal, pagar, tugu atau gerbang<br />
hanya sekedar untuk memanc<br />
a n g k a n t u l i s a n G e r b a n g<br />
Marhamah?<br />
Kepustakaan<br />
Peraturan Daerah No 03 tahun<br />
2 0 0 6 t e n t a n g G e r a k a n<br />
P e m b a n g u n a n M a s y a r a k a t<br />
Berakhlaqul Karimah<br />
Undang-Undang No 10 tahun 2004<br />
tentang Pembentukan Peraturan<br />
Perundang-Undangan<br />
LPPI. 2002. Gerbang Marhamah.<br />
Rencana Strategis Mewujudkan<br />
Masyarakat Cianjur Sugih Mukti<br />
Tur Islami. Cianjur: LPPI<br />
Priyono, AE. 2007. “Projek<br />
Syariahisasi Daerah antara<br />
Imaginasi Moral dan Fantasi<br />
Politik” dalam REFORM. Vol. I No<br />
1, April-Juni.<br />
Http://infokorupsi.com/id/korupsi.p<br />
hp<br />
H t t p : / / n e w s p a p e r . p i k i r a n -<br />
rakyat.com/prprint.php<br />
http://www.tempointeraktif.com/hg/<br />
nusa/2009/07/17<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
19
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
internasional<br />
Komisi HAM ASEAN, Akhirnya Datang juga!<br />
Oleh Haris Azhar<br />
(Wakil Koordinator KontraS/Convenor of SAPA Task Force on Human Rights)<br />
etelah 42 tahun berdiri<br />
akhirnya ASEAN memiliki<br />
sebuah institusi HAM.<br />
Institusi ini bernama SASEAN Intergovernmental<br />
Commission on Human Rights<br />
(AICHR)/Komisi HAM ASEAN.<br />
Komisi ini diresmikan pada 23<br />
Oktober 2009 di Cha Am Thailand<br />
lewat ASEAN Summit. Dalam<br />
Deklarasi Politik saat ia diresmikan,<br />
disebutkan bahwa AICHR<br />
menjadi penting dalam proses<br />
membangun komunitas ASEAN,<br />
sebagai sebuah kendaraan yang<br />
progresif dalam pembangunan<br />
sosial dan keadilan, pemenuhan<br />
kehormatan manusia, dan<br />
pencapaian kualitas hidup yang<br />
lebih tinggi dari masyarakat<br />
ASEAN.<br />
1.Asal Mula Komisi HAM<br />
ASEAN<br />
Ide untuk memiliki komisi HAM di<br />
ASEAN mulai diusung sejak tahun<br />
1993. Hal ini adalah tindak lanjut<br />
dari proses diskusi HAM di<br />
tingkatan global. Pada 1993<br />
Perserikatan Bangsa-Bangsa<br />
(PBB) memulai proses dialog<br />
secara global tentang masa<br />
depan HAM. Pembahasan ini<br />
memuncak di Wina, Austria lewat<br />
sebuah konferensi dan menghasilkan<br />
Deklarasi Wina berikut<br />
Program Aksi 1993. Sebelumnya<br />
di Asia, sebagai persiapan menuju<br />
Wina, dihasilkan Deklarasi<br />
Bangkok (1993). Dalam Deklarasi<br />
Bangkok (angka 26), dikatakan<br />
bahwa penting untuk ditekankan<br />
kebutuhan mengeksplorasi<br />
kemungkinan-kemungkinan<br />
membuat pengaturan regional<br />
guna promosi dan perlindungan<br />
HAM di Asia. Serupa dalam<br />
Deklarasi Wina bagian I angka 37,<br />
dikatakan bahwa “penting untuk<br />
mempertimbangkan mendirikan<br />
pengaturan regional dan sub<br />
regional untuk promosi dan<br />
perlindungan HAM diwilayah yang<br />
belum memilikinya”.<br />
Paska Konferensi Wina 1993, ada<br />
banyak respon dan usaha untuk<br />
mendorong berdirinya Komisi<br />
HAM di ASEAN. Pada pertemuan<br />
Menteri Luar Negeri ASEAN ke 26<br />
(juni 1993), dibuat Komunike<br />
Bersama (Joint Communique)<br />
yang menyatakan “menyambut<br />
baik konsensus international yang<br />
dicapai selama konferensi Wina<br />
mengenai HAM”. Dalam komunike<br />
ini juga dinyatakan bahwa ASEAN<br />
berkomitmen dan menghormati<br />
HAM dan kebebasan yang<br />
fundamental. Oleh karenanya<br />
ASEAN mempertimbangkan<br />
pendirian sebuah mekanisme<br />
HAM ditingkat regional.<br />
Kantor Komisi Tinggi<br />
HAM PBB (Office of High<br />
Commissioner on Human Rights)<br />
juga berperan dalam mendorong<br />
berdirinya mekanisme HAM di<br />
Asia. Hal ini terlihat dalam hasil<br />
lokakarya tahunan dalam Bidang<br />
Kerjasama untuk Promosi dan<br />
Perlindungan HAM se-Asia<br />
Pasific ke 14 di Bali (Juli 2007).<br />
Pada ASEAN Summit ke-11,<br />
Desember 2005, di Kuala Lumpur<br />
dinyatakan penting bagi ASEAN<br />
untuk memiliki Piagam ASEAN<br />
yang didalamnya mengafirmasi<br />
pentingnya 'promosi demokrasi,<br />
hak dan kewajiban asasi'.<br />
Konkritnya, dalam piagam<br />
ASEAN (2005) di pasal 14<br />
dikatakan bahwa ASEAN harus<br />
mendirikan Badan HAM ASEAN<br />
dan badan ini akan beroperasi<br />
yang akan diatur melalui kerangka<br />
acuan yang selanjutnya akan<br />
ditentukan melalui pertemuan<br />
menteri luar negeri ASEAN.<br />
Pada pertemuan Menteri<br />
Luar Negeri ASEAN ke-41 (2008)<br />
di Singapura dibentuk Panitia<br />
Tingkat Tinggi (High Level Panel)<br />
yang bertugas merumuskan<br />
Kerangka Acuan Komisi/Badan<br />
HAM ASEAN. Panitia ini terdiri<br />
dari 10 orang yang mewakili 10<br />
negara anggota ASEAN. Panitia<br />
ini juga bertugas melakukan<br />
konsultasi dengan masyarakat<br />
sipil guna mencari masukan rumusan<br />
kerangka acuan. Sayangnya<br />
konsultasi dengan masyarakat<br />
sipil dilakukan tanpa perinsip<br />
keseimbangan. Masyarakat sipil<br />
diminta memberikan masukan<br />
namun, panitia ini tidak pernah<br />
memberikan secara terbuka<br />
rancangan kerangka acuan<br />
kepada masyarakat. Walhasil,<br />
pada pertemuan Menteri luar<br />
negeri ASEAN ke-42 (2009) di<br />
Phuket Thailand, kerangka acuan<br />
tersebut diterima dan disahkan.<br />
Pada ASEAN Summit ke-15 pada<br />
Oktober 2009 di Cha Am,<br />
Thailand, Komisi HAM ASEAN<br />
dideklarasikan dan 10 orang<br />
komisioner (masing-masing 1 dari<br />
s e t i a p N e g a r a A S E A N )<br />
ditetapkan.<br />
2.Komisi HAM ASEAN<br />
Sebagaimana dalam kerangka<br />
acuan, tujuan dari komisi ini<br />
adalah untuk mempromosi dan<br />
melindungi hak asasi dan<br />
kebebasan fundamental dan<br />
mengangkat derajat hak setiap<br />
orang didalam ASEAN untuk<br />
hidup dalam damai, kehormatan<br />
dan kesejahteraan. Selain itu,<br />
Komisi ini bertujuan untuk<br />
berkontribusi dalam penciptaan<br />
stabilitas dan harmoni di wilayah<br />
ASEAN, menciptakan persahabatan<br />
dan kerjasama diantara Negara<br />
anggota ASEAN, termasuk setiap<br />
20<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
insan, dalam proses membangun<br />
komunitas ASEAN. Namun<br />
demikian Komisi ini diharapkan<br />
tetap mempromosikan konteks<br />
dan kekhususan regional dan<br />
nasional dalam penghormatan<br />
HAM serta menyeimbangkan<br />
antara hak dan kewajiban setiap<br />
orang. Tujuan lainnya adalah<br />
Komisi bisa menggunakan<br />
standar HAM internasional seperti<br />
Deklarasi Umum HAM 1948 dan<br />
Deklarasi Wina 1993.<br />
Pada artikel 4 dari<br />
kerangka acuan terdapat 14<br />
fungsi dan mandat dari Komisi ini.<br />
Kesemuanya dapat dikategorikan<br />
dalam, pertama, fungsi strategis,<br />
berupa membangun strategi<br />
promosi dan perlindungan HAM,<br />
merancang Deklarasi HAM<br />
ASEAN; mendapatkan informasi<br />
dari negara-negara ASEAN dalam<br />
kerja promosi dan perlindungan<br />
HAM dinegara masing-masing;<br />
melakukan studi atas tema-tema<br />
tertentu; membuat laporan<br />
tahunan ke menteri luar negeri<br />
negara-negara ASEAN dan<br />
melakukan tugas tertentu yang<br />
terkait dengan HAM atas<br />
permintaan rapat menteri luar<br />
negeri negara-negara ASEAN.<br />
Kedua, fungsi penguatan<br />
kapasitas (edukatif) berupa<br />
meningkatkan kepedulian masyarakat<br />
ASEAN atas HAM; mendorong<br />
Negara-negara ASEAN<br />
meratifikasi hukum HAM internasional<br />
dan meningkatkan kemampuan<br />
Negara-negara ASEAN<br />
dalam implementasi hukum HAM<br />
internasional; termasuk memberikan<br />
layanan saran dan bantuan<br />
teknis dalam persoalan HAM<br />
sesuai dengan permintaan;<br />
melakukan dialog dan konsultasi<br />
dengan badan-badan lain di<br />
ASEAN termasuk masyarakat<br />
sipil; dan melakukan konsultasi<br />
dengan institusi-institusi internasional<br />
yang peduli dengan promosi<br />
dan perlindungan HAM.<br />
Fungsi-fungsi diatas<br />
memperlihatkan bahwa Komisi ini<br />
merupakan komisi yang bekerja<br />
pada tingkatan promosional saja.<br />
Bahkan secara terbuka dalam<br />
kerangka acuan dinyatakan<br />
bahwa Komisi ini bersifat<br />
konsultatif. Komisi tidak memiliki<br />
fungsi untuk mengintervensi<br />
suatu situasi seperti terjadinya<br />
pelanggaran berat HAM. Dengan<br />
kata lain, komisi ini tidak memiliki<br />
fungsi atau mandat untuk<br />
melakukan investigasi atas<br />
dugaan sebuah pelanggaran<br />
HAM. Lalu apa yang bisa<br />
dilakukan oleh Komisi ini atas<br />
situasi HAM di negara-negara<br />
ASEAN yang masih banyak<br />
mempraktekkan pelanggaran<br />
HAM dinegaranya?<br />
3.Komisi HAM ASEAN: Sudah<br />
datang, lalu mau apa?<br />
Secara umum masih pelanggaranpelanggaran<br />
HAM di ASEAN<br />
masih terus terjadi, baik berupa<br />
Impunitas (ketiadaan penghukuman<br />
atas kejahatan), pelanggaran<br />
HAM atas dasar keamanan,<br />
serta situasi hak ekonomi dan<br />
sosial yang memburuk. Dalam<br />
soal impunitas, di Kamboja<br />
perdana menteri Hun Sen<br />
semakin tidak mendukung usaha<br />
untuk mengadili Khmer rouge atas<br />
genosida (pembasmian manusia)<br />
yang terjadi pada era 70-an.<br />
Bandingkan pula dengan situasi<br />
yang memburuk di Burma dimana<br />
ribuan orang dihilangkan, diperkosa,<br />
diperbudak dan ditahan<br />
secara semena-mena. Di Malaysia<br />
dan Singapura, Undang-undang<br />
Keamanan Internal (Internal<br />
Security Act) masih secara<br />
ekstensif digunakan untuk<br />
memberangus kelompok pro<br />
demokrasi atau oposisi. Dalam<br />
konteks hak ekonomi dan sosial,<br />
masih banyak terjadi ketiadaan<br />
jaminan pemenuhan keamanan<br />
kerja dan non eksploitatif.<br />
Pelanggaran-pelanggaran<br />
diatas masih terjadi karena<br />
karakter negara-negara ASEAN<br />
yang masih melihat HAM secara<br />
setengah-tengah, misalnya<br />
mengedapankan kemajuan<br />
ekonomi dari pada pemenuhan<br />
hak sipil dan politik. Atau<br />
mengedepankan hak-hak komunitas<br />
dari pada hak individual. Selain<br />
cara pandang tersebut, dalam<br />
ASEAN terdapat prinsip-prinsip<br />
organisasi yang membatasi<br />
kemampuan kontrol ASEAN<br />
terhadap anggotanya dan antar<br />
Negara dalam soal HAM. Prinsipprinsip<br />
tersebut berupa nonintervensi<br />
antar Negara anggota<br />
ASEAN, pengutaman kedaulatan,<br />
dan pencapaian keputusan<br />
berdasarkan konsensus (musyawarah<br />
dan mufakat). Ironisnya, prinsipprinsip<br />
ini juga menjadi salah satu<br />
prinsip kerja Komisi HAM ASEAN<br />
(pasal 2).<br />
Secara politik, wajar jika<br />
Komisi HAM ASEAN hanya<br />
diberikan mandat mempromosikan<br />
HAM (tidak proteksi). Konsekuensinya,<br />
Komisi ini tidak<br />
diberikan wewenang mengkritik<br />
kondisi dan situasi HAM atas<br />
suatu Negara. Oleh karenanya,<br />
sementara ini komisi ini harus<br />
digunakan untuk mengoptimalkan<br />
peran promosinya, seperti<br />
mendorong Negara-negara<br />
ASEAN untuk meratifikasi hukum<br />
dan standar HAM internasional,<br />
seperti statuta Roma (tentang<br />
Pengadilan Kriminal Internasional)<br />
atau konvensi perlindungan buruh<br />
migran. Selain itu Komisi ini juga<br />
memiliki kesempatan untuk<br />
menginternalisasikan HAM ke<br />
dalam ASEAN. Oleh karena<br />
penting bagi entitas masyarakat<br />
sipil dan masyarakat internasional<br />
lainnya, seperti Kantor Komisi<br />
Ti n g g i H A M P B B , u n t u k<br />
memberikan masukan dalam<br />
mendorong perbaikan insitusional<br />
Komisi ini. Hal ini dapat dilakukan<br />
mengingat masih terdapat celah<br />
di dalam perumusan Deklarasi<br />
HAM ASEAN, dan adanya<br />
kemungkinan kerangka acuan<br />
untuk dievaluasi dalam 5 tahun<br />
kedepan. Tak kalah pentingnya<br />
untuk melihat bahwa Komisi<br />
merupakan ini merupakan komisi<br />
regional yang melengkapi mekanisme<br />
nasional.<br />
Komisi yang masih bayi ini<br />
adalah harapan ditengah gurun<br />
HAM ASEAN yang terus diterpa<br />
badai pelanggaran dan kesewenangwenangan.<br />
Sehingga penting bagi<br />
setiap kita di ASEAN untuk terus<br />
memberikan susu advokatif guna<br />
memiliki komisi HAM ASEAN yang<br />
dewasa yang efektif dalam<br />
memajukan HAM di ASEAN kelak.<br />
***<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong><br />
21
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA<br />
resensi<br />
Bebas dari Penyiksaan:<br />
Perjalanan Masih Panjang<br />
Oleh Betty Yolanda, SH, LL.M<br />
(Koordinator Unit Studi ELSAM)<br />
Judul Buku<br />
Penulis<br />
: Hak <strong>Asasi</strong> Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan<br />
: Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan<br />
(WGAT) Berkonsultasi dengan the Association for the<br />
Prevention of Torture (APT) dan the World Organisation<br />
Torture (OMCT)<br />
: Emilianus Afandi<br />
: ELSAM dan OMCT<br />
against<br />
Editor<br />
Penerbit<br />
Tahun : November 2009<br />
Data Fisik : 172 halaman<br />
onvensi Menentang<br />
Penyiksaan, yang diratifikasi<br />
oleh Pemerintah<br />
KIndonesia pada tahun<br />
1998, menetapkan bahwa setiap<br />
Negara Pihak pada Konvensi<br />
harus menyerahkan laporan<br />
tentang langkah-langkah yang<br />
telah mereka ambil dalam rangka<br />
pelaksanaan Konvensi ke Komite<br />
Menentang Penyiksaan (Pasal<br />
1 9 ( 1 ) ) . B u l a n M e i 2 0 0 8<br />
merupakan kali kedua laporan<br />
Pemerintah Indonesia sehubungan<br />
dengan pelaksanaan Konvensi<br />
dibahas di Komite. Secara umum,<br />
Pemerintah Indonesia menegaskan<br />
bahwa langkah-langkah<br />
konstitusional, legislatif dan<br />
langkah-langkah lain yang<br />
mereka ambil telah sesuai<br />
dengan apa yang ditetapkan<br />
dalam Konvensi.<br />
Buku “Hak <strong>Asasi</strong> Manusia<br />
di Bawah Penyiksaan” adalah<br />
sebuah buku yang berisikan<br />
ringkasan laporan bayangan yang<br />
disusun oleh Kelompok Kerja<br />
untuk Advokasi Menentang<br />
Penyiksaan (WGAT), sebuah<br />
kelompok kerja yang terdiri dari 33<br />
lembaga swadaya masyarakat<br />
(LSM) di tingkat nasional dan<br />
lokal, yang melakukan advokasi<br />
u n t u k m e n g h a p u s p r a k t i k<br />
penyiksaan di Indonesia.<br />
Berangkat dari kasuskasus<br />
yang diadvokasi oleh para<br />
anggota WGAT, observasiobservasi<br />
lapangan, serta<br />
didukung oleh data-data sekunder<br />
yang diperoleh dari media cetak<br />
dan elektronik, 12 (dua belas) bab<br />
dalam buku ini akan membawa<br />
kita pada diskusi mendalam<br />
m e n g e n a i s e j a u h m a n a<br />
Pemerintah Indonesia telah<br />
m a m p u u n t u k m e m e n u h i<br />
kewajibannya berdasarkan<br />
Konvensi. Juga dilampirkan 2<br />
(dua) dokumen yang dikeluarkan<br />
o l e h K o m i t e M e n e n t a n g<br />
P e n y i k s a a n , y a k n i D a f t a r<br />
Inventaris Permasalahan dan<br />
Kesimpulan Observasi.<br />
22<br />
EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN <strong>2010</strong>
Diawali dengan pemaparan<br />
tentang proses penyusunan dan<br />
struktur laporan bayangan, buku<br />
ini selanjutnya mengingatkan<br />
kembali ingatan kita pada<br />
rekomendasi-rekomendasi yang<br />
dikeluarkan oleh Komite pada<br />
tahun 2001. Dari 17 (tujuh belas)<br />
butir rekomendasi, WGAT<br />
mencatat bahwa Pemerintah<br />
Indonesia belum mampu untuk<br />
mengambil langkah-langkah<br />
yang signifikan, khususnya yang<br />
berkenaan dengan pengembangan<br />
kerangka hukum yang<br />
kuat bagi pencegahan penyiksaan,<br />
reformasi kelembagaan,<br />
dan peningkatan mekanisme<br />
akuntabilitas.<br />
B u k u i n i k e m b a l i<br />
mempertanyakan keseriusan<br />
Pemerintah untuk mengintegrasikan<br />
ketentuan-ketentuan<br />
yang termuat dalam Konvensi ke<br />
dalam hukum domestik. Ironis<br />
memang, sampai saat ini<br />
kejahatan penyiksaan belum juga<br />
diatur dalam Kitab Undang-<br />
Undang Hukum Pidana (KUHP)<br />
yang merupakan payung hukum<br />
dari peraturan perundangundangan<br />
di Indonesia.<br />
Meski RUU KUHP sudah<br />
memuat definisi 'penyiksaan'<br />
yang sesuai dengan definisi<br />
Konvensi, lambannya proses<br />
pengesahan RUU tersebut<br />
menunjukkan ketidakseriusan<br />
Pemerintah untuk mengkriminalisasi<br />
penyiksaan. Kendati UU<br />
No. 39/1999 tentang Hak <strong>Asasi</strong><br />
Manusia, Pasal 1 ayat (4),<br />
memuat definisi penyiksaan<br />
sebagaimana ditetapkan oleh<br />
Konvensi, ruang lingkup undangundang<br />
tersebut terbatas pada<br />
penyiksaan yang dikategorikan<br />
sebagai pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang berat, yakni<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan<br />
dan genosida.<br />
Perlu kita ingat bahwa<br />
Konvensi Menentang Penyiksaan<br />
tidak hanya membatasi dirinya<br />
pada penyiksaan, tetapi juga<br />
pada tindakan-tindakan lain yang<br />
kejam, tidak manusiawi, atau<br />
merendahkan martabat manusia.<br />
Bertitik tolak dari sinilah maka isu<br />
perempuan dan anak-anak pada<br />
akhirnya diintegrasikan dalam<br />
laporan bayangan, terutama<br />
mengingat kerentanan yang<br />
mereka miliki. Pembahasan<br />
mengenai isu ini tersebar di<br />
beberapa bab, yakni Bab 4 (hak<br />
untuk mengadu dan mendapatkan<br />
perlindungan), Bab 5 (kompensasi<br />
dan rehabilitasi), Bab 6 (tahanan<br />
perempuan dan narapidana<br />
anak), dan Bab 11 (bentuk-bentuk<br />
kekerasan yang dialami oleh<br />
perempuan dan anak-anak).<br />
Maraknya pemberitaan<br />
tentang jual-beli kamar di penjara<br />
akhir-akhir ini sebenarnya bukan<br />
merupakan hal yang baru. Buku<br />
ini mengungkapkan bahwa<br />
praktik jual-beli kamar tahanan<br />
hanya merupakan satu dari<br />
berbagai permasalahan pelik<br />
yang terjadi di dalam penjara,<br />
seperti misal penyajian makanan<br />
yang tidak memenuhi standar gizi,<br />
ketiadaan fasilitas sanitasi yang<br />
memadai dan masalah kelebihan<br />
kapasitas.<br />
Buruknya kondisi tempat<br />
penahanan dan perlakuan<br />
terhadap para tahanan merupakan<br />
bentuk tindakan-tindakan<br />
yang tidak manusiawi dan<br />
merendahkan martabat manusia.<br />
Oleh karenanya perlu untuk<br />
meningkatkan peran lembagalembaga<br />
negara yang memiliki<br />
fungsi pengawasan terhadap<br />
tempat-tempat penahanan,<br />
misalnya Komnas HAM, dan untuk<br />
segera meratifikasi Protokol<br />
Tambahan pada Konvensi<br />
Menentang Penyiksaan (OPCAT).<br />
Informasi khusus tentang<br />
praktik-praktik penyiksaan di<br />
wilayah-wilayah konflik seperti di<br />
Poso dan Papua Barat juga tersaji<br />
dalam buku ini. Berdasarkan datadata<br />
yang telah diverifikasi,<br />
terungkap bahwa ketatnya<br />
penerapan kebijakan keamanan<br />
dan kuatnya kehadiran militer di<br />
dua wilayah tersebut berkontribusi<br />
besar pada banyaknya kasus<br />
penyiksaan yang terjadi.<br />
Bab terakhir dari buku ini<br />
mengedepankan kesimpulan dan<br />
r e k o m e n d a s i W G AT y a n g<br />
berhubungan dengan permasalahan-permasalahan<br />
mengenai<br />
perlindungan dan pencegahan<br />
terhadap penyiksaan, kondisi<br />
penahanan, kompensasi dan<br />
rehabilitasi, dan perempuan dan<br />
anak-anak.
PROFIL ELSAM<br />
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy),<br />
disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri<br />
sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha<br />
menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak<br />
asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan<br />
Deklarasi Universal Hak <strong>Asasi</strong> Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.<br />
ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang<br />
berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai<br />
bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan<br />
penyebaran informasi hak asasi manusia.<br />
Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM<br />
Badan Pengurus:<br />
Ketua: Asmara Nababan, SH; Wakil Ketua: Drs. Hadimulyo, MSc.; Sekretaris 1: Ifdhal Kasim,<br />
SH; Sekretaris 2: Francisca Saveria Sika Ery Seda, PhD; Bendahara: Ir. Yosep Adi Prasetyo;<br />
Anggota: Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA;<br />
Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala<br />
Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Sandra Yati Moniaga, SH;<br />
Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM; Raharja Waluya Jati; Abdul Haris Semendawai SH, LLM;<br />
Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Roichatul Aswidah MSc; Herlambang Perdana<br />
SH, MA<br />
Badan Pelaksana:<br />
Direktur Eksekutif: Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA;<br />
Deputi Program: Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH, LL.M;<br />
Deputi Internal: Otto Adi Yulianto, SE;<br />
Staf: Adyani Hapsari W; Ahmad Muzani; Drs. Amiruddin, MSi; Atnike Nova Sigiro, S.Sos, M.Sc ;<br />
Betty Yolanda, SH, LL.M; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini<br />
Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo,<br />
Siti Sumarni, SE MSi; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Wahyu Wagiman SH;<br />
Yuniarti, SS<br />
Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919<br />
2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: office@elsam.or.id,<br />
Website: www.elsam.or.id