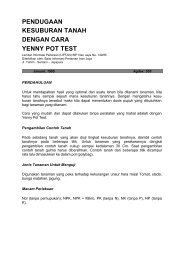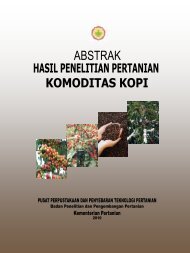Download Fulltext Document - Pustaka
Download Fulltext Document - Pustaka
Download Fulltext Document - Pustaka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Perakitan Pengembangan kelapa Inovasi unggul Pertanian melalui teknik 1(4), molekuler 2008: 259-273 ... 259<br />
PERAKITAN KELAPA UNGGUL MELALUI TEKNIK<br />
MOLEKULER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP<br />
PEREMAJAAN KELAPA DI INDONESIA 1)<br />
Hengky Novarianto<br />
Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain<br />
Jalan Bethesda II, Mapanget, Kotak Pos 1004, Manado 95001<br />
PENDAHULUAN<br />
Bagi masyarakat Indonesia, kelapa merupakan<br />
bagian dari kehidupan karena semua<br />
bagian tanaman dapat dimanfaatkan<br />
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,<br />
sosial, dan budaya. Arti penting kelapa<br />
bagi masyarakat juga tercermin dari luas<br />
areal perkebunan kelapa rakyat yang<br />
mencapai 98% dari total areal kelapa nasional<br />
sekitar 3,86 juta ha, dengan produksi<br />
3,04 juta ton ekuivalen kopra pada tahun<br />
2007 (Direktorat Jenderal Perkebunan<br />
2007), dan melibatkan lebih dari 7 juta<br />
keluarga petani. Pengusahaan kelapa juga<br />
membuka tambahan kesempatan kerja dari<br />
kegiatan pengolahan produk turunan dan<br />
hasil samping yang sangat beragam.<br />
Salah satu permasalahan kelapa pada<br />
tingkat petani adalah rendahnya produktivitas,<br />
yaitu hanya rata-rata 1 ton kopra/<br />
ha/tahun, padahal potensi produksinya<br />
dapat mencapai 3-5 ton kopra/ha/tahun<br />
(Novarianto et al. 2004). Rendahnya produktivitas<br />
disebabkan petani belum menggunakan<br />
benih kelapa unggul. Petani pernah<br />
melakukan peremajaan dengan kelapa<br />
hibrida, tetapi kurang berhasil.<br />
1) Naskah disarikan dari bahan Seminar Praorasi<br />
Profesor Riset yang disampaikan pada tanggal<br />
12 Juni 2008 di Bogor.<br />
Belajar dari pengalaman petani dengan<br />
kelapa hibrida maka penyediaan benih<br />
unggul kelapa bagi petani hendaknya<br />
diseleksi dari jenis kelapa Dalam. Kebutuhan<br />
benih kelapa untuk program peremajaan<br />
mencapai 15% dari total luas kelapa,<br />
yakni sekitar 583.500 ha. Pada saat ini,<br />
kebun induk kelapa Dalam unggul belum<br />
tersedia secara cukup. Penyediaan benih<br />
kelapa Dalam unggul harus disiapkan sejak<br />
awal, mengingat umur produktif tanaman<br />
kelapa cukup panjang. Dalam rangka<br />
menunjang program peremajaan kelapa,<br />
diperlukan strategi penyediaan benih kelapa<br />
Dalam unggul untuk jangka pendek<br />
dan jangka panjang<br />
Program penyediaan benih jangka<br />
pendek dapat dilakukan melalui pemanfaatan<br />
kelapa Dalam unggul lokal, sedangkan<br />
program pembangunan kebun induk<br />
kelapa untuk jangka panjang dilaksanakan<br />
dengan membangun Kebun Induk Kelapa<br />
Dalam Komposit (KIKD Komposit). Untuk<br />
mempercepat seleksi varietas kelapa unggul<br />
di setiap daerah dan sebagai tetua dalam<br />
perakitan kelapa Dalam komposit, dapat<br />
dilakukan dengan memanfaatkan teknik<br />
molekuler. Sudah saatnya setiap daerah<br />
(provinsi/kabupaten) mempunyai pusatpusat<br />
sumber benih kelapa unggul, yang<br />
selain sebagai sumber benih kelapa lokal,<br />
juga secara tidak langsung akan melesta-
260 Hengky Novarianto<br />
rikan keragaman genetik kelapa secara in<br />
situ atau on-farm conservation. Makalah<br />
ini mengulas perakitan kelapa unggul melalui<br />
teknik molekuler serta implikasinya<br />
terhadap prgoram peremajaan kelapa di<br />
Indonesia.<br />
PERKEMBANGAN PEMULIAAN<br />
KELAPA DI INDONESIA<br />
Produktivitas kelapa menurun pada awal<br />
tahun 1970, padahal permintaan minyak<br />
goreng meningkat. Untuk mengatasi masalah<br />
tersebut, pemerintah melaksanakan<br />
berbagai program untuk meningkatkan<br />
produksi kopra, antara lain peremajaan<br />
kelapa tua dan perluasan areal dengan<br />
kelapa hibrida. Untuk memenuhi kebutuhan<br />
benih kelapa hibrida dalam jumlah<br />
banyak dan cepat, pemerintah mengintroduksi<br />
kelapa hibrida PB121 dari Pantai<br />
Gading serta membangun kebun induk<br />
kelapa hibrida di 11 provinsi dengan luas<br />
1.856 ha (Novarianto et al. 1998). Kelapa<br />
hibrida yang dihasilkan adalah silangan<br />
kelapa Genjah Kuning Nias x Dalam Afrika<br />
Barat atau disebut MAWA. Di samping<br />
mendatangkan kelapa hibrida dari luar<br />
negeri, pemerintah melalui Badan Litbang<br />
Pertanian juga merakit kelapa hibrida lokal.<br />
Pemuliaan tanaman merupakan suatu<br />
metode pemanfaatan keragaman genetik<br />
plasma nutfah secara sistematis untuk<br />
menghasilkan varietas baru yang lebih baik<br />
dari sebelumnya. Dalam upaya menghasilkan<br />
kelapa unggul untuk mempercepat<br />
peremajaan kelapa maka tujuan<br />
program pemuliaan pada masa lalu (1970-<br />
1990) adalah menghasilkan bahan tanaman<br />
dalam skala luas dan memiliki karakteristik<br />
hasil kopra tinggi dan cepat berbuah<br />
(Liyanage 1974). Metode pemuliaan yang<br />
dipilih adalah seleksi dan hibridisasi untuk<br />
merakit berbagai jenis kelapa hibrida,<br />
terutama kelapa hibrida silangan antara<br />
kelapa Genjah x kelapa Dalam.<br />
Kelapa Hibrida<br />
Perakitan kelapa hibrida dilakukan untuk<br />
menghasilkan varietas kelapa yang cepat<br />
berbuah dan produktivitasnya tinggi. Pola<br />
persilangan kelapa hibrida dapat dipilih<br />
antara tipe Dalam x Dalam, Genjah x Genjah,<br />
Genjah x Dalam atau Dalam x Genjah.<br />
Tanaman kelapa digolongkan atas dua<br />
tipe, yaitu tipe Genjah dan tipe Dalam.<br />
Kelapa Genjah umumnya menyerbuk<br />
sendiri, sedangkan kelapa Dalam biasanya<br />
menyerbuk silang. Akibatnya, secara fenotipe<br />
kelapa Genjah lebih homogen dan<br />
genotipenya lebih homozigous dibanding<br />
kelapa Dalam yang lebih heterogen dan<br />
heterozigous. Kelapa Genjah mulai berbuah<br />
pada umur 3-4 tahun, sedangkan<br />
kelapa Dalam pada umur 6-7 tahun.<br />
Berdasarkan pola penyerbukan, umur<br />
pertama berbuah, potensi produksi buah,<br />
hasil kopra, serta kualitas kopra dan<br />
minyak, untuk menghasilkan kelapa hibrida<br />
yang cepat berbuah dan hasil kopra tinggi,<br />
dipilih pola persilangan kelapa Genjah x<br />
Dalam. Perakitan kelapa hibrida Genjah x<br />
Dalam dilakukan sejak tahun 1975. Berdasarkan<br />
hasil evaluasi dan seleksi bahan<br />
tanaman kelapa Genjah dan kelapa Dalam<br />
dari plasma nutfah kelapa, ditetapkan<br />
kelapa Genjah Kuning Nias asal Pulau<br />
Nias, Sumatera Utara sebagai tetua betina,<br />
sedangkan sebagai tetua jantan atau<br />
sumber polen dipilih tiga varietas kelapa<br />
Dalam, yaitu Dalam Tenga asal Sulawesi<br />
Utara, Dalam Bali asal Bali, dan Dalam Palu<br />
asal Sulawesi Tengah. Tiga varietas kelapa<br />
hibrida yang dihasilkan adalah KHINA 1<br />
(Genjah Kuning Nias x Dalam Tenga),
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 261<br />
KHINA 2 (Genjah Kuning Nias x Dalam<br />
Bali), dan KHINA 3 (Genjah Kuning Nias x<br />
Dalam Palu). Dengan pemeliharaan yang<br />
intensif, kelapa hibrida tersebut mampu<br />
berproduksi 4-5 ton kopra/ha/tahun (Novarianto<br />
et al. 1992a). Ketiga kelapa hibrida<br />
tersebut telah dilepas oleh Menteri<br />
Pertanian pada tahun 1984.<br />
KHINA-1 mulai berbuah pada umur 3-<br />
4 tahun, hasil kopra rata-rata 4 ton/ha/<br />
tahun dengan hasil tertinggi 5 ton/ha/<br />
tahun, dan kadar minyak kopra 64%.<br />
KHINA-2 mulai berbuah umur 3,5 tahun,<br />
kadar kopra cukup tinggi yaitu 296 g/butir,<br />
atau membutuhkan 3-4 butir kelapa untuk<br />
menghasilkan 1 kg kopra, hasil kopra 4 ton/<br />
ha/tahun dengan kadar minyak kopra 64%.<br />
KHINA-3 menghasilkan kopra rata-rata 4<br />
ton/ha/tahun, lebih tahan kekeringan<br />
dibanding KHINA-1 dan KHINA-2, serta<br />
kadar minyak kopra cukup tinggi yaitu 65%.<br />
Petani kelapa umumnya tidak melakukan<br />
pemupukan pada tanaman kelapa,<br />
sehingga saat membudidayakan kelapa<br />
hibrida, sebagian besar petani tidak dapat<br />
memenuhi syarat pemeliharaan yang baik,<br />
terutama pemupukan secara intensif.<br />
Akibatnya, tanaman tidak mampu berproduksi<br />
sesuai dengan potensinya serta<br />
buah berukuran kecil. Selain produksi<br />
rendah, kelapa hibrida introduksi PB121<br />
dan MAWA sangat peka terhadap penyakit<br />
busuk pucuk dan gugur buah yang<br />
disebabkan oleh Phythopthora palmivora<br />
(Bennett et al. 1985; Warokka dan Mangindaan<br />
1992), serta kurang tahan<br />
terhadap kekeringan (Tampake et al. 1982).<br />
Hal tersebut membuat petani menjadi<br />
kecewa. Kelapa hibrida KHINA-1, KHINA-<br />
2 dan KHINA-3 lebih baik dibanding PB121<br />
dan MAWA, tetapi sebagian besar petani<br />
terlanjur tidak menyukai meremajakan<br />
tanaman kelapa dengan kelapa hibrida.<br />
Hasil survei pengusahaan kelapa di<br />
Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 98%<br />
petani memilih kelapa Dalam untuk digunakan<br />
dalam perluasan areal, peremajaan,<br />
dan rehabilitasi (Akuba et al. 1992).<br />
Rethinam et al. (2002) melaporkan 94,44%<br />
petani kelapa di Indonesia lebih menyukai<br />
kelapa Dalam unggul lokal dan kelapa<br />
hibrida lokal dalam program pengembangan<br />
dibanding kelapa hibrida. Preferensi<br />
petani terhadap kelapa Dalam<br />
tercermin dari areal kelapa Dalam yang<br />
mencapai 93% dari total areal kelapa.<br />
Petani umumnya memilih kelapa Dalam<br />
dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (1)<br />
walaupun potensi produksi kelapa hibrida<br />
lebih tinggi dibanding kelapa Dalam,<br />
kelapa hibrida membutuhkan pemeliharaan<br />
intensif, terutama pemupukan dan pengendalian<br />
penyakit untuk mencapai hasil yang<br />
maksimal dan stabil; (2) kelapa Dalam<br />
berdasarkan pengalaman tidak memerlukan<br />
pemeliharaan intensif untuk mencapai<br />
tingkat produksi yang menguntungkan,<br />
serta lebih tahan terhadap cekaman lingkungan<br />
terutama kekeringan (Akuba 1998)<br />
dan serangan penyakit busuk pucuk<br />
(Hosang dan Lolong 1998), sehingga<br />
produksinya lebih stabil dan berkesinambungan<br />
dibanding kelapa hibrida; (3)<br />
benih kelapa Dalam lebih murah dibanding<br />
benih kelapa hibrida, karena petani dapat<br />
menggunakan buah hasil panen dari<br />
kebunnya sebagai benih atau membeli<br />
benih kelapa Dalam unggul yang relatif<br />
murah dari instansi terkait; dan (4) petani<br />
memiliki pengalaman traumatis dengan<br />
menanam kelapa hibrida PB-121 dan<br />
MAWA, yaitu Setelah kurang lebih 10<br />
tahun mengusahakan kelapa hibrida PB-<br />
121, 5-83% tanaman kelapa dalam suatu<br />
areal terserang penyakit busuk pucuk dan<br />
gugur buah (Akuba 1991).
262 Hengky Novarianto<br />
Kelapa Dalam<br />
Dengan mempertimbangkan keinginan petani<br />
kelapa, pemuliaan kelapa pada tahun<br />
1990-2000 ditujukan untuk menghasilkan<br />
varietas kelapa Dalam yang mampu menghasilkan<br />
kopra tinggi tanpa pemeliharaan<br />
yang intensif, terutama pemupukan. Artinya,<br />
tanpa pemupukan intensif, pertumbuhan<br />
dan hasil kelapa Dalam lebih baik<br />
dibanding kelapa hibrida (Tampake et al.<br />
1983).<br />
Peningkatan produktivitas kelapa Dalam<br />
dapat dilakukan melalui seleksi massa.<br />
Seleksi massa berdasarkan bobot buah<br />
tanpa sabut dapat meningkatkan hasil pada<br />
turunannya. Seleksi 5% pohon induk terbaik<br />
akan meningkatkan hasil 14,4%, selanjutnya<br />
seleksi 10% dan 15% memberikan<br />
kenaikan hasil berturut-turut 10,1%<br />
dan 7,9% (Liyanage 1972; Liyanage 1973).<br />
Jumlah buah dan hasil kopra kelapa Dalam<br />
Mapanget yang diseleksi dari induk dengan<br />
potensi hasil kopra 45-50 kg/pohon/<br />
tahun lebih baik daripada kelapa Dalam<br />
Tenga, Bali, dan Palu (Rompas et al. 1990).<br />
Evaluasi komponen buah pada 17 kultivar<br />
kelapa Dalam asal Sulawesi Utara memperoleh<br />
enam kelompok dengan keragaman<br />
genetik terbesar 52,27% (Miftahorrachman<br />
et al. 1996).<br />
Pada tahun 2000-2008, disiapkan proposal<br />
pelepasan 10 varietas kelapa Dalam<br />
unggul. Hasil penelitian menunjukkan,<br />
beberapa varietas kelapa Dalam memiliki<br />
potensi hasil tinggi dan dapat diusulkan<br />
untuk dilepas (Novarianto 2001; Novarianto<br />
dan Tenda 2002). Varietas kelapa<br />
Dalam yang direkomendasikan sebagai<br />
benih unggul adalah Dalam Mapanget,<br />
Dalam Tenga, Dalam Bali, Dalam Palu, dan<br />
Dalam Sawarna asal Jawa Barat. Hasil<br />
kopra kelima varietas tersebut selama 2-5<br />
tahun observasi di kebun Balai Penelitian<br />
Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Balitka)<br />
dan petani berkisar antara 2,2-3,5 ton<br />
kopra/ha/tahun, lebih tinggi daripada hasil<br />
kelapa Dalam rakyat yang hanya 1,0-1,5 ton<br />
kopra/ha/tahun (Tenda et al. 2004; Tenda<br />
et al. 2006). Kelapa Dalam Mapanget,<br />
Tenga, Bali, dan Palu telah dilepas sebagai<br />
varietas unggul pada tahun 2004, dan<br />
kelapa Dalam Sawarna dilepas pada tahun<br />
2006. Lima varietas lainnya akan dilepas<br />
pada tahun 2008. Varietas kelapa Dalam<br />
unggul tersebut telah dimanfaatkan untuk<br />
peremajaan kelapa rakyat.<br />
Untuk meningkatkan produktivitas<br />
kelapa unggul, kelima kelapa Dalam unggul<br />
tersebut telah dimanfaatkan dalam perakitan<br />
varietas kelapa Dalam komposit.<br />
Pengujian kelapa Dalam komposit sedang<br />
berlangsung di Sulawesi Utara, Gorontalo,<br />
dan Jawa Timur.<br />
PENGGUNAAN CIRI KARAKTER<br />
ISOZIM UNTUK SELEKSI KELAPA<br />
Pemuliaan kelapa sangat bergantung pada<br />
sumber keanekaragaman genetik. Keragaman<br />
genetik bukan hanya mengenai koleksi<br />
plasma nutfah secara fisik, tetapi juga<br />
penilaian sejauh mana keragaman genetik<br />
tersebut diperlukan dalam kegiatan manipulasi<br />
genetik ke arah perakitan varietas<br />
yang diinginkan dan jarak genetik dari sifatsifat<br />
yang digunakan dalam program<br />
persilangan (Makmur 1988). Plasma nutfah<br />
perlu dievaluasi keragaman genetiknya<br />
sebagai dasar seleksi dalam persilangan<br />
atau perakitan varietas yang diinginkan<br />
konsumen.<br />
Evaluasi plasma nutfah merupakan<br />
kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan<br />
informasi tentang potensi<br />
genetik individu populasi suatu kultivar/<br />
jenis/aksesi dengan menggunakan metode
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 263<br />
konvensional maupun nonkonvensional.<br />
Secara konvensional, evaluasi dilakukan<br />
dengan mempelajari dan mengamati karakter<br />
morfologi di lapangan. Evaluasi secara<br />
nonkonvensional dilakukan di laboratorium<br />
untuk karakter yang tidak dapat<br />
diamati di lapangan. Karakter morfologi<br />
menjadi prioritas utama dalam evaluasi<br />
plasma nutfah, karena secara fenotipe,<br />
perbedaan karakter baik kualitatif maupun<br />
kuantitatif dapat langsung terlihat. Namun,<br />
kadang-kadang karakter morfologi saja<br />
tidak cukup sehingga harus didukung<br />
dengan data molekuler.<br />
Plasma nutfah kelapa merupakan<br />
sumber sifat keturunan untuk merakit dan<br />
mengembangkan varietas kelapa unggul.<br />
Di Indonesia, koleksi plasma nutfah kelapa<br />
pertama kali dilakukan oleh ahli pemuliaan<br />
dari Belanda, yaitu Dr. Tammes, dengan<br />
mengevaluasi dan mengoleksi kelapa Dalam<br />
Mapanget asal Kecamatan Mapanget,<br />
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara<br />
pada tahun 1927. Selanjutnya pada tahun<br />
1973 dilakukan survei plasma nutfah kelapa<br />
di 11 provinsi penghasil kelapa utama.<br />
Hingga tahun 2007, Balitka telah berhasil<br />
mengoleksi 115 aksesi kelapa dari berbagai<br />
daerah di Indonesia dan sebagian kecil<br />
hasil introduksi. Koleksi kelapa ditanam di<br />
Kebun Mapanget, Paniki, Kima Atas dan<br />
Pandu (Sulawesi Utara), serta Pakuwon<br />
(Jawa Barat).<br />
Plasma nutfah kelapa dapat dimanfaatkan<br />
secara maksimal apabila potensi<br />
genetik setiap individu atau populasi<br />
diketahui. Evaluasi plasma nutfah kelapa,<br />
selain berdasarkan sifat morfologi, agronomi,<br />
dan fisiko-kimia, untuk mempercepat<br />
perakitan kelapa unggul juga perlu<br />
dilakukan secara molekuler, seperti ciri<br />
karakter isozim.<br />
Produk langsung gen berupa protein<br />
dan enzim dapat dilacak dan dipelajari<br />
keragamannya dengan menggunakan gel<br />
dan elektroforesis. Isozim adalah enzimenzim<br />
yang terdiri atas berbagai molekul<br />
aktif yang berbeda komposisi asam aminonya<br />
dan mengkatalisis reaksi yang sama.<br />
Keragaman isozim dapat dilacak dengan<br />
menggunakan elektroforesis pada gel yang<br />
dihasilkan berupa pola pita setelah diberi<br />
warna.<br />
Isozim dapat digunakan sebagai penciri<br />
genetik untuk mempelajari keragaman<br />
individu dalam suatu populasi, mengidentifikasi<br />
kultivar dan hibridanya (Peirce dan<br />
Brewbaker 1973; Kut dan Evans 1984;<br />
Vences et al. 1987), menentukan keberhasilan<br />
persilangan buatan (Parfitt dan<br />
Arulsekar 1985; Mc Granahan et al. 1986),<br />
membantu menyeleksi sifat-sifat yang<br />
bernilai ekonomi penting (Adams 1983;<br />
Hayward dan Mc Adam 1988; Yupsanis<br />
dan Moustakas 1988), dan mempelajari<br />
penyebaran keragaman genetik suatu<br />
tanaman dari lingkungan yang berbeda<br />
(Second 1982; Nevo et al. 1987). Ciri<br />
genetik pola pita isozim sangat bermanfaat<br />
dalam seleksi tanaman kelapa, karena seleksi<br />
dapat dilakukan lebih cepat, mudah,<br />
dan murah. Untuk jangka panjang, penggunaan<br />
isozim dalam seleksi kelapa lebih<br />
dapat dipercaya, karena tidak atau sedikit<br />
sekali dipengaruhi lingkungan dibandingkan<br />
dengan seleksi berdasarkan morfologi.<br />
Elektroforesis enzim dengan gel sering<br />
menghadapi masalah teknis yang berkaitan<br />
dengan ekstraksi enzim aktif dari jaringan<br />
tanaman. Hal ini berkaitan dengan adanya<br />
kandungan senyawa fenol dalam jaringan<br />
tanaman tahunan, termasuk kelapa. Namun,<br />
ternyata berbagai organ tanaman<br />
kelapa dapat digunakan sebagai materi<br />
dalam analisis isozim melalui elektroforesis<br />
enzim pada gel pati. Daun kelapa termasuk<br />
jaringan tanaman yang baik, karena secara<br />
cepat seleksi pada tingkat bibit dapat
264 Hengky Novarianto<br />
dilakukan melalui daun (Novarianto dan<br />
Hartana 1994).<br />
Sebelum ditanam di lapangan, tanaman<br />
kelapa perlu dibibitkan selama 6 bulan.<br />
Setiap bulan akan terbentuk rata-rata satu<br />
helai daun, sehingga bibit umur 6 bulan<br />
sejak berkecambah memiliki enam helai<br />
daun. Hasil pemeriksaan pada berbagai<br />
tingkat umur daun bibit kelapa menunjukkan<br />
bahwa pola pita isozim peroksidase<br />
(PER), glutamat oksaloasetat transaminase<br />
(GOT), dan esterase (EST) tidak memperlihatkan<br />
perbedaan pada individu bibit<br />
yang sama (Novarianto 1988; Novarianto<br />
dan Hartana 1994). Dengan demikian,<br />
penggunaan daun kelapa sebagai materi<br />
dalam analisis isozim sangat menguntungkan<br />
karena selain tanaman kelapa<br />
produktif, sejak tingkat bibit sudah dapat<br />
dilakukan seleksi awal.<br />
Kelapa hibrida KHINA-1, KHINA-2,<br />
dan KHINA-3 merupakan hasil perakitan<br />
dengan menggunakan varietas kelapa lokal<br />
Indonesia (Novarianto et al. 1984). Seleksi<br />
tetua ketiga kelapa hibrida tersebut didasarkan<br />
pada karakter morfologi. Potensi<br />
hasil kopra ketiga varietas kelapa hibrida<br />
tersebut tinggi dan tidak berbeda nyata.<br />
Efek heterosis terlihat pada hasil kopra<br />
ketiganya, dan nisbah kopra terhadap<br />
bobot buah utuh, buah tanpa sabut, dan<br />
buah tanpa air adalah sama (Novarianto et<br />
al. 1988c). Kemiripan ini sejalan dengan<br />
hasil analisis keragaman pola pita isozim<br />
dari daun. Ternyata ketiga varietas kelapa<br />
hibrida tersebut memiliki pola pita yang<br />
sama pada lima sistem enzim, dan perbedaan<br />
hanya terdapat pada isozim PER<br />
(Novarianto et al. 1988b). Pola pita lima<br />
sistem enzim yang tidak beragam adalah<br />
katalase (CAT), leusin amino peptidase<br />
(LAP), alkohol dehidrogenase (ADH),<br />
endopeptidase (ENP) dan asam fosfatase<br />
(ACP), serta yang beragam yaitu peroksi-<br />
dase (PER). Isozim PER pada tanaman<br />
kelapa memiliki empat macam pola pita PER<br />
(Novarianto et.al. 1988a). Sebaliknya,<br />
delapan jenis kelapa hibrida Genjah x Dalam<br />
lainnya tidak memperlihatkan perbedaan<br />
nyata pada karakter morfologi lingkar<br />
batang semu, tinggi bibit, dan umur pecah<br />
daun pertama. Namun, melalui keragaman<br />
pola pita isozim PER, GOT dan EST,<br />
silangan Genjah Kuning Bali x Dalam<br />
Banyuwangi sangat tidak mirip dengan<br />
tujuh silangan lainnya (Randriany et al.<br />
1993). Ini menunjukkan bahwa ciri genetik<br />
berdasarkan pola pita isozim dapat membantu<br />
dan memperkuat perbedaan berdasarkan<br />
morfologi dalam seleksi kelapa.<br />
Keragaman pola pita isozim telah<br />
digunakan untuk mengukur kemiripan<br />
genetik antaraksesi kelapa pada koleksi<br />
plasma nutfah. Pengelompokan berbagai<br />
aksesi kelapa sangat bermanfaat dalam<br />
pemilihan tetua untuk perakitan kelapa<br />
unggul. Untuk mempelajari kemiripan<br />
genetik kelapa, metode terbaik adalah<br />
dengan analisis gugus berdasarkan jarak<br />
Euclid (Novarianto 1994a).<br />
Keragaman pola pita isozim PER, GOT,<br />
dan EST telah digunakan untuk mengelompokkan<br />
30 aksesi kelapa koleksi plasma<br />
nutfah di KP Bone-bone, Sulawesi Selatan,<br />
berdasarkan kemiripan genetiknya. Berdasarkan<br />
jarak Euclid pada kemiripan genetik<br />
75%, koleksi plasma nutfah kelapa<br />
terbagi menjadi lima kelompok. Aksesi yang<br />
paling tidak mirip adalah kelapa asal Nusa<br />
Tenggara Timur, yaitu kelapa Dalam Boa,<br />
Mogdale, dan Oebafok (Novarianto dan<br />
Hartana 1993). Analisis yang sama telah<br />
dilakukan pula pada 23 aksesi kelapa<br />
koleksi plasma nutfah di KP Pakuwon,<br />
Jawa Barat. Secara umum, kelapa Dalam<br />
mengelompok sendiri, terpisah dari kelapa<br />
Genjah, kecuali Genjah Sri Tanjung dan<br />
Genjah Trenggalek yang berasal dari Jawa
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 265<br />
Timur (Novarianto et al. 1988a). Tiga<br />
kelapa Genjah yang memiliki warna kulit<br />
buah kuning, yaitu Genjah Kuning Nias,<br />
Genjah Kuning Malaysia, dan Genjah<br />
Kuning Bali, paling jauh hubungan kekerabatannya<br />
dengan berbagai aksesi kelapa<br />
Dalam. Di antara kelapa Dalam, Dalam<br />
Banyuwangi dan Dalam Riau paling jauh<br />
hubungan kekerabatannya dengan aksesi<br />
kelapa Dalam lainnya (Novarianto et al.<br />
1993a).<br />
Keragaman pola pita isozim juga telah<br />
digunakan untuk menganalisis gabungan<br />
koleksi plasma nutfah kelapa di tiga lokasi,<br />
yaitu 35 kultivar kelapa dari kebun koleksi<br />
plasma nutfah Mapanget-Sulawesi Utara,<br />
23 kultivar dari kebun Pakuwon-Jawa<br />
Barat, dan 27 kultivar dari kebun Bonebone-Sulawesi<br />
Selatan. Hasil analisis kemiripan<br />
genetik antarkultivar kelapa menunjukkan<br />
bahwa antarkultivar kelapa tipe<br />
Genjah memiliki keragaman genetik isozim<br />
dan morfologi yang lebih besar dibanding<br />
antarkultivar kelapa Dalam. Dari 85 kultivar<br />
yang dianalisis kemiripan genetiknya, sebagian<br />
besar kultivar kelapa Genjah memiliki<br />
kemiripan genetik yang cukup jauh,<br />
namun untuk kelapa Dalam hanya beberapa<br />
kultivar saja (Novarianto et al. 1993b).<br />
Hasil ini menunjukkan bahwa antarkultivar<br />
kelapa Genjah memiliki perbedaan<br />
genetik yang lebih besar dibandingkan<br />
antarkultivar kelapa Dalam. Perbedaan keragaman<br />
genetik berdasarkan pola pita<br />
isozim dapat digunakan bersamaan dengan<br />
keragaman berdasarkan morfologi dalam<br />
seleksi tetua kelapa untuk pemuliaan lebih<br />
lanjut.<br />
Isozim dapat pula digunakan untuk<br />
memperoleh kode gen tunggal pada tanaman<br />
tahunan (Torres et al. 1978). Pada<br />
tanaman kelapa, dari tiga sistem enzim<br />
hanya satu sistem enzim, yaitu GOT yang<br />
mengikuti nisbah Mendel monohibrida.<br />
Sistem enzim GOT memiliki satu gen dua<br />
alel yang mengontrol ekspresi pola pita<br />
GOT-1 dan GOT-2 (Novarianto 1994b). Ciri<br />
pola pita GOT dapat digunakan dalam<br />
seleksi tanaman kelapa yang terkait dengan<br />
sifat unggul, seperti cepat berbuah,<br />
resisten terhadap penyakit, atau toleran<br />
kekeringan.<br />
PERAKITAN KELAPA UNGGUL<br />
MELALUI TEKNIK DNA<br />
Dengan berkembangnya teknologi penanda<br />
DNA, keanekaragaman karakter<br />
genetik dalam plasma nutfah kelapa pada<br />
tingkat DNA dapat diketahui. Penanda<br />
DNA dianggap dapat memberikan informasi<br />
keanekaragaman karakter genetik<br />
yang lebih baik, terutama untuk penanda<br />
suatu populasi atau aksesi tanaman, karena<br />
mampu memberikan pita DNA polimorfis<br />
dalam jumlah banyak, konsisten,<br />
dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan.<br />
Informasi genetik berdasarkan penanda<br />
DNA dapat dilakukan dengan Restriction<br />
Fragment Length Polymorphism (RFLP),<br />
Random Amplified Polymorphic DNA<br />
(RAPD), Amplified Fragment Length<br />
Polymorphism (AFLP), dan Simple Sequence<br />
Repeat (SSR) atau mikrosatelit<br />
(Powel et al. 1996; Karp dan Edwards 1997).<br />
Dengan menggunakan penanda<br />
RAPD, keragaman genetik kelapa Genjah<br />
Orange Sagerat mencapai 22%, Genjah<br />
Kuning Bali 17%, dan Genjah Kuning Nias<br />
14% (Mawikere 1998). Artinya Genjah Kuning<br />
Nias paling seragam, diikuti Genjah<br />
Kuning Nias dan Genjah Orange Sagerat.<br />
Kelapa Genjah Kuning Nias lebih dekat<br />
dengan Genjah Kuning Bali dibandingkan<br />
dengan Genjah Orange Sagerat. Kemiripan<br />
Genjah Kuning Nias dengan Genjah Kuning<br />
Bali ditemukan pula pada analisis
266 Hengky Novarianto<br />
berdasarkan pola pita isozim (Novarianto<br />
et al. 1993a). Dengan demikian, sebagai<br />
bahan tanaman untuk pemuliaan, Genjah<br />
Kuning Nias lebih baik dibanding Genjah<br />
Kuning Bali dan Genjah Orange Sagerat<br />
karena lebih homogen.<br />
Studi dengan menggunakan analisis<br />
RAPD pada populasi asli dan populasi<br />
koleksi memberikan hasil yang cukup berbeda<br />
pada kultivar yang sama. Dengan<br />
teknik analisis DNA, diketahui bahwa<br />
kelapa Genjah Jombang hasil koleksi ex situ<br />
lebih beragam dibanding kultivar yang<br />
sama di tempat aslinya in situ, yaitu di<br />
Jombang (Hayati et al. 2000). Hasil analisis<br />
ini menunjukkan bahwa pemanfaatan<br />
kelapa Genjah Jombang pada koleksi<br />
plasma nutfah untuk pemuliaan membutuhkan<br />
tindakan seleksi dan hibridisasi<br />
agar lebih seragam.<br />
Hasil lain yang memperkuat bahwa<br />
teknik DNA dapat mempercepat seleksi<br />
bahan tanaman kelapa dapat dilihat pada<br />
hasil penelitian jenis-jenis kelapa asal<br />
Papua. Kelapa asal Biak mempunyai<br />
hubungan kekerabatan yang jauh dengan<br />
kelapa asal Sorong, Manokwari, Jayapura,<br />
dan Merauke. Selanjutnya kelapa asal<br />
Papua mempunyai hubungan kekerabatan<br />
yang lebih dekat dengan kelapa asal Nusa<br />
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,<br />
Jawa, Sumatera Utara, Kalimantan Barat,<br />
dan Sulawesi Utara, tetapi sebaliknya<br />
mempunyai hubungan yang lebih jauh<br />
dengan kelapa asal Maluku Utara (Tidore<br />
dan Ternate), Bali (Dalam Bali), dan<br />
Sulawesi Tengah (Dalam Palu) (Mawikere<br />
2005).<br />
Kelapa Dalam Mapanget (DMT) adalah<br />
aksesi kelapa yang pertama kali dikoleksi<br />
di kebun Mapanget. Nomor-nomor terpilih<br />
kelapa ini yang mencapai 100 nomor,<br />
diseleksi berdasarkan potensi hasil buah<br />
dan kopra. Pada beberapa nomor unggulan<br />
seperti DMT no. 10 dan 32 dilakukan<br />
penyerbukan sendiri untuk pemurnian<br />
genotipe. Sampai saat ini telah dilakukan<br />
penyerbukan sendiri sampai generasi<br />
keempat atau selfing DMT S4. Dengan<br />
penanda RAPD diketahui bahwa hasil<br />
penyerbukan sendiri kelapa Dalam Mapanget<br />
sampai generasi ketiga (DMT S3)<br />
sudah lebih homozigot daripada tetuanya,<br />
yaitu DMT S2 dan DMT S0 (Novarianto et<br />
al. 2001). Dengan demikian, kelapa Dalam<br />
Mapanget S3 dapat digunakan sebagai<br />
materi untuk perakitan kelapa unggul.<br />
STRATEGI PEREMAJAAN KELAPA<br />
Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas<br />
kelapa ditempuh antara lain<br />
melalui rehabilitasi dan peremajaan dengan<br />
menggunakan bibit unggul, khususnya<br />
pada tanaman kelapa rakyat yang<br />
tua dan rusak. Dalam rencana kegiatan<br />
penanganan agribisnis perkelapaan nasional,<br />
peremajaan dan pengembangan<br />
tanaman kelapa tahun 2006-2010 masingmasing<br />
meliputi 100.000 dan 10.000 ha, atau<br />
total selama 5 tahun seluas 550.000 ha<br />
(Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan<br />
2004). Jika setiap hektar areal peremajaan<br />
dan pengembangan membutuhkan<br />
220 benih kelapa unggul maka dalam<br />
satu tahun harus tersedia benih unggul<br />
24,2 juta butir yang berasal dari sekitar<br />
3.000 ha kebun induk. Padahal pada saat<br />
ini belum ada kebun induk yang dapat<br />
menyuplai benih kelapa unggul.<br />
Program pengembangan kelapa bertujuan<br />
untuk meningkatkan produktivitas<br />
kelapa. Pada saat ini, secara nasional proporsi<br />
tanaman tua yang berumur lebih dari<br />
50 tahun mencapai 15% atau 583.500 ha
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 267<br />
dari total areal kelapa seluas 3,89 juta ha.<br />
Agar produksi kelapa tidak menurun,<br />
peremajaan dan rehabilitasi harus dilakukan<br />
terus-menerus, karena tanaman muda<br />
akan menjadi tua atau rusak akibat serangan<br />
hama dan penyakit serta bencana<br />
alam. Untuk meningkatkan produktivitas<br />
tanaman yang saat ini tergolong rendah,<br />
peremajaan dan rehabilitasi memerlukan<br />
bibit unggul yang berasal dari kelapa<br />
unggul lokal dan kebun induk.<br />
Program Pemanfaatan Kelapa<br />
Unggul Lokal<br />
Orientasi pengadaan benih kelapa sebagai<br />
bahan tanaman belum sepenuhnya<br />
memenuhi kualitas yang baik tetapi tepat<br />
jumlah harus tercukupi. Pengadaan benih<br />
dengan cara ini mengakibatkan tidak seragamnya<br />
pertanaman dan produktivitas,<br />
baik di dalam maupun di antara populasi.<br />
Apabila pohon induk kelapa sumber<br />
benih berasal dari hasil penyerbukan silang<br />
alami, maka benih yang dihasilkan<br />
stabil secara genetik mengikuti hukum<br />
keseimbangan Hardy Weinberg (Carpena<br />
et al. 1993). Hal ini berarti frekuensi genotipe<br />
populasi tanaman tidak akan berubah<br />
dari generasi ke generasi, sehingga petani<br />
dapat menggunakan buah kelapa tersebut<br />
sebagai benih tanpa terjadi penurunan<br />
kekekaran. Suatu petunjuk bahwa seleksi<br />
massa dapat memperbaiki produktivitas<br />
kelapa.<br />
Penetapan blok penghasil tinggi (BPT)<br />
dan seleksi pohon induk kelapa (PIK)<br />
merupakan metode yang dapat dipilih<br />
untuk mempercepat penyediaan bibit<br />
kelapa unggul lokal bagi setiap daerah.<br />
Setelah BPT ditetapkan, dilanjutkan<br />
dengan seleksi individu sehingga diper-<br />
oleh pohon-pohon induk sumber benih<br />
untuk bahan tanaman. Tingkat seleksi PIK<br />
untuk setiap BPT dianjurkan maksimum<br />
15% tanaman terbaik. Untuk merealisasikan<br />
kegiatan ini, diharapkan Direktorat<br />
Jenderal Perkebunan dan Dinas Perkebunan<br />
Provinsi/Kabupaten terkait dapat<br />
memprogramkan dan menyediakan dana<br />
untuk penetapan BPT dan PIK. Percepatan<br />
seleksi BPT dan PIK dapat dilakukan<br />
berdasarkan data morfologi dan molekuler.<br />
Sejak tahun 2005-2007 beberapa Dinas<br />
Perkebunan Provinsi bekerja sama dengan<br />
Balitka telah melakukan penetapan BPT<br />
dan seleksi PIK, yakni Jawa Timur, Gorontalo,<br />
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,<br />
Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan,<br />
Sulawesi Barat, Daerah Istimewa<br />
Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Sumatera<br />
Utara, dan Jambi. Dari 13 provinsi tersebut<br />
telah ditetapkan lebih dari 1.000 ha<br />
BPT dan terseleksi PIK sekitar 15.000<br />
pohon dengan produksi benih 1,16 juta<br />
butir/tahun. Jumlah ini masih kurang<br />
dibandingkan kebutuhan benih jika peremajaan<br />
dan rehabilitasi berjalan sesuai<br />
dengan target Direktorat Jenderal Perkebunan,<br />
yaitu 100.000 ha/tahun. Dengan<br />
demikian, transfer teknologi benih unggul<br />
Balitka dalam kaitannya dengan penetapan<br />
BPT dan seleksi PIK kepada petugas<br />
lapangan Dinas Perkebunan di 13 provinsi<br />
tersebut perlu diperluas dan diikuti oleh<br />
Dinas terkait lainnya yang telah memprogramkan<br />
pengembangan kelapa di<br />
daerah masing-masing.<br />
Program Pembangunan Kebun<br />
Induk Kelapa Dalam Komposit<br />
Varietas komposit dihasilkan dari persilangan<br />
alami secara acak dari beberapa varietas
268 Hengky Novarianto<br />
unggul yang menyerbuk silang (Hallauer<br />
dan Miranda 1982). Hibridisasi kelapa<br />
Dalam yang menghasilkan kelapa hibrida<br />
Dalam x Dalam telah dilakukan di beberapa<br />
negara penghasil kelapa. Santos et al.<br />
(2000) melaporkan bahwa kelapa hibrida<br />
Dalam x Dalam memperlihatkan penampilan<br />
lebih baik dari kedua tetuanya (efek<br />
heterosis) untuk karakter waktu berbunga,<br />
jumlah buah, dan hasil kopra. Komponen<br />
buah dari kultivar kelapa hibrida ini juga<br />
menunjukkan efek heterosis (Akuba 2002).<br />
Efek heterosis berat kopra pada kelapa<br />
hibrida Dalam Tenga x Dalam Bali dan<br />
resiproknya Dalam Bali x Dalam Tenga umur<br />
7 tahun mencapai 8,6-37,1% (Rompas et<br />
al. 1990). Akuba (2002) melaporkan, heterosis<br />
kelapa hibrida Dalam x Dalam yang<br />
merupakan populasi dasar varietas kelapa<br />
Dalam komposit yang dikembangkan oleh<br />
Philippine Coconut Authority-Zamboanga<br />
Research Center (PCA-ZRC) berkisar 4,5-<br />
29,6% pada bobot buah dan 1,74-17,3%<br />
pada bobot kopra pada umur 10 tahun.<br />
Bobot kopra per buah dari kelapa Dalam<br />
komposit lebih tinggi 8,5% dari tetuanya<br />
kelapa Dalam.<br />
Penyediaan varietas kelapa unggul<br />
untuk memenuhi kebutuhan peremajaan<br />
kelapa tua dilakukan melalui perakitan<br />
kelapa hibrida Dalam x Dalam tanpa persilangan<br />
buatan, yaitu hibrida alami. Kelapa<br />
Dalam komposit memiliki beberapa kelebihan<br />
dibanding kelapa hibrida Genjah x<br />
Dalam. Selain berproduksi tinggi (minimal<br />
2,25 ton kopra/ha/tahun), keragaman genetiknya<br />
besar sehingga lebih tahan terhadap<br />
variasi iklim. Untuk mendapatkan<br />
populasi kelapa Dalam komposit dengan<br />
efek heterosis tertinggi, diperlukan seleksi<br />
kelapa Dalam tetua yang antarvarietas<br />
memiliki ketidakmiripan genetik jauh, tetapi<br />
masing-masing varietas tersebut me-<br />
miliki potensi produksi tinggi. Seleksi<br />
kelapa Dalam sebagai calon tetua dalam<br />
perakitan kelapa Dalam komposit dapat<br />
dipercepat melalui analisis data molekuler.<br />
Balitka telah bekerja sama dengan instansi<br />
terkait untuk membangun KIKD<br />
Komposit di beberapa daerah. Tetua kelapa<br />
Dalam yang digunakan dipilih berdasarkan<br />
karakter morfologi, potensi hasil,<br />
dan jarak genetik dengan menggunakan<br />
data molekuler. Pola kelapa Dalam komposit<br />
yang dibangun adalah perakitan kelapa<br />
Dalam komposit serbuk bebas dan hibrida<br />
intervarietas (Akuba 2008). Pada tahun<br />
2003-2007 telah dibangun KIKD Komposit<br />
114 ha lebih di beberapa provinsi, yaitu<br />
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat,<br />
Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah,<br />
Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,<br />
Jawa Barat, dan Sumatera Utara, dengan<br />
estimasi produksi benih 1 juta butir/<br />
tahun.<br />
Kelapa Dalam komposit serbuk bebas<br />
terdiri atas 10 varietas kelapa Dalam unggul,<br />
yakni Dalam Mapanget, Tenga, Bali,<br />
Palu, Sawarna, Lubuk Pakam, Jepara, Banyuwangi,<br />
Kima Atas, dan Rennel. Lalu<br />
pola serbuk bebas yang lain terdiri atas<br />
empat varietas unggul di atas, yaitu Dalam<br />
Mapanget, Tenga, Bali dan Palu, yang dikombinasikan<br />
dengan tiga kultivar kelapa<br />
Dalam unggul lokal setempat. Tetua kelapa<br />
Dalam komposit ditanam mengikuti model<br />
sarang lebah sehingga persilangan antarvarietas<br />
berpeluang sangat besar untuk<br />
membentuk genotipe heterozigot. Kelapa<br />
Dalam komposit hibrida intervarietas terdiri<br />
atas enam varietas unggul, yaitu Dalam<br />
Mapanget, Tenga, Bali, Palu, Sawarna, dan<br />
Rennel yang disilangkan secara buatan<br />
untuk mendapatkan 15 kombinasi hibrida.<br />
Hasil persilangan ini ditanam campuran<br />
sebagai induk kelapa Dalam komposit
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 269<br />
hibrida intervarietas (Akuba 2008; Kumaunang<br />
2008). Diharapkan setiap provinsi/kabupaten<br />
dapat membangun KKID<br />
Komposit secara bertahap minimal 100 ha<br />
untuk memenuhi kebutuhan benih dalam<br />
peremajaan kelapa.<br />
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI<br />
KEBIJAKAN<br />
Introduksi kelapa hibrida dari luar negeri<br />
ke Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan<br />
produktivitas kelapa dalam rangka<br />
memenuhi kebutuhan kopra dan minyak<br />
goreng. Petani kelapa kurang menyukai<br />
kelapa hibrida untuk peremajaan karena<br />
produktivitas rendah, ukuran buah kecil,<br />
dan peka terhadap penyakit.<br />
Petani kelapa umumnya lebih memilih<br />
kelapa Dalam dengan pertimbangan: (1)<br />
tidak membutuhkan pemeliharaan intensif;<br />
(2) lebih tahan terhadap serangan penyakit<br />
dan cekaman lingkungan kering; (3) benih<br />
lebih mudah diperoleh dan murah; dan (4)<br />
produksi lebih stabil dan ukuran buah<br />
besar. Untuk memenuhi kebutuhan petani<br />
akan benih kelapa Dalam, telah dilepas lima<br />
varietas kelapa Dalam unggul pada tahun<br />
2004 dan 2006.<br />
Metode seleksi secara molekuler seperti<br />
teknik isozim dan DNA dapat digunakan<br />
untuk mempercepat seleksi varietas<br />
dan pohon tetua dalam pemuliaan<br />
kelapa. Teknik molekuler bermanfaat untuk<br />
mengetahui kemiripan genetik antarpopulasi,<br />
aksesi, kultivar, dan varietas<br />
kelapa.<br />
Kebutuhan benih kelapa Dalam untuk<br />
program peremajaan sangat besar dan<br />
belum tersedia sumber benih kelapa unggul<br />
yang cukup. Strategi jangka pendek<br />
untuk penyediaan benih kelapa unggul<br />
adalah dengan memanfaatkan sumber<br />
benih kelapa Dalam unggul lokal. Selanjutnya<br />
penyediaan benih untuk jangka<br />
panjang dilakukan melalui pembangunan<br />
Kebun Induk Kelapa Dalam (KIKD) Komposit<br />
di setiap daerah. Teknik molekuler<br />
dapat digunakan untuk mempercepat<br />
seleksi kelapa sebagai tetua dalam perakitan<br />
kelapa Dalam komposit.<br />
Pembangunan KIKD Komposit dapat<br />
dilakukan dalam bentuk waralaba benih,<br />
yaitu petani, pengusaha, pemerintah daerah,<br />
dan pengguna lainnya sebagai penerima<br />
waralaba dan Balai Penelitian Tanaman<br />
Kelapa dan Palma Lain sebagai pemberi<br />
waralaba. Pembangunan KIKD Komposit<br />
dengan mengikutsertakan petani/asosiasi<br />
petani dan pemerintah daerah akan meningkatkan<br />
partisipasi masyarakat dalam<br />
pembangunan, meningkatkan pendapatan,<br />
mendorong komersialisasi perbenihan,<br />
meningkatkan pendapatan asli daerah,<br />
serta mendukung percepatan pelaksanaan<br />
otonomi daerah.<br />
PENUTUP<br />
Orasi ini mengangkat peran aspek evaluasi<br />
keragaman plasma nutfah kelapa sebagai<br />
pangkalan data dalam pemuliaan kelapa.<br />
Dengan berdasarkan pada sumber genetik<br />
kelapa, seleksi dan hibridisasi kelapa dapat<br />
dilakukan lebih terarah dan tepat sehingga<br />
varietas kelapa unggul yang dirakit<br />
lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen.<br />
Tanaman kelapa adalah perkebunan<br />
rakyat, sehingga program peremajaan<br />
dan pengembangan kelapa harus<br />
melibatkan petani kelapa secara langsung,<br />
termasuk dalam penyediaan bahan tanaman<br />
unggul sebagai salah satu komponen<br />
produksi yang sangat penting.
270 Hengky Novarianto<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
Adams, W.T. 1983. Application of isozymes<br />
in tree breeding. p.381-400. In<br />
S.D. Tanksley and T.J. Orton (Eds.).<br />
Isozymes in Plant Genetics and Breeding.<br />
Part A. Elsevier, New York.<br />
Akuba, R.H. 1991. Pemetaan daerah rawan<br />
serangan penyakit busuk pucuk kelapa<br />
di Sulawesi Utara. Jurnal Penelitian<br />
Kelapa 5(1): 5-11.<br />
Akuba, R.H., H. Hasni, N. Mokodongan,<br />
R. Rahman, dan M.M.M. Rumokoi.<br />
1992. Survei pengusahaan kelapa di<br />
Sulawesi Utara. Laporan Penelitian.<br />
Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan<br />
Palma Lain, Manado.<br />
Akuba, R.H. 1998. Dampak kekeringan dan<br />
kebakaran terhadap kelapa. Prosiding<br />
Konferensi Nasional Kelapa IV. Lampung.<br />
Pusat Penelitian dan PengembanganTanaman<br />
Industri, Bogor.<br />
Akuba, R.H. 2002. Breeding and population<br />
genetic studies on coconut (Cocos<br />
nucifera L.) composite variety using<br />
morphological and microsatellite markers.<br />
PhD Thesis. UPLB, Philippines.<br />
230 pp.<br />
Akuba, R.H. 2008. Merakit Tree of Life.<br />
Badan Lingkungan Hidup, Riset dan<br />
Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo.<br />
313 hlm.<br />
Bennett, C.P.A., O. Roboth, and G. Sitepu.<br />
1985. Aspect of the control of premature<br />
nutfall disease of coconut, Cocos<br />
nucifera L. caused by Phythopthora<br />
palmivora Butler. Seminar Proteksi<br />
Tanaman Kelapa, Bogor. p.157-175.<br />
Carpena, A. L., R. R. C. Espino, T. L. Rosario<br />
and R.P. Laude. 1993. Genetics at<br />
population level. SEAMEO Regional<br />
Center for Graduate Study and<br />
Research in Agriculture (SEAMEO-<br />
SEARCA)-UPLB, Los Banos, Philippines.<br />
Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.<br />
2004. Rencana Makro Pengembangan<br />
Agribisnis Komoditas Kelapa.<br />
Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan,<br />
Jakarta. 50 hlm.<br />
Direktorat Jenderal Perkebunan. 2007.<br />
Statistik Perkebunan Indonesia. Kelapa.<br />
Direktorat Jenderal Perkebunan,<br />
Jakarta. 81 hlm.<br />
Hallauer, A. R. and J. B. Miranda, FO. 1982.<br />
Quantitative Genetics in Maize Breeding.<br />
The Iowa State University Press.<br />
468 pp.<br />
Hayati, P.K.D., A. Hartana, Suharsono, dan<br />
H. Aswidinnoor. 2000. Keanekaragaman<br />
genetik kelapa Genjah Jombang<br />
berdasarkan RAPD. Hayati 7(2): 35-40.<br />
Hayward, M.D. and N.J. McAdam. 1988.<br />
The effect of isozyme selection on yield<br />
and flowering time in Lolium perenne.<br />
Plant Breeding 101(1): 24-29.<br />
Hosang, M.L.A. and A.A. Lolong. 1998.<br />
Pengendalian hama dan penyakit kelapa<br />
terpadu. hlm. 202-222. Prosiding<br />
Konferensi Nasional Kelapa IV, Lampung.<br />
Pusat Penelitian dan Pengembangan<br />
Tanaman Industri, Bogor.<br />
Karp, A.S. and K.J. Edwards. 1997. Techniques<br />
for analysis, characterization<br />
and conservation of plant genetic resources.<br />
p. 11-22. In Karp et al. (Eds.).<br />
Molecular Tools in Plant Genetic Resources<br />
Conservation. A Guide to the<br />
Technologies. IPGRI.<br />
Kumaunang, J. 2008. Kemajuan pembangunan<br />
kebun induk kelapa Dalam<br />
Komposit dan strategi perluasannya.<br />
Warta Penelitian dan Pengembangan<br />
Tanaman Industri 14(1): 10-11.<br />
Kut, S.A. and D.A. Evans. 1984. ADH<br />
isozymes in seed of Nicotiana species
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 271<br />
and somatic hybrids. J. Hered. 75: 215-<br />
219.<br />
Liyanage, D.V. 1972. Production of improved<br />
coconut seed by hybridization.<br />
Oleagineux 12: 597-599.<br />
Liyanage, D.V. 1973. Pemuliaan galur-galur<br />
kelapa berproduksi tinggi. Pemberitaan<br />
LPTI 15-16: 23-27.<br />
Liyanage, D.V. 1974. Survey of coconut<br />
germplasm in Indonesia. UNDP/FAO.<br />
Coconut Industry Development Project,<br />
<strong>Document</strong> No.1. LPTI, Bogor. 30<br />
pp.<br />
Makmur, A. 1988. Masalah pemuliaan<br />
tanaman pada lada, cengkeh, kelapa<br />
dan kapas. Prosiding Lokakarya Pemuliaan<br />
Tanaman Cengkeh, Lada,<br />
Kapas dan Kelapa. Pusat Penelitian<br />
dan Pengembangan Tanaman Industri,<br />
Bogor. hlm. 57-58.<br />
Mawikere, N.D. 1998. Identifikasi dan<br />
kloning DNA ruas berulang tanaman<br />
kelapa kultivar Genjah Kuning Nias.<br />
Makalah Seminar Hasil Program Pascasarjana<br />
Institut Pertanian Bogor.<br />
Mawikere, N.D. 2005. Plasma nutfah kelapa<br />
Papua dan hubungan kekerabatannya<br />
dengan populasi kelapa Indonesia dan<br />
Papua New Guinea berdasarkan penanda<br />
RAPD. Draf Disertasi Sekolah<br />
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.<br />
Mc Granahan, G.H., W. Tulecke, S. Arulsekar,<br />
and J.J. Hansen. 1986. Intergeneric<br />
hybridization in the Juglandaceae:<br />
Terocarya sp. x Juglans regia.<br />
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 111(4): 627-630.<br />
Miftahorrachman, H.F. Mangindaan, dan<br />
H. Novarianto. 1996. Diversitas genetik<br />
komponen buah kultivar kelapa Dalam<br />
Sulawesi Utara. Jurnal Zuriat 7(1): 7-<br />
15.<br />
Nevo, E., A. Beiles, and D. Kaplan. 1987.<br />
Genetic diversity and environmental<br />
associations of wild emmer wheat in<br />
Turkey. Heredity 61(1): 31-45.<br />
Novarianto, H., Miftahorrachman, H.<br />
Tampake, E.T. Tenda, dan T. Rompas.<br />
1984. Pengujian F1 kelapa Genjah x<br />
Dalam. Pemberitaan Puslitbangtri 8(49):<br />
21-27.<br />
Novarianto, H. 1988. Analisis isozim peroksidase<br />
pada bibit kelapa KHINA-1.<br />
Jurnal Penelitian Kelapa 2(2): 74-80.<br />
Novarianto, H., A. Hartana, and L.U. Gadrinab.<br />
1988a. Keanekaragaman pola<br />
pita isozim peroksidase pada koleksi<br />
kelapa di kebun percobaan Pakuwon,<br />
Sukabumi. Floribunda 1(7): 25-28.<br />
Novarianto, H., A. Hartana, A. Makmur, dan<br />
L.U. Gadrinab. 1988b. Analisis isozim<br />
daun kelapa hibrida dan tetuanya. Pemberitaan<br />
Puslitbangtri XIII(3-4): 53-56.<br />
Novarianto, H., H. Tampake, T. Rompas,<br />
dan H.T. Luntungan. 1988c. Komponen<br />
buah kelapa hibrida Indonesia. Pemberitaan<br />
Puslitbangtri XIII(3-4): 61-64.<br />
Novarianto, H., A. Hartana, dan A. Mattjik.<br />
1992a. Analisis kuantitatif karakter<br />
agronomi kelapa hibrida dan tetuanya.<br />
Forum Pascasarjana IPB 15(1): 11-16.<br />
Novarianto, H. dan A. Hartana. 1993. Keragaan<br />
pola pita isozim tanaman kelapa<br />
di kebun Bone-bone, Sulawesi Selatan.<br />
Pemberitaan Puslitbangtri XVIII (3-4):<br />
81-86.<br />
Novarianto, H., A. Hartana, dan A.H. Nasoetion.<br />
1993a. Hubungan kekerabatan<br />
antarpopulasi kelapa di kebun plasma<br />
nutfah Pakuwon, Sukabumi. Jurnal<br />
Biologi Indonesia 1(1): 55-65.<br />
Novarianto, H., A. Hartana, F. Rumawas,<br />
M.A. Rifai, E. Guharja, dan A.H. Nasoetion.<br />
1993b. Kemiripan genetik<br />
antarpopulasi kelapa di Indonesia berdasarkan<br />
pola pita isozim. Jurnal Penelitian<br />
Kelapa 6(2): 1-8.
272 Hengky Novarianto<br />
Novarianto, H. 1994a. Beberapa metode<br />
analisis kemiripan genetika kelapa.<br />
Buletin Balitka 21: 15-24.<br />
Novarianto, H. 1994b. Pola pewarisan<br />
isozim pada tanaman kelapa. Jurnal<br />
Penelitian Kelapa 7(1): 30-35.<br />
Novarianto, H. dan A. Hartana. 1994. Perkembangan<br />
dan diferensiasi isozim<br />
pada tanaman kelapa. Jurnal Biologi<br />
Indonesia 1(2): 35-39.<br />
Novarianto, H., T. Rompas, and S.N. Darwis.<br />
1998. Coconut breeding programme<br />
in Indonesia. p. 28-41. In P.A.<br />
Batugal and V. R. Rao (Eds.). Coconut<br />
Breeding. Proc. Workshop on Standardization<br />
of Coconut Breeding Research<br />
Techniques, Port Bouet, Cote<br />
de Ivoire, 20-25 June 1994. IPGRI-APO,<br />
Serdang Malaysia.<br />
Novarianto, H. 2001. Harapan unggul dari<br />
Balitka. Trubus 384: 101.<br />
Novarianto, H., J. Kumaunang, M.A.<br />
Tulalo, A. Masniawati, dan A. Hartana.<br />
2001. Keragaman genetik kelapa Dalam<br />
Mapanget nomor 32 hasil penyerbukan<br />
sendiri berdasarkan penanda RAPD.<br />
Pemberitaan Puslitbangtri 7(2): 43-48.<br />
Novarianto, H. dan E.T. Tenda. 2002. Persiapan<br />
pelepasan lima varietas kelapa<br />
Dalam. Warta Penelitian dan Pengembangan<br />
Tanaman Industri 8(1): 9-11.<br />
Novarianto, H., R.H. Akuba, dan M.<br />
Hosang. 2004. Memodernisasi perkelapaan<br />
Indonesia dengan inovasi<br />
teknologi. Prosiding Simposium IV<br />
Hasil Penelitian Tanaman Perkebunan,<br />
28-30 September 2004. Pusat Penelitian<br />
dan Pengembangan Perkebunan,<br />
Bogor.<br />
Parfitt, D.E. and S. Arulsekar. 1985. Identification<br />
of plum peach hybrids by<br />
isozymes analysis. Hort. Sci. 20(2): 246-<br />
248.<br />
Peirce, L.C. and Brewbaker. 1973. Application<br />
of isozyme analysis in horticultural<br />
science. Hort. Sci. 8(1): 17-22.<br />
Powel, W., M. Morgante, C. Andre, M.<br />
Hanavey, J. Vogel, S. Tingey, and A.<br />
Rafalski. 1996. The comparison of<br />
RFLP, RAPD, AFLP, and SSR (microsatellite)<br />
markers for germplasm analysis.<br />
Molecular Breeding 2: 225-238.<br />
Randriany, E., H. Tampake, dan H. Novarianto.<br />
1993. Jarak genetik beberapa<br />
jenis kelapa hibrida Genjah x Dalam<br />
berdasarkan sifat-sifat dan pola pita<br />
isozim. Jurnal Penelitian Kelapa 6(1):67-<br />
72.<br />
Rethinam, P., F. Rognon, dan P. Batugal.<br />
2002. Farmer’s perception of high yielding<br />
coconut varieties. p. 170-188. Proc.<br />
the XXXIX Cocotech Meeting, 1-5<br />
July 2002, Pattaya, Thailand.<br />
Rompas,T., H. Novarianto, dan H. Tampake.<br />
1990. Pengujian nomor-nomor terpilih<br />
kelapa Dalam Mapanget di Kebun<br />
Percobaan Kima Atas. Jurnal Penelitian<br />
Kelapa 4(2): 32-34.<br />
Santos, G. A., R. L. Rivera, and G. B. Baylon.<br />
2000. Coconut synthetic variety: A<br />
sustainable option for the farmers. p.<br />
47-92, In S.S. Magat and D.B. Masa<br />
(Eds.). Selected Topics on Current<br />
Trends and Prospects in Enhancing the<br />
Coconut Industry. Proc. the Coconut<br />
Week Symposium, 29 August 2000.<br />
PCA, Philippines.<br />
Second, G. 1982. Origin of the genic diversity<br />
of cultivated rice (Oriza spp.):<br />
Study of the polymorphism scored at<br />
40 isozyme loci. Jpn. J. Genet. 57: 25-<br />
57.<br />
Tampake, H., T. Kuswara, and T.A. Davis.<br />
1982. Coconut germplasm survey of<br />
Nusa Tenggara Timur Province: The<br />
initial step towards resistance in co-
Perakitan kelapa unggul melalui teknik molekuler ... 273<br />
conut strains. Indon. Agric. Res. Dev.<br />
J. 4(2): 52-61.<br />
Tampake, H., H. Novarianto, E.T. Tenda,<br />
dan T. Rompas. 1983. Pengaruh pemeliharaan<br />
intensif terhadap pertumbuhan<br />
kelapa hibrida. Pemberitaan<br />
Puslitbangtri 3(47-48): 6-11.<br />
Tenda, E.T., H. Novarianto, H. Tampake,<br />
Miftahorrachman, R.H. Akuba, H.T.<br />
Luntungan, T. Rompas, Z. Mahmud,<br />
dan J. Kumaunang. 2004. Empat varietas<br />
kelapa Dalam unggul untuk<br />
pengembangan kelapa di Indonesia.<br />
Proposal Pelepasan Varietas. Balai<br />
Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma<br />
Lain, Manado. 19 hlm.<br />
Tenda, E.T., H. Novarianto, H. Tampake,<br />
Miftahorrachman, R.H. Akuba, H.T.<br />
Luntungan, T. Rompas, Z. Mahmud,<br />
dan J. Kumaunang. 2006. Usulan<br />
pemutihan kelapa Dalam Sawarna dan<br />
Takome. Proposal Pelepasan Varietas.<br />
Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan<br />
Palma Lain, Manado. 11 hlm.<br />
Torres, A.M, R.K. Soost, and U. Diedenhofen.<br />
1978. Leaf isozymes as genetic<br />
markers in citrus. Amer. J. Bot. 65(8):<br />
869-881.<br />
Vences, F.J., F. Vaquero, and M. P. de Vega.<br />
1987. Phylogenetic relationships in<br />
Secale (Poaceae), an isozymatic study.<br />
Plant. Syst. Evol. 157(1-2): 33-47.<br />
Warokka. J.S. and H.F. Mangindaan. 1992.<br />
Penyakit busuk pucuk dan kerugian<br />
yang diakibatkannya. Buletin Balitka<br />
16: 48-51.<br />
Yupsanis, T. and M. Moustakas. 1988.<br />
Relationship between quality colour of<br />
glume and gliadin electrophoregrans in<br />
Durum wheat. Plant Breeding 101(1):<br />
30-35.