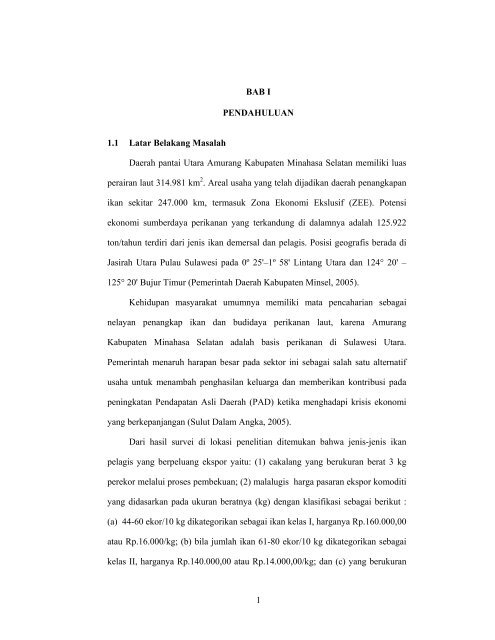Download - Universitas Udayana
Download - Universitas Udayana
Download - Universitas Udayana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1.1 Latar Belakang Masalah<br />
BAB I<br />
PENDAHULUAN<br />
Daerah pantai Utara Amurang Kabupaten Minahasa Selatan memiliki luas<br />
perairan laut 314.981 km 2 . Areal usaha yang telah dijadikan daerah penangkapan<br />
ikan sekitar 247.000 km, termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Potensi<br />
ekonomi sumberdaya perikanan yang terkandung di dalamnya adalah 125.922<br />
ton/tahun terdiri dari jenis ikan demersal dan pelagis. Posisi geografis berada di<br />
Jasirah Utara Pulau Sulawesi pada 0º 25'–1º 58' Lintang Utara dan 124° 20' –<br />
125° 20' Bujur Timur (Pemerintah Daerah Kabupaten Minsel, 2005).<br />
Kehidupan masyarakat umumnya memiliki mata pencaharian sebagai<br />
nelayan penangkap ikan dan budidaya perikanan laut, karena Amurang<br />
Kabupaten Minahasa Selatan adalah basis perikanan di Sulawesi Utara.<br />
Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor ini sebagai salah satu alternatif<br />
usaha untuk menambah penghasilan keluarga dan memberikan kontribusi pada<br />
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika menghadapi krisis ekonomi<br />
yang berkepanjangan (Sulut Dalam Angka, 2005).<br />
Dari hasil survei di lokasi penelitian ditemukan bahwa jenis-jenis ikan<br />
pelagis yang berpeluang ekspor yaitu: (1) cakalang yang berukuran berat 3 kg<br />
perekor melalui proses pembekuan; (2) malalugis harga pasaran ekspor komoditi<br />
yang didasarkan pada ukuran beratnya (kg) dengan klasifikasi sebagai berikut :<br />
(a) 44-60 ekor/10 kg dikategorikan sebagai ikan kelas I, harganya Rp.160.000,00<br />
atau Rp.16.000/kg; (b) bila jumlah ikan 61-80 ekor/10 kg dikategorikan sebagai<br />
kelas II, harganya Rp.140.000,00 atau Rp.14.000,00/kg; dan (c) yang berukuran<br />
1
81-100 ekor/10 kg dikategorikan sebagai ikan kelas III harganya Rp.120.000,00<br />
atau Rp.12.000,00/kg (Dinas Perikanan dan Kelautan Minsel, 2005).<br />
Dalam upaya mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan<br />
kerja bagi generasi muda maka sektor perikanan ini telah membuka lapangan<br />
kerja baru dan menyerap tenaga kerja sebesar 20%, sekaligus telah menurunkan<br />
angka kemiskinan 12% dari jumlah penduduk ± 19.000 jiwa (Pemerintah Daerah<br />
Kabupaten Minsel, 2005).<br />
Di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdapat beberapa macam alat<br />
penangkapan ikan antara lain: payang, pukat pantai, pukat cincin, pukat insang<br />
hanyut/tetap, bagan perahu, serok, funai atau huhate pancing tonda atau noru,<br />
dan bubu. Dari deskripsi macam alat tangkap yang ada, maka pukat cincin atau<br />
purse seine ini yang oleh nelayan di Sulawesi Utara lebih dikenal dengan istilah<br />
soma pajeko sebagai salah satu alat penangkapan ikan-ikan sejenis pelagis.<br />
Pukat cincin adalah termasuk jenis jaring lingkar dimana jaring ditebarkan<br />
mengelilingi segerombalan ikan sehingga membentuk dinding penghalang untuk<br />
mencegah agar ikan yang tertangkap tidak keluar. Ikan-ikan yang ditangkap<br />
seperti: lajang, selar, kembung dan cakalang yang hidupnya membentuk kawanan<br />
besar dengan kepadatan yang tinggi.<br />
Operasi penangkapan dilakukan pada malam hari sampai subuh dini hari<br />
dengan menggunakan alat bantu lampu laguna dan rumpon. Rumpon berfungsi<br />
sebagai tempat hidup habitat plankton-plankton kecil untuk dijadikan umpan<br />
makanan bagi ikan-ikan sejenis pelagis, sedangkan lampu dimanfaatkan untuk<br />
merangsang plankton-plankton berkumpul di suatu tempat dengan demikian ikan<br />
2
akan bergerombol dengan kepadatan tinggi di tempat tersebut sehingga mudah<br />
dilakukan penangkapan (Nomura dan Yamazaki, 2003).<br />
Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan ditemukan bahwa<br />
proses penangkapan ikan di laut dilakukan dengan cara penawuran atau<br />
pelemparan jaring sampai pada penarikan tali pukat cincin. Pada waktu nelayan<br />
menarik pukat cincin dengan kedua tangan dalam waktu lama, duduk di lantai<br />
perahu, sikap kerja membungkuk ke depan, tungkai terjulur dan telapak kaki<br />
sebagai bantalan penahan tarikan berisiko memunculkan rasa lelah dan rasa sakit<br />
pada otot skeletal.<br />
Hasil pengamatan membuktikan bahwa selama proses penangkapan ikan<br />
berlangsung sikap kerja yang menyertai nelayan pada waktu penarikan pukat<br />
cincin didominasi oleh aktivitas fisik yang berat sehingga cepat menimbulkan<br />
kelelahan dan keluhan muskuloskeletal bahkan terjadi kecelakaan kerja sampai<br />
jari kelingking tangan kanan putus pada waktu penawuran jaring dan sakit akibat<br />
kerja. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja nelayan dan pada akhirnya<br />
akan menurunkan kesejahteraan kerja nelayan.<br />
Sikap kerja yang tidak fisiologis ini akan cepat menimbulkan kelelahan dan<br />
berbagai gangguan pada sistem otot skeletal serta memerlukan energi yang lebih<br />
besar dalam usaha yang sama seperti pada proses penangkapan ikan sehingga<br />
kelelahan lebih cepat muncul (Manuaba, 1990; Nala, 1990; Adiputra, 1998).<br />
Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan penyakit<br />
akibat kerja (Sutjana, 2003).<br />
Waktu kerja selama proses penangkapan ikan berlangsung 6 jam yaitu dari<br />
pukul 23.00-05.00. Selama penangkapan nelayan dalam posisi duduk lama<br />
3
sambil menarik tali pukat cicin secara berulang-ulang dengan tempo penarikan<br />
lamban karena dilakukan secara manual dengan sikap kerja yang tidak<br />
fisiologis. Kondisi kerja seperti ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan<br />
munculnya berbagai gangguan kumulatif pada otot-otot (Grandjean, 1993;<br />
Manuaba, 2003b).<br />
Penggunaan otot berlebihan terjadi pada saat nelayan menarik tali pukat<br />
cincin yang terkumpul di bagian tengah. Pemanfaatan otot yang cukup besar<br />
terjadi pula ketika mengangkut dan mengangkat hasil tangkapan dari dalam air<br />
dan dimasukkan ke dalam perahu atau ke kotak-kotak penampung ikan yang<br />
sudah disiapkan.<br />
Berdasarkan jawaban nelayan dari kuesioner Nordic Body Map pada<br />
penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di K.M.Tiberias Amurang ditemukan<br />
bahwa nelayan: a) mengeluh rasa sakit pada tangan kanan dan kiri (100%); b)<br />
sakit pada lengan bawah kanan dan kiri (100%); c) sakit pada punggung (80%);<br />
d) sakit pada pinggang (100%); e) sakit pada pantat (80%); f) sakit pada betis<br />
kanan dan kiri (60%); dan g) rasa sakit pada kaki kiri dan kanan (60 %). Artinya<br />
nelayan yang bekerja mengalami keluhan-keluhan otot sebagai akibat stasiun<br />
kerja yang belum ergonomis dan berpotensi terjadinya risiko kecelakaan kerja.<br />
Denyut nadi dihitung sebelum dan sesudah nelayan melakukan pekerjaan<br />
penangkapan ikan dengan menggunakan metode 10 denyut dengan teknik palpasi<br />
pada nadi radialis tangan kiri. Rerata denyut nadi kerja yang diperoleh adalah<br />
126,00 ± 1,87 denyut permenit. Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan pada<br />
saat bekerja menarik pukat cincin berdasarkan hasil perhitungan termasuk<br />
kategori beban kerja sangat berat (125-150dpm). Untuk mengatasi kondisi kerja<br />
4
yang tidak ergonomis ini perlu dilakukan perbaikan dengan merancang alat kerja<br />
guna mengatasi sikap kerja yang tidak alamiah.<br />
Rerata skor kelelahan yang didata dengan 30 items of rating scale dengan<br />
skala Likert adalah: a) skor item 1 – 10, nilainya 43 ± 2,97; b) skor item 11 –<br />
20, nilainya 44 ± 3,29; c) skor item 21 – 30, nilainya 45 ± 1,82; dan total skor<br />
item 1 – 30, nilainya 132 ± 5,94. Ini berarti bahwa nelayan dalam keadaan lelah<br />
sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan kerja menurunkan<br />
kinerjanya. Dalam kondisi kerja yang tidak ergonomis ini kalau dibiarkan dan<br />
tidak ditangani secepatnya, maka akan menimbulkan masalah terhadap<br />
kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kerja (Manuaba, 1998).<br />
Berdasarkan pada aspek-aspek ergonomi bahwa tuntutan tugas dan kondisi<br />
lingkungan organisasi kerja yang belum mengikuti kaidah-kaidah ergonomi pada<br />
perancangan alat kerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan, kelelahan,<br />
peningkatan kecelakaan kerja yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya<br />
penurunan efisiensi dan produktivitas kerja (Manuaba, 2000; Grandjean, 1993;<br />
Pulat, 1992; Sanders dan McCormick, 1987; Suma’mur, 1982).<br />
Dari hasil identifikasi masalah dan data penelitian pendahuluan yang telah<br />
dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa perlu dilakukan<br />
perbaikan melalui intervensi ergonomi dengan pendekatan ergonomi total<br />
(Manuaba, 2004a). Pendekatan ergonomi yang terdiri dari pendekataan SHIP<br />
(Sistemik, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori) dan Teknologi Tepat Guna<br />
(Manuaba, 2005a).<br />
Intervensi ergonomi dilakukan untuk memperbaiki sikap kerja melalui<br />
perancangan alat kerja yang mengacu pada teknologi tepat guna yang dikaji<br />
5
secara komprehensif melalui enam kriteria yaitu: a) secara teknis bahwa sistem<br />
kerja dapat dikerjakan oleh pekerja nelayan; b) secara ekonomis harga<br />
pembuatan katrol dapat dijangkau dengan mudah dan biaya murah; c) secara<br />
ergonomis dapat menciptakan kondisi kerja dan lingkungan kerja sehat, aman<br />
dan nyaman; d) secara sosial budaya sistem kerja dapat diterima oleh pekerja dan<br />
pemilik bahkan masyarakat di sekitar; e) hemat dalam pemakaian energi karena<br />
dapat mengurangi beban kerja nelayan; dan f) penggunaan teknologi tersebut<br />
ramah terhadap lingkungan atau tidak merusak lingkungan karena tidak<br />
menggunakan bahan beracun atau bahan peledak.<br />
Perbaikan organisasi kerja meliputi pemanfaatan tenaga otot secara efisien<br />
dengan cara merancang alat katrol dan tempat duduk, pengaturan suplesi gizi<br />
kerja, pengaturan waktu istirahat, memperhatikan kondisi informasi, kondisi<br />
sosial budaya yang tetap mengikuti kaidah-kaidah ergonomi. Di samping itu<br />
berusaha untuk membudayakan ergonomi di lingkungan masyarakat nelayan,<br />
sehingga diharapkan nelayan berada dalam kondisi lebih sehat, aman, nyaman,<br />
efektif, dan efisien serta tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya.<br />
Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada sistem kerja yang terkait<br />
dengan pekerjaan nelayan sebagai penangkap ikan di Laut. Kinerja yang dinilai<br />
yaitu dari indikator: beban kerja, kelelahan, dan keluhan muskuloskeletal.<br />
Melalui intervensi ergonomi diharapkan terjadi penurunan, sehingga hasil yang<br />
dicapai lebih manusiawi, kompetitif, dan lestari (Manuaba, 2004a; 2004b).<br />
Peningkataan kesejahteraan mengacu pada indikator pengukuran terhadap<br />
pendapatan nelayan melalui analisis keuntungan ekonomi perusahaan yaitu:<br />
Return of Investment (ROI), titik impas atau Break Event point (BEP), biaya dan<br />
6
manfaat atau Benefit Cost Ratio (BCR) dalam proses penangkapan ikan melalui<br />
sistem bagi hasil, sehingga tingkat kepuasan kerja yang dirasakan seseorang<br />
dapat tercapai.<br />
1.2 Perumusan Masalah<br />
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan<br />
masalah penelitian sebagai berikut.<br />
1) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin meningkatkan kinerja nelayan yang dinilai dari penurunan beban<br />
kerja nelayan ?<br />
2) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan kelelahan<br />
nelayan ?<br />
3) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin meningkatkan kinerja yang dinilai dari Penurunan Keluhan<br />
Muskuloskeletal nelayan ?<br />
4) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari kepuasan kerja<br />
nelayan ?<br />
5) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari produktivitas<br />
nelayan ?<br />
6) Apakah intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari keuntungan<br />
nelayan ?<br />
7
1.3 Tujuan Penelitian<br />
1.3.1 Tujuan Umum<br />
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh<br />
intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
terhadap kinerja dengan indikator: beban kerja, kelelahan, keluhan<br />
muskuloskeletal dan kesejahteraan nelayan di Amurang Kabupaten Minahasa<br />
Selatan Provinsi Sulawesi Utara.<br />
1.3.2 Tujuan Khusus<br />
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.<br />
1. Mengetahui besar penurunan beban kerja nelayan setelah melakukan<br />
intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin.<br />
2. Mengetahui besar penurunan kelelahan nelayan setelah melakukan intervensi<br />
ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin.<br />
3. Mengetahui besar penurunan keluhan muskuloskeletal nelayan setelah<br />
melakukan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin.<br />
4. Mengetahui besar peningkatan kesejahteraan nelayan melalui indikator<br />
kepuasan kerja pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin.<br />
5. Mengetahui besar peningkatan kesejahteraan nelayan melalui indikator<br />
produktivitas pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin.<br />
6. Mengetahui besar peningkatan kesejahteraan nelayan melalui indikator<br />
pendapatan ekonomi.<br />
8
1.4 Manfaat Penelitian<br />
1.4.1 Manfaat Akademik<br />
berikut.<br />
Manfaat akademik yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai<br />
1) Dapat digunakan sebagai acuan bagi kaum akademisi dalam menerapkan ilmu<br />
ergonomi-fisiologi kerja di Perguruan Tinggi masing-masing.<br />
2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan<br />
memecahkan masalah-masalah di lapangan yang berkaitan dengan ergonomi<br />
total khususnya kesehatan dan keselamatan kerja.<br />
3) Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merancang alat bantu kerja ergonomi<br />
dengan mudah dan murah didapat serta sangat besar manfaatnya.<br />
4) Dapat dijadikan sarana informasi untuk penelitian dan pengembangan ilmu<br />
ergonomi lebih lanjut.<br />
1.4.2 Manfaat Praktis<br />
berikut.<br />
Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai<br />
1) Dengan mengetahui permasalahan yang diteliti terkait dengan peningkatan<br />
kinerja yaitu beban kerja, kelelahan dan keluhan muskuloskeletal nelayan<br />
dalam proses penangkapan ikan dengan pukat cincin dapat diatasi melalui<br />
penerapan prinsip-prinsip ergonomi.<br />
2) Intervensi ergonomi melalui pedekatan ergonomi total terbukti dapat<br />
memecahkan masalah-masalah pembangunana berkelanjutan secara umum dan<br />
mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kehidupan sosial,<br />
9
ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja untuk peningkatan kesejahteraan<br />
dan kualitas hidup masyarakat quality of life.<br />
3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar acuan untuk menyusun rencana<br />
perbaikan sistem kerja secara bertahap dan berkesinambungan sebagai upaya<br />
untuk menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang layak dalam mensosialisasi<br />
budaya kerja yang sehat, aman, nyaman, efektif, efisien dan produktif.<br />
4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan proyek percontohan atau pilot project bagi<br />
stakeholder, investor, pengusaha dan masyarakat untuk peningkatan kontribusi<br />
pendapatan ekonomi nelayan khususnya di Bidang usaha penangkapan ikan<br />
menggunakan pukat cincin.<br />
10
2.1 Pengertian Ergonomi<br />
BAB II<br />
KAJIAN PUSTAKA<br />
Secara etimologi istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri<br />
dari dua kata, yaitu ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan atau hukum.<br />
Secara morfologi ergonomi adalah aturan, norma atau hukum yang berlaku dalam<br />
suatu pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Jadi secara ringkas ergonomi<br />
adalah aturan atau norma dalam sistem kerja. Di Indonesia menggunakan istilah<br />
ergonomi, tetapi di Beberapa negara seperti di Scandinavia menggunakan istilah<br />
Biotecnology, sedang di Amerika menggunakan istilah human engineering atau<br />
human factors engineering. Namun demikian kesemuanya membahas hal yang<br />
sama yaitu tentang optimalisasi fungsi manusia terhadap aktivitas kerja yang<br />
dilakukan.<br />
Beberapa ahli menampilkan definisi tentang ergonomi dari sudut pandang<br />
yang berbeda, tetapi secara umum definisi-definisi tersebut membicarakan hal<br />
yang sama, yaitu masalah hubungan antara manusia pekerja dengan tugas-tugas<br />
dan pekerjaannya serta desain dari objek yang digunakannya. Pada dasarnya kita<br />
boleh mengambil definisi ergonomi dari sudut pandang mana saja, tetapi perlu<br />
disesuaikan dengan apa yang sedang kita kaji secara mendalam.<br />
Berikut ini dikutip beberapa definisi ergonomi yang berhubungan dengan<br />
penulisan disertasi ini, yaitu :<br />
1. Ergonomi adalah ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi<br />
oleh manusia terkait dengan desain kerja (Phesant, 1988).<br />
11
2. Ergonomi adalah studi tentang kemampuan dan karakteristik manusia<br />
yang memberikan efek terhadap desain peralatan sistem dan pekerjaan<br />
(Corlett and Clark, 1995).<br />
3. Ergonomi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang<br />
karakter, kapasitas, dan keterbatasan manusia dalam merancang tuntutan<br />
tugas (task), sistem mesin, lingkungan, dan ruang gerak sehingga manusia<br />
dapat hidup, bekerja, dan bermain dengan aman, nyaman, dan efisien<br />
(Annis and McConville, 1996).<br />
4. Ergonomi adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berupaya<br />
untuk menyerasikan alat, metode, dan lingkungan kerja terhadap kapasitas,<br />
kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga tercipta kondisi dan<br />
lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien sehingga dapat<br />
dicapai produktivitas yang setinggih-tinggihnya (Manuaba, 1988).<br />
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, apabila dicermati lebih<br />
mendalam, maka ruang lingkup ergonomi sangat luas dan mencakup beberapa<br />
aspek yang dapat diterapkan pada sistuasi dan kondisi apa saja, kapan, dan dimana<br />
saja. Apabila definisi-definisi tersebut disatukan dalam satu persepsi tentang<br />
ergonomi, maka akan diperoleh definisi yang utuh yaitu : Ergonomi adalah<br />
ilmu, teknologi dan seni dalam penerapannya untuk menyerasikan dan<br />
menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas<br />
maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan baik fisik maupun mental<br />
sehingga kualitas hidup manusia secara keseluruhan menjadi lebih baik. Kualitas<br />
12
hidup yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh organisasi buruh internasional<br />
(ILO) secara umum yaitu sebagai berikut (Manuaba, 1994) :<br />
1. Pekerjaan harus mengutamakan aspek kehidupan dan kesehatan pekerja,<br />
2. Pekerjaan harus memberi kesempatan bagi pekerja untuk beristirahat dan<br />
bersantai,<br />
3. Pekerjaan harus memberikan peluang bagi pekerja untuk bersosialisasi dan<br />
memenuhi kebutuhannya melalui pengembangan kapasitas diri.<br />
Dari definisi di atas, maka pencapaian kualitas hidup secara optimal baik di<br />
tempat kerja, dilingkungan sosial masyarakat, maupun dalam lingkungan<br />
keluarga, menjadi tujuan utama dari penerapan ergonomi.<br />
2.2 Tujuan dan Manfaat Ergonomi<br />
Tujuan dan manfaat ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas<br />
kerja manusia untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan, seperti pada uraian<br />
berkut ini, (Manuaba, 2003) :<br />
1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan<br />
cidera dan penyakit akibat kerja serta menurunkan beban kerja fisik dan<br />
mental, serta mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.<br />
2. Mampu memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia serta<br />
meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan<br />
manusia (human error) (Suma’mur, 1992., Wignyosoebroto, 2003).<br />
3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu: teknis,<br />
ekonomis, biologis, dan budaya serta setiap sistem kerja yang dilakukan<br />
13
sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi.<br />
Untuk mencapai tujuan dan manfaat tersebut, maka prinsip ergonomi<br />
fitting the task to the man yaitu setiap pekerjaan harus disesuaikan dengan<br />
kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga hasil yang dicapai meningkat<br />
(Grandjean, 1993). Dan inilah yang menjadi peranan ergonomi adalah untuk<br />
melindungi tenaga kerja dari pengaruh negatif akibat pemakaian peralatan atau<br />
mesin yang tidak serasi dengan gerakan kerja manusia, dalam hal ini peralatan<br />
kerja yang dipakai oleh manusia harus sesuai, supaya tidak terjadi sikap kerja<br />
yang alamiah akibat dari kondisi yang tidak ergonomis sehingga menyebabkan<br />
perusahaan mengalami banyak kerugian produksi yang tidak seimbang dengan<br />
hasil yang diperoleh (Atmosoehardjo, 1994).<br />
Dari sudut pandang ergonomi antara manusia dan peralatan kerja harus<br />
sesuai dan seimbang sehingga tercapai kinerja yang tinggi dan tuntutan pekerjaan<br />
tidak boleh terlalu rendah (underload) dan juga tidak boleh terlalu berlebihan<br />
(overload), karena keduanya akan menurunkan kinerja yang terekspresikan<br />
melalui indikator kualitas kerja seperti : kelelahan, ketidaknyamanan, cidera,<br />
strees kerja, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Seperti pada gambar 2.1<br />
(Manuaba, 2000).<br />
14
Karakteristik<br />
material<br />
Karakteristik<br />
organisasi<br />
Peralatan<br />
kerja/mesin<br />
Karakteristik<br />
stasiun kerja<br />
Karakteristik<br />
lingkungan<br />
Kualitas Kinerj<br />
Kelelahan<br />
Ketidaknyamanan<br />
Cidera<br />
Karakteristik<br />
pribadi<br />
Kapasitas<br />
psikologis<br />
Stress<br />
Kecelakaan<br />
Penyakit<br />
Produktivitas<br />
Manusia<br />
Gambar 2.1 Konsep Keseimbangan dalam Ergonomi<br />
(Sumber : Manuaba, 2000)<br />
Kapasitas<br />
fisiologik<br />
Kapasitas<br />
biomekanik<br />
Penerapan keseimbangan dalam ergonomi secara umum akan mampu<br />
memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas dalam suatu proses<br />
produksi yang bermuara pada peningkatan kinerja yang berlangsung secara sehat,<br />
aman, nyaman, efektif, efisien dan produktif (Manuaba, 1999a, Manuaba,1999b).<br />
Bagi pekerja selain kondisi kerja yang aman dan nyaman juga terpeliharanya<br />
kondisi fisik yang sehat dan bugar dan kelelahan dapat diminimalisasikan.<br />
Dalam perkembangannya, sasaran ergonomi yang ingin dicapai adalah<br />
seluruh tenaga kerja baik pada sektor modern maupun pada sektor tradisional dan<br />
informal. Pada sektor modern penerapan ergonomi dalam bentuk pengaturan<br />
sikap, tata cara kerja dan perencanaan kerja yang tepat adalah efisiensi dan<br />
produktivitas yang tinggi. (Chaffin and Park, 1993). Menyatakan hasil<br />
penelitiannya dalam berbagai macam pekerjaan baik formal maupun nonformal<br />
telah terbukti dapat menyebabkan kenaikan produktivitas kerja mencapai 5 % -<br />
10 % dan tenaga kerja berada dalam kondisi nyaman dalam bekerja, namun yang<br />
15
perlu dikendalikan adalah lingkungan fisik yang mempengaruhi aktivitas kerja<br />
manusia. Kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia masih dipengaruhi<br />
oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor yang datang dari luar<br />
ialah kondisi lingkungan kerja di sekitar tempat kerja seperti : temparatur,<br />
sirkulasi udara, cahaya, kebisingan, dan kelembaban yang kesemuanya<br />
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja manusia dan kondisi pekerjaan<br />
agar senantiasa memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehataan kerja (ILO,<br />
1998).<br />
Dengan terciptanya keadaan fisik dan psikis yang sehat, dan adanya jaminan<br />
sosial, maka produktivitas kerja akan dapat dicapai. Secara khusus ergonomi akan<br />
memberi beberapa manfaat antara lain (Manuaba, 2000b) : a) pemakaian otot dan<br />
energi lebih efisien, b) pemakaian waktu lebih efisien, c) kelelahan berkurang, d)<br />
kecelakaan kerja berkurang, e) penyakit akibat kerja berkurang, f) kenyamanan<br />
dan kepuasan kerja meningkat, g) efisiensi kerja meningkat, h) mutu produk dan<br />
produktivitas kerja meningkat, i) kesalahan kerja berkurang dan kerusakan dapat<br />
diminimalkan, dan j) pengeluaran atau biaya untuk mengatasi akibat kecelakaan<br />
dan penyakit akibat kerja dapat dikurangi dan konsekuensinya biaya operasional<br />
dapat ditekan.<br />
Sutjana, (2000) menyatakan bahwa upaya pencapaian hasil kerja dapat<br />
dilakukan dengan proses efisiensi penggunaan alat, energi yang dikeluarkan dan<br />
beban kerja yang dialami oleh masing-masing pekerja, sehingga kinerja dapat<br />
dihitung dengan rerata jumlah produksi yang dihasilkan selama bekerja dengan<br />
peningkatan denyut nadi diatas nadi istirahat. Aktivitas rancang bangun (design)<br />
16
ataupun rancang ulang (redesign) dimana aspek manusia tidak lagi harus<br />
menyesuaikan dirinya dengan mesin yang dioperasikan (the man fits to the<br />
design), melainkan sebaliknya yaitu mesin dirancang dengan terlebih dahulu<br />
mmperhatikan dimensi tubuh manusia (anthropometri) kelebihan dan keterbatasan<br />
manusia yang mengoperasikannya (the design fits to the man) hal ini meliputi<br />
perangkat keras dan perangkat lunak.<br />
Perangkat keras misalnya perkakas kerja, bangku kerja, kursi dan perangkat<br />
lunak misalnya desain pekerjaan dalam suatu organisasi seperti penentuan jumlah<br />
jam istirahat, pembagian waktu kerja dan variasi pekerjaan. Sedangkan dalam<br />
dunia kerja tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, melainkan mencakup<br />
bidang-bidang yang sangat luas, antara lain : a) dalam perancangan alat kerja, b)<br />
evaluasi proses dan produk kerja, c) perancangan bangunan/arsitektur, dan d)<br />
dipergunakan oleh ahli anatomi, fisika, fisioterapi, psikologi dan kaum profesional<br />
lainnya.<br />
Hasil penelitian ( Chavalitsakulchai and Shanavaz, 1991) melaporkan<br />
bahwa hampir seluruh tenaga kerja yang bekerja dengan sikap kerja yang tidak<br />
fisiologis atau alamiah mengalami gangguan otot skeletal dan kelelahan otot<br />
berlebihan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Adiputra, et.al., 2001) bahwa<br />
perkembangan industri yang cukup pesat yang tidak diikuti oleh perhatian<br />
terhadap lingkungan kerja dan peralatan kerja dipastikan akan menimbulkan<br />
gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal merupakan fenomena<br />
fisiologis yang secara objektif dapat didata dengan kuesioner Nordic Body Map<br />
17
(NBM) yaitu suatu kuesioner berbentuk gambar tubuh manusia berdasarkan 28<br />
item pertanyaan kelelahan sistem otot dalam tubuh.<br />
Dengan ergonomi, dampak negatif dapat ditekan, karena berbagai penyakit<br />
akibat kerja, kecelakaan, pencemaran, keracunan, ketidak puasan kerja, kesalahan<br />
unsur manusia bisa dihindari. Dengan kata lain untuk mendapatkan hasil kerja<br />
yang optimal dengan produktivitas yang tinggi maka setiap aktivitas kerja harus<br />
berpedoman pada kaidah ergonomi.<br />
Penerapan ergonomi dalam suatu sistem kerja dapat menghindari keluhan<br />
muskuloskeletal yang bersifat sementara maupun menetap dapat<br />
diminimalisasikan, beban kerja dan kelelahan sebagai suatu keadaan yang<br />
tercermin dari gejala perubahan psikologis akibat aktivitas kerja yang berlebihan<br />
yang dalam jangka panjang terjadi tumpang tindih dan mengakibatkan inefisiensi<br />
atau ketidak mampuan fisik pekerja, sesuai tingkatan pekerjaan baik ringan<br />
sampai yang berat, baik dengan tenaga manual maupun mesin, hal ini terjadi<br />
karena perbaikan kondisi kerja bersifat sektoral dan belum dilakukan sinergitas<br />
antara sektor yang satu dengan sektor yang lain dalam satu kesatuan sistem. Atas<br />
dasar kesadaran akan kegagalan tersebut, maka pada era globalisasi yang sedang<br />
bergulir ini, mulailah dikembangkan dengan apa yang dinamakan dengan konsep<br />
pendekatan ergonomi total.<br />
2.3 Pendekatan Ergonomi Total<br />
Pendekatan ergonomi total adalah penerapan prinsip ergonomi melalui<br />
pendekatan Systemic, Holistic, Interdisiplinary & Participatory (SHIP Approach)<br />
yang dipadukan dengan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (Manuaba,<br />
18
2003e; 2005a; 2006). Pendekatan ergonomi total adalah suatu pendekatan<br />
konseptual yang muncul dalam usaha pemecahan berbagai permasalahan yang<br />
timbul berkaitan dengan kerja atau aktivitas yang dilakukan manusia kapan dan<br />
dimana saja. Pendekatan ergonomi total muncul sebagai reaksi dari dampak<br />
pembangunan yang terjadi di tiga sektor di Propinsi Bali yaitu pariwisata,<br />
pertanian, dan industri kecil. Sebagai dampak dari pembangunan tersebut, maka<br />
muncul berbagai keluhan rasa sakit pada saat melakukan pekerjaan, keracunan,<br />
kecelakaan kerja, polusi udara, air, tanah, kerusakan lingkungan, adanya rasa tidak<br />
aman, nyaman masyarakat akibat proyek, penyakit akibat kerja. Upaya untuk<br />
mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan pendekatan komprehensif yang<br />
lebih menekankan pada kajian dari berbagai disiplin ilmu dan melibatkan berbagai<br />
unsur terkait yang dalam pelaksanaannya membentuk satu kerja tim (team work)<br />
melalui sistem yang demokratis, mengedepankan kolaborasi potensi, membangun<br />
keterbukaan, kejujuran serta berpandangan jauh kedepan (Manuaba, 2003b).<br />
Pendekatan SHIP yang dimanfaatkan secara intensif oleh Bali oleh Bali-<br />
Human Ecology Study Group (Bali-HESG) yang memberikan kontribusi positif<br />
bagi pembangunan di Bali, sehingga makin banyak institusi pemerintah maupun<br />
swasta meminta untuk melaksanakan lokakarya berkaitan dengan pembangunan<br />
yang berkelanjutan. Pendekatan SHIP yang diawali dengan pendekatan :<br />
1) Sistemik<br />
Pendekatan sistemik diartikan bahwa kondisi kesehatan, kenyamanan dan<br />
keselamatan kerja yang dilihat dari aspek beban kerja, kelelahan dan<br />
gangguan muskuloskeletal serta produktivitas pekerja dalam melaksanakan<br />
19
aktivitas kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dipandang<br />
sebagai suatu sistem yang terkait satu dengan yang lain.<br />
Melalui pendekatan sistem dimana semua faktor yang berada di dalam satu<br />
sistem dan diperkirakan dapat menimbulkan masalah harus ikut<br />
diperhitungkan sehingga tidak ada lagi masalah yang tertinggal atau<br />
munculnya masalah baru sebagai akibat dari keterkaitan sistem.<br />
2) Holistik<br />
Pendekatan holistik diartikan bahwa semua sistem yang terkait harus<br />
diperhitungkan. Subsistem yang terkait dengan masalah yang ada haruslah<br />
dipecahkan secara proaktif, profesional, dan menyeluruh. Secara holistik<br />
bahwa pemecahan masalah lebih menekankan pada faktor yang terkait<br />
dengan masalah kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kerja.<br />
3) Interdisipliner<br />
Pendekatan interdisipliner diartikan semua disiplin ilmu yang terkait<br />
haruslah dimanfaatkan secara maksimal, karena makin tinggi kompleksitas<br />
masalah, maka makin dibutuhkan lintas disiplin ilmu yang terkait untuk<br />
dipecahkan. Karena masalah tidak akan terpecahkan secara maksimal, jika<br />
hanya satu disiplin ilmu saja yang ada di dalamnya.<br />
4) Partisipatori<br />
Pendekatan partisipatori adalah semua yang terlibat dalam pemecahan<br />
masalah tersebut harus dilibatkan seperti : Stakeholder, pimpinan<br />
perusahaan, karyawan, peneliti sejak awal dilibatkan agar dapat di<br />
20
wujudnyatakan suatu mekanisme kerja yang kondusif dan diperoleh produk<br />
yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.<br />
Pendekatan SHIP memfokuskan pada semua masalah yang ada dalam<br />
sistem kerja harus dipecahkan melalui pendekatan sistem, dikaji secara holistik<br />
dan memanfaatkan lintas disiplin ilmu dengan maksud agar semua komponen<br />
dalam suatu sistem dapat terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,<br />
monitoring sampai pada tahap evaluasi agar supaya mereka semua mengetahui<br />
suatu keberhasilan dan kegagalan dan secara bersama-sama mencari solusi<br />
pemecahannya. Dan sistem kerja akan memberikan hasil yang lebih baik, jika<br />
setiap pemecahan masalah dimanfaatkan secara baik sehingga tidak ada lagi<br />
masalah yang tertinggal atau muncul masalah baru dikemudian hari (Manuaba,<br />
2004c).<br />
Apabila dalam pelaksanaan perbaikan diperlukan teknologi, maka harus<br />
didahului dengan analisis teknologi tepat guna (TTG) yang dapat diterapkan<br />
dalam setiap perbaikan ergonomi (Manuaba, 2003,2004, 2005a) meliputi kajian<br />
dari aspek : a) teknis, b) ekonomi, c) ergonomi, d) sosial-budaya, e) hemat enerji,<br />
dan f) ramah lingkungan. Dalam setiap aktivitas kerja untuk dapat bersaing, maka<br />
dengan menggunakan pendekatan ergonomi total harus mampu mengubah tempat<br />
kerja, tenaga kerja, pasar kerja dan manajemen kerja lebih efektif dan efisien<br />
sehingga mendapatkan hasil yang positif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan<br />
ergonomi total yang diawali dengan mengindentifikasi 8 aspek masalah<br />
(Manuaba, 2006) yang terdiri dari :<br />
1) Nutrisi.<br />
21
Status kesehatan dan nutrisi atau keadaan gizi berhubungan erat dan<br />
berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas kerja. Agar nutrisi dapat<br />
diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh, maka diperlukan tubuh yang<br />
sehat. Keadaan gizi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara<br />
energi yang masuk dan keluar. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, maka<br />
perlu pengaturan komposisi dan pola makan yang disesuaikan dengan<br />
karakteristik dan beban kerja.<br />
Untuk pekerjaan fisik seperti pemasangan dinding batu yang<br />
dilakukan di tempat panas, maka kebutuhan karbohidrat dan mineral lebih<br />
dominan (Grandjean, 1993; Dekker, dkk., 1996). Pemberian tambahan<br />
nutrisi pada saat istirahat sangat dianjurkan untuk mengembalikan kalori<br />
dan memulihkan tenaga yang terpakai.<br />
2) Penggunaan Tenaga Otot<br />
Proses kerja secara manual lebih memerlukan penggunaan tenaga otot.<br />
Kekuatan otot ditentukan oleh sifat dari sel otot itu sendiri. Kontraksi otot<br />
memerlukan energi dan menghasilkan zat sisa metabolisme (Cummings,<br />
2003). Ketersediaan energi tergantung pada ketersediaan oksigen dan zat<br />
makanan yang dihantarkan oleh sirkulasi intramuskular. Kontraksi kontinyu<br />
dan monoton akan menyebabkan oklusi intramuskular sehingga mengurangi<br />
produksi ATP menjadi dua mol dan terbentuk asam laktat akibat<br />
metabolisme dan anaerobik (Grandjean & Kroemer, 2000). Penurunan<br />
energi dan akumulasi asam laktat akan mempercepat timbulnya kelelahan<br />
dan keluhan otot yang apabila terakumulasi akan menimbulkan nyeri otot<br />
22
(Guyton & Hall, 2000). Oleh karena itu di dalam merancang kondisi kerja,<br />
perlu diperhatikan batas-batas kemampuan baik gerakan maupun kekuatan<br />
otot. Untuk setiap metode dan peralatan kerja harus dirancang sedemikian<br />
rupa sehingga gerakan otot tidak bertentangan dengan gerakan fisiologis<br />
atau gerakan alamiah dari otot bersangkutan.<br />
3) Sikap Kerja<br />
Sikap kerja hendaknya diupayakan dalam posisi alamiah sehingga<br />
tidak menimbulkan sikap paksa yang melampaui kemampuan fisiologis<br />
tubuh (Grandjean dan Kroemer, 2000; Manuaba, 1998). Sikap kerja paksa<br />
bisa terjadi pada saat memegang, mengangkat dan mengangkut, duduk atau<br />
berdiri terlalu lama dan lain sebagainya (Adnyana, 2001; Chung, dkk.,<br />
2003; Dempsey, 2003; Ferreira, 2005; Ferguson, dkk., 2005). Sikap tidak<br />
alamiah ini terjadi karena interaksi antara pekerja dan alat kerja yang kurang<br />
berimbang atau alat kerja yang digunakan kurang sesuai dengan<br />
antropometri pekerja.<br />
4) Lingkungan Kerja<br />
Kondisi lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja<br />
seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung (Rodahl, 1989;<br />
Manuaba, 2000). Kondisi mikroklimat, kebisingan, getaran, dan kualitas<br />
udara yang melebihi nilai ambang batas atau standar yang telah<br />
direkomendasikan, dapat memperlemah fungsi tubuh, menurunkan kinerja<br />
dan pada akhirnya menurunkan produktivitas kerja. Dalam proses<br />
pemasangan dinding bata yang lebih banyak dilakukan di tempat terbuka,<br />
23
kondisi lingkungan yang perlu dicermati adalah paparan panas matahari,<br />
kebisingan, dan kadar debu yang tinggi.<br />
5) Waktu Kerja<br />
Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa waktu kerja optimal<br />
adalah 7 jam perhari atau 40 jam perminggu untuk enam hari kerja<br />
(Spurgeon, 2003). Dalam beberapa kasus, perpanjangan waktu kerja justru<br />
menurunkan hasil kerja dan mempunyai kecenderungan untuk timbulnya<br />
kelelahan, gangguan/penyakit dan kecelakaan. Waktu kerja maksimal di<br />
mana seseorang dapat bekerja dengan baik dengan kondisi lingkungan kerja<br />
yang normal adalah 8 jam per hari termasuk jam istirahat (Suma’mur, 1982;<br />
Grandjean, 1993; Decker dkk, 1996). Tentu saja untuk kondisi lingkungan<br />
yang tidak memenuhi standar/nilai yang disyaratkan, perlu dilakukan<br />
penyesuaian sehingga pekerja tidak terpapar oleh kondisi ekstrim dalam<br />
waktu yang lama.<br />
6) Sistem Informasi.<br />
Informasi bagi karyawan merupakan suatu hal yang penting dalam<br />
proses produksi. Penyampaian rincian tugas untuk masing-masing karyawan<br />
secara jelas dan terperinci dapat menekan timbulnya kesalahan. Dalam<br />
penyampaian informasi, ada beberapa sistem yang dapat digunakan, antara<br />
lain dengan komunikasi lisan, informasi tertulis baik yang disampaikan<br />
langsung kepada karyawan atau dipasang di papan pengumuman dan dapat<br />
pula berupa slogan-slogan kerja yang dipasang di tempat-tempat strategis<br />
24
yang dapat dilihat oleh karyawan setiap saat. (Grandjean & Kroemer, 2003;<br />
Manuaba, 1999).<br />
7) Kondisi Sosial Budaya<br />
Rasa nyaman di tempat kerja dipengaruhi pula oleh kondisi sosial<br />
budaya di lingkungan kerja, lingkungan keluarga maupun lingkungan<br />
masyarakat (Nala, 2002). Pekerja akan merasa nyaman bila keadaan<br />
keluarga, hubungan antar keluarga, antar pekerja dan antara atasan dan<br />
bawahan berlangsung harmonis. Harmonisasi lingkungan kerja akan<br />
menyebabkan pekerja akan lebih berkonsentrasi pada tugasnya masing-<br />
masing sehingga efisiensi tercapai dan akhirnya pencapaian produktivitas<br />
bisa optimal.<br />
8) Interaksi Manusia – mesin<br />
Budaya kerja yang ada hingga saat ini lebih mengkondisikan pekerja<br />
sebagai bagian dari mesin, sehingga manusialah yang diharapkan mampu<br />
menyesuaikan diri dengan cara kerja mesin. Hal ini sangat bertentangan<br />
dengan prinsip dasar ergonomi. Dalam konsep ergonomi, maka prioritas<br />
utama adalah menyesuaikan desain dan system kerja mesin dengan<br />
kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan manusia (Fitting the job to the<br />
man) (Grandjean & Kroemr, 2000; Manuaba, 2005b). Oleh karena itu<br />
setiap interaksi alat dengan mesin harus dirancang sedemikian rupa<br />
sehingga terjadi keharmonisan antara daya kerja mesin dengan<br />
kemampuan, kebolehan dan keterbatasan pekerja. Desain alat dan<br />
perlengkapan kerja hendaknya benar-benar disesuaikan dengan ukuran<br />
25
tubuh pekerja sehingga pekerja dapat melakukan tugasnya dengan sikap<br />
yang alamiah.<br />
2.4 Penerapan Ergonomi Total Pada Proses Penangkapan Ikan<br />
Penerapan konsep ergonomi total pada proses penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin yang pertama di Indonesia ini, pada dasarnya berdasarkan pada 8<br />
aspek ergonomi, dan 6 kriteria dari teknologi tepat guna yang dimulai dari :<br />
1. Gizi dan Nutrisi<br />
Gizi dan nutrisi sangat mempengaruhi kondisi kerja nelayan pada waktu<br />
penangkapan ikan di Malam hari. Untuk menjaga keseimbangan antara energi<br />
yang masuk dan keluar. Energi yang masuk selalu terdapat zat dan mineral yang<br />
diperlukan untuk mempertahankan fungsi sel tubuh melalui pengaturan pola<br />
makan dan minum serta istirahat, dan energi yang keluar akibat adanya aktivitas<br />
kerja menangkap ikan.<br />
Berkaitan dengan gizi dan nutrisi yang adi kuat sebagai sumber energi,<br />
maka pola pengaturan makan, minum dan istirahat berlangsung sebagai berikut :<br />
1) snack dan minum pagi, pukul 07.00-08.00, 2) istirahat, pukul 09.00-13.00, 3)<br />
makan siang, pukul 13.00-14.00, 4) istirahat, pukul 14.00-18.00, 5) makan<br />
malam, pukul 18.00-19.00. Aktivitas penangkapan ikan mulai persiapan sampai<br />
pelaksanaan berlangsung dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 06.00 pagi dan<br />
untuk rehat disediakan teh manis dan air putih. Kondisi kerja seperti ini terasa<br />
cukup dan berlangsung selama melakukan aktivitas penangkapan ikan.<br />
26
2) Penggunaan Tenaga Otot.<br />
Dalam proses penangkapann ikan dengan pukat cincin, maka penggunaan<br />
tenaga otot sangat berlebihan pada saat penawuran jaring sampai pada penarikan<br />
pukat cincin. Penurunan energi dan akumulasi asam laktat akan mempercepat<br />
timbulnya kelelahan fisik dan keluhan otot apabila terakumulasi, maka akan<br />
menimbulkan nyeri otot. Untuk itu, setiap metode dan peralatan kerja harus<br />
dirancang dengan berpedoman pada kaidah ergonomi sehingga gerakan otot tidak<br />
bertentantangan dengan gerakan fisiologis atau gerakan alamiah dari otot<br />
tersebut.<br />
3) Sikap Kerja.<br />
Sikap kerja nelayan pada waktu menarik pukat cincin, nampak jelas<br />
dilakukan nelayan dengan kedua tangan dalam waktu lama, badan membungkuk<br />
kedepan, dan kedua kaki terjulur menahan beban tarikan sehingga menimbulkan<br />
sikap kerja paksa. Sikap kerja seperti ini kurang nyaman, beban kerja sangat berat<br />
dan sering ada keluhan muskuloskeletal, apabila hal ini dilakukan berulang-<br />
ulang, maka akan menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk<br />
menghindari sikap kerja paksa ini, maka perlu dirancang alat bantu kerja berupa<br />
katrol untuk menarik pukat cincin dengan cepat dan mengurangi beban kerja,<br />
kelelahan dan keluhan muskuloskeletal sehingga kecelakaan dan penyakit akibat<br />
kerja dapat diminimalisasikan.<br />
4) Kondisi Lingkungan.<br />
Kondisi lingkungan iklim mikro seperti kecepatan angin, suhu udara dan<br />
kelembaban sangat mempengaruhi kondisi lingkungan tempat bekerja. Di<br />
27
Perairan laut daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan dalam<br />
melakukan aktivitas sangat sangat membutuhkan cuaca yang tenang dan<br />
pengaturan tata letak perahu lampu agar tidak menyilaukan nelayan pada waktu<br />
penarikan pukat cincin.<br />
5) Kondisi Waktu<br />
Nelayan dalam tugas kerja menangkap ikan di laut pada malam hari<br />
memerlukan aktivitas fisik yang lebih berat karena banyak mengeluarkan energi.<br />
Untuk itu, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat menjadi prioritas utama<br />
dan bilamana terjadi perbaikan dengan adanya intervensi ergonomi dengan pola<br />
kebiasaan lama, hendaknya itu sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi sehingga<br />
aspek kesehatan, kenyamanan dan keselamatan kerja menjadi prioritas utama<br />
sehingga kesejahteraan nelayan meningkat.<br />
6) Kondisi Informasi dan Komunikasi<br />
Kondisi informasi dalam proses penangkapan ikan di laut sangat<br />
menentukan, sebab pemberian informasi dari pimpinan (tonaas) kepada nelayan<br />
harus jelas dan terperinci baik tertulis maupun secara lisan, agar supaya masing-<br />
masing nelayan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diberikan seperti : 1)<br />
siapa yang bertugas menarik tali pelampung, 2) yang bertugas menarik isi perut<br />
jaring, 3) yang bertugas menarik tali cincin, dan 4) yang bertugas penawuran<br />
jaring. Peranan komunikasi sangat menentukan terhadap peningkatan produksi<br />
penangkapan serta dapat menekan timbulnaya kesalahan pada waktu aktivitas<br />
penangkapan berlangsung.<br />
28
Menciptakan komunikasi dua arah yang harmonis antara nelayan pemilik<br />
dan nelayan penangkap sangat didambahkan terutama dalam sistim bagi hasil dari<br />
usaha penangkapan ikan. Komunikasi yang terjalin penuh kemesraan, akan<br />
memberikan motivasi dan semangat etos kerja yang tinggi serta membangkitkan<br />
rasa percaya diri dan rasa memiliki terhadap keberlangsungan usaha, sebab<br />
nelayan penangkap ikan bukan salah satu faktor produksi perusahaan, tetapi<br />
sebagai bagian dari investasi perusahaan dalam meningkatkan produksi hasil<br />
penangkapan.<br />
7) Kondisi Sosial Budaya<br />
Kondisi sosial budaya bagi masyarakat nelayan, baik nelayan pemilik<br />
maupun nelayan penangkap bagaikan bapak-pengikut (patron-client). (Scott,<br />
1988) menyatakan bahwa pada satu pihak seorang individu nelayan pemilik<br />
dengan status sosial yang lebih tinggi disebut (patron), menggunakan<br />
pengaruhnya dengan sumber-sumber yang dimiliki untuk memberikan<br />
perlindungan bagi seorang yang status ekonominya lebih rendah yaitu nelayan<br />
penangkap (client), dan sebaliknya client membalas dengan memberikan<br />
dukungan dan bantuan pelayanan termasuk motivasi dan etos kerja yang tinggi.<br />
Hubungan sosial budaya yang terbentuk pada masyarakat nelayan terjadi<br />
pada saat pembagian hasil tangkapan atau yang biasa disebut sistim bagi hasil.<br />
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi sistim bagi hasil yang disepakati<br />
bersama, maka akan menimbulkan konflik internal antara nelayan pemilik dan<br />
nelayan penangkap dan mengakibatkan nelayan tidak melaut, sehingga tidak<br />
terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.<br />
29
8) Interaksi Manusia – Mesin<br />
Interaksi manusia mesin (man-machine interface) dapat berfungsi lebih<br />
efektif dan efisien, apabila manusia dan mesin terpadu dan disiplin dalam<br />
melakukan fungsi produksi. Manusia yang menggunakan peralatan kerja mampu<br />
beradaptasi, berinteraksi dengan mesin atau alat yang dirancang secara ergonomi<br />
dan hasil rancangan kerja harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan<br />
dengan kemampuan dan keterbatasan manusia (Manuaba, 2004, 2005a, 2005b).<br />
Interaksi manusia mesin pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin dilakukan secara serasi untuk menjamin bahwa proses kerja dapat<br />
mencapai hasil yang optimal. Dengan intervensi ergonomi yang diterapkan di<br />
lingkungan kerja nelayan adalah merupakan aktivitas rancang bangun yang<br />
disesuaikan dengan kemajuan teknologi, maka diperlukan pemahaman tentang<br />
antropometri melalaui data ukuran tubuh setiap nelayan dan dalam penerapannya<br />
selalu menghendaki adanya perbaikan pada setiap lingkungan kerja secara<br />
terpadu dan integrasi, sehingga dapat membangun suatu kondisi kerja yang<br />
kondusif, sehat, aman, nyaman, efektif, efisien dan produktif.<br />
Dalam penerapan konsep ergonomi total pada penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin, memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari : a) indentifikasi<br />
masalah, b) penentuan prioritas terhadap masalah-masalah yang diindentifikasi<br />
termasuk kekuatan dan kelemahannya dengan menggunakan (SWOT analysis), c)<br />
disusun suatu rencana kerja aksi (action plan) yang bersumber pada teknologi<br />
tepat guna (TTG) dengan 6 kriteria utama (Adiputra, 2000 dan Manuaba, 2005a)<br />
yaitu :<br />
30
1) Secara teknik, pembuatan alat kerja katrol oleh nelayan sangat mudah<br />
dikerjakan dan tidak sulit dirawat, menggunakan bahan dan material sangat<br />
sederhana, aman, kuat dan memiliki daya tahan lama serta kualitas hasil lebih<br />
baik dan sangat praktis untuk dioperasikan.<br />
2) Secara ekonomi, lebih efisien dan harganya murah dan mudah untuk didapati<br />
serta dapat dijangkau oleh nelayan, sehingga memberikan keuntungan bagi<br />
setiap keluarga nelayan dan tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja<br />
(PHK) bagi nelayan, tetapi sebaliknya menciptakan lapangan kerja baru dan<br />
memberikan kesempatan kerja bagi generasi muda yang putus kuliah.<br />
3) Secara ergonomi, alat tersebut tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan<br />
penyakit akibat kerja, tetapi sebaliknya menciptakan kondisi kerja yang sehat,<br />
aman, nyaman, efektif, efisien dan produktif.<br />
4) Hemat energi, alat kerja katrol yang dalam penggunaannya pada aktivitas<br />
penangkapan ikan dengan pukat cincin dapat menghemat dan mengurangi<br />
energi.<br />
5) Sosial budaya, alat kerja katrol dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat<br />
nelayan baik nelayan pemilik maupun nelayan penangkap dengan mengikuti<br />
tatanan, aturan, norma serta tradisi budaya masyarakat setempat baik tertulis<br />
maupun lisan, sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat yang tradisional<br />
menjadi masyarakat modern (Nala, 2002).<br />
6) Ramah lingkungan, alat kerja katrol tidak merusak lingkungan, tetapi<br />
menciptakan keseimbangan ekosistem antara keragaman dan keseragaman<br />
biota laut, bahkan ikan-ikan yang tertangkap sejenis pelagis pilihan berukuran<br />
31
esar sesuai dengan mata jaring pukat cincin.<br />
2.5 Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai<br />
Kehidupan masyarakat nelayan yang mendiami daerah pesisir pantai<br />
dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan penangkap ikan yang hidupnya<br />
tergantung langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan<br />
ataupun budi daya ikan. Dan dalam kelangsungan hidupnya sangat tergantung<br />
pada cuaca alam, apabila situasi alam terganggu laut bergelombang dan disertai<br />
angin kencang, maka nelayan tidak melaut, sehingga mengakibatkan tidak<br />
terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga nelayan.<br />
Dalam banyak hal masyarakat nelayan di Pesisir pantai mereka telah<br />
membentuk sebuah lingkungan permukiman sendiri dan memiliki sosio-budaya<br />
yang khas yaitu berburu dan menangkap ikan (hunting and fishing) dan memiliki<br />
daerah jelajah yang berpindah-pindah tempat sebagai proses adaptasi terhadap<br />
habitat yang dekat pantai dan sekaligus telah menyatu dengan laut, dalam<br />
kehidupannya mereka membentuk tradisi yang diwariskan secara turun-temurun<br />
dari generasi ke generasi.<br />
Proses adaptasi di kalangan masyarakat nelayan mereka memiliki ciri-<br />
ciri utama yaitu : a) kedua pihak menguasai sumber daya yang tidak<br />
seimbang, b) saling menguntungkan dan tidak ada unsur paksaan di antara<br />
kedua belah pihak, c) adanya hubungan mesra di antara kedua belah pihak<br />
(Imron, 2003).<br />
32
Dilihat dari kesejahteraan hidupnya nelayan di pesisir pantai tergolong<br />
masyarakat yang mempunyai pandapatan rendah bila dibandingkan dengan<br />
pendapatan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena alat tangkap yang<br />
digunakan nelayan bersifat tradisional, mulai dari armada penangkapan perahu,<br />
alat tangkap, dan teknik menangkap ikan sampai tingkat pengetahuan dan<br />
keterampilan yang dimiliki masih rendah.<br />
Proses penangkapan ikan terjadi apabila adanya kesempatan melaut, musim<br />
ikan, dan keadaan laut angin yang tenang bertiup tidak merubah arah, arus yang<br />
teduh. Hasil tangkapan sangat tergantung pada faktor-faktor produksi seperti : a)<br />
adanya rumpon, b) biaya tetap sebagai modal investasi, c) biaya bahan-bahan<br />
seperti biaya perawatan, d) bahan bakar dan konsumsi nelayan selama di laut<br />
serta, e) jenis alat tangkap yang digunakan.<br />
Dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di lokasi penangkapan<br />
ikan laut Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara didapati<br />
bahwa nelayan pada waktu proses penangkapan berlangsung mereka masih<br />
menggunakan sistem kerja lama menarik pukat cincin dengan kedua tangan<br />
dalam waktu lama dan fasilitas kerja yang ada masih tergolong tradisional.<br />
Sistem bagi hasil dikalangan masyarakat nelayan antara nelayan pemilik<br />
dan nelayan penangkap (buruh) masih mengikuti pola kelembagaan tradisi<br />
masyarakat pantai dengan kebiasaan sebagian besar masih menggunakan hukum<br />
adat tidak tertulis (konvensi), dimana hukum yang hidup sebagai peraturan<br />
kebiasaan yang dipertahankan dari masa ke masa.<br />
33
Dilihat dari segi individu nelayan dalam keberadaannya tidak dapat<br />
mempengaruhi harga ikan di pasar, sedangkan target produksi penangkapan harus<br />
mencapai 8000 kg perbulan. Dan untuk mencapai target penangkapan ini, maka<br />
disinilah terjadi gangguan kesehatan dan keselamatan kerja nelayan sehingga<br />
mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.<br />
2.6 Peralatan Tangkap Pukat Cincin<br />
Pukat cincin atau purse seine yang oleh masyarakat nelayan di Sulawesi<br />
Utara lebih dikenal dengan nama soma pajeko adalah termasuk salah satu jenis<br />
jaring lingkar yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan-ikan sejenis<br />
pelagis yang membentuk gerombolan dengan kepadatan yang tinggi dimana<br />
jaring ditebarkan mengelilingi kelompok ikan sehingga akan menjadi dinding<br />
penghalang yang berfungsi untuk mencegah agar ikan yang tertangkap tidak<br />
keluar (Kanagaya, 2005).<br />
Jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya, maka alat tangkap pukat<br />
cincin ini dapat menangkap ikan hingga kedalaman 150 meter atau lebih<br />
tergantung ukuran dan konstruksi jaring. Pukat cincin terdiri dari beberapa bagian<br />
antara lain : bagian kantong, perut, bahu dan sayap (Nomura dan Yamazaki,<br />
2003). Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2<br />
34
Keterangan dan Ukurannya :<br />
Kantong = 45 m 1. Tali pelampung = 310 m 6. Timah pemberat = 0,55 kg<br />
Perut = 30 m 2. Tali ris atas = 310 m 7. Tali ikatan cincin = 30<br />
cm<br />
Bahu = 20 m 3. Pelampung = 310 m 8. Tali cincin = 290 m<br />
Sayap = 10 m 4. Tali ris bawah = 310 m 9. Cincin timah = 0.10 kg<br />
5. Tali pemberat = 310 m<br />
Gambar 2.2 Model Pukat Cincin<br />
35
Dari hasil survei pada masing-masing bagian di atas, dapatlah dijelaskan<br />
bahwa: a) bagian kantong adalah tempat mengumpulkan ikan dari hasil<br />
tangkapan. Dalam proses penangkapan maka bagian kantong akan menjadi huruf<br />
“U” setelah penarikan tali cincin, b) perut jaring berfungsi mempercepat tarikan<br />
tali pukat cincin, c) bahu jaring adalah tempat menahan beban cincin, d) sayap<br />
jaring adalah tempat memagari dan mengurung ikan untuk tidak keluar dari<br />
tangkapan.<br />
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan fungsi dari<br />
masing-masing bagian pukat cincin yaitu: 1) tali pelampung berfungsi sebagai<br />
pengikat pelampung, 2) tali ris atas berfungsi untuk menggantungkan jaring yang<br />
berpasangan dengan tali pelampung, 3) pelampung adalah tempat menahan jaring<br />
dan timah pemberat gaya apung yang berbentuk bola terbuat dari plastik di<br />
pasang pada bagian kantong dan bagian ujung tali tarik, 4) tali ris bawah berfungsi<br />
sebagai penahan jaring bagian bawah yang berpasangan dengan tali pemberat<br />
yang digunakan sebagai penghubung cincin dengan jaring, 5) tali pemberat<br />
berfungsi untuk mengikat pemberat timah yang bersama-sama dengan tali ris<br />
bawah dirangkai pada jaring bagian bawah, 6) timah adalah pemberat yang<br />
digunakan dari bahan timah hitam (Pb) berbentuk lonjong dengan berat di udara<br />
200 gr, 7) tali ikatan cincin dirangkai bersama dengan jaring bagian bawah<br />
berfungsi sebagai tempat menahan pemberat, 8) tali cincin dipasang pada cincin<br />
dan berfungsi untuk menarik agar cincin berkumpul sehingga jaring membentuk<br />
kantong, dan 9) cincin yang digunakan pada pukat adalah menggunakan bahan<br />
kuningan (Br) dengan masa jenis 7,82 kg/m3 berbentuk bulat dengan ukuran dan<br />
jumlahnya sesuai kebutuhan.<br />
36
Berdasarkan uraian di atas, maka konstruksi pembuatan pukat cincin yang<br />
terdiri dari dari beberapa bagian yaitu : jaring, tali-temali, pelampung, pemberat<br />
(timah), dan cincin yang di pasang pada bagian bawah dan pada sisi jaring. Maka<br />
pukat cincin dapat memberikan hasil yang sangat besar pada proses penangkapan<br />
ikan, karena panjang pukat cincin sesuai dengan panjang tali pelampung dan<br />
lebar pukat cincin sesuai dengan kedalaman jaring yang terentang sempurna<br />
didalam air dan penawuran jaring harus dilakukan dengan cepat sesuai dengan<br />
kecakapan dan keahlian pemimpin tonaas (Katiandagho, 2006).<br />
Operasi penangkapan ikan dengan pukat cincin dilakukan pada malam hari,<br />
dengan menggunakan alat bantu rumpon (rakit) dan perahu lampu. Perahu lampu<br />
seperti tipe perahu pelang yang digunakan untuk meletakkan lampu laguna yang<br />
menyerupai lampu petromax berfungsi untuk memikat ikan supaya berkumpul<br />
dalam satu area penangkapan. Tipe perahu dapat diuraikan berikut ini.<br />
2.6.1 Perahu dan Lampu Laguna<br />
Hasil penelitian peandahuluan membuktikan bahwa proses penangkapan<br />
ikan dengan pukat cincin dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat<br />
bantu perahu dan lampu laguna yaitu : Perahu lampu tipe pelang ini mempunyai<br />
ukuran panjang (L) 8 m, Lebar (B) 1 m, di samping kiri dan kanan terdapat<br />
sema-sema dari bambu, sedangkan di depan dan belakang perahu terlihat 2 balok<br />
melintang yang terbuat dari batang kelapa sebagai tempat meletakkan lampu<br />
laguna dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan perahu agar tidak goyah dan<br />
tengelam bila diterpa gelombang laut.<br />
37
Bentuk perahu type pelang Panjang 8 meter Lebar 0,8 meter yang<br />
digunakan untuk meletakkan lampu laguna seperti tampak pada Gambar 2.3<br />
Gambar 2.3 Perahu lampu tipe pelang<br />
1<br />
2<br />
3 Keterangan gambar :<br />
1 = Kepala lampu<br />
4<br />
2 = Kap lampu<br />
3 = Kaos lampu<br />
5<br />
4 = Tiang lampu<br />
Gambar 2.4 Lampu Laguna<br />
Lampu laguna adalah lampu yang menyerupai petromax, dimana lampu<br />
laguna dilengkapi dengan sebuah kap, kepala lampu, kaca, tiang besi dan kaos<br />
lampu serta tengki sebagai tempat penampung bahan bakar dari minyak tanah dan<br />
lampu laguna memiliki daya tahan 15 jam.<br />
2.6.2 Rumpon dan Rakit<br />
Rumpon adalah alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul dalam suatu<br />
area penangkapan fishing ground. Posisi rumpon berada pada kedalaman 1200<br />
meter dan konstruksi pelampung dari bambu, aktraktor atau gara-gara dari daun<br />
38
kelapa atau daun lontar, tali-temalinya menggunakan tali nilon (sintetic fibres)<br />
dan pemberat menggunakan drum yang sudah dilakukan pengecoran beton,<br />
seperti pada Gambar 2.5.<br />
Keterangan :<br />
a. Rakit (8 m x 2 m) terbuat dari bambu<br />
b. Tali Anak (diameter 8 mm)<br />
c. Tali jangkar (diameter 20 mm)<br />
d. Gara-gara (daun lontar / daun kelapa)<br />
e. Jangkar/ pemberat (drum) = 200 – 300 kg<br />
Gambar 2.5 Posisi Rakit di Laut<br />
Disekitar rakit dan rumpon terdapat tempat berkumpulnya banyak<br />
plankton-plankton dan spesis ikan-ikan kecil lainnya sehingga menarik ikan yang<br />
lebih besar untuk memakannya.<br />
A<br />
Bentuk rumpon seperti tampak pada Gambar 2.6.<br />
drum cor<br />
B C<br />
kumpulan<br />
kumpulan<br />
Gambar 2.6 Posisi Rumpon A, B dan C di Permukaan Laut<br />
39
Dapat pula dijelaskan bahwa pada gambar A bentuk rumpon dengan tiga<br />
buah sahu yang menahan tali induk dan dilengkapi dengan gara-gara daun kelapa,<br />
segi tiga di atas rakit memberikan tanda atau kode bagi kapal-kapal penumpang<br />
yang melewati supaya tidak ditabrak.<br />
Pada gambar B bentuk rumpon lengkap dengan gara-gara dan penahan<br />
tali induk terdiri dari sekumpulan batu-batu besar yang diikat menjadi satu.<br />
Sedangkan bentuk rumpon pada gambar C dimana posisi rumpon akan melepas<br />
dari ikatan tali induk sebab akan dilakukan penangkapan dengan pukat cincin.<br />
Tampak pada foto 2.1 ini sebuah rakit di atas permukaan laut.<br />
Foto 2.1 Rakit di atas permukaan laut<br />
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di Lokasi penelitian<br />
membuktikkann bahwa operasi penangkapan yang dilakukan dengan pukat cincin<br />
menggunakan alat bantu rakit dilakukan pada malam hari.<br />
40
Untuk melakukan operasi penangkapan di malam hari, rakit dan lampu<br />
menjadi satu untuk mengumpulkan dan menaikkan ikan ke permukaan. Jika ikan<br />
masih menyebar, maka posisi rakit bergerak perlahan untuk memisahkan dengan<br />
pelampung yang diikat dan gara-gara yang ada dibawah rakit dinaikkan dan<br />
nelayan perahu lampu menutup sebagian cahaya sehingga ruang gerak ikan<br />
dibatasi, setelah ikan bergerombol dengan kepadatan yang tinggi maka nelayan<br />
yang ada di perahu lampu memberikan isyarat pada kapal induk untuk bersiap<br />
melakukan penangkapan sehingga ikan dapat dijinakkan. Pada proses<br />
penangkapan melalui penawuran jaring dengan cepat, melingkari secara<br />
horizontal, memagari secara vertikal dari permukaan laut hingga suatu<br />
kedalaman tertentu, mengurung dengan menutup bagian bawah jaring dan<br />
penarikan tali cincin maka muncul masalah ergonomi.<br />
Pada penarikan pukat cincin nelayan menggunakan kedua tangan dalam<br />
waktu lama dan panjang, sikap kerja duduk menarik, postur tubuh membungkuk,<br />
tungkai terjulur dan telapak kaki sebagai bantalan penahan tarikan, dan sering<br />
memanfaatkan jangkauan tangan ke depan dari batas maksimal dan pada akhir<br />
penarikan muncul rasa lelah dan nelayan mengeluh rasa sakit. Selama proses<br />
penangkapan berlangsung nelayan menunjukkan sikap kerja paksa menyebabkan<br />
timbulnya kelelahan, beban kerja berat dan adanya keluhan muskuloskeletal<br />
sehingga akan mengakibatkan penyakit dan cidera akibat kerja.<br />
Posisi jaring, rumpon dan perahu lampu terentang sempurna seperti<br />
tampak pada Gambar 2.7.<br />
41
.<br />
Gambar 2.7 Operasi penangkapan menggunakan rumpon dan lampu<br />
Pada gambar di atas tampak jelas bahwa proses penangkapan dengan<br />
pukat cincin sedang melakukan operasi penangkapan di malam hari terlihat pukat<br />
masih melebar berbentuk bulat disaat penarikan tali cincin dan perahu lampu<br />
masih berada dalam jaring. Apabila pukat sudah mengecil, maka akan terlihat<br />
sejumlah ikan yang tertangkap, seperti pada Gambar 2.8.<br />
Gambar 2.8 Pukat cincin berbentuk kantong<br />
Dengan penarikan tali cincin dan pelampung dari permukaan hingga suatu<br />
kedalaman, maka pukat cincin menjadi mengecil berbentuk kantong sehingga ikan<br />
yang tertangkap tidak dapat keluar.<br />
42
2.6.3 Tali Penarikan Pukat Cincin<br />
Jenis tali pemberat sebagai tempat pemasangan cincin disebut brid<br />
berukuran polyethylene (PE) ∅ 18-22 mm yang dipasang dengan cara<br />
dimasukkan kedalam cincin dan berfungsi untuk menarik cincin agar cincin<br />
terkumpul sehingga jaring membentuk kantong.<br />
Dari<br />
hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di atas kapal KM. Tiberias<br />
didapatkan bahwa ada jenis tali-temali lainnya yang dipasang tersambung dengan<br />
tali ris atas pelampung dan tali ris bawah pemberat dan berfungsi untuk<br />
menggantungkan jaring, panjang kedua tali ini sesuai dengan panjang jaring<br />
soma pajeko dan tergantung sesuai dengan ukuran dan konstruksi pukat cincin<br />
(Nomura dan Yamazaki, 2003). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada foto 2.2.<br />
Foto : 2.2 Tali pukat cincin<br />
Semakin dalam tenggelamnya jaring maka semakin besar tali cincin yang<br />
dibutuhkan, hal ini berarti ikan yang tertangkap tidak ada yang keluar sehingga<br />
43
tempo penarikan semakin lama dan panjang dan waktu yang dibutuhkan akan<br />
cenderung bertambah.<br />
Dalam proses ini jaring harus tengelam mencapai kedalaman maksimum,<br />
sehingga ikan tidak dapat berenang lebih dalam lagi, oleh karenanya dibutuhkan<br />
kelajuan dari tali pemberat untuk mengimbangi kecepatan renang ikan<br />
(Kanagaya, 2005) menyatakan bahwa tegangan pada tali cincin mempunyai<br />
pengaruh terhadap keberhasilan operasi penangkapan terutama kedalaman<br />
tenggelam tali pemberat dan perubahan kedalaman selama penarikan tali cincin.<br />
Jika selama penawuran jaring, tali cincin mendapat tegangan yang<br />
besar, maka jaring tidak dapat terbuka dengan kedalaman penuh oleh karena<br />
keberhasilan pengambilan hasil tangkapan tergantung pada beberapa faktor<br />
antara lain : penarikan tali cincin, penarikan jaring, kecepatan kapal, keadaan<br />
perairan, pendidikan dan keterampilan anak buah kapal, pengalaman<br />
menangkap ikan dan perlengkapan yang digunakan di atas kapal (Katiandagho<br />
and Fridman, 2006).<br />
2.6.4 Kapal Penangkapan Ikan<br />
Armada penangkapan yang mengoperasikan pukat cincin untuk<br />
penangkapan sejenis ikan pelagis adalah kapal yang mempunyai tipe lambut<br />
dengan bobot 40 – 80 GT sebagai kapal induk. Tenaga penggerak yang digunakan<br />
pada kapal induk berupa motor tempel merk Yamaha tipe enduro dengan<br />
kekuataan dorong 40 HP sebanyak 4-5 buah untuk setiap unit perahu penangkap<br />
dan ada sebagian aramada penangkap menggunakan mesin dalam. Untuk jelasnya<br />
dapat dilihat pada foto 2.3<br />
44
(a) Tampak Samping<br />
(b) Tampak Atas<br />
Foto 2.3 Tipe kapal penangkap ikan<br />
Gambar 2.9 Kapal Tipe Lambut Pukat Cincin<br />
45
Nama Perahu /<br />
Tipe<br />
A. KM. Tiberias<br />
“Lambut”<br />
B. KM. Masmur<br />
“Lambut”<br />
Tabel 2.1<br />
Keterangan kapal tipe Lambut Penangkap Ikan<br />
Ukuran Utama Kapal<br />
Tenaga<br />
Panjang (L) Lebar (B) Dalam (D) Penggerak<br />
(m) (m) (m) (HP)<br />
21,5 5,15 2,25 Mesin tempel<br />
40PK (5 buah)<br />
21,5 5,15 2,25 Mesin tempel<br />
40PK (5 buah)<br />
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dapat dijelaskan bahwa nelayan<br />
pukat cincin adalah pekerja yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi<br />
penangkapan pada malam hari dengan menggunakan alat bantu rumpon dan<br />
lampu berdasarkan musim dan bagi sebagian besar anak buah kapal adalah laki-<br />
laki, sedangkan wanitanya dibatasi pada kegiatan-kegiatan di tepi pantai saja<br />
termasuk usaha pendistribusian dan pemasaran hasil tangkapan dan dibantu oleh<br />
anak-anak.<br />
2.7 Penangkapan Ikan Jenis Pelagis<br />
Alat penangkapan ikan sangat menetukan jumlah ikan yang diperoleh,<br />
sebab operasi penangkapan harus dilakukan dengan cepat, kelajuan melingkar,<br />
kecepatan perahu dan kecakapan tonaas (pemimpin) mengelilingi besarnya<br />
kelompok ikan yang terkumpul.<br />
Begitu pula perahu yang digunakan pada umumnya menggunakan kapal<br />
motor dalam dan atau motor tempel sebanyak 5 motor 40 pk. Kebutuhan perahu<br />
disesuaikan dengan alat penangkap yang dipakai.<br />
46
Intensitas penangkapan ikan-ikan sejenis pelagis yang dilakukan oleh<br />
nelayan adalah angka yang menunjukkan seringnya penangkapan dilakukan pada<br />
malam hari. Intensitas tersebut dihitung dalam jumlah kali penangkapan yang<br />
untuk selanjutnya disebut trip dalam jangka waktu tertentu. Jenis ikan-ikan<br />
pelagis yang tertangkap di perairan laut Amurang Kabupaten Minahasa Selatan<br />
yang dikenal sebagai basis ikan pelagis seperti tampak pada Gambar 2.10.<br />
Gambar 2.10 Sejenis Ikan Pelagis (Malalugis)<br />
Untuk menangkap ikan pelagis ini yang hidup sampai kedalaman 150<br />
meter (Katiandagho, 2006) kelajuan tali pemberat sangat menentukan untuk<br />
mencegah agar ikan tidak cepat keluar melalui bagian bawah jaring setelah<br />
penawuran sampai pada penarikan tali cincin.<br />
2.8 Kerja Malam Menangkap Ikan<br />
Apabila manusia bekerja pada malam hari dan tidur siang, maka irama<br />
fisiologi kerja akan terganggu, karena fungsi fisiologis tenaga kerja tidak dapat<br />
disesuaikan dengan irama kerja tersebut. Suhu badan, deyut nadi, tekanan darah<br />
yang bekerja pada malam hari sangat berbeda dengan yang bekerja pada pagi,<br />
siang dan sore (Grandjean, 1988). Oleh karena metabolisme tidak dapat<br />
sepenuhnya atau tidak dapat sama sekali diadaptasikan dengan kerja malam dan<br />
tidur siang.<br />
47
Keseimbangan elektrolit sebagai akibat albumin dan klorida di darah<br />
dapat beradaptasi dengan keperluan kerja malam dan tidur siang, tetapi<br />
pertukaran zat-zat seperti : kalium, sulfur, fosformangan terikat pada sel-sel<br />
sehingga dengan pergantian waktu kerja siang menjadi malam tidak dapat<br />
dipengaruhinya. Metabolisme zat-zat terakhir tidak dapat diserasikan dengan<br />
kebutuhan kerja pada malam hari, sehingga untuk kerja malam kelelahan relatif<br />
sangat besar disebabkan oleh faktor faal dan metabolisme yang tidak dapat<br />
diserasikan serta sangat kuatnya kerja syaraf para simpatis dibanding simpatis<br />
pada malam hari (Suma’mur, 1991), sedangkan semestinya adalah simpatis harus<br />
melebihi kekuatan para simpatis.<br />
Banyaknya dan lamanya waktu tidur pada siang hari relatif lebih sedikit<br />
dibandingkan dengan tidur malam. Hal ini disebabkan oleh suasana lingkungan<br />
pada siang hari seperti : suhu, kebisingan, aktivitas manusia, binatang dan juga<br />
karena kebutuhan, misalnya terbangun karena lapar, buang air kecil atau besar<br />
dan sebagainya dan pada malam hari alat pecernaan tidak berfungsi secara<br />
normal, sebab jumlah makanan yang diambil lebih sedikit, sedangkan pencernaan<br />
kurang bekerja sebagaimana mestinya sehingga berakibat pada menurunnya berat<br />
badan.<br />
Selain masalah biologis dan faal, maka kerja malam disertai reaksi<br />
psikologis sebagai suatu mekanisme defensif terhadap gangguan tubuh akibat<br />
ketidak serasian badani terhadap pekerjaan malam. Dengan demikian keluhan-<br />
keluhan relatif lebih banyak ditemukan pada kerja malam. Untuk itu perlu<br />
dipertimbangkan pemberian gizi dan makanan eksra dan aspek-aspek yang perlu<br />
48
juga diperhatikan pada kerja malam adalah : aspek kesehatan, sosial, budaya,<br />
biologi, dan ekonomi (Manuaba, 1998).<br />
Jadi makin panjang waktu kerja malam, maka makin besar pula efeknya<br />
terhadap kesehatan. Bagaimanapun juga kerja malam lebih banyak mempunyai<br />
dampak kurang baik bila dibandingkan dengan kerja siang. Sebaiknya kerja<br />
malam dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang benar-benar urgensi<br />
atau tidak boleh tidak dan harus dilakukan.<br />
Terkait dengan penjelasan di atas, maka nelayan dalam usaha<br />
penangkapan ikan dangan pukat cincin pada malam hari mempunyai dampak<br />
negatif yang kurang menguntungkan bagi kesehatan, keselamatan, kenyamanan<br />
dan keamanan kerja, dimana mereka melakukan penangkapan ikan di perairan<br />
laut tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang prinsip dan kaidah ergonomi<br />
yang bermanfaat bagi kualitas hidup manusia tentang budaya sehat, aman,<br />
nyaman, dan efisien sehingga produktivitas meningkat. Tetapi untuk mengubah<br />
budaya kerja malam dengan berbagai risiko menjadi waktu kerja siang sangat<br />
dibutuhkan intervensi ergonomi dengan pendekatan ergonomi total sehingga<br />
diharapkan adanya peningkatan produktivitas, kinerja dan kesejahteraan bagi<br />
keluarga nelayan.<br />
49
2.9 Mengindentifikasi Masalah Ergonomi Total pada Penangkapan Ikan<br />
dengan Pukat Cincin<br />
Sikap kerja adalah sikap tubuh saat melakukan aktivitas kerja dan<br />
berinteraksi dengan alat kerja hendaknya diupayakan dalam posisi alamiah<br />
sehingga tidak menimbulkan sikap kerja paksa yang melampaui kemampuan<br />
fisiologis tubuh (Grandjean dan Kroemer, 2000; Manuaba, 1998). Sikap kerja<br />
yang tidak fisiologis dapat menimbulkan gangguan pada sistem muskuloskeletal<br />
dan dapat menyebabkan hilangnya stabilitas, mudah tergelincir dan rawan<br />
terhadap kecelakaan (Manuaba, 1998b dan Sariputra, 2003).<br />
Sikap kerja paksa bisa terjadi pada saat mengangkat, mengangkut,<br />
memegang, menarik, duduk, berdiri terlalu lama (Ferguson, 2001 et.al. Adnyana,<br />
2005). Sikap kerja yang dijumpai pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin yang oleh nelayan adalah sikap paksa. Sikap kerja paksa dimulai dari<br />
penawuran jaring, dimana jaring ditebarkan mengelilingi sekelompok ikan sejenis<br />
pelagis, melingkari secara horisontal, memagari secara vertikal dari permukaan<br />
laut hingga suatu kedalaman, mengurung dengan menutup bagian bawah jaring<br />
sampai pada penarikan tali pukat cincin.<br />
Pada penarikan pukat cincin, muncul permasalahan dimana mereka<br />
menarik dengan kedua tangan dalam waktu lama dan panjang serta dialksanakan<br />
berulang-ulang, sikap kerja duduk di lantai papan perahu dan berdiri menarik<br />
pukar postur tubuh membungkuk dan tungkai terjulur, telapak kaki sebagai<br />
bantalan penahan tarikan dan sering memanfaatkan jangkauan tangan kedepan dan<br />
pada akhir penarikan muncul rasa lelah dan nelayan mengeluh rasa sakit.<br />
50
2.9.1 Sikap Kerja Nelayan Menarik Pukat Cincin Duduk di Lantai Perahu<br />
Bekerja dengan sikap kerja duduk terlalu lama dan dilakukan dengan<br />
posisi yang tidak tepat maka akan menyebabkan beberapa masalah pada<br />
beberapa bagian tubuh terutama pada tulang belakang dan bagian posterior bawah<br />
tulang pinggul. Sikap duduk yang tegang akibat posisi yang tidak tepat akan<br />
memberi tekanan pada lekukan tulang belakang.<br />
Dinamika posisi duduk yang tidak alamiah atau dipaksakan sebaiknya<br />
diimbangi dengan perbaikan beberapa faktor (Bridger, 1995; Henning, 1997;<br />
Schlumberger, 1998) antara lain : 1) karakteristik pengguna (subject), umur,<br />
antropometri, berat badan, kesegaran jasmani, pergerakan sendi, masalah<br />
muskuloskeletal, penglihatan, kegemukan dan ketangkasan tangan, 2) tuntutan<br />
jenis tugas pekerjaan (task deman), posisi tubuh, siklus waktu kerja, periode<br />
istirahat, urut-urutan pekerjaan, 3) rancangan luasan kerja (workspace),<br />
ukuran kursi, ukuran bahan yang dikerjakan, rancangan kursi, ukuran luasan<br />
kerja ruang pergerakan kepala, lengan, kaki (privacy), dan 4) faktor<br />
lingkungan kerja (environment), kualitas intensitas penerangan, suhu<br />
lingkungan, kelembaban udara, kecepatan udara, kelicinan lantai, kebisingan,<br />
debu, vibrasi.<br />
Diusahakan suatu perbaikan kearah sikap kerja duduk yang sesuai dengan<br />
kenyamanan duduk saat bekerja sangat penting terhadap pergerakan tubuh<br />
(Helander dan Zhang, 1997). Kebutuhan pergerakan tubuh dalam sikap kerja<br />
duduk dipengaruhi oleh posisi pekerjaan (single position and group position)<br />
dalam mengerjakan bagian-bagian dari pekerjaan dan juga tipe kerja yang<br />
51
dilakukan seperti : kerja statis, kerja dinamis, kerja repetitif, gaya dan kekerapan<br />
kerja.<br />
Dari hasil penelitian pendahuluan didapati bahwa sikap kerja duduk<br />
terlalu lama menarik pukat cincin adalah lebih banyak melibatkan aktivitas fisik<br />
yang berpotensi menimbulkan beban kerja berat, kelelahan dan gangguan<br />
muskuloskeletal pada saat gerakan lengan tangan menarik tali cincin sehingga<br />
mengakibatkan keluhan-keluhan rasa sakit pada tangan kiri dan kanan, bagian<br />
punggung, pinggang, sakit pada pantat, sakit pada betis kiri dan kanan, kaki<br />
kanan dan kiri sebab dijadikan sebagai bantalan penahan untuk menarik pukat<br />
cincin hal ini berarti nelayan berada dalam sikap kerja paksa.<br />
Sikap kerja duduk terlalu lama seperti tampak pada foto 2.4<br />
Foto 2.4 Sikap kerja nelayan menarik pukat cincin<br />
Sikap tubuh manusia ketika melakukan pekerjaan diakibatkan oleh<br />
hubungan antara dimensi pekerja dengan dimensi variasi dari tempat kerjanya<br />
disebut sikap kerja (Phesant, 1991). Sikap kerja nelayan pada waktu melakukan<br />
aktivitas penangkapan ikan dengan menarik tali pukat cincin dilakukan dengan<br />
52
sikap kerja paksa. Sikap kerja paksa dapat menyebabkan timbulnya berbagai<br />
gangguan pada sistem otot skeletal (Manuaba, 1990; Adiputra, 1998). Kondisi<br />
tersebut tentunya akan dapat menyebabkan keluhan atau kenyerian pada bagian<br />
otot-otot skeletal, khususnya pinggang dan punggung serta otot-otot bagian bawah<br />
seperti : paha, lutut, betis, pantat dan kaki; dan bagian atas seperti : pergelangan<br />
tangan kanan dan kiri, bahu, leher dan sebagainya.<br />
Nala, (1990) mengemukakan bahwa dibandingkan dengan kontraksi otot<br />
yang dinamis, maka kerja statis mempunyai kekurangan, yaitu kerja otot statis<br />
menghasilkan energi yang lebih besar dan cepat melelahkan. Pada gambar di atas<br />
sikap kerja duduk menarik tali pukat cincin dapat dijelaskan sebagai berikut :<br />
1) Cara kerja pada posisi duduk dalam waktu yang lama dan berulang-ulang<br />
akan menimbulkan kejenuhan dan kelelahan karena dipengaruhi oleh<br />
gravitasi bekerja pada garis lurus vertikal melalui pusat tubuh yang ditahan<br />
oleh tulang belakang, akibatnya terjadi momen gaya yang menyebabkan<br />
tubuh cenderung jatuh ke depan, jika posisi duduk yang salah<br />
mengakibatkan masalah pada tulang belakang bagian bawah dan kaki. Pada<br />
saat duduk tekanan tulang belakang bagian bawah lebih besar dibandingkan<br />
pada saat berdiri, sehingga dibutuhkan suatu tempat duduk yang ergonomis.<br />
2) Gerak badan atau tangan, kaki dan menarik beban yaitu memerlukan energi<br />
yang optimal apabila arah tarikan tersebut adalah 60 derajat maka benda<br />
yang diangkat atau ditarik harus sedekat mungkin ke badan dan masih<br />
dalam wilayah antara sendi lutut dan paha. Posisi badan harus diupayakan<br />
tetap tegak dan otot perut dan pantat harus dalam keadaan berkonsentrasi<br />
53
kuat. Tetapi yang terjadi pada nelayan saat menarik pukat tali cincin tidak<br />
ergonomis sehingga mereka selesai bekerja mengeluh rasa sakit.<br />
2.9.2 Sikap Kerja Nelayan Menarik Pukat Cincin Berdiri Terlalu Lama<br />
Sikap kerja berdiri, membungkuk dan menjongkok terlalu lama dan<br />
dilakukan secara berulang-ulang tidak teratur dan tidak alamiah dapat dijumpai<br />
pada nelayan pada saat menarik pukat cincin. Seperti yang terlihat pada foto 2.5<br />
Foto 2.5 Penarikan pukat dengan sikap kerja berdiri<br />
Phesant, (1991) menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar dalam<br />
mengatasi sikap tubuh selama bekerja antara lain adalah sebagai berikut.<br />
1) Hindari inklinasi ke depan dari kepala dan leher.<br />
2) Hindari inklinasi ke depan dari tubuh.<br />
3) Hindari penggunaan anggota gerak bagian atas dalam keadaan terangkat.<br />
4) Hindari pemutaran badan atau sikap asimetris (terpilin/twisty).<br />
5) Sendi hendaknya dalam rentang 1/3 dari gerakan maksimal.<br />
54
6) Sediakan sandaran punggung dan pinggang pada semua tempat duduk.<br />
7) Sikap menggunakan otot, hendaknya dalam posisi yang mengakibatkan<br />
kekuatan maksimal.<br />
Dalam melaksanakan tugasnya nelayan/pekerja melakukan sikap kerja<br />
sebagai berikut (Phesant, 1991).<br />
a) Inklinasi ke depan pada leher dan kepala, karena medan kerja terlalu rendah<br />
atau obyek terlalu kecil.<br />
b) Sikap kerja posisi badan berdiri dan membungkuk kedepan, karena medan<br />
kerja terlalu rendah dan obyek di luar jangkauan.<br />
c) Sikap asimetris yang mengakibatkan terjadinya perbedaan beban pada kedua<br />
sisi tulang belakang.<br />
d) Sikap kerja yang salah dapat menyebabkan postural deformitas pada tubuh<br />
antara lain : lordosis, khiposis, dan skoliosis.<br />
Prinsip kerja secara ergonomis, agar terhindar dari resiko cidera antara lain<br />
adalah sbb. (Manuaba, (1990) ; Adiputra, (1998) ; Sutjana, (2000)).<br />
1) Gunakan tenaga seefisien mungkin, beban yang tidak perlu harus dikurangi<br />
atu dihilangkan, perhitungan gaya berat yang mengacu pada berat badan dan<br />
bila perlu gunakan pengungkit sebagai alat bantu.<br />
2) Sikap kerja duduk, berdiri dan jongkok hendaknya disesuaikan dengan<br />
prinsip-prinsip ergonomi.<br />
3) Panca indra dapat digunakan sebagai kontrol, bila payah harus istirahat<br />
(jangan dipaksa) dan bila lapar atau haus harus makan dan minum (jagan<br />
ditahan).<br />
55
4) Jantung digunakan sebagaai parameter yang diukur melalui denyut nadi<br />
permenit yaitu jangan lebih dari jumlah maksimum yang diperbolehkan.<br />
Dengan mengetahui kriteria sikap kerja yang ideal, maka prinsip dasar<br />
untuk mengatasi sikap tubuh yang salah selama bekerja dapat diatasi. Kasus<br />
penangkapan ikan yang sering terjadi pada nelayan pukat cincin berkaitan<br />
dengan sikap kerja yang tidak ergonomis, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk<br />
diambil langkah-langkah pencegahan yang lebih spesifik di dalam melakukan<br />
perbaikan. Dalam melakukan perbaikan dari hasil penelitian pendahuluan yang<br />
telah dilakukan, maka setiap karakteristik data diindentifikasi dengan<br />
menggunakan pendekatan ergonomi total.<br />
2.10 Intervensi Ergonomi<br />
Intervensi ergonomi yang dilakukan dimulai dari indentifikasi setiap<br />
masalah yang berhubungan dengan proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam upaya-upaya<br />
membangun budaya kerja yang sehat, aman, nyaman, efektif dan efisien<br />
sehingga terjadi peningkatan kinerja dan kesejahteraan nelayan seperti pada :<br />
1) pemanfaatan tenaga otot, 2) sikap kerja, 3) kondisi kondisi waktu, 4)<br />
kondisi sosial budaya, 5) kondisi informasi dan komunikasi.<br />
Dari kelima permasalahan yang diindentifikasi, maka semua masalah<br />
yang ada pada nelayan pada waktu proses penangkapan ikan harus dipecahkan<br />
melalui pendekatan sistem, dikaji secara holistik dan melalui lintas disiplin<br />
ilmu dapat digunakan pendekatan partisipatori, dengan maksud agar semua<br />
56
komponen dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi<br />
dapat dipecahkan secara bersama-sama (Manuaba, 2005b).<br />
Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
mutlak diperlukan terutama pada saat melakukan penawuran jaring sampai pada<br />
penarikan tali pukat cincin sehingga akan dapat menurunkan kelelahan, beban<br />
kerja dan gangguan muskuloskeletal nelayan, sebab melalui intervensi ergonomi<br />
dapat memperbaiki kinerja nelayan dalam pencapaian hasil penangkapan ikan<br />
yang optimal dengan demikian kesejahteraan hidup keluarga nelayan dapat<br />
meningkat.<br />
Melalui intervensi ergonomi yang dilakukan terhadap kinerja nelayan<br />
pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin diharapkan dapat<br />
menurunkan beban kerja fisik terutama frekuensi denyut nadi kerja (Adiputra,<br />
2002). Kelelahan sebagai suatu keadaan yang tercermin dari gejala perubahan<br />
psikologis berupa aktivitas motoris adanya perasaan rasa sakit dan pelemahan<br />
motivasi dapat dihindari (Grandjean, 1993) dan keluhan muskuloskeletal yang<br />
bersifat sementara maupun menetap dapat diminimalisasikan bahkan dihindari<br />
agar supaya pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan risiko kecelakaan lebih kecil<br />
(Manuaba, 2003a).<br />
Model intervensi ergonomi melalui pendekatan ergonomi total pada<br />
proses penangkapan ikan dengan pukat cincin menurunkan beban kerja,<br />
kelelahan, dan gangguan muskuloskeletal serta meningkatkan kinerja dan<br />
kesejahteraan nelayan penangkap ikan, dapat dilihat pada Gambar 2.11<br />
57
SHIP<br />
1. Gizi atau<br />
nutrisi<br />
2. Sikap kerja,<br />
3. Penggunaan<br />
otot,<br />
4. Kondisi<br />
lingkungan,<br />
5. Kondisi<br />
waktu,<br />
6. Kondisi<br />
TTG<br />
1.Teknis<br />
2. Ekonomi<br />
3. Ergonomi<br />
4. Sosial Budya<br />
5. Hemat Energi<br />
Tidak<br />
Intervensi<br />
Ergonomi<br />
Indikator<br />
5 masalah<br />
ergonomi total<br />
1. Gizi atau<br />
nutrisi<br />
2. Sikap kerja,<br />
3. Penggunaan<br />
Gambar 2.11 Model Intervensi dan Penerapan Ergonomi Total Pada<br />
Aktivitas Penangkapan ikan dengan Pukat Cincin<br />
2.11 Pertimbangan Antropometri dalam Desain Alat Kerja<br />
Antropometri adalah cabang dari ilmu ergonomi yang berkaitan dengan<br />
pengukuran dan karakteristik dari tubuh manusia. Pengukuran tubuh manusia<br />
dilakukan baik dalam keadaan diam statis dan bergerak dinamis untuk menerima<br />
beban dari luar termasuk disini ukuran linier, berat volume, ruang gerak dan lain-<br />
lain (Sanders dan McCormick, 1992., Bridger, 1995).<br />
Indikator<br />
Kinerja dapat<br />
menurunkan<br />
1. Beban kerja<br />
2. Kelelahan<br />
3. Gangguan<br />
muskuloskel<br />
etal<br />
Meningkatka<br />
n<br />
kesejahteraan<br />
Data antropometri sangat bermanfaat di dalam perencanaan dan<br />
perancangan peralatan kerja atau fasilitas-fasilitas kerja.. Persyaratan ergonomi<br />
menyarankan agar supaya peralatan kerja dan fasilitas kerja sesuai dengan orang<br />
58
yang menggunakan khususnya menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam<br />
menentukan ukuran maksimum dan minimum biasanya digunakan data<br />
antropometri antara persentil 5 dan 95 dari populasi, dan rancangan untuk ukuran<br />
rerata dengan menggunakan persentil –50 (Phullat, 1992; Phesant, 1998).<br />
Pedoman pengukuran antropometri telah dikeluarkan oleh IAIFI<br />
Komisariat Denpasar (Sutjana IDP dkk, 2000) mengemukakan bahwa beberapa<br />
tahun terakhir ini banyak peralatan kerja maupun mesin yang ukurannya belum<br />
sesuai dengan ukuran tubuh orang (tenaga kerja) Indonesia sehingga<br />
menyebabkan cepat lelah, kurang efisien, produktivitas kerja rendah bahkan<br />
sering menimbulkan kecelakaan kerja kondisi demikian disebabkan kurangnya<br />
data antropometri orang Indonesia yang dipakai sebagai acuan pedoman untuk<br />
keperluan perancangan peralatan kerja.<br />
Cara perhitungan antropometri dalam distribusi normal adalah seperti<br />
pada Tabel 2.2.<br />
Tabel 2.2<br />
Macam persentil dan Cara Perhitungan dalam Distribusi Normal<br />
No. Persentil Perhitungan<br />
1 1 th<br />
Rata-rata – 2.325 α<br />
2 2.5 th<br />
Rata-rata – 1.96 α<br />
3 5 th<br />
Rata-rata – 1.645 α<br />
4 10 th<br />
Rata-rata – 1.28 α<br />
5 50 th<br />
Rata-rata – X<br />
6 90 th<br />
Rata-rata + 1.28 α<br />
7 95 th<br />
Rata-rata + 1.645 α<br />
8 97.5 th<br />
Rata-rata + 1.96 α<br />
9 99 th<br />
Rata-rata + 2.325 α<br />
Keterangan : α = Standar deviasi (Wignyosoebroto, 1995)<br />
59
Penerapan antropometri dalam perancangan alat kerja yang berkaitan<br />
dengan penelitian ini khususnya pembuatan alat kerja katrol pada nelayan pukat<br />
cincin dalam proses penangkapan ikan yang penting dan harus diperhatikan<br />
dalam memperbaiki sikap kerja duduk menurut (Grandjean, 1993., Phesant,<br />
1988., Sanders, and McCormick, 1987) adalah penerapan ukuran antropometri<br />
tubuh pemakai alat tersebut dan yang dibutuhkan sebagai berikut :<br />
1) Tinggi tubuh yaitu tinggi dari lantai sampai ke vertex. Sikap tubuh : berdiri<br />
tegak dengan sikap bersiap, pandangan lurus ke depan dengan tumit, pantat,<br />
punggung dan belakang kepala menyentuh tembok tanpa alas kaki;<br />
2) Jarak dari pantat ke popliteal adalah ukuran horisontal dari belakang pantat<br />
ke sudut popliteal dibelakang lutut yaitu pertemuan antara betis dengan sisi<br />
bawah paha diukur dalam posisi duduk;<br />
3) Jarak dari pantat ke lutut adalah ukuran horisontal dari belakang pantat ke<br />
puncak lutut diukur dalam posisi duduk;<br />
4) Tinggi popliteal adalah ukuran vertikal dari lantai ke sudut popliteal disisi<br />
bawah lutut, terletak pada betis femoris otot tendon di ujung dalam betis;<br />
5) Tinggi lutut adalah ukuran vertikal dari lantai ke atas luasan daerah lutut;<br />
6) Lebar pinggul adalah ukuran maksimum pinggul yang melintang horisontal<br />
dalam posisi duduk;<br />
7) Panjang jangkauan tangan lurus ke depan adalah ukuran dari akromion ke<br />
tengah objek sambil menggenggam alat, dalam posisi duduk dan lengan siku<br />
tangan lurus ke depan;<br />
60
8) Panjang jangkauan ke samping adalah ukuran dari akromion ke tengah<br />
objek tangan menggenggam alat dalam posisi duduk dan lengan siku tangan<br />
lurus ke samping;<br />
9) Antropometri tangan; bagian-bagian yang di ukur yaitu : a) 1, panjang<br />
tangan, b) 2, panjang telapak tangan, c) 3, lebar tangan sampai ibu jari, d) 4,<br />
lebar tangan sampai metakarpal, e) 5, ketebalan tangan pada metakarpal,<br />
f) 6, lingkar tangan sampai telunjuk, g) 7, lingkar tangan sampai ibu jari,<br />
h) 8, jarak pergelangan sampai ke ujung ibu jari.<br />
10) Antropometri kaki; bagian-bagian yang diukur : a) 9, panjang kaki, b) 10,<br />
lebar kaki, c) 11, jarak antara tumit dengan bagian telapak kaki, d) 12, lebar<br />
tumit, e) 13, lingkar telapak kaki (ukur yang paling lebar), f) 14, lingkar<br />
kaki membujur,g) 15, tinggi mata kaki bagian luar, h) 16, tinggi mata kaki<br />
bagian dalam, i) 17, lingkaran pergelangan kaki.<br />
Ukuran beberapa segmen dan dimensi tubuh yang diperlukan sebagai data<br />
dasar untukl desain alat katrol diukur dengan alat antropometer. Dapat dilihat<br />
pada Gambar 2.12<br />
61
Gambar 2.12 Pengukuran Antropometri<br />
62
17<br />
6<br />
7<br />
1 2<br />
14 15 16<br />
Gambar 2.13 Antropometri tangan dan kaki<br />
2.12 Prinsip ergonomi dalam perancangan alat kerja<br />
Aspek ergonomi yang perlu mendapat perhatian dalam perancangan alat<br />
kerja pada penelitian ini yaitu melakukan intervensi ergonomi dan penerapan<br />
ergonomi total. Penerapan ergonomi total merupakan salah satu bentuk<br />
intervensi ergonomi yang bertujuan untuk mendapatkan sistem kerja yang<br />
manusiawi, kompetitif dan lestari (Manuaba, 2004a).<br />
4<br />
Dalam merancang alat kerja yang akan digunakan oleh manusia selalu<br />
berusaha menserasikan alat kerja/mesin, cara kerja dan lingkungan terhadap<br />
kemampuan, kebolehan dan batasan manusia dengan sasaran tercapainya kondisi<br />
3<br />
8<br />
9<br />
11<br />
10<br />
13<br />
12<br />
5<br />
63
kerja dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien demi<br />
tercapainya produktivitas yang tinggih. Peningkatan produktivitas yang tinggih<br />
dapat tercapai, jika semua komponen dalam sistem kerja yaitu manusia,<br />
peralatan, material dan lingkungan kerja dirancang secara ergonomi (Manuaba,<br />
1992).<br />
Desain merupakan suatu kegiatan daya inovatif atau rekayasa rancang<br />
bangun yang dimulai dari ide-ide inovasi, atau kemampuan untuk menghasilkan<br />
karya dan cipta yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan permintaan<br />
manusia karena adanya penelitian dan pengembangan teknologi secara terus<br />
menerus dengan tujuan sebagai berikut :<br />
1) Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, hal tersebut mencegah<br />
munculnya cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban fisik dan<br />
mental serta mempromosikan kepuasan kerja.<br />
2) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperbaiki kualitas hidup dan<br />
kinerja serta mengorganisasikan sistem kerja sebaik-baiknya.<br />
3) Meningkatkan interaksi manusia/mesin antara aspek teknis, ekonomi,<br />
antropologi dan budaya dari suatu sistem kerja.<br />
Untuk mencapai tujuan yang ergonomis dari suatu desain, maka perlu<br />
dijadikan suatu bahan pertimbangan dari beberapa problem ergonomi antara lain<br />
sebagai berikut :<br />
1) Aplikasi dari tenaga otot secara optimal dan efisien untuk menekan stres<br />
pekerjaan sampai batas minimum.<br />
2) Sikap tubuh yang diterapkan pada sikap kerja dengan memperhatikan situasi<br />
64
pembebanan terhadap tubuh dan kesehatan dan jenis lingkup pekerjaan.<br />
3) Kondisi lingkungan kerja untuk mencegah beban kerja yang berlebihan<br />
terhadap fisik dan mental.<br />
4) Kondisi yang terkait dengan pola kerja, waktu kerja. Waktu istirahat dan<br />
hari-hari libur.<br />
5) Kondisi sosial untuk meningkatkan interaksi antara manusia, lingkungan<br />
kerja, teknologi dan seni dapat memeberikan penghargaan reward terhadap<br />
harga diri dan kepuasan kerja.<br />
Desain juga dapat diartikan sebagai salah satu aktifitas luas dari inovasi<br />
yang berhubungan dengan pegembangan bentuk, pengembangan teknik, proses<br />
produksi dan peningkatan pasar. Ruang lingkup kegiatannya menyangkut<br />
masalah yang berhubungan dengan sarana kebutuhan manusia melalui proses<br />
industri. Untuk menilai suatu hasil akhir sebagai kategori nilai desain yang baik<br />
biasanya ada tiga unsur yang mendasarinya yaitu: fungsional, estetika, dan<br />
ekonomi yang disebut sebagai (fit-form-function).<br />
Salah satu unsur penilaian yang efektif dari sebuah desain adalah untuk<br />
meningkatkan daya cipta, karsa dan rasa dari hasil produk yang bernilai positif<br />
sesuai tujuannya yaitu dapat dipergunakan dengan tingkat kenyamanan yang<br />
tinggi, mempunyai nilai tambah dan dengan mudah pengoperasian dan<br />
pemeliharaan secara fleksibel sehingga mempunyai masa pakai yang cukup<br />
panjang (Prasetyowibowo, 2000). Kesesuaian, keselamatan, keamanan, dan<br />
kenyamanan manusia adalah merupakan prasyarat untuk menggunakan suatu<br />
hasil desain alat tersebut. Aktifitas atau kegiatan manusia berupa sikap dan<br />
65
gerakan tubuh yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan suatu desain alat akan<br />
berakibat pada ketidaknyamanan, dan bahkan menimbulkan rasa sakit pada<br />
tubuh.<br />
Disisi lain desain alat merupakan suatu langkah strategis untuk bisa<br />
menghasilkan produk-produk yang secara komersial harus mampu dicapai guna<br />
menghasilkan laju pengembalian modal (rate of return investment). Disini<br />
diperlukan penyusunan konsep desain baru maupun desain lama yang sudah<br />
dimodifikasi menjadi sebuah produk baru dalam bentuk rancangan teknik<br />
(engeenering design) dan juga rancangan industri (industrial design) untuk<br />
memenuhi kebutuhan pasar (demand pull), atau dilatar belakangi oleh adanya<br />
dorongan memanfaatkan inovasi teknologi.<br />
Desain dari sebuah alat akan terkait dengan semua analisis perhitungnan<br />
yang menyangkut pemilihan dan perhitungan kekuatan material, dimensi<br />
geometris, toleransi dan standar kualitas yang hendak dicapai yang kesemuanya<br />
akan sangat menentukan derajat kualitas dan reliabilitas untuk memenuhi<br />
tuntutan fungsi serta spesifikasi teknis yang diharapkan (Prihartono, 2000).<br />
Rancangan alat sangat berpengaruh signifikan terutama didalam memberikan<br />
estetika keindahan dan sentuhan kenyamanan sebagai kelayakan operasional<br />
yang dalam hal ini diperlukan berbagai macam evaluasi dan pengujian dengan<br />
menggunakan tolok ukur ergonomi sebagai salah satu langkah pengujian agar<br />
supaya pengujian alat pada saat dioperasikan tidak hanya memberikan fungsi<br />
yang direncanakan, tetapi juga mampu memberikan suatu keselamatan,<br />
kesehatan, kenyamanan pada saat dioperasikan (Wignjosoebroto, 2000).<br />
66
Proses sebuah desain alat yang baik terutama bertujuan menganalisa,<br />
menilai dan menyusun suatu sistem fisik/non fisik yang optimum diwaktu<br />
mendatang dengan memanfaatkan informasi (Adiputra, 2003). Pertama-tama<br />
desainer menentukan produk yang akan dirancang need, yang dilanjutkan dengan<br />
pengembangan ide-ide untuk memenuhi kebutuhan tersebut idea, setelah<br />
diperoleh ide-ide, dilakukan penilaian dan pemilihan alternatif sehingga<br />
didapatkan suatu keputusan yang menghasilkan rencana desain yang optimal<br />
decision. Langkah terakhir adalah penanganan action yang dapat diklasifikasikan<br />
menjadi dua kategori yaitu: 1) produk yang sama sekali baru, dan 2) produk yang<br />
dikembangkan dari produk lama yang sudah ada tetapi memiliki fungsi,<br />
penampilan dan karakteristik lain yang diharapkan dapat lebih menguntungkan<br />
konsumen.<br />
Proses pengembangan desain sebuah alat mempunyai urutan langkah-<br />
langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah konsep desain<br />
suatu produk adalah sebagai berikut :<br />
1) Pengembangan konsep<br />
Mengindentifikasi kebutuhan target konsumen, mengevaluasi alternatif<br />
konsep dan menentukan konsep tunggal untuk pengembangan lebih lanjut.<br />
2) Desain tahapan sistem<br />
Membuat rancangan produk, geometri produk, pembagian produk menjadi<br />
subsistem dan komponen beserta spesifikasinya dan diagram alir proses<br />
perakitan produk.<br />
67
3) Desain detail<br />
Dokumentasi kontrol untuk produk file yang berisi ukuran setiap komponen,<br />
spesifikasi komponen-komponen yang dibeli, peralatan produksi, dan<br />
perencanaan untuk pabrikasi dan perakitan produk.<br />
4) Pengujian dan perbaikan<br />
Pembuatan prototype misalnya A yang merupakan prototype yang dibuat<br />
dengan menggunakan komponen-komponen dengan bentuk dan jenis<br />
material pada produksi sesungguhnya, namun tidak membutuhkan proses<br />
pabrikasi dengan proses yang sama dengan yang dilakukan pada produksi<br />
yang sesungguhnya; dan (prototype) misalnya B yang dibuat dengan<br />
komponen-komponen yang dibutuhkan pada produksi namun dirakit dengan<br />
menggunakan proses perakitan akhir seperti pada proses perakitan<br />
sesungguhnya. Kedua (prototype) tersebut diuji dengan ketat baik secara<br />
internal maupun diuji oleh konsumen dalam lingkungan pengguna.<br />
5) Produksi Ramp up<br />
Dalam tahap ini produk dibuat dengan sistem produksi yang sebenarnya,<br />
dengan tujuan untuk melatih tenaga kerja dan untuk menyelesaikan<br />
permasalahan yang masih terdapat dalam proses produksi. Dalam fase ini<br />
terdapat launch produc (Ulrich, Karl and Steven, 2001). Lebih jelas tahap-<br />
tahap pengembangan desain alat kerja dapat ditunjukkan pada Gambar 2.14<br />
68
Mission<br />
Statement<br />
Identifikasi<br />
Kebutuhan<br />
Pemakai<br />
Spesifikasi<br />
Target<br />
Analisa<br />
Produk<br />
Pesaing<br />
Menurunkan<br />
Beberapa<br />
Konsep Produk<br />
Gambar 2.14 Tahap-tahap Pengembangan Desain<br />
Analisa<br />
Ekonomi<br />
PENGEMBANGAN KONSEP<br />
Memilih<br />
Konsep<br />
(Sumber : Ulrich; Karl and Steven, 2001).<br />
69<br />
Memperbaiki<br />
Spesifikasi<br />
Merencanakan<br />
Kegiatan dan<br />
Pengembangan<br />
Rencana<br />
Pengembangan
2.12.1 Prinsip ergonomi dalam perancangan alat kerja katrol<br />
Dalam melakukan perancangan alat kerja katrol pada penelitian ini maka<br />
sangatlah penting untuk memperhatikan faktor manusia sebagai faktor utama<br />
didalam perancangan kerja (Wignjosoebroto, 1989) menyatakan bahwa suatu<br />
sistem kerja dimana komponen kerja seperti manusia (operator), mesin dan atau<br />
fasilitas kerja lainnya, material serta lingkungan kerjafisik akan berinteraksi<br />
bersama-sama dalam memberikan hasil kerja.<br />
Komponen tersebut dianalisis guna memperoleh kerja yang sebaik-<br />
baiknya dengan mekanisme sebagai berikut :<br />
a) Komponen manusia yang dianalisis adalah posisi orang pada saat<br />
melaksanakan kerja berlangsung agar mampu memberikan gerakan kerja<br />
yang efektif dan efisien (baik posisi duduk, berdiri, jongkok, membungkuk<br />
dan sebagainya).<br />
b) Komponen material yang dianalisis adalah cara penempatan material, tata<br />
letak dan pemilihan jenis material yang mudah diproses.<br />
c) Komponen mesin yang dianalisis adalah rancangan mesin dan atau peralatan<br />
kerja lainnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip ergonomi.<br />
d) Komponen lingkungan kerja yang dianalaisis adalah kondisi kenyamanan<br />
dan keamanan lingkungan kerja fisik tempat operasi kerja tersebut<br />
dilaksanakan.<br />
e) Sosial-budaya yang dianalisis ialah sikap dan interaksi pekerja dalam<br />
menerima perubahan sistem kerja terutama dalam penggunaan teknologi<br />
baru (Purnomo, 2007).<br />
Dalam perancangan alat katrol peran ergonomi sangat penting untuk<br />
mendapatkan sistem kerja yang ergonomis. Perancangan disebut ergonomis,<br />
70
apabila alat tersebut secara antropometri, faal, biomekanika dan psikologi<br />
berkompatibel dengan manusia sebagai pemakainya. Untuk itu pengetahuan<br />
tentang anatomi manusia, fisiologi dan psikologi sangat dibutuhlan (Bridger,<br />
1995). Selain itu perancangan harus berorientasi pada produksi, distribusi,<br />
instalasioperasi dan pemeliharaan yang mudah dan murah.<br />
Pukat cincin merupakan alat penangkapan ikan dengan sistem kerja yang<br />
sangat mengandalkan keberadaan dan kekuatan fisik manusia sebab pada saat<br />
menarik, cincin dan jaring bertumpuh pada tali sehingga beban tarikan menjadi<br />
semakin berat, cepat lelah dan adanya keluhan muskuloskeletal. Hal ini kalau<br />
dibiarkan maka akan menimbulkan kecelakaan dan cidera akibat kerja.<br />
Upaya pencegahan kecelakaan dan cidera pada proses penangkapan ikan<br />
dengan pukat cincin, maka perlu merancang alat bantu kerja yang ergonomis<br />
dengan tujuan terciptanya keadaan fisik dan psikis nelayan yang sehat dengan<br />
mengupayakan rancangan peralatan, fasilitas dan kondisi kerja yang dapat<br />
menjamin para nelayan terbebas dari kecelakaan yang mengakibatkan cidera dan<br />
penyakit akibat kerja.<br />
Perancangan alat yang ergonomis akan memberikan manfaat (Manuaba,<br />
2000b; 2003a) antara lain : a) pemakaian otot dan energi lebih efisien,<br />
b) pemakaian waktu lebih efisien, c) kelelahan berkurang, d) kecelakaan kerja<br />
berkurang, e) penyakit akibat kerja berkurang, f) kenyamanan dan kepuasan kerja<br />
meningkat, g) efisiensi kerja meningkat, h) mutu produk dan produktivitas kerja<br />
meningkat, i) kesalahan kerja berkurang dan kerusakan kerja dapat<br />
diminimalisasikan, dan j) pengeluaran biaya pengobatan untuk mengatasi<br />
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikurangi dan konsekwensi biaya<br />
operasional dapat ditekan.<br />
71
Dalam penerapan ergonomi beberapa prinsip yang perlu diingat untuk<br />
merancang suatu alat kerja (Adiputra, 2000) mengemukakan sebagai berikut :<br />
a) memaksimalkan teknologi tepat guna, b) menerapkan asaz manajemen<br />
partisipasi; (c) bertahap namun tetap holistik, d) selalu berorientasi pada masalah,<br />
e) biaya murah dan mudah didapat, dan f) tetap menggunakan pendekatan<br />
ergonomi total.<br />
Dari kajian ilmiah ini diharapkan semaksimal mungkin sistem kerja yang<br />
dihasilkan akan mampu menjamin kesehatan, kenyamanan dan keselamatan kerja.<br />
(Adiputra, 2003). Menyatakan pertama-tama desainer menentukan produk alat<br />
yang akan dirancang (need), dilanjutkan dengan pengembangan ide (idea), setelah<br />
diperoleh ide dilakukan penilaian dan pemilihan alternatif, sehingga didapatkan<br />
keputusan yang menghasilkan rencana desain yang optimal (decision), langkah<br />
terakhir adalah penanganan (action).<br />
Tahapan pembuatan desain alat kerja katrol sebagai berikut :<br />
1) Pembuatan desain, termasuk juga komponen-komponen pendukungnya<br />
terdiri dari tahapan berikut.<br />
a) Desain bentuk keseluruhan alat yang ergonomi<br />
b) Spesifikasi fungsionalnya dari alat katrol ini memiliki 3 bagian penting<br />
yaitu : penahan atau pengalas kaki, penggulungan penarikan, setting<br />
bagian rangka. Seperti tampak pada Gambar 2.15., 2.16., dan 2.17.<br />
Gambar 2.15 Tampak samping kanan alat katrol pukat cincin<br />
72
2) Pengujian prototype, dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang<br />
dirancang sesuai dengan antropometri nelayan pukat cincin yang akan<br />
menggunakan alat tersebut. Data pengukuran antropometri tubuh (cm) yang<br />
akan diukur dalam penelitian ini adalah tinggi badan, tinggi siku, jangkauan<br />
tangan, keliling lingkaran genggam tangan, tinggi bahu, lebar bahu dan<br />
jarak genggam tangan kedepan dalam posisi duduk. Data antropometri<br />
tersebut dihitung berdasarkan persentil 5, 50 dan 95. Sedangkan data<br />
pengukuran bentuk dan ukura alat katrol adalah sebagai berikut.<br />
a) Bentuk dan ukuran alat, apakah telah sesuai<br />
b) Pengujian alat ini, apakah dapat berfungsi seperti keinginan nelayan<br />
pemakai<br />
c) Pengukuran kecepatan waktu yang dibutuhkan pada saat penggunaan<br />
alat tersebut.<br />
Gambar 2.16 Tampak belakang alat katrol pukat cincin<br />
73
Gambar 2.17 Tampak depan alat katrol pukat cincin<br />
3) Kebutuhan bahan dan estimasi biaya<br />
Kebutuhan dan jenis bahan kayu dan perhitungan biaya yang diperlukan<br />
untuk pembuatan alat kerja katrol ini sebagai berikut :<br />
Tabel 2.3<br />
Kebutuhan Bahan dan Estimasi Biaya<br />
No. Jenis Bahan Kuantitas Harga<br />
01 Besi bulat berdiameter 80 2 unit Rp. 500.000,-<br />
02 Besi bulat berukuran 5,8 cm<br />
- Tinggi 48 cm<br />
- Lebar 45 cm<br />
- Tebal 50 cm<br />
- Panjang 60 cm<br />
8 saf/ujung Rp. 400.000,-<br />
03 Mur (disesuaikan dengan ukuran baut) 16 buah Rp. 120.000,-<br />
04 Gigi engsel 50 buah Rp. 100.000,-<br />
05 Paku 10 cm, 5 cm, 3 cm 5 kg Rp. 80.000,-<br />
06 Cat besi berwarna 5 kg Rp. 100.000,-<br />
07 Tenaga kerja dll 3 orang Rp. 500.000,-<br />
Total Rp.1.800.000,-<br />
2.12.2 Prinsip ergonomi dalam perancangan tempat duduk<br />
Posisi duduk membutuhkan energi yang lebih kecil bila dibandingkan<br />
dengan posisi berdiri, tetapi posisi duduk tidak fisiologis menyebabkan gangguan<br />
74
pada (diskus intervertebralis). Pada posisi duduk tekanan pada (diskus<br />
intervertebralis) lebih besar dibandingkan dengan posisi berdiri. Posisi duduk<br />
yang benar mempunyai keuntungan antara lain : mengurangi pengeluaran energi,<br />
melancarkan aliran darah, dan mengurangi tekanan antara ruas tulang punggung.<br />
Sikap duduk tang salah dapat menyebabkan keluhan pada kepala, leher, bahu,<br />
pinggang, panatat, lengan atas, paha, lutut dan kaki (Grandjean, 2000)<br />
Pada posisi duduk otot mengalami pembebanan secara statis. Beban otot<br />
statis terjadi ketika otot dalam keadaan tegang (tension) tanpa menghasilkan<br />
gerakan tangan atau kaki sekalipun. Tegangnya otot sebenarnya terjadi pada<br />
kondisi menahan beban tubuh. Pada sikap duduk yang tidak fisiologis otot-otot<br />
tertentu akan terus bekerja dalam upaya memberi reaksi pada gaya-gaya gravitasi.<br />
Jadi terdapat hubungan antara tingkat usaha (level effort) yang diberikan dengan<br />
lamanya usaha (effort duration) (Pulat, 1992). Sebuah konsep ergonomi adalah<br />
duduk yang lebih baik akan memberikan manfaat antara lain : sikap duduk tegak<br />
dengan sandaran belakang dan lengan bawah, sudut yang dibentuk oleh abdomen<br />
dan paha diperbesar sehingga tulang belakang menjadi tegak.<br />
Perancangan tempat duduk memerlukan beberapa data antropometri untuk<br />
menentukan dimensi bagian-bagian tempat duduk. Beberapa dimensi tempat<br />
duduk yang harus diperhatikan dalam proses perancangan yang ergonomis yaitu :<br />
(a) tinggi tempat duduk; (b) kedalaman/panjang tempat duduk; (c) lebar tempat<br />
duduk; (d) sudut alas duduk. Bila tempat duduk tidak dirancang secara ergonomis,<br />
maka akan menyebabkan pekerja membungkukkan badan sehingga tulang<br />
belakang akan menekuk ke depan yang akan berakibat terjadinya sakit pada otot,<br />
leher dan bahui serta pinggang atau punggung (Sanders & McCormic, 1987).<br />
75
2.12.3 Prinsip ergonomi dalam kondisi sosial budaya<br />
Kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir pantai dalam banyak hal,<br />
mereka telah membentuk sebuah lingkungan permukiman sendiri dan memeliki<br />
sosio-budaya yang khas yaitu berburu dan menangkap ikan (hunting and fisihing)<br />
sebagai proses adaptasi terhadap habitat dekat pantai dan sekaligus menyatu<br />
dengan laut dan dalam kehidupannya mereka membentuk tradisi yang diwariskan<br />
secara terus menerus dari generasi ke generasi.<br />
Dari hasil pengamatan didapati bahwa kehidupan nelayan pukat cincin<br />
dalam sistem pembagian hasil tangkapan sering terjadi hubungan tidak harmonis<br />
oleh karena masih mengikuti pola kelembagaan tradisi masyarakat pantai dengan<br />
kebiasaan menggunakan hukum adat tidak tertulis (konvensi) yaitu: (a) isteri dan<br />
anak tidak dilibatkan dalam proses penangkapan ikan; (b) hubungan antar<br />
keluarga sering terjadi mis komunikasi; (c) secara individu tidak dapat<br />
mempengaruhi harga ikan di pasar.<br />
Prinsip ergonomi dalam kehidupan sosial budaya di tempat kerja<br />
menambahkan terciptanya suasana damai, senang, tenang, rasa aman dan nyaman<br />
dalam bekerja. Rasa nyaman di lingkungan kerja, dipengaruhi oleh faktor<br />
lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pekerja akan merasa<br />
nyaman bila lingkungan kerja, hubungan antar keluarga (suami, istri dan anak),<br />
hubungan antar pekerja, hubungan antar atasan dan bawahan berlangsung<br />
harmonis. Harmonisasi lingkungan dapat menyebabkan pekerja lebih<br />
berkonsentrasi pada tugasnya masing-masing sehingga efisiensi tercapai dan<br />
akhirnya pencapaian produktivitas bisa optimal (Manuaba, 2006; Manuaba, 2003).<br />
76
2.12.4 Prinsip ergonomi dalam manusia-mesin<br />
Keserasian antar manusia dan mesin sangat dibutuhkan untuk menjamin<br />
bahwa proses kerja dapat mencapai hasil yang optimal. Penerapan ergonomi<br />
dalam hal perancangan alat kerja yang merupakan aktivitas rancang bangun<br />
(desain) dan atau rancang ulang (redesain) yang disesuaikan dengan kemajuan<br />
teknologi dengan tanpa melupakan unsur anatomi, psikologi, lingkungan dan<br />
kesehatan kerja (Adiputra, 2003). Untuk memudahkan proses perancangan atau<br />
perbaikan suatu produk atau alat bantu kerja, maka diperlukan pemahaman<br />
tentang antropometri, yaitu : Ilmu yang mempelajari proporsi ukuran dari setiap<br />
bagian tubuh manusia (Pulat, 1992). Data ukuran tubuh ini digunakan untuk<br />
menentukan dimensi atau ukuran alat dan perlengkapan kerja sehingga tercipta<br />
keserasian antar alat dengan pemakainya (Manuaba, 2003; Sutjana, 2005;<br />
Grandjean, 2003).<br />
Menurut Phesant (1988), ada 3 informasi penting yang diperlukan untuk<br />
dapat memilih ukuran terbaik yang menciptakan keserasian antara pekerja dengan<br />
mesin yaitu : 1) karakteristik ukuran tubuh dari populasi pengguna/pekerja,<br />
2) bagaimana karakteristik ukuran tubuh tersebut memberikan rasa nyaman dalam<br />
bekerja, 3) kriteria tentang keserasian yang efektif antara hasil rancangan dengan<br />
pengguna. Atas dasar teori tersebut, maka interaksi manusia mesin<br />
memperhatikan kesesuaian alat ataufasilitas kerja dengan pekerja, interaksi antar<br />
pekerja dengan fasilitas kerja yang digunakan untuk bekerja, agar pekerja lebih<br />
mudah dan aman untuk mengoperasikan alat-alat yang digunakan.<br />
77
2.13 Tujuan dan Manfaat Kinerja<br />
Performance sering diartikan sebagai suatu kinerja, hasil kerja atau<br />
prestasi kerja seseorang yang mempunyai hubungan dengan pencapaian tujuan<br />
organisasi dan kepuasan konsumen yang memberikan kontribusi positif terhadap<br />
peningkatan kerja. Kinerja berhubungan pula dengan apa yang dikerjakan dan<br />
bagaimana mengerjakannya (Amstrong and Baron, 1998). Faktor yang<br />
berpengaruh terhadap kinerja adalah kualitas sumber daya manusia sebagai<br />
tuntutan yang digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan dalam<br />
melaksanakan tugas dan pekerjaan, prilaku pekerja dan hasil capaian kerja (Rivai,<br />
2005).<br />
Pandangan ergonomi terhadap kinerja sumber daya manausia adalah<br />
tuntutan tugas, motivasi kerja dan kemampuan menghadapi (complexity,<br />
competition and chage – 3C) (Manuaba, 2004a) menyatakan bahwa hal yang<br />
sangat mendasar yang harus dihadapi manusia adalah kopleksitas tugas<br />
pekerjaan, memenangkan kompetisi dan sikap manusia menerima perubahan,<br />
hasil dari perubahan dapat terjadi secara outomatisasi, informasi, transformasi<br />
dan substitusi sebagai salah satu jawaban keinginan untuk memperbaiki diri.<br />
Tujuan dan manfaat dari kinerja yaitu untuk melakukan penilaian<br />
terhadap capaian hasil kerja berdasarkan tuntutan tugas yang dipengaruhi oleh<br />
karakteristik pekerjaan task, lingkungan, (environment), dan organisasi<br />
(organization) dimana pekerjaan itu dilakukan sehingga tercapai kondisi kerja<br />
yang sehat, aman, nyaman, efisien, efektif dan produktif yang pada akhirnya<br />
78
ermuara pada peningkatan kualitas penampilan kinerja dan keuntungkan<br />
perusahaan (Manuaba, 2000., Grandjean 1993).<br />
2.14 Indikator Penilaian Kinerja<br />
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional<br />
suatu organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang<br />
telah diterapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001) lebih lanjut pengukuran penilaian<br />
kinerja merupakan proses dan mengukur pencapaian dan pelaksanaan kegiatan<br />
dalam arah pencapian misi (mission accoplishment) melalui hasil-hasil yang<br />
ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.<br />
Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara :<br />
1) memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi,<br />
2) mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan,<br />
3) mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja,<br />
4) menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu<br />
prioritas perhatian, 5) menghindari konsekuensi dan rendahnya kualitas,<br />
6) mempertimbangkan penggunaan sumber daya; dan (7) mengusahakan umpan<br />
balik untuk mendorong perbaikan.<br />
Indikator pengukuran kinerja adalah merupakan penilaian secara kualitatif<br />
maupun secara kuantitatif yang dapat memberikan gambaran-gambaran baik-<br />
buruk apakah segala komponen organisasi telah berjalan sesuai dengan yang<br />
digariskan dan penilaian kinerja adalah untuk mencapai tujuan organisasi,<br />
sehingga karyawan termotivasi dalam mematuhi standar prilaku yang telah<br />
ditetapkan sebelumnya (berupa kebijakan manajemen/rencana formal yang<br />
79
dituangkan dalam anggaran) agar membutuhkan tindakan dan hasil yang<br />
diinginkan (Setyawan, 2001).<br />
Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat obyektif sehingga<br />
diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama diharapkan<br />
memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara obyektif dan adil. Kriteria<br />
suatu ukuran kinerja menurut (Amstrong dan Baron, 1998) seharusnya yaitu : a)<br />
dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara organisasional<br />
penting dan mendorong kinerja bisnis, b) relevan dengan sasaran dan<br />
akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan, c) memfokuskan pada<br />
output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan<br />
bagaimana tingkalaku mereka, d) mengindikasi data yang akurat dan terukur<br />
sebagai dasar pengukuran, e) dapat didiverifikasi, dengan mengusahakan<br />
informasi yang akan mengonfirmasi tingkat seberapa jauh harapan yangdapat<br />
dipenuhi.<br />
Indikator penilaian kinerja yaitu : 1) beban kerja, 2) kelelahan, dan<br />
3) keluhan muskuloskeletal yang dapat diuraikan sebagai berikut.<br />
2.15 Beban Kerja (Workload)<br />
Beban kerja pada operasi penangkapan ikan sangatlah berat oleh karena<br />
aktivitas tubuh pada saat menarik pukat cincin semakin tinggi menyebabkan<br />
metabolisame tubuh semakin meningkat sehingga kebutuhan oksigen semakin<br />
besar dan frekuensi denyut nadi semakin besar pula (Adiputra, 2002). Dari<br />
pendekatan ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus<br />
sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif<br />
maupun keterbatasan manusia yang menerima beban kerja tersebut. Oleh karena<br />
80
setiap orang kemampuan dan kebolehan kerja berbeda-beda satu dengan yang<br />
lain. Menurut (Suma’mur, 1982) kemampuan tenaga kerja seseorang berbeda<br />
dan sangat tergantung pada tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, keadaan<br />
gizi, jenis kelamin, usia dan ukuran postur tubuh dari pekerja yang bersangkutan.<br />
(Rodahl, 1989) mengemukakan bahwa hubungan antara beban kerja dan<br />
kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik<br />
eksternal maupun internal.<br />
1) Beban kerja eksternal (external load) mencakup :<br />
a) tugas task, yang dilakukan baik yang bersifat fisik seperti : sarana kerja,<br />
kondisi kerja, sikap kerja maupun yang bersifat mental yaitu kopleksitas<br />
pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi kerja.<br />
b) organisasi sistem kerja meliputi : jam kerja, waktu istirahat, upah, kerja<br />
tim, jadwal kerja.<br />
c) lingkungan kerja meliputi: suhu, kebisingan, getaran, kelembaban,<br />
kecepatan udara, intensitas cahaya dan polusi.<br />
2) Beban kerja internal (Internal load) mencakup:<br />
a) faktor somatis meliputi: jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi<br />
kesehatan, status gizi; serta<br />
b) faktor psikis motivasi, persepi, kepercayaan, keinginan, harapan, norma<br />
adat dan budaya, tabu, ketegangan akibat manajemen.<br />
2.15.1 Penilaian Beban Kerja<br />
Rodahl, (1989) mengemukakan penilaian beban kerja fisik dapat<br />
dilakukan dengan dua metode yang secara obyektif yaitu metode penilaian<br />
langsung maupun metode penilaian tidak langsung. Metode penilaian langsung<br />
yaitu dengan mengukur energi ying dikeluarkan (energy expenditure) melalui<br />
81
asupan oksigen selama bekerja. Semakin berat beban kerja akan semakin banyak<br />
energy yang dikonsumsi. Meskipun metode dengan menggunakan asupan oksigen<br />
lebih akurat, namun hanya dapat mengukur untuk waktu kerja yang singkat dan<br />
diperlukan peralatan yang cukup mahal. Sedangkan metode penilaian tidak<br />
langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama bekerja. (Christensen,<br />
1991 and Grandjean, 1993) menjelaskan bahwa salah satu pendekatan untuk<br />
mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung nadi kerja,<br />
konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi paru dan suhu inti tubuh. Pada batas tertentu<br />
ventilasi paru, denyut jantung dan suhu mempunyai hubungan yang linier dengan<br />
konsumsi oksigen atau pekerjaan yang dilakukan.<br />
Kategori berat ringannya beban kerja didasarkan pada metabolisme,<br />
respirasi, temperatur dan denyut jantung (Christensen, 1991). Seperti pada<br />
Tabel 2.4<br />
Tabel 2.4<br />
Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi,<br />
Kategori beban kerja<br />
Temperatur dan Denyut Jantung.<br />
Konsumsi<br />
Oksigen<br />
1/min<br />
Ventilasi<br />
paru<br />
1/min<br />
Suhu<br />
Rektal<br />
(°C)<br />
82<br />
Denyut<br />
jantung<br />
(Denyut/Min)<br />
Sangat ringan 0,25 – 0,3 06 – 07 37,5 60 - 70<br />
Ringan 0,50 – 1,0 11 – 20 37,5 75 - 100<br />
Sedang 1,0 – 1,5 20 – 31 37,5 - 38,0 100 - 125<br />
Berat 1,5 – 2,0 31 – 43 38,0 - 38,5 125 - 150<br />
Sangat berat 2,0 – 2,5 43 – 56 38,5 - 39,0 150 - 175<br />
Sangat berat sekali 2,5 – 4,0 60 - 100 > 39,0 > 175
2.15.2 Denyut Nadi sebagai Alat Ukur Beban Kerja<br />
Pengukuran denyut nadi selama nelayan melaksanakan kegiatan<br />
penangkapan ikan merupakan metode untuk menilai cardiovascular. Salah satu<br />
cara yang dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi dengan menggunakan<br />
metode 10 denyut meraba denyut nadi pada arteri radialis tangan kiri dan dicatat<br />
secara manual memakai stop watch (Kilbon, 1992). Pengunaan nadi kerja untuk<br />
menilai berat ringannya beban kerja mempunyai beberapa keuntungan. Selain<br />
mudah, cepat dan murah juga tidak diperlukan peralatan yang mahal, hasilnya<br />
cukup reliabel. Di samping itu tidak terlalu menganggu proses kerja dan tidak<br />
menyakiti orang yang diperiksa. Denyut nadi akan segera berubah seirama<br />
dengan perubahan pembebanan, baik yang berasal dari pembebanan mekanik,<br />
fisika maupun kimiawi (Grandjean, 1993) mengemukakan denyut nadi yang<br />
perlu dihitung untuk mengestimasi indek beban kerja fisik adalah sebagai<br />
berikut.<br />
1) Denyut nadi istirahat adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai<br />
2) Denyut nadi kerja adalah rerata denyut nadi selama bekerja<br />
3) Nadi kerja adalah perbedaan antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi<br />
kerja<br />
4) Total denyut nadi pemulihan adalah jumlah denyutan nadi dari pekerjaan<br />
dihentikan sampai denyutan kembali ke level istirahat.<br />
5) Total nadi kerja adalah jumlah denyutan nadi dari mulai kerja sampai<br />
istirahat.<br />
Selanjutnya, (Grandjean, 1998) menggolongkan beban kerja berdasarkan<br />
denyut nadi seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.5<br />
83
Tabel 2.5<br />
Menggolongkan Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi<br />
No. Kategori Beban Kerja Rentangan denyut nadi/menit<br />
1 Sangat rendah = istirahat 60 – 70<br />
2 Ringan 75 – 100<br />
3 Sedang 100 – 125<br />
4 Berat 125 – 150<br />
5 Sangat Berat 150 – 175<br />
6 Luar Biasa Beratnya > 175<br />
2.15.3 Faktor Penilaian Beban Kerja<br />
Faktor penilaian untuk menurunkan beban kerja, ada dua kriteria yang<br />
dapat dipakai (Rodahl, 1989) antara lain adalah sebagai berikut.<br />
1) Kriteria objektif; yang dapat diukur dan dilakukan oleh pihaklain yang<br />
meliputi: reaksi fisiologis, reaksi psikologis dan perubahan tindak tanduk<br />
2) Kriteria subjektif; yang dilakukan orang yang bersangkutan sebagai<br />
pengalaman pribadi, misalnya beban kerja yang dirasakan sebagai kelelahan<br />
yang menggangu, rasa sakit atau pengalaman lain yang dirasakan.<br />
Penilaian beban kerja secara objektif yang paling mudah dan murah,<br />
secara kuantitatif dapat dipercaya akurasinya adalah pengukuran frekuensi denyut<br />
nadi. Frekuensi denyut nadi dari keseluruhan jam kerja, selanjutnya dipakai dasar<br />
penilaian beban kerja fisik, karena perubahan rerata denyut nadi berhubungan<br />
liner dengan pengambilan oksigen. Hal ini merupakan refleksi dari proses reaksi<br />
(strain) terhadap (stressor) yang diberikan oleh tubuh, dimana biasanya besar<br />
(strain) berbanding lurus dengan (stress).<br />
84
Penilaian beban kerja secara subjektif dapat dilakukan dengan<br />
menggunakan kuesioner, dimana dengan kuesioner tersebut akan terlihat tanda-<br />
tanda yang menyatakan adanya suatu kelelahan yang dialami orang akibat beban<br />
kerja yang membebaninya, oleh karena interaksi pekerja dengan jenis pekerjaan,<br />
tempat kerja, organisasi/cara kerja, peralatan kerja dan lingkungannya (Bridger,<br />
1995). Penilaian beban kerja pada proses penangkapan ikan dapat dilihat pada<br />
beberapa variabel seperti pemakaian O2, penggunaan kalori dan denyut nadi.<br />
Salah satu cara dalam menentukan konsumsi kalori atau pengarahan tenaga kerja<br />
untuk amengetahui derajat beban kerja adalah perhitungan denyut nadi kerja, yaitu<br />
rerata denyut nadi selama bekerja. Berdasarkan pemakaian O2, konsumsi kalori,<br />
denyut nadi dan tingkat beban kerja dibedakan untuk kondisi istirahat, beban kerja<br />
sangat ringan, ringan, agak berat, berat, sangat berat dan luar biasa berat (Sanders<br />
and McCormick, 1987). Cara lain untuk menentukan penilaian klasifikasi beban<br />
kerja fisik pada proses kerja penangkapan ikan adalah klasifikasi yaitu klasifikasi<br />
beban kerja fisik berdasarkan beban (cardiovascular) yang dihitung berdasarkan<br />
data denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja dan nadi kerja maksimum 8 jam kerja<br />
(Intaranot and Vanwonterghem, 1993., Suyasning, 1998).<br />
2.16 Kelelahan Kerja<br />
Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh<br />
terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat.<br />
Istilah kelelahan biasanya menunjukkan pada kondisi yang berbeda-beda pada<br />
setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan<br />
85
penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh (Grandjean, 1993). Kelelahan<br />
diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum.<br />
Kelelahan otot merupakan remor pada otot atau perasaan nyerih pada otot.<br />
Sedangkan kelalahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemampuan<br />
untuk bekerja yang disebabkan oleh karena monotoni, intensitas dan lamanya<br />
kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status, kesehatan dan<br />
keadaan gizi. Secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan<br />
sampai perasaan yang sangat melelahkan. (Pulat, 1992) menyatakan secara umum<br />
gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai perasaan yang<br />
sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya terjadi pada akhir jam kerja,<br />
apabila rata-rata beban kerja melebihi 30% - 40% dari tenaga aerobik maksimal.<br />
2.16.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya kelelahan<br />
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja bervariasi,<br />
untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan dan efisiensi, maka proses<br />
penyegaran harus dilakukan diluar tekanan cancel out the stress (Grandjean,<br />
1993). Penyegaran terjadi terutama selama waktu tidur malam, tetapi periode<br />
istirahat dan waktu-waktu berhenti kerja dapat memberikan penyegaran.<br />
Kelelahan yang disebabkan oleh karena kerja statis berbeda dengabn kerja<br />
dinamis. Pada kerja otot statis dengan pengarahan tenaga 50 % dari kekuatan<br />
maksimum otot hanya dapat bekerja selama satu menit, sedangkan pada<br />
penyegaran tenaga < 20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama, tetapi<br />
penyegaran otot statis sebesar 15 – 20 % akan menyebabkan kelelahan dan nyeri<br />
jika perbedaan langsung sepanjang hari. Astrand and Rodahl (1977)<br />
86
mengemukakan bahwa kerja dapat dipertahankan beberapa jam perhari tanpa<br />
gejala kelelahan jika tenaga yang dikerahkan tidak melebihi 80 % dari maksimum<br />
tenaga otot. Lebih lanjut (Grandjean, 1993); juga menyatakan bahwa kerja otot<br />
statis merupakan kerja berat strenous, kemudian mereka membandingkan antara<br />
kerja otot statis dan dinamis. Pada kondisi yang hampir sama, kerja otot statis<br />
mempunyai konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat dan diperlukan<br />
waktu istirahat yang lebih lama.<br />
2.16.2 Pengukuran Kelelahan<br />
Mengukur kelelahan menurut Grandjean (1993) dapat dilakukan dengan<br />
metode sebagai berikut.<br />
1) Pengukuran kuantitas dan kualitas kerja.<br />
2) Keluhan subjektif.<br />
3) Electroensefalograph (EEG).<br />
4) Tremor detector; sebagai tes psikomotorik.<br />
5) Flicker fusion.<br />
6) Tes mental<br />
Salah satu cara untuk mengukur keluhan subjektif menurut Adiputra<br />
(1998) dapat digunakan kuesioner 30 item (self rating test), skala empat yang<br />
dikeluarkan oleh (Japan Association Industrial Health) (JAIH) yang berisi daftar<br />
gejala-gejala yang berhubungan dengan kelelahan yang ditanyakan kepada subjek<br />
dan diisi secara subjektif sesuai dengan apa yang dirasakannya dan dilakakuan<br />
setelah selesai bekerja. Substansi dimensionalnya meliputi : a) adanya pelemahan<br />
aktivitas item 1-10, b) adanya pelemahan motivasi item 11-20, c) adanya<br />
87
kelelahan fisik akibat kelelahan secara umum item 21-30. Dan disamping juga<br />
disebabkan oleh karena jenis pekerjaan, kelelahan juga terjadi karena keadaan<br />
lingkungan kerja yang tidak nyaman, aman dan sehat.<br />
2.17 Gangguan Muskuloskeletal<br />
Keluhan kerja akibat gangguan sistem muskuloskeletal nelayan pada saat<br />
proses penangkapan ikan adalah lebih banyak melibatkan bagian-bagian otot<br />
skeletal mulai dari penawuran jaring sampai pada penarikan tali pukat cincin.<br />
Keluhan yang sering dirasakan setelah selesai kerja khususnya sakit pada<br />
pergelangan tangan kanan dan kiri, sakit pada punggung, sakit pada pinggang,<br />
sakit pada pantat, lutut dan sakit pada kaki kiri dan kanan. Metode subjektif untuk<br />
menilai keluhan otot skeletal adalah dengan menggunakan (Nordic Body Map)<br />
baik (rating) maupun (ranking). Prosedur menggunakan mapping untuk menilai<br />
keluhan otot skeletal tersebut dapat dilakukan pada interval selama keseluruhan<br />
jam akerja dan istirahat. Subjek ditanya pada bagian-bagian anggota tubuh yang<br />
mengalami sakit atau ketidak nyamanan melalui kuesioner pada 4 skala likert<br />
(Corlett, 1992).<br />
Secara garis besar keluhan muskuloskeletal dapat dikelompokkan menjadi<br />
dua bagian besar yaitu keluhan sementara dan keluhan menetap. Keluhan otot<br />
sementara adalah keluhan yang terjadi pada saat otot menerima beban statis dan<br />
segera hilang apabila pemberian beban dihentikan. Sedangkan keluhan otot<br />
menetap adalah keluhan yang bersifat lebih permanen dan rasa sakit pada otot<br />
tidak hilang meskipun pemberian beban dihentikan (Grandjean, 1993). Keluhan<br />
88
subjektif akibat kerja berhubungan erat dengan reaksi perasaan individu terhadap<br />
pengalaman kerjanya (Adiputra, 1998b)<br />
Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan<br />
keluhan muskuloskeletal atau cedera pada sistem muskuloskeletal (Grandjean,<br />
1993). Keluhan pada sistem muskuloskeletal disebabkan karena , 1) memaksakan<br />
beban yang terlalu berat, 2) gerakan tertentu yang berulang, 3) sikap tubuh ketika<br />
duduk, berdiri dan melakukan aktivitas, 4) menggunakan teknik pengangkatan<br />
yang salah, dan 5) tekanan kerja (Cani-news, 2006; HSE, 2006). Beberapa alat<br />
ukur ergonomi yang sering digunakan antara lain adalah sebagai berikut:<br />
1) Model biomekanik adalah model yang menerapkan konsep mekanika teknik<br />
pada fungsi tubuh untuk mengetahui reaksi otot yang terjadi akibat tekanan<br />
beban kerja (Chaffin and Andersons, 1991).<br />
2) Tabel psikofisik merupakan penilaian berdasarkan pada ilmu psikologi yang<br />
digunakan untuk mengevaluasi pemindahan material secara manual tentang<br />
berapa banyak kapasitas pekerja dalam mengangkat, menurunkan,<br />
mendorong, menarik dan membawa beban (Snook, 2005).<br />
3) Model flsik merupakan suatu metode untuk mengetahui sumber keluhan<br />
otot dapat dilakukan secara tidak langsung dengan mengukur tingkat beban<br />
kerja. Tingkat beban kerja dapat diketahui melalui indikator denyut nadi,<br />
konsumsi oksigen dan kapasitas paru. Melalui indikator tingkat beban kerja<br />
dapat diketahui tingkat risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal<br />
(Christensen, 1991).<br />
4) Pengukuran dengan (videotape) adalah analisis (videotape) yang dilakukan<br />
89
dengan menggunakan (video camera). Melalui video camera dapat direkam<br />
setiap tahapan aktivitas kerja, selanjutnya hasil rekaman ini digunakan<br />
sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap sumber terjadinya keluhan<br />
otot (Rodgers, 2005).<br />
5) Pengukuran melalui monitor merupakan pengukuran berbagai aspek dari<br />
aktivitas fisik yang meliputi posisi, kecepatan dan percepatan gerakan.<br />
Sistem ini terdiri dari sensor mekanik yang dipasang pada bagian tubuh<br />
pekerja. Melalui monitor dapat dilihat secara langsung karakteristik dari<br />
perabahan gerak yang dapat digunakan untuk mengestimasi risiko keluhan<br />
otot yang akan terjadi sekaligus dapat dianalisis solusi ergonomi yang tepat<br />
untuk mencegah terjadinya keluhan tersebut (Waters and Putz-Anderson,<br />
1996a).<br />
6) Metode analitik merupakan metode analitik yang direkomendasikan oleh<br />
NIOSH untuk pekerjaan mengangkat. (NIOSH) memberikan cara sederhana<br />
untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya peregangan otot yang<br />
berlebihan (over exertiori) atas dasar karakteristik pekerjaan, yaitu dengan<br />
menghitung (Recommended Weight Limit. RWL) dan (Lifting Index. LI).<br />
RWL adalah berat beban yang masih aman untuk dikerjakan oleh pekerja<br />
dalam waktu tertentu tanpa meningkatkan risiko gangguan sakit pinggang<br />
(Waters and Putz-Anderson, 1996b).<br />
7) (Nordic Body Map) (NBM) adalah penilaian subjektif dengan menggunakan<br />
peta tubuh untuk mengetahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan<br />
dengan tingkat keluhan mulai dari rasa agak sakit sampai sakit. Dengan<br />
90
melihat dan menganalisis peta tubuh maka dapat diestimasi jenis dan tingkat<br />
keluhan otot yang dirasakan oleh pekerja (Corlett, 1992).<br />
8) (Quick Exposure Checklist. QEC) adalah penilaian objektif terhadap risiko<br />
cedera di tempat kerja terhadap keluhan muskuloskeletal. QEC didasarkan<br />
pada kebutuhan praktis dan riset terhadap faktor risiko. Prosedur dalam<br />
penggunaan QEC adalah : a) pengguna harus paham tentang kategori<br />
penilaian yang digunakan dalam checklist, b) penilaian peneliti berdasarkan<br />
pada checklist, c) penilaian pekerja yang didasarkan pada checklist, d)<br />
menghitung skor, e) mempertimbangkan tindakan (Li and Buckle, 2005).<br />
Keluhan otot skeletal dapat terjadi karena adanya sikap kerja yang tidak<br />
alamiah oleh karena ketidakserasian hubungan antara alat kerja dengan ukuran<br />
tubuh pemakainya (Phesant, 1988 and Manuaba, 2000). Keluhan muskuloskeletal<br />
berhubungan erat dengan pekerjaan tangan secara berulang-ulang dan merupakan<br />
penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan dan ketidak mampuan kerja<br />
(worker impairment and disability) (Armstrong, 2003). Penilaian keluhan<br />
subjektif individu merupakan hal yang tidak dapat diabaikan untuk memahami<br />
beban kerja secara menyeluruh. Di samping itu pengetahuan tentang penilaian<br />
subjektif sangat berguna untuk mendeteksi masalah-masalah yang timbul sebagai<br />
akibat kondisi kerja (Vanwonterghem, 1995).<br />
Dalam melakukan pekerjaan, otot memegang peranan utama diantara<br />
sekian banyak otot-otot skeletal yang paling banyak berperan dalam setiap<br />
pergerakan aktivitas. Keluhan Muskuloskeletal terjadi dalam tiga tahap yaitu : a)<br />
tahap pertama biasanya terasa sakit ringan atau terasa lelah, b) tahap kedua terasa<br />
91
sakit agak berat khususnya pada malam hari, c) tahap ketiga terasa sakit yang<br />
cukup berat (Annim, 2006). Keluhan pada sistem muskuloskeletal dipengaruhi<br />
oleh adanya kerja otot yang bekerja tidak secara normal akibat dari sikap kerja<br />
yang tidak alamiah. Dampaknya dapat menimbulkan kenyerian otot dan rasa tidak<br />
nyaman (Chaffin, 2003). Sikap kerja membungkuk dan pembebanan yang tidak<br />
simetris dapat menyebabkan cidera dan kenyerian pada otot bagian belakang<br />
(Bridger, 1995). Menyatakan bahwa rasa tidak nyaman bisa terjadi karena adanya<br />
tekanan pada jaringan yang lembut yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran<br />
darah ke jaringan, sehingga menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan<br />
menumpuknya karbon dioksida dan terjadinya penimbunan asam laktat.<br />
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan<br />
muskuloskeletal antara lain (MacLeod, 1995; Tayyari and Smith, 1997)<br />
mengemukakan sebagai berikut :<br />
1) Peregangan otot yang berlebihan (over exertion)<br />
Peregangan otot yang berlebihan pada umumnya sering dikeluhkan<br />
pekerja dimana aktivitas kerjanya menuntut pengerahan tenaga yang besar<br />
seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban yang<br />
berat.<br />
2) Aktivitas berulang<br />
Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus<br />
menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, mengangkat<br />
dan sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat<br />
beban kerja secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan relaksasi.<br />
92
3) Sikap kerja tidak fisiologis atau alamiah<br />
Sikap kerja tidak fisiologis atau alamiah adalah sikap kerja yang<br />
menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah,<br />
misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk,<br />
kepala terangkat dan sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari<br />
pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya keluhan<br />
otot skeletal.<br />
4) Faktor penyebab sekunder<br />
Faktor penyebab sekunder seperti adanya tekanan langsung pada<br />
jaringan otot lunak, getaran dengan frekuensi tinggi, mikroklimat baik<br />
dalam suhu yang dingin maupun panas.<br />
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa berat ringannya beban kerja<br />
dan keluhan muskuloskeletal yang dialami oleh pekerja selain dipengaruhi oleh<br />
faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu task, organisasi kerja<br />
dan lingkungan kerja.<br />
2.18 Peningkatan Kesejahteraan<br />
Pada masyarakat nelayan pola adaptasinya dengan ekosistem lingkungan<br />
fisik laut dan lingkungan sosial di sekitarnya adalah tergantung pada perubahan-<br />
perubahan yang salah satunya adalah perubahan strategi mata pencaharian. Bagi<br />
masyarakat nelayan, lingkungan fisik laut sangatlah mengandung banyak bahaya<br />
dan dalam banyak hal mengandung risiko kecelakaan karena pekerjaan nelayan<br />
adalah memburuh dan menangkap ikan, hasilnya tidak dapat ditentukkan dan<br />
93
penuh dengan ketidakpastian, semuanya hampir serba spekulatif karena laut<br />
adalah wilayah yang dianggap bebas untuk dieksploitasi common property milik<br />
bersama.<br />
Pemahaman tingkat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan bervariasi.<br />
Dilihat dari segi pendapatan usaha nelayan, bahwa kesejahteraan adalah besarnya<br />
hasil atau keuntungan yang diperoleh nelayan dari satu trip penangkapan. Bentuk<br />
dan jumlah pendapatan dalam usaha perikanan mempunyai fungsi yang sama<br />
yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan memberikan kepuasan bagi nelayan<br />
agar dapat melanjutkan kegiatannya (Mulyadi, 2005) menyatakan kesejahteraan<br />
merupakan adaptasi tingkalaku dalam upaya memaksimalkan kesempatan untuk<br />
bertahan hidup. Suatu usaha penangkapan dikatakan sukses kalau situasi<br />
pendapatannya memenuhi syarat sebagai berikut :<br />
1) Cukup untuk membayar semua sarana produksi.<br />
2) Cukup untuk membayar bunga modal yang ditanamkan.<br />
3) Cukup untuk membayar upah tenaga kerja.<br />
Biaya dan pendapatan usaha nelayan terdiri dari dua kategori, yaitu ongkos<br />
berupa pengeluaran nyata dan ongkos yang tidak merupakan pengeluaran nyata.<br />
Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran nyata ada yang kontan dan ada yang tidak<br />
kontan. Pengeluaran-pengeluaran kontan adalah (1) bahan bakar dan oli; (2) bahan<br />
pengawet (es dan garam); (3) pengeluaran untuk makanan konsumsi awak; (4)<br />
pengeluaran untuk raparasi; (5) pengeluaran untuk retribusi dan pajak.<br />
Pendapatan nelayan sangat ditentukan oleh sistim bagi hasil dan jarang<br />
diterima upah tetap. Tujuan dilakukannya peningkatan kesejahteraan bagi nelayan<br />
94
adalah untuk mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi keuntungan dan<br />
kerugian bagi perusahaan jika berinvestasi baik dalam jangka waktu panjang<br />
maupun pendek.<br />
Modal usaha pukat cincin terdiri dari alat-alat penangkapan jaring, motor,<br />
perahu, pengawetan di dalam kapal, makanan dan minuman dapat dilakukan<br />
penilain dengan melalui 3 cara yaitu: (1) penilaian didasarkan kepada nilai alat<br />
yang baru yaitu, berupa ongkos memperoleh alat tersebut menurut harga yang<br />
berlaku sekarang dan dapat dihitung dengan besarnya modal sekarang, (2)<br />
berdasarkan pada harga pembelian atau pembuatan alat tangkap, jadi berapa<br />
investasi awal yang telah dilaksanakan nelayan dan nelayan mengingat harga<br />
pembeliannya, (3) dengan menaksir nilai alat tangkap pada waktu sekarang yakni<br />
harga yang akan diperoleh apabila alat tersebut akan dijual. Oleh karenanya<br />
analisis ekonomi pendapatan nelayan adalah sebagai berikut.<br />
2.18.1 Kepuasan Kerja<br />
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan<br />
kinerja hasil yang dirasakannya dengan harapan yang diinginkan. Pengukuran<br />
tingkat kepuasan menggunakan pendekatan kualitas yang meliputi 5 dimensi<br />
yaitu: 1) hal-hal yang tampak konkrit (tangibles), meliputi infrastruktur,<br />
telekomunikasi, proses administrasi pendaftaran, penampilan situs, gedung,<br />
penampilan karyawan dan desain brosur yang ditampilkan, 2) dapat dipercaya<br />
(reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan,<br />
penyelesaian penanganan pengaduan, dan konsisten pelayanan sebagaimana yang<br />
dinjanjikan, 3) daya tanggap responsiveness yaitu kesiaptanggapan dalam<br />
95
melayani permintaan, kemauan untuk membantu dan sikap karyawan dalam<br />
menerima pengaduan, 4) jaminan (assurance) mencakup kemampuan karyawan<br />
dalam menanamkan kepercayaan, keterampilan dalam memberikan pelayanan dan<br />
prilaku karyawan dalam memberikan pelayanan, 5) empati (empathy) meliputi<br />
kemauan karyawan dalam membantu permasalahan pelanggan, kemampuan<br />
perusahaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan<br />
dan kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan.<br />
Perasaan puas atau tidaknya seseorang tergantung dari tingkat harapan dan<br />
tingkat persepsi jasa yang diterima, kalau terjadinya gap negatif dalam arti tingkat<br />
persepsi lebih rendah dari tingkat harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa<br />
Demikian pula sebaliknya, jika terjadi gap positif dalam arti tingkat persepsi lebih<br />
tinggi dari tingkat harapan, maka seseorang akan merasa puas.<br />
2.18.2 Produktivitas Kerja<br />
Konsep umum dari produktivitas adalah suatu perbandingan antara luaran<br />
(output) dan masukan (input) per satuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan<br />
meningkat apabila jumlah luaran meningkat dengan masukan yang sama (Chew,<br />
1991., Pheasant, 1991). Menurut Manuaba (1992) peningkatan produktivitas dapat<br />
dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam<br />
memanfaatkan sumber daya manusia dan peningkatan luaran sebesar-besarnya.<br />
Pengukuran produktivitas secara umum dapat dibedakan menjadi dua<br />
macam yaitu : (1) Produktivitas total, adalah perbandingan antara total luaran<br />
dengan total masukan per satuan waktu. Dalam perhitungan produktivitas total,<br />
semua faktor masukan terhadap total luaran diperhitungkan. (2) Produktivitas<br />
96
parsial, adalah perbandingan dari luaran dengan satu jenis masukan seperti upah<br />
tenaga kerja, bahan daya, beban daya, skor keluhan subjektif dan lain-lain :<br />
Produktivitas tenaga kerja =<br />
Luaran<br />
Masukan xWaktu<br />
Luaran merupakan hasil kerja dalam proses penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin, maka luaran dapat diproyeksikan dengan berat tarikan pukat cincin<br />
yang ditarik nelayan. Sedangkan masukan dapat diproyeksikan sebagai rerata<br />
beban kerja, keluhan otot skeletal, kelelahan. Beberapa hasil penelitian telah<br />
berhasil menunjukkan bahwa pendekatn ergonomi dalam perbaikan kondisi kerja<br />
telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menekan biaya<br />
produksi.<br />
2.18.3 Analisis Keuntungan Ekonomi<br />
Analisis pendapatan ekonomi dalam ergonomi bertujuan untuk<br />
menganalisis berbagai unsur yang mempengaruhi produktivitas. Pendekatan<br />
holistik menempatkan analisis ekonomi secara sistemik, holistik, interdisipliner<br />
dan partisipasi antara pemilik perusahaan dan karyawannya (Manuaba, 2001;<br />
2003b; 2005). Analisis yang dilakukan hendaknya melihat secara keseluruhan<br />
semua unsur yang mempengaruhi produktivitas kerja.<br />
Produktivitas secara ekonomis berupaya meningkatkan efisiensi dan<br />
efektivitas, sehingga biaya produksi perusahaan dapat ditekan dan penerimaan<br />
neraca keuangan perusahaan meningkat akibat adanya intervensi ergonomi<br />
(Hendricks, 2002) sebagai berikut :<br />
1) Peningkatan jumlah produk, dimana terjadi peningkatan secara kuantitas<br />
97
maupun kualitas produk.<br />
2) Peningkatan nilai jual produk, yaitu terjadi peningkatan harga jual produk.<br />
3) Penurunan biaya kerja tiap unit, yaitu terjadi efisiensi tiap unit kerja.<br />
4) Penurunan biaya karyawan, akibat berkurangnya karyawan yang sakit atau<br />
cedera akibat kerja.<br />
Bila mengacu pada indeks produktivitas, maka secara ekonomis<br />
peningkatan keuangan perusahaan dapat terjadi akibat efisiensi sumber daya<br />
maupun akibat peningkatan hasil produksi sebagai berikut.<br />
1) Efisiensi sumber daya–hasil produksi sama.<br />
2) Efisiensi sumber daya–hasil produksi meningkat.<br />
3) Sumber daya sama–hasil produksi meningkat.<br />
4) Sumber daya meningkat–hasil produksi meningkat.<br />
Dalam keadaan kondisi kerja tidak ergonomis maka akan mempengaruhi<br />
kapasitas sumber daya yang ada sehingga akan mempengaruhi kualitas dan<br />
kuantitas produksi. Artinya efisiensi sumber daya dalam proses produksi akan<br />
berubah menjadi in-efisiensi sehingga mempengaruhi produktivitas secara<br />
keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu asuransi kesehatan, yang<br />
diharapkan akan mampu mengefisienkan biaya pemeliharaan kesehatan karyawan<br />
(Cubed, 2000).<br />
Terdapat 3 kunci pokok analisis ekonomi dalam ergonomi menurut<br />
(Bridger, 2003) yaitu : 1) efikasi, apakah pelaksanaan pekerjaan berada di bawah<br />
kondisi yang ideal, 2) efektif, apakah pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam<br />
kondisi yang normal, 3) efisien, apakah pelaksanaan pekerjaan dapat menghemat<br />
biaya bahan baku dan dan biaya produksi.<br />
98
Efisiensi peningkatan produktivitas menurut (The US Sub Committee on<br />
Benefits and Cost, 1988) dapat diukur dengan menggunakan indikator ekonomi<br />
yaitu menentukkan tingkat keuntungan profitability dan efisiensi sistem untuk<br />
mengevaluasi kelayakan dari sebuah investasi yang diperoleh dari adanya biaya<br />
yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan.<br />
2.18.3.1 Break Event Point (BEP)<br />
BEP adalah adalah salah satu perhitungan ekonomi mikro untuk<br />
mengetahui suatu titik atau keadaan dimana perusahaan atau investor di dalam<br />
menginvestasikan modal usahanya tidak memperoleh keuntungan dan tidak<br />
menderita kerugian, dengan kata lain pulang pokok dimana pendapatan yang<br />
diperoleh perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dengan pengeluaran yang<br />
dibiayai pada dasarnya sama atau perusahaan mengalami titik impas dalam jangka<br />
waktu tertentu.<br />
Untuk menentukan BEP dapat dilihat melalui rumus bangun di bawah ini :<br />
BEP =<br />
BEP =<br />
BiayaTetap<br />
Harga Jualperunit<br />
−BiayaVariabel<br />
=......unit.<br />
Biaya Tetap<br />
= ......Rupiah<br />
I - Biaya variabel / Penjualan bersih<br />
Asumsi yang digunakan dalam menghitung BEP adalah sebagai berikut.<br />
1) Biaya tetap harus konstan selama periode tertentu<br />
2) Biaya variabel dalam hubungannya dengan penjualan harus konstan; dan<br />
3) Harga jual perunit tidak berubah dalam periode waktu tertentu.<br />
Berdasarkan batasan tertentu, maka BEP akan berubah apabila :<br />
1) Terdapat perubahan dalam biaya tetap;<br />
99
2) Terdapat perubahan dalam harga jual perunit; dan<br />
3) Terdapat perubahan pada ratio biaya variabel perunit.<br />
2.18.3.2 Benefit Cost Ratio (BCR)<br />
100<br />
Dalam menginvestasi salah satu usaha di bidang penangkapan ikan, maka<br />
diperlukan suatu analisis terhadap biaya dan manfaat dari suatu usaha di<br />
bidangnya Sedangkan BCR dalam menginvestasi modal usaha mempunyai tiga<br />
kriteria penilaian yaitu :<br />
1) ‘B-C’ = Manfaat kurang Biaya<br />
2) B-C/I = Manfaat kurang biaya / Investasi<br />
3) ∆B/∆C = Perubahan manfaat dibagi perubahan biaya<br />
Dari kriteria di atas, yang paling baik dan handal adalah B/C; dimana<br />
dalam kriteria ini rasio biaya dan manfaat merupakan ukuran bagi evaluasi<br />
suatu pembuatan alat, jika B/C = 1, maka alat tersebut bersifat marjinal, dan<br />
jika B/C>1, maka manfaat yang diperoleh lebih besar, dari pada biaya yang<br />
dikeluarkan, sehingga alat itu layak untuk dilaksanakan. Sedangkan B/C 1. Perhitungan<br />
analisis biaya dan manfaat antara lain adalah sebagai berikut.<br />
1) Dari segi waktu; horison waktu sangat penting untuk diperhatikan, sebab<br />
manfaat yang diperoleh di masa depan tidak sama dengan biaya dan hasil<br />
saat ini. Oleh karenanya aturan penilaian mengharuskan adanya
101<br />
pendiskontoan manfaat yang dirasakan oleh seseorang setelah beroperasinya<br />
kegiatan tersebut dan kriteria ini disebut (net present value) (NPV) menurut<br />
Sartono, (1994).<br />
Kriteria keputusannya yaitu : 1) apabila jumlah dari keseluruhan proceed<br />
yang diharapkan lebih besar PV dari investasinya, maka usulan investasi<br />
tersebut dapat diterima, 2) apabila jumlah PV dari keseluruhan proceed yang<br />
diharapkan PV dari investasinya (PV negatif), maka usulan investasi<br />
ditolak.<br />
Kelebihan dari NPV adalah : 1) memperhitungkan nilai waktu dan uang,<br />
2) memperhitungkan aliran kas selama<br />
2) Dari segi pendapatan; hasil yang diperoleh seseorang setelah megerjakan<br />
suatu pekerjaan disebut kriteria tingkat hasil (internal rate of return). IRR<br />
Kriteria ini mengacu pada tingkat penghasilan yang secara implisit<br />
terkandung didalam arus hasil dan biaya. IRR adalah tingkat hasil internal<br />
sebagai tingkat penghasilan berupa upah yang diperoleh pekerja, dikurangi<br />
biaya. Jadi dengan IRR dapat mengetahui apakah tingkat bunga yang<br />
menghasilkan benefit terdiskonto sama dengan biaya terdiskonto.<br />
2.18.3.3 Return Of Investment (ROI)<br />
Return of invesment merupakan nilai keuntungan yang diperoleh<br />
pengusaha (pemilik pukat cincin) dari setiap jumlah uang yang diinvestasikan<br />
dalam periode waktu tertentu. Perusahaan perlu membuat perhitungan ROI karena<br />
manfaatnya sangat besar, yaitu perusahaan dapat mengukur tingkat kemampuan<br />
usaha dalam mengembalikan modal yang telah ditanamnya. Dengan demikian
102<br />
analisis ROI dapat digunakan untuk mengkukur efisiensi penggunaan modal<br />
dalam perusahaan tersebut.
3.1 Kerangka Konsep Penelitian<br />
BAB III<br />
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS<br />
Setelah memperhatikan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka<br />
dapatlah disusun kerangka konsep sebagaimana berikut ini.<br />
1) Berdasarkan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin terungkap bahwa kinerja yang dinilai dari indikator beban<br />
kerja, kelelahan, dan keluhan muskuloskeletal akan dapat diatasi sehingga<br />
terjadi peningkatan kinerja nelayan.<br />
2) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dilihat dari ROI, BEP dan<br />
BCR.<br />
3) Penerapan ergonomi total dilakukan melalui intervensi ergonomi pada<br />
beberapa aspek yaitu: 1) suplesi gizi, 2) perbaikan sikap kerja,<br />
3) penggunaan perlengkapan pelindung diri, 4) waktu istirahat, 5) motivasi<br />
dalam bekerja seperti: perbaikan komunikasi, perbaikan informasi dan<br />
penggunaan alat bantu kerja katrol.<br />
4) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan nelayan<br />
penangkap ikan dengan pukat cincin adalah faktor internal dan faktor<br />
eksternal.<br />
5) Faktor internal yang turut mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan nelayan<br />
penangkap ikan dengan pukat cincin adalah: umur, jenis kelamin, berat<br />
badan, pengalaman kerja, pendidikan, dan status kesehatan.<br />
103
104<br />
6) Faktor eksternal yang turut mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan<br />
nelayan penangkap ikan dengan pukat cincin adalah: musim, suhu udara,<br />
kelembaban, kecepatan angin, hasil tangkapan, arus, ombak dan tipe kapal.<br />
Untuk lebih jelas, secara skematis, kerangkan konsep dapat disajikan<br />
pada Gambar 3.1.<br />
MASUKAN<br />
Faktor Intervensi ergonomi<br />
1) Suplesi gizi,<br />
2) Perbaikan sikap kerja,<br />
3) Penggunaan Perlengkapan<br />
pelindung diri,<br />
4) Pemberian waktu istirahat,<br />
5) Memberikan dorongan<br />
(motivasi),<br />
6) Perbaikan komunikasi,<br />
7) Perbaikan informasi, dan<br />
8) Penggunaan katrol untuk<br />
menarik pukat cincin<br />
Faktor internal<br />
1) umur<br />
2) jenis kelamin<br />
3) berat badan<br />
4) pengalaman kerja<br />
5) pendidikan<br />
6) kondisi kesehatan<br />
Faktor eksternal<br />
1) musim<br />
2) suhu udara<br />
3) kelembaban<br />
4) kecepatan angin<br />
5) arus<br />
6) ombak<br />
7) tipe kapal<br />
8) ukuran kapal<br />
PROSES<br />
Proses kerja<br />
penangkapan ikan<br />
dengan pukat cincin<br />
yang dirancang<br />
melalui pendekatan<br />
ergonomi total dengan<br />
perbaikan sbb:<br />
1. perbaikan sikap<br />
kerja nelayan<br />
menarik pukat<br />
cincin dengan<br />
menggunakan<br />
katrol.<br />
2. perbaikan alas<br />
duduk dan<br />
pemakaian sarung<br />
tangan pada saat<br />
menarik pukat<br />
cincin.<br />
3. pemberian teh<br />
manis.<br />
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian<br />
Keterangan:<br />
LUARAN<br />
Kinerja (Beban Kerja,<br />
Kelelahan, keluhan<br />
muskuloskeletal) dan<br />
Kesejahteraan<br />
nelayan (kepuasan<br />
kerja, produktivitas<br />
dan keuntungan<br />
ekonomi nelayan<br />
Diintervensi<br />
Dikontrol<br />
Proses Kerja dan<br />
gejala yang diamati
3.2 Hipotesis<br />
Berdasarkan kajian teori dan kerangka konsep penelitian yang telah<br />
dikemukakan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.<br />
105<br />
1) lntervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan beban kerja nelayan.<br />
2) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan kelelahan nelayan.<br />
3) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan keluhan<br />
muskuloskeletal nelayan.<br />
4) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari kepuasan kerja.<br />
5) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kesejahteraan yang nilai dari produktivitas.<br />
6) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari keuntungan nelayan.
4.1 Tempat dan Waktu Penelitian<br />
BAB IV<br />
METODE PENELITIAN<br />
Penelitian ini dilakukan di perairan laut Amurang Kabupaten Minahasa<br />
Selatan Propinsi Sulawesi Utara sepanjang 30 mil laut dan ditempuh dalam waktu<br />
5 jam perjalanan.<br />
Waktu penelitian dilaksanakan selama 8 minggu yaitu dari bulan Agustus<br />
2009 s/d bulan Oktober 2009 berdasarkan kalender yang disesuaikan dengan<br />
musim ikan.<br />
4.2 Rancangan Penelitian<br />
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan<br />
rancangan sama subjek (treatment by subject design) (Colton, 1985., Dimitrov &<br />
Rumrill., Hudock, 2005). Rancangan penelitian ini dipilih karena sesuai dengan<br />
tujuan penelitian yang ingin mengetahui adanya peningkatan kinerja; serta<br />
peningkatan kesejahteraan nelayan setelah intervensi ergonomi dengan<br />
pendekatan ergonomi total dilakukan terhadap proses penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin oleh nelayan penangkap ikan di Amurang Kabupaten Minahasa<br />
Selatan Provinsi Sulawesi Utara.<br />
Skema rancangan sama subjek (treatment by subject design) diberikan<br />
dalam Gambar 4.1.<br />
106
Gambar 4.1 Skema rancangan penelitian sama subyek<br />
4.3 Populasi dan Sampel<br />
4.3.1 Populasi<br />
107<br />
Keterangan :<br />
P : populasi untuk penelitian;<br />
R : pengambilan secara acak;<br />
S : sampel dipilih secara random dari populasi.;<br />
O1 : observasi awal tanpa intervensi<br />
,O2 : observasi akhir tanpa intervensi;<br />
P0 : aktivitas penangkapan ikan sebelum intervensi;<br />
WO : washing out (waktu untuk menghilangkan efek aktivitas sebelum<br />
intervensi) selama 3 hari;<br />
P1 : aktivitas penangkapan ikan dengan intervensi;<br />
O3 : observasi awal dengan intervensi;<br />
: observasi akhir dengan intervensi.<br />
O4<br />
P<br />
R<br />
Populasi adalah 250 orang nelayan pukat cincin, sedangkan populasi<br />
terjangkau adalah 90 nelayan pukat cincin dan besar sampel yang benar-benar<br />
diteliti 18 orang nelayan pukat cincin di Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan<br />
Provinsi Sulawesi Utara.<br />
4.3.2 Kriteria Sampel<br />
Sampel diambil dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi,<br />
ekklusi dan (drop out).<br />
S<br />
O1<br />
P0<br />
O2 WO<br />
O3<br />
P1<br />
O4
a. Kriteria inklusi<br />
berikut.<br />
108<br />
Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai<br />
1) Nelayan pukat cincin berumur 40 – 60 tahun.<br />
2) Berat badan berkisar antarar 57 – 70 kg<br />
3) Berjenis kelamin laki-laki.<br />
4) Pendidikan minimal tamat SD.<br />
5) Pengalaman kerja sebagai nelayan pukat cincin minimal 1 tahun.<br />
6) Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat yang dibuktikan dengan surat<br />
keterangan dokter.<br />
7) Bersedia menjadi subjek penelitian sampai selesai dan dibuktikan dengan<br />
adanya (inform consent).<br />
b. Kriteria eksklusi<br />
Kriteria eksklusi yang dipertimbangkan dalam pemilihan sampel adalah<br />
sebagai berikut.<br />
1) Pekerjaan sebagai nelayan pukat cincin dalam operasi penangkapan ikan<br />
tidak dilakukan setiap malam.<br />
2) Nelayan yang terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa selama<br />
periode penelitian.<br />
3) Memanfaatkan alat bantu yang terkait dengan proses penangkapan ikan<br />
sesuai dengan yang ditetapkan dalam penelitian.<br />
4) Tidak kecanduan alkohol<br />
5) Tidak kecanduan game<br />
6) Sulit berkomunikasi (tuli)
c. Kriteria drop out (gugur) :<br />
109<br />
1) Karena alasan tertentu mengundurkan diri sebagai sampel pada waktu<br />
penelitian;<br />
2) Tidak mengikuti kegiatan penelitian sampai selesai;<br />
3) Menderita sakit pada waktu penelitian dilaksanakan.<br />
4.3.3 Besar Sampel<br />
Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan<br />
hasil penelitian pendahuluan (Josephus, 2006). Berdasarkan data pada Tabel 4.1<br />
dengan harapan akan terjadi perubahan 15% pada beban kerja (denyut nadi),<br />
kelelahan, keluhan muskuloskeletal dan kesejahteraan, maka besar sampel<br />
dihitung dengan menggunakan rumus Colton (Colton, 1985) sebagai berikut :<br />
di mana<br />
n = besar sampel;<br />
Zα = 1,64;<br />
Zβ = -2,33;<br />
σ (z α − z β)<br />
n =<br />
2<br />
(µ − µ )<br />
2 2<br />
1 2<br />
=<br />
2<br />
σ<br />
(µ − µ )<br />
1 2<br />
2<br />
x f( α,β)<br />
µ1 = rata-rata secara tersendiri hasil pengamatan dari kinerja dengan<br />
indikator: beban kerja (denyut nadi), kelelahan; keluhan<br />
muskuloskeletal; serta kesejahteraan;<br />
µ2 = rata-rata secara tersendiri hasil pengamatan dari kinerja dengan<br />
indikator: beban kerja (denyut nadi), kelelahan; keluhan<br />
muskuloskeletal; serta kesejahteraan yang dianggap akan teramati bila<br />
intervensi dilakukan dan biasanya diasumsikan µ2 = µ1 ± 0,15 µ1;<br />
σ 2 = varians; dan
110<br />
f (α,β) = f (α, β) = 10,82 (dihitung dengan menggunakan fungsi = NORMSINV<br />
(peluang) dalam program Excel, 2003).<br />
Tabel 4.1<br />
Data yang Digunakan Sebagai Informasi untuk Pendugaan Ukuran Sampel<br />
Subyek Denyut Nadi Keluhan<br />
Item Kelelahan<br />
1-10 11-20 21-30 1-30<br />
Kesejahteraan<br />
Rata-rata 126,00 94,80 43 44 45 132 9<br />
Standar Deviasi 1,8708 8,58 2,97 3,29 1,82 5,94 1,63<br />
Variance<br />
Besar Sampel<br />
(n), Asumsi<br />
Perubahan<br />
3,50 73,70 8,80 10,80 3,30 35,30 2,67<br />
15%: 0,21 7,89 4,49 5,47 1,54 1,94 15,83<br />
Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh n terbesar adalah 15,83.<br />
Untuk mengantisipasi kemungkinan drop out dan berbagai variasi populasi maka<br />
jumlah sampel ditambah 10% menjadi 17,42 dan dibulatkan menjadi 18 orang.<br />
Dengan demikian besar sampel secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah<br />
18 orang.
4.4 Variabel Penelitian<br />
4.4.1 Identifikasi dan Klasifikasi Variabel<br />
Variabel penelitian yang ada, diklasifikasikan menjadi :<br />
111<br />
1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intervensi ergonomi pada proses<br />
penangkapan ikan dengan pukat cincin.<br />
2) Variabel tergantung : kinerja (indikator: beban kerja, kelelahan, dan keluhan<br />
muskuloskeletal) dan kesejahteraan (indikator: usaha pengembalian<br />
investasi, titik impas dan pendapatan nelayan).<br />
3) Variabel kontrol yaitu : umur, jenis kelamin, berat badan, pengalaman<br />
kerja, pendidikan, dan status kesehatan, musim, suhu udara, kelembaban,<br />
kecepatan angin, tipe kapal, dan peran dari pemimpin (tonaas).<br />
4) Variabel rambang yaitu : arus laut dan gelombang<br />
Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 4.2
Variabel Bebas :<br />
Proses penangkapan ikan dengan<br />
intervensi melalui pendekatan<br />
ergonomi total<br />
Variabel Kontrol<br />
a) Faktor internal: umur, jenis<br />
kelamin, berat badan, pengalaman<br />
kerja, nelayan, pendidikan, dan<br />
status kesehatan.<br />
b) Faktor eksternal; musim,<br />
kelembaban udara,kecepatan angin,<br />
tipe kapal, perlengkapan nelayan<br />
dan peran tonaas/pemimpin.<br />
- Arus Laut<br />
- Gelombang<br />
Variabel Rambang<br />
Gambar 4.2 Diagram Hubungan Antar Variabel<br />
4.4.2 Definisi Operasional Variabel<br />
112<br />
Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengumpulan data, maka<br />
berdasarkan indentifikasi setiap variabel dibuat definisi operasional dari masing-<br />
masing variabel sebagai berikut.<br />
4.4.2.1 Variabel bebas<br />
Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dilakukan berdasarkan pendekatan ergonomi total yaitu:<br />
Variabel Tergantung<br />
a) Kinerja (beban kerja,<br />
kelelahan, keluhan<br />
muskuloskeletal)<br />
b) Kesejahteraan<br />
nelayan : kepuasan<br />
kerja, produktivitas,<br />
dan pendapatan<br />
keuntungan nelayan.<br />
1) Pemakaian katrol oleh nelayan waktu penarikan tali pukat cincin.
113<br />
2) Pemakaian sarung tangan oleh nelayan pada waktu penarikan tali,<br />
pelampung, penggalian isi perut jaring, dan penarikan tali pukat cincin.<br />
3) Pengaturan waktu jadwal kerja yang dimulai pukul 23.00 – 05.00 dan<br />
istirahat 5 menit untuk minum.<br />
4) Perbaikan tempat duduk berupa penambahan alas duduk (spon) nelayan<br />
pada waktu penarikan pukat cincin.<br />
5) Memberikan informasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada<br />
nelayan dengan menggunakan alat pelindung diri berupa pemakaian jaket<br />
hujan, topi dan sarung tangan pada saat melakukan penangkapan ikan<br />
sehingga kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisasikan.<br />
6) Proses penangkapan ikan yang dimaksud yaitu di mulai dari penawuran<br />
jaring atau melempar jaring dari dalam perahu ke permukaan laut sampai<br />
pada penarikan pukat cincin.<br />
7) Pukat cincin atau (purse seine) dikenal dengan nama (soma pajeko) adalah<br />
jenis jaring lingkar untuk menangkap sejenis ikan pelagis yang membentuk<br />
gerombolan dengan kepadatan yang tinggi.<br />
8) Nelayan diberikan kesempatan untuk minum teh manis sebanyak 250cc.<br />
Adapun kondisi kerja sebelum melakukan intervensi yaitu :<br />
a) melakukan pekerjaan menarik pukat cincin dengan kedua tangan tidak<br />
memakai sarung tangan dengan sikap paksa dalam waktu 6 jam;<br />
b) sikap kerja menarik tali cincin yaitu duduk di lantai kayu perahu terlalu<br />
lama tanpa alas duduk, sikap tubuh membungkuk ke depan, tungkai<br />
terjulur dan kedua telapak kaki sebagai bantalan penahan tarikan;
114<br />
c) sikap kerja nelayan yang bertugas untuk menarik pelampung dilakukan<br />
dengan posisi berdiri tidak teratur;<br />
d) waktu kerja selama proses penangkapan berlangsung 6 jam yaitu: pukul<br />
23.00 – 05.00 WITA tidak ada kesempatan minum;<br />
9) Sistem kerja pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin setelah<br />
dilakukan intervensi ergonomi, maka terjadi perbaikan sebagai berikut.<br />
a) Setelah selesai penawuran jaring, maka nelayan menggunakan katrol<br />
menarik pukat cincin, dimana katrol diletakkan disamping kanan perahu.<br />
b) untuk menghindari sikap paksa dalam melakukan pekerjaan dan gerakan<br />
otot tidak bertentangan dengan gerakan fisiologis, maka alat katrol<br />
dirancang sesuai data antropometri nelayan.<br />
c) katrol adalah sebuah alat yang berbentuk lingkaran sebagai tempat<br />
lilitan tali yang dapat berputar pada saat melakukan penarikan pukat<br />
cincin;<br />
d) katrol dapat berfungsi ganda yaitu pada satu pihak sebagai alat bantu<br />
untuk mengurangi berat penarikan, dan di pihak lain mengunci cincin<br />
lebih cepat sehingga ikan tidak sempat keluar dari tangkapan. Seperti<br />
tampak pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3 Katrol Pukat Cincin<br />
115<br />
e) kedua tangan pada saat menarik pukat cincin menggunakan sarung<br />
tangan sejenis karet agar supaya tidak menimbulkan rasa sakit;<br />
f) menggunakan alas duduk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kerja di<br />
atas perahu penangkap;<br />
g) waktu kerja selama proses penangkapan ikan berlangsung 6 jam yaitu:<br />
pukul 23.00-05.00 dengan istirahat pendek 5 menit.<br />
h) nelayan diberikan kesempatan untuk minum teh manis sebanyak 250cc.<br />
i) pada waktu istirahat diberikan musik pengiring musik rock.<br />
j) mengatur kondisi informasi dengan melakukan komunikasi dua arah.<br />
k) mengatur kondisi sosial ekonomi terutama sistem pembagian hasil<br />
tangkapan.<br />
l) mengawasi secara langsung melihat penggunaan alat katrol agar supaya<br />
interaksi penggunaan alat katrol dengan nelayan serasi.<br />
4.4.2.2 Variabel Tergantung<br />
Tali Cincin<br />
Tali Cincin<br />
Katrol untuk<br />
menggulung tali cincin<br />
Sumbu<br />
pemutar katrol<br />
1) Kinerja adalah tampilan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan<br />
penangkapan ikan dengan pukat cincin. Penilaian baik dan buruknya kinerja<br />
seseorang dapat dilihat dari capaian kerja yang dihasilkan. Kemampuan
116<br />
nelayan didalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh karakteristik<br />
pekerjaan, kondisi lingkungan dan organisasi kerja. Tingkat kinerja nelayan<br />
diukur dengan menggunakan indikator yaitu: beban kerja, kelelahan,<br />
keluhan muskuloskeletal dan kesejahteraan. Indikator Pengukuran Kinerja<br />
nelayan pada penelitian ini yaitu :<br />
a. Beban kerja adalah beban yang diterima oleh tenaga kerja (nelayan)<br />
selama melakukan pekerjaan (beban kerja utama + beban kerja<br />
tambahan). Kategori berat ringannya beban kerja ditentukan berdasarkan<br />
perhitungan yaitu : Denyut Nadi Kerja (DNK), dikurangi Denyut Nadi<br />
Istirahat (DNI) sama dengan Nadi Kerja (NK) yang diukur setiap<br />
30 menit selama jam kerja. Pengukuran dilakukan secara palpasi pada<br />
arteri radialis tangan kiri dengan metode 10 denyut dengan<br />
menggunakan stop. watch.<br />
b. Kelelahan merupakan suatu perasaan subyektif disertai adanya<br />
penurunan fungsi persepsi, interpretasi dan reaksi motoris yang<br />
dirasakan oleh subjek selama melakukan pekerjaan. Kelelahan diukur<br />
sebelum dan sesudah bekerja dengan menggunakan 30 item of rating<br />
scale dalam kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan (lampiran 7a,b<br />
dan 8a,b) Untuk aktivitas melemah (item 1-10), penurunan motivasi<br />
(item11-20) dan (item 21-30) kelelahan fisik.<br />
c. Keluhan otot skeletal adalah keluhan otot yang dirasakan oleh subjek<br />
pada bagian-bagian tubuh mulai dari rasa tidak enak sapai sangat sakit.<br />
Keluhan otot skeletal didata sebelum dan sesudah bekerja dengan
117<br />
menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) yang dimodifikasi<br />
dengan 4 skala Likert (lampiran 8a dan 8b).<br />
2) Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan kuesioner<br />
kesejahteraan dilihat dari aspek kepuasan kerja, produktivitas dan<br />
keuntungan pandapatan nelayan.<br />
4.4.2.3 Variabel Kontrol<br />
Faktor Internal<br />
1) Umur adalah jangka waktu dalam tahun yang dihitung mulai subjek<br />
dilahirkan sampai dengan saat terpilih sebagai sampel penelitian dengan<br />
melihat KTP. Umur anggota sampel ditentukan dengan pembulatan ke<br />
bawah.<br />
2) Jenis kelamin adalah ciri fenotip subjek adalah laki-laki yang ditunjukkan<br />
oleh ciri kelamin sekunder dan didukung oleh keterangan yang ada pada<br />
kartu tanda penduduk KTP.<br />
3) Pendidikan adalah surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperoleh melalui<br />
di lingkungan sekolah formal. Dalam penelitian ini subjek minimal<br />
berpendidikan tamat SD.<br />
4) Berat badan adalah bobot tubuh subjek yang diukur dengan timbangan<br />
badan merk (Camry).<br />
5) Kesehatan adalah kondisi kesehatan subjek yang ditunjukkan dengan surat<br />
keterangan dokter.<br />
6) Pengalaman kerja adalah lama waktu subjek melakukan pekerjaan<br />
penangkapan ikan dengan batas minimal 2 tahun yang ditunjukkan dengan<br />
sertifikat sebagai nelayan penangkap.
118<br />
7) Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung<br />
langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun<br />
budi daya.<br />
Faktor Eksternal<br />
1) Musim yang dimaksud adalah periode waktu musiman. Dalam penelitian ini<br />
aktivitas penangkapan ikan disesuaikan dengan musim ikan menurut<br />
perhitungan kalender Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa<br />
Selatan, kalender Bali dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) selama<br />
bulan agustus sampai dengan desember 2009.<br />
2) Kelembaban udara dinilai dari jumlah relatif uap air yang ada di udara pada<br />
suatu suhu tertentu. Kelembaban diukur dengan menggunakan higrometer<br />
dan dikonversikan kedalam psikrometer chart dan dinyatakan dengan<br />
satuan %. Pengukuran kelembaban udara dilakukan sepanjang aktivitas<br />
penangkapan ikan setiap interval 5 atau 10 menit.<br />
3) Kecepatan angin adalah laju rata-rata hembusan angin pada lokasi<br />
penangkapan ikan. Variabel ini diukur dengan menggunakan anemometer<br />
dan dinyatakan dengan satuan menit/jam. Pengukuran dilakukan setiap<br />
interval waktu 5-10 menit.<br />
4) Tipe kapal (perahu) adalah tipe lambut dengan bobot 40-80 GT. Tenaga<br />
penggerak yang digunakan berupa motor tempel merk Yamaha tipe enduro<br />
dengan kekuatan dorong 40 HP.<br />
5) Perlengkapan nelayan adalah jas hujan, makanan, minuman dan bahan bakar<br />
minyak (BBM).
119<br />
6) Tonaas adalah pimpinan nelayan berfungsi memberikan komando dan<br />
petunjuk tentang cara dan teknik penangkapan.<br />
4.4.2.4 Variabel Rambang<br />
1) Arus laut adalah pergerakan massa air laut dengan panas matahari<br />
kepermukaan bumi dan pemanasan ini tidak merata sehingga menimbulkan<br />
perbedaan tekanan atmosfir dan perbedaan densitas air laut sehingga<br />
menyebabkan terjadinya arus. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya<br />
arus yaitu : angin, pasang surut dan gelombang.<br />
2) Gelombang laut terjadi akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa yang<br />
menimbulkan terjadinya air pasang-surut di laut.<br />
4.5 Bahan Pengumpul Data<br />
Bahan pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sbb.<br />
1) Bahan baku atau material yang digunakan dalam pembuatan katrol adalah<br />
besi siku, plat dan bulat, baut atau mur, paku, martil, gergaji, ring, gerigi<br />
engsel, meter dan besi plat.<br />
2) Kuesioner Nordic Body Map untuk mendata keluhan muskuloskeletal.<br />
3) 30 items of rating scale yang dimodifikasi dengan 4 skala likert untuk<br />
mendata kelelahan.<br />
4) Kuesioner kesejahteraan dan didukung dengan data analaisis ekonomi (BEP,<br />
BCR dan ROI)
4.6 Alat Pengumpul Data<br />
1) Perahu/kapal penangkap ikan dan perangkat kelengkapannya.<br />
2) Pukat cincin atau soma pajeko dan perangkat kelengkapannya.<br />
3) Stopwatch digital merk Casio HS-3 digunakan untuk menentukan waktu kerja.<br />
120<br />
4) Kamera digital merk Sony DSC-P41 digunakan untuk mengambil gambar<br />
dokumen penelitian.<br />
5) Timbangan barang merk super arjuna dengan ketelitian 0,05 kg untuk<br />
mengukur berat hasil tangkapan<br />
6) Timbangan badan merk Elephant buatan Jepang dengan ketelitian 0,2 kg<br />
untuk mengukur berat badan nelayan penangkap ikan.<br />
7) Ecosonder buatan Jepang untuk mengukur kecepatan arus dan ombak.<br />
8) Higrometer merk Luxtrom LM 800 buatan Jepang, digunakan untuk<br />
mengukur kelembaban udara.<br />
9) Meteran logam merk Helsen dengan ketelitian 1mm untuk mengukur alat-<br />
alat kerja dan jarak antara alat dan tempat kerja.<br />
10) Anemometer merk Luxtron AM-4201 buatan Taiwan untuk mengukur<br />
kecepatan angin.<br />
11) Alimeter analog untuk mengukur tinggi rendahnya di atas permukaan laut.<br />
4.7 Prosedur Penelitian<br />
Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam penelitian, maka<br />
dalam pengambilan data digunakan tata aturan sebagai berikut.
4.7.1 Tahap Persiapan<br />
121<br />
Sebelum proses penangkapan ikan baik untuk periode tanpa intervensi (TI)<br />
maupun periode dengan intervensi (DI), maka dilakukan kegiatan persiapan<br />
seperti uraian berikut ini.<br />
1) Mempersiapkan kuesioner NBM sebelum intervensi dan kuesioner NBM<br />
dengan intervensi ergonomi dan kusesioner 30 items of rating scale dengan<br />
skala likert untuk pengukuran kelelahan secara umum sebelum dan sesudah<br />
intervensi.<br />
2) Kuesioner kesejahteraan yang diisi oleh nelayan dalam proses penangkapan<br />
ikan dengan pukat cincin.<br />
3) Data pengukuran denyut nadi dan alat tulis menulis.<br />
4) Menyusun jadwal pemberian perlakuan untuk masing-masing kelompok<br />
subjek. Secara keseluruhan, penelitian dilakukan selama 8 minggu. Data<br />
beban kerja, kelelahan, keluhan muskuloskeletal, ROI, BEP dan pendapatan<br />
nelayan dilakukan pada proses penangkapan ikan, yaitu pada setiap minggu<br />
setiap periode sesuai jadwal seperti dalam Tabel 4.2.
Tabel 4.2<br />
Jadwal pengambilan data untuk masing-masing periode<br />
No. Uraian M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8<br />
1 Periode TI (Po)<br />
01 Observasi Awal →02<br />
Observasi Akhir<br />
01 Observasi Awal →02<br />
Observasi Akhir<br />
01 Observasi Awal →02<br />
Observasi Akhir<br />
122<br />
01 Observasi Awal →02<br />
Observasi Akhir<br />
WOP (washing out period) Selama 3 hari untuk menghilangkan carry<br />
over effect<br />
2 Periode DI (P1)<br />
03 Observasi Awal →04<br />
Observasi Akhir<br />
03 Observasi Awal →04<br />
Observasi Akhir<br />
03 Observasi Awal →04<br />
Observasi Akhir<br />
03 Observasi Awal →04<br />
Observasi Akhir<br />
5) Mempersiapkan petugas pengumpul data dan alat-alat yang akan digunakan.<br />
6) Memberikan pengarahan dan pemahaman tentang tujuan, jadwal kerja, dan<br />
prosedur pelaksanaan pengukuran dan penggunaan alat ukur kepada petugas<br />
pengumpul data.<br />
7) Memberikan pengarahan kepada subjek penelitian tentang tujuan, jadwal<br />
kerja, dan prosedur pelaksanaan pengukuran yang harus diikuti dan ditaati<br />
selama proses penelitian.
123<br />
8) Mempersiapkan area kerja sesuai dengan rancangan dan jadwal yang telah<br />
ditentukan.<br />
4.7.2 Protokol Penelitian<br />
Tahap persiapan dan perbaikan sistem kerja nelayan dengan mengikuti<br />
proses tahapan uraian seperti ini :<br />
1) Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan meliputi<br />
pengurusan surat ijin tempat penelitian pada sahbandar Amurang, surat<br />
pemeberitahuan kepada Badan Meterologi dan Geofisika (BMG)<br />
Kabupaten Minahasa Selatan dan kwitansi pembayaran kapal motor<br />
penelitian khususnya pukat cincin.<br />
2) Penetapan sampel peneltian sesuai random sampling rancangan sama<br />
subyek sebanyak 18 0rang nelayan pukat cincin berdasarkan inform<br />
concent surat persetujuan dari subyek sebagai responden.<br />
3) Mengukur antropometri (ukuran tubuh) subyek penelitian khususnya<br />
ukuran bagian-bagian tubuh seperti: tinggi tubuh, berat, jangkauan<br />
lengan, tinggi badan duduk, tinggi mata duduk, tinggi popliteal,<br />
panjang lengan atas, panjang lengan bawah dan tinggi siku dalam<br />
piosisi duduk khususnya pada saat menarik pukat cincin dengan<br />
intervensi ergonomi menggunakan alat kerja katrol.<br />
4) Indentifikasi setiap permasalahan ergonomi dengan melakukan studi<br />
pendahuluan dengan fokus pada 8 aspek permasalahan ergonomi yang<br />
meliputi : (1) gizi/nutri kerja; (2) penggunaan tenaga otot; (3) sikap
124<br />
kerja; (4) lingkungan kerja; (5) waktu kerja; (6) sistem informasi; (7)<br />
kondisi sosial budaya; (8) interaksi manusia mesin.<br />
5) Mensosialisasikan hasil pengukuran kepada masing-masing subyek<br />
penelitian untuk diketahui guna memperkuat analisis data penelitian.<br />
6) Menyusun anggaran dan belanja untuk pembelian bahan peralataan<br />
katrol meliputi : pipa besi berdiameter 80 dan panjang 40 cm sebanyak<br />
2 unit; besi ukuran 5,8 cm sebanyak 2 saf; besi poros panjang 60 cm,<br />
mur, bout, gerigi, cat warna dan papan cempaka serta biaya<br />
pembayaran teknisi pengelasan untuk pembuatan alat kerja katrol.<br />
7) Mengangkat dan meletakkan alat kerja katrol di atas perahu untuk<br />
digunakan pada waktu melakukan perbaikan kondisi kerja melalui<br />
intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin<br />
8) Pembelian alat pelindung diri nelayan seperti : jaket hujan , topi dan<br />
sarung tangan digunakan pada waktu melakukan perbaikan sistem<br />
kerja penangkapan ikan dengan pukat cincin dengan intervensi<br />
ergonomi.<br />
9) Mempersiapkan makanan dan air minum (Aqua gelas) untuk<br />
digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan dengan intervensi<br />
ergonomi.<br />
10) Untuk mengubah sikap kerja berdiri menjadi sikap kerja duduk, maka<br />
diperlukan penambahan alas duduk papan khusus untuk penarikan tali<br />
pukat cincin berdasarkan hasil antropometri yang diukur.
125<br />
11) Mempersiapkan alat tulis menulis dan peralatan kerja lainnya yang<br />
berhubungan dengan penelitian di Lokasi penelitian daerah<br />
penangkapan ikan perairan laut Amurang Kabupaten Minahasa Selatan<br />
Provinsi Sulawesi Utara.<br />
4.7.3 Tahap Pelaksanaan<br />
4.7.3.1 Periode Sebelum Intervensi (selama 4 hari)<br />
1) Peneliti dan 2 orang asisten peneliti berada dalam persiapan 1 jam sebelum<br />
pergi melaut berkumpul bersama-sama di tepi pantai dan mengadakan<br />
pengecekan satu persatu.<br />
2) Peneliti dan 2 orang asisten peneliti, dan bersama subjek 18 orang nelayan<br />
naik ke perahu menuju lokasi penelitian di areal penangkapan ikan dengan<br />
menempuh jarak 20 mil laut (36 Km) atau 5 jam perjalanan mulai pukul<br />
11.00-16.00 WITA.<br />
3) Setibanya di lokasi penelitian pukul 17.00 WITA diberikan penyampaian<br />
arahan tentang cara-cara yang akan dilakukan subyek selama proses<br />
penangkapan ikan.<br />
4) Pimpinan yang disebut tonaas mengadakan pengecekan pada masing-<br />
masing anggota yaitu: (1) nelayan yang bertugas menarik tali cincin<br />
8 orang (2) yang bertugas menarik pelampung 4 orang dan (3) nelayan yang<br />
bertugas menarik isi perut jaring 6 orang.<br />
5) Sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan, maka dilakukan<br />
pengukuran denyut nadi istirahat sebagai data awal: subyek dalam posisi<br />
duduk santai, tangan kanan/kiri diletakkan di atas paha dan peneliti mulai
126<br />
bertugas mengambil data (a) denyut nadi istirahat secara palpasi pada<br />
masing-masing nelayan pada arteri radialis kiri selama 15 detik; (b) mengisi<br />
kuesioner Nordic Body Map (NBM) sebelum intervensi: subyek melihat<br />
peta tubuh dan menandai kolom yang telah disediakan sesuai dengan tingkat<br />
keluhan yang dirasakan pada setiap bagian otot tubuh: (c) mengisi kuesioner<br />
kelelahan 30 items of Rating Scales dengan skala likert sebelum intervensi:<br />
(d) mengisi kuesioner kesejahteraan yang dipersiapkan peneliti sebelum<br />
intervensi.<br />
6) Tepat pukul 23.00 Wita yang ditandai dengan bunyi suling, maka operasi<br />
penangkapan dimulai dan masing-masing subjek melakukan tugasnya sesuai<br />
dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan yang disebut tonaas.<br />
7) Penawuran atau melepas jaring 6 orang dan pelampung 4 orang serta tali<br />
cincin 8 orang.<br />
8) Penawuran jaring 10 menit, melingkar secara horisontal 10 menit, memagari<br />
jaring secara vertikal dari permukaan sampai suatu kedalaman 10 menit,<br />
mengurung dengan menutup bagian bawah jaring 10 menit. Sehingga total<br />
waktu penawuran jaring 40 menit.<br />
9) Selama melakukan aktivitas kerja penangkapan ikan menarik pukat cincin,<br />
maka pengambilan data denyut nadi kerja, dilakukan setiap 30 menit selama<br />
kerja dengan menggunakan metode 10 denyut, subyek dalam posisi berdiri,<br />
dan dilakukan tanpa menghentikan aktivitas kerja<br />
10) Proses penangkapan ikan sebelum intervensi dari nomor 1 sampai 9 diatas<br />
diulang selama 4 kali selama proses penangkapan.
127<br />
Washing Out Period (WOP) 3 hari (istirahat) tidak boleh melaut dan<br />
melaksanakan pekerjaan yang lain seperti membuat ikan garam.<br />
4.7.3.2 Periode Dengan Intervensi (selama 4 hari)<br />
1) Peneliti dan 2 orang asisten peneliti berada dalam persiapan 1 jam sebelum<br />
pergi melaut berkumpul bersama-sama di tepi pantai dan mengadakan<br />
pengecekan satu persatu.<br />
2) Peneliti dan 2 orang asisten peneliti, dan bersama subjek 18 orang nelayan<br />
naik ke perahu menuju lokasi penelitian di areal penangkapan ikan dengan<br />
menempuh jarak 20 mil laut (36 Km) atau 5 jam perjalanan mulai pukul<br />
11.00-16.00 WITA.<br />
3) Setibanya di lokasi penelitian pukul 17.00 WITA diberikan penyampaian<br />
arahan tentang cara-cara yang akan dilakukan subyek selama proses<br />
penangkapan ikan.<br />
4) Pimpinan yang disebut tonaas mengadakan pengecekan pada masing-<br />
masing anggota yaitu: (1) nelayan yang bertugas menarik tali cincin<br />
8 orang (2) yang bertugas menarik pelampung 4 orang dan (3) nelayan yang<br />
bertugas menarik isi perut jaring 6 orang.<br />
5) Sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan intervensi, maka<br />
dilakukan pengukuran denyut nadi istirahat sebagai data awal: subyek dalam<br />
posisi duduk santai, tangan kanan/kiri diletakkan di atas paha dan peneliti<br />
mulai bertugas mengambil data (a) denyut nadi istirahat secara palpasi pada<br />
masing-masing nelayan pada arteri radialis kiri selama 15 detik; (b) mengisi<br />
kuesioner Nordic Body Map (NBM): subyek melihat peta tubuh dan
128<br />
menandai kolom yang telah disediakan sesuai dengan tingkat keluhan yang<br />
dirasakan pada setiap bagian otot tubuh: (c) mengisi kuesioner kelelahan 30<br />
items of Rating Scales dengan skala likert: (d) mengisi kuesioner<br />
kesejahteraan yang dipersiapkan peneliti.<br />
6) Tepat pukul 23.00 Wita yang ditandai dengan bunyi suling, maka operasi<br />
penangkapan dimulai dan masing-masing subjek melakukan tugasnya sesuai<br />
dengan tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan yang disebut tonaas.<br />
7) Penawuran atau melepas jaring 6 orang dan pelampung 4 orang serta tali<br />
cincin 8 orang.<br />
8) Penawuran jaring 10 menit, melingkar secara horisontal 10 menit, memagari<br />
jaring secara vertikal dari permukaan sampai suatu kedalaman 10 menit,<br />
mengurung dengan menutup bagian bawah jaring 10 menit. Sehingga total<br />
waktu penawuran 40 menit.<br />
9) Pengambilan data denyut nadi kepada masing-masing dilakukan pada saat<br />
penarikan pukat cincin setiap 30 menit. Mulai pukul 23.00 sampai pukul<br />
04.30 wita, waktu penarikan tali cincin lebih cepat 30 menit karena<br />
menggunakan alat katrol, subjek dalam posisi duduk dan mengambil waktu<br />
istirahat 5 menit untuk minum teh setelah jaring terkunci.<br />
10) Proses penangkapan ikan dengan intervensi dari nomor 1 sampai 9 diatas<br />
diulang subjek selama 4 x selama proses penangkapan.<br />
Washing Out Period (WOP) 3 hari (istirahat) tidak boleh melaut dan<br />
melaksanakan pekerjaan yang lain seperti membuat ikan garam.
4.8 Teknik Analisis Data<br />
129<br />
Data yang akan diperoleh dan teknik analisis yang digunakan adalah<br />
sebagai berikut.<br />
1) Data kondisi subjek dianalisis dengan cara (a) umur, tinggi badan, dan berat<br />
badan dicari rata-rata dan simpangan bakunya dan (b) antropometrik<br />
nelayan dicari persentil 5, 50 dan 95.<br />
2) Pengaruh variabel bebas yaitu proses melakukan penangkapan ikan dengan<br />
pukat cincin melalui pendekatan ergonomi total terhadap variabel<br />
tergantung yaitu kinerja (indikator: beban kerja, kelelahan dan keluhan<br />
muskuloskeletal) dan kesejahteraan (indikator: pengembalian investasi, titik<br />
impas dan pendapatan nelayan) diuji dengan menggunakan uji t paired pada<br />
taraf signifikansi 5%, bila data berdistribusi normal, dan akan menggunakan<br />
uji wilcoxon bila data tidak berdistribusi normal. Untuk pengujian<br />
normalitas data akan digunakan uji Shapiro-Wilk. Analisis akan dilakukan<br />
dengan SPSS release 13.0. Hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai<br />
berikut.<br />
1.1 Ho: µ1 = µ2 (rerata frekuensi denyut nadi kerja nelayan penangkap<br />
ikan dengan pukat cincin pada periode TI sama dengan rerata<br />
frekuensi denyut nadi pada periode DI).<br />
Ha: µ1 > µ2 (rerata frekuensi denyut nadi nelayan penangkap ikan<br />
dengan pukat cincin pada periode TI lebih tinggi daripada rerata<br />
frekuensi denyut nadi pada periode DI).<br />
Aturan keputusan:<br />
Tolak Ho (terima Ha) bila p-value dari statistik uji < 0,05 (taraf<br />
signifikansi), dan terima Ho bila p-value dari statistik uji > 0,05.
130<br />
1.2 Ho: µ1 = µ2 (rerata skor kelelahan nelayan penangkap ikan dengan<br />
pukat cincin pada periode TI sama dengan rerata skor kelelahan<br />
pada periode DI).<br />
Ha: µ1 > µ2 (rerata skor kelelahan nelayan penangkap ikan dengan<br />
pukat cincin pada periode TI lebih tinggi dari pada rerata skor<br />
kelelahan pada periode DI).<br />
Aturan keputusan:<br />
Tolak Ho (terima Ha) bila p-value dari statistik uji < 0,05 (taraf<br />
signifikansi), dan terima Ho bila p-value dari statistik uji > 0,05.<br />
1.3 Ho: µ1 = µ2 (rerata skor keluhan muskuloskeletal nelayan penangkap<br />
ikan dengan pukat cincin pada periode TI sama dengan rerata<br />
skor keluhan muskuloskeletal pada periode DI).<br />
Ha: µ1 > µ2 (rerata skor keluhan muskuloskeletal nelayan pada periode<br />
TI lebih tinggi dibandingkan dengan rerata skor keluhan<br />
muskuloskeletal pada periode DI).<br />
Aturan keputusan:<br />
Tolak Ho (terima Ha) bila p-value dari statistik uji < 0,05 (taraf<br />
signifikansi), dan terima Ho bila p-value dari statistik uji > 0,05.<br />
1.4 Ho: µ1 = µ2 (rerata skor kesejahteraan nelayan penangkap ikan<br />
dengan pukat cincin pada periode TI sama dengan rerata skor<br />
kesejahteraan periode DI).<br />
Ha: µ1 > µ2 (rerata skor kesejahteraan nelayan penangkap ikan dengan<br />
pukat cincin pada periode TI sama lebih tinggi dengan rerata skor<br />
kesejahteraan periode DI).
131<br />
3) Data iklim mikro yang terdiri dari kecepatan angin, suhu udara, dan<br />
kelembaban udara angin yang diambil rata-rata setiap interval 10 menit<br />
dijadikan data pendukung. Analisis untuk komparabilitas iklim mikro pada<br />
kedua periode menggunakan uji t independen pada taraf signifikansi 5%.<br />
Terlebih dahulu diadakan uji normalitas data dengan Shapiro-Wilk test.<br />
Bila data tidak normal akan digunakan uji Mann-Whitney pada taraf<br />
signifikan 5 %.<br />
4.9 Antropometri Subjek<br />
Pengukuran antropometri dalam penelitian ini adalah antropometri duduk,<br />
dimana data antropometri pada saat diukur subyek dalam posisi duduk tegak di<br />
atas buritan kapal/perahu penangkap ikan dalam posisi menarik tali pukat cincin<br />
pada waktu proses penangkapan ikan.<br />
Tabel 4.3<br />
Nilai Persentil, Simpang Baku dan Rentangan Antropometri Subjek<br />
Nelayan Pukat Cincin<br />
Antropometri Tubuh Persentil 5<br />
(cm)<br />
(5 th Persentil 95<br />
) (95 th SB Rentangan<br />
)<br />
(cm)<br />
Jangkauan lengan 65,61 73,43 2,64 65 – 76<br />
Tinggi badan duduk 113,53 123,97 3,36 115 – 126<br />
Tinggi mata duduk 102,80 115,07 3,74 103 – 117<br />
Tinggi popliteal 37,58 48,17 2,63 37 – 49<br />
Panjang lengan atas 27,03 31,87 1,73 26 – 35<br />
Panjang lengan bawah 22,37 27,98 1,41 22 – 30<br />
Tinggi siku dalam posisi<br />
duduk<br />
53,93 64,04 3,04 53 – 65
4.10 Tahap-tahap Pengembangan Desain Katrol<br />
132<br />
Proses pengembangan desain sebuah alat mempunyai urutan langkah-<br />
langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah konsep desain<br />
dan mengkomersilkan suatu produk adalah sebagai berikut.<br />
1. Pengembangan konsep<br />
Mengidentifikasi kebutuhan target konsumen, mengevaluasi alternatif<br />
konsep dan menentukan konsep tunggal untuk pengembangan lebih lanjut.<br />
2. Desain tahapan sistem<br />
Membuat rancangan produk, geometri produk, pembagian produk menjadi<br />
subsistem dan komponen beserta spesifikasinya dan diagram alir proses<br />
perakitan produk.<br />
3. Desain detail<br />
Dokumentasi kontrol untuk produk file yang berisi ukuran setiap komponen,<br />
spesifikasi komponen-komponen yang dibeli, peralatan produksi, dan<br />
perencanaan untuk pabrikasi dan perakitan produk.<br />
4. Pengujian dan perbaikan<br />
Pembuatan prototype misalnya A yang merupakan prototype yang<br />
dibuat dengan menggunakan komponen-komponen dengan bentuk dan<br />
jenis material pada produksi sesungguhnya, namun tidak membutuhkan<br />
proses pabrikasi dengan proses yang sama dengan yang dilakukan pada<br />
produksi yang sesungguhnya; dan prototype misalnya B yang dibuat<br />
dengan komponen-komponen yang dibutuhkan pada produksi namun<br />
dirakit dengan menggunakan proses perakitan akhir seperti pada proses
133<br />
perakitan sesungguhnya. kedua prototype tersebut diuji dengan ketat<br />
baik secara internal maupun diuji oleh konsumen dalam lingkungan<br />
pengguna.<br />
5. Produksi Ramp up<br />
dalam tahap ini produk dibuat dengan sistem produksi yang sebenarnya,<br />
dengan tujuan untuk melatih tenaga kerja dan untuk menyelesaikan<br />
permasalahan yang masih terdapat dalam proses produksi. dalam fase ini<br />
terdapat launch produc. Lebih jelas tahap-tahap pengembangan desain alat<br />
kerja dapat ditunjukkan di bawah ini :<br />
4.10.1 Spesifikasi Alat Katrol untuk Pukat Cincin<br />
Gambar 4.4. Alat Katrol Pukat Cincin
Tabel 4.4<br />
Spesifikasi Alat Katrol Penarik Pukat Cincin<br />
Jenis Peralatan Ukuran Bahan Keterangan<br />
Perahu pukat<br />
cincin<br />
Panjang : 21,5 m<br />
Lebar : 5,15 m<br />
Dalam : 2,25 m<br />
Tempat duduk Panjang : 36 cm<br />
Lebar : 25 cm<br />
Tinggi dari<br />
Tempat bahan<br />
baku<br />
lantai : 20 – 40 cm<br />
Panjang : 60 cm<br />
Lebar : 60 cm<br />
Tinggi dari<br />
lantai : 20 – 40 cm<br />
Alat katrol Panjang : 135 cm<br />
Lebar : 120 cm<br />
Tinggi dari<br />
lantai : 120 cm<br />
Alat ukur katrol Ukuran disesuaikan<br />
dengan ukuran produk.<br />
Kayu dan<br />
besi<br />
Kayu papan,<br />
spon gabus<br />
dan karet<br />
Besi, papan,<br />
mur, baut,<br />
bendrat dan<br />
karet.<br />
Balok papan,<br />
mur, baut,<br />
bendrat.<br />
Menggunakan<br />
mesin tempel<br />
40PK (5 buah)<br />
134<br />
Ketinggian dapat<br />
disesuaikan<br />
Ketinggian dapat<br />
disesuaikan<br />
Sistem kerja<br />
ditarik generator.<br />
Besi dan cat Sudah standar<br />
Data pembuatan alat katrol sebagai ditunjukkan pada Gambar 4.5.<br />
Gambar 4.5. Alat Katrol Pukat Cincin
4.10.2 Penggunaan Alat Kerja Katrol<br />
135<br />
Berdasarkan data hasil pengukuran antropometri para nelayan pukat<br />
cincin, maka dalam pembuatan desain alat kerja katrol yang ergonomi<br />
menggunakan pendekatan ergonomi total yang terdiri dari pendekatan SHIP<br />
(Sistemik, Holistik, Interdisipliner, Partisipatori) dan Penerapan Teknologi Tepat<br />
Guna (Manuaba, 2003e;2005a). Pendekatan ergonomi total merupakan salah satu<br />
bentuk intervensi ergonomi yang bertujuan untuk mendapatkan sistem kerja yang<br />
manusiawi, kompetititf dan lestari.<br />
Sikap kerja dengan menggunakan alat kerja katrol yang ergonomis seperti<br />
tampak pada Gambar 4.6.<br />
Gambar 4.6. Sikap kerja nelayan menggunakan alat kerja katrol<br />
Sikap tubuh manusia ketika melakukan pekerjaan diakibatkan oleh<br />
hubungan antara dimensi pekerja dengan dimensi variasi dari tempat kerjanya<br />
disebut sikap kerja (Phesant, 1991). Sikap kerja nelayan pada waktu melakukan
136<br />
aktivitas penangkapan ikan dengan menarik tali pukat cincin dilakukan dengan<br />
sikap kerja paksa. Sikap kerja paksa dapat menyebabkan timbulnya berbagai<br />
gangguan pada sistem otot skeletal (Manuaba, 1990; Adiputra, 1998). Kondisi<br />
tersebut tentunya akan dapat menyebabkan keluhan atau kenyerian pada bagian<br />
otot-otot skeletal, khususnya pinggang dan punggung serta otot-otot<br />
bagianbawah seperti : paha, lutut, betis, pantat dan kaki; dan bagian atas seperti :<br />
pergelangan tangan kanan dan kiri, bahu, leher dan sebagainya.
4.11 Alur Penelitian<br />
SAMPEL<br />
18 orang<br />
Periode TI<br />
Tahap Persiapan<br />
Penetapan tempat penelitian<br />
Meminta persetujuan (subjek)<br />
Data antropometri<br />
Membuat desain<br />
Mempersiapan alat dan petugas<br />
Tray out tempat dan uji coba<br />
Tahap Pelaksanaan<br />
Aktivitas penangkapan Tanpa Intervensi<br />
Pengukuran / Pengambilan Data<br />
Kinerja:<br />
1) beban kerja,<br />
2) kelelahan,<br />
3) keluhan muskuloskeletal<br />
4) kesejahteraan<br />
Washing Out<br />
3 hari<br />
Periode DI<br />
Tahap Persiapan<br />
Penetapan tempat penelitian<br />
Meminta persetujuan (subjek)<br />
Data antropometri<br />
Membuat desain<br />
Mempersiapan alat dan petugas<br />
Tray out tempat dan uji coba<br />
Tahap Pelaksanaan<br />
Aktivitas penangkapan dengan Intervensi<br />
Pengukuran / Pengambilan Data<br />
Kinerja:<br />
1) beban kerja,<br />
2) kelelahan,<br />
3) keluhan muskuloskeletal<br />
4) kesejahteraan<br />
Gambar 4.7. Alur Penelitian<br />
Treatment by subject<br />
Analisisnya uji t-paired<br />
137
5.1 Subjek Penelitian<br />
BAB V<br />
HASIL PENELITIAN<br />
Data karakteristik subjek nelayan pukat cincin meliputi : umur, berat<br />
badan, tinggi badan, dan indeks masa tubuh (IMT), disajikan pada Tabel 5.1.<br />
Tabel 5.1<br />
Data Karakteristik Subjek Penelitian<br />
Karakteristik Subjek Rerata SD Rentangan<br />
Berat badan (kg) 63,06 3,15 57 – 70<br />
Umur (thn) 51,28 3,34 45 – 57<br />
Tinggi badan (cm) 160,94 4,09 153 – 168<br />
Indeks masa tubuh (IMT, kg/m 2 ) 24,35 0,97 22,04 – 25,48<br />
Dari Tabel 5.1 terlihat bahwa berat badan subjek berkisar dari 57 kg<br />
sampai 70 kg dengan rerata 63,06 ± 3,15 kg. Umur subjek berkisat dari 45 tahun<br />
sampai 57 tahun dengan rerata 51,28 ± 3,34 tahun. Tinggi badan subjek berkisar<br />
dari 153 cm sampai 168 cm dengan rerata 160,94 ± 4,09 cm. Berdasarkan data<br />
berat badan dan tinggi badan maka diperoleh IMT subjek berkisar dari 22,04<br />
sampai 25,48 kg/m 2 .<br />
Indeks Massa Tubuh (IMT) dan umur subjek menjadi unsur karakteristik<br />
utama dalam menentukan sampel yang terlibat dalam penelitian, terutama<br />
berkaitan dengan kriteria inklusi sebagaimana dinyatakan dalam Bab III.<br />
138
5.2 Antropometri Subjek<br />
139<br />
Data Pengukuran antropometri subjek dalam penelitian ini adalah<br />
Antropometri duduk, dimana pada saat dukur subjek dalam posisi duduk tegak di<br />
atas buritan perahu pada proses penangkapan ikan di saat menarik pukat cincin.<br />
Penerapan data antropometri memerlukan nilai rerata dan simpang baku dari data<br />
pengamatan yang berdistribusi normal dan nilai persentil, sebagaimana tabel 5.2<br />
di bawah ini.<br />
Tabel 5.2<br />
Nilai Persentil, Simpang Baku dan Rentangan Antropometri Subjek<br />
Nelayan Pukat Cincin<br />
Antropometri Tubuh<br />
(cm)<br />
Jangkauan Lengan<br />
Tinggi Badan Duduk<br />
Tinggi Mata Duduk<br />
Tinggi Popliteal<br />
Panjang Lengan Atas<br />
Panjang Lengan Bawah<br />
Tinggi Siku dalam Posisi<br />
Duduk<br />
5.3 Kondisi Lingkungan Kerja<br />
Persentil 5<br />
(5 th )<br />
65,61<br />
113,53<br />
102,80<br />
37,58<br />
27,03<br />
22,37<br />
53,93<br />
Persentil 95<br />
(95 th )<br />
73,43<br />
123,97<br />
115,07<br />
48,17<br />
31,87<br />
27,98<br />
64,04<br />
Simpang<br />
Baku (SB)<br />
2,64<br />
3,36<br />
3,74<br />
2,63<br />
1,73<br />
1,41<br />
3,04<br />
Rentangan<br />
(cm)<br />
65 –76<br />
115 – 12<br />
103 – 117<br />
37 – 49<br />
26 – 35<br />
22 – 30<br />
53 - 65<br />
Kondisi lingkungan kerja yang dimaksud adalah mengenai kondisi iklim<br />
mikro tempat kerja nelayan pukat cincin melakukan proses penangkapan ikan di<br />
perairan laut Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.<br />
Dalam penelitian ini iklim mikro yang didata meliputi kecepatan angin, suhu<br />
udara, dan kelembaban relatif (relative humidity). Data hasil pengukuran disajikan<br />
pada Lampiran 8. Hasil uji normalitas data iklim mikro disajikan pada Lampiran
140<br />
12. Hasil pada Lampiran 9 menunjukkan bahwa data iklim mikro pada periode I<br />
sampai periode IV tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan<br />
p
141<br />
Berdasarkan uji beda iklim mikro dengan menggunakan uji Mann-Whitney<br />
diperoleh bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (p>0,05), berarti tidak ada<br />
perubahan yang bermakna antara periode tanpa intervensi dan periode dengan<br />
intervensi.<br />
5.4 Beban Kerja<br />
Beban kerja dinilai dari perubahan denyut nadi nelayan pada saat<br />
melakukan penarikan pukat cincin, yang dihitung dengan metode sepuluh denyut<br />
(ten pulse method) pada nadi radialis tangan kiri dalam posisi berdiri sebelum<br />
intervensi dan dalam posisi duduk setelah melakukan intervensi. Denyut nadi<br />
yang dihitung adalah : a) denyut nadi istirahat (rest pulse rate) yang dihitung<br />
adalah sebelum nelayan melakukan penangkapan ikan, b) denyut nadi kerja (work<br />
pulse rate) yang dihitung adalah setiap kali melakukan penangkapan pada saat<br />
menarik tali pukat cincin dan diukur dengan cepat sehingga nelayan belum sempat<br />
istirahat, dan c) nadi kerja (working pulse rate), yang dihitung adalah denyut nadi<br />
kerja (DNK) dikurangi denyut nadi istirahat (DNI) sama dengan nadi kerja (NK)<br />
sesudah nelayan selesai menarik pukat cincin.<br />
Hasil pengamatan beban kerja yang diukur dari denyut nadi kerja sesuai<br />
prosedur metodologis yang telah ditetapkan, disajikan pada Lampiran 11. Hasil uji<br />
normalitas data untuk rata-rata denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja dan nadi<br />
kerja disajikan pada Lampiran 12. Berdasarkan hasil tersebut maka terlihat bahwa<br />
data denyut nadi istirahat tampa intervensi dan dengan intervensi hanya dua
142<br />
semua berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan p > 0,05, yang<br />
lainnya tidak dengan p
Tabel 5.5<br />
Hasil Uji Beda Rerata Denyut Nadi Istirahat, Denyut Nadi Kerja Dan Nadi<br />
Kerja Sebelum Intervensi dan Dengan Intervensi<br />
Parameter<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD z p<br />
DNI 75,33 1,14 71,33 1,24 -3,748 0,000<br />
DNK 142,44 6,34 102,61 1,58 -3,733 0,000<br />
NK 67,11 6,75 31,17 2,04 -3,729 0,000<br />
143<br />
Oleh karena denyut nadi istirahat berbeda secara signifikan (p
144<br />
kategori. Sebagaimana yang diuraikan dalam Bab IV, pengamatan skor kelelahan<br />
juga dilakukan dua kali setiap periode aktivitas penangkapan ikan, yaitu sebelum<br />
subjek melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas.<br />
Hasil pengamatan skor kelelahan subjek berdasarkan prosedur<br />
metodologis yang telah ditetapkan disajikan pada Lampiran 17 a s/d (d). Hasil Uji<br />
Normalitas data skor kelelahan tiap kategori disajikan pada Lampiran 18, yang<br />
dapat riringkas dalam Tabel 5.6.<br />
Tabel 5.6<br />
Hasil Uji Normalitas Data Skor Kelelahan Sebelum Aktivitas KerjaTanpa<br />
Intervensi dan Dengan Intervensi.<br />
No Parameter<br />
N<br />
Orang<br />
Rerata SD p<br />
a. Periode Tanpa Intervensi<br />
1. Kategori Aktivitas Melemah 18 21,583 0,888 0,140<br />
2. Kategori Motivasi Melemah 18 21,403 0,777 0,236<br />
3. Kategori Kelelahan Fisik 18 18,875 1,976 0,968<br />
Total Kategori 18 61,861 3,641 0,220<br />
b. Periode dengan Intervensi<br />
1. Kategori Aktivitas Melemah 18 18,653 0,675 0,027<br />
2. Kategori Motivasi Melemah 18 19,347 0,687 0,668<br />
3. Kategori Kelelahan Fisik 18 18,819 0,939 0,220<br />
Total Kategori 18 56,819 2,301 0,006<br />
Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Data yang tidak berasal dari<br />
populasi yang berdistribusi normal dengan nilai p
145<br />
Hasil uji beda rerata skor kelelahan sebelum aktivitas penangkapan ikan<br />
dengan uji Wilcoxon dan uji-t disajikan pada Lampiran 19. Ringkasan hasil<br />
tersebut disajikan pada Tabel 5.7.<br />
Tabel 5.7<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Kelelahan Sebelum Aktivitas Kerja Periode<br />
Tanpa Intervensi dan Periode Dengan Intervensi.<br />
Skor Kelelahan<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD z/t p<br />
Kategori Aktivitas<br />
Melemah<br />
21,583 0,888 18,653 0,675 -3,730 0,000<br />
Kategori Motivasi<br />
Melemah<br />
21,403 0,777 19,347 0,687 9,629 0,000<br />
Kategori<br />
Kelelahan Fisik<br />
18,875 1,976 18,819 0,939 -123,973 0,000<br />
Total Ketegori 61,861 3,641 56,819 2,301 -1,785 0,074<br />
Berdasarkan hasil pada Tabel 5.7 dapat dikemukakan bahwa pada taraf<br />
signifikan 5% rerata skor kelelahan semua kategori sebelum melakukan aktivitas<br />
pada periode tanpa intervensi (TI) dan periode dengan intervensi (DI) berbeda<br />
secara signifikan dengan nilai p0,05 yaitu p=0,074. Perbedaan rerata skor<br />
kelelahan semua kategori periode tanpa intervensi dan periode dengan intervensi<br />
diuji dari selisih rerata sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kerja proses<br />
penagkapan ikan, sedangkan untuk perbedaan skor total, didapati dari rerata<br />
sesudah aktivitas penangkapan ikan.<br />
Hasil Uji Normalitas data rerata selisih skor kelelahan tiap kategori<br />
disajikan pada Lampiran 20, yang diringkaskan pada Tabel 5.8.
Tabel 5.8<br />
Hasil Uji Normalitas Data Rerata Selisih Skor Kelelahan Setelah dan<br />
Sebelum Aktivitas Kerja Tanpa Intervensi dan Dengan Intervensi.<br />
No Parameter<br />
N<br />
Orang<br />
Rerata SD p<br />
a. Periode Tanpa Intervensi<br />
1. Kategori Aktivitas Melemah 18 22,75 1,10 0,231<br />
2. Kategori Motivasi Melemah 18 15,56 1,15 0,946<br />
3. Kategori Kelelahan Fisik 18 20,32 1,41 0,518<br />
Total Kategori 18 58,62 2,73 0,974<br />
b. Periode dengan Intervensi<br />
1. Kategori Aktivitas Melemah 18 18,21 2,07 0,361<br />
2. Kategori Motivasi Melemah 18 13,74 1,49 0,623<br />
3. Kategori Kelelahan Fisik 18 17,21 1,43 0,405<br />
Total Kategori 18 49,15 3,12 0,365<br />
146<br />
Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua data berasal dari<br />
populasi yang berdistribusi normal dengan nilai p>0,05. Perbedaan selisih skor<br />
kelelahan semua kategori dilakukan dengan uji t-t.<br />
5.5.1 Kategori aktivitas melemah (item 1-10)<br />
Hasil uji beda rerata selisih skor kelelahan setelah dan sebelum aktivitas<br />
penangkapan ikan dengan uji-t disajikan pada Lampiran 21. Ringkasan hasil uji<br />
beda untuk kategori aktivitas melemah disajikan pada Tabel 5.9.
Tabel 5.9<br />
Hasil Uji Beda Rerata Selisih Skor Kelelahan Semua Kategori dan Total<br />
Kategori Tanpa Intervensi dan Dengan Intervensi.<br />
Periode<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD t p<br />
Kategori Aktivitas<br />
Melemah<br />
22,75 1,10 18,21 2,07 3,187 0,000<br />
Kategori Motivasi<br />
Melemah<br />
15,56 1,15 13,74 1,49 3,353 0,000<br />
Kategori Kelelahan<br />
Fisik<br />
20,32 1,41 17,21 1,43 -57,500 0,000<br />
Total Kategori 58,62 2,73 49,15 3,12 -57,500 0,000<br />
147<br />
Berdasarkan hasil pada Tabel 5.9 dapat dikemukakan bahwa pada taraf<br />
signifikansi 5% rerata selisih skor kelelahan kategori aktivitas melemah pada<br />
periode tanpa intervensi (TI) dan periode dengan intervensi (DI) berbeda secara<br />
signifikan dengan nilai p
148<br />
Hasil pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%<br />
terdapat perbedaan yang signifikan (p
149<br />
ergonomi pada aktivitas penangkapan ikan telah menurunkan skor kelelahan<br />
subjek secara signifikan (p
150<br />
Hasil uji beda rerata skor keluhan muskuloskeletal sebelum dan sesudah<br />
aktivitas kerja proses penangkapan ikan, dengan uji wilcoxom disajikan pada<br />
Lampiran 23. Ringkasan hasil tersebut disajikan pada Tabel 5.12.<br />
Tabel 5.12.<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Keluhan Muskuloskeletal Sebelum dan Sesudah<br />
Aktivitas Kerja pada Tanpa Intervensi dan Dengan Intervensi.<br />
Periode<br />
Skor Sebelum<br />
Aktivitas<br />
Skor Sesudah<br />
Aktivitas<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD Z p<br />
42,47 0,99 42,14 3,79 -0,240 0,810<br />
88,75 7,89 76,53 9,32 -3,724 0,000<br />
Berdasarkan hasil pada tabel 5.12 dapat dikemukakan bahwa pada taraf<br />
signifikansi 5% rerata skor keluhan muskuloskeletal sebelum melakukan aktivitas<br />
penangkapan ikan pada periode tanpa intervensi (TI) dan periode dengan<br />
intervensi (DI) tidak berbeda secara signifikan dengan nilai p>0,05. Perbedaan<br />
rerata skor keluhan muskuloskeletal periode sebelum intervensi dan periode<br />
dengan intervensi diuji dari rerata skor sesudak aktivitas penangkapan ikan.<br />
Berdasarkan hasil pada Tabel 5.12 dapat dikemukakan bahwa pada taraf<br />
signifikansi 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata skor keluhan<br />
muskuloskeletal subjek sebelum intervensi dan dengan intervensi dalam proses<br />
penangkapan ikan. Hal tersebut terlihat dari nilai p < 0,05.<br />
Hasil-hasil yang diperoleh mengenai beban kerja, (denyut nadi), kelelahan,<br />
dan keluhan muskuloskeletal sebagai indikator kinerja diringkaskan pada<br />
Tabel 5.13.
Tabel 5.13.<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Kinerja Subjek pada Tanpa Intervensi<br />
dan Dengan Intervensi.<br />
151<br />
Indikator<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Perubahan Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD Nilai/Skor % t/z P<br />
Nadi Kerja 67,111 6,747 31,167 2,036 -35,94 -53,56 -3,748 0,000<br />
Kelelahan 142,44 6,34 102,61 1,58 -39,83 -27,96 -3,733 0,000<br />
Kel.Mus. 67,11 6,75 31,17 2,04 -35,94 -53,55 -3,729 0,000<br />
Hasil pada Tabel 5.13 menunjukkan bahwa rangkaian intervensi pada<br />
aktivitas penangkapan ikan telah meningkatkan kinerja subjek secara signifikan<br />
(p
Tabel 5.14<br />
Hasil Uji Normalitas Data Rerata Skor Kesejahteraan Kepuasan Kerja<br />
Subjek Tanpa Intervensi dan Dengan Intervensi<br />
No Parameter<br />
N<br />
Orang<br />
Rerata SD p<br />
1. Periode TIN 18 47,64 3,97 0,006<br />
2. Periode DIN 18 51,49 1,48 0,359<br />
152<br />
Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu data yaitu skor<br />
sebeum intervensi tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan<br />
p=0,006. Perbedaan rerata skor kesejahteraan pada periode tanpa intervensi dan<br />
periode dengan intervensi diuji dengan uji-Wilcoxon.<br />
Tabel 5.15<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Kesejahteraan Kepuasan Kerja Subjek<br />
Tanpa Intervensi dan Dengan Intervensi.<br />
Indikator<br />
Periode Tanpa<br />
Intervensi<br />
Periode Dengan<br />
Intervensi<br />
Perubahan Statistik<br />
Rerata SD Rerata SD Nilai/Skor % t/z p<br />
Kesejahteraan 47,64 3,97 51,49 1,48 3,85 8,08 -3,580 0,000<br />
Hasil uji beda rerata skor kesejahteraan subjek tanpa intervensi dan dengan<br />
intervensi berdasarkan Tabel 5.15 menunjukkan bahwa pada taraf signifikan 5%<br />
terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata skor kesejahteraan subjek periode<br />
tanpa intervensi dan dengan intervensi. Hal tersebut terlihat dari nilai p < 0,05.<br />
Perbedaan yang signifikan rerata skor kesejaheraan menunjukkan dengan jelas<br />
terdapat adanya bahwa rangkaian intervensi ergonomi pada aktivitas penangkapan<br />
ikan telah meningkatkan kesejahteraan secara signifikan (p < 0,05).
5.7.2 Produktivitas<br />
153<br />
Produktivitas ditentukan berdasarkan perbandingan antara output (O)<br />
dengan input (I) dan time (T), produktivitas yang dihitung dalam penelitian ini<br />
berdasarkan perhitungan produktivitas parsial, dimana output adalah rerata berat<br />
tarikan pukat cincin yang ditarik nelayan pada waktu proses penangkapan ikan.<br />
sedangkan input adalah rerata beban kerja yang diterima oleh 18 orang nelayan<br />
selama 6 jam kerja, dalam hal ini beban kerja adalah hasil perhitungan nadi kerja<br />
dalam satuan denyut per menit.<br />
Hasil perhitungan produktivitas sebelum intervensi bahwa berat tarikan<br />
pukat cincin yang terdiri dari : a) berat tali dan pelampung = 128 kg, b) berat<br />
jaring = 325 kg, c) berat pemberat (timah), tali dan cincin = 500 kg. Total berat<br />
tarikan = 953 kg yang ditarik oleh 18 orang nelayan selama 6 jam kerja, yang<br />
dimulai dengan ; (a) penawuran jaring = 10 menit; (b) melingkar secara horisontal<br />
= 10 menit; (c) memagari jaring secara vertikal dari permukaan sampai suatu<br />
kedalaman = 10 menit ; (d) mengurung dengan menutup bagian bawah jaring = 10<br />
menit; dan (e) menarik tali pukat cincin = 300 menit. Jadi total waktu penarikan =<br />
340 menit atau 6 jam x 18 orang nelayan = 108 jam kerja.<br />
Setelah dengan intervensi bahwa total berat tarikan pukat cincin dari<br />
masing-masing bagian yaitu : (a) tali dan pelampung turun menjadi = 100 kg;<br />
(b) berat tarikan jaring turun menjadi = 200 kg; dan (c) berat tarikan tali cincin<br />
turun menjadi = 300 kg, sehingga total tarikan pukat cincin setelah dilakukan<br />
intervensi menjadi 600 kg atau turun sebesar 353 kg atau 3,53%.
154<br />
Setelah dilakukan intervensi ergonomi dari hasil analisis produktivitas<br />
kerja periode sebelum intervensi dan periode dengan intervensi pada 6 jam kerja<br />
yang sama dapat ditujukan pada Gambar 5.1.<br />
DK<br />
23.30 24.00 24.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 04.00 04.30 05.00<br />
Gambar 5.1<br />
Grafik rerata skor produktivitas subjek pada periode sebelum intervensi dan<br />
periode dengan intervensi pada 6 jam kerja diantara waktu 30 menit.<br />
Dari grafik diatas dapat dinyatakan bahwa dengan intervensi ergonomi<br />
maka terjadi peningkatan produktivitas kerja diantara 18 orang nelayan dimana<br />
subjek merasakan tarikan pukat cincin pada saat proses penangkapan semakin<br />
panjang, maka semakin ringan selama 6 jam kerja.<br />
Kelebihan perhitungan produktivitas dalam penelitian ini adalah<br />
menghitung produksi hasil penangkapan ikan sebelum intervensi dan dengan<br />
intervensi, dimana terdapat perbedaan bermakna produksi penangkapan sebelum<br />
intervensi 5.000 kg per bulan. Sedangkan setelah dilakukan intervensi terjadi<br />
SI<br />
DI<br />
W
155<br />
peningkatan produksi hasil tangkapan sebanyak 8,166 kg per bulan atau terjadi<br />
peningkatan produksi penangkapan sebesar 8,08%.<br />
Dengan demikian dilihat dari segi investasi bahwa perusahaan dalam hal ini<br />
pemilik pukat cincin mengalami keuntungan setiap bulan 3.166 kg per bulan dan<br />
nelayan penangkap mendapatkan keuntungan sebesar 91.700.000,- per tahun.<br />
Sehingga dengan intervensi ergonomi baik perusahaan pemilik pukat cincin<br />
maupun nelayan bersama-sama mendapatkan keuntungan.<br />
5.7.3 Keuntungan Nelayan<br />
Data hasil penelitian keuntungan nelayan diperoleh berdasarkan<br />
perhitungan produksi penangkapan ikan yang sudah di pasarkan, sehingga dalam<br />
pembagian melalui sistim bagi hasil nelayan mendapatkan keuntungan dalam<br />
bentuk uang. Analisis perhitungan ekonomi dilakukan sebelum dan dengan<br />
intervensi ergonomi. Hasil analisis ekonomi yang dimaksud diuraikan berikut ini.<br />
1) Capital Investment peralatan penangkapan ikan pukat cincin berubah<br />
dari sebelum intervensi, Total Investmen Rp. 785.000.000,- menjadi<br />
Rp. 800.000.000,-.<br />
2) Working Capital yang terdiri dari Variabel Cost dan Fixed Cost tidak<br />
mengalami perubahan sebelum dan sesudah intervensi sehingga Total<br />
Investment menjadi Rp. 2.801.000.000,-.<br />
3) Total investment yang terdiri dari capital investment dan working capital<br />
berubah dari Rp. 900.000.000,- sebelum intervensi menjadi Rp. 917.000.000,-<br />
setelah dilakukan intervensi.
156<br />
4) Bunga modal juga turut mengalami perubahan dari Rp. 144.000.000,-<br />
sebelum intervensi menjadi Rp. 146.720.000,- setelah dilakukan intervensi.<br />
5) Total Variable Cost mengalami perubahan dari Rp. 2.457.800.000,- menjadi<br />
Rp. 3.406.200.000,- setelah dilakukan intervensi.<br />
6) Total Fixed Cost tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah intervensi,<br />
tetap Rp. 434.475.000,-.<br />
7) a. Sebelum intervensi Perhitungan Profit, Break Event Point (BEP) dan<br />
Procentage Return on Investment (ROI) :<br />
Variable cost = V = Rp. 2.457.800.000,-/Thn Rp. 204.816.000,-/Bln<br />
Fixed cost = F = Rp. 343.475.000,-/Thn Rp. 28.622.916,-/Bln<br />
TOTAL COST Rp. 2.801.275.000,-/Thn Rp. 233.438.916,-/Bln<br />
Hasil Tangkapan/Penjualan = S<br />
600 Ton ikan-ikan pelagis.<br />
Dasar @ Rp.5.500 Rp.3.500.000.000,-/Thn Rp. 291.666.000,-/Bln<br />
Gross Profit :<br />
S - ( V + F ) Rp.698.725.000,-/Thn Rp. 58.227.084,-/Bln<br />
S - V Rp.1.042.200.000,-/Thn Rp. 113.600.000,-/Bln<br />
Break Event Point (BEP) :<br />
Coorporation Tax =<br />
10 % x Gross Profit = Rp.69.872.500,-/Thn Rp. 5.822.708,-/Bln<br />
Net Profit = Gross Profit -<br />
Coorporation Tax Rp. 628.852.500./Thn Rp. 5.822.708,-/Bln.
Procentage Return On Fixed Investment (ROI) =<br />
157<br />
b. Dengan Intervensi. Perhitungan Ptrofit, Break Event Point (BEP) Dan<br />
Procentage Return On Investment (ROI) :<br />
Variable cost = V Rp.3.406.200.000,-/Thn Rp. 283.850.000,-/Bln<br />
Fixed cost = F Rp. 343.475.000,-/Thn Rp. 28.622.916,-/Bln<br />
––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––<br />
TOTAL COST Rp. 3.749.675.000,-/Thn Rp. 312.472.916,-/Bln<br />
Hasil Tangkapan/Penjualan = S<br />
980 Ton sejenis ikan-ikan pelagis.<br />
Dasar @ Rp.5.500 Rp.5.390.000.000,-/Thn Rp. 449.666.666,-/Bln<br />
Gross Profit :<br />
S - ( V + F ) Rp.2.021.079.825./Thn Rp. 1.684.233.181/Bln<br />
S - V Rp.1.983.800.000,-/Thn Rp. 165.316.666,-/Bln<br />
Break Event Point (BEP) :<br />
Coorporation Tax =<br />
10 % x Gross Profit = Rp.2.021.079.825-Thn Rp. 1.684.233.181/ Bln<br />
Net Profit = Gross Profit - Coorporation Tax<br />
Rp.202.107.982,-/Thn Rp. 168.423.319,-/Bln.<br />
.
Procentage Return On Fixed Investment (ROI) =<br />
= 63,82%<br />
158<br />
8) Production capacity sebelum intervensi pinjaman yang harus dikembalikan<br />
kepada Bank = Nihil. Sedangkan dengan intervensi pinjaman yang harus<br />
dikembalikan pada tahun ke IX antara pemilik pukat cincin dan nelayan<br />
penangkap ikan sama-sama mendapatkan keuntungan/profit.
6.1 Karakteristik Subjek<br />
BAB VI<br />
PEMBAHASAN<br />
159<br />
Subjek penelitian ini semuanya berjenis kelamin laki-laki, dan<br />
karakteristik subjek yang dilihat adalah: berat badan, tinggi badan (atau indeks<br />
massa tubuh) dan usia. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IMT subjek<br />
berkisar dari minimum 22,04 sampai maksimum 25,48 dengan rerata 24,35<br />
± 0,97 kg/m 2 . Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa subjek memiliki IMT<br />
yang berada dalam kisaran normal, dan nilai ini sesuai dengan kriteria IMT<br />
normal yang dikemukakan oleh Sandowsky (2000) yaitu 18 s/d 25 kg/m 2 .<br />
Dengan kisaran IMT yang lebih sempit sesuai kriteria, berarti variabilitas<br />
subjek dalam penelitan ini lebih kecil, dan hal ini menguntungkan karena menurut<br />
Avellini et al. (1980) subjek dengan IMT yang lebih besar, luas permukaan<br />
tubuhnya juga lebih besar dan dapat kehilangan panas dengan laju lebih cepat<br />
dibandingkan dengan subjek dengan luas permukaan tubuh lebih kecil. Selain itu<br />
kisaran IMT yang lebih sempit juga memperkecil berbagai risiko penyakit dan<br />
keluhan otot di tempat kerja (Schulte, et al., 2007) karena subjek dengan<br />
IMT>25,00 berisiko terhadap penyakit dan keluhan otot di tempat kerja.<br />
Bila dibandingkan dengan subjek yang bukan nelayan dengan jenis<br />
pekerjaan yang berbeda ternyata diperoleh rerata IMT yang tidak jauh berbeda,<br />
seperti yang diperoleh Artayasa (2007), IMT 23,68 kg/m 2 dan Sajiyo (2008), IMT<br />
22,21 kg/m 2 .
160<br />
Umur subjek berkisar dari minimum 45 tahun sampai maksimum 57 tahun<br />
dengan rerata 51,28 ± 3,34 tahun. Rerata umur subjek ini jauh berbeda bila<br />
dibandingkan dengan umur subjek pada penelitian Adiatmika (2007) dan Sajiyo<br />
(2008) yang memperoleh masing-masing 17 s/d 50 tahun dan 30,78±4,63 tahun.<br />
Dengan demikian dilihat dari umur, kisaran umur subjek tergolong sempit<br />
dibanding subjek pada penelitian Adiatmika (2007) dan Sajiyo (2008). Dilihat<br />
dari kriteria umur subjek, semua subjek berada pada kisaran yang ditetapkan yaitu<br />
40 s/d 60 tahun. (Dengan kisaran umur yang sempit seperti yang telah<br />
dikemukakan maka berarti bahwa variabilitas umur antar subjek di dalam<br />
kelompok diperkecil). Hal ini penting karena menurut Rodahl (2003) usia subjek<br />
mempengaruhi respon termal. Subjek dengan umur yang lebih muda kehilangan<br />
panas evaporatif lebih rendah dan suhu kulit lebih tinggi pada kondisi lingkungan<br />
yang sama dibandingkan dengan subjek yang lebih dewasa. Dalam konteks<br />
penelitian ini, variabilitas umur yang sempit turut memperkecil variabilitas<br />
berkaitan dengan respon termal dalam bentuk kehilangan panas tubuh seperti yang<br />
dikemukakan oleh Rodahl (2003).<br />
6.2 Kondisi Lingkungan Kerja<br />
Kondisi lingkungan kerja yang diukur pada penelitian ini adalah suhu<br />
udara, kelembaban relatif dan kecepatan angin. Dicatat setiap interval 10 menit<br />
sepanjang malam selama penelitian berlangsung dari pukul 18.00 s/d 06.00<br />
WITA. Pengukuran variabel lingkungan kerja ditujukan untuk mengetahui kondisi
161<br />
lingkungan kerja dan kondisi yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kualitas<br />
kerja.<br />
Ditemukan bahwa sepanjang periode penelitian, rerata suhu udara pada<br />
periode aktivitas tanpa intervensi adalah terrendah 24,36 ± 1,53 o C dan tertinggi<br />
27,97 ± 0,30 o C. Sedangkan untuk periode dengan intervensi terrendah 24,30<br />
± 1,06 o C dan tertinggi 27,74 ± 1,42 o C.<br />
Dilihat dari nilai rerata suhu udara, dapat dikemukakan bahwa kondisi<br />
suhu lingkungan kerja pada periode tanpa intervensi dan periode dengan<br />
intervensi termasuk di bawah kisaran nyaman untuk daerah tropis yaitu 26 – 28 o C<br />
(Manuaba, 1998d), di bawah kisaran nyaman menurut kriteria Grandjean (1998),<br />
dan jauh di bawah kisaran nyaman untuk pekerja Indonesia yaitu 29-30 o C<br />
(Suma'mur, 1982).<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata suhu udara<br />
pada periode dengan intervensi tidak berbeda secara signifikan dengan rerata pada<br />
periode tanpa intervensi (p>0,05), berarti paparan suhu udara tidak berpengaruh<br />
yaitu sama.<br />
Untuk kelembaban relatif (KR) ditemukan bahwa rerata kelembaban pada<br />
periode aktivitas tanpa intervensi terrendah adalah 74,91 ± 11,09 % dan tertinggi<br />
88,82 ± 4,73%, sedangkan untuk periode dengan intervensi, terrendah 74,83<br />
± 11,64 % dan tertinggi 89,60 ± 4,76%. Harga kelembaban relatif ternyata<br />
termasuk di atas kriteria nyaman untuk orang Indonesia menurut kriteria Manuaba<br />
(1998) yaitu 70-80%, dan jauh di atas kriteria nyaman menurut ASHRAE<br />
(Whytmyre, 2002; Princton Analytical Laboratory, 2004) yaitu 30 − 60%. Kondisi
162<br />
kelembaban relatif yang tidak nyaman ini dapat diatasi dengan serangkaian<br />
intervensi ergonomi sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata<br />
kelembaban relatif udara pada periode dengan intervensi tidak berbeda secara<br />
signifikan dengan rerata pada periode tanpa intervensi (p>0,05). Hal ini berarti<br />
bahwa pada periode tanpa intervensi dan periode dengan intervensi subjek<br />
melakukan aktivitas kerja dengan pengaruh paparan kelembaban relatif udara<br />
yang sama.<br />
Untuk kecepatan angin ditemukan bahwa pada periode tanpa intervensi<br />
rerata kecepatan angin terrendah 0,28 ± 0,28 m/detik dan tertinggi 3,90 ± 0,28<br />
m/det, sedangkan untuk periode dengan intervensi terrendah 0,27 ± 0,38 m/det<br />
dan tertinggi 3,72 ± 1,17 m/det.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata kecepatan<br />
angin pada periode dengan intervensi tidak berbeda secara signifikan dengan<br />
rerata pada periode tanpa intervensi (p>0,05). Hal ini berarti bahwa pada periode<br />
tanpa intervensi dan periode dengan intervensi subjek melakukan aktivitas kerja<br />
dengan pengaruh paparan kecepatan angin yang sama.<br />
Dengan demikian berdasarkan hasil analisis mengenai lingkungan kerja<br />
yang terdiri dari suhu udara, kelembaban relatif dan kecepatan angin, dapat<br />
dikatakan bahwa ternyata kondisi lingkungan kerja pada periode aktivitas tanpa<br />
intervensi dan periode aktivitas dengan intervensi sama saja. Oleh karena itu dapat<br />
dikemukakan bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh yang sama terhadap
163<br />
subjek baik pada periode aktivitas tanpa intervensi maupun periode aktivitas<br />
dengan intervensi<br />
Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa perbedaan kinerja (beban kerja,<br />
kelelahan dan keluhan muskuloskeletal) dan kesejahteraan yang diuraikan pada<br />
bagian-bagian berikut bukanlah akibat dari lingkungan kerja pada waktu aktivitas<br />
kerja dilakukan melainkan akibat perlakuan yang diberikan yaitu serangkaian<br />
intervensi ergonomi.<br />
6.3 Beban Kerja<br />
Sesuai metodologi, pengukuran denyut nadi sebagai indikator beban kerja<br />
dilakukan sebelum bekerja, sedang bekerja dan setelah bekerja dalam empat<br />
periode pengamatan. Satu periode pengamatan terdiri dari satu kali melaut untuk<br />
aktivitas tanpa intervensi dan, setelah periode washing out, satu kali melaut untuk<br />
aktivitas dengan intervensi ergonomi.<br />
Pada periode tanpa intervensi dan periode dengan intervensi, ditemukan<br />
bahwa rerata denyut nadi istirahat adalah: 75,33 ± 1,14 dan 71,33 ± 1,24<br />
denyut/menit. Ternyata denyut nadi istirahat nelayan pukat cincin pada periode<br />
tanpa dan dengan intervensi lebih kecil dari 90 denyut/menit sesuai pendapat Fox,<br />
Bowers and Foss (1988). Nilai-nilai ini: sedikit lebih rendah dari denyut nadi<br />
istirahat pekerja pemangkas pohon (sejenis pohon cemara) yang bervariasi dari<br />
72 s/d 85 denyut/menit dengan rerata 77,8 denyut/menit (Kirk and Parker, 1994);<br />
rendah rendah dari denyut nadi istirahat pekerja pemanen tanaman pertanian lahan<br />
kering dengan denyut nadi istirahat 80,21 denyut/menit (Hasalkar, et.al., 2004);
164<br />
dan hampir sama dengan denyut nadi istirahat pekerja pengangkut kelapa di<br />
Tabanan Bali seperti yang diperoleh Artayasa (2007) sebesar 74,65 denyut/menit.<br />
Meskipun lebih kecil dari 90 denyut/menit, akan tetapi hasil uji-beda<br />
menunjukkan bahwa denyut nadi istirahat pada periode tanpa dan dengan<br />
intervensi ergonomi berbeda secara signifikan (p
165<br />
125−150 denyut/menit. Menurut Christensen (1991) frekuensi denyut nadi kerja<br />
antara 75 sampai 100 denyut/menit masuk dalam kategori beban kerja ringan,<br />
antara 100 sampai 125 denyut/menit masuk dalam kategori sedang, antara 125<br />
sampai 150 denyut/menit masuk dalam kategori berat dan antara 150 sampai 175<br />
denyut/menit masuk dalam kategori sangat berat.<br />
Denyut nadi kerja pada periode dengan intervensi ergonomi sebesar<br />
102,61 ± 1,58 denyut/menit. Nilai ini, sekalipun mengalami menurunan, masih<br />
lebih besar dari nilai kritis (a warning value) yaitu 90 denyut/menit (Blazejczyk<br />
and Blazejczyk, 2007); lebih kecil dari denyut nadi kerja pekerja pemangkas<br />
pohon sejenis cemara dengan denyut nadi 112 denyut/menit (Kirk and Parker,<br />
1994); lebih tinggi dari denyut nadi kerja pekerja pemanen tanaman pertanian<br />
lahan kering dengan denyut nadi kerja sebesar 94,36 denyut/menit (Hasalkar,<br />
et.al., 2004); lebih rendah dari denyut nadi kerja pekerja pemanen padi dengan<br />
menggunakan arit ergonomis dengan denyut nadi kerja berkisar 103 s/d 136<br />
denyut/menit dengan rerata 115,5 ± 11,76 denyut/menit (Sutjana, dkk, 1999). Bila<br />
dilihat hubungan dengan beban kerja, menurut Christensen (dalam Nurmianto,<br />
2004), maka beban kerja aktivitas penangkapan ikan dengan intervensi ergonomi<br />
ketika sedang bekerja, turun menjadi beban kerja sedang yang terletak dalam<br />
kisaran 100−125 denyut/menit.<br />
Sekalipun pada periode dengan intervensi ergonomi, terlihat bahwa denyut<br />
nadi kerja mengalami penurunan dan beban kerja mengalami perubahan dari<br />
beban kerja berat menjadi beban kerja ringan sampai sedang, akan tetapi untuk<br />
melihat beda rerata secara statistk harus dilihat dari nadi kerja ketika sedang
166<br />
melakukan aktivitas kerja dan nadi kerja tepat setelah selesai melakukan aktivitas<br />
kerja. Hal ini disebabkan denyut nadi istirahat periode tanpa dan dengan<br />
intervensi ergonomi sudah berbeda secara signifikan (p
167<br />
dehidrasi dapat terjadi, apalagi di alam terbuka seperti aktivitas penangkapan ikan di<br />
laut lepas dimana rerata kecepatan angin dapat mencapai jauh melebihi 0,2 m/det.<br />
Lebih lanjut menurut Fox, Bowers and Foss (1988) dan juga Derchak, Ostertag,<br />
and Coyle (2004) dehidrasi pada mulanya muncul karena suatu kenaikan dalam<br />
denyut nadi pada suatu beban kerja tertentu. Peningkatan denyut nadi ini pada suatu<br />
beban kerja yang tetap dinamakan "cardiac drift." Dalam hal ini, berkeringat<br />
mengurangi volume darah dimana ada suatu reduksi dalam kembalinya darah ke<br />
jantung melalui venous system. Untuk dapat mempertahankan Q dan tekanan darah,<br />
denyut nadi (HR) meningkat. Bila dehidrasi berlanjut, venous kembali dan stroke<br />
volume terus berkurang dan denyut nadi (HR) terus meningkat. Proses dehidrasi<br />
menjadi suatu siklus yang berbahaya yang dapat secara cepat menyebabkan seseorang<br />
mengalami bahaya/kerusakan yang berarti (significant harm) ketika Q tidak lagi dapat<br />
dipertahankan meskipun denyut nadi (HR) meningkat.<br />
Dengan demikian, dibandingkan dengan aktivitas tanpa intervensi, maka<br />
intervensi ergonomi telah menghasilkan sistem regulasi yang lebih efisien yang<br />
terlihat dari denyut nadi yang menurun secara signifikan sepanjang aktivitas dan<br />
dipertahankannya stroke volume karena adanya suplesi gizi dalam bentuk segelas<br />
aqua (240 ml) serta satu gelas teh manis (suhu 29−30 o C) setelah 2 x 40 menit<br />
(menit ke 80) yang menghindari kemungkinan terjadinya dehidrasi.<br />
Bila dihubungkan dengan peningkatan denyut nadi yang direkomendasikan<br />
oleh Grandjean (1988), yaitu sebesar 30 denyut/menit, maka peningkatan denyut<br />
nadi nelayan pukat cincin di Amurang, sudah melampaui batas karena secara<br />
rerata terjadi kenaikan 67,11 denyut/menit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
168<br />
kondisi ini, para nelayan tidak direkomendasikan bekerja selama delapan jam<br />
secara terus-menerus, apalagi pekerjaan ini dilakukan pada malam hari. Menurut<br />
Grandjean (1988), bila bekerja pada malam hari, maka irama faal sedikit<br />
banyaknya pasti terganggu, karena fungsi fisiologis pekerja tidak dapat<br />
disesuaikan dengan irama kerja tersebut. Suhu badan, denyut nadi, tekanan darah<br />
yang bekerja pada malam hari berbeda dengan yang bekerja pada pagi, siang dan<br />
sore (Grandjean, 1988). Metabolisme tidak dapat sepenuhnya atau tidak dapat<br />
sama sekali diadaptasikan dengan kerja malam dan tidur siang. Keseimbangan<br />
elektrolit sebagai akibat albumin dan klorida di darah dapat beradaptasi dengan<br />
keperluan kerja malam dan tidur siang, tetapi pertukaran zat-zat seperti kalium,<br />
sulfur, fosfor, mangan terikat pada sel-sel sehingga dengan pergantian waktu kerja<br />
siang menjadi malam tidak dapat dipengaruhinya. Dari penjelasan tersebut, maka<br />
pada penelitian ini dilakukan tindakan dengan menerapkan pendekatan ergonomi,<br />
sehingga para nelayan tetap dapat bekerja secara terus-menerus dalam kondisi<br />
yang sehat dan nyaman. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah<br />
penerapan pendekatan ergonomi, yakni: diadakan waktu istirahat, pemberikan teh<br />
manis, perbaikan sikap kerja, pengurangan beban angkat melalui desain alat<br />
(katrol ergonomis).<br />
Ketika intervensi ergonomi dilakukan, ternyata peningkatan peningkatan<br />
denyut nadi kerja, hampir sama dengan nilai yang direkomendasikan oleh<br />
Grandjean (1988), yaitu 31,17 denyut/menit. Dengan demikian pekerjaan<br />
penangkapan ikan dapat direkomendasikan untuk dilakukan oleh nelayan pukat
169<br />
cincin, asalkan elemen-elemen intervensi ergonomi yang telah diterapkan dalam<br />
penelitian ini, sebagaimana yang telah dikemukakan, benar-benar dilakukan.<br />
6.4 Kelelahan<br />
6.4.1 Kelelahan Kategori Aktivitas Melemah (item 1-10)<br />
Ditemukan bahwa rerata selisih skor kelelahan kategori aktivitas melemah<br />
(item 1-10) sebelum melakukan aktivitas panangkapan ikan pada periode aktivitas<br />
tanpa dan dengan intervensi ergonomi adalah: 22,75 ± 1,10 dan 18,21 ± 2,07.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata selisih skor<br />
kelelahan subjek untuk kategori aktivitas melemah (item 1-10) pada periode<br />
dengan intervensi berbeda secara signifikan dengan rerata pada periode tanpa<br />
intervensi (p>0,05), dengan nilai p = 0,000. Hal ini berarti bahwa pada periode<br />
tanpa intervensi dan periode dengan intervensi kondisi kelelahan subjek kategori<br />
aktivitas melemah tidak sama.<br />
Adanya perbedaan ini merupakan indikasi bahwa intervensi ergonomi<br />
yang dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan telah berhasil menurunkan<br />
kelelahan kategori aktivitas melemah yang dialami subjek dibandingkan dengan<br />
kondisi tanpa intervensi. Persentase penurunan skor kelelahan subjek untuk<br />
kategori aktivitas melemah (item 1-10) akibat intervensi ergonomi yang dilakukan<br />
pada aktivitas penangkapan ikan dibandingkan dengan aktivitas tanpa intervensi<br />
adalah sebesar 19,96%.
6.4.2 Kelelahan Kategori Motivasi Melemah (item 11-20)<br />
170<br />
Ditemukan bahwa rerata selisih skor kelelahan kategori motivasi melemah<br />
(item 11-21) pada periode aktivitas tanpa dan dengan intervensi ergonomi adalah:<br />
15,56 ± 1,15 dan 13,74 ± 1,49.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata selisih skor<br />
kelelahan subjek untuk kategori motivasi melemah (item 11-21) pada periode<br />
dengan intervensi berbeda secara signifikan dengan rerata pada periode tanpa<br />
intervensi (p>0,05), dengan nilai p = 0,000. Hal ini berarti bahwa pada periode<br />
tanpa intervensi dan periode dengan intervensi kondisi kelelahan subjek kategori<br />
motivasi melemah tidak sama.<br />
Adanya perbedaan ini merupakan indikasi bahwa intervensi ergonomi<br />
yang dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan telah berhasil menurunkan<br />
kelelahan kategori motivasi melemah yang dialami subjek dibandingkan dengan<br />
kondisi tanpa intervensi. Persentase penurunan skor kelelahan subjek untuk<br />
kategori motivasi melemah (item 11-21) akibat intervensi ergonomi yang<br />
dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan dibandingkan dengan aktivitas tanpa<br />
intervensi adalah sebesar: 11,70%.<br />
6.4.3 Kelelahan Kategori Kelelahan Fisik (item 21-30)<br />
Ditemukan bahwa rerata selisih skor kelelahan kategori kelelahan fisik<br />
(item 21-30) pada periode aktivitas tanpa dan dengan intervensi ergonomi adalah:<br />
20,32 ± 1,41 dan 17,21 ± 1,43.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata selisih skor<br />
kelelahan subjek untuk kategori kelelahan fisik (item 21-30) pada periode dengan
171<br />
intervensi berbeda secara signifikan dengan rerata pada periode tanpa intervensi<br />
(p>0,05), dengan nilai p = 0,000. Hal ini berarti bahwa pada periode tanpa<br />
intervensi dan periode dengan intervensi kondisi kelelahan subjek kategori<br />
kelelahan fisik tidak sama. Hal ini berarti bahwa pada periode tanpa intervensi dan<br />
periode dengan intervensi secara rerata kondisi kelelahan subjek kategori<br />
kelelahan fisik tidak sama.<br />
Adanya perbedaan ini merupakan indikasi bahwa intervensi ergonomi<br />
yang dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan telah berhasil menurunkan<br />
kelelahan kategori kelelahan fisik yang dialami subjek dibandingkan dengan<br />
kondisi tanpa intervensi. Persentase penurunan skor kelelahan subjek untuk<br />
kategori kelelahan fisik (item 21-30) akibat intervensi ergonomi yang dilakukan<br />
pada aktivitas penangkapan ikan dibandingkan dengan aktivitas tanpa intervensi<br />
adalah sebesar: 15,31%.<br />
6.4.4 Kelelahan Secara Umum (total ketiga kategori)<br />
Ditemukan bahwa rerata selisih skor kelelahan total kategori (item 1-30)<br />
pada periode aktivitas tanpa dan dengan intervensi ergonomi adalah: 58,62 ± 2,73<br />
dan 49,156 ± 3,12.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata selisih skor<br />
kelelahan subjek untuk total kategori (item 1-30) pada periode tanpa dan dengan<br />
intervensi ergonomi terdapat perbedaan yang signifikan (p
172<br />
Adanya perbedaan ini merupakan indikasi bahwa intervensi ergonomi<br />
yang dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan telah berhasil menurunkan<br />
kelelahan yang dialami subjek dibandingkan dengan kondisi tanpa intervensi.<br />
Persentase penurunan skor kelelahan subjek (item 1-30) akibat intervensi<br />
ergonomi yang dilakukan pada aktivitas penangkapan ikan dibandingkan dengan<br />
aktivitas tanpa intervensi adalah sebesar: 16,15%.<br />
Dapat dikatakan bahwa dengan intervensi ergonomi pada penangkapan<br />
ikan, telah terjadi penurunan skor kelelahan subjek nelayan baik pada masing-<br />
masing kategori maupun secara keseluruhan. Dibandingkan dengan kondisi tanpa<br />
intervensi, skor kelelahan kategori aktivitas melemah turun 19,96%, skor<br />
kelelahan kategori motivasi melemah turun 11,70%, skor kelelahan kategori<br />
kelelahan fisik turun 15,31%, dan skor total semua kategori turun 16,15%.<br />
Persentase penurunan skor kelelahan ini lebih rendah dibandingkan dengan yang<br />
diperoleh Sutajaya (2006) yang mendapatkan skor kategori aktivitas melemah<br />
turun 64,0%, kategori motivasi melemah turun 45,8%, kategori kelelahan fisik<br />
turun 39,9% dan secara keseluruhan turun 47,4%. Persentase penurunan skor<br />
kelelahan umum ini lebih rendah dengan yang diperoleh Palilingan (2008) yang<br />
mendapatkan bahwa dengan intervensi ergonomi terjadi penurunan skor kelelahan<br />
umum: skor kategori aktivitas melemah turun 30,65%, skor kategori motivasi<br />
melemah turun 41,66%, skor kategori kelelahan fisik turun 31,58%, dan skor<br />
gabungan ketiga ketegori turun 34,01% pada subjek mahasiswa yang melakukan<br />
aktivitas praktikum lapangan di daerah dingin Rurukan Kecamatan Tomohon.<br />
Persentase penurunan ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang
173<br />
diperoleh Wijana (2008) yang mendapatkan skor kategori aktivitas melemah turun<br />
78,466%, kategori motivasi melemah turun 67,89%, kategori kelelahan fisik turun<br />
77,19% dan secara keseluruhan turun 73,76%.<br />
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya penurunan skor<br />
kelelahan secara signifikan (p
174<br />
pada pendapat Manuaba (1983; 1992) dapat dikemukakan bahwa memang benar<br />
aktivitas penangkapan ikan tanpa intervensi ergonomi: (a) bersifat monoton<br />
karena subjek melakukan aktivitas kerja dalam sikap duduk selama aktivitas berl<br />
angsung; (b) berlangsung cukup lama dimana subjek terpapar pada iklim mikro<br />
setempat sekitar enam jam dengan kondisi yang buruk; (c) adanya iklim mikro<br />
yang buruk (dingin) yang berada di luar kategori nyaman; dan (d) adanya<br />
keluhan-keluhan fisik karena sikap-sikap yang tidak ergonomis sewaktu<br />
melakukan aktivitas penangkapan ikan.<br />
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya penurunan skor<br />
kelelahan umum secara signifikan (p0,05) dengan nilai p sebesar 0,810. Hal ini berarti bahwa pada<br />
periode tanpa intervensi dan periode dengan intervensi kondisi subjek dilihat dari<br />
skor keluhan muskuloskeletal sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan
175<br />
tidak berbeda. Perbedaan rerata skor keluhan muskuloskeletal subjek oleh karena<br />
perlakuan yang diberikan dapat dilihat dari rerata skor keluhan muskuloskeletal<br />
setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan.<br />
Ditemukan bahwa rerata skor keluhan muskuloskeletal setelah melakukan<br />
aktivitas penangkapan ikan pada periode tanpa dan dengan intervensi ergonomi<br />
adalah 88,75 ± 7,89 dan 76,53 ± 9,32.<br />
Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata skor<br />
keluhan muskuloskeletal subjek setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan<br />
pada periode dengan intervensi berbeda secara signifikan dengan rerata skor<br />
keluhan muskuloskeletal subjek setelah melakukan aktivitas pada periode tanpa<br />
intervensi (p
176<br />
Persentase penurunan skor keluhan muskuloskeletal subjek dilihat dari<br />
skor setelah kerja adalah adalah 13,77%. Persentase penurunan ini, terutama<br />
dilihat dari rerata persentasi penurunan, jauh lebih kecil dibandingkan dengan<br />
yang diperoleh oleh: Purnomo (2007) yang mendapatkan bahwa dengan intervensi<br />
ergonomi terjadi penurunan skor keluhan muskuloskeletal sebesar 87,8% pada<br />
pekerja industri Gerabah di Kasongan Bantul, Sajiyo (2008) yang mendapatkan<br />
bahwa dengan intervensi ergonomi terjadi penurunan 66,94% keluhan bagian<br />
kepala, 61,52% keluhan bagian bahu, dan 81,75% keluhan anggota gerak atas<br />
pada pekerja tukang giling sigaret kretek tangan pada industri rokok “X” di kediri<br />
Jawa Timur.<br />
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya penurunan skor<br />
keluhan muskuloskeletal secara signifikan (p
177<br />
motivasi melemah, kelelahan fisik, maupun kelelahan secara umum; dan<br />
menurunkan keluhan muskuloskelatal subjek. Dengan demikian dapat dikatakan<br />
bahwa, dibandingkan dengan aktivitas kerja tanpa intervensi, aktivitas dengan<br />
intervensi ergonomi ternyata dapat meningkatkan kinerja subjek di dalam<br />
melakukan aktivitas penangkapan ikan, yang ditandai dengan penurunan beban<br />
kerja, penurunan tingkat kelelahan, dan penurunan keluhan muskuloskeletal.<br />
6.6 Kesejahteraan<br />
6.6.1 Kepuasan Kerja<br />
Ditemukan bahwa rerata skor kesejahteraan dilihat dari aspek kepuasan<br />
kerja bahwa periode tanpa dan dengan intervensi ergonomi adalah 47,64 ± 3,97<br />
dan 51,49 ± 1,48. Dengan uji beda rerata, ditemukan bahwa secara statistik rerata<br />
skor kesejahteraan kepuasan kerja subjek dalam melakukan aktivitas pada periode<br />
dengan intervensi berbeda secara signifikan dengan rerata pada periode tanpa<br />
intervensi (p
178<br />
tampak konkrit (tangibles) yang meliputi profesi nelayan sebagai penangkap ikan<br />
dan penampilan menggunakan katrol sebagai alat bantu kerja, jaket, topi dan<br />
sarung tangan serta alas duduk pada waktu melaksanakan proses penarikan pukat<br />
cincin dari masing-masing nelayan sesuai tugas dan tanggung jawab yang<br />
diberikan pimpinan atau tonaas, 2) dapat dipercaya (reliability) yang meliputi<br />
kemampuan nelayan dalam memberikan hasil tangkapan dan menerapkan sistim<br />
bagi hasil yang disepakati bersama antara nelayan pemilik pukat cincin dan<br />
nelayan penangkap sehingga kedua-duanya dapat memberikan hasil pelayanan<br />
yang lebih baik, 3) daya tangkap (responsiveness) yang meliputi kesiaptanggapan<br />
nelayan mengikuti permintaan peningkatan produksi penangkapan dan harga ikan<br />
baik harga di pasar lokal maupun internasional, 4) jaminan (assurance), yang<br />
meliputi kepercayaan antara nelayan pemilik pukat cincin dan nelayan penangkap<br />
terhadap pemberian asuransi di hari tua dan keikutsertaan nelayan terhadap<br />
kegiatan sosial kemasyarakatan berdasarkan hak dan kewajiban dari kedua belah<br />
pihak, dan 5) empati (empathy) meliputi kemampuan nelayan dalam menjaga<br />
hubungan yang baik, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang harmonis antara<br />
nelayan pemilik pukat cincin dan nelayan penangkap dan kemampuan nelayan<br />
dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi selama proses<br />
penangkapan ikan sehingga nelayan merasa puas terhadap hasil yang dicapai.<br />
6.6.2 Produktivitas<br />
Dalam penelitian ini, hanya dikaji produktivitas parsial yang dihitung<br />
berdasarkan perbandingan antara luaran adalah rerata berat tarikan pukat cincin
179<br />
yang ditarik nelayan pada saat proses penangkapan ikan. Sedangkan masukan<br />
adalah rerata beban kerja yang diterima oleh 18 orang nelayan (subjek) selama<br />
6 jam kerja yang dalam hal ini beban kerja dari hasil perhitungan nadi kerja<br />
dalam satuan denyut per menit.<br />
Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata produktivitas antara nelayan<br />
sebelum intervensi dan dengan intervensi ergonomi berbeda bermakna dari 953 kg<br />
turun menjadi 600 kg atau terjadi peningkatan produktivitas sebesar 3,53%.<br />
Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan adanya peningkatan<br />
produktivitas secara bermakna pada proses penangkapan ikan dimana nelayan<br />
merasakan bahwa semakin cepat penarikan, maka semakin ringan pukat cincing<br />
yang ditarik. Hal ini disebabkan karena adanya intervensi ergonomi dengan<br />
menggunakan alat kerja katrol sehingga produksi penangkapan meningkat. Hal ini<br />
diperkuat dengan hasil penelitian Artayasa menunjukkan bahwa dengan intervensi<br />
ergonomi melalui perbaikan alat kerja, pemberian tambahan asupan energi dan<br />
istirahat pendek dapat meningkatkan produktivitas. Sebesar 48,84 %. Sedangkan<br />
penelitian Oesman tentang intervensi ergonomi pada proses stamping part body<br />
component disebuah perusahaan otomotif menunjukkan bahwa intervensi<br />
ergonomi dalam bentuk redesain alat kerja, pergantian posisi kerja dan pemberian<br />
tambahan asupan energi telah mampu meningkatkan produktivitas kerja secara<br />
bermakna sebesar 32,65%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bridger (2003)<br />
bahwa kondisi fisik yang lebih sehat, dapat meningkatkan kemampuan, kecepatan<br />
dan ketepatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.
180<br />
Dalam penelitian ini, peningkatan produktivitas terjadi karena intervensi<br />
argonomi pada sistem kerja proses penangkapan ikan dengan pukat cincin dan<br />
telah memperbaiki kondisi kerja sehingga terjadi penurunan beban kerja. Dimana<br />
pukat cincin yang ditarik menjadi ringan dan cepat serta mengurangi keluhan otot<br />
skeletal. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka perbaikan kondisi kerja yang<br />
dilakukan dengan menerapkan ergonomi total pada proses penangkapan ikan yang<br />
telah dilakukan, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja nelayan dalam<br />
aktivitas penangkapan ikan.<br />
6.6.3 Keuntungan Nelayan<br />
Dalam penelitian ini, keuntungan nelayan yang dihitung secara ekonomi<br />
adalah merupakan hasil perhitungan dari masing-masing aspek ekonomi setelah<br />
dilakukan intervensi ergonomi yaitu : return of investment (ROI), break event<br />
point (BEP) dan cost and benefit (B&C).<br />
6.6.3.1 Return of Investment (ROI)<br />
ROI merupakan nilai keuntungan yang diperoleh nelayan pemilik pukat<br />
cincin dan nelayan penangkap yang secara bersama-sama dapat mengukur tingkat<br />
kemampuan usaha secara efisien dalam mengembalikan modal yang<br />
ditanamkannya, yaitu :<br />
1. Capital Investment<br />
Peralatan penangkapan ikan dengan intervensi ergonomi meningkat<br />
sebesar Rp. 15.000.000,-. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan
181<br />
alat katrol, pengadaan pakaian pelindung diri (PPD) jacket, sarung tangan<br />
dan penambahan spons alas duduk nelayan pada saat menarik pukat cincin<br />
sebesar Rp. 15.000.000,-.<br />
2. Working Capital<br />
Working capital yang terdiri dari variabel cost dan fixed cost sebesar<br />
Rp. 2.801.275.000,-. Variabel cost meliputi : komisi bagi hasil 30% =<br />
Rp. 1.000.000.000,-., Bahan Penolong seperti bahan bakar minyak (BBM)<br />
dan bahan pengawet ikan (es balok) sebesar Rp. 1.035.000.000,-. Biaya<br />
konsumsi nelayan selama melaut Rp. 180.000.0000,-, biaya pemasaran<br />
ikan Rp. 16.200.000,- dan retribusi perikanan 5% = Rp. 175.000.000,-.<br />
Total Variabel Cost Rp. 2.457.800.000,- per tahun. Sedangkan Fixed Cost<br />
meliputi : biaya pemeliharaan (kapal/perahu, mesin motor, jaring/pukat<br />
cincin, tali temali, asuransi). Total Fixed Cost Rp. 343.475.000.<br />
3. Total Investment yang terdiri dari capital investment dan working capital<br />
meningkat sebesar Rp. 17.000.000,-.<br />
4. Bunga modal 16% menjadi Rp. 2.720.000,-<br />
Dengan intervensi ergonomi yang dilakukan pada nelayan pukat cincin,<br />
maka telah berhasil meningkatkan pendapatan keuntungan nelayan melalui<br />
peningkatan produksi penangkapan ikan dari 600 ton Rp. 291.666.000,-/bulan<br />
menjadi 980 ton Rp. 449.000.000,-/bulan atau meningkat sebesar<br />
Rp. 157.334.000,- dan nelayan memperoleh saldo sebesar Rp.99.000.000,-
6.6.3.2 Break Event Point (BEP)<br />
182<br />
Dalam penelitian ini, BEP dapat dihitung dengan mengetahui suatu titik<br />
atau keadaan dimana nelayan pemilik pukat cincin dan nelayan penangkap ikan<br />
didalam menginvestasikan modal usahanya, maka kedua-duanya tidak<br />
mendapatkan keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan intervensi<br />
ergonomi yang dilakukan hal ini dapat dilihat bahwa pada waktu yang ditentukan<br />
pada tahun ke-X atau (120 bulan) nelayan dapat mengembalikan pinjaman ke<br />
Bank sebesar Rp. 171.500.000,- dimana pendapatan yang diterima nelayan sama<br />
dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan<br />
ikan dengan pukat cincin, maka biaya yang dikeluarkan pada dasarnya sama<br />
dengan pendapatan yang diterima atau mengalami titik impas dalam jangka waktu<br />
tertentu dengan kata lain pulang pokok.<br />
6.6.3.3 Cost and Benefit (B&C)<br />
Dalam penelitian ini, biaya dan manfaat atau cost and benefit dalam usaha<br />
penangkapan ikan dengan pukat cincin diperlukan suatu analisis ekonomi dan<br />
salah satu kriteria yang layak digunakan adalah : benefit – cost = >1 (B - C = >1)<br />
berarti manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang didapati.<br />
Dari segi waktu, usaha ini sangat penting untuk dianalisis sebab waktu di<br />
masa yang akan datang tidak sama dengan biaya dan hasil saat ini. Oleh<br />
karenanya aturan penilaian mengharuskan adanya pendiskontroan manfaat yang<br />
dirasakan oleh seorang nelayan setelah beroperasinya alat tersebut, kritria ini<br />
disebut Net Present Value (NPV) .
183<br />
Dari segi pendapatan, hasil yang diperoleh nelayan setelah melakukan<br />
penangkapan ikan harus mendapatkan upah yang layak. Hal ini dihitung<br />
berdasarkan kriteria internal rate of return (IRR) sebagai tingkat penghasilan<br />
berupa upah yang diterima nelayan.<br />
Dengan intervensi ergonomi yang dilakukan melalui penerapan ergonomi<br />
total pada proses penangkapan ikan oleh nelayan pukat cincin di Amurang,<br />
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, ternyata nelayan<br />
mendapatkan manfaat yang besar bila dibandingkan dengan biaya yang<br />
dikeluarkan. Manfaat yang diperoleh nelayan yaitu :<br />
a. Dapat meningkatkan kinerja dengan menurunkan beban kerja, yang ditandai<br />
oleh penurunan nadi kerja.<br />
b. Meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui penurunan tingkat kelelahan<br />
dan keluhan otot skeletal.<br />
c. Meningkatkan kehidupan ekonomi nelayan dengan berkurangnya biaya<br />
pengobatan dan meningkatkan penghasilan, sehingga nelayan merasa sehat,<br />
aman, nyaman, produktif dan efisien dalam melakukan pekerjaan<br />
penangkapan ikan.<br />
6.7 Temuan Baru Hasil Penelitian (Novelty)<br />
Temuan baru yang telah dibuktikan dari hasil penelitian ini menunjukkan<br />
bahwa intervensi ergonomi melalui penerapan ergonomi total pada proses<br />
penangkapan ikan dengan pukat cincin dapat meningkatkan kinerja dan<br />
kesejahteraan nelayan. Alat kerja katrol dapat memberikan manfaat secara
184<br />
signifikan pada penggunaan tenaga otot dan energi lebih efisien, pemakaian waktu<br />
lebih efisien, kelelahan kerja, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja<br />
berkurang oleh karena alat kerja katrol dapat mengubah sikap kerja lama yang<br />
tidak fisiologis ke sikap kerja baru yang fisiologis lebih sehat, aman, nyaman,<br />
efisien dan produktif.<br />
6.8 Kelemahan Penelitian<br />
Berdasarkan hasil penelitian ini, dibuktikan bahwa desain alat katrol pukat<br />
cincin secara ergonomis dapat meningkatkan kinerja para nelayan pukat cincin di<br />
Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang diamati dari beberapa indikator<br />
seperti: terjadi penurunan keluhan kerja dan peningkatan produktivitas kerja.<br />
Kendatipun demikian, namun kelemahannya adalah mengenai kesinambungan<br />
dari penerapan hasil redesain peralatan kerja di masa yang akan datang. Hal<br />
tersebut mengingat: (1) para nelayan di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan<br />
dalam menjalankan usahanya, mereka telah terbiasa menggunakan peralatan<br />
dengan cara lama sekalipun tidak ergonomis dan berpotensi menimbulkan risiko<br />
bagi keselamatan kerja. (2) Kurang yakin akan keberhasilan yang akan diperoleh<br />
dari investasi yang dilakukan terhadap desain peralatan kerja secara ergonomis.<br />
Oleh sebab itu, maka perlu diberi pengarahan tentang keuntungan yang diperoleh<br />
dari aplikasi ergonomi dalam kegiatan penangkapan ikan. Perlu ditanamkan<br />
kewirausahaan berbasis ergonomi.
7.1 Simpulan<br />
BAB VII<br />
SIMPULAN DAN SARAN<br />
Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat<br />
dikemukakan simpulan sebagai berikut:<br />
1) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan beban kerja nelayan<br />
sebesar 53,56%.<br />
2) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan tingkat kelelahan<br />
16,15% dan dalam kategori aktivitas melemah, turun 19,96%, kategori<br />
motivasi melemah, turun 11,70% dan kategori kelelahan fisik, turun<br />
14,53%.<br />
3) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kinerja yang dinilai dari penurunan keluhan<br />
muskuloskeletal sebesar 53,55%.<br />
4) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari peningkatan kepuasan<br />
kerja nelayan sebesar 8.08%.<br />
5) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari peningkatan<br />
produktivitas nelayan sebesar 3,53%.<br />
185
186<br />
6) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
dapat meningkatkan kesejahteraan yang dinilai dari peningkatan keuntungan<br />
nelayan sebesar Rp. 157.334.000,-.<br />
7.2 Saran<br />
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat<br />
dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :<br />
1) Intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
terbukti dapat meningkatkan kinerja nelayan berdasarkan hasil penelitian<br />
dimana dapat menurunkan beban kerja, kelelahan dan keluhan<br />
muskuloskeletal nelayan pada waktu melakukan penangkapan ikan di laut.<br />
Oleh karena itu disarankan agar pengusaha penangkapan ikan dan pemilik<br />
pukat cincin di Amurang dapat menerapkan pokok-pokok intervensi<br />
ergonomi dalam usaha mereka.<br />
2) Untuk keberlanjutan hasil penelitian ini, maka diharapkan agar penerapan<br />
prinsip-prinsip dasar ergonomi dimasukan kedalam suatu model dan<br />
hendaknya menjadi pilihan dalam merancang alat penangkap ikan karena<br />
mudah dilakukan dan fleksibel.<br />
3) Penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh peneliti yang lain tetapi dengan<br />
subyek yang sama yaitu nelayan penangkap ikan sehingga dapat diketahui<br />
secara fisibel dan reliabel efek intervensi ergonomi dan profit ekonomi pada<br />
proses penangkapan ikan baik bagi stekholder, perusahaan dan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA<br />
Adiatmika, I P. 2007. Perbaikan Kondisi Kerja dengan Pendekatan Total<br />
Menurunkan Keluhan Muskuloskeletal dan Kelelahan serta Meningkatkan<br />
Produktivitas Pengerajin Pengecatan Kerajinan Logam di Kediri Tabanan.<br />
Disertasi UNUD.<br />
Adiputra, N.,Sutjana, D.P.,Widana, K., Manuaba, A.,O’Neill.1997. Participatory<br />
Ergonomics in Agriculture, Case study. In Bali Village. Indonesia editors.<br />
Proceeding of 5th SEAES Conference, 6-7 Nov. Kuala lumpur : IEA Press<br />
P.464.467.<br />
Adiputra, N. 2000, Ergonomi kuratif. Jurnal Ergonomi Indonesia. 1 (1,6) : 2-5.<br />
Adiputra, N., Sutjana, D.P., Suyasning, Tirtayasa, K. 2001. Gangguan<br />
muskuloskeletal karyawan beberapa perusahaan kecil di Bali. Jurnal<br />
ergonomi Indonesia.2 (1,6) : 6-9.<br />
Adiputra, N.; Sutjana, D.P. & Manuaba, A. 2000. Ergonomics Intervention in<br />
Small Scale Industry in Bali. Dalam : Lim, K.Y. ed. Proceendings of the<br />
joint Conference of APCHI and ASEAN Ergonomics. Singapore<br />
Adiputra, N. 2003. Materi Kuliah Design and Redesign. Program Studi<br />
Ergonomi-Fisiologi Kerja. Ilmu Kedokteran <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong><br />
Denpasar.<br />
Adnyana, W. B. 2001. Perbaikan Pegangan dan Perbaikan Bantal pada Proses<br />
Penggilingan Kopi Darat Menurunkan Keluhan Subjektif System<br />
Muskuloskeletal Pekerja Penggilingan Kopi Tradisional. Proseding<br />
Seminar Nasional XX1. Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia. Malang, 27-28<br />
Oktober.<br />
Annim, S. 2006. Industri Kecil Pengolahan Hasil Perikanan Laut. Fakultas<br />
Perikanan dan Kelautan. <strong>Universitas</strong> Sam Ratulangi Manado.<br />
Annis, J.F. and McConville, J.T.n 1996 Anthropometry. In Bharattacharya, A and<br />
McGlothlin, J.D. editors. Occupational Ergonomics Theory and<br />
Application New York : Marcell Dekker Inc.P. 1-46.<br />
Anonim, 2006. Prevent Musculoskeletal Injury in Your Health Care Facility.<br />
[cited 2006 Okt.7]. Available from: URL:http:/www.ergosafeproduct.com/musculoskeletal-injury/htm.<br />
Anonim, 2007b. Applying Principles of Adult Learning, [cited 2007 Feb 17].<br />
Available at: URL: http://www.luc.edu/schools/nursing/preceptor/2B.pdf.<br />
187
188<br />
Anonim, 2003. Papuaweb, the Celebes Group, [cited 2006 Mar. 20]. Available at:<br />
URL :http://www.papuaweb.erg/dlib/bk/wallace/celebes.html.<br />
Artayasa, N. 2007. Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kualitas Hidup<br />
Pekerja Wanita Pengangkut Kelapa di Banjar Semaja Desa Antosasi<br />
Tabanan Bali. Disertasi UNUD.<br />
Atmosoehardjo, 1994. Penerapan ergonomi dalam rekayasa manusia<br />
mesin/peralatan: (Man-Machine design). Forum ilmu kesehatan<br />
masyarakat XII No. 1-2 : 133-122 Surabaya.<br />
Armstrong, T. 2003. Handwork and Musculoskeletal Disorder.<br />
www.ergoweb.com. <strong>Download</strong> Tanggal 3 February 2003.<br />
Astrand, P.O. and Rodahl, K. 1986 Texbook of Work Physiology. 2nd Edition<br />
Philadelpia: WB Saunders Co.<br />
Avellini, B. A., Kamon, E., & Krajewski, J. T. (1980). Physiological responses of<br />
physically fit men and women to acclimation to humid heat. Noll<br />
Laboratory for Human Performance Research, The Pennsylvania State<br />
University, University Park, Pennsylvania, [cited Oct. 13, 2006]. Available<br />
from, URL:<br />
http://jap.physiology.org/cgi/reprint/49/2/254?ijkey=04e37563a3a2d3b495e269b1a<br />
6bab6e386056c48&keytype2=tf_ipsecsha.<br />
Beaulieu, M. B., 2005. Pree-Cooling for Performance in the Tropics. National<br />
Healt Training and Acclimatisation Centre. Northerm Territory Institute<br />
of Sport and Faculty of Education. Charles Darwin University. Darwin<br />
[eited.2008 Jun 10]. Available from<br />
URL.http:www.Sportsct.org/jour.03/mbb.doc<br />
Blazejczyk, K and Blazejczyk, M. 2007. BioKlima (Man-Environment heat<br />
Exchange, MENEX 2007). New Tool For Bioclimatic and<br />
Thermophysiological Studies, [cited 2007 Nov. 7]. Available from: URL:<br />
http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/bioklima.htm.<br />
Bridger, R.S. 1995. Inroduction to Ergonomi. Singapore : Mc. Graw - Hill<br />
International.<br />
Cani-news, 2006. Cedera Punggung : Hindari dan Kurangi Tekanan. [cited 2006<br />
Okt.7].Available.from:URL.http:/www.caninews.com/men_health/article.<br />
php/htm.<br />
Chaffin, D.B. and Park, K.S. 1993 A Longitudinal Study of Low Back Pain<br />
Occupational Weight Lifting Factors. American Industrial Hygiene<br />
Association Journal. 34 : 513-525.
189<br />
Chaffin, D.B. and Anderson, G.B. 1991. Occupational Biomechanics. New York :<br />
John Wiley.<br />
Chavalitsakulchai, P. & Shahnavaz, H. 1991. Musculoskeletal Discomfort and<br />
Feeling of Fatique Among Female Professiona! Workers : The Need for<br />
Ergonomics Consideration. Journal of Human Ergology. 20 : 257-264.<br />
Christensen, E.H. 1991. Physiology of Work.. Encyclopedia of Occupational<br />
Health and Safety, 3nd. Ed. Geneva : ILO.p.1698-1700.<br />
Chung, M. K., Lee. ID., and Kee. 2003. Asessment of Postural Load For Lower<br />
Limb Postures Based On Perceived Discomford. International Journal Of<br />
Industrial Ergonomics. January: 31 (1): 17-32<br />
Corlett, E.N. 1992. Static Muscle Loading and Evaluation of Poslure. in: Wilson<br />
J.R. Evaluation of Human Work, a Practisel Ergonomics Methodology.<br />
London. Taylor & Fraricis.p. 542-570.<br />
Colton, T. 1985. Statiscs in Medicine. Diterjemahkanoleh Sanusi, R : Statistika<br />
Kedokteran Univ. Gadjah Mada. Yogyakarta Gadjah Mada University<br />
Press.<br />
Coyle, P. 2004., Method for Assesing Exposure To Musculceletal Disordes Risk<br />
Factors [cited 2007 May 21]. Available from:<br />
URL:http:/www.suderland.ac.uk/QEC/htm.<br />
Cummings, B. 2003. Interactive Physiology. Pearson Education. Inc<br />
Derchak, P. A.; Ostertag, K. L.; and Coyle, M. A. 2004. LifeShirt System as a<br />
Monitor of Heat Stress and Dehydration. VivoMetrics, Inc., [cited 2008<br />
Jun. 10]. Available from: URL:<br />
http://www.vivometrics.com/docs/Ab%20and%20posters/2004%20White%20Paper%20Life<br />
Shirt%20System%20as%20a%20Monitor%20of%20Heat%20Stress%20and%20Dehydration<br />
%20Derchak%20Ostertag%20Coyle.pdf<br />
Dinas Perikanan dan Kelautan, 2005. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan<br />
Propinsi Sulawesi Utara.<br />
Dinas Perikanan dan Kelautan, 2003. Data Laporan Hasil Perikanan Laut dan<br />
Darat. Kabupaten Minahasa Selatan. Provinsi Sulawesi Utara.<br />
Dekkers, D. K., 1996. The HumanFactorAspect of Shifwork In: Bhattacharya, A<br />
& McGlothin. J. D. Occupational Ergonomics Theory and Application.<br />
New York : Marcell Dekker. Inc. P.403-416.<br />
Dempsey, P.G., 2003. A Survey of Lifting and Lowering Tasks. International<br />
Journal On Industry Ergonomics. January 31(1):11-16.
190<br />
Fox, E. L, Bowers, R. W, and Foss, M. L. 1988. The Physiological Basis of<br />
Physical Education and Athletics, 4 th eds. New York: W.B.Saunders<br />
Company.<br />
Grandjean, E. 1993 Fitting the Task to The Man. 4 th edition. London : Taylor &<br />
Francis.<br />
Grandjean, E. and Kroemer. 2000. Fitting The Task To The Human. A Texbook<br />
Of Occupational Ergonomics 5 th. Edition Philadelphie: Taylor and Francis.<br />
Guyton, A. C. And Hall. 2000. Fisiologi Olahraga Kedokteran. Irawati Setiawan<br />
(editor) Edisi 9 Jakarta., Penerbit Buku Kedokteran EGC. h. 93-95.<br />
Hasalkar, S., Budihal, R., Shivalli, R and Biradar, N. 2004. Assesment of<br />
Workload of Weeding Activity in crop Production Through Heart Rate. J.<br />
Hum. Ecol, 14(3):165-167.<br />
Helander, M. 1995. A Guide to the Ergonomics of Manufacturing. London: Taylor<br />
& Francis<br />
http://www.saioh.org/ioha2005/Proceedings/Papers/SSK/PaperK1_1web.pdf<br />
Hendrick, H. W. and Kleiner, B. M., Macro Ergonomics. 2002. Human Factors<br />
and Ergonomics Society, Santa Monica.<br />
ILO, 1998. Encyclopedia of Occupational Healt and Safety. In : Stellman. Editor.<br />
Geneva. International Labour Organization.<br />
Imron dan Masyuri, 2001. Pemberdayaan Masyaraakat Nelayan : Yogyakarta<br />
Media Pressindo.<br />
Intaranont, K. and Vanwonterghem, K. 2001. Sutdy of Exposure Limit in<br />
Contraining Climatic Condition for Sterenous Task : An Ergonomics<br />
Approach Final Report. Bangkok: Chulangkom University Departement<br />
of industrial Engineering.<br />
Josephus, J. 1996. Studi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Hasil<br />
Perikanan Laut di Propinsi Sulawesi Utara (Tesis) Program Pascasarjana<br />
S2 Institut Pertanian Bogor IPB.<br />
Josephus, J. 1999. Usaha Penangkapan di Bidang Perikanan Laut. Fakultas<br />
Ekonomi <strong>Universitas</strong> Sam Ratulangi Manado.<br />
Josephus, J. 2004. Perancangan Aalat Takal Pukat Cincin Meningkatkan<br />
Produktivitas Kerja dan Menggurangi Gangguan Muskuloskeletal, Beban<br />
Kerja Kelompok Nelayan di Sulawesi Utara. Seminar Nasional. Aplikasi<br />
Ergonomi Dalam Industri. Prosiding. Forum Komunikasi Teknik Industri<br />
Yogyakarta P. 63.
191<br />
Kanagaya, T. 2001. Purse Seine fishing gear Method. Japan International<br />
Cooperation Agency. P.183-190 Tokyo.<br />
Katiandgho, E. & Fridman, 2005. Fiching boat and Fiching Managemet. Fakultas<br />
Perikanan. <strong>Universitas</strong> Sam Ratulangi. Manado<br />
Kilbon, A. 1992. Measurement and Assessment of Dynamic Work. Dalam Wilson,<br />
J.R. & Corlett, E.N. eds. Evaluation of Human Work, A Practical<br />
Ergonomics Metodology. Taylor and Francis Great Britain.<br />
Kirk, P.M. Parker, R.J. An Ergonomic Evaluation og Douglas Fir Manual<br />
Pruning in New Zealand. Journal of Forest Engineering. Vol 7(2):43-<br />
50.[cited 2006 Oct. 13]. Available from: URL:<br />
http://www.lib.unb.ca/Texts/JFE/backissues/pdf/vol7-2/kirk.pdf.<br />
Kroemer, K. & Kroemer, H and Kroemer-Elbert, K. 1994. Ergonomics How To<br />
Design for Ease & Efficiensy. New Yersey : Prentice Hall. Englewoodds<br />
Clifts.<br />
Manuaba, A. 2006a. A Total Approach In Ergonomics Is A Must To Attain<br />
Humane, Competitive And Sustainable Work System And Products. In :<br />
Adiatmika and Putra, D.W. editors. Proceeding Ergo Future 2006 :<br />
International Symposium On Past, Present And Future Ergonomics,<br />
Occupational Safety and Health. 28 - 30 th August. Denpasar : Department<br />
of Physiology <strong>Udayana</strong> University- School of Medicine. p. 1-6.<br />
Manuaba, A. 2006b. Macro Ergonomics Approach On Work Organization, With<br />
Special Reference To Utilization Of Total Ergonomic SHIP Approach To<br />
Obtain Humane, Competitive And Sustainable Work System and product.<br />
Proceeding Seminar Nasional Ergonomi 2006. Pendekatan Ergonomi<br />
Makro Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi. Jakarta : Jurusan Teknik<br />
Industri <strong>Universitas</strong> Trisakti. Jurusan Teknik Industri.<br />
Manuaba, A. 2005a. Total Ergonomic Enhancing Productivity, Product Quality<br />
and Customer Satisfaction. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional<br />
II Peningkatan Kualitas Sistem Manufaktur dan Jasa, Forum Komunikasi<br />
Teknik Industri, Yogyakarta.<br />
Manuaba, A. 2005b. To Achieve A Better Life Throught Total Ergonomic SHIP<br />
Approach Technology. Presented at the 2 nd National Technology Seminar :<br />
“The Aplication of Technology toward a Better Life”. University of<br />
Technology Yogyakarta. Yogyakarta 1 O th December.
192<br />
Manuaba, A. 2005c. Accelerating OHS-Ergonomics Program by Integrating<br />
“Built-In” with in The Industry's Economic Development Scheme is a<br />
must-with Special Attention to Small and Medium Enterprisses (SMEs).<br />
Presented at the 21st Annual Conference of The Asia Pasific Occupational<br />
Safety & Health Organization. Denpasar 5-8 th September.<br />
Manuaba, A. 2005d. In Designing Task, Organization and Environment, Human<br />
Capability and Limitattion Must Be Highly Considered To Attain<br />
Humane, Competitive And Sustainable Work System And Product.<br />
Presented at DIMNAS RAPIIV. UMS. Surakarta 2 th December.<br />
Manuaba, A. 2004a. Pendekatan Ergonomi Holistik Satu Keharusan Dalam<br />
Otomasi Untuk Mencapai Proses Kerja Dan Produk Yang Manusiawi,<br />
Kompetitif Dan Lestari. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional<br />
Ergonomi, Aplikasi Ergonomi dalam Industri, Forum Komunikasi Teknik<br />
Industri Yogyakarta dan Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Yogyakarta<br />
27 Maret.<br />
Manuaba, A. 2004b. Pendekatan Total Perlu Untuk Adanya Proses Produksi dan<br />
Produk Yang Manusiawi, Kompatibel dan Lestari. Makalah.<br />
Dipresentasikan pada Seminar Nasional Teknik Industri Atma Jaya.<br />
Yogyakarta.<br />
Manuaba, A. 2003 a. Aplikasi Ergonomi Dengan Pendekatan Holistik Perlu, Demi<br />
Hasil Yang lebih Lestari Dan Mampu Bersaing. Makalah. Temu Ilmiah<br />
dan Musyawarah Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ergonomi.<br />
Hotel Sahid Jakarta.<br />
Manuaba, A. 2003d. Penerapan Ergonomi Meningkatkan Produktivitas. Makalah.<br />
Denpasar : Bagian Ilmu Faal Fakultas Kedokteran <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>.<br />
Manuaba, A. 2003e. Total Ergonomic Approach to Enhance and Harmonize The<br />
Development of Agriculture, Tourism and Small Scale Industry, with<br />
Special Reference to Bali. Dalam : Purwanto, W., Sugema, L.I. dan<br />
Ushada, M. editors. Prosiding Seminar Nasional Ergonomi. Yogyakarta :<br />
Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan Fakultas Teknologi Pertanian<br />
<strong>Universitas</strong> Gadjah Mada.h. 16-21.<br />
Manuaba, A. 2003f. Holistic Design Is Must To Attain Sustainable Product.<br />
Presented at The National Seminar on Product Design and Development,<br />
Industrial Engineering UK Maranatha. Bandung 4-5 th Juli.<br />
Manuaba, A. 2000a. Ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dalam :<br />
Sritomo Wignyosoebroto dan Stefanus Eko Wiranto. editor. Prosiding<br />
Seminar Nasional Ergonomi 2000. Surabaya : Guna Widya. h. 1-4.
193<br />
Manuaba, A. 2000b. Ergonomi Meningkatkan Kinerja Tenaga Kerja dan<br />
Perusahaan. Dalam : Hermansyah. editor. Prosiding Simposium dan<br />
Pameran Ergonomi Indonesia 2000. Bandung : ITB Press. h. 11-19.<br />
Manuaba, A. 1999a. Penerapan Ergonomi Partisipasi dalam Meningkatkan<br />
Kinerja Industri. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional<br />
Ergonomi, Reevaluasi Penerapan Ergonomi dalam Meningkatkan Kinerja<br />
Industri. Surabaya 23 Nopember.<br />
Manuaba, A. 1998a. Penerapan Ergonomi Kesehatan Kerja di Rumah Tangga.<br />
Bunga Rampai Ergonomi. Denpasar : Program Studi Ergonomi-Fisiologi<br />
Kerja <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>. 1 : 38-48.<br />
Manuaba, A. 1998d. Pengaturan Suhu dan Water Intake. Bunga Rampai<br />
Ergonomi. Denpasar : Program Studi Ergonomi-Fisiologi Kerja<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>. 1:165-175.<br />
Manuaba, A. 1992. Penerapan Ergonomi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber<br />
Daya Manusia dan Produktivitas. Makalah. Seminar Kesehatan dan<br />
Keselamatan Kerja (K3) IPTN. Bandung.<br />
Mulyadi, 2005. Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Kebudayaan. Gramedia<br />
Pustaka Utama. Jakarta.<br />
Macleod, Tayyari. F. and Smith. J. L. 1997. Occupational Ergonomics Principles<br />
and Aplication. New York. Chapment dan Hal-hal.<br />
Nala, N. 1994. Penerapan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan. Denpasar :<br />
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>.<br />
Nala, N. 2002. Ballinese Traditional Culture in Changing World. Dalam Susila,<br />
I.G.N. editor. Procceeding National – International Seminar Traditional<br />
Culture in Changing World, March, Denpasar. Bali HESG.<br />
Nomura, M. and T. Yamazaki. 2003. Fishing Techniques. Fish. News Books.<br />
Japan International Cooperation Agenzy. Tokyo p. 200-210.<br />
Nurmianto, E. 2004. Ergonomi. Konsep Dasar dan Aplikasinya. Edisi<br />
kedua.Surabaya: Guna Widya.<br />
Palilingan, R. N. 2008. Penerapan Pendekatan Ergonomi Total pada Aktifitas<br />
Praktikum Lapangan Memperbaiki Respons Fisiologis Tubuh Menurunkan<br />
Kelelahan dan Meningkatkan Kinerja Mahasiswa FMIPA UNIMA.<br />
Disertasi UNUD.<br />
Pangkahila, J.A. 2003. Teknik Pembuatan Proposal Tesis dan Disertasi. Materi<br />
Kuliah Mahasiswa 83. Fakultas Kedokteran <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>,<br />
Denpasar.
194<br />
Pangkahila, W.I. 2003. Etika Penelitian. Materi Kuliah Mahasiswa S3. Fakultas<br />
Kedokteran <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>, Denpasar.<br />
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Propinsi Sulawesi Utara. 2005<br />
Kota Amurang.<br />
Pheasant, S. 1991. Ergonomics Work and Heatlh. London: Macmillan Press.<br />
Scientific & Medical.<br />
Prasetyowibowo, 2000. Manajemen Kerja. Raja Wali. Grafindo Persada. Jakarta<br />
Prihartono, M. 2000. Metodologin Penelitian. Surabaya. Program Pascasarjana<br />
<strong>Universitas</strong> Airlangga.<br />
Princton Analytical Laboratory. (2004), [cited April 11, 2004]. Available at,<br />
URL: http://yeeha.org/enterrhtml/live/lab/quality.html.<br />
Pulat, B.M. 1992 Fundamentals of Industrial Ergonomic. New Yersey : Prentice<br />
Hall. Englewood Cliffs.<br />
Purnomo, H. 2007. Sistem Kerja dengan Pendekatan Ergonomi Total Mengurangi<br />
Keluhan Muskuloskeletal, Kelelahan dan Beban Kerja Serta<br />
Meningkatkan Produktivitas Pekerja Industri Gerabah di Kasongan, Bantul<br />
(disertasi). Denpasar: Program Doktor, Program Studi Ilmu Kedokteran,<br />
Program Pascasarjana, <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>.<br />
Rivai, V. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. PT.<br />
Rajagrafindo. Persada Jakarta.<br />
Rodahl, K. 1989. The Physiology of Work. London : Taylor & Francis Ltd.<br />
Rodahl, K. (2003). Occupational Health Conditions in Extreme Environments.<br />
Ann. occup. Hyg., 47(3): 241–252. , 47 (3), 241–252.<br />
Rodgers, S.H. 2005. Ergonomics Desain for People at Work New York : Van<br />
Nostrand Reinhold Company.<br />
Sajiyo, 2008. Redesign Tempat dan Sistem Kerja dengan Intervensi Ergonomi<br />
Meningkatkan Kinerja Tukang Giling Sigaret Kretek Tangan Pada Industri<br />
Rokok “X” di Kediri Jawa Timur. Disertasi UNUD.<br />
Sanders, M.S. and McCormic, E.J. 1987. Human Factors in Engineering and<br />
Design. USA : McGraw Hill-Book Company<br />
Sandowsky, S. A. 2000. What is The Ideal Body Weight. Oxford University.<br />
Press Family Practice. 17.(4):384-351.<br />
Sartono, S. W. 2001. Psikologi Sosial. Balai Pustaka. Cetakan ke-4 Jakarta
195<br />
Setyawan, 2001. Relation Between Feelings of Fatique ReactionTime and Work<br />
Productivity. Journal of human ergology. 25(1):129-134.<br />
Schulte, P. A., Wagner, G., Ostry, A., Blanciforti, L. A., Cutlip, R. G., Luster, M.,<br />
et al. (2007). Work, Obesity, and Occupational Safety and Health.<br />
American Journal of Bublic, 97(3), 428-436<br />
Scott, L. S. 1993. Fundamental On The Fishing Efficiency Gearnet Design.<br />
United Nation. Fish New Book. London. P. 160-167.<br />
Snook, L. 2005. Human Physiology : From Cells to Systems. West Virginia. West<br />
Adivision of International. Thomson Publishing. Inc.<br />
Spurgeon, M. M. 2003. Effect Of A Participatory Computer Workshop For<br />
University Student. A. Pilot Intervention to Present Disability in<br />
Tomorrow’s Workers. Scan j. Work Environ Health. USA. IOS.<br />
Press.p.305-314.<br />
Sulawesi Utara Dalam Angka. 2005. Badan Perencanaan Daerah Propinsi<br />
Sulawesi Utara.<br />
Suma’mur, P.K. 1982. Ergonomi Untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: Yayasan<br />
Swabhawa Karya.<br />
Sutajaya, I.M. 2006. Pembelajaran Melalui Pendekatan SHIP Mengurangi<br />
Kelelahan, Keluhan Muskuloskeletal dan Kebosanan serta Meningkatkan<br />
Luaran Proses Belajar Mahasiswa Biologi IKIP Singaraja. Disertasi<br />
UNUD Denpasar.<br />
Sutjana, D. P. Adiputra, N. Manuaba, A. Tirtayasa, K. 1996.Improvement of<br />
working posture increase productivity of Roof Tile Home Industry Workes<br />
at Darmasaba Village, Badung Regency. J. Human Ergol, 25 (1,6) 62-65.<br />
Sutjana, D. P. 2003. Peningkatan Produktivitas Kerja Penyabit Padi Menggunakan<br />
Sabit Bergerigi Dibandingkan dengan Sabit Biasa (Tesis) Denpasar.<br />
Program Pascasarjana <strong>Universitas</strong> <strong>Udayana</strong>.<br />
Sutjana, D. P. dan Sutajaya, I.M. 2005. Penuntun Tugas Lapangan Program Studi<br />
Ergonomi-Fisiologi Kerja. Program Pascasarjana Unud Denpasar.<br />
Sutjipta, N. 2004. Modifikasi Meja Pengumpan dan Penambahan Peredam<br />
Kebisingan Mesin Perontok Padi Meningkatkan Produktifitas. Disertasi<br />
UNUD Denpasar.<br />
The US Sub Committe on Benefits and Cost, 1988. The Economic Developmen<br />
Planning. Vicas Publishing House Ltd.
196<br />
Ulrich, Karl T. and Steven D. Eppinger. 2001. Perancangan dan Pengembangan<br />
Produk. Salemba. Teknika Jakarta.<br />
Vanwonterghem, K.J. Verboven, De Beeck, F. Willems. 2000. Subjective<br />
Workload Index. Disampaikan pada Seminar Ergonomi yang<br />
Diselenggarakan Laboratonum Fisiologi Fakultas Kedokteran <strong>Universitas</strong><br />
<strong>Udayana</strong> di Denpasar.<br />
Waters, T.S. and Putz-Anderson, V. 1996. Revise NIOSH Lifting Equation. Inc<br />
New York.<br />
Wignyosoebroto, S. 1989. Teknik Tata Cara Kerja. Surabaya : Lab. Ergonomi dan<br />
Teknik Tata Cara , Program Studi Teknik Industri. Fak. Teknik Industri,<br />
ITS. Surabaya<br />
Wignyosoebroto dan Stefanus, Eko Wiranto. Preceeding Seminar Nasional<br />
Ergonomi 2000. Guna Wijaya Surabaya.<br />
Whytmyre, G. K.-F. (2002, December 31`). Impacts Of Vent-Free Gas Heating<br />
roducts On Indoor Relative Humidity. Executive Summary, [cited March<br />
11, 2005]. Available from, URL:<br />
http://www.ventfreealliance.org/Final_ex_summary.pdf.
197
Lampiran 1<br />
“ Inform Concent ”<br />
LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN<br />
DAN<br />
PERSETUJUAN DARI SUBYEK / RESPONDEN<br />
Oleh :<br />
Johan Josephus<br />
NIM. 0390271001<br />
PROGRAM DOKTOR ILMU KEDOKTERAN<br />
UNIVERSITAS UDAYANA<br />
2009<br />
198
KATA PENGANTAR<br />
199<br />
Saudara diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ergonomi di<br />
Bidang Perikanan dan Kelautan dengan judul : Intervensi Ergonomi Pada Proses<br />
Penangkapan Ikan Dengan Pukat Cincin Meningkatkan Kinerja Dan<br />
Kesejahteraan Nelayan Di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi<br />
Sulawesi Utara.<br />
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan<br />
rancangan pre and post test design dalam bentuk cross over design dalam<br />
pelaksanaan di lokasi penelitian pada waktu operasi penangkapan ikan di laut<br />
menggunakan dua kapal secara bersama-sama dilakukan pendataan terhadap dua<br />
kelompok nelayan dalam kondisi kerja yang berbeda yaitu : (1) kelompok nelayan<br />
yang melakukan penangkapan ikan dengan pukat cincin dalam kondisi kerja yang<br />
terjadi seperti saat ini (sebelum intervensi) dan (2) kelompok nelayan yang<br />
melakukan penangkapan ikan dengan pukat cincin dalam kondisi kerja telah<br />
dilakukan intervensi ergonomi (sesudah intervensi).<br />
Intervensi ergonomi yang dilakukan melalui pendekatan ergonomi total<br />
pada penelitian ini mempunyai tujuan adalah untuk menilai penurunan beban<br />
kerja fisik dan keluhan subyektif (keluhan otot dan kelelahan) nelayan sehingga<br />
tercapainya budaya kerja sehat, aman, nyaman, efisien dan produktif serta dapat<br />
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan nelayan pada umumnya dan khususnya<br />
terkait dengan lamanya waktu pengembalian modal, titik impas dan besarnya<br />
pendapatan yang diperoleh nelayan dalam usaha penangkapan ikan dengan pukat<br />
cincin pada kondisi kerja yang berbeda.<br />
Apa yang harus saudara lakukan ?<br />
Yang harus saudara lakukan dalam penelitian ini adalah selama periode<br />
waktu 2 bulan (60 hari) pelaksanaan penelitian ini, masing-masing kelompok<br />
subyek diminta sebagai berikut : (1) Tahap persiapan, setelah saudara beradaptasi<br />
dengan hasil desain alat katrol pukat cincin, maka saudara dapat memberikan<br />
keterangan indentitas diri (nama, umur/tempat tanggal lahir, status keluarga
200<br />
kawin/belum, gizi sehari-hari dan bersedia diukur dimensi setiap bagian tubuh,<br />
tinggi dan berat badan); (2) Tahap pelaksanaan kelompok I (sebelum intervensi),<br />
pada waktu melakukan operasi penangkapan ikan dengan pukat cincin<br />
sebagaimana yang lazimnya dilakukan, saudara didata dengan menghitung denyut<br />
nadi, mengisi kuesioner kelelahan dan Nordic Body Map (NBM) dan pada tahap<br />
pelaksanaan kelompok II, saudara akan melakukan operasi penangkapan ikan<br />
dengan pukat cincin pada kondisi kerja baru (dengan intervensi) menggunakan<br />
katrol, menggunakan alas duduk, menggunakan sarung tangan, pemberian air teh,<br />
pengaturan waktu istirahat, perbaikan kondisi informasi dan sosial budaya dan<br />
saudara didata dengan menghitung denyut nadi mengisi kuesioner kelelahan dan<br />
kuesioner Nordic Body Map (NBM).<br />
Apa ada resikonya ?<br />
Selama penelitian ini berlangsung, tidak akan memberikan dampak negatif<br />
baik fisik maupun psikis kepada saudara, justru sebaliknya saudara diberikan<br />
perlakuan khusus pada saat melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan<br />
sarung tangan, pemberian alas duduk, menggunakan katrol dan perbaikan gizi<br />
saudara sesuai dengan yang telah dirancang berdasarkan standar kesehatan dan<br />
keselamatan kerja sehingga diharapkan kondisi saudara akan lebih sehat, aman,<br />
nyaman, efektif dan efisien.<br />
Berapa biaya yang harus dikeluarkan dari penelitian ini ?<br />
Selama menjadi subyek, saudara tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan<br />
saudara akan mendapat biaya kompensasi sebagai uang lelah, termasuk pada saat<br />
saudara diliburkan sesuai dengan prosedur penelitian.<br />
Kapan selesai atau saudara berhenti berpartisipasi sebagai subyek<br />
disebabkan oleh satu dan lain hal?<br />
Perlu diketahui bahwa partisipasi saudara bersifat sukarela, kapan saudara<br />
berhenti dan kapan saja saudara mau. Sebab keputusan saudara untuk berhenti<br />
dari penelitian ini tidak mempengaruhi proses penangkapan ikan dengan pukat
201<br />
cincin. Jika saudara memutuskan untuk berhenti sebelum penelitian berakhir,<br />
maka saudara diminta untuk menyampaikan hal tersebut secepatnya kepada<br />
peneliti. Mengingat bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan<br />
manfaat jangka panjang baik kepada saudara sebagai subyek, pemerintah setempat<br />
masyarakat dan peneliti sendiri, sehingga keikutsertaan saudara sampai selesai<br />
sangat diharapkan.<br />
Apakah indentitas dan informasi saudara dirahasiakan ?<br />
Hanya tim peneliti dan petugas pengambil data yang tahu indentitas dan<br />
data diri saudara. Indentitas saudara tetap dirahasiakan.<br />
Apakah yang terjadi apabila saudara memutuskan untuk ikut dalam<br />
penelitian ini ?<br />
Yang terjadi adalah saudara diminta menanda tangani formulir surat<br />
persetujuan yang menyatakan bahwa saudara atau yang mewakili telah mendapat<br />
penjelasan tentang pelaksanaan penelitian ini dan secara sukarela bersedia untuk<br />
ikut ambil bagian dalam penelitian ini.<br />
Jadi bagaimana, apakah saudara masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang<br />
belum jelas ?<br />
Peneliti akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh saudara<br />
atau keluarga saudara tentang penelitian ini. Jika ada yang ingin saudara tanyakan<br />
selama penelitian berlangsung dapat menghubungi peneliti.<br />
Nama Peneliti Utama : Drs. Johan Josephus, M.Si<br />
Alamat : Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado<br />
Telepon/Hp : 0431-855942 Rmh/HP. 081356005460.
Pengesahan Oleh Peneliti<br />
Bersama ini saya menyatakan bahwa saya telah memberikan penjelasan<br />
tentang semua resiko yang akan terjadi selama penelitian ini dan telah dimengerti<br />
oleh nelayan sebagai calon subyek penelitian.<br />
Peneliti :<br />
Nama :<br />
Ditetapkan pada tanggal:<br />
202
Lampiran 2<br />
KUESIONER KESEJAHTERAAN DALAM PROSES PENANGKAPAN IKAN<br />
DENGAN PUKAT CINCIN<br />
Berilah tanda √ di depan jawaban yang tersedia yaitu:<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
pada setiap pernyataan di bawah ini.<br />
203<br />
1. Profesi yang saya tekuni sekarang ini sebagai nelayan telah membuat saya<br />
merasa sejahtera.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
2. Kondisi ruangan di kapal pada waktu proses penangkapan ikan yang dimulai<br />
dari penawuran sampai penarikan pukat cincin terasa leluasa sehingga<br />
membuat saya nyaman dalam bekerja.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
3. Dalam satu trip penangkapan ikan (pergi pulang melaut) jumlah tangkapan<br />
yang diperoleh telah mencukupi.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju
204<br />
4. Pemilik pukat cincin menerapkan sistem bagi hasil pada setiap trip<br />
penangkapan ikan. Hasil yang saya peroleh telah memuaskan.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
5. Pada waktu-waktu tertentu sistem bagi hasil bukan dalam bentuk hasil<br />
tangkapan, melainkan oleh pemilik pukat cincin diberikan dalam bentuk<br />
uang. Pembagian yang saya peroleh terasa memuaskan.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
6. Penyediaan kebutuhan air minum dan tambahan kalori lainnya (teh manis)<br />
sudah teratur dan memuaskan<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
7. Perlengkapan pelindung diri untuk keamanan pekerja sangat dibutuhkan<br />
(seperti sarung tangan, jacket dll.). Selama ini perlengkapan tersebut sudah<br />
memadai.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
8. Masalah kebutuhan makan dan minum amat penting untuk pekerja. Selama<br />
ini pengaturan dan pembagian makanan dan minum selama proses<br />
penangkapan ikan sudah memuaskan.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju
� Kurang Setuju<br />
205<br />
� Tidak setuju<br />
9. Kotak P3K amat penting, selama ini penyediaan kotak tersebut sudah<br />
memuaskan sehingga setiap kali dibutuhkan komponen-komponen di<br />
dalamnya tersedia dan terkontrol.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
10. Istirahat sepanjang proses pangkapan ikan sangat diperlukan, dan selama ini<br />
pengaturan waktu istirahat sudah dilakukan dengan baik.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
11. Bila tidak pergi melaut kegiatan yang dilakukan diarahkan pada kegiatankegiatan<br />
sosial kemasyarakatan di desa. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut<br />
dengan profesi sebagai nelayan saya merasa percaya diri karena dapat<br />
memenuhi kewajiban-kewajiban organisasi sosial kemasyarakatan.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
12. Di dalam kapal tersedia ruang istirahat, dan selama ini ruang tersebut sudah<br />
termanfaatkan dengan baik.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju
206<br />
13. Komunikasi antara pimpinan (tonaas) dengan para pekerja (nelayan) sebelum<br />
melaut amat penting. Selama ini komunikasi tersebut sudah berjalan dengan<br />
baik.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
14. Selama proses penangkapan ikan komunikasi antar pekerja dan antar<br />
pimpinan (tonaas) dengan pekerja sudah berjalan dengan baik.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju<br />
15. Proses penangkapan ikan yang dilakukan selama ini meskipun terasa amat<br />
memeras tenaga, tetapi tidak diperlukan cara alternatif karena sebagai pekerja<br />
sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut.<br />
� Sangat setuju<br />
� Setuju<br />
� Kurang Setuju<br />
� Tidak setuju
Lampiran 3<br />
Form Data Karakteristik Subyek<br />
NO.<br />
1<br />
NAMA BERAT<br />
BADAN<br />
(KG)<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
UMUR<br />
(TH)<br />
TINGGI<br />
BADAN<br />
(CM)<br />
207<br />
INDEKS<br />
MASSA TUBUH
208<br />
Lampiran 4.a<br />
Kuesioner Nordic Body Map (sebelum intervensi)<br />
Berilah tanda (x) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan keluhan<br />
sakit/kaku pada otot yang saudara rasakan saat ini.<br />
No JENIS KELUHAN<br />
0 Sakit/kaku di leher bagian atas<br />
1 Sakit/kaku di leher bagian bawah<br />
2 Sakit di bahu kiri<br />
3 Sakit di bahu kanan<br />
4 Sakit pada lengan kiri atas<br />
5 Sakit di punggung<br />
6 Sakit pada lengan kanan atas<br />
7 Sakit pada pinggang<br />
8 Sakit pada bokong<br />
9 Sakit pada pantat<br />
10 Sakit pada siku kiri<br />
11 Sakit pada siku kanan<br />
12 Sakit pada lengan bawah kiri<br />
13 Sakit pada lengan bawah kanan<br />
14 Sakit pada pergelangan tangan kiri<br />
15 Sakit pada pergelangan tangan kanan<br />
16 Sakit pada tangan kiri<br />
17 Sakit pada tangan kanan<br />
18 Sakit pada paha kiri<br />
19 Sakit pada paha kanan<br />
20 Sakit pada lutut kiri<br />
21 Sakit pada lutut kanan<br />
22 Sakit betis kiri<br />
23 Sakit pada betis kanan<br />
24 Sakit pada pergelangan kaki kiri<br />
25 Sakit pada pergelangan kaki kanan<br />
26 Sakit pada kaki kiri<br />
27 Sakit pada kaki kanan<br />
Catatan : TS = Tidak sakit S = Sakit<br />
AS = Agak sakit SS = Sangat sakit<br />
JAWABAN<br />
TS AS S SS
209<br />
Lampiran 4.b<br />
Kuesioner Nordic Body Map (sesudah intervensi)<br />
Berilah tanda (x) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan keluhan<br />
sakit/kaku pada otot yang saudara rasakan saat ini.<br />
No JENIS KELUHAN<br />
0 Sakit/kaku di leher bagian atas<br />
1 Sakit/kaku di leher bagian bawah<br />
2 Sakit di bahu kiri<br />
3 Sakit di bahu kanan<br />
4 Sakit pada lengan kiri atas<br />
5 Sakit di punggung<br />
6 Sakit pada lengan kanan atas<br />
7 Sakit pada pinggang<br />
8 Sakit pada bokong<br />
9 Sakit pada pantat<br />
10 Sakit pada siku kiri<br />
11 Sakit pada siku kanan<br />
12 Sakit pada lengan bawah kiri<br />
13 Sakit pada lengan bawah kanan<br />
14 Sakit pada pergelangan tangan kiri<br />
15 Sakit pada pergelangan tangan kanan<br />
16 Sakit pada tangan kiri<br />
17 Sakit pada tangan kanan<br />
18 Sakit pada paha kiri<br />
19 Sakit pada paha kanan<br />
20 Sakit pada lutut kiri<br />
21 Sakit pada lutut kanan<br />
22 Sakit betis kiri<br />
23 Sakit pada betis kanan<br />
24 Sakit pada pergelangan kaki kiri<br />
25 Sakit pada pergelangan kaki kanan<br />
26 Sakit pada kaki kiri<br />
27 Sakit pada kaki kanan<br />
Catatan : TS = Tidak sakit S = Sakit<br />
AS = Agak sakit SS = Sangat sakit<br />
JAWABAN<br />
TS AS S SS
Lampiran 5.a<br />
Kusioner 30 Items of Rating Scales dengan Skala Likert<br />
untuk Pengukuran Kelelahan Secara Umum (sebelum intervensi)<br />
Berilah tanda cek (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan<br />
kondisi saudara saat ini!<br />
STT ttid kt TT tid k t AT kt<br />
JAWABAN<br />
No. PERTANYAAN<br />
STT TT AT T ST<br />
1 Apakah saudara merasa berat di bagian kepala ?<br />
2 Apakah saudara merasa lelah pada seluruh badan ?<br />
3 Apakah kaki saudara terasa berat ?<br />
4 Apakah saudara merasa sering menguap ?<br />
5 Apakah pikiran saudara terasa kacau ?<br />
6 Apakah saudara merasa mengantuk ?<br />
7 Apakah saudara merasakan ada beban pada mata ?<br />
8 Apakah saudara merasa kaku atau canggung dalam<br />
bergerak ?<br />
9 Apakah saudara merasa sempoyongan ketika berdiri ?<br />
10 Apakah ada perasaan angin berbaring ?<br />
11 Apakah saudara merasa susah berpikir ?<br />
12 Apakah saudara merasa lelah untuk bicara ?<br />
13 Apakah sudara merasa gugup ?<br />
14 Apakah saudara merasa tidak bisa berkonsentrasi ?<br />
15 Apakah saudara merasa tidak dapat memusatkan<br />
perhatian terhadap sesuatu ?<br />
210
Lampiran 5.b<br />
Kusioner 30 Items of Rating Scales dengan Skala Likert<br />
untuk Pengukuran Kelelahan Secara Umum (sesudah intervensi)<br />
Berilah tanda cek (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan<br />
kondisi saudara saat ini!<br />
STT ttid kt TT tid k t AT kt<br />
JAWABAN<br />
No. PERTANYAAN<br />
STT TT AT T ST<br />
1 Apakah saudara merasa berat di bagian kepala ?<br />
2 Apakah saudara merasa lelah pada seluruh badan ?<br />
3 Apakah kaki saudara terasa berat ?<br />
4 Apakah saudara merasa sering menguap ?<br />
5 Apakah pikiran saudara terasa kacau ?<br />
6 Apakah saudara merasa mengantuk ?<br />
7 Apakah saudara merasakan ada beban pada mata ?<br />
8 Apakah saudara merasa kaku atau canggung dalam<br />
bergerak ?<br />
9 Apakah saudara merasa sempoyongan ketika berdiri ?<br />
10 Apakah ada perasaan angin berbaring ?<br />
11 Apakah saudara merasa susah berpikir ?<br />
12 Apakah saudara merasa lelah untuk bicara ?<br />
13 Apakah sudara merasa gugup ?<br />
14 Apakah saudara merasa tidak bisa berkonsentrasi ?<br />
15 Apakah saudara merasa tidak dapat memusatkan<br />
perhatian terhadap sesuatu ?<br />
211
Lampiran 6<br />
STUDI GERAK DAN WAKTU (TIME MOTION STUDY)<br />
PROSES PENANGKAPAN IKAN DENGAN PUKAT CINCIN<br />
Prinsip Penangkapan<br />
Pukat Cincin<br />
Penawuran jaring<br />
Melingkari secara<br />
horizontal<br />
Memagari secara<br />
vertikal<br />
Mengurung dengan<br />
menutup bagian<br />
bawah jaring<br />
Menarik tali pukat<br />
cincin<br />
Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi<br />
Studi Gerak dan<br />
Waktu<br />
Nelayan<br />
melempar<br />
pelampung, jaring<br />
dan tali cincin<br />
sikap kerja<br />
berdiri,<br />
membungkuk<br />
selama 30 menit<br />
10 menit<br />
10 menit<br />
10 menit<br />
Nelayan belum<br />
memakai katrol<br />
dan alas duduk<br />
waktu penarikan<br />
120 menit<br />
1.Total Waktu = 180 menit<br />
2.Gerakan/Aktivitas penangkapan<br />
sebanyak 5 tahap.<br />
Prinsip<br />
Penangkapan<br />
Pukat Cincin<br />
Penawuran<br />
jaring<br />
Menarik tali<br />
pukat cincin<br />
Studi Gerak dan<br />
Waktu<br />
Nelayan<br />
melempar<br />
pelampung,<br />
jaring dan tali<br />
cincin sikap<br />
kerja duduk<br />
menggunakan<br />
alas duduk<br />
selama 30 menit<br />
Nelayan<br />
Menggunakan<br />
Katrol dan alas<br />
duduk waktu<br />
penarikan ??<br />
1.Total Waktu =........? menit<br />
2.Gerakan/Aktivitas penangkapan<br />
menjadi 2 tahap.<br />
212
Lampiran 7<br />
213<br />
Data Karakteristik Subjek, yang terdiri dari: Berat badan (BB), Umur, Tinggi<br />
badan (TB) dan Indeks massa tubuh (IMT).<br />
No. Nama Subjek BB Umur TB IMT<br />
1 Hans Gonta 60 55 155 24.97<br />
2 Nyong Pangkey 62 52 156 25.48<br />
3 Johny Matheos 62 51 160 24.22<br />
4 Alex Heydemans 65 57 162 24.77<br />
5 Hendrik Josephus 64 57 160 25.00<br />
6 Abraham Mononimbar 66 50 163 24.84<br />
7 Arnol Piters 60 48 165 22.04<br />
8 Christian Assa 62 49 160 24.22<br />
9 Rein Sinubu 57 51 158 22.83<br />
10 Albert Johanis 65 52 160 25.39<br />
11 Joppy Anes 58 49 153 24.78<br />
12 Gaspar Tumbuan 65 45 162 24.77<br />
13 Ungke Ottay 65 50 160 25.39<br />
14 Elis Sariowan 63 49 160 24.61<br />
15 Cornelis Weydekam 61 50 161 23.53<br />
16 Maxi Kindangen 65 52 168 23.03<br />
17 Lexi Josephus 65 57 166 23.59<br />
18 Raul Sariowan 70 49 168 24.80<br />
Rerata 63.06 51.28 160.94 24.35<br />
Minimum 57.00 45.00 153.00 22.04<br />
Maximum 70.00 57.00 168.00 25.48<br />
SD 3.15 3.34 4.09 0.97
Lampiran 8<br />
214<br />
Data Iklim Mikro Lingkungan Kerja Nelayan Pukat Cincin, Terdiri Dari:<br />
Kecepatan Angin (u), Suhu Udara (T), dan Kelembanan Relatif (KR).<br />
(a) Hari I dan Hari II<br />
Periode Seb Int. Periode dgn Int.<br />
Waktu<br />
U<br />
(Hari I)<br />
T<br />
(Hari II)<br />
(m/det) ( 0 KR U T<br />
C) (%) (m/det) ( 0 KR<br />
C) (%)<br />
2009-08-03 10:00 4.9 28.2 65.0 4.0 28.3 65.5<br />
2009-08-03 10:10 5.6 28.1 70.6 5.2 28.2 70.9<br />
2009-08-03 10:20 5.7 28.1 72.6 4.4 28.0 72.8<br />
2009-08-03 10:30 5.3 28.0 73.0 5.3 28.0 73.6<br />
2009-08-03 10:40 4.9 28.0 73.0 5.1 28.2 73.2<br />
2009-08-03 10:50 4.5 28.0 73.4 4.6 28.3 73.5<br />
2009-08-03 11:00 5.5 28.1 73.9 5.4 28.2 74.5<br />
2009-08-03 11:10 5.2 28.1 75.7 5.0 28.0 76.4<br />
2009-08-03 11:20 4.5 28.1 76.9 4.2 28.4 77.6<br />
2009-08-03 11:30 5.1 28.1 78.5 5.0 28.0 78.8<br />
2009-08-03 11:40 4.8 28.1 80.0 4.7 28.6 79.3<br />
2009-08-03 11:50 5.2 28.1 80.4 5.0 28.4 80.2<br />
2009-08-03 12:00 4.4 28.0 82.0 4.3 28.0 81.1<br />
2009-08-03 12:10 4.0 28.0 83.0 4.0 28.0 82.1<br />
2009-08-03 12:20 4.7 28.0 81.0 4.4 27.9 82.2<br />
2009-08-03 12:30 4.6 28.1 80.0 4.2 28.1 82.3<br />
2009-08-03 12:40 4.8 28.1 82.0 4.2 28.2 83.2<br />
2009-08-03 12:50 4.5 28.2 81.9 3.9 28.6 82.8<br />
2009-08-03 13:00 4.6 28.3 83.0 4.0 28.5 82.8<br />
2009-08-03 13:10 4.3 28.2 82.2 4.2 28.0 83.1<br />
2009-08-03 13:20 4.7 28.2 83.9 4.4 28.0 84.0<br />
2009-08-03 13:30 5.0 28.2 84.6 4.8 28.1 84.4<br />
2009-08-03 13:40 4.1 28.1 84.6 4.2 28.0 85.0<br />
2009-08-03 13:50 4.3 28.1 85.4 4.0 28.2 85.6<br />
2009-08-03 14:00 4.3 28.1 85.5 3.9 28.2 86.4<br />
2009-08-03 14:10 4.5 28.1 85.8 4.1 28.0 86.4<br />
2009-08-03 14:20 3.8 28.0 86.3 3.7 28.1 86.5<br />
2009-08-03 14:30 4.0 27.9 86.9 3.5 28.0 87.8<br />
2009-08-03 14:40 3.5 27.8 87.9 3.0 27.7 88.1<br />
2009-08-03 14:50 3.8 27.8 87.8 3.9 28.0 88.3<br />
2009-08-03 15:00 4.2 27.8 88.2 4.0 27.9 88.7<br />
2009-08-03 15:10 4.6 27.8 88.9 4.4 27.9 89.3<br />
2009-08-03 15:20 4.3 27.8 88.8 4.0 27.9 89.2<br />
2009-08-03 15:30 4.2 27.8 89.0 4.0 27.7 89.0<br />
2009-08-03 15:40 4.2 27.9 88.6 3.8 28.0 88.5<br />
2009-08-03 15:50 3.9 27.9 88.4 4.0 28.0 88.1
2009-08-03 16:00 3.7 28.0 87.9 4.2 28.1 88.5<br />
2009-08-03 16:10 4.0 28.0 89.0 4.1 28.0 89.1<br />
2009-08-03 16:20 2.9 27.9 89.2 3.0 28.0 89.8<br />
2009-08-03 16:30 1.9 27.9 90.0 2.0 27.9 90.2<br />
2009-08-03 16:40 1.9 27.9 90.3 2.2 27.8 90.4<br />
2009-08-03 16:50 2.4 28.1 90.2 2.5 28.2 90.3<br />
2009-08-03 17:00 1.7 27.9 90.1 2.0 28.0 90.2<br />
2009-08-03 17:10 1.2 27.3 90.0 1.5 27.6 90.1<br />
2009-08-03 17:20 1.3 27.0 89.0 1.0 26.5 90.1<br />
2009-08-03 17:30 1.3 27.5 90.0 1.1 28.0 90.0<br />
2009-08-03 17:40 1.3 27.5 88.0 1.1 28.0 89.4<br />
2009-08-03 17:50 1.5 27.0 88.2 1.2 28.0 89.2<br />
2009-08-03 18:00 1.5 27.4 88.8 1.4 28.1 89.2<br />
2009-08-03 18:10 2.2 27.7 87.9 2.3 28.5 89.6<br />
2009-08-03 18:20 1.5 27.9 89.0 1.6 26.8 90.2<br />
2009-08-03 18:30 1.6 27.8 87.0 1.8 28.6 90.4<br />
2009-08-03 18:40 2.1 27.9 89.0 2.4 28.0 90.5<br />
2009-08-03 18:50 2.0 28.0 90.4 2.5 29.0 90.7<br />
2009-08-03 19:00 2.6 28.0 90.0 2.7 29.6 90.4<br />
2009-08-03 19:10 2.8 28.1 90.0 3.0 29.0 90.6<br />
2009-08-03 19:20 3.5 28.1 90.2 3.6 29.0 90.7<br />
2009-08-03 19:30 3.5 28.2 90.0 3.7 29.4 90.3<br />
2009-08-03 19:40 3.2 28.1 90.4 3.0 28.9 90.5<br />
2009-08-03 19:50 2.8 28.0 90.2 2.5 30.0 90.9<br />
2009-08-03 20:00 3.3 28.1 90.5 3.0 28.5 91.6<br />
2009-08-03 20:10 4.2 28.0 90.7 4.0 28.6 91.7<br />
2009-08-03 20:20 3.4 28.0 90.6 3.2 28.5 91.1<br />
2009-08-03 20:30 3.8 28.0 90.4 3.1 28.6 90.7<br />
2009-08-03 20:40 4.8 28.0 90.6 4.5 28.4 90.8<br />
2009-08-03 20:50 6.2 28.0 90.0 6.0 27.9 91.3<br />
2009-08-03 21:00 5.7 27.9 90.5 5.0 26.0 90.9<br />
2009-08-03 21:10 6.3 27.9 90.0 6.0 24.0 90.5<br />
2009-08-03 21:20 5.6 27.9 90.1 5.2 23.0 90.4<br />
2009-08-03 21:30 4.9 27.8 90.2 5.0 26.0 89.8<br />
2009-08-03 21:40 5.4 27.7 89.0 5.1 22.2 88.6<br />
2009-08-03 21:50 4.9 27.7 88.0 4.7 22.5 87.1<br />
2009-08-03 22:00 4.0 27.7 84.0 3.9 23.5 83.1<br />
2009-08-03 22:10 4.8 27.7 77.0 4.2 25.0 76.3<br />
2009-08-03 22:20 4.8 27.7 74.0 4.1 26.1 72.1<br />
2009-08-03 22:30 4.5 27.8 68.0 4.4 27.2 66.2<br />
2009-08-03 22:40 4.8 28.2 58.2 4.2 27.5 63.8<br />
2009-08-03 22:50 4.2 28.5 57.7 4.0 28.3 62.0<br />
2009-08-03 23:00 4.3 28.7 57.8 4.1 28.4 61.7<br />
2009-08-03 23:10 3.8 28.9 57.6 3.6 28.4 60.3<br />
2009-08-03 23:20 3.7 29.1 56.8 3.4 28.5 60.0<br />
215
(b) Hari III dan Hari IV<br />
Periode Seb Int. Periode dgn Int.<br />
Waktu<br />
U<br />
(Hari III)<br />
T<br />
(Hari IV)<br />
(m/det) ( 0 KR T<br />
C) (%) ( 0 U KR<br />
C) (m/det) (%)<br />
2009-09-28 10:00 1.8 29.4 57.0 1.6 29.8 45.9<br />
2009-09-28 10:10 1.7 29.4 58.4 1.5 29.4 47.6<br />
2009-09-28 10:20 2.1 29.3 57.1 2.0 28.9 49.8<br />
2009-09-28 10:30 1.4 29.3 57.3 1.2 28.8 51.5<br />
2009-09-28 10:40 1.6 29.1 56.9 0.7 28.7 52.1<br />
2009-09-28 10:50 1.6 28.9 57.1 0.9 28.2 54.1<br />
2009-09-28 11:00 1.5 29.0 57.2 0.5 28.8 54.5<br />
2009-09-28 11:10 1.6 28.9 57.7 0.0 28.8 55.4<br />
2009-09-28 11:20 1.2 28.8 57.9 0.1 28.3 57.2<br />
2009-09-28 11:30 1.3 28.8 58.5 0.2 28.2 59.0<br />
2009-09-28 11:40 1.4 28.6 59.4 0.2 28.6 59.2<br />
2009-09-28 11:50 1.1 28.5 59.8 0.0 29.0 60.9<br />
2009-09-28 12:00 0.7 28.3 60.8 0.0 28.5 61.1<br />
2009-09-28 12:10 0.8 28.3 61.1 0.0 28.6 61.4<br />
2009-09-28 12:20 0.8 28.2 61.0 0.1 28.0 63.4<br />
2009-09-28 12:30 0.4 28.1 60.9 0.5 27.9 64.5<br />
2009-09-28 12:40 1.4 28.0 61.6 0.7 27.8 65.4<br />
2009-09-28 12:50 0.7 27.8 63.0 0.4 27.2 65.7<br />
2009-09-28 13:00 0.7 27.5 64.1 0.0 27.0 65.9<br />
2009-09-28 13:10 0.5 27.5 64.0 0.4 27.0 66.9<br />
2009-09-28 13:20 0.8 27.2 67.2 0.3 26.0 67.9<br />
2009-09-28 13:30 0.2 27.1 66.3 0.0 26.5 68.3<br />
2009-09-28 13:40 0.0 27.1 66.8 0.1 26.9 68.6<br />
2009-09-28 13:50 0.0 26.8 68.6 0.1 26.5 70.2<br />
2009-09-28 14:00 0.0 26.7 69.2 0.2 26.0 70.3<br />
2009-09-28 14:10 0.6 26.6 70.4 0.2 26.2 70.8<br />
2009-09-28 14:20 0.0 26.4 71.4 0.4 26.1 71.7<br />
2009-09-28 14:30 0.0 26.3 72.3 0.2 25.9 72.5<br />
2009-09-28 14:40 0.0 26.1 73.5 0.3 25.8 73.2<br />
2009-09-28 14:50 0.0 25.8 75.4 0.2 26.0 73.9<br />
2009-09-28 15:00 0.0 25.5 76.6 0.0 26.1 74.1<br />
2009-09-28 15:10 0.0 25.5 77.0 0.0 25.6 74.3<br />
2009-09-28 15:20 0.0 25.3 78.5 0.2 25.8 75.5<br />
2009-09-28 15:30 0.0 25.3 78.7 0.5 24.5 76.5<br />
2009-09-28 15:40 0.0 25.3 78.2 0.4 24.9 77.7<br />
2009-09-28 15:50 0.0 25.4 78.0 0.4 24.0 79.2<br />
2009-09-28 16:00 0.0 25.3 78.7 0.1 25.0 80.5<br />
2009-09-28 16:10 0.0 25.1 79.9 0.0 24.9 80.4<br />
216
2009-09-28 16:20 0.0 25.1 80.1 0.1 25.3 81.3<br />
2009-09-28 16:30 0.0 25.1 80.8 0.5 25.0 80.5<br />
2009-09-28 16:40 0.0 25.1 80.7 0.8 25.2 80.5<br />
2009-09-28 16:50 0.0 25.0 81.0 0.3 25.5 80.8<br />
2009-09-28 17:00 0.0 24.9 81.5 0.6 25.0 80.0<br />
2009-09-28 17:10 0.0 24.6 82.6 0.5 25.0 80.4<br />
2009-09-28 17:20 0.0 24.5 83.0 0.6 25.2 80.8<br />
2009-09-28 17:30 0.0 24.3 84.1 0.6 25.0 80.6<br />
2009-09-28 17:40 0.0 24.2 84.3 0.3 24.9 80.6<br />
2009-09-28 17:50 0.1 24.1 85.1 0.3 24.6 81.1<br />
2009-09-28 18:00 0.1 24.0 84.9 0.6 24.4 81.9<br />
2009-09-28 18:10 0.1 23.9 85.5 0.2 24.0 83.7<br />
2009-09-28 18:20 0.0 23.8 85.6 0.0 24.2 84.0<br />
2009-09-28 18:30 0.0 23.7 85.8 0.0 24.0 83.6<br />
2009-09-28 18:40 0.0 23.5 86.5 0.0 24.2 83.8<br />
2009-09-28 18:50 0.0 23.3 87.6 0.1 22.2 83.8<br />
2009-09-28 19:00 0.0 23.3 87.4 0.0 24.0 84.7<br />
2009-09-28 19:10 0.0 23.4 86.8 0.0 23.8 84.6<br />
2009-09-28 19:20 0.0 23.3 86.9 0.0 23.0 85.0<br />
2009-09-28 19:30 0.0 23.3 86.8 0.0 21.9 85.2<br />
2009-09-28 19:40 0.1 23.1 87.1 0.0 21.8 85.7<br />
2009-09-28 19:50 0.3 23.0 85.8 0.0 21.6 86.8<br />
2009-09-28 20:00 0.0 22.9 85.8 0.0 21.6 87.1<br />
2009-09-28 20:10 0.0 22.7 86.8 0.0 21.5 87.3<br />
2009-09-28 20:20 0.1 22.5 86.3 0.0 21.6 87.8<br />
2009-09-28 20:30 0.0 22.4 86.3 0.0 21.6 87.5<br />
2009-09-28 20:40 0.0 22.4 85.9 0.0 21.5 87.8<br />
2009-09-28 20:50 0.3 22.3 85.8 0.0 21.5 87.9<br />
2009-09-28 21:00 0.0 22.1 86.5 0.0 21.3 87.9<br />
2009-09-28 21:10 0.0 21.9 87.2 0.0 21.3 88.5<br />
2009-09-28 21:20 0.0 21.8 87.4 0.0 21.3 88.4<br />
2009-09-28 21:30 0.0 22.3 86.4 0.0 21.4 88.4<br />
2009-09-28 21:40 0.0 21.9 86.6 0.0 21.6 87.6<br />
2009-09-28 21:50 0.0 22.7 83.2 0.0 21.6 87.5<br />
2009-09-28 22:00 0.0 23.4 80.5 0.3 22.0 86.7<br />
2009-09-28 22:10 0.0 25.8 70.5 0.1 22.7 83.9<br />
2009-09-28 22:20 0.0 21.9 87.1 0.1 23.6 80.2<br />
2009-09-28 22:30 1.1 27.3 63.8 0.2 24.6 76.6<br />
2009-09-28 22:40 1.8 27.8 63.1 0.2 24.9 75.9<br />
2009-09-07 23:50 2.0 27.4 66.9 0.3 25.4 73.9<br />
217
(c) Hari V dan Hari VI<br />
Periode Seb Int. Periode dgn Int.<br />
Waktu<br />
U<br />
(Hari V)<br />
T<br />
(Hari VI)<br />
(m/det) ( 0 KR U T<br />
C) (%) (m/det) ( 0 KR<br />
C) (%)<br />
2009-09-28 10:00 3.5 29.3 89.0 4.1 25.0 90.5<br />
2009-09-28 10:10 2.0 29.2 88.9 1.5 24.8 90.9<br />
2009-09-28 10:20 2.6 29.2 88.0 2.5 24.6 91.6<br />
2009-09-28 10:30 2.1 29.2 90.0 2.3 24.7 92.2<br />
2009-09-28 10:40 1.5 29.3 89.0 1.9 24.8 92.8<br />
2009-09-28 10:50 2.2 29.3 90.0 1.6 24.8 92.4<br />
2009-09-28 11:00 2.6 29.4 89.9 2.2 24.8 91.8<br />
2009-09-28 11:10 1.7 29.5 90.0 1.2 25.0 91.8<br />
2009-09-28 11:20 1.5 29.3 89.9 1.2 25.1 91.6<br />
2009-09-28 11:30 0.8 29.2 88.9 0.6 25.1 91.9<br />
2009-09-28 11:40 0.1 28.7 90.0 0.1 25.0 92.8<br />
2009-09-28 11:50 0.6 28.2 91.0 0.4 24.9 94.5<br />
2009-09-28 12:00 0.6 27.8 90.8 0.5 24.7 91.9<br />
2009-09-28 12:10 0.1 27.5 88.0 0.1 24.7 88.7<br />
2009-09-28 12:20 0.4 27.2 87.9 0.4 24.8 89.0<br />
2009-09-28 12:30 0.1 27.1 86.0 0.2 25.0 86.8<br />
2009-09-28 12:40 0.3 26.9 86.2 0.2 25.1 86.7<br />
2009-09-28 12:50 0.1 26.5 86.1 0.2 25.0 86.8<br />
2009-09-28 13:00 0.4 26.1 85.0 0.5 25.0 86.0<br />
2009-09-28 13:10 0.1 25.9 85.6 0.1 24.9 85.9<br />
2009-09-28 13:20 0.1 25.8 85.8 0.3 25.0 86.6<br />
2009-09-28 13:30 0.1 25.6 87.9 0.2 24.9 88.1<br />
2009-09-28 13:40 0.1 25.4 88.3 0.2 24.7 88.9<br />
2009-09-28 13:50 0.2 25.3 88.1 0.3 24.7 88.6<br />
2009-09-28 14:00 0.1 25.2 85.9 0.2 24.7 86.1<br />
2009-09-28 14:10 0.2 25.1 84.0 0.1 24.8 85.8<br />
2009-09-28 14:20 0.2 25.1 86.0 0.2 24.6 87.6<br />
2009-09-28 14:30 0.8 25.0 87.0 0.6 24.4 88.2<br />
2009-09-28 14:40 0.5 24.7 87.2 0.6 24.4 87.6<br />
2009-09-28 14:50 0.8 24.6 87.1 0.7 24.3 87.5<br />
2009-09-28 15:00 0.2 24.3 86.8 0.1 24.4 87.1<br />
2009-09-28 15:10 0.4 24.1 86.2 0.5 24.4 86.7<br />
2009-09-28 15:20 0.1 23.7 88.8 0.2 24.1 89.1<br />
2009-09-28 15:30 0.2 23.7 88.9 0.1 24.0 89.7<br />
2009-09-28 15:40 0.1 23.7 89.8 0.4 23.9 90.1<br />
2009-09-28 15:50 0.2 23.7 90.0 0.3 23.8 90.7<br />
2009-09-28 16:00 0.2 23.5 90.4 0.4 23.8 91.0<br />
2009-09-28 16:10 0.1 23.5 90.1 0.3 23.8 90.6<br />
2009-09-28 16:20 0.1 23.4 89.8 0.1 23.8 90.2<br />
2009-09-28 16:30 0.2 23.3 89.9 0.1 23.7 90.8<br />
2009-09-28 16:40 0.1 23.3 90.9 0.1 23.7 91.6<br />
2009-09-28 16:50 0.1 23.4 90.8 0.1 23.6 92.0<br />
2009-09-28 17:00 0.1 23.3 91.7 0.3 23.6 92.5<br />
218
2009-09-28 17:10 0.5 23.2 91.0 0.4 23.6 92.3<br />
2009-09-28 17:20 0.2 23.2 89.8 0.3 23.7 90.9<br />
2009-09-28 17:30 0.2 23.2 89.2 0.1 23.9 89.6<br />
2009-09-28 17:40 0.2 23.1 90.1 0.1 23.7 90.5<br />
2009-09-28 17:50 0.1 23.1 90.0 0.2 23.6 91.3<br />
2009-09-28 18:00 0.1 22.7 90.1 0.1 23.5 91.3<br />
2009-09-28 18:10 0.2 22.6 91.0 0.1 23.3 92.0<br />
2009-09-28 18:20 0.3 22.5 91.9 0.2 23.2 92.6<br />
2009-09-28 18:30 0.3 22.5 92.0 0.5 23.1 93.3<br />
2009-09-28 18:40 0.9 22.5 93.0 0.2 23.1 94.0<br />
2009-09-28 18:50 0.5 22.7 94.5 0.7 23.1 94.4<br />
2009-09-28 19:00 0.3 22.6 94.2 0.2 23.1 94.1<br />
2009-09-28 19:10 0.4 22.5 93.4 0.5 23.1 92.9<br />
2009-09-28 19:20 0.1 22.4 94.0 0.2 23.1 92.4<br />
2009-09-28 19:30 0.0 22.3 93.1 0.3 23.1 92.5<br />
2009-09-28 19:40 0.3 22.2 92.0 0.2 23.1 93.0<br />
2009-09-28 19:50 0.9 22.4 94.0 0.6 23.1 93.3<br />
2009-09-28 20:00 1.0 22.5 90.2 0.8 23.1 93.3<br />
2009-09-28 20:10 0.9 22.6 92.5 0.7 23.1 93.5<br />
2009-09-28 20:20 0.5 22.4 95.0 0.4 23.1 94.5<br />
2009-09-28 20:30 0.1 22.1 95.5 0.2 23.1 95.0<br />
2009-09-28 20:40 0.1 21.8 95.0 0.2 23.2 94.8<br />
2009-09-28 20:50 0.0 21.8 94.0 0.2 23.4 93.1<br />
2009-09-28 21:00 0.0 21.7 90.0 0.1 23.7 91.1<br />
2009-09-28 21:10 0.8 21.5 92.0 0.7 23.6 91.8<br />
2009-09-28 21:20 0.1 21.5 94.0 0.2 23.7 92.1<br />
2009-09-28 21:30 0.1 21.6 93.0 0.3 24.1 91.0<br />
2009-09-28 21:40 0.1 21.5 88.0 0.2 24.8 87.3<br />
2009-09-28 21:50 0.0 21.7 79.0 0.1 25.9 79.8<br />
2009-09-28 22:00 0.0 22.0 83.0 0.1 25.4 83.1<br />
2009-09-28 22:10 0.0 22.1 76.3 0.2 26.9 75.8<br />
2009-09-28 22:20 0.3 23.5 72.0 0.2 28.3 70.2<br />
2009-09-28 22:30 0.0 24.0 71.0 0.1 28.3 70.8<br />
2009-09-28 22:40 0.1 24.8 74.0 0.2 26.5 78.3<br />
219
(d) Hari VII dan Hari VIII<br />
Periode Seb Int. Periode dgn Int.<br />
Waktu<br />
(Hari VII)<br />
U T<br />
(Hari VIII)<br />
(m/det) ( 0 KR U T<br />
C) (%) (m/det) ( 0 KR<br />
C) (%)<br />
2009-10-19 10:20 0.2 26.6 76.0 0.2 26.8 80.0<br />
2009-10-19 10:30 0.2 26.4 77.8 0.1 26.2 80.1<br />
2009-10-19 10:40 0.7 26.2 78.3 0.5 25.9 80.2<br />
2009-10-19 10:50 0.2 26.2 78.8 0.3 26.0 80.0<br />
2009-10-19 11:00 0.0 25.9 80.3 0.2 25.7 80.9<br />
2009-10-19 11:10 0.2 25.8 81.0 0.4 25.6 82.0<br />
2009-10-19 11:20 0.2 25.6 82.3 0.3 25.2 82.8<br />
2009-10-19 11:30 0.5 25.4 83.3 0.7 24.7 83.6<br />
2009-10-19 11:40 0.1 25.3 84.0 0.2 24.5 84.5<br />
2009-10-19 11:50 0.0 25.3 84.1 s0.1 24.4 84.8<br />
2009-10-19 12:00 0.1 25.3 84.1 0.1 24.5 85.0<br />
2009-10-19 12:10 0.0 25.3 84.5 0.0 24.4 85.2<br />
2009-10-19 12:20 0.0 25.1 85.1 0.0 24.4 85.6<br />
2009-10-19 12:30 0.1 25.2 84.3 0.0 25.0 85.0<br />
2009-10-19 12:40 0.3 25.4 83.2 0.0 25.1 84.0<br />
2009-10-19 12:50 0.1 25.4 83.0 0.1 25.3 83.5<br />
2009-10-19 13:00 0.0 25.5 81.5 0.0 25.2 82.0<br />
2009-10-19 13:10 0.5 25.5 81.9 0.6 25.4 82.2<br />
2009-10-19 13:20 0.4 25.4 82.2 0.5 25.3 82.8<br />
2009-10-19 13:30 0.5 25.3 82.9 0.4 25.1 83.0<br />
2009-10-19 13:40 0.1 25.2 82.8 0.0 25.1 83.2<br />
2009-10-19 13:50 0.0 25.2 83.2 0.2 25.0 83.6<br />
2009-10-19 14:00 0.6 25.0 84.2 0.7 24.9 84.8<br />
2009-10-19 14:10 0.5 24.8 84.8 0.5 24.6 85.2<br />
2009-10-19 14:20 0.0 24.8 84.0 0.1 24.6 85.0<br />
2009-10-19 14:30 0.1 24.7 84.4 0.2 24.3 85.3<br />
2009-10-19 14:40 0.2 24.7 84.3 0.6 24.5 85.1<br />
2009-10-19 14:50 0.2 24.7 84.1 0.1 24.3 85.5<br />
2009-10-19 15:00 0.2 24.6 85.0 0.4 24.4 85.4<br />
2009-10-19 15:10 0.6 24.5 85.8 0.5 24.5 86.0<br />
2009-10-19 15:20 0.7 24.4 85.8 0.5 24.5 86.2<br />
2009-10-19 15:30 0.2 24.3 86.1 0.4 24.5 86.5<br />
2009-10-19 15:40 0.0 24.1 87.2 0.1 24.5 87.8<br />
2009-10-19 15:50 0.3 24.0 87.2 0.4 24.1 87.9<br />
2009-10-19 16:00 0.2 23.9 87.3 0.3 24.0 87.9<br />
220
2009-10-19 16:10 0.1 23.8 87.6 0.2 24.1 88.0<br />
2009-10-19 16:20 0.1 23.7 88.0 0.2 23.9 88.2<br />
2009-10-19 16:30 0.2 23.6 88.4 0.0 23.7 88.6<br />
2009-10-19 16:40 0.0 23.7 87.8 0.1 23.9 88.0<br />
2009-10-19 16:50 0.4 23.7 87.6 0.3 23.9 88.2<br />
2009-10-19 17:00 0.6 23.8 86.7 0.5 23.9 88.4<br />
2009-10-19 17:10 0.4 23.8 86.6 0.2 23.9 87.2<br />
2009-10-19 17:20 0.0 23.6 87.9 0.1 23.7 88.3<br />
2009-10-19 17:30 0.5 23.5 88.5 0.6 23.5 88.9<br />
2009-10-19 17:40 0.7 23.4 89.0 0.6 23.6 90.0<br />
2009-10-19 17:50 0.0 23.3 89.0 0.2 23.6 90.1<br />
2009-10-19 18:00 0.0 23.1 89.4 0.1 23.3 90.0<br />
2009-10-19 18:10 0.0 23.0 89.7 0.0 23.2 90.2<br />
2009-10-19 18:20 0.0 22.9 90.2 0.2 23.0 90.0<br />
2009-10-19 18:30 0.5 22.9 90.1 0.6 23.1 90.6<br />
2009-10-19 18:40 0.3 22.9 90.0 0.4 22.8 90.2<br />
2009-10-19 18:50 0.7 22.9 89.9 0.6 23.1 90.4<br />
2009-10-19 19:00 0.0 22.9 89.2 0.2 23.1 90.6<br />
2009-10-19 19:10 0.0 22.9 89.4 0.0 23.4 90.4<br />
2009-10-19 19:20 0.3 22.9 89.5 0.4 23.2 90.0<br />
2009-10-19 19:30 0.5 23.0 89.0 0.6 23.2 90.0<br />
2009-10-19 19:40 0.4 22.9 89.2 0.3 23.1 90.2<br />
2009-10-19 19:50 0.2 22.8 89.7 0.2 22.9 90.6<br />
2009-10-19 20:00 0.2 22.8 89.7 0.2 23.0 90.5<br />
2009-10-19 20:10 0.4 22.8 89.4 0.5 23.1 90.4<br />
2009-10-19 20:20 0.3 22.7 89.9 0.2 22.9 90.2<br />
2009-10-19 20:30 0.6 22.5 90.6 0.5 22.8 90.9<br />
2009-10-19 20:40 0.0 22.3 91.5 0.0 22.6 91.8<br />
2009-10-19 20:50 0.0 22.2 92.0 0.1 22.5 92.6<br />
2009-10-19 21:00 0.2 22.1 92.4 0.3 22.4 93.0<br />
2009-10-19 21:10 0.2 22.1 92.3 0.2 22.3 93.1<br />
2009-10-19 21:20 0.0 22.2 92.2 0.4 22.5 92.8<br />
2009-10-19 21:30 0.1 22.3 91.8 0.2 22.5 92.0<br />
2009-10-19 21:40 0.0 22.4 91.3 0.0 22.6 92.1<br />
2009-10-19 21:50 0.0 22.5 90.8 0.0 22.7 90.2<br />
2009-10-19 22:00 0.0 22.8 90.2 0.1 22.9 90.7<br />
2009-10-19 22:10 0.4 23.4 87.5 0.2 23.5 89.8<br />
2009-10-19 22:20 0.8 24.4 82.7 0.7 24.7 83.0<br />
2009-10-19 22:30 0.2 24.9 80.2 0.3 25.0 81.1<br />
221
Lampiran 9<br />
2009-10-19 22:40 0.5 25.3 78.9 0.4 25.2 80.7<br />
2009-10-19 22:50 1.3 25.6 77.7 1.5 25.9 80.9<br />
2009-10-19 23:00 0.9 26.5 74.3 1.0 27.4 80.6<br />
2009-10-19 23:10 0.5 27.1 72.0 0.6 27.5 79.9<br />
2009-10-19 23:20 0.3 27.9 68.3 0.4 27.7 78.4<br />
2009-10-19 23:30 0.3 28.2 67.6 0.3 27.8 77.1<br />
2009-10-19 23:40 1.0 28.2 69.0 0.9 28.0 77.2<br />
2009-10-19 23:50 1.0 28.4 68.8 1.2 28.0 77.3<br />
Hasil Uji Normalitas Data Iklim Mikro.<br />
(a) Hari I dan II<br />
Tests of Normality<br />
222<br />
Klp Statistic df Sig. Statistic<br />
Shapiro-Wilk<br />
df Sig.<br />
u 1.00 .134 81 .001 .932 81 .000<br />
2.00 .176 81 .000 .942 81 .001<br />
T 1.00 .191 81 .000 .875 81 .000<br />
2.00 .332 81 .000 .674 81 .000<br />
KR 1.00 .218 81 .000 .760 81 .000<br />
2.00 .215 81 .000 .787 81 .000<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
(b) Hari III dan IV<br />
u<br />
T<br />
KR<br />
Klp<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Tests of Normality<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Shapiro-Wilk<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
.329 78 .000 .691 78 .000<br />
.240 78 .000 .715 78 .000<br />
.088 78 .200* .942 78 .002<br />
.103 78 .039 .943 78 .002<br />
.148 78 .000 .861 78 .000<br />
.171 78 .000 .905 78 .000<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
a.<br />
Lilliefors Significance Correction
(c) Hari V dan VI<br />
u<br />
T<br />
KR<br />
Klp<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
Tests of Normality<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Shapiro-Wilk<br />
223<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
.259 77 .000 .665 77 .000<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
(d) Hari VII dan VIII<br />
u<br />
T<br />
KR<br />
Klp<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
.277 77 .000 .591 77 .000<br />
.187 77 .000 .873 77 .000<br />
.150 77 .000 .852 77 .000<br />
.163 77 .000 .824 77 .000<br />
.172 77 .000 .773 77 .000<br />
Tests of Normality<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Shapiro-Wilk<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
.190 82 .000 .873 82 .000<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 10<br />
.169 82 .000 .875 82 .000<br />
.105 82 .027 .945 82 .001<br />
.093 82 .078 .930 82 .000<br />
.116 82 .009 .886 82 .000<br />
.138 82 .001 .951 82 .003<br />
Uji Beda non parametric dengan Mann-Whitney data iklim mikro<br />
(a) Hari I dan II.<br />
Test Statistics a<br />
u T KR<br />
Mann-Whitney U 2879.500 2720.500 2938.000<br />
Wilcoxon W<br />
6200.500 6041.500 6259.000<br />
Z<br />
-1.344 -1.894 -1.148<br />
Asymp. Sig. (2-tailed) .179 .058 .251<br />
a.<br />
Grouping Variable: Klp
(b) Hari III dan IV.<br />
Mann-Whitney U<br />
Wilcoxon W<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
a. Grouping Variable: Klp<br />
(c) Hari V dan VI.<br />
Test Statistics a<br />
u T KR<br />
2831.000 2760.500 3014.500<br />
5912.000 5841.500 6095.500<br />
-.794 -.998 -.097<br />
.427 .318 .922<br />
Test Statistics a<br />
u T KR<br />
Mann-Whitney U 2591.500 2625.000 2459.500<br />
Wilcoxon W<br />
5594.500 5628.000 5462.500<br />
Z<br />
-1.371 -1.228 -1.825<br />
Asymp. Sig. (2-tailed) .170 .219 .068<br />
a. Grouping Variable: Klp<br />
(d) Hari VII dan VIII.<br />
Mann-Whitney U<br />
Wilcoxon W<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
a.<br />
Grouping Variable: Klp<br />
Test Statistics a<br />
u T KR<br />
3006.500 3341.500 2981.000<br />
6409.500 6744.500 6384.000<br />
-1.182 -.067 -1.253<br />
.237 .946 .210<br />
224
Lampiran 11<br />
Data Hasil Pengamatan Denyut Nadi Istirahat dan Denyut Nadi Kerja Nelayan Pukat Cincin di Perairan Amurang Kecamatan<br />
Minahasa Selatan.<br />
(a) Periode Tanpa Intervensi<br />
Nama<br />
Sebelum Kerja: Sedang Kerja: Setelah Kerja:<br />
Periode Periode Periode<br />
I II III IV I II III IV I II III IV<br />
Hans Gonta 76 74 74 75 149 148 140 149 119 144 145 146<br />
Nyong Pangkey 77 75 73 77 152 157 151 158 128 140 143 140<br />
Johny Matheos 75 75 75 78 152 157 153 156 127 144 144 139<br />
Alex Heydemans 75 74 72 76 151 140 126 156 129 135 131 140<br />
Hendrik Josephus 74 75 74 75 152 156 154 157 128 137 146 144<br />
Abraham Mononimbar 72 74 75 76 153 157 153 158 129 140 142 135<br />
Arnol Piters 72 73 72 76 155 151 157 153 128 144 142 137<br />
Christian Assa 73 75 70 77 154 158 155 155 128 140 140 139<br />
Rein Sinobo 74 76 71 78 156 122 131 100 128 126 135 98<br />
Albert Johanis 73 76 75 76 144 157 156 158 123 140 144 143<br />
Joppy Anes 72 75 72 75 158 155 153 157 136 135 144 135<br />
Gaspar Tumbuan 75 76 73 75 155 155 155 153 137 144 146 140<br />
Ungke Ottay 75 76 75 77 135 126 144 154 138 135 148 135<br />
Elis Sariowan 77 76 76 78 158 158 157 113 135 144 149 111<br />
Cornelis Weydekam 75 76 74 75 155 158 158 153 136 143 148 144<br />
Maxi Kindangen 76 78 76 75 135 157 158 155 122 144 147 144<br />
Lexi Josephus 77 77 75 78 157 158 157 113 136 142 146 108<br />
Raul Sariowan 78 78 74 78 157 126 122 101 136 142 128 144<br />
225
(b) Periode dengan Intervensi<br />
Nama<br />
Sebelum Kerja: Sedang Kerja: Setelah Kerja:<br />
Periode Periode Periode<br />
I II III IV I II III IV I II III IV<br />
Hans Gonta 75 72 68 73 101 105 92 104 102 105 104 94<br />
Nyong Pangkey 72 71 66 74 107 109 106 107 102 104 102 85<br />
Johny Matheos 68 72 65 72 107 108 106 106 104 102 102 98<br />
Alex Heydemans 69 73 60 70 107 106 101 106 102 106 103 98<br />
Hendrik Josephus 72 75 62 73 106 98 106 106 99 99 103 99<br />
Abraham Mononimbar 71 74 64 72 106 108 97 109 99 104 104 98<br />
Arnol Piters 70 75 65 75 107 106 97 107 100 104 105 94<br />
Christian Assa 73 75 66 74 108 107 101 109 99 102 102 98<br />
Rein Sinobo 70 70 68 75 108 107 106 114 98 103 103 106<br />
Albert Johanis 70 74 70 70 96 108 98 110 95 102 101 94<br />
Joppy Anes 72 74 71 72 109 108 110 108 99 102 102 85<br />
Gaspar Tumbuan 71 73 71 71 106 98 114 106 98 99 102 85<br />
Ungke Ottay 70 75 73 70 107 109 99 106 99 106 102 98<br />
Elis Sariowan 70 71 72 75 95 108 112 114 98 102 105 105<br />
Cornelis Weydekam 70 72 70 72 107 108 110 109 97 106 102 85<br />
Maxi Kindangen 70 72 69 75 108 107 106 108 95 105 105 85<br />
Lexi Josephus 71 74 69 74 106 99 106 107 96 104 106 94<br />
Raul Sariowan 72 73 71 75 107 109 92 101 94 105 102 94<br />
226
Lampiran 12<br />
Hasil Uji Normalitas Data Denyut Nadi Istirahat pada Periode Tanpa Intervensi<br />
dan Periode dengan Intervensi.<br />
Tests of Normality<br />
Statistic df Sig. Statistic<br />
Shapiro-Wilk<br />
df Sig.<br />
I_TI ,159 18 ,200* ,937 18 ,260<br />
II_TI ,188 18 ,093 ,936 18 ,248<br />
III_TI ,188 18 ,092 ,929 18 ,187<br />
IV_TI ,201 18 ,052 ,828 18 ,004<br />
I_DI ,210 18 ,035 ,920 18 ,127<br />
II_DI ,173 18 ,162 ,923 18 ,144<br />
III_DI ,136 18 ,200* ,952 18 ,452<br />
IV_DI ,171 18 ,174 ,882 18 ,028<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 13<br />
Hasil Uji Beda Rerata Denyut Nadi Istirahat Periode Tanpa Intervensi dan Periode<br />
Dengan Intervensi.<br />
(a) Uji-t<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
227<br />
Pair 1 Pair 2 Pair 3<br />
I_TI - I_DI II_TI - II_DI III_TI - III_DI<br />
3,889 2,444 5,889<br />
2,374 2,281 3,462<br />
,559 ,538 ,816<br />
2,709 1,310 4,167<br />
5,069 3,579 7,611<br />
6,951 4,547 7,216<br />
17 17 17<br />
,000 ,000 ,000
(b) Uji-Wilcoxon<br />
Z<br />
Test Statistics b<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
IV_DI - IV_TI<br />
a. Based on positive ranks.<br />
-3,655 a<br />
,000<br />
b.<br />
Wilcoxon Signed Ranks Test<br />
228
Lampiran 14<br />
Data Selisih Denyut Nadi Kerja dan Denyut Nadi Istirahat Untuk 4 Empat Kali Ulangan pada Periode Tanpa Intervensi dan Periode<br />
Dengan Intervensi.<br />
(a) Selisih Periode Tanpa Intervensi<br />
Periode Tanpa Intervensi:<br />
No. Nama<br />
I II III IV<br />
DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI<br />
1 Hans Gonta 72 43 73 70 65 71 74 71<br />
2 Nyong Pangkey 75 50 81 64 79 71 80 62<br />
3 Johny Matheos 77 51 82 69 78 69 78 61<br />
4 Alex Heydemans 76 54 65 61 54 58 80 63<br />
5 Hendrik Josephus 78 53 81 62 80 72 81 69<br />
6 Abraham Mononimbar 81 57 83 65 78 67 81 59<br />
7 Arnol Piters 82 56 78 71 84 70 77 60<br />
8 Christian Assa 81 55 82 64 85 69 78 61<br />
9 Rein Sinobo 81 53 45 50 59 64 22 20<br />
10 Albert Johanis 71 50 80 63 81 69 81 67<br />
11 Joppy Anes 85 64 80 60 81 72 81 60<br />
12 Gaspar Tumbuan 80 62 78 68 82 73 78 64<br />
13 Ungke Ottay 60 63 50 59 69 72 77 58<br />
14 Elis Sariowan 80 58 81 68 80 72 34 33<br />
15 Cornelis Weydekam 80 61 81 67 83 73 78 69<br />
16 Maxi Kindangen 59 45 78 66 81 70 80 69<br />
17 Lexi Josephus 80 59 80 65 81 71 34 30<br />
18 Raul Sariowan 78 58 48 64 47 54 23 66<br />
229
(b) Selisih Periode dengan Intervensi<br />
Periode Dengan Intervensi:<br />
No. Nama<br />
I II III IV<br />
DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI DNSdK‐DNI DNK‐DNI<br />
1 Hans Gonta 26 27 32 32 24 35 31 20<br />
2 Nyong Pangkey 34 30 37 32 39 36 33 11<br />
3 Johny Matheos 38 35 36 30 41 37 34 26<br />
4 Alex Heydemans 38 33 33 33 41 43 35 28<br />
5 Hendrik Josephus 34 27 22 24 43 41 33 26<br />
6 Abraham Mononimbar 35 27 33 29 33 39 37 25<br />
7 Arnol Piters 37 30 31 29 31 40 32 18<br />
8 Christian Assa 36 26 32 27 35 36 35 24<br />
9 Rein Sinobo 37 27 37 33 37 34 39 31<br />
10 Albert Johanis 26 25 33 28 27 31 40 23<br />
11 Joppy Anes 36 27 33 28 39 31 36 13<br />
12 Gaspar Tumbuan 35 26 24 25 43 31 34 14<br />
13 Ungke Ottay 36 28 33 31 26 29 35 27<br />
14 Elis Sariowan 25 28 37 31 39 33 39 30<br />
15 Cornelis Weydekam 37 27 35 34 40 32 37 13<br />
16 Maxi Kindangen 38 25 34 33 36 35 33 10<br />
17 Lexi Josephus 34 25 24 29 36 37 33 19<br />
18 Raul Sariowan 35 21 35 32 21 31 26 18<br />
230
Lampiran 15<br />
Hasil Uji Normalitas Data Selisih Denyut Nadi pada Periode Tanpa Intervensi dan<br />
Periode dengan Intervensi.<br />
Tests of Normality<br />
Statistic df Sig. Statistic<br />
Shapiro-Wilk<br />
df Sig.<br />
ISdTI ,198 18 ,060 ,800 18 ,002<br />
ISsTI ,082 18 ,200* ,969 18 ,772<br />
IISdTI ,356 18 ,000 ,677 18 ,000<br />
IISsTI ,149 18 ,200* ,907 18 ,077<br />
IIISdTI ,333 18 ,000 ,767 18 ,001<br />
IIISsTI ,299 18 ,000 ,734 18 ,000<br />
IVSdTI ,393 18 ,000 ,614 18 ,000<br />
IVSsTI ,336 18 ,000 ,729 18 ,000<br />
ISdDI ,307 18 ,000 ,747 18 ,000<br />
ISsDI ,223 18 ,018 ,907 18 ,077<br />
IISdDI ,253 18 ,003 ,817 18 ,003<br />
IISsDI ,148 18 ,200* ,941 18 ,299<br />
IIISdDI ,167 18 ,198 ,905 18 ,070<br />
IIISsDI ,126 18 ,200* ,956 18 ,520<br />
IVSdDI ,153 18 ,200* ,944 18 ,339<br />
IVSsDI ,125 18 ,200* ,942 18 ,309<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 16.<br />
Hasil Uji Beda Rerata Selisiah Denyut Nadi Periode Tanpa Intervensi dan Periode<br />
Dengan Intervensi.<br />
(a) Uji-t<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Pair 1<br />
ISsTI - ISsDI<br />
231<br />
Pair 2<br />
IISsTI - IISsDI<br />
27,667 34,222<br />
7,029 5,956<br />
1,657 1,404<br />
24,171 31,260<br />
31,162 37,184<br />
16,699 24,376<br />
17 17<br />
,000 ,000
(b) Uji-Wilcoxon<br />
Test Statistics b<br />
232<br />
-3,731a -3,728a -3,727a -3,725a -3,336a -3,616a IIISdDI - IIISsDI - IVSdDI - IVSsDI -<br />
ISdDI - ISdTI IISdDI - IISdTI IIISdTI IIISsTI IVSdTI IVSsTI<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000<br />
a. Based on positive ranks.<br />
Z<br />
b. Wilcoxon Signed Ranks Test<br />
(c) Uji Normalitas Rerata Selisih Empat Periode<br />
SdTI<br />
SsTI<br />
SdDI<br />
SsDi<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Tests of Normality<br />
Shapiro-Wilk<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
,256 18 ,003 ,796 18 ,001<br />
,263 18 ,002 ,808 18 ,002<br />
,113 18 ,200* ,938 18 ,272<br />
,064 18 ,200* ,984 18 ,981<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
(d) Uji Beda Rerata Selisih Empat Periode<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
Test Statistics b<br />
a. Based on positive ranks.<br />
b.<br />
Wilcoxon Signed Ranks Test<br />
-3,724a -3,724a SdDI - SdTI SsDi - SsTI<br />
,000 ,000
Lampiran 17<br />
Data Hasil Pengamatan Skor Kelelahan Nelayan Pukat Cincin di Perairan Amurang Kecamatan Minahasa Selatan.<br />
(a) Sebelum Aktivitas Kerja.<br />
Hari I: Hari II: Hari III: Hari IV:<br />
TIN DIN Total TIN DIN Total TIN DIN Total TIN DIN Total<br />
I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN<br />
14 15 14 15 15 14 43 44 21 24 22 24 25 21 67 70 14 23 13 15 24 15 50 54 27 24 24 25 24 25 75 74<br />
13 15 12 13 15 14 40 42 23 23 22 23 22 23 68 68 15 24 12 13 25 14 51 52 27 25 22 27 23 25 74 75<br />
15 17 14 16 15 15 46 46 23 25 24 22 24 21 72 67 15 25 17 13 23 16 57 52 24 24 24 25 23 25 72 73<br />
14 15 16 16 16 16 45 48 22 26 23 23 23 22 71 68 15 24 15 15 20 15 54 50 21 25 23 23 26 25 69 74<br />
14 16 17 15 17 16 47 48 24 25 25 23 25 25 74 73 16 25 14 15 23 16 55 54 22 24 27 23 23 22 73 68<br />
17 14 14 14 18 15 45 47 22 24 23 23 24 23 69 70 16 24 17 15 23 15 57 53 22 24 26 26 24 23 72 73<br />
16 16 17 16 16 15 49 47 24 25 24 21 22 25 73 68 18 25 13 15 26 14 56 55 22 23 25 26 26 26 70 78<br />
14 15 14 15 13 14 43 42 23 25 23 23 21 26 71 70 17 22 17 16 29 15 56 60 24 24 23 24 26 22 71 72<br />
16 15 15 14 16 17 46 47 20 22 23 22 22 24 65 68 14 24 15 15 22 16 53 53 22 24 23 26 25 24 69 75<br />
10 12 11 15 15 15 33 45 20 22 23 23 27 23 65 73 15 22 15 16 22 15 52 53 27 25 22 23 25 26 74 74<br />
10 11 11 14 13 20 32 47 21 23 23 22 22 23 67 67 14 25 16 17 24 15 55 56 24 26 22 25 27 24 72 76<br />
15 14 11 17 11 18 40 46 20 23 24 22 24 21 67 67 14 24 15 18 24 15 53 57 23 26 22 24 25 26 71 75<br />
12 15 11 10 15 15 38 40 23 20 23 23 24 21 66 68 17 25 16 14 23 15 58 52 21 24 24 26 24 26 69 76<br />
10 12 13 10 10 10 35 30 23 23 22 22 21 24 68 67 16 24 16 15 25 15 56 55 22 26 25 29 30 30 73 89<br />
14 12 11 10 15 10 37 35 24 26 23 21 22 23 73 66 18 24 16 14 24 14 58 52 25 23 26 26 24 24 74 74<br />
13 15 17 13 15 16 45 44 21 23 23 22 21 21 67 64 13 22 14 14 24 16 49 54 24 22 23 28 25 23 69 76<br />
14 16 12 14 15 15 42 44 21 20 22 20 23 23 63 66 15 23 11 16 20 15 49 51 27 22 26 21 21 20 75 62<br />
10 13 11 14 12 13 34 39 21 21 25 23 25 23 67 71 16 22 14 15 27 15 52 57 24 25 24 24 26 26 73 76<br />
Keterangan: TIN atau TI = Tanpa intervensi; DIN atau DI = Dengan Intervensi.<br />
233
(b) Total Sebelum Aktivitas Kerja.<br />
Rerata<br />
TIN DIN<br />
I II III Total I II III Total<br />
19,00 21,50 18,25 58,75 22,00 18,75 58,75 60,50<br />
19,50 21,75 17,00 58,25 21,25 19,00 58,25 59,25<br />
19,25 22,75 19,75 61,75 21,25 19,25 61,75 59,50<br />
18,00 22,50 19,25 59,75 21,25 19,50 59,75 60,00<br />
19,00 22,50 20,75 62,25 22,00 19,75 62,25 60,75<br />
19,25 21,50 20,00 60,75 22,25 19,00 60,75 60,75<br />
20,00 22,25 19,75 62,00 22,50 20,00 62,00 62,00<br />
19,50 21,50 19,25 60,25 22,25 19,25 60,25 61,00<br />
18,00 21,25 19,00 58,25 21,25 20,25 58,25 60,75<br />
18,00 20,25 17,75 56,00 22,25 19,75 56,00 61,25<br />
17,25 21,25 18,00 56,50 21,50 20,50 56,50 61,50<br />
18,00 21,75 18,00 57,75 21,00 20,00 57,75 61,25<br />
18,25 21,00 18,50 57,75 21,50 19,25 57,75 59,00<br />
17,75 21,25 19,00 58,00 21,50 19,75 58,00 60,25<br />
20,25 21,25 19,00 60,50 21,25 17,75 60,50 56,75<br />
17,75 20,50 19,25 57,50 21,25 19,00 57,50 59,50<br />
19,25 20,25 17,75 57,25 19,75 18,25 57,25 55,75<br />
17,75 20,25 18,50 56,50 22,50 19,25 56,50 60,75<br />
Keterangan: TIN atau TI = Tanpa intervensi; DIN atau DI = Dengan Intervensi.<br />
234
(c) Setelah Aktivitas Kerja.<br />
Hari I: Hari II: Hari III: Hari IV:<br />
TIN DIN Total TIN DIN Total TIN DIN Total TIN DIN Total<br />
I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN I II III I II III TIN DIN<br />
41 35 39 31 32 32 115 95 40 31 34 27 32 33 105 92 41 42 43 37 41 35 126 113 47 42 43 48 42 36 132 126<br />
40 41 39 36 37 37 120 110 38 31 34 37 31 32 103 100 39 38 38 36 37 39 115 112 43 42 44 44 42 38 129 124<br />
41 37 40 38 39 38 118 115 39 31 36 37 32 33 106 102 41 42 43 39 30 38 126 107 44 42 45 43 39 39 131 121<br />
41 36 38 31 32 31 115 94 40 31 34 35 35 31 105 101 41 38 40 40 40 39 119 119 44 42 46 33 42 43 132 118<br />
39 36 40 37 38 35 115 110 38 31 34 36 31 33 103 100 38 45 40 41 35 39 123 115 43 40 46 40 39 45 129 124<br />
45 44 46 42 41 42 135 125 39 31 34 27 30 32 104 89 42 37 41 40 40 32 120 112 44 43 45 41 36 44 132 121<br />
45 42 45 41 41 42 132 124 40 31 34 40 31 35 105 106 40 42 41 40 35 36 123 111 46 38 48 41 36 46 132 123<br />
40 31 35 36 36 27 106 99 40 31 35 41 32 34 106 107 41 35 40 35 42 37 116 114 45 46 44 42 34 43 135 119<br />
42 40 43 36 38 41 125 115 38 31 34 35 31 35 103 101 40 44 41 35 39 35 125 109 44 38 48 38 40 48 130 126<br />
39 31 33 32 33 33 103 98 39 31 33 35 33 32 103 100 39 37 34 33 40 37 110 110 44 44 42 40 36 43 130 119<br />
39 31 33 34 33 33 103 100 37 31 33 37 31 33 101 101 41 40 42 38 37 36 123 111 44 43 43 39 34 40 130 113<br />
43 37 40 35 34 31 120 100 39 31 34 34 33 32 104 99 40 38 36 36 32 39 114 107 46 41 43 40 37 41 130 118<br />
45 45 45 33 31 32 135 96 39 31 34 38 32 35 104 105 40 38 40 43 25 36 118 104 44 42 43 44 43 40 129 127<br />
40 31 36 37 34 35 107 106 40 31 36 35 33 34 107 102 42 40 40 29 36 34 122 99 48 43 45 36 40 44 136 120<br />
40 31 34 38 32 33 105 103 40 31 34 37 33 34 105 104 41 37 39 30 37 30 117 97 47 39 43 43 38 42 129 123<br />
39 31 34 35 33 36 104 104 39 31 34 34 31 29 104 94 40 41 44 38 33 33 125 104 45 43 44 42 37 43 132 122<br />
40 31 34 35 34 37 105 106 40 31 34 35 31 28 105 94 43 39 37 40 38 35 119 113 46 43 40 48 38 42 129 128<br />
40 31 34 33 30 35 105 98 40 31 34 28 33 34 105 95 40 40 41 41 29 43 121 113 44 38 43 45 41 43 125 129<br />
235
(d) Total Setelah Aktivitas Kerja<br />
Rerata<br />
TIN DIN<br />
I II III Total I II III Total<br />
42,25 37,50 39,75 119,50 36,75 34,00 119,50 106,50<br />
40,00 38,00 38,75 116,75 36,75 36,50 116,75 111,50<br />
41,25 38,00 41,00 120,25 35,00 37,00 120,25 111,25<br />
41,50 36,75 39,50 117,75 37,25 36,00 117,75 108,00<br />
39,50 38,00 40,00 117,50 35,75 38,00 117,50 112,25<br />
42,50 38,75 41,50 122,75 36,75 37,50 122,75 111,75<br />
42,75 38,25 42,00 123,00 35,75 39,75 123,00 116,00<br />
41,50 35,75 38,50 115,75 36,00 35,25 115,75 109,75<br />
41,00 38,25 41,50 120,75 37,00 39,75 120,75 112,75<br />
40,25 35,75 35,50 111,50 35,50 36,25 111,50 106,75<br />
40,25 36,25 37,75 114,25 33,75 35,50 114,25 106,25<br />
42,00 36,75 38,25 117,00 34,00 35,75 117,00 106,00<br />
42,00 39,00 40,50 121,50 32,75 35,75 121,50 108,00<br />
42,50 36,25 39,25 118,00 35,75 36,75 118,00 106,75<br />
42,00 34,50 37,50 114,00 35,00 34,75 114,00 106,75<br />
40,75 36,50 39,00 116,25 33,50 35,25 116,25 106,00<br />
42,25 36,00 36,25 114,50 35,25 35,50 114,50 110,25<br />
41,00 35,00 38,00 114,00 33,25 38,75 114,00 108,75<br />
236
Lampiran 18<br />
Hasil Uji Normalitas Data Skor Kelelahan Sebelum Aktivitas Kerja pada Periode<br />
Tanpa Intervensi dan Periode dengan Intervensi.<br />
Tests of Normality<br />
Kolmogorov-Smirnov<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
I_TIN<br />
,213 18 ,030 ,922 18 ,140<br />
II_TIN<br />
,144 18 ,200* ,935 18 ,236<br />
III_TIN<br />
,132 18 ,200* ,982 18 ,968<br />
TOT_TIN ,180 18 ,129 ,933 18 ,220<br />
I_DIN<br />
,200 18 ,056 ,881 18 ,027<br />
II_DIN<br />
,140 18 ,200* ,963 18 ,668<br />
III_DIN<br />
,180 18 ,129 ,933 18 ,220<br />
TOT_DIN ,174 18 ,156 ,842 18 ,006<br />
a<br />
Shapiro-Wilk<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 19<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Kelelahan Kategori Aktivitas Melemah dan Skor<br />
Total Sebelum Aktivitas Kerja Periode Tanpa Intervensi dan Periode Dengan<br />
Intervensi.<br />
(a) Uji-t<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
(b) Uji-Wilcoxon<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Test Statistics b<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
-3,730a -1,785a I_DIN - I_TIN<br />
TOT_DIN -<br />
TOT_TIN<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
,000 ,074<br />
a. Based on negative ranks.<br />
b.<br />
Wilcoxon Signed Ranks Test<br />
237<br />
Pair 1 Pair 2<br />
III_TIN -<br />
II_TIN - II_DIN III_DIN<br />
2,05556 -40,05556<br />
,90568 1,37080<br />
,21347 ,32310<br />
1,60517 -40,73724<br />
2,50594 -39,37387<br />
9,629 -123,973<br />
17 17<br />
,000 ,000
Lampiran 20<br />
Hasil Uji Normalitas Data Selisih Skor Kelelahan Setelah dan Sebelum Aktivitas<br />
Kerja pada Periode Tanpa Intervensi dan Periode dengan Intervensi.<br />
I_I_TI<br />
I_II_TI<br />
I_III_TI<br />
I_I_DI<br />
I_II_DI<br />
I_III_DI<br />
I_T_TI<br />
I_T_DI<br />
II_I_TI<br />
II_IITI<br />
II_III_TI<br />
II_I_DI<br />
II_II_DI<br />
II_III_DI<br />
II_T_TI<br />
II_T_DI<br />
III_I_TI<br />
III_II_TI<br />
III_III_TI<br />
III_I_DI<br />
III_II_DI<br />
III_III_DI<br />
III_T_TI<br />
III_T_DI<br />
IV_I_TI<br />
IV_IITI<br />
IV_III_TI<br />
IV_I_DI<br />
IV_II_DI<br />
IV_III_DI<br />
IV_T_TI<br />
IV_T_DI<br />
R_I_TI<br />
R_II_TI<br />
R_III_TI<br />
R_I_DI<br />
R_II_DI<br />
R_III_DI<br />
R_T_TI<br />
R_T_DI<br />
Tests of Normality<br />
Kolmogorov-Smirnov<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
,184 18 ,108 ,889 18 ,038<br />
,223 18 ,018 ,912 18 ,095<br />
,224 18 ,017 ,938 18 ,268<br />
,135 18 ,200* ,957 18 ,545<br />
,170 18 ,183 ,919 18 ,123<br />
,158 18 ,200* ,934 18 ,227<br />
,240 18 ,007 ,929 18 ,184<br />
,125 18 ,200* ,954 18 ,491<br />
,164 18 ,200* ,904 18 ,068<br />
,151 18 ,200* ,934 18 ,232<br />
,167 18 ,200* ,920 18 ,131<br />
,283 18 ,000 ,861 18 ,013<br />
,176 18 ,147 ,930 18 ,197<br />
,125 18 ,200* ,958 18 ,562<br />
,147 18 ,200* ,957 18 ,537<br />
a<br />
Shapiro-Wilk<br />
,170 18 ,181 ,930 18 ,197<br />
,253 18 ,004 ,914 18 ,100<br />
,164 18 ,200* ,900 18 ,057<br />
,167 18 ,197 ,951 18 ,434<br />
,167 18 ,198 ,948 18 ,400<br />
,156 18 ,200* ,939 18 ,280<br />
,121 18 ,200* ,974 18 ,873<br />
,107 18 ,200* ,955 18 ,504<br />
,130 18 ,200* ,968 18 ,758<br />
,155 18 ,200* ,967 18 ,747<br />
,123 18 ,200* ,970 18 ,805<br />
,197 18 ,063 ,939 18 ,283<br />
,199 18 ,057 ,958 18 ,557<br />
,137 18 ,200* ,955 18 ,501<br />
,122 18 ,200* ,968 18 ,753<br />
,111 18 ,200* ,956 18 ,521<br />
,145 18 ,200* ,942 18 ,313<br />
,201 18 ,053 ,934 18 ,231<br />
,127 18 ,200* ,980 18 ,946<br />
,134 18 ,200* ,956 18 ,518<br />
,096 18 ,200* ,983 18 ,974<br />
,134 18 ,200* ,946 18 ,361<br />
,115 18 ,200* ,961 18 ,623<br />
,134 18 ,200* ,949 18 ,405<br />
,136 18 ,200* ,946 18 ,365<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
a.<br />
Lilliefors Significance Correction<br />
238
Lampiran 21<br />
Hasil Uji Beda Rerata Selisih Skor Kelelahan Semua Kategori Periode Tanpa<br />
Intervensi dan Periode Dengan Intervensi.<br />
(a) Periode I<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
(b) Periode II<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Pair 1<br />
I_I_TI - I_<br />
I_DI<br />
Pair 2<br />
I_II_TI - I_<br />
II_DI<br />
239<br />
Pair 3<br />
I_III_TI - I_<br />
III_DI<br />
Pair 4<br />
I_T_TI - I_<br />
T_DI<br />
6,056 ,944 4,722 11,722<br />
4,221 4,881 5,421 11,380<br />
,995 1,150 1,278 2,682<br />
3,956 -1,483 2,026 6,063<br />
8,155 3,372 7,418 17,381<br />
6,086 ,821 3,696 4,370<br />
17 17 17 17<br />
,000 ,423 ,002 ,000<br />
Pair 1<br />
II_I_TI - II_<br />
I_DI<br />
Pair 2<br />
II_IITI - II_<br />
II_DI<br />
Pair 3<br />
II_III_TI - II_<br />
III_DI<br />
Pair 4<br />
II_T_TI - II_<br />
T_DI<br />
4,611 -1,111 1,167 4,667<br />
5,315 3,027 2,407 7,029<br />
1,253 ,713 ,567 1,657<br />
1,968 -2,616 -,030 1,171<br />
7,254 ,394 2,364 8,162<br />
3,681 -1,557 2,056 2,817<br />
17 17 17 17<br />
,002 ,138 ,055 ,012
(c) Periode III<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
(d) Periode IV<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Pair 1<br />
III_I_TI - III_<br />
I_DI<br />
Pair 2<br />
III_II_TI - III_<br />
II_DI<br />
240<br />
Pair 3<br />
III_III_TI -<br />
III_III_DI<br />
Pair 4<br />
III_T_TI -<br />
III_T_DI<br />
2,833 3,778 4,000 10,611<br />
4,706 5,917 4,243 7,326<br />
1,109 1,395 1,000 1,727<br />
,493 ,836 1,890 6,968<br />
5,174 6,720 6,110 14,254<br />
2,554 2,709 4,000 6,146<br />
17 17 17 17<br />
,021 ,015 ,001 ,000<br />
Pair 1<br />
IV_I_TI - IV_<br />
I_DI<br />
Pair 2<br />
IV_IITI - IV_<br />
II_DI<br />
Pair 3<br />
IV_III_TI -<br />
IV_III_DI<br />
Pair 4<br />
IV_T_TI -<br />
IV_T_DI<br />
4,667 3,667 2,556 10,889<br />
6,212 4,640 4,422 9,773<br />
1,464 1,094 1,042 2,304<br />
1,578 1,359 ,356 6,029<br />
7,756 5,974 4,755 15,749<br />
3,187 3,353 2,452 4,727<br />
17 17 17 17<br />
,005 ,004 ,025 ,000
(e) Rerata empat periode<br />
Paired DifferencesMean<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interva<br />
of the Difference<br />
Paired Samples Test<br />
Lower<br />
Upper<br />
Pair 1<br />
R_I_TI - R_<br />
I_DI<br />
Pair 2<br />
R_II_TI - R_<br />
II_DI<br />
Pair 3<br />
R_III_TI -<br />
R_III_DI<br />
241<br />
Pair 4<br />
R_T_TI -<br />
R_T_DI<br />
-35,87500 -2,65278 6,58333 -31,94444<br />
2,32197 2,11462 1,87671 2,35702<br />
,54729 ,49842 ,44235 ,55556<br />
-37,02969 -3,70435 5,65006 -33,11656<br />
-34,72031 -1,60120 7,51660 -30,77232<br />
-65,550 -5,322 14,883 -57,500<br />
17 17 17 17<br />
,000 ,000 ,000 ,000
Lampiran 22<br />
Data Hasil Pengamatan Skor Keluhan Muskuloskeletal Nelayan Pukat Cincin di Perairan Amurang Kecamatan Minahasa Selatan<br />
Periode Tanpa Intervensi (TI) Periode Dengan Intervensi (DI)<br />
I II III IV I II III IV<br />
Rerata Seb Rerata Ses<br />
Seb Ses Seb Ses Seb Ses Seb Ses<br />
Seb Ses Seb Ses Seb Ses Seb Ses<br />
242<br />
Rerata Seb Rerata Ses<br />
43 63 49 83 42 84 45 88 44,75 79,50 28 68 44 66 28 68 28 75 32,00 69,25<br />
45 87 42 87 41 87 45 87 43,25 87,00 56 85 45 89 56 92 43 92 50,00 89,50<br />
41 84 42 90 43 93 47 92 43,25 89,75 40 80 40 84 42 85 40 87 40,50 84,00<br />
42 98 41 98 41 98 42 102 41,50 99,00 40 45 41 100 40 94 40 101 40,25 85,00<br />
45 63 43 86 42 85 42 84 43,00 79,50 42 73 46 80 41 87 42 43 42,75 70,75<br />
39 69 41 85 41 85 39 82 40,00 80,25 43 71 41 82 41 91 45 42 42,50 71,50<br />
45 79 42 93 43 92 42 94 43,00 89,50 42 71 41 86 42 70 41 41 41,50 67,00<br />
44 80 41 94 39 93 42 90 41,50 89,25 42 42 42 79 42 91 42 42 42,00 63,50<br />
42 79 43 103 42 91 42 95 42,25 92,00 43 73 44 101 41 73 43 43 42,75 72,50<br />
43 104 43 96 42 96 43 100 42,75 99,00 42 98 44 98 42 100 42 88 42,50 96,00<br />
41 51 41 87 41 92 44 94 41,75 81,00 43 54 42 60 42 96 44 89 42,75 74,75<br />
42 82 42 81 42 82 43 82 42,25 81,75 42 73 45 80 44 92 42 88 43,25 83,25<br />
42 82 45 93 41 97 43 92 42,75 91,00 38 80 43 95 45 80 43 93 42,25 87,00<br />
45 84 42 84 42 86 43 84 43,00 84,50 35 35 42 77 43 58 42 90 40,50 65,00<br />
42 105 42 101 41 98 42 105 41,75 102,25 56 56 45 90 48 49 45 94 48,50 72,25<br />
44 97 42 97 42 98 43 97 42,75 97,25 42 42 42 77 41 64 42 91 41,75 68,50<br />
44 98 41 98 42 96 42 98 42,25 97,50 51 51 44 74 44 72 41 103 45,00 75,00<br />
42 39 42 96 44 86 43 89 42,75 77,50 28 56 42 95 42 87 39 93 37,75 82,75
Lampiran 23<br />
Hasil Uji Normalitas Data Skor Keluhan Muskuloskeletal Sebelum Aktivitas<br />
Kerja pada Periode Tanpa Intervensi dan Periode dengan Intervensi.<br />
I_TIN<br />
III_TIN<br />
V_TIN<br />
VII_TIN<br />
IX_TIN<br />
I_DIN<br />
III_DIN<br />
V_DIN<br />
VII_DIN<br />
IX_DIN<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
Tests of Normality<br />
Statistic df Sig. Statistic df Sig.<br />
,189 18 ,088 ,912 18 ,094<br />
,314 18 ,000 ,665 18 ,000<br />
,231 18 ,012 ,886 18 ,033<br />
,251 18 ,004 ,875 18 ,022<br />
,166 18 ,200* ,930 18 ,192<br />
,271 18 ,001 ,877 18 ,023<br />
,207 18 ,040 ,936 18 ,243<br />
,278 18 ,001 ,770 18 ,001<br />
,248 18 ,005 ,667 18 ,000<br />
,218 18 ,023 ,881 18 ,027<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 24<br />
243<br />
Shapiro-Wilk<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Keluhan Muskuloskeletal Sebelum Aktivitas Kerja<br />
Periode Tanpa Intervensi dan Periode Dengan Intervensi.<br />
Test Statistics c<br />
-,807a -1,168b -,840b -1,687a -,240a III_DIN -<br />
VII_DIN - IX_DIN -<br />
I_DIN - I_TIN III_TIN V_DIN - V_TIN VII_TIN IX_TIN<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed) ,420 ,243 ,401 ,092 ,810<br />
a. Based on positive ranks.<br />
b. Based on negative ranks.<br />
c.<br />
Wilcoxon Signed Ranks Test
Lampiran 25<br />
Hasil Uji Normalitas Data Skor Keluhan Muskuloskeletal Setelah Aktivitas Kerja<br />
pada Periode Tanpa Intervensi dan Periode dengan Intervensi.<br />
Tests of Normality<br />
Statistic df Sig. Statistic<br />
Shapiro-Wilk<br />
df Sig.<br />
II_TIN ,195 18 ,069 ,939 18 ,279<br />
IV_TIN ,154 18 ,200* ,954 18 ,490<br />
VI_TIN ,159 18 ,200* ,905 18 ,071<br />
VIII_TIN ,100 18 ,200* ,968 18 ,761<br />
X_TIN ,146 18 ,200* ,931 18 ,203<br />
II_DIN ,157 18 ,200* ,961 18 ,618<br />
IV_DIN ,109 18 ,200* ,964 18 ,681<br />
VI_DIN ,178 18 ,138 ,928 18 ,177<br />
VIII_DIN ,325 18 ,000 ,755 18 ,000<br />
X_DIN ,176 18 ,145 ,939 18 ,276<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 26<br />
244<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Keluhan Muskuloskeletal Setelah Aktivitas Kerja<br />
pada Periode Tanpa Intervensi dan Periode Dengan Intervensi.<br />
(a) Dengan uji-t<br />
Paired DifferencMean<br />
Std. Deviation<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence InteLower<br />
of the Difference Upper<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Paired Samples Test<br />
Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4<br />
IV_TIN - VI_TIN -<br />
I_TIN - II_DINIV_DIN<br />
VI_DINX_TIN<br />
- X_DIN<br />
16,167 7,722 10,556 12,222<br />
24,558 9,291 16,354 11,011<br />
5,788 2,190 3,855 2,595<br />
3,954 3,102 2,423 6,747<br />
28,379 12,343 18,688 17,698<br />
2,793 3,526 2,738 4,709<br />
17 17 17 17<br />
,012 ,003 ,014 ,000
Z<br />
(b) Dengan uji-Wilcoxon<br />
Test Statistics b<br />
VIII_DIN -<br />
VIII_TIN<br />
-2,269 a<br />
Asymp. Sig. (2-tailed) ,023<br />
a. Based on positive ranks.<br />
b. Wilcoxon Signed Ranks Test<br />
Lampiran 27<br />
Data Hasil Pengamatan Skor Kesejahteraan Nelayan Pukat Cincin di Perairan<br />
Amurang Kecamatan Minahasa Selatan<br />
245<br />
Periode Pengamatan<br />
I II III IV V<br />
TI DI TI DI TI DI TI DI TI DI<br />
56 54 48 47 48 54 45 52 49,25 51,75<br />
56 55 49 51 50 52 47 52 50,50 52,50<br />
54 54 52 50 47 49 47 51 50,00 51,00<br />
56 55 48 52 52 50 53 52 52,25 52,25<br />
52 54 49 50 49 52 44 48 48,50 51,00<br />
52 56 48 51 51 52 47 49 49,50 52,00<br />
42 49 46 49 53 51 45 48 46,50 49,25<br />
47 51 46 48 49 50 50 48 48,00 49,25<br />
53 50 47 48 52 51 52 53 51,00 50,50<br />
58 55 46 50 48 51 53 54 51,25 52,50<br />
46 55 51 52 53 52 51 52 50,25 52,75<br />
45 48 47 51 50 53 49 48 47,75 50,00<br />
47 50 48 51 38 51 49 47 45,50 49,75<br />
51 52 49 51 42 51 45 46 46,75 50,00<br />
50 56 46 52 45 50 27 49 42,00 51,75<br />
55 54 52 51 50 53 36 52 48,25 52,50<br />
49 55 32 52 36 55 25 54 35,50 54,00<br />
46 56 51 53 56 55 26 52 44,75 54,00
Lampiran 28<br />
Hasil Uji Normalitas Data Skor Kesejahteraan pada Periode Tanpa Intervensi dan<br />
Periode dengan Intervensi.<br />
Tests of Normality<br />
Statistic df Sig. Statistic<br />
Shapiro-Wilk<br />
df Sig.<br />
I_TIN<br />
,310 18 ,000 ,688 18 ,000<br />
I_DIN<br />
,232 18 ,011 ,915 18 ,106<br />
II_TIN ,201 18 ,053 ,897 18 ,051<br />
II_DIN ,176 18 ,144 ,934 18 ,230<br />
III_TIN ,280 18 ,001 ,797 18 ,001<br />
III_DIN ,240 18 ,007 ,904 18 ,068<br />
IV_TIN ,131 18 ,200* ,958 18 ,564<br />
IV_DIN ,277 18 ,001 ,855 18 ,010<br />
I_IV_TIN ,178 18 ,137 ,840 18 ,006<br />
I_IV_DIN ,126 18 ,200* ,946 18 ,359<br />
*. This is a lower bound of the true significance.<br />
Kolmogorov-Smirnov a<br />
a. Lilliefors Significance Correction<br />
Lampiran 29<br />
246<br />
Hasil Uji Beda Rerata Skor Kesejahteraan Periode Tanpa Intervensi dan Periode<br />
Dengan Intervensi.<br />
(a) Uji-Wilcoxon<br />
Test Statistics b<br />
-3,132a -2,735a -2,208a -3,580a III_DIN - IV_DIN - I_IV_DIN -<br />
I_DIN - I_TIN III_TIN IV_TIN I_IV_TIN<br />
Z<br />
Asymp. Sig. (2-tailed)<br />
,002 ,006 ,027 ,000<br />
a. Based on negative ranks.<br />
b.<br />
Wilcoxon Signed Ranks Test
(b) Uji-t<br />
Paired Differences<br />
t<br />
df<br />
Sig. (2-tailed)<br />
Mean<br />
Std. Deviation<br />
Paired Samples Test<br />
Std. Error Mean<br />
95% Confidence Interval<br />
of the Difference<br />
Lower<br />
Upper<br />
Pair 1<br />
II_TIN - II_DIN<br />
-3,500<br />
5,469<br />
1,289<br />
-6,220<br />
-,780<br />
-2,715<br />
17<br />
,015<br />
247
Lampiran 30<br />
ALAT-ALAT UKUR PENELITIAN DAN<br />
Gambar 1<br />
Sound Level Meter<br />
Gambar 4<br />
Stop Watch<br />
Gambar 7<br />
Jacket<br />
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)<br />
Gambar 2<br />
Alat ukur mikroklimat<br />
Gambar 5<br />
Anthropometer<br />
Gambar 8<br />
Sarung tangan<br />
Gambar 10<br />
Papan<br />
248<br />
Gambar 3<br />
Timbangan badan<br />
Gambar 6<br />
Digital Camera<br />
Gambar 9<br />
Topi
Lampiran 31<br />
FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN SEBELUM DAN<br />
SESUDAH INTERVENSI ERGONOMI<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
KM Cristos sebagai kapal penangkap<br />
pukat cincin untuk penelitian<br />
Setelah tiba di lokasi penelitian tim<br />
peneliti memberikan arahan dan<br />
penjelasan<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Subjek sedang memikul es balok ke<br />
bawa ke KM Cristos<br />
249<br />
Subjek sedang mendengar arahan dan<br />
penjelasan dari tim peneliti<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Es balok akan diisi kedalam bak<br />
penampung KM Cristos<br />
Subjek menerima dan mengisi<br />
kuesioner NBM, 30 items of rating<br />
scales
Sebelum Intervensi Dengan Intervansi<br />
Perjalanan menuju ke lokasi<br />
penelitian dengan menggunakan<br />
4 motor temple Yamaha<br />
250<br />
Subjek menerima dan mengisi<br />
kuesioner kesejahteraan nelayan oleh<br />
peneliti<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Salah satu rumpon milik KM Cristos Subjek menerima penjelasan tentang<br />
cara-cara memasukan tali cincin ke<br />
katrol<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Tiba di lokasi penelitian seorang<br />
subjek sedang mengikat tali kapal di<br />
rumpon<br />
Subjek menerima penjelasan tentang<br />
cara-cara penarikan tali pelampung
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Tim peneliti sedang mengatur pola<br />
makan dan minum subjek<br />
Aktifitas penangkapan penawuran<br />
jaring oleh subjek<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Pengaturan pembagian makanan dan<br />
minuman<br />
Aktifitas penangkapan penawuran<br />
tali cincin<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Nelayan sedang menikmati makanan<br />
dan minuman<br />
Proses penawuran isi perut jaring<br />
251
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
2 orang subjek sedang menikmati<br />
makanan dan minuman yang diatur<br />
oleh tim peneliti<br />
Aktifitas penangkapan penawuran<br />
tali cincin<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Subjek yang lain sedang menjurai<br />
jaring yang lobang<br />
Aktifitas penangkapan penawuran<br />
tali pelampung oleh subjek<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Subjek yang lain sedang asik<br />
mengkail ikan tenggiri<br />
di dekat rumpon<br />
Proses penangkapan kapal<br />
mengelilingi rumpon<br />
252
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Peneliti sedang memeriksa<br />
persediaan air dan alat tangkap pukat<br />
cincin<br />
Posisi rumpon di tengah-tengah<br />
lingkaran pukat cincin<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Persiapan penangkapan dengan alat<br />
pukat cincin<br />
Penarikan tali pelampung dengan<br />
sikap kerja duduk<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Proses penangkapan penawuran<br />
jaring<br />
Penarikan tali cincin dengan<br />
menggunakan katrol<br />
253
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Proses penangkapan penawuran tali<br />
timah dan cincin<br />
Penggunaan alat kerja katrol<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Proses penangkapan penawuran tali<br />
pelampung<br />
Posisi penariksn pukat cincin sedang<br />
merapat<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Proses penarikan isi perut jaring Hasil penangkapan pukat cincin<br />
dengan intervensi ergonomi<br />
254
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Proses penarikan tali pelampung Subjek sedang mengangkat hasil<br />
tangkapan<br />
Sebelum Intervensi Sebelum Intervensi<br />
Proses penarikan tali cincin dengan<br />
sikap kerja berdiri kaki sebagai<br />
bantalan penahan<br />
Penarikan pukat cincin sudah dekat<br />
Sebelum Intervensi Sebelum Intervensi<br />
Penarikan pukat cincin sudah dekat<br />
dan hasil tangkapan sudah kelihatan<br />
Subjek sedang mengangkat hasil<br />
tanggapan dari jaring<br />
255
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Hasil tangkapan akan dimasukan<br />
kedalam bak penampung<br />
Mengangkat hasil tangkapan<br />
dari jaring<br />
Sebelum Intervensi Sebelum Intervensi<br />
Tiba di pelabuhan pendaratan ikan<br />
nelayan sedang mengangkat hasil<br />
tangkapan dari dalam bak<br />
Selesai penangkapan nelayan<br />
mengangkat daun lontar sebagai<br />
tempat berkumpulnya ikan<br />
Sebelum Intervensi Dengan Intervensi<br />
Kapal penangkap kembali pulang<br />
menggunakan 4 motor pendorong<br />
Kapal penangkap kembali pulang<br />
menuju pelabuhan<br />
pendaratan ikan<br />
256