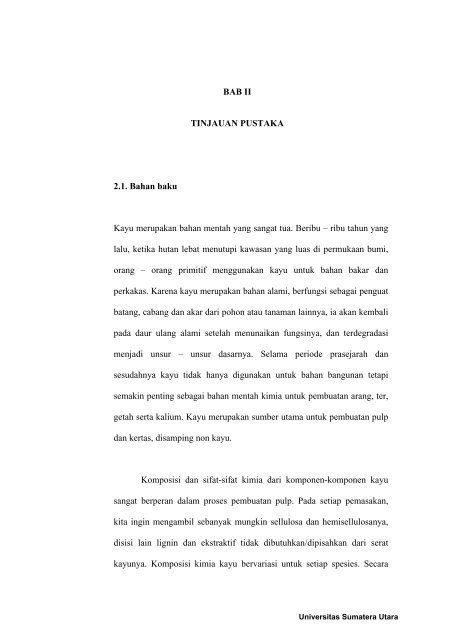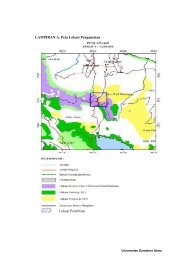Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...
Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...
Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.1. Bahan baku<br />
BAB <strong>II</strong><br />
TINJAUAN PUSTAKA<br />
Kayu merupakan bahan mentah yang sangat tua. Beribu – ribu tahun yang<br />
lalu, ketika hutan lebat menutupi kawasan yang luas di permukaan bumi,<br />
orang – orang primitif menggunakan kayu untuk bahan bakar dan<br />
perkakas. Karena kayu merupakan bahan alami, berfungsi sebagai penguat<br />
batang, cabang dan akar dari pohon atau tanaman lainnya, ia akan kembali<br />
pada daur ulang alami setelah menunaikan fungsinya, dan terdegradasi<br />
menjadi unsur – unsur dasarnya. Selama periode prasejarah dan<br />
sesudahnya kayu tidak hanya digunakan untuk bahan bangunan tetapi<br />
semakin penting sebagai bahan mentah kimia untuk pembuatan arang, ter,<br />
getah serta kalium. Kayu merupakan sumber utama untuk pembuatan pulp<br />
dan kertas, disamping non kayu.<br />
Komposisi dan sifat-sifat kimia dari komponen-komponen kayu<br />
sangat berperan dalam proses pembuatan pulp. Pada setiap pemasakan,<br />
kita ingin mengambil sebanyak mungkin sellulosa dan hemisellulosanya,<br />
disisi lain lignin dan ekstraktif tidak dibutuhkan/dipisahkan dari serat<br />
kayunya. Komposisi kimia kayu bervariasi untuk setiap spesies. Secara<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
umum, hardwood atau kayu jarum (Gymnospermae) mengandung lebih<br />
banyak sellulosa, hemisellulosa dan ekstraktif dibanding dengan softwood<br />
atau kayu daun (Angiospermae).<br />
Kayu tersusun atas sel-sel yang memanjang, kebanyakan<br />
diantaranya berorientasi dalam arah longitudinal batang. Mereka<br />
dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui pintu-pintu, yang<br />
dinyatakan sebagai noktah. Sel-sel ini, yang bentuknya bervariasi<br />
tergantung pada fungsinya, memberikan kekuatan mekanik yang<br />
diperlukan oleh pohon, dan juga melakukan fungsi pengangkut cairan<br />
maupun penyimpan persediaan cadangan makanan. Struktur makroskopis<br />
kayu seperti terlihat dengan mata. Empelur yang terletak dipusat dapat<br />
dilihat sebagai garis gelap ditengah batang atau cabang. (Hardjono, 1995).<br />
Kayu lunak (softwood) yang homogen , berserat lurus dan ringan<br />
lebih disukai untuk dijadikan kayu – kayu konstruksi kayu lapis. Xylem<br />
kayu lunak (softwood) sangat sederhana. Kebanyakan spesies memiliki<br />
tidak lebih dari empat atau lima macam sel yang berbeda, dan hanya satu<br />
atau dua tipe sel banyak terdapat. Karena kesederhanaan dan keseragaman<br />
struktur inilah, kayu lunak (softwood) cenderung serupa dalam<br />
kenampakannya. Dilain pihak, kayu keras (softwood) tersusun atas jenis –<br />
jenis sel yang sangat berbeda dengan variasi proporsi yang luas dan<br />
karenanya sering menjadi unik bahkan memiliki gambaran kayu yang<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
sangat indah. Karena gambaran unik yang banyak dimiliki oleh spesies –<br />
spesies kayu keras (hardwood), maka kayu – kayu tersebut banyak<br />
digunakan untuk perabot rumah tangga, panil, dan tujuan – tujuan<br />
dekoratif yang lain. (Haygreen, 1996).<br />
2.1.1. Selulosa<br />
Selulosa merupakan bagian utama yang membentuk dinding sel daripada<br />
kayu. Merupakan polimerisasi yang sangat kompleks dari gugus<br />
karbohidrat yang mempunyai persen komposisi yang mirip dengan<br />
“starch” yaitu glukosa yang terhidrolisa oleh asam.<br />
Sifat – sifat polimer selulosa<br />
Sifat-sifat polimer selulosa biasanya dipelajari dalam keadaan larutan,<br />
menggunakan pelarut seperti CED atau Kadoksen. Berdasarkan sifat-sifat<br />
larutan kesimpulan dapat diperoleh mengenai berat molekul rata-rata,<br />
polidisperitas, dan konformasi polimer. Pengukuran-pengukuran berat<br />
molekul menunjukkan bahwa selulosa kapas dalam keadaan asalnya<br />
mengandung kira-kira 15000 dan selulosa kayu mengandung kira-kira<br />
10000 sisa glukosa. (Hardjono, 1995).<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
2.1.2. Hemiselulosa<br />
Hemisellulosa juga merupakan polimer-polimer gula. Berbeda dengan<br />
glukosa yang terdiri hanya dari polimer glukosa, hemisellulosa merupakan<br />
polimer dari lima bentuk gula yang berlainan yaitu : glukosa, mannosa,<br />
galaktosa, xylosa dan arabinosa. Rantai hemiselulosa lebih pendek<br />
dibandingkan dengan rantai sellulosa, karena hemiselulosa mempunyai<br />
derajat polimerisasi yang lebih rendah. Molekul hemisellulosa terdiri dari<br />
300 unit gugus gula. Berbeda dengan sellulosa, polimer hemisellulosa<br />
berbentuk tidak lurus, tapi merupakan polimer-polimer yang berarti<br />
hemisellulosa tidak akan dapat membentuk struktur Kristal dan serat<br />
mikro seperti halnya selulosa. Pada proses pembuatan pulp hemisellulosa<br />
bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan sellulosa.<br />
2.1.3. Lignin<br />
Lignin adalah polimer yang sangat kompleks, juga merupakan komponen<br />
utama penyusun kayu dengan kandungan antara 17-32% berat kayu<br />
kering. Adanya lignin didalam pulp menyebabkan warna pada pembuatan<br />
kertas untuk maksud tertentu seperti kertas cetak. Lignin perlu dipisahkan<br />
dari pulp melalui proses pemutihan. Struktur molekul lignin sangat<br />
berbeda bila dibandingkan dengan polisakarida karena terdiri atas sistem<br />
aromatik yang tersusun atas unit-unit fenil propana. Dalam kayu lunak<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
kandungan lignin lebih banyak bila dibandingkan dalam kayu keras. Sifat<br />
kimia lignin sangat rumit oleh karena itu tidak banyak ahli yang<br />
menjelaskan tentang lignin.<br />
Lignin merupakan senyawa yang tidak diharapkan dalam<br />
pembuatan pulp karena akan membuat lembaran kaku dan mengurangi<br />
aktivitas ikatan permukaan antara serat dan akan menghalangi<br />
pengembangan serta sehingga menurunkan kualitas pulp yang dihasilkan.<br />
Sifat-sifat lignin secara umum antara lain tidak larut dalam air, berat<br />
molekul berkisar antara 2000 - 15000, molekul lignin mengandung gugus<br />
hidroksil, metoksil dan karboksil dan bila didegradasi oleh basa akan<br />
membentuk turunan benzene. (Fessenden, 1992).<br />
Lignin merupakan zat yang tidak bersama-sama dengan sellulosa<br />
membentuk dinding sel dari pohon kayu. Ia berfungsi sebagai bahan<br />
perekat atau semen antara sel-sel selulosa yang membuat kayu menjadi<br />
kuat. Lignin merupakan polimer tiga dimensi yang bercabang banyak.<br />
Molekul utama pembentuk lignin adalah phenyl propane. Satu molekul<br />
Lignin dengan derajat polimerisasi yang tinggi merupakan molekul yang<br />
besar, karena ukurannya dan struktur tiga dimensinya. lignin didalam kayu<br />
berfungsi sebagai lem atau semen. Lapisan (lamella) tengah, dengan<br />
kandungan utamanya adalah lignin, mengikat sel-sel itu dan sehingga<br />
terbentuk struktur kayu. Dinding sel juga mengandung lignin. Pada<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
dinding sel, lignin bersama dengan hemisellulosa,membentuk semen<br />
(matriks) dimana tersusunlah sellulosa yang berupa “mikrofibrils”.<br />
Ada beberapa test prosedur yang sekarang digunakan untuk<br />
menentukan lignin, seperti:<br />
1. Lignin Klason : mengukur lignin dalam kayu secara langsung<br />
2. Kappa Number : Jumlah konsumsi permanganat dalam sampel<br />
pulp yang mengandung lignin yang belum bereaksi<br />
3. Hypo test : Jumlah konsumsi hypo dalam sample pulp yang<br />
mengandung lignin yang belum bereaksi<br />
4. Chlorine Number : Jumlah konsumsi klorin dalam pulp yang<br />
mengandung lignin yang belum bereaksi<br />
5. Nu-Number : Test absorbsi spektrofotometer lignin yang terlarut<br />
dalam asam dengan panjang gelombang 425 nm<br />
6. Pulp Permittivity : Dielectric strength atau permititivitas pulp sheet<br />
yang berhubungan dengan kandungan lignin dalam sampel.<br />
7. Spectrophotometric Methods : Absorpsi sinar UV pada sampel<br />
yang mengandung lignin. (Chemistry.org).<br />
2.1.4. Ekstraktif<br />
Ekstraktif adalah senyawa kimia dengan BM rendah yang dapat larut<br />
dalam air dan pelarut organik. Pada umumnya kadar ekstraktif yang<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
terkandung dalam bahan baku nonwood lebih tinggi daripada kayu daun<br />
dan kayu jarum. Zat ekstraktif terdiri dari senyawa yang mudah menguap<br />
seperti terpentin, resin, asam lemak, fenol, karbohidrat dengan BM rendah<br />
dan juga pektin. Zat ekstraktif yang larut dalam air meliputi gula, pektin,<br />
garam-garam organik dan zat warna. Sedangkan ekstraktif yang larut<br />
dalam pelarut organik yaitu tannin , asam lemak, resin, dan terpen. Pelarut<br />
organik yang biasa digunakan yaitu; petroleum eter, metanol, alkohol<br />
benzen, dan etanol benzen.<br />
Ekstraktif dapat mengkonsumsi bahan kimia banyak juga dapat<br />
menghambat proses penetrasi larutan kemasan. Pada pembuatan kertas<br />
akan timbul masalah yang biasa disebut pitch trouble, hal ini disebabkan<br />
karena pitch yang dilepaskan pada waktu proses penggilingan akan<br />
cenderung terkumpul sebagai partikel suspensi koloidal sehingga akan<br />
menyumbat kawat kasa pada mesin kertas atau terkumpul pada felt serta<br />
melekat pada mesin sebagai gumpalan selap. Dengan adanya hal ini, akan<br />
menyebabkan kertas berlubang transparan (bernoda) dan kotor.Kayu<br />
biasanya mengandung berbagai zat-zat dalam jumlah yang tidak banyak<br />
yang disebut dengan istilah “extractive”. Zat-zat ini dapat diambil /<br />
dipisahkan dari kayu apakah dengan memakai pelarut air maupun pelarut<br />
organik seperti eter atau alkohol.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Asam-asam lemak, asam-asam resin, lilin, terpentin dan gugus<br />
phenol adalah merupakan beberapa grup yang juga merupakan ekstraktif.<br />
Kebanyakan dari ekstraktif itu terpisahkan dalam proses pembuatan pulp<br />
dengan cara Kraft Pulping. Minyak mentah terpentin dapat diperoleh dari<br />
digester pada waktu mengeluarkan gas. Lemak-lemak, asam-asam lemak<br />
akan membentuk sabun (soap) pada proses “Kraft” dan terlarut dalam<br />
larutan pemasak. Soap ini selanjutnya akan dipisahkan dari black liquor<br />
dan daur ulang sebagai “tall oil”. Beberapa / sebagian kecil dari ekstraktif<br />
yang terlarut akan menyebabkan timbulnya getah (“pitch”) dalam<br />
pembuatan pulp secara kraft dan pada pembuatan kertas. Bentuk ini<br />
merupakan gumpalan yang mengotori peralatan seperti halnya screen dan<br />
wire.<br />
2.1.5. Mineral<br />
Mineral atau senyawa anorganik didalam kayu mempunyai kadar kurang<br />
dari 1%. Didalam pulp senyawa ini kadang-kadang masih terkandung<br />
yang berasal dari bahan baku, bahan kimia, air dan peralatan yang<br />
digunakan. Untuk mengetahui kadar mineral dalam air dilakukan<br />
pengabuan dimana abu tersebut terdiri dari garam-garam karbonat, fosfat,<br />
oksalat, sulfat dan sisanya merupakan senyawa logam seperti besi,<br />
kalsium, tembaga dan mangan.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Abu yang tidak larut dalam HCl (asam klorida) 6M biasanya<br />
mengandung banyak silikat terutama dalam bahan baku bukan kayu.<br />
Adanya abu dalam pulp akan menggangu pada hasil atau kualitas<br />
kertasnya, sedangkan silika yang tinggi akan mengakibatkan pengerakan<br />
atau korosi dalam digester, alat-alat pipa recovery dan dapat menumpulkan<br />
pisau pemotong.<br />
2.2. Proses Pembuatan Pulp<br />
Pulp adalah produk utama kayu, terutama digunakan untuk pembuatan<br />
kertas, tetapi juga diproses menjadi berbagai turunan selulosa, seperti<br />
sutera rayon dan selofan. Tujuan utama pembuatan pulp kayu adalah untuk<br />
melepaskan serat – serat yang dapat dikerjakan secara kimia atau secara<br />
mekanik atau dengan kombinasi kedua perlakuan tersebut. Pemisahan<br />
serat sellulosa dari bahan-bahan yang bukan serat didalam kayu dapat<br />
dilakukan dengan berbagai macam cara/proses, yaitu :<br />
a. Proses mekanik<br />
b. Proses semi kimia<br />
c. Proses kimia<br />
Dalam proses pembuatan pulp secara mekanik, pemisahan serat<br />
dilakukan dengan cara menggunakan tenaga mekanik. Proses ini dilakukan<br />
dengan menggerinda kayunya menjadi serat pulp dan menghasilkan<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
andemen sebesar 90-95 %, tetapi menyebabkan kerusakan pada serat.<br />
Penggunaan pulp yang dihasilkan pada proses mekanik ini nilainya kecil<br />
sekali, juga pulp itu masih mengandung banyak lignin, dan serat-serat nya<br />
tidak murni sebagai serat.<br />
Proses semi kimia meliputi pengolahan secara kimia yang diikuti<br />
dengan perbaikan secara mekanik dan beroperasi pada randemen yang<br />
tingginya dibawah proses mekanik. Biasanya bahan kimia yang digunakan<br />
pada proses ini adalah sodium sulphite (Na2S). Pada proses kimia, bahan-<br />
bahan yang terdapat ditengah lapisan kayu akan dilarutkan agar serat dapat<br />
terlepas dari zat yang mengikatnya. Hal yang merugikan pada proses ini<br />
adalah randemen yang rendah yaitu 45-55 %.<br />
Proses kimia dibagi menjadi tiga kategori :<br />
1. Soda Process<br />
2. Sulphite Process<br />
3. Sulphate Process<br />
Dalam proses soda, kayu dimasak dengan larutan sodium<br />
hidroksida (NaOH). Larutan sisa pemasakan dipekatkan dan kemudian<br />
dibakar, yang akan menghasilkan sodium karbonat (Na2CO3), dan apabila<br />
diolah dengan menambahkan batu kapur akan menghasilkan sodium<br />
hidroksida (NaOH). Nama proses “soda” karena bahan kimia yang<br />
ditambahkan kedalam prosesnya berupa sodium karbonat (Na2CO3).<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Proses ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Pada proses sulfit, larutan<br />
pemasak yang dipakai adalah asam-asam yang mengandung sulfur dari<br />
logam alkali, atau alkali tanah berupa bisulfit.<br />
Proses pembuatan pulp yang paling banyak dipakai saat ini adalah<br />
proses sulphate atau disebut juga proses kraft. Kraft berasal dari bahasa<br />
Jerman yang berarti kuat.Kekuatan dari proses kraft ini dikarenakan<br />
adanya bahan kimia yang terkandung dalam larutan pemasak yang disebut<br />
“sulfidity”.Yang menjadi target pada proses ini adalah untuk memisahkan<br />
serat-serat yang terdapat dalam kayu secara kimia dan melarutkan<br />
sebanyak mungkin lignin yang terdapat pada dinding-dinding serat.<br />
2.2.1. Unit Persiapan Kayu<br />
Secara umum operasi persiapan kayu (Wood Handling and Preparation<br />
Plant) meliputi:<br />
1. Penimbunan kayu batangan di areal TPK (Tempat Penimbunan Kayu)<br />
2. Hasil pemotongan kayu di timbun di Chip File.<br />
Eukaliptus dan akasia adalah bahan baku utama proses pembuatan<br />
pulp di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Porsea. Persiapan bahan baku dimulai<br />
dari penebangan, pemupukan, pemotongan, pengulitan, penyerpihan, dan<br />
pengangkutan.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
2.2.2. Unit Pemasak (Digester)<br />
Digester adalah alat pemasak chip/serpihan kayu yang berbentuk silinder<br />
yang dilas bersusun tegak, mempunyai volume 200m 3 dan tinggi 18,67 m,<br />
diameter 4,2 m yang dirancang untuk bekerja pada tekanan tinggi hingga<br />
12 kg/cm 2 , temperatur 195 o C dan terdapat dua saringan yang diletakkan di<br />
dalam digester. Dimana tempat saringan terletak dibagian atas digester<br />
yang disebut relief striner dan yang terletak di tengah digester disebut<br />
middle strainer. Fungsi dari strainer tersebut untuk menjaga agar serat-<br />
serat kayu yang sedang dimasak tidak keluar dari digester pada waktu<br />
mensirkulasikan cairan pemasak dan pada waktu membuang gas yanga<br />
ada di digester.<br />
2.2.3. Washing<br />
Bubur pulp dari blowing tank dengan konsistensi 4 - 4,2% yang<br />
dipompakan ke pressure knotter dengan menambahkan cairan pengencer<br />
hingga konsistensinya 2% agar memudahkan pemisahan antara hasil<br />
dengan sisa. Hasil dari primary dan secondary knotter masuk ke vibrating<br />
knotter. Serat kasar dari vibrating knotter masuk ke drum trailer untuk di<br />
angkut ke chip pile dan airnya dibuang keselokan.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Bubur pulp dari knotter dicuci dalam empat unit washer.<br />
Didalamnya dilengkapi dengan sistem vakum sehingga bubur pulp dapat<br />
dicuci dengan baik dengan hasil cuciannya tidak melekat pada dinding<br />
washer yang terus berputar. Di daerah masukan, bubur pulp dicuci dengan<br />
sistem penyemprotan secara berlawanan. Air pencuci unutk washer satu<br />
diambil dari filtrat no.4 sedangkan bubur pulp pada washer empat dicuci<br />
dengan air panas yang baru. Bubur pulp yang menempel pada dinding<br />
washer dipotong dengan doctor blade yang dipasang sedemikian rupa<br />
sehingga bubur pulp yang sudah bersih tidak bercampur dengan bubur<br />
pulp yang kotor. Bubur pulp dari doctor blade dihancurkan lagi dengan<br />
menggunakan repulper low speed dan high speed yang memiliki sudu-<br />
sudu.<br />
Cara kerja repulper pada washer 1, 2, 3 dan 4 sama, yang berbeda<br />
hanya pada washer 3 karena memiliki satu repulper yang berbentuk screw.<br />
Hasil pencucian dari washer 4 dimasukkan ke washer stock tank dengan<br />
konsistensi 10-12% untuk selanjutnya dikirim ke unit penyaring.<br />
2.2.4. Screening<br />
Setelah washing, bubur pulp yang masuk pada washer stock selanjutnya<br />
dimasukkan ke unit screening. Tujuannya adalah untuk mendapatkan<br />
bubur pulp yang benar-benar bersih. Screener ada enam unit, yang terdiri<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
dari 3 unit primary screen, 1 unit tertiari screen, 1 unit swing screen serta<br />
dilengkapi dengan vibrating screen. Bubur pulp dari wash stock masuk ke<br />
primary screen. Hasil penyaringannya yaitu accept masuk ke washer ke<br />
empat dan reject masuk ke secondary screen dengan diamater 2 mm. Hasil<br />
dari secondary screen masuk ke primary screen dan buangaannya masuk<br />
ke tertiary screen. Hasil dari tertiary screen masuk ke secondary screen<br />
dan sisanya masuk ke vibrating screen. Hasil screening dan vibrating<br />
screen dikembalikan lagi ke tertiary screen, reject dari vibrating screen<br />
akan dimasukkan ke screw press untuk dipisahkan antara air dan serat<br />
kasar. Air dari screw press dikembalikkan ke wash stock tank untuk<br />
dilution dan sisanya akan diolah lagi ke digester. Dengan menggunakan<br />
pump bubur pulp hasil screening akan dipompakan ke high density<br />
unbleach stock tower sebagai tempat penyimpana<br />
2.2.5. Proses Pemutihan (Bleaching Plant)<br />
Pada normalnya proses penghilangan lignin adalah melarutkan pulp ke<br />
bentuk yang larut dalam air. Penghilangan bentuk-bentuk lignin<br />
merupakan kehilangan sebahagian dari hasil pada proses pemutihan, yang<br />
mana ini adalah antara 5% sampai dengan 10% (dihitung mulai dari pulp<br />
yang telah selesai dimasak), tergantung pada metode pemasakan dan<br />
sasaran brightness dari pulp. Warna pada pulp yang belum diputihkan<br />
umumnya disebabkan oleh lignin yang tersisa. Penghilangan lignin dapat<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
lebih banyak pada proses pemasakan, tetapi akan mengurangi hasil yang<br />
banyak sekali dan merusak serat, jadi menghasilkan kualitas pulp yang<br />
rendah. Oleh karena itu, proses pemasakan agar benar-benar cukup dimana<br />
proses penghilangan lignin dengan bahan kimia, umumnya memiliki suatu<br />
dampak terhadap dekomposisi dari lignin.<br />
Operasi pemutihan (Bleaching) terdiri dari 4 tahap, untuk 2 tahap<br />
yang pertama pada BKP dan DKP adalah sama, tahap pertama adalah<br />
perlakuan pengolahan terhadap pulp dengan menggunakan Klorin<br />
Dioksida yang diikuti dengan Ekstraksi oleh Kaustik/Oksigen pada tahap<br />
yang kedua. Pemutihan (Bleaching) pada tahap ketiga dan keempat pada<br />
BKP adalah perlakuan dengan Klorin Dioksida. Untuk DKP tahap yang<br />
ketiga adalah perlakuan pengelolahan dengan Klorin Dioksida yang diikuti<br />
dengan Sodium Hypo-Khlorite pada tahap yang terakhir.<br />
Pulp dari bagian pemutihan (Bleaching) disimpan di dalam Bleach<br />
High Density Stored Tower dengan konsistensi 12%.Pulp tersebut<br />
kemudian dikirim ke unit penyaringan dan Centri-Cleaner sebelum<br />
dijadikan ke dalam bentuk lembaran pada pulp machine dan dikeringkan<br />
di dalam sebuah alat pengeringan dengan nama Air Borne Flakt Drier,<br />
sesudah itu, lembaran tersebut dipotong-potong, ditimbang, dibungkus,<br />
diikat dengan kawat dan diberi tanda serta disimpan di Gudang.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Cairan lindi hitam (Black Liquor) berkonsentrasi rendah yang<br />
berasal dari unit pencucian dipekatkan dengan menggunakan Evaporator<br />
jenis failling film plate dan Konsentrator. Cairan yang sudah dipekatkan<br />
dengan konsentrasi 65% padatan selanjutnya dibakar didalam sebuah<br />
Ketel Uap dan pemutih bahan kimia. Uap air tekanan tinggi diproduksi<br />
dengan membakar bahan organik yang dapat di dalam cairan, ini<br />
digunakan untuk menghasilkan sumber elektrik pada Turbo Generator dan<br />
kelebihan steam digunakan untuk tujuan pemanasan pada proses.<br />
Tahap I, Klorin Dioksida (D0)<br />
Pulp hasil pencucian dan pennyaringan dialirkan dengan stock pump<br />
menuju unbleach tower yang berkapasitas 2000 m 3 . Klorin dioksida (ClO2)<br />
dicampur didalam stock tank kemudian dialirkan ke unbleach tower.<br />
Campuran pulp dengan bahan kimia ClO2 dialirkan ke blow stock<br />
blending tank, dan didalamnya campuran pulp dan bahan kimia tersebut<br />
akan bereaksi. Kemudian pulp dipompakan menuju D0 tower (menara<br />
klorinasi) melalui sebuah pipa. Dan didalam pipa, ClO2 diinjeksikan lagi<br />
dan juga terdapat mixer untuk mencampurnya.<br />
Campuran bahan kimia dan pulp ini masuk kedalam D0 tower yang<br />
berkapasitas 335 m 3 , pada bagian bawah dan keluar melalui bagian atas.<br />
• Temperatur reaksi : 60-65 o C<br />
• Brightness akhir : 55-60% ISO<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
• Waktu : ± 45 menit<br />
• pH reaksi : 2-4<br />
Tahap <strong>II</strong>, ekstraksi Peroksida( EP)<br />
Konsistensi pulp pada tahap ini adalah 10% dan alkali/caustic soda<br />
(NaOH) akan ditambah sebelum pulp masuk ke ekstrak tower atau menara<br />
ekstraksi. Jumlah NaOH yang ditambahkan diatur melalui katub pH.<br />
Bahan kimia yang digunakan adalah NaOH, O2, H2O2.<br />
• Temperatur reaksi : 70-75 o C<br />
• Brightness akhir : 65-75% ISO<br />
• Waktu : 45-60 menit<br />
• pH reaksi : 10,8-11<br />
Tahap <strong>II</strong>I, Dioksida I (DI)<br />
Tahap lanjutan ini juga memakai klorin dioksida (ClO2) sebagai<br />
bahan pengelantang dan NaOCl (sodium hipoklorit) juga diperlukan.<br />
Tujuan utama dalah untuk menaikkan brightness pulp sesuai dengan target<br />
yang ingin dicapai.<br />
Proses pada tahap ini berlangsung :<br />
• Temperatur reaksi : (HYPO) 40- 50 o C<br />
(ClO2) 78- 80 o C<br />
• Brightness akhir : 85-88% ISO<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
• Waktu : 180 menit<br />
• pH reaksi : 3,0-3,5<br />
Tahap IV, Peroksida (D<strong>II</strong>)<br />
Pulp dari tahap dioksida pertama diproses selanjutnya ditahap<br />
peroksida. Prinsip perlakuan kimia pada tahap ini sama dengan tahap<br />
dioksida pertama. Tujuannya adalah untuk penyempurnaan kemurnian<br />
pulp dan tercapainya brightness pulp. Bahan kimia yang dipakai juga<br />
menggunakan ClO2.<br />
• Temperatur reaksi : 78-80 o C<br />
• Brightness akhir : 89-90% ISO<br />
• Waktu : 240 menit<br />
• pH reaksi : 3,0-3,5<br />
2.2.6. Pulp Machine<br />
Pulp machine merupakan intergrasi dari bagian operasi pabrik pulp. Kini<br />
dengan perkembangan teknologi telah menghasilkan tingkat efesiensi yang<br />
tinggi. Pulp machine dirancang mengubah suspensi pulp yang dikirim dari<br />
bleaching plant atau proses bleaching menjadi lembaran pulp kering yang<br />
selanjutnya diproses kedalam bentuk bal-bal unutk dikirim ke konsumen.<br />
Mengatur dan mengubah suspensi pulp menjadi lembaran dengann kadar<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
air 10% lalu dilakukan pengebalan yang tujuannya untuk mempermudah<br />
pengiriman dalam transportasi.<br />
Pulp machine dirancang dengan fungsi utamanya memisahkan air<br />
dari buburan pulp dengan cara efesiensi tanpa merusak struktur serat, berat<br />
dasar dan formasi pulp yang dihasilkan memiliki kekuatan lembaran yang<br />
maksimum. Pulp machine merupakan tahapan terakhir dari proses<br />
produksi pulp yang memiliki kepentingan sendiri. Setiap menit kehilangan<br />
waktu produksi menggambarkan kehilangan penghasilan, karena itu<br />
kemampuan operasi dalam bagian ini sangat diperlukan unutk menurunkan<br />
down time seminimum mungkin.<br />
2.3. Bilangan Kappa (Kappa Number)<br />
Agar supaya pengendalian tahapan pemutihan berjalan dengan efesien<br />
untuk mendapatkan pulp dengan kualitas yang diharapkan maka dilakukan<br />
beberapa pengujian, yaitu:<br />
• Kappa Number (bilangan kappa) yaitu : pengujian untuk<br />
mengetahui tingkat delignifikasi, kekuatan relatif dari pulp dan<br />
kesanggupannya untuk diputihkan.<br />
• Brightness (Kecerahan) yaitu : sifat lembaran pulp untuk<br />
memantulkan cahaya yang diukur pada suatu kondisi yang baku,<br />
digunakan sebagai indikasi tingkat keputihan. Keputihan pulp<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
diukur dengan kemampuan memantulkan cahaya monokromatik<br />
dan diperbandingkan dengan standar yang telah diketahui<br />
(biasanya Magnesium Oksida), dan diukur dengan alat<br />
Brightnessmeter (Elrepho)<br />
• Viskositas yaitu : pengujian terhadap kekuatan dari pada pulp,<br />
pengujian mengevaluasi derajat polimerisasi dari pada selulosa<br />
atau dengan kata lain degradasi dari pada selulosa. (Sirait, 2003).<br />
2.4. Analisis Titrimetri<br />
Reaksi yang digunakan dalam analisis titrimetri dapat dibagi dalam dua<br />
golongan utama :<br />
a) Reaksi dimana tidak terjadi perubahan keadaan oksidasi; reaksi ini<br />
bergantung pada bersenyawanya ion – ion.<br />
b) Reaksi oksidasi – reduksi, ini melibatkan suatu perubahan keadaan<br />
okidasi, atau dengan kata lain, pemindahan elektron. (Basset, 1994).<br />
Titrimetri atau analisis volumetrik adalah salah satu cara<br />
pemeriksaan jumlah zat kimia yang luas pemakaiannya. Hal ini<br />
disebabkan karena beberapa alasan. Pada satu segi, cara ini<br />
menguntungkan karena pelaksanaannya mudah dan cepat, ketelitian dan<br />
ketepatannya cukup tinggi. Pada segi lain, cara ini menguntungkan karena<br />
dapat digunakan untuk menentukan kadar berbagai zat yang mempunyai<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
sifat yang berbeda - beda. Pada dasarnya cara titrimetri ini terdiri dari<br />
pengukuran volume larutan pereaksi yang dibutuhkan untuk bereaksi<br />
secara stokiometri dengan zat yang akan ditentukan. Larutan pereaksi itu<br />
biasanya diketahui kepekatannya dengan pasti, dan disebut pentiter atau<br />
larutan baku. Sedangkan proses penambahan pentiter ke dalam larutan zat<br />
yang akan ditentukan disebut titrasi.<br />
Dalam proses satu bagian demi bagian pentiter ditambahkan ke<br />
dalam larutan zat yang akan ditentukan dengan bantuan alat yang disebut<br />
buret sampai tercapai titik kesetaraan. Titik kesetaraan adalah titik pada<br />
saat pereaksi dan zat yang ditentukan bereaksi sempurna secara<br />
stokiometri. Titrasi harus dihentikan pada atau dekat titik kesetaraan ini.<br />
Jumlah volume ini disebut volume kesetaraan. Dengan mengetahui<br />
volume kesetaraan kadar pentiter dan faktor stokiometri, maka jumlah zat<br />
yang ditentukan dapat dihitung dengan mudah.<br />
Agar proses titrasi dapat berjalan dengan baik sehingga<br />
memberikan hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti, maka persyaratan<br />
berikut perlu diperhatikan dalam setiap titrasi :<br />
1) Interaksi antara pentiter dan zat yang ditentukan harus berlangsung<br />
secara stokiometri dengan faktor stokiometrinya berupa bilangan bulat.<br />
Faktor stokiometri ini harus diketahui atau ditetapkan secara pasti,<br />
karena faktor ini perlu dalam penghitungan hasil titrasi.<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
2) Laju reaksi harus cukup tinggi agar titrasi berlangsung dengan cepat<br />
3) Interaksi antara pentiter dan zat yang ditentukan harus berlangsung<br />
secara terhitung. Artinya, sesuai dengan ketepatan yang dapat dicapai<br />
dengan peralatan yang lazim digunakan dalam titrimetri, reaksi harus<br />
sempurna sekurang-kurangnya 99.9% pada titik kesetaraan.<br />
Suatu indikator merupakan asam atau basa lemah yang berubah<br />
warna diantara bentuk terionisasinya dan bentuk tidak terionisasinya.<br />
Kisaran penggunaan indikator adalah 1 unit pH disekitar nilai pKa nya.<br />
Sebagai contoh fenolftalein(PP), mempunyai pKa 9.4 (perubahan warna<br />
antara pH 8.4 – 10.4). Struktur fenolftalein akan mengalami penataan<br />
ulang pada kisaran pH ini karena proton dipindahkan dari struktur fenol<br />
dari PP sehingga pHnya meningkat akibatnya akan terjadi perubahan<br />
warna. Metil orange (MO) mempunyai pKa (perubahan warna antara pH<br />
2.7 dan pH 4.7), mengalami hal serupa terkait dengan perubahan warna<br />
yang tergantung pada pH. Kedua indikator ini berada pada kisaran titik<br />
balik (titik infleksi) pada titrasi asam kuat dan basa kuat.<br />
Fenolftalein adalah indikator dari golongan ftalein yang banyak<br />
digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan kimia. Fenolftalein merupakan<br />
senyawa hablur putih yang mempunyai kerangka lakton. Indikator ini<br />
sukar larut dalam air, tapi dapat bereaksi dengan air hingga cincin<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
laktonnya terbuka dan membentuk asam yang tidak berwarna. (Rohman,<br />
2007).<br />
2.3.1. Proses Oksidasi – Reduksi<br />
Pada mulanya, proses oksidasi dan reduksi diberi batasan sebagai reaksi<br />
pelepasan dan penangkapan oksigen oleh suatu zat. Sekarang, untuk<br />
memperjelas inti sari gejala tersebut, telah dikemukakan batasan yang<br />
lebih umum, yaitu : oksidasi adalah proses pelepasan elektron dari suatu<br />
zat, sedangkan reduksi adalah proses penangkapan elektron oleh suatu zat.<br />
Pada waktu melepaslan elektron suatu zat berubah menjadi bentuk<br />
teroksidasinya, karena zat itu bertindak sebagai zat pereduksi. Sebaliknya,<br />
zat pengoksidasi adalah zat yang menerima elektron dan karena itu zat<br />
tersebut mengalami reduksi.<br />
Bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi dari suatu zat merupakan<br />
suatu system yang berpasangan yang disebut system redoks atau pasangan<br />
redoks. Bentuk teroksidasi sering ditandai dengan “ox” dan bentuk<br />
tereduksi ditandai dengan “red”. Kesetimbangan reaksinya ditulis sebagai<br />
berikut :<br />
ox + n e = red proses reduksi<br />
red = ox + n e proses oksidasi<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
Disini n adalah jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima. Dari<br />
batasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada kemiripan antara reaksi<br />
oksidasi – reduksi dengan reaksi asam – basa. Perbedaan pokok antara<br />
kedua proses itu adalah bahwa pada reaksi oksidasi – reduksi elektron<br />
merupakan zarah dasar yang dipindahkan antara bentuk teroksidasi dan<br />
bentuk teroksidasi berpasangan, sedangkan reaksi asam – basa hanya satu<br />
proton yang dapat saling dipertukarkan, sedangkan pada reaksi oksidasi –<br />
reduksi lebih dari satu elektron dapat terlibat dalam reaksi. (Rivay, 1995).<br />
2.3.2. Titrasi Permanganometri<br />
Kalium permanganat digunakan secara luas sebagai pereaksi yang mudah<br />
diperoleh, tidak mahal, dan tidak memerlukan suatu indikator kecuali<br />
kalau digunakan larutan yang sangat encer. Satu tetes 0.1 N KMnO4<br />
memberikan suatu warna merah muda yang jelas kepada volume larutan<br />
yang biasanya digunakan dalam suatu titrasi. Warna ini digunakan untuk<br />
menunjukkan kelebihan pereaksi.<br />
Permanganat mengalami reaksi kimia yang bermacam – macam<br />
dalam keadaan – keadaan oksidasi. Reaksi yang paling banyak dijumpai<br />
berada dalam laboratorium pendahuluan yaitu dalam larutan yang sangat<br />
asam. Permanganat bereaksi sangat cepat dengan banyak pereaksi tetapi<br />
beberapa zat memerlukan pemanasan atau penggunaan katalis untuk<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara
mempercepat reaksinya. Kelebihan yang sedikit dari permanganat yang<br />
ada pada titik akhir satu titrasi cukup untuk menyebabkan pengendapan<br />
beberapa MnO2 akan tetapi karena reaksinya lambat maka MnO2 biasanya<br />
tidak diendapkan pada titik akhit tiitrasi permanganometri. (Underwood,<br />
1988).<br />
<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara