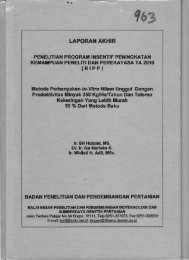LAPORAN AKHIR - KM Ristek
LAPORAN AKHIR - KM Ristek
LAPORAN AKHIR - KM Ristek
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
·.~<br />
<strong>LAPORAN</strong> <strong>AKHIR</strong> <br />
PENG1 0,4 KG PEDET PRA SAPIH or SUMATERA BARAT<br />
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN<br />
1. (Ketahanarl P3ngat1J)<br />
Kode Produk Target<br />
1.09 (panga~ substitu-ii imp.!);,,)<br />
Kode I(egiatan 1.09.05<br />
~~rlang Fokus<br />
,. <br />
BADAN PENElITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAt.t <br />
BAlAI BESAR PENGKIlJIAN DAN PlENGfMSANGAN TEKNOlOGI PERTANIAtj <br />
BALAI PENGKAJIA:\I TEI{NOlOGI PERTANIAN (BPTP) SUt-1ATERA SARAT <br />
Alamat: Jalan Rava Padang-Solok km 40 SukaramiwSolok-Sumatera Barat, 21366<br />
JD~ November 2010
<strong>LAPORAN</strong> <strong>AKHIR</strong> <br />
PEI\JGKAJIAN SISTEM REPROOUKSI SAPI BERPOTENSI BERANAK KEMBAR (Jarak beranak 5 12<br />
bulan), PENGULANGAN KELAHlRAN KEMBAR (~ 50%), SERTA TEKNOLOGI PEMBER1AN<br />
RANSUM BERBAHAN LOKAL UNTUK PBBH > 0,4 KG PEOET PRA SAPIH 01 SUMATERA BARAT<br />
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN<br />
Bidang Fokus<br />
Kode Produk Target<br />
Kode Kegiatan<br />
1. (Ketahanan Pangan) <br />
1.09 (pangan substitusi impor) <br />
1.09.05 <br />
Peneliti Utama<br />
: Yanovi Hendri, Sptl MSc<br />
BADAN PENELmAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN <br />
BALAl BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN <br />
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA BARAT <br />
A l amat~ lalan Raya Padang-Solok km 40 Sukarami-Solok-Sumatera Barat, 27366<br />
J() November 2010
Judul<br />
Fokus Bidang Prioritas<br />
Kode Produk Target 1.09<br />
Kode Kegiatan 1.09.05<br />
Lokasi<br />
Penelitian Tahun ke<br />
I<br />
Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian<br />
A. Lembaga Pelaksana Penelitian<br />
Nama Koordinaor/Peneliti Utama Yanovi Hendri, SPt, MSc<br />
-4ama Lembaga/ l nstitusi<br />
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pertanian<br />
Sumatera Barat<br />
Unit Organisasi<br />
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi<br />
Pertanian (BBP2TP)<br />
' I amat Jln. Tentara Pelajar No. 10 Bogor (161 14)<br />
- e epon! Fax! E-mail Telp 0755-3 1122/ Fax 0755-31138/ e-mail<br />
sum bar _ bptp@yahoo.com<br />
B. Lembaga Lain Yang<br />
Teriibat<br />
\Cima Pimpinan<br />
maLernbaga<br />
• mat<br />
- €.lepO nj Fax/ E-mail<br />
.li:l9ka Waktu<br />
1 tahun<br />
- ya tahun -1 Rp. 136.309.091,<br />
30aya tahun-2<br />
- - Biaya<br />
. tan (baru/lanjutan) Baru<br />
Rek:apitulasi Biaya<br />
No. Uraian Jum'ah (Rp)<br />
1. Gaji dan Upah 29.000.000,-<br />
2. Bahan habis pakai 36.659.000,-<br />
3. Perjalanan 54.900.000,<br />
4. Lain-lain 12.750.091,<br />
lumlah Biaya 136.309.091,-<br />
Mengetahui :<br />
Kepala l embagajInstitusi<br />
BPTP Sumbar<br />
tvutg<br />
"<br />
LEMBAR PENGESAHAN<br />
Pengkaj ian Sistem Reproduksi Sapi Berpotensi Beranak<br />
Kembar (Jarak beranak :S 12 bulan), Pengulangan Kela hiran<br />
kembar (~ 50%), serta Teknologi Pemberian Ransum<br />
Berbahan l okal Untuk PBBH > 0,4 KG Pedet Pra Sapih di<br />
Sumatera Barat<br />
Ketahana n Pangan<br />
Sumatera Barat<br />
Koordinator<br />
Dr.!r. ~..psam a Y{Jfdy. MSc<br />
Yanovi Hendri. SPt, MSc<br />
NIP. 195910.10 198603 1 002<br />
v<br />
- ,<br />
NIP. 19730130 199803 1 002<br />
1
RINGKASAN <br />
Sapi merupakan komoditas peternakan yang berperan strategis dalam aspek ketahanan pangan<br />
masyarakat sebagai penghasil protein hewani. BHa ditinjau kondisi existing, produksi daging<br />
sapi hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan pasar domestik. Oleh sebab itu, perlu upaya<br />
meningkatkan populasi sapi secara cepat dalam jangka pendek misalnya meningkatkan<br />
persentase kelahiran kembar sapi betina produktif. Pemikiran sederhana adalah, bila sapi betina<br />
o oduktif yang ada beranak kembar maka populasi meningkat, impor berkurang, hemat devisa<br />
r"legara, pendapatan petemak bertambah dan permintaan pasar domestik terpenuhi. Sifat<br />
_ ahiran kembar genetik yang dapat diwariskan, seleksi mempercepat effisiensi mencapai<br />
e a iran kembar. Sapi yang dipilih adalah sapi dengan tingkat kesuburan superior (High<br />
a'itY) . Selain itu, kelahiran kembar dapat dilusahakan melalui peningkatan fertilitas melalui<br />
- akuan homonal. Kegiatan ini bertujuan untuk : merakit teknologi reproduksi sapi dengan<br />
00 - 5i kelahiran kembar tinggi, merakit teknologi pakan dan sistem pemberian pakan untuk<br />
c~ - I( sapi prasapih dengan kenaikan berat badan 0,4 kg/ ekor/hari. Kegiatan mencakup 2<br />
. ~ ata yaitu : Kajian Sistem Reproduksl Sapi Berpotensi beranak kembar dan Kajian<br />
- cnfaatan Pakan berbahan Lokal untuk anak sapi prasapih dengan kenaikan berat badan 0,4<br />
; : r/hari . Kegiatan berbentuk penelitian lapangan, dimana pada kajian sistem reproduksi,<br />
sc _ I duk akan mendapat perlakuan penyerentakan birahi dan superovulasi dengan hormon<br />
- _... P oses sinkronisasi dan superovulasi diatur sehingga sapi betina dalam kondisi<br />
lasi saat dikawinkan. Sistem perkawinan menggunakan kawin IB (2 kali IS dengan<br />
=r~a 5 jam). Materi kegiatan ini terdiri dan 20 ekor sapi betina yang telah beranak minimal<br />
.sc::: Ii. Pada kajian pakan anak sapi prasapih, pakan tambahan akan diberikan dengan<br />
an protein 15 - 16% dan pemberian hijauan 10% berat badan. Pakan tambahan sapi<br />
:.:-a diformulasl mengandung protein 12 - 15 persen dengan lama pemberlan 3 bulan.<br />
~ e':er yang diamati adalah : berat badan, konsumsi pakan, dan keberhasilan kebuntingan.<br />
pengkajian adalah terdapatnya teknologi reproduksi atau sistem perkawinan sapi<br />
embar, teknologl pakan dan sistem pemberian pakan anak sapi prasapih dengan<br />
berat badan 0,4 kg/ekor/hari. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pada akhir<br />
•~ .:.rz.... te dapat 16 dari 20 ekor sapi betina yang diseleksi berhasil di inseminasi buatan dan<br />
• ::-; c;:C'" pakan tam bahan untuk anak sapl prasaplh menghasilkan kenaikan berat badan harian<br />
,EA ekor/hari. Hasil tersebut lebih tinggi dari target kenaikan berat badan yang hanya 0,4<br />
eKor ari.<br />
2
·...<br />
PRAKATA <br />
Puji syukur kepada Allah Swt penulis telah dapat menyelesaikan penulisan laporan<br />
emajuan triwulan kedua program insentif kegiatan sapi kembar. Amin<br />
Laporan akhir ini memuat segala kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan<br />
aksanaan kegiatan sepanjang T.A 2010. Sepanjang hal tersebut sejumlah pelaksanaan<br />
= ~ ' atan telah dilaksanakan antara lain s~leksi sapi betina, suntik PGF2 alpha pertama dan<br />
""a, perkawinan dengan IB serta perJakuan beberapa formulasi ransum untuk anak sapi<br />
:TCSa
DAFTARISI <br />
Halaman <br />
.£ BAR PENGESAHAN 1 <br />
GKASAN<br />
2 <br />
;;<br />
KATA " 3 <br />
c:;-T"AR ISI<br />
TABEL<br />
LAM PIRAN<br />
""- PENDAHULUAN 7 <br />
.1 Latar Belakang 7 <br />
.2 Ruang Ungkup 9 <br />
1.3 Hipotesis 9 <br />
Perumusan Masalah<br />
-. = ....... SJAUAN PUSTAKA 11 <br />
JUAN DAN MANFAAT<br />
14 <br />
:: :rODOLOGI 15 <br />
..! ' Pendekatan 15 <br />
.! <br />
Tempat dan Waktu 16 <br />
- De aksanaan kegiatan 16 <br />
- A PEMBAHASAN 17 <br />
~<br />
PULAN DAN SARAN<br />
22 <br />
5TAKA<br />
23 <br />
4 <br />
5 <br />
6 <br />
9 <br />
4
DAFTAR TABEL <br />
Tabel1 :<br />
Tabel 2:<br />
Tabel3 :<br />
Tabel4 :<br />
Tabel5 :<br />
Tabel6 :<br />
Tabel7 :<br />
Persentase kelahiran kembar pada barbagai macam sapi (Arthur et al,<br />
1996)<br />
Pemeriksaan CL (Corpus Luteum) dan Fisik Ternak Dalam Rangka<br />
Seleksi Sapi Betlna<br />
Keragaan Kondisi Sapi Betina Setelali Suntik PGF2£ ke I dan II<br />
Keragaan Sapi Betina Setelah penyuntikan Hormon FSH<br />
Distribusi Kooperator Untuk Pengkajian Anak Sapi Prasapih<br />
Rata-rata pertambahan berat badan anak sapi prasapih yang diberikan<br />
perlakuan pakan dengan formula berbeda<br />
Rata-rata pertambahan berat badan harian anak sapi yang diberikan<br />
pakan tambahan dengan formulasi berbeda<br />
Halaman<br />
11<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
20<br />
21<br />
5
DAFTAR LAMPIRAN <br />
Halaman <br />
Lampiran 1 : Nama-nama peternak kooperator Sapi Betina 22 <br />
Lampiran 2 : Nama-nama peternak kooperator Pengkajian Anak Sapi Prasapih 23 <br />
Lampiran 3 : Data Penimbangan Anak Sapi Rrasapih 24 <br />
6
I. PENDAHULUAN <br />
1.1 Latar Belakang<br />
Pentingnya peranan ternak sapi untuk mencapai tujuan pembangunan tidak diragukan<br />
berbagai kalangan nasional maupun internasional. Sapi komoditas peternakan penghasil<br />
protein hewani terutama daging yang mempunyai andil dalam aspek ketahanan pangan.<br />
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa, tingkat konsumsi protein hewani berkorelasi pasitif<br />
dengan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa (Agustar dan Jaswandi, 2006).<br />
BHa dilihat kondisi existing, produksi daging sapi dalam negeri belum mencukupi<br />
kebutuhan konsumsi protein hewani penduduk Indonesia. Dewasa ini, produktifitas dan<br />
reproduktifitas temak sapi berjalan lambat. 30% kebutuhan daging nasional masih<br />
mengandalkan negara-negara pengekspor seperti Australia dan New Zealand (Asdi Agustar dan<br />
Jaswandi, 2006). Oleh sebab itu, untuk memacu peningkatan produksi daging Menteri Pertanian<br />
mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi 2014.<br />
Ditinjau sudut pandang produksi dan reproduksi, sapi termasuk hewan ruminansia<br />
dengan pola reproduksi relative lama, masa bunting 9 bulan dan masa pertumbuhan lebih dari<br />
18 bulan. Secara konvensional, sapi dikelompokkan sebagai hewan monoovulasi (Echternkamp<br />
~t al., 2007a). Sapi betina hanya menghasilkan satu ovulasijsatu ovum pada akhir siklus.<br />
Panjangnya masa produksi dan reproduksi menyebabkan agribisnis peternakan sapi secara<br />
komersial kurang berkembang. Pemeliharaan sapi didominasi petemakan rakyat menggunakan<br />
sistem konvensional dan merupakan usaha sambilan disamping berusaha pertanian<br />
(Wirdahayati dan A. Bamualim, 2006). Oleh sebab itu, perbaikan manajemen pemeliharaan<br />
ernak lokal perlu menjadi acuan kebijakan untuk mengembangkan petemakan sapi<br />
berwawasan agribisnis mendukung PSDS.<br />
Dewasa ini, terjadi pengurasan populasi secara berlebihan, banyak sapi berumur muda<br />
dan sap; betina produktif diserap pasar. Bila kondisi tersebut tetap berlanjut maka produktifitas<br />
sa pi menurun dan menghambat pencapaian swasembada daging sapi di propinsi Sumatera<br />
Barat. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan populasi secara cepat misalnya meningkatkan<br />
persentase kelahiran kembar. Pemikiran sederhana adalah, bila sapl beranak kembar maka<br />
populasi akan bertambah dengan cepat, pemotongan betina produktif dan pengurasan populasi<br />
sapi pesisir terhindarkan.<br />
7
Manipulasi genetik merupakan suatu cara dalam bidang reproduksi digunakan untuk<br />
pembentukan variasi dan peningkatan kualitas ternak. Berkaitan dengan itu, kelahiran kembar<br />
termasuk sifat keturunan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Persentase kelahiran<br />
kembar berbagai macam jenis sapi berkisar antara 0,5% sampai 8,85% (Arthur et al, 1996).<br />
Bila ditinjau dari sudut reproduksi, sifat genetik sebagian sapi yang dipelihara melalui<br />
peternakan rakyat berpotensi tinggi menghasilkan kelahiran kembar. Hal in; mengingat,<br />
sebagian sapi betina produktif memiliki f~rtilitas superior (high fertilitY; mampu beranak satu<br />
kali dalam setahun. laporan hasil pengkajian menyatakan bahwa diantara sapi betina bunting<br />
terdapat juga kelahiran kembar (Hosen, dkk, 2009). Sapi dengan tingkat kesuburan superior<br />
(high fertilitY; mempunyai peluang tinggi mencapai kelahiran kembar (Echternkamp and<br />
Gregory, 2002).<br />
Seleksi kembar meningkatkan effisiensi percepatan reproduksi beranak kembar pada<br />
~ernak sap; (Echternkamp et aI., 2007a,b). Seleksi sapi melahirkan kembar telah dilakukan<br />
nited States of Meat Animal Research Center (US MARC), sapi yang melahirkan kembar<br />
meningkat dari 4% (tahun 1984) menjadi lebih dari 50% (tahun 2000), peningkatan kelahiran<br />
embar terjadi secara linier 3.1% per tahun (Echtemkamp and Gregory, 2002).<br />
Selain bertujuan meningkatkan populasi, kelahiran kembar beresiko tinggi terhadap<br />
ematian anak sapi. Penelitian sementara Hosen, dkk (2009) menunjukkan bahwa 50 persen<br />
eproduksi mencapai kelahiran kembar dengan perlakuan hormonal dan teknologi pakan<br />
tambahan anak sapi prasapih dengan kenaikian berat badan 0,4 kg/ekor/hari.<br />
1.2 Ruang Ungkup<br />
a. Pengkajian Sistem Reproduksi Sapi Berpotensi Beranak Kembar (Jarak beranak 5 12<br />
bulan) Pengulangan Kelahiran Kembar ( ~ 50%)<br />
b. Teknologi Pemberian Ransum Berbahan Lokal Untuk PBBH ~ 0,4 Kg Pedet Pra Sapih<br />
1.3 Hipotesis<br />
Kelahiran kembar bisa berulang dan jarak beranak bisa diperpendek dengan perlakuan sistem<br />
eproduksi pada sapi betina beranak kembar atau keturunannya.<br />
a. Kelahiran kembar bisa berulang dan jarak beranak bisa diperpendek (5 12 bulan)<br />
dengan perlakuan sistem reproduksi pad a sapi betina.<br />
b. Ransum yang diformulasi dengan bahan pakan lokal dapat meningkatkan PBBH ~ 0,4<br />
Kg pada anak sapi prasapih<br />
1.4 Perumusan Masalah<br />
Kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan bergizi asal temak sapi semakin tinggi<br />
sehingga terjadi ketidakseimbangan laju pertambahan populasi dan permintaan. Kebijakan<br />
mpor daging dan ternak sapi yang dilakukan Pemerintah mencapai 30% kebutuhan pasar<br />
domestik. Hal tersebut menguras devisa negara dan membebani APBN.<br />
Lambatnya pertumbuhan ternak sapi juga menimbulkan masalah regional misalnya<br />
temak sap; tidak berproduksi maksimal sesuai potensi genetik. Sebagian sapi yang dikonsumsi<br />
merupakan sapi muda bahkan sapi betina prod u ktif. Sementara itu, sapi dewasa yang dipotong<br />
oada rumah pemotongan hewan (RPH) tidak mencapai berat daging optimal. Dengan demikian,<br />
terjadi pengurasan populasi temak untuk memenuhi kebutuhan pasar ya ng cendrung<br />
meningkat setiap tahun.<br />
Dari sudut pandang reproduksi, sapi hewan ruminansia dengan pola reproduksi relative<br />
ama, masa bunting 9 bulan dan pertumbuhan hingga dewasa butuh waktu lebih dari 18 bulan.<br />
Secara konvensional, sapi dikelompokkan sebagai hewan monoovulasi. Sapi betina hanya<br />
l1enghasilkan satu ovulasi/satu ovum pada akhir siklus. Dengan karakteristik seperti adanya,<br />
5ulit diharapkan pertumbuhan populasi yang cepat dalam jangka waktu singkat.<br />
Manipulasi genetik adalah teknik pada bidang reproduksi biasanya digunakan dalam<br />
membentuk variasi dan meningkatkan kualitas temak sapi. Berkajtan dengan kondisi diatas,<br />
9
maka diperlukan upaya mengoptima isasi patensi genetik ternak agar populasi ternak<br />
bertambah da/am waktu singkat. Diamaranya adalah melalui kelahiran kembar. Pemikiran<br />
sederhana adalah, bila sapi beranak kembar papulasi meningkat dua kali Iipat dengan demikian<br />
permintaan masyarakat akan konsumsi daging bisa te rata si dan pengurasan populasi dapat<br />
dihindarkan..<br />
Seleksi genetik mempercepat proses mencapai kelahiran kembar. Namun, kelahiran<br />
kembar dapat pula melalui manipulasi sjstem reproduksi temak yakni dengan perlakuan<br />
hormonal yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembar. Perlakuan secara hormonal pada<br />
sapi mengakibatkan superovu/asi dimana sapi betina menghasilkan lebih dari satu sel telur<br />
dalam suatu siklus birahi. Hasil dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa memperlakukan<br />
sap; betina dengan hormon PGF2o, GnRH dan FSH memberikan peluang kelahiran kembar pada<br />
sapi betina. Namun, penerapan sistem reproduksi dengan perlakuan hormonal pada sapi betina<br />
masih memerlukan kajian yang mendalam dan perlu penyesuaian dengan kondisi daerah.<br />
Tingkat kematian terhadap anak sapi yang lahir kembar tinggi. Untuk itu, perlu<br />
manajemen pakan yang baik dengan pemberian pakan tambahan selama masa kebuntingan<br />
sa pi betina yang diduga melahirkan anak kembar .. Selain itu, perlu upaya menekan kamatian<br />
anak sapi prasapih anak sapi dengan perlakuan sama yaitu memberikan pakan tambahan<br />
sehingga anak sap; dalam kondisi sehat.<br />
10
n. TINJAUAN PUSTAKA <br />
Dari sudut pandang reproduksi, sapi merupakan ternak ruminansia dengan masa<br />
reproduksinya relative lama, masa bunting 9 bulan dan pertumbuhan sapi hingga dewasa<br />
, embutuhkan waktu lebih dari 18 bulan. Dengan demikian, sulit mengharapkan peningkatan<br />
populasi dalam waktu relatif cepat. Pandangan se€ara konvensional, sapi juga di kelompokkan<br />
sebagai hewan monovulasi (Echtemkamp et aI., 2007a), yaitu induk betina diketahui umum<br />
anya menghasilkan satu ovulasi/ satu ovum pada akhir siklus.<br />
Sapi dapat menunjukkan tingkah laku birahi secara bersarna- sarna dan dapat dilakukan<br />
- seminasi secara serentak. Namun infertilitas tetap mencapai 30-40% dari betina produktif.<br />
Dari informasi diatas, rnaka reproduktifitas sapi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategory: 1.<br />
Sapi yang tidak subur (Infertile), tidak bunting, 2. Sapi yang menghasilkan satu ovum, bunting<br />
an melahirkan (Fertile), 3. Sapi yang menghasilkan ovum lebih dari satu, bunting dan<br />
rnelahirkan (High fertilitYJ.<br />
Sejalan dengan informasi reproductive wastage yang relatif tinggi tersebut, studi<br />
'nfertilitas pada sapi (Weigel, 2008), menghasilkan bahwa 85% penyebab kegagalan sapi untuk<br />
Tlenghasilkan anak di sebabkan oleh faktor management, 10-12,5% disebabkan oleh faktor<br />
:;api betina dan 2,5 hingga 5 % disebabkan oleh faktor jantan. Dengan data infertilitas yang<br />
'nggi tersebut, diperlukan usaha untuk meningkatkan fertilitas hinga mencapai fertilitas yang<br />
optimum. Usaha yang telah dilakukan yaitu seleksi sapi yang dapat melahirkan kembar<br />
Echternkamp and Gregory, 2002) untuk dapat mencapai lahir kembar, sapi-sapi yang dipili<br />
::dalah sapi yang mencapai kesuburan yang superior (High fertilitYJ.<br />
Pemikiran yang sederhana adalah, bahwa bila sapi dapat beranak kembar maka jumlah<br />
X'lpulasi dapat meningkat dengan cepat dan kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dapat<br />
:erpenuhi dan swasembada daging dapat terlaksana lebih cepat. Persentase kelahiran kembar<br />
:x\da berbagai macam jenis sapi berkisar pada kondisi alamnya yang terrendah 0,5% dan<br />
:-ertinggi 8,85% (Arthur et al, 1996) dapat dilihat pada Tabel 1.<br />
-abel 1. Persentase kelahiran kembar pada barbagai macam sapi (Arthur etal, 1996)<br />
No Jenis Sa i Ke"adian kembar 0/0<br />
1 1,Cf4 <br />
2 ~5<br />
3<br />
4<br />
5<br />
27- 8 85<br />
308- 3,3<br />
~8<br />
11
Hasil penelitian yang relative.<br />
e gejutkan (Echternkamp and Gregory, 2002) yaitu<br />
seleksi sapi yang melahirkan kembar d-Iakukan di United States of Meat Animal Research Center<br />
(US MARC) dengan hasil, sapi yang melahirkan kembar dapat meningkat dari 4% (tahun 1984)<br />
menjadi lebih dari 50% (tahun 2000), jadi peningkatan kelahiran kembar terjadi secara linier<br />
3.1% per tahun (Echternkamp and Gregory, 2002). Lebih lanjut Echtemkamp et 131., (2007a,b)<br />
melaporkan bahwa rasio jumlah pedet per kelahiran dapat ditingkatkan dari 1,34 pedet per<br />
kelahiran pada tahun 1994 menjadi 1,56 pada tahun 2004. Hasil tersebut adalah<br />
pengembangan pad a sapi komposit yaitu campuran dari 9 jenis sapi di USA, yang memberikan<br />
indikasi prospek pengembangan sapi beranak kembar di waktu mendatang.<br />
Penelitian fisiology perkembang biakan telah dilakukan untuk mendukung seleksi sapi<br />
yang melahirkan kembar, menggunakan evaluasi hormonal (Echtemkamp et 131, 2006a,b) dan<br />
identifikasi ovulasi dobel (Cushman et 131, 2006,2007 & Donagh et 131, 2007) dengan hasil yang<br />
baik. Studi dan seleksi sapi yang beranak kembar telah dilakukan pada sapi menggunakan DNA<br />
marker telah dilakukan untuk memilih sapi yang melahirkan anak kembar (multiple calving).<br />
Evaluasi genetic menggunakan single nucleotide polymorphism (T9/T1O) pada osteopontin gene<br />
(SPP1) telah digunakan untuk seleksi sapi yang dapat melahirkan kembar (Aad et 131., 2006;<br />
Allan et 131.,<br />
2006;2007a,b). Peningkatan produksi dan reproduksi dari tingkat ovulasi dan<br />
jumlah fetus dan distribusinya dalam uterus telah dipelajari (Echtemkamp et 131., 2007a,b), yang<br />
menyimpulkan bahwa seleksi kembar dapat meningkatkan efisiensi produksi pada sapi.<br />
Indonesia juga mempunyai sapi sebagai spesies asH Indonesia yang juga mempL va;<br />
potensi kembar yang belum didokumentasikan. Oleh karena itu potensi ini perlu dikemba<br />
pada sapi yang ada di Indonesia. Dari data sapi dengan fertilitas yang rendah, maka d<br />
perbaikan management, pemberian pakan yang baik, sapi betina terseleksi disamping itu pe<br />
dibarengi dengan usaha untuk menaggulangi kendala lahir kembar, effisiensi perkembang<br />
biakan akan meningkat dengan cepat.<br />
Dari uraian diatas, perlu ditambahkan informasi tentang keunggulan dan hambatan atau<br />
endala kelahiran kembar. Keunggulannya yaitu sapi dapat menghasilkan 2 pedet per tahun,<br />
dapat meningkatkan efisiensi perkembang biakan, dapat meningkatkan pendapatan petani,<br />
dapat memperpendek lama bunting, kenungkingan akan ada investor yang akan berminat<br />
untuk investasi pada petemakan sapi. Disamping keuntungan dan keunggulan dari lahir kembar<br />
j ga menimbulkan hambatan dan kendala.<br />
12
Hambatan dan kendala (Kirkpatrick, 2002) yang akan dihadapi yaitu meningkatnya<br />
angka kematian pedet, meningkatnya mal-presentasi fetus, meningkatnya salah letal fetus<br />
dystocia), meningkatnya lahir muda dan abortus, meningkatnya induk yang meninggalkan<br />
anaknya (tidak mau menyusui anaknya), meningkatnya retensio plasenta, menyebabkan<br />
~eemartin pada pedet lahir kembar dengan jenis kelamin berbeda dan memperpanjang interval<br />
Dunting setelah melahirkan.<br />
Untuk itu diperlukan kesiapan untuk. menanggulangi hambatan dan kendala diatas<br />
(Kirkpatrick, 2002) yaitu dengan pemberian makanan yang ber energi tinggi pada akhir<br />
I
III. TUJUAN DAN MANFAAT <br />
3.1 Tujuan<br />
a. Merakit teknologi sistem reproduksi sapi berpotensi beranak kembar (Jarak beranak s<br />
12 bulan) pengulangan kelahiran kembar (~ 50%)<br />
b. Menyusun formluasi ransum berbahan loka! Untuk PBBH ~ 0,4 Kg Pedet Pra Sapih<br />
3.2 Manfaat<br />
a. Meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan petani<br />
b. Mensukseskan program swasembada daging 2014<br />
c. Meningkatkan dinamika perekonomian daerah berbasis sektor peternakan<br />
d. Meningkatkan jumlah sapi dengan kelahiran kembar<br />
e. Mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan peternakan<br />
14
IV. METODOLOGI <br />
-<br />
4.1 Pendekatan<br />
Kegiatan ini merupakan suatu pendekatan menyeluruh guna mendapatkan teknologi<br />
reproduksi yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembar dan teknologi pakan berbahan lokal<br />
untuk anak sapi pra sapih. Penelitian berbentuk--kegiatan lapangan yang melibatkan beberapa<br />
orang petemak kooperator. Dalam hal .tersebut petemak kooperator dipilih berdasarkan<br />
pertimbangan sebagai berikut : bersedia bekerjasama dan membuat perjanjian tertulis, memiliki<br />
sapi beranak kembar atau keturunan sapi beranak kembar, memiliki anak sapi berumur < 4<br />
bulan, dan menyediakan waktu serta tenaga untuk mendukung keberhasilan kegiatan.<br />
4.2 Tempat Dan Waktu<br />
Pengkajian telah dilakukan pada dua kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten 50<br />
Kota (Jorong 8ukit Apit dan Balubus, Kecamatan Sungai Talang) dan Kabupaten Agam<br />
(Kenagarian Panampung, Kecamatan IV Angkek). Waktu penelitian adalah selama tahun 2010<br />
mulai bulan Februari sampai November 2010.<br />
4.3 Pelaksanaan Kegiatan<br />
a. Pengkajian Teknologi Reproduksi (Jarak beranak S 12 bulan) Pengulangan Kelahiran<br />
Kembar(~ 50%)<br />
Pengkajian menggunakan 20 ekor sapi betina (minimal telah melahirkan 1 kali). Dalam<br />
hal tersebut, sapi betina akan diberikan perlakuan reproduksi dengan tahapan sebagai berikut:<br />
No. Uraian Kegiatan Waktu<br />
1 PGF 5 cc 1 M Hari ke 1<br />
2 PGF 5 cc 1M Hari ke 11<br />
3 FSH ke-1 (0,5 cc Pagi dan sore) Hari ke 22<br />
4 FSH ke-2 (0,5 cc pagi dan sorel Hari ke 23<br />
5 FSH ke-3 (OSee pagi dan sorel Hari ke 24<br />
6 Kawin (18 2 kali) Hari 24-27<br />
7 Pemeriksaan CL Hari ke 19 setelah kawin/lB<br />
8 PKB Han ke 90 setelah kawain/IB<br />
Dosis pemberian hormon FSH masing-masing 3 cc yang dlberikan secara selama tiga<br />
-.ari berturut-turut setiap pagi dan sore dengan dosis menurun 0,6 ee, 0,5 ec dan 0,4 cc setiap<br />
.ali suntik. Kemudian sapi betina dikawinkan dengan sistem perkawinan inseminasi buatan (IB)<br />
5ebanyak 2 kali yaitu 10 jam setelah birahi, dan 5 jam kemudian setelah di lB.<br />
Selama kegiatan perlakuan reproduksi sapi betina diberikan pakan tambahan. Bahan<br />
:lakan merupakan bahan lokal yang tersedia in-situ terdiri dari dedak, jagung, bungkil kelapa,<br />
15
tepung ikan, mineral dan garam. Pakan tambahan akan diformulasi dengan kandungan protein<br />
12 - 15 persen. Pemberian pakan ta mbahan sebanyak 1 persen berat badan per ekor per hari<br />
atau rata-rata 2 -<br />
3 kg. Pakan hijauan tetap dibelikan seperti biasa yakni 10 persen berat<br />
badan. Pemberian hijauan dilakukan dengan metode cut and curry namun pada saat tertentu<br />
sapi akan dilepas untuk mencari sendiri kebutuhan hijauannya. Air minum diberikan secara adlibitum<br />
pada tempat khusus yang disediakan. Pemberian hijauan dilakukan dua jam setelah<br />
pemberian pakan tambahan dan diberikan dua kali sehari setiap pagi dan sore. Parameter<br />
yang diamati meliputi : pengamatan birahi dan jumlah sapi betina bunting.<br />
b. Pengkajian Formulasi Ransum 8erbahan Lakal (P88H ~ 0, 4 Kg/han) Untuk Pedet Pra Sapih<br />
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAl) terdiri dari 4 ulangan dan 4<br />
periakuan. Materi terdiri dari 16 ekor anak sapi prasapih yang berumur kira-kira 3 bulan. lama<br />
pengamatan adalah 3 (tiga) bulan dan masa adaptasi terhadap pakan selama 1 bulan.<br />
Pemberian pakan tambahan terhadap anak sapi adalah 1 % berat badan. Data yang didapatkan<br />
selama penelitian akan diolah secara statistik. Perlakuan yang berbeda nyata akan diuji lanjut<br />
dengan menggunakan Duncan. Pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling dimana<br />
sapi yang dijadikan sebagai materi penelitian dalam kondisi awal yang relatif seragam.<br />
Penetapan perlakuan adalah berdasarkan berat badan yang diharapkan tidak mempunyai selisih<br />
terlalu jauh pad a awal perlakuan. Penimbangan ternak dilakukan menggunakan timbangan<br />
digital. Selama kegiatan penelitian, penimbangan dilakukan setiap bulan sedangkan konsumsi<br />
pakan diamati setiap hari oleh peternak. Perlakuan adalah sebagai berikut :<br />
No. Uraian R1 R2 R3 R4<br />
1. Bangsa sapi Simental Simental Simental Simental<br />
2. Umur sapi (bin) ± 3 bulan ± 3 bulan ± 3 bulan ± 3 bulan<br />
3. Hijauan Jerami Fermentasi Jerami Fermentasi Rumput (10%) Rumput (l OOk )<br />
4. Pakan tambahan Dedak45% Dedak35% Dedak 35% Dedak 35%<br />
Bungkil Sawit 35% B. Sawit 30% B. Sawit 30% . B. Sawit 30%<br />
B. Kedelai 10% KKFP 20% KKFP 20% KKFP 20%<br />
T. l kan 5%, B. Kedelai 5% B. Kedelai 10% T. Ika n 10%<br />
Mineral 5% T. lkan 5% Minera l 4% Minera l 4%<br />
(Formulasi Mineral 4% Garam 1% Garam 1%<br />
r petemak) Garam 1%<br />
_:J. Protein (0/0) 13-14 13-14 1314 13-14<br />
3. Air minum Adlibitum Adlibitum Adlibitum Adlibitum<br />
.. Pemberian pakan<br />
- Hljauan 2 !
V. HASIL DAN PEMBAHASAN <br />
a. Pengkajian 51'stem Reproduksi (Jarak beranak S 12 bulan) Pengulangan Kelahiran Kembar<br />
(~ 50%)<br />
1. Seleksi Sap; Betina<br />
Pelaksanaan seleksi sapi betina melibatkan petugas IB setempat dan tenaga kesehatan<br />
hewan dari BPPV Regional II Baso. Dalam proses seleksi sapi betina hal-hal yang diamati antara<br />
lain kondisi alat reproduksi, kondisi tubuh ternak (skor 1-5), kesehatan dan kesediaan peternak<br />
sebaga; kooperator. Pada saat ini kepada peternak dijelaskan tentang maksud dan tujuan<br />
program serta resiko-resiko yang timbul. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi<br />
tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Untuk mendapatkan 20 ekor sapi betina maka seleksi<br />
dilakukan terhadap 35 ekor sapi betina diketahui ciri-ciri dan kondisi fisiknya berdasarkan<br />
informasi petugas. Hasil pengamatan terlihat pada tabel 2 berikut :<br />
Tabel 2 : Pemeriksaan CL (Corpus Luteum) dan Fisik Ternak Dalam Rangka Seleksi Sapi Betina<br />
No. Lokasi lumlah Temak Kondisi CL Skor body (1-5)<br />
(ekor) KcI Nor Bsr 1 2 3 4 5<br />
1. Jrg. Lundang 16 3 11 2 - 5 8 3 -<br />
2. Jrg. Bonjo 7 1 6 - - - ) 6 - I - I<br />
3. Jrg. Sei. Beringin 4 4 - - - - I 4 I -I <br />
I<br />
4. Jrg. 51. Lauik 3 2 1 - 3 I - I - I - ,<br />
I<br />
~<br />
5. Tjg. Alam 5 1 4 1 - 4 I -I -<br />
Hasil seleksi memperlihatkan bahwa kondisi fisik sebagian besar sapi betina memiliki<br />
skorbody 3 dan alat reproduksi (Corpus Luteum) normal. Sapi betina dengan kondisi baik<br />
tersebut digunakan sebagai temak ujicoba perlakuan sistem reproduksi berpotensi beranak<br />
kembar (Nama peternak dan alarnat pada larnpiran 1). Berdasarkan data perneriksaan kondisi<br />
reproduksi sapi betina didapatkan sebanyak 21 ekor sapi betina dengan rincian jrg. Lundang 11<br />
ekor, Jrg. Bonjo 6 ekor dan Tjg. Aiam 4 ekor. Sedangkan sapi betina yang terdapat dua tempat<br />
lainnya dieliminir dan tidak digunkan untuk tahap selanjutnya. Pada urnumnya sap; betina<br />
terseleksi tersebut pernah beranak antara 2 - 4 kali narnun belurn mempunyai sejarah kelahiran<br />
kembar (nama peternak terlampir).<br />
17
2. Pemberian Pakan Tambahan dan Obat (acing<br />
Untuk kondisi sapi betina terseleksi agar tetap baik dan sehat selama ujicoba sistem<br />
reproduksi maka dilakukan pemberian pakan tambahan sebanyak 1% berat badan. Pakan<br />
tambahan diformulasi dengan kandungan protein 13,5 persen menggunakan bahan pakan lokal<br />
yang tersedia. Komposisi pakan tambahan adalah dedak 40%, bungkil sawit 35%, jagung 10%,<br />
bungkil kedelai 7%, tepung ikan 3%, mineral 4% dan garam 1%.<br />
Sebelum pemberian pakan tambahan ini juga dilakukan penyuntikan obat cacing pada<br />
masing-masing sapi betina terseleksi. Pemberian obat cacing bertujuan untuk mempertinggi<br />
kesehatan ternak dan memperkuat pengaruh makanan terhadap pemeliharaan kondisi tubuh<br />
ternak. Pertimbangan pemberian pakan tambahan tersebut berdasarkan hasil penyidikan BPPV<br />
Baso dimana gangguan reproduksi sapi betina terutama Sumatera Barat diakibatkan minimnya<br />
pemberian pakan berkualitas. Kondisi demikian cukup mengkawatirkan terhadap keberhasilan<br />
pengkajian sistem reproduksi bila tidak diantisipasi dengan pemberian pakan tambahan<br />
berkualitas.<br />
3. Suntik hormon PGf2£<br />
Proses perkawinan terhadap sapi betina dapat berlangsung bila temak dalam kondisi<br />
birahi yang dicirikan sebagai berikut : keluar lendir dari vulva, temak gelisah dan aktif bersuara.<br />
Siklus birahi secara normal terjadi setiap 21 hari namun siklus bisa dipercepat dengan<br />
penyerentakan menggunakan hormon PGF2£. Pada pengkajian sistem reproduksi sapi betina<br />
berpotensi beranak kembar penyerentakan birahi dilaksanakan 2 kali dengan jarak 11 hari. Hal<br />
ini dimaksudkan supaya sapi betina alam kondisi siap bereproduksi ketika dikawinkan. Hasil<br />
penyerentakan birahi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :<br />
Tabel 3 : Keragaan Kondisi Sapi Betina Setelah Suntik PGF2£ ke I dan II<br />
No. Lokasi Jumlah Sapi Hari Tlmbul Birahi Setelah PGF I dan II<br />
(ekor) 1 2 3 4 1 2 3 4<br />
1. Jrg. Lundang 11 - 6 3 2 - 5 5 1<br />
2. Jrg. Sonjo 6 - - 5 1 - 4 1 1<br />
5. TjC). Afam 4 - - 4 - - - 4 -<br />
Secara umum berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa penyerentakan birahi dengan<br />
'1ormon PGF2£ berpengaruh positif terhadap timbulnya birahi sapi betina. Munculnya tanda<br />
-:.anda birahi tidak serentak namun bervariasi antara hari ke 2 sampai ke 4, sedangkan<br />
:erbanyak di hari ketiga setelah penyuntikan harmon. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa<br />
18
espon alat reproduksi sapi beti a t adap hormon cukup tinggi dan kondisi sistem reproduksi<br />
sapi betina yang telah terselekst cukup baik.<br />
3. Suntik hormon FSH<br />
Tahap berikut dari proses sistem reproduksi berpotensi menghasilkan kelahiran<br />
kembar adalah penyuntikan hOnTlOn FSH. Penggunaan hormon ini bertujuan untuk<br />
memperbanyak folikel yang matang sehingga diharapkan saat perkawinan lebih dari satu sel<br />
telur dapat dibuahi. Penyuntikan hormon FSH dilakukan selama tiga hari berturut-turut setiap<br />
pagi dan sore dan dimulai pada hari kesebelas setelah terlihatnya tanda birahi sesuai hasil<br />
PGF2£. Dosis penyuntikan diatur menurut dosis menurun yaitu 0,6, 0,5 dan 0,4. Setelah tiga<br />
hari pelaksanaan suntik FSH maka dilakukan pengamatan birahi dan perkawinan. Keragaan<br />
perkembangan reproduksi temak sapi setelah penyuntikan hormon FSH dapat dilihat pada<br />
tabel 4 berikut :<br />
Tabel 4 : Keragaan Sapi Setina Setelah Penyuntikan Hormon FSH<br />
No. Lokasi Jumlah Sapi Hari IB Setelah Suntik FSH<br />
(ekor) 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1. Jrg. Lundang 11 - - - - 6 2 - -<br />
2. Jrg. Bonjo 6 - - - 4 - - - -<br />
5. Tjg. Alam 4 - - - - 2 2 - -<br />
Serdasarkan tabel 4 dapat dilihat sapi betina pertama dikawinkan pada 4 hari setelah<br />
suntik FSH, kemudian hari ke 5 dan hari ke 6. Hasil memperlihatkan bahwa proses perkawinan<br />
dilakukan mengikuti siklus birahi secara alami yang terjadi pada hari ke 18 - 21. Namun tidak<br />
semua sapi betina dapat di inseminasi buatan (IB) hanya sebanyak 16 ekor, sedangkan sisanya<br />
5 ekor tidak berhasil memperlihatkan tanda-tanda birahi setelah FSH. Kondisi demikian terjadi<br />
karena kegagalan pematangan corpus lutheum sehingga proses perkawinan tidak dapat<br />
dilaksanakan sebagaimana mestinya.<br />
Perkawinan secara inseminasi buatan terhadap sapi betina dilaksanakan dua kali<br />
dengan selang waktu 5 jam. Pelaksanaan IB pertama yaitu 6-8 jam setelah tanda-tanda birahi<br />
muncul. Semen beku yang digunakan adalah berasaI dari BIB lembang yang diadakan oleh<br />
petugas inseminator. Untuk mengetahui sa pi betina dalam keadaan bunting kemudian<br />
dilaksanakan pemeriksaan kebuntingan (PKB) .<br />
19
. Pengkajian Formulas; Ransum 8erbahan Lakal (P88H ~ 0, 4 Kg/harij Untuk Pedet Pra<br />
Sapih<br />
1. Lokasi dan Kooperator<br />
Kegiatan pengkajian dilakukan di Kenagarian Sungai Kalang pada dua Jorong yaitu<br />
Jorong Bukit Apit dan Jorong Balubus. Penyebaran kooperator pada masing-masing jorong<br />
dapat dilihat pada tabel 5 berikut dan nama-nama peternak terdapat di lampiran 2.<br />
Tabel 5 : Distribusi Kooperator Untuk Pengkajian Anak Sapi Prasapih<br />
No. Uraian Jumlah Petemak Jumlah Sapi<br />
(orang)<br />
(ekor)<br />
1. Jorong Bukit Apit 6 11<br />
2. Jorong Balubus 5 5<br />
2. Pertambahan Berat Badan<br />
Tabel 6 menyajikan data pertambahan berat badan anak sapi yang diberikan pakan<br />
tambahan dengan dan tanpa penggunaan kulit kakao fermentasi dan pengamatan selama 90<br />
hari.<br />
Tabel 6 : Rata-rata pertambahan berat badan anak sap; prasapih yang diberikan perlakuan<br />
pakan dengan formula berbeda<br />
No. Uraian BB Awal I II III PBB<br />
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg )<br />
1. Formula A 136,38 153,12 165,5 188 51,62<br />
2. Formula B 135,75 153,5 172,62 193,5 57,75<br />
3. Formula C 132 142 149,75 168,5 36,S<br />
4. Formula D 135,5 147,62 160,62 176,87 41,37<br />
I<br />
Hasil pada tabel 6 memperlihatkan bahwa perlakuan formula pakan tambahan<br />
memberi pengaruh terhadap pertambahan berat badan anak sapi. Perlakuan formula pakan<br />
tambahan formula B (20% Kulit kakao fermentasi) tertinggi dalam pertambahan berat badan.<br />
Hasil tersebut lebih baik dibandingkan formula A (formula petemak tanpa kulit kakao<br />
fermentasi) dan formula C serta 0 dimana formulasi pakan ini mengandung 20% kulit kakao<br />
fermentasi sama dengan Formula B.<br />
Pertambahan berat badan tertinggi pada pakan tambahan formula 8, ransum yang<br />
diformulasi dengan komposisi 20% kulit kakao fermentasi tersebut menggunakan sumber<br />
20
protein pakan lengkap hewani dan nabati (tepung ikan dan bungki/ kede/aJ). Kondisi demlkian<br />
berbeda dengan ransum formula C dan 0 meski memiliki kandungan 20% kulit kakao dalam<br />
pakan tambahan namun memakai salah satu sumber protein saja. Formula A merupakan pakan<br />
tambahan yang biasa digunakan peternak. Pakan tambahan belum diformulasi dengan bahan<br />
pakan lokal kulit kakao fermentasi.<br />
Berdasarkan hasil dlatas dapat disimpulkan bahwa kulit kakao fermentasi bila<br />
diformulasi sebagai pakan tambahan hendpklah menggunakan bahan-bahan pakan sumber<br />
protein (nabati dan hewani) dengan komposisi seimbang. Formula pakan tambahan B dapat<br />
dijadikan sebagai ransum altematif berbiaya murah tertutama bagi peternak mengingat<br />
ketersediaan limbah kulit kakao melimpah di lokasi pengkajian.<br />
3. Pertambahan Berat Badan Harian/ekor<br />
Tabel 7 memperlihatkan data pertambahan berat badan anak sapi ya 9 c':)efloca<br />
pakan tambahan dengan formulasi berbeda.<br />
Tabel 7 : Rata-rata pertambahan berat badan harian anak sapi yang diberlkan paka n ta mbahan<br />
dengan formulasi berbeda<br />
No. Uraian BB Awal BB Akhir PBB/hari/ ekor<br />
(Kg) 90 hari (Kg) (Kg)<br />
1. Formula A 136,38 188 0,57<br />
2. Formula B 135,75 193,5 0,64<br />
3. Formula C 132 168,5 0,40<br />
4. Formula 0 135,5 176,87 0,46<br />
Hasil memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif formulas; ransum terhadap<br />
pertambahan berat badan harian per ekor anak sapi prasapih. Formalasi B memberikan<br />
pertambahan berat badan harian tinggi yakni 0,64 kg/ekor/hari. Formulasi A (peternak)<br />
memberikan pertambahan berat badan harian 0,57 kg/ ekor/hari lebih tinggi dibandingkan<br />
formulasi C dan D.<br />
Berdasarkan hasH tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan kulit kakao<br />
ferrnentasi yang diformulasi sebesar 20% pada pakan tambahan memberikan kenaikan berat<br />
badan tertinggl. Formula A (petemak) memberikan kenaikan berat badan yang lebih baik<br />
dibandingkan formula C dan D. Dari 4 formulasi pakan tambahan yang diujicoba selama<br />
pengkajian, pakan tambahan dengan 20% kulit kakao fermentasi memberikan kenaikan berat<br />
badan harian tertinggi yakni 0, 67 kgJekor/hari .<br />
21
VI. KESIMPULAN DAN SARAN <br />
6.1 Kesimpulan<br />
1. Seleksi sapi betina berhasil menjaring 21 ekor temak untuk ujicoba sistem reproduksi<br />
berpotensi menghasilkan kelahiran kembar<br />
2. Suntik hormon PGF2£ pada 21 ekor sapi betina positif menggertak birahi berkisar 2 - 3<br />
setelah penyuntikan.<br />
3. Superovulasi dengan hormon FSH berhasil pada 16 ekor sapi betina yang diinseminasi<br />
buatan antara 4-6 setelah aplikasi<br />
4. Formulasi pakan tambahan dengan perlakuan B memberikan pertambahan berat badan<br />
tertinggi yakni 57,75 kg selama 90 han pengamatan.<br />
5. Formula pakan tambahan dengan perlakuan B juga memberikan kenaikan berat badan<br />
harian tertinggi yakni 0,64 kg/ekor/hari<br />
6. Pakan tambahan yang diformulasi dengan kakao fermentasi hendaklah menggunakan bahan<br />
pakan dengan sumber-sumber protein lengkap hewani dan nabati.<br />
6.2 Saran<br />
Dalam rangka mencapai hasil sesuai harapan maka pengkajian ini perlu dilanjutkan<br />
dengan pengamatan hasil dan aplikasi perlakuan hormonal terhadap sapi betina yang akan<br />
akan lahir tahun 2011. Untuk menjaga kesehatan ternak selama masa kebuntingan dan<br />
persalinan maka diperlukan juga pemberian pakan tambahan (flushing) dua bulan sebelum dan<br />
sesudah melahirkan. Pada masa datang perlu juga pengkajian pakan anak sapi pra sapih dan<br />
hasil kelahiran kembar.<br />
22
DAFTAR PUSTAKA <br />
Arthur G.H., Noakes D.E., Pearson H. and Parkinson TJ. 1996. Veterinary Reproduction and<br />
Obstetrics. WB Saunders Co Ltd. :79.<br />
Asdi Agustar dan jaswandi, 2006. Melirik Potensi Sapi Pesisir Sebagai Penghasil Daging di<br />
Sumatera Barat. Prosiding Seminar Na-sional di Padang; "Pengembangan temak di<br />
Sumbar. Balai Besar Pengkajian dan Pengembagan TeknoJogi Pertanian. Badang Utbang<br />
Dept.Pertanian.<br />
BamuaJim, A dan Wirdahayati, 2006. Peran Teknologi Dalam Pengembangan Sapi Lokal di<br />
Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional di Padang; "Pengembangan temak di<br />
Sumbar. Balai Besar Pengkajian dan Pengembagan Teknologl Pertanian. Badang Litbang<br />
Dept.Pertanian.<br />
E>inas Peternakan Propinsi Sumatera Barat. 2007. Program Pengembangan Peternakan Tahun<br />
2007. Dinas Petemakan Sumatera Barat Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Padang.<br />
Echtemkamp, S.E. and Gregory, K.E. 2002. Reproductive, growth, feedlot and carcass traits of<br />
twin vs single births in cattle. Journal ofAnimal Science. aO(E. Suppl. 2):E64-E73.<br />
Echtemkamp, S.E., Cushman, R.A., Allan, M.F., ThaI/man, R.M., Gregory, K.E. 2007a. Effects of<br />
ovulation rate and fetal number on fertility in twin-producing cattle. Journal ofAnimal<br />
Science. 85(12):3228-3238.<br />
Echtemkamp, S.E., Thallman, R.M., Cushman, R.A., Allan, M.F., Gregory, K.E. 2007b. Increased<br />
calf production in cattle selected for twin ovulations. Journal ofAnimal Science.<br />
85(12):3239-3248.<br />
Hosen, N, Yanovi Hendri, Numayetti, Aryunis, Agusfiwraman (2009) Laporan Tengah Tahun<br />
Identlfikasi dan Karakterlsasl Potensl Sapl pesisir Beranak Kembara. BPTP Sumatera<br />
Barat<br />
Kirkpatrick, B.W. 2002. Management of twinning cow herds. Joumal ofAnimal Science. Suppl.<br />
2: E14-E18.<br />
Wirdahayatl R.B dan A.Bamualim, 2006. Profil Petemakan Sapi dan kerbau di Propinsi Sumatera<br />
Barat. Prosldlng Seminar Nasional Peternakan BPT Sumatera Barat<br />
23
Lampiran 1 : Nama-nama petemak kooperator Sapi Betina<br />
No. Peternak Alamat<br />
1. Arief Suherman Jorong Lundang<br />
2. Arief Suherman Jorong Lundang<br />
3. Arief Suherman Jorong Lundang<br />
4. Amnis Joron.g Lundang<br />
5. Amnis Jorong Lundang<br />
6. Bujang St. 8asa Jorong Lundang<br />
7. 8ujang St. Basa Jorong Lundang<br />
8. Putra Maryulis Jorong Lundang<br />
9. Des Ateng Jorong Lundang<br />
10. Boby Jorong Lundang<br />
11. Maizar Jorong Lundang<br />
12. Erli Ibrahim Tanjung Alam<br />
13. Erti Ibrahim Tanjung Alam<br />
14. Erli Ibrahim Tanjung Alam<br />
15. Nasrul Tanjung Alam<br />
16. Ertis Jorong Bonjo<br />
17. Delius Jorong Bonjo<br />
18. Oelius Jorong Bonjo<br />
19. Erni Jorong Bonjo<br />
20. Maston Jorong Bonjo<br />
21. Erwin Jorong Sonjo<br />
24
0 _ _ •<br />
Lampiran 2 : Nama-nama petemak kooperator Pengkaj ian Anak Sapi Prasapih<br />
No.<br />
Petemak<br />
1. Hendra (3 ekor) Jorong Bukik Apik<br />
2. Haji Akmal (3 ekor)<br />
Jorong Bukik Apik<br />
3.<br />
Lia (2 ekor)<br />
Jorong Bukik apik<br />
4. Mahar Jorong Balubus<br />
5. Yal Jorong Balubus<br />
6. Yalmin Jorong Balubus<br />
7. Dedi<br />
Jorong Balubus<br />
B. On Jorong Balubus<br />
9. Depi Jorong Bukik Apik<br />
10. Dt. Gindo Sati<br />
11. Jhon<br />
- --_.., - --<br />
Jorong Bukik Apik<br />
Jorong Bukik apik<br />
Alamat<br />
25
Lampiran 3 : Data Penimbangan Anak. Sapi Prasapih<br />
No. Ur ai a n SS Awal 11mbang I Timbang IT 11mbang III PBB/ekor PBB/ hari<br />
Kg Kg Kg Kg (90 Hari) Kg/ hari<br />
Kg<br />
1. Formula R1<br />
- Hendra 136 157 177 204 68 0. 75<br />
.,<br />
- Hendra 149 164 174 190,5 41,5<br />
I 0,46<br />
- Hendra 105 124 133.5 142,5 37, 5 0,42<br />
- H. Akmal 155.5 1678 177.5 215 59,5 0,00<br />
2.<br />
13638 153,12 1655 188 51,62 I 0,57<br />
Formula R2<br />
- H. Akmal 137 160 180 197 60 -, ,<br />
- H. Akmal 150 163 171 90<br />
n<br />
:~<br />
- Ua 104 124 144.5 169 65 - 72<br />
- lia 152 167 195 21.8 56 : - 3<br />
135,75 153,5 I In 62 193.5 <br />
~ /,I -:; 0,64 j<br />
3. Formula R3 I<br />
Mahar 136 143 154 In - ; .!<br />
"2' -:: •.<br />
Yal 154.5 160 171 186 - - - ..<br />
I - -<br />
Yalmin 150 160 168 183 33 ~ T37<br />
Depi 87.5 105 106 133 ~5 . 5 0,50<br />
132 142 14975 168 5 36 5 0,40<br />
4. Formula R4<br />
On 134.5 144.5 152 169,5 35 0,39<br />
Depi 124 144 159 179 55 0,61<br />
Dt. Gindo Sati 139.5 148 169.5 169,5 30 0,33<br />
Jhon 144 154 162 1895 45 5 050<br />
1355 147,62 160,62 176 87 4137 0,46<br />
I<br />
26