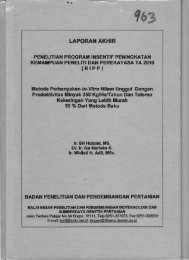pengembangan desain tekno-sosial untuk peningkatan ... - KM Ristek
pengembangan desain tekno-sosial untuk peningkatan ... - KM Ristek
pengembangan desain tekno-sosial untuk peningkatan ... - KM Ristek
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LAPORAN AKHIR <br />
-<br />
PENGEMBANGAN DESAIN TEKNO-SOSIAL UNTUK <br />
PENINGKATAN KECUKUPAN PANGAN <br />
DI TINGKAT RUMAH TANGGA <br />
Oleh: <br />
Agus Heri Purnomo <br />
Siti Hajar Suryawati <br />
Rizky Muhartono <br />
<br />
BAlAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN <br />
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN <br />
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN <br />
2010
· ...<br />
LEMBAR PENGES'<br />
IiIR<br />
Judul Kegiatan Riset<br />
Penanggung Jawab<br />
a. Nama<br />
b. Pangkat/Gol<br />
c. Jabatan<br />
Unit Kerja<br />
Status<br />
Pagu Anggaran<br />
c1. Struktural<br />
c2. Fungsional<br />
Tahun Anggaran<br />
Sumber Anggaran<br />
Pe ge e Sos ial Untuk Peningkatan<br />
Kec o-a ~c: ~g.:- . n g
· .. <br />
KATA PENGANTAR <br />
Konsep ketahanan pangan sudah mulai dikenal sejak Repelita VI, dan kemudian diperkuat<br />
keberadaannya di dalam Undang-Undang tentang Pangan No.7 tahun 1996.<br />
Pada tingkat<br />
internasional ketahanan pangan telah dibicarakan pada World Food Summit di Roma, dan<br />
disepakati suatu Policy Statement Toward Universal Food Security.<br />
Komitmen pemerintah<br />
tentang ketahanan pangan semakin jelas dengan dicantumkannya pada sasaran jangka panjang<br />
pembangunan pangan di Indonesia.<br />
Pemahaman dan antisipasi kebijakan strategis ketahanan pangan akan semakin mantap<br />
bila didukung oleh hasil kajian yang menganalisis konsumsi secara menyeluruh pada tingkat<br />
rumah tangga. Permasalahannya, meskipun potensi sumberdaya perikanan sangat besar, sejauh<br />
ini perannya belum dimaksimalkan sebagai salah satu sumber penting dalam pemenuhan<br />
kebutuhan pangan masyarakat. Sebagian penduduk telah mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang<br />
cukup besar, namun sebagian lain sangat rendah asupan ikannya. Jarak sentra produksi dari<br />
konsentrasi sebagian konsumen dan sistem distribusi yang tidak mendukung merupakan salah<br />
satu penyebab rendahnya akses dan keterjangkauan ikan dan prod uk perikanan bagi konsumen.<br />
Salah satu solusi potensial yang perlu dikaji adalah mendekatkan lokasi produksi dengan<br />
lokasi konsumen. Penelitian <strong>pengembangan</strong> <strong>desain</strong> <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> <strong>untuk</strong> <strong>peningkatan</strong> kecukupan<br />
pangan di tingkat rumah tangga, merupakan salah satu kegiatan dari program insentif<br />
<strong>peningkatan</strong> kemampuan peneliti dan perekayasa tahun anggaran 2010. Penelitian difokuskan<br />
pada wilayah yang berbasis pada perikanan pantai, perikanan budidaya dan pertanian di<br />
Kabupaten Kulon Progo.<br />
Pada kesempatan ini penyusun dan segenap anggota tim peneliti yang terlibat tidak lupa<br />
menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada berbagai pihak yang telah memberikan<br />
kemudahan sehingga memperiancar jalannya riset sehingga kajian ini dapat terselesaikan dengan<br />
baik. Semoga kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dapat terus berianjut hingga waktu<br />
yang akan datang dan hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dalam<br />
mendukung <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan sektor peri kanan, dan juga bermanfaat bagi seluruh<br />
masyarakat Indonesia.<br />
Jakarta, Nopember 2010<br />
-<br />
Tim Peneliti
· .. <br />
EXECUTIVE SUMMARY <br />
Introduction<br />
Refering to the resources capacity, Indonesian fisheries sector has the potential to<br />
contribute at least one-third of the recommended protein allowance. This is particularly true if<br />
two problems are taken care of: supply and demand problems. On the supply side, the underlying<br />
problem comprises the production, distribution and product loss. On the demand side, the<br />
problem is primarily associated with disparity in income and preferences. These two problems<br />
lead to an idea of shifting fish production concentrations closer to the consumers: household<br />
fishery for household level food security. Regognizing this, the current research proposal is meant<br />
to answer the following relevant open quenstions: (1) What is the best techno-social design of<br />
the so-called<br />
a household fishery for household level food security (2) What strategies are<br />
normally available for people to go about implementing such a design given their respective<br />
socio-technical circumstances, and (3) What are best roles that the government can and should<br />
play in order that people can maximize their potentials in securing access to food following such a<br />
design.<br />
Methodology<br />
The design, which is to be the primary expected output of the research is expected to<br />
equip policy makers with an effective tool to accelerate the national food security programs. The<br />
study will follow the case study approach, wherein two locations are selected to respectively<br />
represent aquaculture and capture fisheries. In those locations, the following steps will be carried<br />
out: (1) Quick survey to identify key variables of the development of household fishery for<br />
household level food security, (2) Desk study focusing on integrating variables into a draft design,<br />
(3) Extended field survey based on previously identified variables, (4) Communicating the draft to<br />
-<br />
key persons and collecting feed back, (5) Reconstructing the design, and (6) writing report.<br />
Result and Discussion<br />
This research was conducted in Kulon Progo District of The Special Territory of Yogyakarta<br />
(DIY) which has an administrative area of 58,672.54 Ha or 586,72 Km 2 • Geographically, this<br />
location is situated between 7°38'42" - T38'42" South Latitudes and 110°1'37" - 110°16'26" East<br />
-<br />
-<br />
longitude. Kulon Progo in the Javanese means to the west of Progo River. On the east, the district<br />
is bordering with Sleman and Bantul Districts, on the north with Magelang District, on the west<br />
with Purworejo Districts and on the south with the I dian Ocean. Three villages in the districts<br />
were purposively selected as the study locatio s: h ar Illage (predominantly aquaculture),
· ..<br />
Sogan Village (predominantly agriculture) and Karangwuni Village (predominantly capture<br />
fishery).<br />
Social-Ecological System<br />
The social-ecological system in the study locations are formed of 4 (four) components,<br />
namely: (A) natural resource, (B) resource user, (C) infrastructure provider and (D) public<br />
infrastructure. It was identified that the resource exists in terms of coastal water, aquaculture<br />
ponds and agricultural land. Users are fishers, aquaculturist and farmer. Infrastructure providers<br />
are different in every village; in Karangwuni, there are economic institutions such as Micro finance<br />
institution (L<strong>KM</strong>) anf farmer groups (Gapoktan). In Sogan, the existing economic institutions are<br />
Binangun Microfinance, Panca Manunggal Microfinance, Village Credite Bank (BKD), Productive<br />
Economic Enterprise, and Eko Martani Cooperatives (exclusive membership) and farmer group<br />
(Gapoktan). In Kulwaru, economic institutions consists of Village Microfinance (L<strong>KM</strong>D), People<br />
Independence Council (B<strong>KM</strong>), Village People Council (LMD), and Village People Development<br />
Council (LPMD). In additions to the village institions, people also have the access to financial<br />
institutions at the district and sub-district levels.<br />
Food Security Condition<br />
The commodity of focus in the present study of food security were preference on fishery<br />
- products (preference rank on animal products, the reason of selecting animal products, the<br />
decision on the selected animal product, the frequency of fish consumption, the number of family<br />
member consuming fish, and the availability of fish products), the stability of availability<br />
(affordable fish price and the influence of season), quality and safety (knowledge), and<br />
accessibility factor.<br />
The condition of aquaculture lIariables to support household lellelfood security<br />
The condition of aquaculture variables to support household level food security consists<br />
of household and non-household variables. For non-household variables, observation on land use<br />
allocation shows that household yards are available for aquaculture. Infrastructure and facilities<br />
are available in terms of irrigation system, transportation and a variety of supporting institutions<br />
including financial and marketing institutions.<br />
In the mean time, observation on household variables shows that household structure in<br />
the three study locations varies between cohorts of $ 40 year age, 41- 50 year age, and ~ 60 year<br />
-<br />
age. Education varies from unfinished elementary school, finished junior high, finished high school<br />
v
· ... <br />
and finished universities. The similar case is true for the observation on the occupational<br />
structure.<br />
Policy perspective<br />
The design of food security improvement through fisheries-based enterprises is very<br />
much in line with the philosophy and the objectives of the national policy on minapolitan, which<br />
deals with increasing production and<br />
improving people welfare. Minapolitan program is the<br />
program of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries which refers to the concept of zone<br />
development implemented in various locations. The District of Kulon Progo is among those<br />
locations listed in the Ministerial Decision no 32/2009 reo minapolitan locations. In the minapoitan<br />
concept, the two targets exist, namely the business system and the settlement system, wherein<br />
the issue of food / consumption is an important element.<br />
The development of food security system as studied in this research activity certainly<br />
support the implementation of minapolitan. The development of fishery-based business is part of<br />
the minapolitan concept; household business units as suggested by this research can be a<br />
significant sustainer for the function of hinterland location as referred to by the minapolitan<br />
concept. In the mean time, the target of increasing fish consumption is in line with the target of<br />
improving the settlement system.<br />
Conclusion and Policy Implication<br />
The opportunity exists to develop fishery-based business units, which are managed<br />
associated with monapolitan programs. This research propses a deSign to materialize such an<br />
opportunity. The design is basically a framework of development of fishery-based business units,<br />
which are formed of a number of important elements, both technical and social ones. Those<br />
elements are structure, type of business, selected commodity, business scale, institutional<br />
arrangement, coordination span, and the form of intervention .<br />
The deSign also includes the direction to integrate the development of business units<br />
mentioned above with minapolitan program, where these business units are to be the sustainers<br />
of hinterland zones, which will be linked with a certain minapolis. The design was also particularly<br />
aimed at a certain target of fisheries development, namely increase in fish consumption and the<br />
reduction of economic leakages in village communities.<br />
<br />
<br />
The policy implications are : 1) The local government needs to follow up the result of this<br />
research and incorporate with the local government pol icies, including the budgeting policy; and<br />
2) This result also needs to be socialized in ord er th at all relevant stakeholders have the same<br />
perspectives such that implementation can be effective.
·.. <br />
RINGKASAN EKSEKUTIF <br />
Pendahuluan<br />
Mengacu pada data potensi yang ada, sektor perikanan Indonesia berpeluang menopang<br />
ketahanan pangan, yaitu melalui kontribusi minimal sepertiga dari angka kecukupan protein. Hal<br />
ini terutama benar apabila dua masalah utama ditangani dengan baik: masalah pas ok don<br />
konsumsi. Di sisi pasok, masalah utama yang ada meliputi produksi, distribusi dan susut hasil.<br />
Sementara itu, di sisi konsumsi masalah utamanya terkait dengan kesenjangan pendapatan dan<br />
preferensi konsumen. Dua masalah ini memunculkan ide penggeseran pusat-pusat produksi<br />
perikanan kearah yang lebih dekat dengan konsumen : perikonon rumah tangga <strong>untuk</strong> ketahanan<br />
pangan tingkat rumah tangga. Sejalan dengan itu, proposal ini dimaksudkan <strong>untuk</strong> menjawab<br />
pertanyaan-pertanyaan relevan berikut ini: (1) Bagaimana <strong>desain</strong> <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> terbaik yang<br />
seharusnya dikembangkan <strong>untuk</strong> perikanan rumah tangga <strong>untuk</strong> ketahanan pang an tingkat<br />
rumah tangga tersebut; (2) Strategi apa yang tersedia bagi masyarakat pada umumnya <strong>untuk</strong><br />
mengimplementasikan <strong>desain</strong> semacam itu dalam kondisi dan situasi <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> yang mereka<br />
hadapi; dan (3) Peran terbaik apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menukung<br />
implementasi <strong>desain</strong> terse but.<br />
Metode Penelitian<br />
Desain termaksud, diharapkan dapat dijadikan sebagai alat efektif bagi pengambil<br />
kebijakan <strong>untuk</strong> mempercepat pencapaian target-target program ketahanan nasional. Penelitian<br />
ini akan mengacu pada pendekatan studi kasus, dimana dua lokasi utama dipilih, berturut-turut<br />
<strong>untuk</strong> mewakili perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di lokasi-Iokasi tersebut, langkahlangkah<br />
penelitian berikut akan dilaksanakan: (1) Quick survey <strong>untuk</strong> mengidentifikasi variabelvariabel<br />
perikanan rumah tangga <strong>untuk</strong> ketahanan pangan tingkat rumah tangga, (2) Desk study<br />
yang difokuskan pada pengintegrasian variabel-variabel tersebut kedalam draft <strong>desain</strong>, (3) Survai<br />
lapang pendalaman yang didasarkan pada varia bel-varia bel yang telah diidentifikasi pada tahapan<br />
sebelumnya, (4) Mengkomunikasikan draft tersebut kepada narasumber kunci dan<br />
mengumpulkan umpan balik, (5) penyempurnaan <strong>desain</strong>, dan (6) penulisan laporan.<br />
- Hasil dan Pembahasan<br />
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah otonom di<br />
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) denga:o luas wil ayah 58.672,54 ha atau 586,72 kmz.<br />
-<br />
Secara geografis terletak antara 7°38'42" - r 38'42" Lin -a g Selatan dan 110°1'37" - 110°16'26"<br />
Bujur Timur. Kulon Progo dalam bahasa Jawa oe ' ~r:- se'oe a. arat Sunga i Progo, wilayahnya<br />
-
terletak di sebelah barat Sungai Progo . . cL :-e:- ,'_ c-<br />
s..eb€l ah timur berbatasan<br />
dengan Kabupaten Sleman dan Kab upa12 __- Oa e a Istimewa Yogyakarta, di<br />
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten<br />
si Jawa Tengah, di sebelah barat<br />
berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Pro ' si .cwa Tengah, dan di sebelah selatan<br />
berhadapan dengan Samudra Indonesia. Pene fitian dila<br />
kan di 3 (tiga) desa, yaitu Oesa Kulwaru<br />
(Oesa berbasis perikanan budidaya), Oesa Sogan (Oesa berbasis usaha pertanian) dan Oesa<br />
Karangwuni (Oesa berbasis usaha perikanan tangkap) .<br />
Sistem Sosial-Ekologis<br />
Sistem <strong>sosial</strong>-ekologis yang terbentuk di lokasi penelitian mencakup 4 (empat) komponen<br />
pembentuk sistem yaitu: (A) sumberdaya, (B) pengguna sumberdaya,(C) penyedia prasarana dan<br />
(0) berbagai bentuk prasarana publik. Berdasarkan hasil identifikasi, sumberdaya yang dimaksud<br />
adalah dalam bentuk perairan pantai, kolam pembudidaya dan lahan pertanian. Sedangkan<br />
pengguna sumbedaya adalah masyarakat nelayan, pembudidaya dan petani. Penyedia prasarana<br />
yang berhasil teridentifikasi di lokasi penelitian berbeda-beda di setiap desa. Oi desa Karangwuni<br />
terdapat lembaga perekonomian seperti lembaga keuangan mikro (L<strong>KM</strong>) dan gabungan kelompok<br />
tani (Gapoktan). Adapun di desa Sogan lembaga perekonomian yang ada diantaranya adalah L<strong>KM</strong><br />
Binangun, L<strong>KM</strong> Panca Manunggal, bank kredit desa (BKD), Usaha ekonomi Produktif, Koperasi Eko<br />
Martani (hanya <strong>untuk</strong> anggota) dan Gapoktan. Sedangkan di desa Kulwaru lembaga<br />
perekonomian yang ada adalah lembaga keuangan mikro desa (L<strong>KM</strong>D), badan keswadayaan<br />
masyarakat (B<strong>KM</strong>), lembaga masyarakat desa (LMO), dan lembaga pembangunan masyarakat<br />
desa (LPMD). Selain di tingkat desa, masyarakat juga dapat mengakses permodalan ke berbagai<br />
lembaga yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan.<br />
Kondisi Ketahanan Pangan<br />
Kondisi ketahanan pangan yang menjadi focus dalam kajian ini adalah preferensi produk<br />
perikanan (urutan kesukaan pangan hewani, alas an memilih pangan hewani, penentuan pangan<br />
-<br />
.<br />
hewani yang dikonsumsi, frekuensi mengkonsumsi ikan, jumlah anggota keluarga yang<br />
mengkonsumsi ikan, dan ketersediaan pangan ikan yang mencakup cara mendapatkan ikan dan<br />
tempat membeli ikan), stabilitas ketersediaan ikan (harga ikan yang terjangkau dan pengaruh<br />
musim), kualitas dan keamanan pangan (pengetahuan tentang ikan dan keracunan ikan), serta<br />
fakktor aksesibilitasnya.<br />
viii
. .. <br />
Kondisi Variabe/ Pengembangan Usaha Pendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berbasis<br />
Perikanan<br />
Kondisi variabel <strong>pengembangan</strong> usaha yang mendukung <strong>pengembangan</strong> ketahanan<br />
pangan rumah tangga berbasis perikanan dibedakan menjadi dua yaitu varia bel di luar dan di<br />
dalam rumah tangga. Untuk variabel di luar rumah tangga, dengan mengamati tataguna lahan<br />
yang ada adalah bahwa <strong>untuk</strong> <strong>pengembangan</strong> perikanan banyak dilakukan masyarakat di lokasi<br />
penelitian dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Sarana dan prasarana yang mendukung<br />
adalah sarana prasarana produksi budidaya perikanan dan pertanian serta sarana prasarana<br />
umum seperti irigasi, transportasi (angkutan darat seperti bis, kereta api, dan lain-lain) termasuk<br />
berbagai lembaga pendukung baik keuangan, permodalan dan pemasaran.<br />
Kondisi variabel di dalam rumah tangga sendiri, struktur rumah tangga contoh penelitian<br />
bervariasi berada pada kelompok umur :5 40 tahun, 41 - 50 tahun, dan ~ 60 tahun. Demikian pula<br />
halnya dengan kondisi tingkat pendidikan dan pekerjaan bervariasi dari mulai tidak tamat SD,<br />
tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan Kuliah. Demikian pula halnya dengan pekerjaan utama<br />
contoh sebagaimana tipologi sumberdayanya.<br />
Perspekti/ Kebijakan<br />
Desain <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan melaui <strong>pengembangan</strong> usaha berbasis perikanan<br />
ini sangat sejalan dengan filosofi maupun tujuan dari kebijakan nasional tentang minapolitan,<br />
-<br />
yang menyangkut <strong>peningkatan</strong> produksi dan pensejahteraan masyarakat. Program minapolitan<br />
merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada konsep<br />
<strong>pengembangan</strong> kawasan, yang diterapkan di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia.<br />
Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang termasuk dalam SK Menteri no 32/2009 tentang<br />
penetapan lokasi minapolitan. Dalam konsep minapolitan tersebut, dua system utama yang<br />
menjadi targetnya adalah system usaha dan system permukiman, dimana masalah pangan /<br />
konsumsi merupakan salah satu elemen utamanya.<br />
Pengembangan sistem ketahanan pangan sebagaimana dikaji melalui penelitian ini jelas<br />
mendukung pelaksanaan program minapolitan. Pengembangan usaha berbasis perikanan sangat<br />
sesuai dengan penanganan sistem usaha didalam minapolitan; unit-unit usaha rumah tangga yang<br />
. diusulkan melalui penelitian ini dapat dijadikan penopang kuat bagi keberadaan wilayah-wilayah<br />
pendukung bagi lokasi minapolisnya. Sementara itu, sasaran <strong>peningkatan</strong> konsumsi selaras<br />
dengan sasaran perbaikan sistem permukiman.<br />
ix
· ..<br />
Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan<br />
Terdapat peluang <strong>untuk</strong> mengembangkan unit-unit usaha berbasis perikanan yang<br />
dikelola terkait dengan <strong>pengembangan</strong> minapolitan. Penelitian ini mengusulkan sebuah <strong>desain</strong><br />
<strong>untuk</strong> merealisasikan peluang terse but. Desain tersebut, pada intinya merupakan kerangka kerja<br />
<strong>pengembangan</strong> system usaha seperti tersebut di atas, yang terbangun atas sejumlah elemen<br />
penting< dari sisi teknis maupun social. Elemen penting tersebut adalah struktur, jenis usaha,<br />
komoditas pilihan, skala usaha, kelembagaan, rentang koordinasi, dan bentuk intervensi utama.<br />
Desain tersebut juga menyangkut arahan <strong>untuk</strong> mengintegrasikan <strong>pengembangan</strong> unitunit<br />
usaha terse but kedalam program minapolitan, dimana unit-unit usaha tersebut diusulkan<br />
<strong>untuk</strong> djadikan penopang wilayah hinterland, yang akan diintegrasikan dengan sebuaah minapolis<br />
tertentu. Desain itu, di sisi lain dasain tersebut secara khusus juga dirancang <strong>untuk</strong> membidik<br />
target tertentu dalam pembangunan perikanan, yaitu <strong>peningkatan</strong> konsumsi ikan dan<br />
pengurangan kebocoran ekonomi di masyarakat pedesaan.<br />
Implikasi kebijakannya adalah: 1) Perlu tindak lanjut oleh pemerintah daerah dalam<br />
rangka mengimplementasikan <strong>desain</strong> tersebut dalam kebijakan pembangunan di daerah,<br />
termasuk kebijakan penganggarannya; dan 2) Perlu <strong>sosial</strong>isasi tentang gagasan sebagaimana<br />
dihasilkan oleh penelitian ini.<br />
x
· ..<br />
DAFTAR 151 <br />
Halaman<br />
-<br />
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ...... ........................................................... ..... .........<br />
KATA PENGANTAR ..................... ... ....... ................................................... ..... .. .................. .. .. .<br />
EXECUTIVE SUMMARy..... ...... ....... .... ...... ....... .... ....... ... ... ..... ................... ................... .... ....... iv <br />
ii <br />
iii<br />
RINGKASAN EKSEKUTIF .... .. .... ... ........ ..... ... .. ........ ..... ...... .. .. .......................................... .... ....<br />
DAFTAR lSi ........... .................. ......................... .. ...... ....................................................... .......<br />
DAFTAR TABEL................................ .. ..................... ..... .... ............................ .. ............ ... ... ......<br />
DAFTAR GAMBAR.............. ............................................. .................. .... ... ................. ............<br />
vii <br />
xi <br />
xiii <br />
xvi <br />
I. PENDAHULUAN ... .. ............. ................. ....... ................................................................... 1 <br />
1.1. Latar Belakang........... .. ............... .......... ... ............................................................... 1 <br />
1.2. Justifikasi ........... ... ... .............. .. ..... ... .. ... .............. ......... ... ... ... .. ... ... ................. ... .. .... 2 <br />
1.3. Tujuan Penelitian.......................................... .... .. ................. .................... .. ............. 2 <br />
1.4. Keluaran Penelitian ....................... .. .. .. .............. ... .. .. .. ... .................... ... .................. 2 <br />
1.5. Rancangan Penelitian .......................... ................................................................... 2 <br />
1.5.1. Jenis data dan teknik pengumpulan data................................ .. ...... .. .. ........ 2 <br />
1.5.2. Pentahapan penelitian ............................................ .... .... .. ......................... 3 <br />
II. TINJAUAN PUSTAKA........... .. .................... ........ .. ... ... ........... ... ..................... .................. 4 <br />
2.1. Ketahanan Pangan........................................... ........... ............... ... .......................... 4 <br />
2.2. Ketahanan Pangan Rumah Tangga.......... .. .. .. .. .. .. ............ .... .. .. .......... ...................... 5 <br />
2.2.1. Indikator dan Pengukuran Ketahanan Pangan ............................................ 5 <br />
2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga....... 7 <br />
2.3. Ketersediaan dan Konsum si Ikan .. ................ .... ...................................................... 9 <br />
2.4. Pendekatan Sistem Sosial-Ekologis ............ .... ........ .. ............................................... 9 <br />
III. METODA PENELITIAN ......... ........................................ .... ...................... ......................... 10 <br />
3.1. Kerangka Pemikiran .................. ......... ... .... .... ...... .................. .................... ... .......... 10 <br />
3.2. Survey .. .. ..... ... ................ ......... .......... ... ............ ..... .......... .. ............... ... ... .... ......... ... 12 <br />
3.2.1. Sampling ............... ................................... .... .. ........... ...... .... .... ................... 12 <br />
3.2.2. Contoh ........................ ..................... ... .. .. ................................................... 12 <br />
3.2.3. Jenis data ................ .. ... ... ........ ................... ........ .... .................... ............ .. .. 12 <br />
3.3. Metoda Analisis .. .................. ..... ... .... ................. .. ..... ..................... .................. ... .. . 17 <br />
-<br />
xi
· .. <br />
Halaman<br />
IV. HASIL DAN ANALISIS .................................................... ....... ...... .... ................................ 18 <br />
4.1. Kondisi Urn urn Kabupaten Kulon progo ............ ............. ........................................ 18 <br />
4.1.1. Letak Geografis ................................... ...................... .............................. ... 18 <br />
4.1.2. Kondisi Topografi ....................................................................................... 19 <br />
4.1.3. Kondisi Hidrologi ...................................... .... .......... .................................... 20 <br />
4.2. Kondisi Urn urn Sosial dan Ekologi Lokasi Penelitian............................................... 20 <br />
4.3. Kondisi Ketahanan Pangan .................................................................................... 25 <br />
4.3.1. Pendapatan per Kapita Keluarga Contoh .................................................... 25 <br />
4.3.2. Preferensi produk perikanan ...................................................................... 25 <br />
4.3.3. Ketersediaan pangan ikan ....... ................................................................... 26 <br />
4.3.4. Stabilitas ketersediaan ikan .......... ....... ...................................................... . 31 <br />
4.3.5. Kualitas dan keamanan pangan ......................................................... ......... 28 <br />
4.3.6. Aksesibilitas .... .. .............. ........ ..... ....... .. ..... ...................................... ... ..... .. 29 <br />
4.4. Kondisi Variabel Pengernbangan Usaha Pendukung Ketahanan Pangan Berbasis<br />
Perikanan................................. ............ ................................................... .. .............<br />
33 <br />
4.4.1. Variabel-variabel di luar rumah tangga....................................................... 33 <br />
4.4.2. Variabel tingkat rumah tangga ... ......................................................... ....... 35 <br />
4.4.3. Sintesa ............................ .......... ................................................................. 68 <br />
4.4.4. Analisis terhadap <strong>desain</strong> ..... .. .. ............................................ .... ......... ........... 70 <br />
4.5. Aplikasi dan Kelernahan Desain .. ............................................................... .. .......... 71 <br />
4.6. Perspektif Kebijakan ...................... ... ....... .............................................................. 72 <br />
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ... ................................... .. ................... .......... 73 <br />
5.1. Kesirnpulan.. ........... ... ......... .... ............. .. ... .. ........................................ ........ ... ... ..... 73 <br />
5.2. Irnplikasi kebijakan (Butir-Butir Kebijakan)..... ............................. .... ... ....... ..... ....... 73 <br />
5.3. Perkiraan Darnpak ..... .. .. .... .. ........ .. .. .. ... ...... ..... ....................... .. .. ..... ... ............... .... 73 <br />
DAFTAR PUSTAKA.......................... ................. .... .. ....................... ....... .... .. .. ...... ...... ....... .......<br />
74 <br />
xii
. ..<br />
DAFTAR A9 <br />
No<br />
Halaman<br />
1. Tahapan penelitian menurut pendekatan, pe laksa - a da outpun yang diharapkan.... 3 <br />
2. Skor Konsumsi Pangan (SKP) <strong>untuk</strong> Mengide n . ~ asi e a anan Pangan Rumah <br />
Tangga .................................................. ... ....... .. ...... .....................................................<br />
3. Cakupan dan Jumlah Responden Riset Pengembangan Desain Tekno-Sosial <strong>untuk</strong> <br />
Peningkatan Kecukupan Pangan di Tingkat Rumah Tangga...........................................<br />
7 <br />
13 <br />
4. Contoh Penelitian ............................. ........ ... ....................... ............ ............................. 13 <br />
5. Jenis dan Sumber Data Primer ....................... .. ............................................................ 14 <br />
6. Jenis dan Sumber Data Sekunder ............................................ .. ................................... 15 <br />
7. Kelompok data yang diperlukan dalam penelitian ........................................................ 14 <br />
8. Tujuan, Lingkup Data, Jenis Data, Metode Analisis dan Output Tahapan Penelitian .... .. 17 <br />
9. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luasan Kabupaten Kulon Progo ......................... 18 <br />
10. Potensi dan realisasi penggunaan lahan (ha) di lokasi penelitian, 2009 ........................ 21 <br />
11. Rumah tangga perikanan di lokasi penelitian, 2009 ...................................................... 21 <br />
12. Kelompok perikanan di desa kulwaru kecamatan wates, 2009 ..................................... 22 <br />
13. Kelompok perikanan di desa sogan kecamatan wates, 2009......................................... 22 <br />
14. Kelompok perikanan di desa karangwuni kecamatan wates, 2009................................ 22 <br />
15. Lembaga penyedia permodalan tingkat Kabupaten Kulon Progo, 2009 .............. .... ...... 22 <br />
16. Lembaga penyedia permodalan tingkat kecamatan di lokasi penelitian, 2009 .............. 23 <br />
17. Lembaga pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan di lokasi penelitian, 2009... 23 <br />
18. Pendapatan per kapita keluarga contoh di lokasi penelitian, 2010........................... 25 <br />
19. Urutan kesukaan pangan hewani contoh di lokasi penelitian, 2010.............................. 26 <br />
20. Alasan yang diberikan contoh dalam memilih pangan hewani di lokasi penelitian, <br />
2010 ......................................... .. .. .................... ........................ ................................... 27 <br />
21. Penentu pangan hewani yang dikonsumsi contoh di lokasi penelitian, 2010 ................ 27 <br />
22 . Frekuensi mengkonsumsi ikan contoh di lokasi penelitian, 2010 ........ ........ .. ........ ........ 28 <br />
23 . Jumlah anggota keluarga contoh yang mengkonsumsi ikan di lokasi penelitian, 2010.. 28 <br />
24 . Cara mendapatkan ikan contoh di lokasi penelitian, 2010............................................ 29 <br />
25. Cara membeli ikan contoh di lokasi penelitian, 2010 .......... .......................................... 29 <br />
. 26. Tempat membeli ikan contoh di lokasi penelitian, 2010............................................... 30 <br />
27. Rata-rata harga ikan (Rp) yang terjangkau contoh di lokasi penelitian, 2010 ................ 30 <br />
28. Pengaruh musim terhadap konsumsi ikan contoh di lokasi penelitian, 2010................. 31 <br />
29. Pengetahuan tentang ciri-ciri ikan contoh di lokasi penelitian, 2010.. ........................... 32 <br />
30. Kejadian keracunan ikan contoh di lokasi penelitian, 2010...... ..................................... 32 <br />
31. Jarak dari desa ke kecamatan (km) menurut lokasi penelitian, 2008............................. 33 <br />
xiii
. .. <br />
No<br />
Halaman<br />
32. Tata gun a lahan di lokasi penelitian(ha) .................................................. .......... ........... 33 <br />
33. Luas tanah sawah menurut jenis pengairan di lokasi penelitian (ha)............................. 33 <br />
34. Sarana prasarana pendukung di lokasi penelitian, 2010 ........... .................................... 30 <br />
35. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Lokasi Penelitian, 2007............................ 34 <br />
36. Banyaknya rumah tangga menurut sektor kegiatan utama di lokasi penelitian, 2007... 35 <br />
37. Karakteristik rumah tangga contoh berdasarkan kelompok umur (%), 2010................. 35 <br />
38. Karakteristik Rumah tangga contoh berdasarkan umur rata-rata dan jumlah anggota <br />
rumah tangga, 2010..................... ................................................................................<br />
36 <br />
39. Kondisi Pendidikan SDM di lokasi penelitian, 2010 ................. ...................................... 36 <br />
40. Karakteristik rumah tangga contoh berdasarkan pekerjaan, 2010............................... . 37 <br />
4l. Kondisi Kewirausahaan SDM dengan mengikuti pelatihan di lokasi penelitian, 2010 .... 38 <br />
42. Kondisi Kewirausahaan SDM <strong>untuk</strong> jenis pelatihan yang diikuti di lokasi penelitian, <br />
2010 ...................................................................................................................... ...... 38 <br />
43. Kelengkapan rumah tangga contoh di lokasi penelitian, 2010 ...................................... 38 <br />
44. Sistem pemasaran usaha perikanan di lokasi penelitian, 2010...................................... 39 <br />
45. Sistem pemasaran usaha pertanian di lokasi penelitian, 2010...................................... 40 <br />
46. Sistem pemasaran usaha peternakan di lokasi penelitian, 2010 ................................... 41 <br />
47. Pengeluaran rumah tangga di lokasi penelitian, 2010................................................... 42 <br />
48. Analisis usaha budidaya lele di kolam terpal 8 x 4 m yang dilakukan responden di lokasi <br />
penelitian, 2010 .. ............................... ..........................................................................<br />
49. Analisis usaha budidaya gurame di kolam terpal 8 x 4 m yang dilakukan responden di <br />
lokasi penelitian, 2010 ..................... .......................................................... ..................<br />
44 <br />
45 <br />
50. Kalender tanam di lokasi penelitian ...................... ....................................................... 45 <br />
5l. Analisa usaha pertanian padi (ha) di lokasi penelitian, 2010......................................... 47 <br />
52 . Analisa usaha pertanian kedelai (ha) di lokasi penelitian, 2010 .................. .............. .... 48 <br />
53. Analisa usaha pertanian kacang tanah (ha) di lokasi penelitian, 2010 ........................... 49 <br />
54. Analisa usaha pertanian jagung (hal di lokasi penelitian, 2010......................... ............ 50 <br />
55. Analisa usaha pertanian cabe merah (ha) di lokasi penelitian, 2010......................... .... 53 <br />
56. Analisa usaha pertanian semangka/melon (ha) di lokasi penelitian, 2010.. .. ............ ..... 55 <br />
57. Analisa usaha pertanian sayuran kacang panjang (ha) di lokasi penelitian, 2010 .......... 56 <br />
58. Analisa usaha pertanian sayuran caisim (ha) di lokasi penelitian, 2010 .. ....................... 56 <br />
59. Analisa usaha pertanian kacang tanah lokal (ha) di lokasi penelitian, 2010.............. ..... 57 <br />
60. Analisa usaha pertanian jagung lokal (ha) di lokasi penelitian, 2010 ............................. 57 <br />
61. Analisa usaha penggemukkan sapi potong (10 ekor, 3 bulan) yang dilakukan <br />
responden di lokasi penelitian, 2010 .....................................................................................................<br />
59 <br />
62. Analisa usaha domba (40 ekor, 2 tahun) yang dilakukan responden di lokasi penelitian, <br />
2010 ................................. ........................ ....... ......... ..... ............................................. 61 <br />
-i
No<br />
Halaman<br />
63. Analisa usaha ayam yang dilakukan re sponden di lokasi penelitian, 2010........ .. .. .. .... .. . 62 <br />
64. Sistem permodalan di lokasi penelitian, 2010 ............................................ .................. 63 <br />
65. Total Produksi Ikan (ton) di Desa Sampel Tahun 2009 .. .. .. .................................. .. .. .... .. 64 <br />
66. Pasokan Ikan Konsumsi dari Luar Desa .. ...... .... ............. .. .................................. ...... .. .. .. 64 <br />
67 . Kebutuhan konsumsi ikan <strong>untuk</strong> ta rget memenuhi 38,67 kg /thn/kapita...................... 65 <br />
68. Defisit kebutuhan konsumsi <strong>untuk</strong> target 38,67 kg /thn/kapita .................................... 65 <br />
69. Jumlah keluarga yang bekerja off farm di lokasi penelitian........................................... 66 <br />
70. Jumlah keluarga yang bekerja non farm di lokasi penelitian ......................................... 66 <br />
71. Rataan pendapatan offfarm per tahun di lokasi penelitian .......................................... 67 <br />
72 . Rataan pendapatan non farm (Rp 000) per tahun di lokasi penelitian........................... 67 <br />
73. Identifikasi <strong>desain</strong> <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan di lokasi penelitian ........................ 70 <br />
xv
·... <br />
DAFTAR GA', BAR<br />
No<br />
Halaman<br />
1. Suatu Model Konseptual dari SES (Anderies et 012004).. ... ......... ... .... .. ......................... 10 <br />
2. Kerangka Pemikiran Riset Pengembangan es.ain Te o-Sosial <strong>untuk</strong> Peningkatan <br />
Kecukupan Pangan di Tingkat Rumah Tangga ... ...... .. .. ...... .. .... .. ..... .. .......... .. .................<br />
11 <br />
3. Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo .... ... .. ..... .. .... ...... ....................... ..................... .... 19 <br />
4. Kondisi SES di Lokasi Penelitian (Diadopsi dari Anderies et a/2004)............. .. ......... .... .. 21 <br />
xvi <br />
r
· .. <br />
I. PENDAHULUAN <br />
1.1. Latar Belakang<br />
Meskipun ikan memberikan kontribusi signifikan di dalam komposisi diet segenap<br />
kalangan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa peran ikan di dalam program<br />
ketahanan pangan negara-negara di dunia belum dioptimalkan sebegaimana mestinya<br />
(Purnomo, 2009). Hal ini diungkapkan dalam sebuah dokumen regional yang melaporkan<br />
bahwa program-program utama negara-negara ASEAN tentang ketahanan pangan, yaitu<br />
ASEAN's Integrated Food Security (AIFS) dan Framework and Strategic Plan of Action (SPA)<br />
sejauh ini hanya memfokuskan pada komoditas serealia dan gula, tanpa mencantumkan ikan<br />
dan produk perikanan (Anon., 2009 a )<br />
Sejalan dengan itu, badan konsultasi antar-negara<br />
ASEAN, SEAFDEC, merekomendasikan pemasukan ikan di dalam program ketahanan pangan<br />
di masing-masing negara ASEAN.<br />
Sebagai salah satu langkah lanjut dari rekomendasi lembaga regional tersebut,<br />
simposium Hari Pangan Sedunia telah menyiapkan rumusan rekomendasi kepada Presiden,<br />
yang salah satu butirnya mengamanatkan agar ikan dan produk perikanan diakomodasikan di<br />
dalam program ketahanan pangan nasional Anon., 200g b }.<br />
Langkah merupakan sebuah<br />
langkah maju, yang memang sangat relevan, yang harus segera direspon oleh masyarakat<br />
perikanan.<br />
Permasalahannya, meskipun potensi sumberdaya perikanan sangat besar, sejauh ini<br />
perannya belum dimaksimalkan sebagai salah satu sumber penting dalam<br />
pemenuhankebutuhan pangan masyarakat. Sebagian penduduk telah mengkonsumsi ikan<br />
dalam jumlah yang cukup besar, namun sebagian lain sangat rendah asupan ikannya. Jarak<br />
sentra produksi dari konsentrasi sebagian konsumen dan sistem distribusi yang tidak<br />
mendukung merupakan salah satu penyebab rendahnya akses dan keterjangkauan ikan dan<br />
produk perikanan bagi konsumen.<br />
Salah satu solusi potensial yang perlu dikaji adalah mendekatkan lokasi produksi<br />
dengan lokasi konsumen. Lebih tepatnya, solusi potensial tersebut adalah dimana produksi<br />
perikanan dilakukan lahan-Iahan produksi yang dimiliki oleh konsumen. Pendekatan tersebut<br />
diharapkan dapat meningkatkan ketersedian, akses maupun keterjangkauan ikan dan produk<br />
perikanan bagi konsumen. Tidak hanya menyediakan ikan secara langsung bagi konsumen,<br />
kegiatan produksi oleh konsumen juga diharapkan secara tidak langsung memperbesar<br />
peluang bagi konsumen <strong>untuk</strong> meningkatkan pendapatan, yang secara tidak langsung dapat<br />
mendukung ketahanan pangan. Pendekatan serupa telah diuji-cobakan di sektor lain, yaitu<br />
pertanian, dan menunjukkan berbagai indikasi keberhasilan (Maryanto, 2008) Proposal ini<br />
1
· ..<br />
akan mengadaptasi sebagia :-"3- ="3 ~::a - - sektor pertanian terse but dan<br />
memodifikasinya dengan variabe - . c - ~ ::r- ~ :~: _ _€ ~ _ kelautan dan perikanan.<br />
1.2. Justifikasi<br />
Sebagaimana tersirat dalam pe a I a a permasalahan mendesak yang perlu<br />
dikaji melalui penelitian ini, yaitu adanya gap pasok dan konsumsi ikan, yang dihipotesakan<br />
dapat dijembatani dengan model perikana n ruma tangga <strong>untuk</strong> ketahanan tingkat rumah<br />
tangga. Untuk masalah tersebut, perlu ada sebuah penelitian yang menghasilkan output<br />
berupa <strong>desain</strong> atau model seperti itu, yang dapat dirumuskan melalui tahapan : penggalian<br />
informasi-informasi dasar, perumusan draft awal, pendalaman melalui sebuah seri survai<br />
lapang, penyempurnaan draft, diskusi kelompok fokus dan finalisasi <strong>desain</strong> .<br />
1.3. Tujuan Penelitian<br />
Tujuan dari penelitian ini adalah :<br />
1. Merumuskan <strong>desain</strong> <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> terbaik yang seharusnya dikembangkan <strong>untuk</strong><br />
perikonon rumoh tongga <strong>untuk</strong> ketahanan pangan tingkat rumah tangga<br />
2. Mengidentifikasi strategi yang tersedia bagi masyarakat <strong>untuk</strong> mengimplementasikan<br />
<strong>desain</strong> tersebut dalam kondisi dan situasi <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> yang mereka hadapi,<br />
3. Mengidentifikasi peran terbaik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam<br />
mendukung implementasi <strong>desain</strong> tersebut.<br />
1.4. Keluaran Penelitian<br />
Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:<br />
1. Laporan teknis<br />
2. Laporan ilmiah yang akan dipublikasikan pada Jurnal Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi<br />
Kelautan dan Perikanan<br />
3. Makalah Seminar<br />
4. Rekomendasi kebijakan yang siap <strong>untuk</strong> dikomunikasikan kepada policy makers<br />
J. 1.5. Rancangan Penelitian<br />
1.5.1. Jenis data dan teknik pengumpulan data<br />
Data-data sebagian besar akan dikumpulkan melalui teknik wawancara, dengan<br />
sasaran dan jumlah responden yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil dari<br />
studi literatur dan penelitian pendahuluan, yang akan mengawali semua kegiatan<br />
penelitian ini.<br />
2
· ..<br />
1.5.2. Pentahapan penelitian<br />
Mengacu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tahapan penelitian akan<br />
dilaksanakan mengikuti rencana sebagaimana ditunjukkan dalam label 1 berikut ini:<br />
label 1. lahapan penelitian menurut pendekatan, pelaksanan dan outpun yang<br />
diharapkan<br />
Bulan<br />
Kegiatan<br />
ke<br />
1 Studi literatur<br />
2 Penelitian<br />
pendahuluan<br />
3 Penyusunan<br />
draft awal<br />
<strong>desain</strong><br />
4-8 Pendalaman<br />
data dan<br />
informasi<br />
9 Penyempurnaa<br />
n draft<br />
10 Finalisasi<br />
Lokasi<br />
Jakarta dan<br />
sekitarnya<br />
Lokasi<br />
target<br />
Jakarta dan<br />
sekitarnya<br />
Lokasi2<br />
target<br />
Lokasi<br />
target<br />
Jakarta<br />
Pendekata<br />
n<br />
Desk study<br />
Quick<br />
survey<br />
Desk study<br />
&<br />
konsinyasi<br />
Studi<br />
lapang /<br />
survai<br />
Diskusi<br />
kelompok<br />
fokus<br />
Konsinyasi<br />
Pelaksana<br />
Semua anggota tim<br />
Semua anggota tim<br />
Semua anggota tim<br />
Output<br />
Varia bel utama<br />
<strong>untuk</strong><br />
mengarahkan<br />
penelitian<br />
pendahuluan<br />
Data awal <strong>untuk</strong><br />
pembuatan draft<br />
awal <strong>desain</strong><br />
Draft awal <strong>desain</strong><br />
Anggota tim yang Data dan<br />
dibagi menurut lokasi informasi detil<br />
target yang ditentukan mengenai<br />
variabel-variabel<br />
yang tercakup<br />
dalam <strong>desain</strong><br />
Anggota tim dan Umpan balik dan<br />
wakil responden informasi<br />
klarifikasi<br />
Anggota tim<br />
Desain final<br />
3
· ...<br />
II.<br />
TINJAUAN PUSTAKA<br />
2.1. Ketahanan Pangan<br />
Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari food security merupakan<br />
fenomena yang komplek mencakup banyak aspek dan factor lain yang terkait secara luas<br />
sehingga setiap orang mencoba menterjemahkan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan<br />
data. Seperti diungkapkan oleh Reutlinger (1987) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan<br />
dengan banyak cara sesuai kebutuhan dan tujuannya. Ketahanan Pangan didefinisikan<br />
sebagai Ilikondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya<br />
pangan yang cukup, baik jum/ah maupun mutunya, oman merata dan terjangkau" (Undang<br />
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Bab I pasal 7 ayat 18).<br />
Untuk kepentingan perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan maka<br />
perlu dilakukan redefinisi yang memuat enam komponen dasar ketahanan pangan yaitu : (a)<br />
pemenuhan kebutuhan gizi <strong>untuk</strong> hidup aktif dan sehat sesuai nilai setempat (pola pangan<br />
dan religi); (b) jaminan keamanan pangan sebagai bagian dari pol a pemenuhan kebutuhan<br />
kesehatan; (c) akses pangan secara fisik (produksi dan ketersediaan pangan); (d) akses<br />
pangan secara ekonomi atau <strong>sosial</strong> (kemampuan membeli atau memperoleh pangan); (e)<br />
akses informasi tentang jumlah, mutu dan harga pangan; dan (f) kesinambungan, yaitu<br />
terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu (Hardinsyah eta/., 1999).<br />
Atmodjo, Syarief, Sukandar dan Latifah (1995) menyebutkan bahwa kondisi<br />
ketidaktahanan pangan (food insecurity) tingkat rumahtangga ada dua<br />
bentuk yaitu : (a)<br />
ketidaktahanan pangan kronis yaitu terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang<br />
biasanya disebabkan oleh rendahnya daya beli dan kualitas sumberdaya yang sering terjadi di<br />
wilayah miskin dan gersang; dan (b) ketidaktahanan pangan akut, terjadi secara mendadak<br />
yang disebabkan oleh bencana alam, kegagalan produksi dan kenaikan harga yang<br />
mengakibatkan masyarakat sukar memperoleh pangan yang memadai.<br />
Konsep dari ketahanan pangan sangat luas dan beragam yang meliputi dimensi<br />
sasaran global, nasional, regional, rumah tangga dan individu serta dimensi waktu atau<br />
musim, ruang dan dimensi social ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan global, nasional,<br />
I<br />
-'<br />
regional, local dan rumah tangga serta individu merupakan suatu rangkaian system hirarkis,<br />
dimana ketahanan pangan nasional dan regional merupakan syarat keharusan (necessary<br />
condition) bagi ketahanan pangan masyarakat, rumah tangga dan individu. Dan ketahanan<br />
pangan individu merupakan syarat kecukupan (sufficiency condition) bagi ketahanan pangan<br />
nasional (Simatupang, 1999).<br />
4
Ketahanan pangan merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu: (1)<br />
ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability and stability), (2) kemudahan<br />
memperoleh pangan (food accessibility), dan (3) pemanfaatan pangan (food utilization) (FAD,<br />
1996) .<br />
•<br />
2.2. Ketahanan Pangan Rumah Tangga<br />
Ketahanan pangan rumahtangga didefinisikan dalam beberapa alternatif rumusan<br />
yaitu : (1) Kemampuan <strong>untuk</strong> memenuhi kebutuhan pangan anggota rumahtangga dalam<br />
jumlah, mutu dan ragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar dapat hidup<br />
sehat; (2) Kemampuan rumahtangga <strong>untuk</strong> memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari<br />
fa<br />
produksi sendiri dan atau membeli dari waktu ke waktu agar dapat hidup; dan (3)<br />
Kemampuan rumahtangga <strong>untuk</strong> memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke<br />
waktu agar hidup sehat (Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1996).<br />
Syarief, Hardinsyah dan Atmojo (1999) menyebutkan bahwa makna atau dimensi<br />
yang terkandung dalam definisi tersebut adalah dimensi fisik pangan (penyediaan), dimensi<br />
ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan kebutuhan gizi individu (dimensi gizi dan sasaran)<br />
sesuai nilai-nilai budaya religi (pola pangan yang sesuai), dimensi keamanan pangan<br />
(kesehatan), dan dimensi waktu (secara berkesinambungan). Definisi ini secara mendasar<br />
sudah menganut konsep yang holistik dan mengandung makna yang selaras dengan<br />
paradigma baru kesehatan.<br />
Usaha <strong>untuk</strong> mewujudkan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumahtangga<br />
dapat ditempuh melalui <strong>peningkatan</strong> efektivitas dan efisiensi distribusi pangan, <strong>peningkatan</strong><br />
daya beli masyarakat, <strong>peningkatan</strong> kemampuan penyediaan pangan, <strong>peningkatan</strong><br />
pembentukan cadangan pangan, dan <strong>peningkatan</strong> pengetahuan pangan dan gizi. Kebijakan<br />
<strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan memberikan perhatian secara khusus kepada mereka yang<br />
memiliki resiko tidak mempunyai akses <strong>untuk</strong> memperoleh pangan yang cukup (Suhardjo,<br />
1996; Soetrisno, 1996).<br />
2.2.1. Indikator dan Pengukuran Ketahanan Pangan<br />
.<br />
Mengacu pada pada pengertian ketahanan pangan dalam UU RI No.7 Tahun<br />
~ 1996, Soetrisno (1996) mengemukakan beberapa indicator yang dapat digunakan<br />
meliputi : 1} Angka ketersediaan pangan setara energi, protein dan lemak<br />
dibandingkan angka kecukupan berdasarkan rekomendasi; 2} Angka konsumsi energi,<br />
protein dan lemak penduduk dibandingkan angka kecukupan berdasarkan<br />
rekomendasi; 3} Prosentase jumlah penduduk yang mengalami rawan pangan; 4}<br />
Angka Indeks Ketahanan Pangan Rumahta ngga; 5} Angka rasio antara stok dengan<br />
5
· .. <br />
konsumsi pada berbagai tingkat wilayah; 6) tingkat harga pangan pokok penduduk<br />
setempat; 7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) <strong>untuk</strong> tingkat ketersediaan atau<br />
konsumsi; 8) Kondisi keamanan pangan; 9) Keadaan kelembagaan cadangan pangan<br />
masyarakat; dan 10) Tingkat cadangan pangan pemerintah dibandingkan perkiraan<br />
kebutuhan.<br />
Secara konseptual ketahanan pangan yang telah diterima oleh Sidang Komite<br />
Pangan Dunia tahun 1993 mencakup tiga aspek penting yaitu : (1) ketersediaan<br />
pangan;<br />
(2) stabilitas penyediaan pangan; dan (3) akses individu dan atau<br />
rumahtangga <strong>untuk</strong> mendapatkan pangan. Ketiga aspek diterjemahkan dalam suatu<br />
indeks yang mengukur keadaan ketahanan pangan.<br />
Karena sasaran ketahanan<br />
pangan adalah rumahtangga maka indicator ketahanan pangan yang disusun<br />
difokuskan pada Indeks Rata-Rata Ketahanan Pangan Rumahtangga (AHFSI =Average<br />
Household Food Security Index). Secara ringkas formula ukuran ketahanan pangan<br />
digambarkan sebagai berikut :<br />
AHFSI = 100 - [ H {G + (1- G) I} + O,5Q { 1- H (G + (1 - G) I) } ]100<br />
Keterangan:<br />
H rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan (undernourished) terhadap jumlah<br />
penduduk.<br />
G Proporsi angka kekurangan kalori terhadap angka rata-rata kebutuhan kalori. Angka ini<br />
diukur dari selisih antara ketersediaan rata-rata energi <strong>untuk</strong> kelompok penduduk<br />
kekurangan pangan dengan rata-rata kebutuhan kalori.<br />
Ketimpangan dalam distribusi (inequality in distribution offood gaps) yang diukur dengan<br />
koefisien GINI dari distribusi konsumsi kalori.<br />
Q Koefisien variasi DES (Dietary Energy Supplies) atau ketersediaan energi <strong>untuk</strong> konsumsi,<br />
yang menjadi ukuran kemungkinan yang dikaitkan denganketidaktahanan pangan yang<br />
mendadak (temporaryfood security).<br />
Berdasarkan Indeks Rata-Rata Ketahanan Pangan Rumahtangga (AHFSI) status<br />
ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam 4 (em pat) kelompok sebagai berikut : (1)<br />
Sangat Tahan (AHFSI Tinggi di atas 85); (2) Tahan (AHFSI Menengah antara 75 - 85);<br />
(3) Tidak Tahan (AHFSI Rendah antara 65 - 75); dan (4) Sangat Rawan/Kritis (AHFSI<br />
Sangat Rendah di bawah 65) (FAO, 1994 dalam Soetrisno, 1995).<br />
Pada dasarnya model yang dianjurkan FAO (AHFSI) tersebut cukup baik dan<br />
akurat dalam menangkap kondisi ketahanan pangan suatu negara (Soetrisno, 1995),<br />
namun <strong>untuk</strong> menangkap ketahanan pangan tingkat rumahtangga belum terbukti<br />
handal dan ditinjau dari aspek operasional model tersebut relatif sulit <strong>untuk</strong><br />
diterapkan.<br />
Menurut Hasan (1995) ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat<br />
dketahui melalui pengumpulan data konsumsi dan ketersediaan pangan dengan cara<br />
survei pangan secara langsung.<br />
Hasilnya kemudian dibandingkan dengan norma<br />
6
· ... <br />
kecukupan yang telah ditetapkan.<br />
Selain pengukuran konsumsi dan ketersediaan<br />
pangan, melalui survei tersebut dapat pula dikumpulkan data mengenai ekonomi.<br />
<strong>sosial</strong> dan demografi, harga pangan, pengeluaran dan sebagainya.<br />
Data tersebut<br />
dapat digunakan sebagai indikator resiko terhadap ketahanan pangan pada tingkat<br />
ru m a hta ngga.<br />
Foster (1992) dalam Hardinsyah et 01. (1998) menyarankan tiga alternatif<br />
konsep dan pengukuran ketahanan pangan rumahtangga yang lebih melihat dari<br />
sudut ekonomi, dimana rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika:<br />
1. Nilai kekurangan produksi di dalam s Pendapatan dan asset rumah <br />
rumahtangga<br />
tangga <strong>untuk</strong> belanja pangan <br />
2. Kebutuhan pangan x harga s Pendapatan dan asset rumah <br />
rumah tangga pangan tangga <strong>untuk</strong> belanja pangan <br />
3. Kebutuhan konsumsi x harga s Pendapatan dan asset rumah<br />
dan produksi pangan pangan tangga <strong>untuk</strong> belanja pangan<br />
Selanjutnya Hardinsyah (1996) menyarankan penggunaan Skor Konsumsi<br />
Pangan (SKP) <strong>untuk</strong> pengukuran ketahanan pangan rumahtangga. Ukuran sederhana<br />
ini dapat digunakan <strong>untuk</strong> menduga pemenuhan kebutuhan gizi rumahtangga. SKP<br />
mempunyai korelasi yang erat dengan rata-rata tingkat konsumsi zat gizi (Energi,<br />
Protein, Lemak, Vitamin A, Vitamin (, Thiamin, Kalsium, Fosfor, Besi dan Seng) seperti<br />
dapat dilihat pada Tabel 2.<br />
- *)<br />
Tabel 2. Skor Konsumsi Pangan (SKP) <strong>untuk</strong> Mengidentifikasi Ketahanan Pangan<br />
Rumah Tangga<br />
Kelompok Pangan<br />
Jumlah Pangan yang Dibutuhkan per Unit<br />
Konsumen bagi Pria Dewasa ")<br />
Skor<br />
1. Makanan Pokok') 5 piring (500 gr) 0 1 2<br />
2. Lauk Pauk 4 potong (200 gr) 0 1 2<br />
3. Sayuran 2 mangkuk (150 gr) 0 1 2<br />
4. Buah-buahan 2 buah/potong (200 gr) 0 1 2<br />
5.Susu 1 gelas (200 ml) 0 1 2<br />
Keterangan : <br />
Skor =0, jika konsumsi makanan s Y, UK<br />
Skor = 1, jika konsumsi makanan = Y, ·1 UK 6 -10<br />
Skor Total: <br />
: Cukup Tahan <br />
Skor =2, jika konsumsi makanan ~ 1 UK < 6 : Tidak Cukup Tahan <br />
Dengan asumsi peron makanan jajanan sebesar 10 %dan umbi·umbian < 20 %<br />
**) Dengan asumsi bagi pria dewasa dengan kegiatan sedang<br />
2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan<br />
Menurut Soetrisno (1995) terdapat dua komponen penting dalam ketahanan<br />
pangan yaitu ketersediaan dan akses terhadap pangan.<br />
Maka tingkat ketahanan<br />
pangan suatu negara/wilayah dapat bersumber dari kemampuan produksi,<br />
-<br />
kemampuan ekonomi <strong>untuk</strong> menyediakan pangan dan kondisi yang membedakan<br />
-<br />
-<br />
7
· ... <br />
tingkat kesulitan dan hambatan <strong>untuk</strong> akses pangan. Hal senada dinyatakan Sawit<br />
dan Ariani (1997) bahwa penentu ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah<br />
akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko yang terkait dengan akses<br />
serta ketersediaan pangan tersebut.<br />
Menurut Aziz (1990) ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai dengan<br />
pendapatan (daya beli) dan produksi pangan yang cukup. Tingkat pendapatan sangat<br />
berpengaruh nyata terhadap konsumsi gizi berupa, protein, vitamin A dan zat besi<br />
(Hartoyo, 1996). Sementara menurut Hasan (1995) resiko ketidaktahanan pangan<br />
tingkat rumah tangga timbul karena faktor rendahnya produksi dan ketersediaan<br />
pangan maupun faktor geografis.<br />
Sedangkan menurut Susanto (1996) kondisi<br />
ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan pangan<br />
(pada tingkat makro dan tingkat di dalam pasar dan kemampuan daya beli, tetapi juga<br />
oleh beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan aspek sosio budaya.<br />
Ketersediaan pangan keluarga mempunyai hubungan dengan pendapatan<br />
keluarga, ukuran keluarga dan potensi desa (LlPI, 1988).<br />
Rendahnya pendapatan<br />
merupakan rintangan lain yang menyebabkan orang tidak mampu membeli pangan<br />
dalam jumlah yang diperlukan (Sayogyo, 1989).<br />
Keluarga dan masyarakat yang<br />
berpenghasilan rendah, mempergunakan sebagian besar dari keuangannya <strong>untuk</strong><br />
membeli makanan dan bahan makanan dan tentu dalam jumlah uang yang<br />
dibelanjakan juga rendah (Suhardjo, 1989).<br />
Selanjutnya Suhardjo (1989) menyatakan bahwa bila kebutuhan akan pangan<br />
dapat dipenuhi dari produksi sendiri, maka penghasilan dalam bentuk uang tidak<br />
menentukan.<br />
Kapasitas penyediaan bahan pangan dapat dipertinggi dengan<br />
meningkatkan produksi pangan sendiri.<br />
Namun sebaliknya jika kebutuhan pangan<br />
banyak tergantung pada apa yang dibelinya, maka penghasilan (daya beli) harus<br />
sanggup membeli bahan makanan yang mencukupi baik kuantoitas maupun<br />
kualitasnya. Sementara itu menurut Soemarwoto (1994) menyatakan bahwa faktor<br />
ekonomi menyebabkan penilaian kemampuan manusia <strong>untuk</strong> mendapatkan makanan<br />
ditentukan oleh harga makanan.<br />
Selanjutnya Purwaka (1994) menyatakan bahwa<br />
walaupun pendapatan per kapita rata-rata meningkat, harga akan menjadi kendala<br />
bagi masyarakat berpenghasilan rendah <strong>untuk</strong> dapat mengkonsumsi pangan terutama<br />
hasillaut.<br />
-<br />
-<br />
Agar rumah tangga memperoleh pangan <strong>untuk</strong> dikonsumsi, maka pangan<br />
harus tersedia. Ketersediaan pangan secara makro maupun mikro banyak ditentukan<br />
oleh tinggi rendahnya produksi pangan dan dari keluar/masuknya pangan dari/ke<br />
8
· , <br />
wilayah yang bersangkutan. Sementara itu ketidakterjaminan ketersediaan pangan di<br />
pasar selain pengaruh faktor produksi juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar,<br />
sarana/prasarana, dan sebagainya. Banyak sedikitnya pangan yang dibeli dari pasar<br />
termasuk keragamannya sangat ditentukan oleh pendapatan/daya beli rumah tangga,<br />
harga-harga pangan serta pengetahuan rumah tangga <strong>untuk</strong> memilih makanan/bahan<br />
makanan yang akan dikonsumsi.<br />
Oleh karena itu ketersediaan pangan di rumah<br />
tangga sangat tergantung pada hasil pertaniannya (bagi yang mengusahakan lahan)<br />
dan dari apa yang dibeli di pasar (bagi yang memiliki daya beli). Walaupun rumah<br />
tangga memiliki daya beli yang cukup dan pangan tersedia juga cukup, namun bila<br />
pengetahuan pangan dan gizi yang dimiliki masih rendah akan sangat sulit bagi rumah<br />
tangga yang bersangkutan dapat memenuhi kecukupan pangannya baik kualitas,<br />
kuantitas maupun keragamannya (Suhardjo, 1996).<br />
2.3. Ketersediaan dan Konsumsi Ikan<br />
Secara umum konsumsi pangan dipengaruhi oleh tiga hal utama, yaitu pendapatan,<br />
ketersediaan pangan setempat dan pengetahuan/faktor budaya. Di bidang peri kanan, <strong>untuk</strong><br />
memenuhi kebutuhan ikan akibat <strong>peningkatan</strong> jumlah penduduk dan konsumsi ikan per<br />
kapita per hari, pemerintah terus berusaha meningkatkan produksi ikan.<br />
Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI<br />
telah merekomendasikan standar<br />
kecukupan nasional pangan dan gizi <strong>untuk</strong> kecukupan protein sebesar 50 gram<br />
protein/kapita/hari dan energi sebesar 2,200 Kkal/kapita/hari. Dari angka kecukupan protein<br />
rata-rata per kapita per hari tersebut dianjurkan sebanyak 18 gram diantaranya dipenuhi dari<br />
pangan sumber protein hewani, dengan perincian 6 gram berasal dari ternak dan 12 gram<br />
berasal dari ikan.<br />
2.4. Pendekatan Sistem Sosial-Ekologis<br />
Sistem <strong>sosial</strong>-ekologis didefinisikan sebagai sistem yang terpadu dari alam dan<br />
manusia dengan hubungan yang timbal balik (Folke 1998; Carpenter and Folke 2006).<br />
Sementara itu menurut Anderies et 01 (2004), sistem <strong>sosial</strong>-ekologis adalah sebuah sistem<br />
dari unit biologi/ekosistem dihubungkan dengan dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem<br />
<strong>sosial</strong>. Suatu sistem ekologis dapat digambarkan sebagai suatu sistem unit biologi atau<br />
organisme yang saling tergantung. Sosial sederhananya berarti membentuk ko-operasi dan<br />
hubungan saling tergantung dengan orang yang lain (Merriam-Webster Online Dictionary,<br />
<br />
9<br />
2004). Dengan demikian sistem <strong>sosial</strong>-ekologis ini membicarakan unit ekosistem seperti<br />
wilayah pesisir, ekosistem mangrove, danau, terumbu karang, pantai yang berasosiasi
· ...<br />
dengan struktur dan proses sos·al. Hal tersebut sebagaimana yang digambarkan pada<br />
Gambar 1.<br />
8<br />
B.<br />
c. Public<br />
Infrastructure<br />
8<br />
Gambar 1. Suatu Model Konseptual dari SES (Anderies et 012004)<br />
10
II. METODA<br />
Desain <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> <strong>pengembangan</strong><br />
nan <strong>untuk</strong> ketahanan pangan tingkat<br />
tangga penelitian akan ngun dengan bertumpu pada sistem sosiaJ pj,f,'1/(')rHt::<br />
Lln,np,-,..,,, dkk., 2004}, dimana interaksi <strong>sosial</strong> dan menjadi pertimbangan<br />
utama dalam pemilihan komponen dan <strong>desain</strong>. Dalam int yang<br />
dibicarakan adalah unit ekosistem yang dihubungkan dengan dan dipengaruhi oleh sistem <strong>sosial</strong><br />
yang di mana aspek sistem alam (ekosistem) dan sistem manusia, merupakan suatu hal<br />
yang<br />
relevan.<br />
Data-data utama yang dikumpulkan<br />
bentuk primer di lokasi-Iokasi<br />
melalui pendekatan survai dan diklarifikasi melalui diskusi-diskusi kelompok fokus di lapangan,<br />
yang melibatkan sumber data/informasi. data dilakukan dengan desk<br />
study dan konsinyasi yang melibatkan semua anggota tim penellti, dengan output utama berupa<br />
data tabulatif Berdasarkan rancangan-rancangan <strong>desain</strong><br />
dan melalui yang dilakukan dengan<br />
narasumber di Semua penelitian sesuai perencanaan dapat<br />
d<br />
dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.<br />
3.1 Pemikiran<br />
Dalam ketahanan pangan, rumah adalah salah satu komponen<br />
penting yang<br />
diperhatikan agar memperoleh hasil yang maksimal. Rumah tangga di<br />
daerah perdesaan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan mengoptimalkan<br />
sumberdaya kelembagaan maupun alamnya Kerangka pemikiran upaya<br />
<strong>peningkatan</strong> pangan rumah tangga di dengan<br />
memperhatikan:<br />
1. Kondisi dan<br />
Akses sumberdaya (Iahan,<br />
laut dan hutan)<br />
Modernisasi usaha perikanan dan pertanian (meliputi <strong>tekno</strong>logi dan sumber daya<br />
manusia)<br />
Sistem<br />
perikanan dan pertanian (meliputi industri dan kelembagaan usaha)<br />
Pembiayaan usaha (meliputi swasta dan pemerintah)<br />
2. Desain Tekno-Sosial melalui:<br />
(meliputi KUD, bank<br />
dan lain-lain)<br />
Investasi dan pembentukan model.<br />
11
· ..<br />
Gambaran tentang kerargka pemikiran <strong>pengembangan</strong> <strong>desain</strong> <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> <strong>untuk</strong><br />
<strong>peningkatan</strong> kecukupan pangan di tingkat rumah tangga ini tersaji paga Gambar 2.<br />
Survey<br />
1<br />
- - -------------------~<br />
I<br />
I<br />
Kondisi Varia bel<br />
Rumah Tangga<br />
Desain Perbaikan<br />
Kondisi Variabel<br />
Pembangunan<br />
FGD<br />
Umpan Balik<br />
Analyses work<br />
Umpan Balik<br />
Desain Final<br />
Rekomendasi<br />
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Riset Pengembangan Oesain Tekno-Sosial <strong>untuk</strong><br />
Peningkatan Kecukupan Pangan di Tingkat Rumah Tangga<br />
3.2 Survey<br />
3.2.1 Sampling<br />
Penelitian dilakukan di Propinsi 01 Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Wates,<br />
Kabupaten Kulon Progo dengan cakupan dapat dilihat pada Tabel 3.<br />
Oesa Kulwaru (desa dengan kegiatan perikanan budidaya khususnya komoditas lele)<br />
Oesa Karangwuni (desa dengan kegiatan perikanan tangkap)<br />
Oesa Sogan (desa dengan kegiatan pertanian)<br />
12
.. ..<br />
Tabel3.<br />
Cakupan dan Jumiah Responden Riset Pengembangan Desain Tekno-Sosial<br />
<strong>untuk</strong> Peningkatan Kecukupan Pangan di Tingkat Rumah Tangga<br />
Jenis Responden Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
1 Responden<br />
I<br />
15 15 15<br />
2 Informan kunci 2 2 2<br />
3 Pedagang 1 1 1<br />
4 Stakeholder 2 2 2<br />
Jumlah 20 20 20<br />
3.2.2 Contoh<br />
Contoh dalam penelitian ini meliputi stakeholder dan responden yang secara<br />
rinci dapat dilihat pada Tabel 4.<br />
Tabel 4. Contoh Penelitian<br />
No Jenis Contoh Rincian<br />
1 Stakeholder - Dinas Kelautan dan Perikanan<br />
- Badan Ketahanan Pangan<br />
- Badan Pusat Statistik<br />
- Pemerintah Kecamatan<br />
- Pemerintah Desa<br />
- Penyuluh<br />
- Kelompok Pembudidaya<br />
- Kelompok Petani<br />
- Dan lain-lain<br />
2 Responden - Pembudidaya ikan lele<br />
- Nelayan<br />
- Petani<br />
- Pedagang<br />
- Informan kunci<br />
3.2.3 Jenis Data<br />
Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer<br />
dikumpulkan langsung dari pembudidaya ikan, nelayan dan petani. Sedangkan data<br />
sekunder diperoleh dari berbagai instansi di Kabupaten Kulon Progo. Jenis data baik<br />
primer maupun sekunder yang dibutuhkan dan sumber perolehannya adalah seperti<br />
pada Tabel 5 dan Tabel 6.<br />
13
· .. <br />
TabelS. Jenis dan Sumber Data Primer<br />
No Jenis Data primer Sumber<br />
1 Karakteristik rumah tangga contoh Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
2 Penguasaan sumberdaya lahan dan asset Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
lahan<br />
3 Jumlah anggota yang keluarga yang bekerja Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
dan jenis pekerjaan masing-masing<br />
4 Tingkat pendapatan dari masing-masing Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
pekerjaan<br />
5 Struktur input dan output usaha perikanan Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
6 Biaya dan keuntungan usaha perikanan Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
7 Cara memperoleh modal dan sarana Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
produksi perikanan<br />
8 Sistem usaha perikanan yang dilakukan Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
9 Tingkat penerapan <strong>tekno</strong>logi (penggunaan Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
input, pengolahan, produktivitas)<br />
10 Pemasaran hasil perikanan (bentuk yang<br />
dipasarkan, tempat pemasaran dan sistem<br />
Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
pembayaran)<br />
11 Tingkat harga input dan harga produk Pembudidaya, Nelayan, Petani,<br />
Pedagang<br />
12 Komposisi sumber pendapatan keluarga<br />
(on-farm, off-farm, non-farm)<br />
13 Struktur pengeluaran rumah tangga<br />
14 Permasalahan yang dihadapi dalam<br />
melakukan usaha perikanan dan usaha di<br />
luar perikanan<br />
15 Data dan informasi lain yang berkaitan<br />
dengan penelitian yang dilaksanakan<br />
Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
Pembudidaya, Nelayan, Petani,<br />
Industri<br />
Pembudidaya, Nelayan, Petani<br />
14
· ... <br />
Tabel6. Jenis dan Sumber DatCl Sekunder<br />
No Jenis data sekunder Sumber<br />
1 Data dan informasi tentang kependudukan BPS<br />
(demografi)<br />
2 Data dan informasi tentang peran sektor Dinas Kelautan dan Perikanan<br />
perikanan dan PDRB<br />
3 Data dan informasi tentang tata guna lahan Bappeda<br />
4 Data dan informasi tentang komoditas<br />
unggulan daerah<br />
5 Data dan informasi tentang perusahaan<br />
perikanan (industri dan jasa)<br />
6 Data dan informasi tentang<br />
pembudidaya/nelayan/petani/mitra<br />
7 Data dan informasi tentang program daerah<br />
dalam <strong>pengembangan</strong> sistem usaha<br />
perikanan komoditas unggulan<br />
8 Data dan informasi tentang kondisi<br />
infrastruktur pendukung sektor perikanan<br />
9 Data dan informasi tentang program daerah<br />
dalam pembangunan infrastruktur<br />
pendukung sektor perikanan<br />
10 Data dan informasi tentang perkembangan<br />
luas lahan, jumlah panen, produksi dan<br />
produktivitas usaha perikanan<br />
11 Data dan informasi tentang kondisi<br />
ketahanan pangan daerah<br />
12 Berbagai bahan dan studi yang berkaitan<br />
dengan <strong>pengembangan</strong> multiusaha tumah<br />
tangga perikanan<br />
13 Data dan informasi lain yang berkaitan<br />
dengan penelitian yang dilaksanakan<br />
Bappeda, Dinas Kelautan dan<br />
Perikanan<br />
Dinas Kelautan dan<br />
Perikanan, Dinas<br />
Perindustrian dan<br />
Perdagangan, Kadin<br />
Dinas Kelautan dan Perikanan<br />
Dinas Kelautan dan Perikanan<br />
Bappeda<br />
Bappeda<br />
BPS<br />
Badan Ketahanan Pangan<br />
Dinas Kelautan dan<br />
Perikanan, Dinas<br />
Perindustrian dan<br />
Perdagangan, Kadin<br />
Instansi terkait<br />
15<br />
-
· ..<br />
Adapun data yang di umpulkan dapat dikelompokkan sebagaimana yang dapat<br />
dilihat pada Tabel 7.<br />
Tabel7. Kelompok data yang diperlukan dalam penelitian<br />
No Kelompok Data Jenis Data Rincian<br />
1 Aspek teknis (termasuk sumberdaya)<br />
1. Aspek sumberdaya Usaha Budidaya - Luasan lahan usaha<br />
budidaya perikanan (kolam,<br />
terpal, dll)<br />
- Status kepemilikan lahan<br />
- Komoditi yang diusahakan<br />
Usaha Nelayan<br />
Usaha Pertanian<br />
- Jenis alat tangkap yang<br />
digunakan<br />
- Jenis perahu<br />
- Daerah tangkapan<br />
- Luasan lahan usahatani<br />
- Status kepemilikan lahan<br />
- Komoditi yang diusahakan<br />
2. Aspek teknis Teknologi Penerapan <strong>tekno</strong>logi<br />
2 Aspek <strong>sosial</strong> (termasuk ekonomi dan kelembagaan)<br />
1. Aspek <strong>sosial</strong> Budaya Perilaku masyarakat<br />
2. Aspek ekonomi Struktur usaha - Biaya operasional<br />
- Penerimaan usaha<br />
- Total pendapatan<br />
Sistem pemasaran<br />
3. Aspek kelembagaan Sistem<br />
kelembagaan<br />
3 Aspek ketahanan<br />
pangan<br />
i<br />
Preferensi<br />
Produksi<br />
Distribusi<br />
Konsumsi<br />
- Cara pembayaran<br />
Keadaan kelembagaan<br />
pangan (produksi,<br />
pemasaran, dll)<br />
-Urutan kesukaan pangan<br />
hewani<br />
-Alas an memilih pangan<br />
hewani<br />
-Penentuan pangan hewani<br />
yang dikonsumsi<br />
- Frekuensi mengkonsumsi<br />
ikan<br />
-Jumlah anggota keluarga<br />
yang mengkonsumsi ikan<br />
-Ketersediaan pangan ikan<br />
(cara mendapatkan ikan dan<br />
tempat membeli ikan)<br />
Produksi ikan<br />
-Harga ikan yang terjangkau<br />
- Pengaruh musim<br />
Kualitas dan keamanan<br />
pangan<br />
16
· ..<br />
3.3 Metoda Analisis<br />
Untuk mencapai tuj 'a _. j a<br />
pene litian seperti yang telah diuraikan pada bagian<br />
pendahuluan, maka akan dilakukan beberapa tahapan anal isis sesuai tujuan yang ingin<br />
dicapai (TabeI8) sebagai berikut:<br />
Tabel 8. Tujuan, Lingkup Data, Jenis Data, Metode Analisis dan Output Tahapan Penelitian<br />
No<br />
Tujuan<br />
1 Merumuskan <strong>desain</strong><br />
<strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> terbaik<br />
yang seharusnya<br />
dikembangkan <strong>untuk</strong><br />
perikanan rumah<br />
tangga <strong>untuk</strong><br />
ketahanan pangan<br />
tingkat rumah tangga<br />
2 Mengidentifikasi<br />
strategi yang tersedia<br />
bagi masyarakat <strong>untuk</strong><br />
mengimplementasikan<br />
<strong>desain</strong> terse but dalam<br />
kondisi dan situasi<br />
<strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> yang<br />
mereka hadapi<br />
3 Mengidentifikasi peran<br />
terbaik yang<br />
seharusnya dilakukan<br />
oleh pemerintah dalam<br />
mendukung<br />
implementasi <strong>desain</strong><br />
tersebut<br />
Ungkup dan<br />
sumber data<br />
- Studi<br />
pustaka<br />
- Responden<br />
di lokasi<br />
- Survey dan<br />
FGD<br />
- Studi<br />
pustaka<br />
- Surveydan<br />
FGD<br />
- Data-data<br />
terolah dari<br />
hasil<br />
sebelumnya<br />
- Data-data<br />
terolah dari<br />
hasil<br />
sebelumnya<br />
Jenis data<br />
- Data<br />
primer<br />
- Data<br />
sekunder<br />
- Data<br />
primer<br />
- Data<br />
sekunder<br />
- Data<br />
primer<br />
- Data<br />
sekunder<br />
Metode<br />
Analisis<br />
- Desk study<br />
- Deskriptif<br />
- Matriks dan<br />
tabulasi<br />
- Desk study<br />
dan diskusi<br />
- Deskriptif<br />
- Matriks dan<br />
tabulasi<br />
- Matriks dan<br />
tabulasi<br />
- Deskriptif<br />
Output yang<br />
diharapkan<br />
Rumusan <strong>desain</strong><br />
<strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong> terbaik<br />
yang seharusnya<br />
dikembangkan<br />
Strategi yang<br />
tersedia bagi<br />
masyarakat <strong>untuk</strong><br />
mengimplementasikan<br />
<strong>desain</strong> tersebut<br />
dalam kondisi dan<br />
situasi <strong>tekno</strong>-<strong>sosial</strong><br />
yang mereka hadapi<br />
Kesimpulankesimpulan<br />
tentang<br />
peran pemerintah<br />
dalam mendukung<br />
implementasi<br />
<strong>desain</strong> yang akan<br />
dikembangkan<br />
17
· .. <br />
IV. HASIL DAN ANALISIS <br />
4.1. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo<br />
4.1.1. Letak Geografis<br />
Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi<br />
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas wi/ayah 58.672,54 ha atau 586,72<br />
km 2 • Secara geografis terletak antara 7°38'42" - 7°38'42" Lintang Selatan dan<br />
110°1'37" - 110°16'26" Bujur Timur. Kulon Progo dalam bahasa Jawa berarti sebelah<br />
barat Sungai Progo, wilayahnya terletak di sebelah barat Sungai Progo. Kabupaten<br />
Kulon Progo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten<br />
Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah utara berbatasan dengan<br />
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan<br />
Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berhadapan<br />
dengan Samudra Indonesia.<br />
Secara administrasi, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah<br />
dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi DIY, dengan luas wilayahnya<br />
mencakup 18,36% luas wilayah Propinsi DIY. Ibukota Kabupaten adalah Wates yang<br />
terdiri atas 12 Kecamatan, 88 desa dan 930 Dusun (Tabel 9) dengan peta wilayah<br />
yang dapat dilihat pada Gambar 3.<br />
Tabel 9. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luasan Kabupaten Kulon Progo<br />
No Kecamatan Luas (Ha) Desa Dusun<br />
% Luas<br />
Kabupaten<br />
1 Temon 3.629 15 96 6,19<br />
2 Wates 3.200 8 68 5,46<br />
3 Panjatan 4.459 11 100 7,61<br />
4 Galur 3.291 7 75 5,61<br />
5 Lendah 3.559 6 62 6,07<br />
6 Sentolo 5.265 8 84 8,98<br />
7 Pengasih 6.167 7 78 10,52<br />
8 Kokap 7.380 5 59 12,59<br />
9 Nanggulan 3.961 6 61 6,76<br />
10 Girimulyo 5.491 4 57 9,37<br />
11 Samigaluh 6.929 7 106 11,82<br />
12 Kalibawang 5.296 4 84 9,03<br />
Total 58.627 88 930 100,00<br />
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo (2008)<br />
Wilayah pantai Kabupaten Kulon Progo, terletak di bagian selatan wilayah<br />
kabupaten ini, terdiri dari empat kecamatan dengan 10 desa, yaitu: Kecamatan<br />
Temon dengan empat desa: Jangkaran, Sindutan, Palihan dan Glagah; Kecamatan<br />
Wates dengan satu desa : Karangwuni; Kecamatan Panjatan dengan tiga desa:<br />
18
· ...<br />
Garongan, Pleret dan Bugel; serta Kecamatan Galur dengan dua desa: Karangsewu<br />
dan Banaran.<br />
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo<br />
4.1.2. Kondisi Topografi<br />
Kondisi topografi Kabupaten Kulon Progo terdiri atas dataran pantai di<br />
bagian selatan, di bagian tengah dan timur berupa topografi bergelombang sampai<br />
berbukit, dan di bagian barat serta utara berupa perbukitan-pegunungan. Rangkaian<br />
perbukitan-pegunungan di bagian barat dan utara Kulon Progo ini dikenal sebagai<br />
perbukitan Menoreh.<br />
Secara fisiografis kondisi Kabupaten Kulon Progo wilayahnya adalah daerah<br />
datar, meskipun dikelilingi pegunungan yang sebagian besar terletak pada wilayah<br />
utara. luas wilayahnya 17,58 % berada pada ketinggian < 7 m di atas permukaan<br />
19
.. ... <br />
laut, 15,20 % berada pada ketinggian 8 - 25 m di atas permukaan laut, 33,00 %<br />
berada pada ketinggian 101 - 500 m di atas permukaan laut, dan 11,37 % berada<br />
pada ketinggian > 500 m di atas permukaan laut. Jika dilihat letak kemiringannya luas<br />
wilayahnya 58,81 % kemiringannya < 15°, 18,73 % kemiringannya 16° - 40° dan 22,46<br />
% kemiringannya > 40°.<br />
4.1.3. Kondisi Hidrologi<br />
Sungai Progo dengan anak-anak sungainya, memiliki daerah pengalirannya<br />
seluas 8.894 hektar, dengan debit maksimum 381,90 m 3 /detik dan debit minimum<br />
13,00 m 3 /detik. Sungai Serang dengan anak-anak sungainya, memiliki daerah<br />
pengaliran seluas 3.635,75 hektar, dengan debit maksimum 153,6 m 3 /detik dan debit<br />
minimum 00,03 m 3 /detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan <strong>untuk</strong> irigasi<br />
persawahan seluas 9.351 ha. Selain air permukaan di Kabupaten Kulon Progo,<br />
terdapat potensi air bawah tanah dangkal sebanyak 7.000.204 m 3 •<br />
Curah hujan rata-rata/tahun di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2004<br />
adalah sebesar 2.664 mm dengan hari hujan rata-rata/bulan selama 14 hari. Musim<br />
hujan terjadi pada bulan Nopember - April. Hari hujan terbasah terjadi pada bulan<br />
Oesember sebesar 2.455 mm dengan hari hujan selama 19 hari hujan. Kondisi curah<br />
hujan yang tinggi ini telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di<br />
Kabupaten Kulon Progo, sedangkan <strong>untuk</strong> musim kemarau terjadi pada bulan Mei -<br />
Oktober.<br />
4.2. Kondisi Umum Sosial dan Ekologi Lokasi Penelitian<br />
Permasalahan dan berbagai penyebabnya saling terkait, mencakup aspek ekologis dan<br />
aspek-aspek <strong>sosial</strong> ekonomi masyarakat, yang terintegrasi dalam sebuah sistem. Integrasi<br />
seperti itu dikenal sebagai Social-Ecological Systems (SES) (Adrianto dan Aziz, 2006). Oengan<br />
menggunakan pendekatan SES diharapkan mampu meningkatkan ketahanan (resilience)<br />
melalui beberapa aksi baik dalam kerangka sistem lokal maupun nasional. Mengacu pada<br />
konsep sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi, sistem <strong>sosial</strong>-ekologi di lokasi<br />
penelitian dapat dimodelkan seperti pada Gambar 4. Oalam model tersebut, empat<br />
komponen pembentuk sistem adalah: (A) sumberdaya, (B) pengguna sumberdaya, (C)<br />
penyedia prasarana dan (0) berbagai bentuk prasarana publik.<br />
20
· ..<br />
7<br />
A. Sumberdaya<br />
- perairan pantai<br />
- k%m budidoyo<br />
-/ohon pertonian<br />
C. Penyedia Prasarana<br />
Publik<br />
Gambar 4. Kondisi SES di Lokasi Penelitian (Diadopsi dari Anderies et 0/2004)<br />
Berdasarkan hasil identifikasi, sumberdaya yang dimaksud adalah dalam bentuk<br />
perairan pantai, kolam pembudidaya dan lahan pertanian. Potensi dan realisasi penggunaan<br />
lahannya dapat dilihat pada Tabel10.<br />
Tabel10. Potensi dan realisasi penggunaan lahan (ha) di lokasi penelitian, 2009<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
RTP<br />
No<br />
Potensi Realisasi Potensi Realisasi Potensi Realisasi<br />
1 Kolam 4 0,8 4 0,5 9 0,4<br />
2 Sawah 9 - 3 - 6 -<br />
3 Keramba 0,9 - 0,7 - 2 -<br />
4 Tambak - - - - 40 -<br />
Jumlah 13,9 0,8 7,7 0,5 57 0,4<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaji data), Profil Data Pokok Kelautan dan Perikanan Kecamatan Wates<br />
2010<br />
Sedangkan pengguna sumbedaya adalah masyarakat nelayan, pembudidaya dan<br />
petani. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya rumah tangga perikanan yang ada di lokasi<br />
penelitian (Tabel 11) dan berkembangnya jumlah kelompok perikanan dan juga pertanian.<br />
Data kelompok perikanan di lokasi penelitian menurut desa secara berturut-turut dapat<br />
dilihat pada tabel12, 13 dan 14.<br />
Tabel11. Rumah tangga perikanan di lokasi penelitian, 2009<br />
No RTP Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
1 Budidaya kolam 91 73 65<br />
2 Tangkaplaut - - 10<br />
Jumlah 91 73 75<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Profil Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
21
· ..<br />
Tabel12. Kelompok perikanan di desa kulwaru kecamatan wates, 2009<br />
No Nama kelompok Kelas kelompok Jumlah anggota Jenis usaha<br />
1 Mina prospek Lanjut 30 Pembesaran Jele dan<br />
gurame<br />
2 Mina arya Pemula 30 Pembesaran lele dan<br />
gurame<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Profil Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
Tabel13. Kelompok perikanan di desa sogan kecamatan wates, 2009<br />
No Nama kelompok Kelas kelompok Jumlah anggota Jenis usaha<br />
1 Mina Aji Mandiri Pemula 25 Pembesaran lele dan<br />
gurame<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaji data), Profil Data Pokok Kelautan dan Perikanan Kec. Wates 2010<br />
Tabel14. Kelompok perikanan di desa karangwuni kecamatan wates, 2009<br />
No Nama kelompok Kelas kelompok Jumlah anggota Jenis usaha<br />
1 Ngudi Rezeki Madya 70 Tangkaplaut<br />
2 Sumber Rezeki Madya 25 Pedagang olahan<br />
3 Mina MuJya - 55 Pembesaran lele dan<br />
gurame<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Profil Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
Penyedia prasarana yang berhasil teridentifikasi di lokasi penelitian berbeda-beda di<br />
setiap desa. Di desa Karangwuni terdapat lembaga perekonomian seperti lembaga keuangan<br />
mikro (L<strong>KM</strong>) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Adapun di desa Sogan lembaga<br />
perekonomian yang ada diantaranya adalah L<strong>KM</strong> Binangun, L<strong>KM</strong> Panca Manunggal, bank<br />
kredit desa (BKD), Usaha ekonomi Produktif, Koperasi Eko Martani (hanya <strong>untuk</strong> anggota)<br />
dan Gapoktan. Sedangkan di desa Kulwaru lembaga perekonomian yang ada adalah lembaga<br />
keuangan mikro desa (L<strong>KM</strong>D), badan keswadayaan masyarakat (B<strong>KM</strong>), lembaga masyarakat<br />
desa (LMD), dan lembaga pembangunan masyarakat desa (LPMD). Selain di tingkat desa,<br />
masyarakat juga dapat mengakses permodalan ke lembaga di tingkat kabupaten dan<br />
kecamatan yang secara berturut-turut dapat dilihat di pada Tabel15 dan Tabel16.<br />
Tabel15. Lembaga penyedia permodalan tingkat Kabupaten Kulon Pro go, 2009<br />
No Kelompok Jenis Institusi<br />
1 Perikanan - UPP (unit pelayanan <strong>pengembangan</strong> bidang perikanan)<br />
- LEPM3 (<strong>untuk</strong> nelayan tangkap/pesisir)<br />
2 Pertanian - LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan)<br />
- PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan)<br />
- WPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat<br />
3 Peternakan L<strong>KM</strong>A (Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis)<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Profll Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
22
· ..<br />
Tabel16. Lembaga penyedia permodalan tingkat kecamatan di lokasi penelitian, 2009<br />
No Institusi Jumlah<br />
1 BPD, BRI, NUSAMBA 3<br />
2 Penggadaian 1<br />
3 Kantor Pos 1<br />
4 UPK {unit pelaksana keuangan)-PNPM 1<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Prof" Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
Selain lembaga permodalan, terdapat lembaga pembinaan baik di tingkat kabupaten<br />
dan kecamatan yang dapat dilihat pad a Tabel17.<br />
Tabel17. Lembaga pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan di lokasi penelitian,<br />
2009<br />
No Institusi Jenis Lembaga<br />
1 Kabupaten 1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Kulon Progo<br />
2. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab.Kulon Progo<br />
2 Kecamatan 1. BPP/BP3 kecamatan Wates<br />
2. PMD (kecamatan)<br />
3. l<strong>KM</strong>D (desa)<br />
4. KK lPMD (dusun)<br />
..<br />
Sumber: P3D (petugas pengelola penyaJI data), Profil Data Pokok Kelautan dan Penkanan Kec. Wates 2010<br />
I<br />
Keempat komponen utama terse but terikat dalam interaksi-interaksi sebagai berikut:<br />
1. Hubungan antara sumberdaya dan masyarakat<br />
Oeskripsi: berbagai kegiatan <strong>sosial</strong> maupun ekonomi masyarakat dengan kondisi<br />
sumberdaya alam dan penguasaan <strong>tekno</strong>loginya. Masyarakat tidak hanya memiliki satu<br />
jenis usaha sebagai sumber mata pencahariannya, meskipun memang ada dominasi<br />
tertentu.<br />
2. Hubungan antara masyarakat dan penyedia prasarana<br />
Oeskripsi: di kabupaten Kulon Progo tersedia sarana dan prasarana yang membantu<br />
<strong>peningkatan</strong> kondisi <strong>sosial</strong> ekonomi masyarakat.<br />
3. Hubungan antara penyedia prasarana dengan prasarana<br />
Deskripsi : Pembangunan infrastruktur yang semakin baik, seperti pembangunan jalan,<br />
jembatan, maupun jasa-jasa layanan komunikasi yang bertambah banyak. Jumlah sarana<br />
transportasi darat yang semakin banyak dan masuk ke pelosok-pelosok desa sehingga<br />
mengurangi kesenjangan daerah terisolir merupakan nilai tam bah bagi Kulonprogo. Sarana<br />
transportasi lain adalah tersedianya kereta api yang melewati Kabupaten Kulonprogo<br />
dengan stasiun yang berada di Kecamatan Temon, Wates, Pengasih, dan Sentolo<br />
merupakan kemudahan sarana transportasi massal dari dan ke Kulonprogo.<br />
23
·.. <br />
4. Hubungan antara sumberdaya dengan prasarana:<br />
Oeskripsi: sumberdaya yang tersedia baik lahan maupun pantai dimanfaatkan oleh<br />
masyarakat dengan baik sebagai sarana perekonomian. Untuk wilayah pesisir disekitar<br />
desa Karangwuni telah tersedia sarana pariwisata Pantai Glagah yang dilengkapi fasilitas<br />
agrowisata buah naga, bahkan dibangun pelabuhan perikanan. Dengan adanya<br />
pembangunan tersebut diharapkan memberikan multiflier effect bagi masyarakat di<br />
sekitarnya. Menurut Budihardjo dan Musofie, (2001) aktivitas tersebut berpotensi<br />
memberi dampak antara lain: <strong>pengembangan</strong> industri, pemukiman, reklamasi pantai,<br />
pelabuhan navigasi, transportasijinfastruktur, penangkapan ikan, budidaya tambak, lahan<br />
pertanian, aktivitas wisata/hotel, pertambangan/bahan galian dan lain-lain.<br />
5. Hubungan antara prasarana dengan interaksi antara masyarakat dan pengguna<br />
sumberdaya<br />
Oeskripsi: ketersediaan prasarana di lokasi penelitian membuat masyarakat dan pengguna<br />
sumberdaya memiliki kemudahan dalam mengakses tidak hanya informasi tetapi juga<br />
bahan baku dan pemasaran. Dengan format pemasaran terpadu yaitu mengintegrasikan<br />
semua komponen diharapkan komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat mampu berdaya<br />
saing karena didukung oleh kelembagaan yang baik dari hulu sampai hilir.<br />
6. Hubungan antara masyarakat dengan prasarana:<br />
Oeskripsi: Sarana dan prasarana yang tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan<br />
masyarakat. Berbagai fasilitas dimaksudkan <strong>untuk</strong> mempermudah masyarakat dalam<br />
mengakses bahan baku dan memasarkan hasil usahanya ke berbagai wilayah baik di<br />
sekitar maupun di luar Kulonprogo.<br />
7. Pengaruh eksternal terhadap prasarana:<br />
Oeskripsi: pengaruh eksternal terhadap prasarana yang ada di lokasi penelitian tentunya<br />
mendukung kearah pembangunan yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat<br />
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari rencana akan<br />
dibangunnya bandara bertaraf internasional di wilayah Kabupaten Kulonprogo.<br />
8. Pengaruh eksternal terhadap penyedia prasarana:<br />
Oeskripsi: pengaruh eksternal terhadap penyedia prasarana yang ada di lokasi penelitian<br />
bisa dikatakan tidak banyak karena penyedia prasarana yang ada merupakan institusi atau<br />
stakeholder yang berkewajiban <strong>untuk</strong> melaksanakan fungsi pelayanan baik itu pemerintah<br />
pusat ataupun daerah.<br />
24
4.3. Kondisi Ketahanan Pangan<br />
4.3.1. Pendapatan per Kapita Keluarga Contoh<br />
Pendapatan suatu keluarga akan menentukan daya beli keluarga tersebut<br />
baik <strong>untuk</strong> pangan maupun non pangan. Semakin besar pendapatan, semakin tinggi<br />
daya beli keluarga tersebut. Menurut Camelia (2002) rendahnya pendapatan<br />
merupakan rintangan yang menyebabkan orang tidak mampu membeli, memilih<br />
pangan yang bermutu gizi baik dan beragam. Sesuai Biro Pusat Statistik (2003) DIY,<br />
yang termasuk keluarga miskin jika pendapatannya ::; Rp 137.132/kap/bl dan tidak<br />
miskin > Rp 137.132/kap/bl.<br />
Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa seluruh keluarga contoh memiliki<br />
pendapatan per kapita keluarga dalam kategori tidak miskin (> Rp 137.132,-) di<br />
semua lokasi penelitian. Sesuai rata-rata pendapatan per kapita keluarga wilayah<br />
DIY sesuai data BPS 2003 maka, kedua wilayah penelitian termasuk dalam kategori<br />
tidak miskin (> Rp 137.132/kap/bln).<br />
Tabel 18. Pendapatan per kapita keluarga contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Pendapatan per Oesa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
Kapita Keluarga<br />
(Rp/kap/bln)<br />
n % n % n % n %<br />
Miskin ($ 137.132) - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Tidak miskin (><br />
137.132)<br />
15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
4.3.2. Preferensi produk perikanan<br />
Urutan kesukaan pangan hewani<br />
Dari Tabel 19 dapat dilihat bahwa sebagian besar contoh di semua lokasi<br />
penelitian (desa Kulwaru, desa Sogan dan desa Karangwuni) menyatakan suka<br />
dengan pangan hewani seperti daging, ikan, susu dan telur. Meskipun masih ada<br />
sebagian kecil saja contoh di semua lokasi penelitian yang menyatakan tidak suka<br />
<strong>untuk</strong> semua jenis pangan hewani tersebut.<br />
25
• <br />
Tabel19. Urutan kesukaan pangan hewani contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Urutan<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
kesukaan<br />
pangan hewani n % n % n % n %<br />
Daging<br />
Suka sekali 2 13,33 5 33,33 - 0,00 7 15,56<br />
Suka 7 46,67 4 26,67 9 60,00 20 44,44<br />
Biasa 4 26,67 5 33,33 5 33,33 14 31,11<br />
Tidak suka 2 13,33 1 6,67 1 6,67 4 8,89<br />
Tidak suka - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Ikan<br />
sekali<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Suka sekali 6 40,00 4 26,67 9 60,00 19 42,22<br />
Suka 8 53,33 10 66,67 5 33,33 23 51,11<br />
Biasa 1 6,67 1 6,67 1 6,67 3 6,67<br />
Tidak suka - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Tidak suka - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
sekali<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Telur<br />
Suka sekali 1 6,67 3 20,00 - 0,00 4 8,89<br />
Suka 8 53,33 10 66,67 5 33,33 23 51,11<br />
Biasa 5 33,33 2 13,33 9 60,00 16 35,56<br />
TIdak suka 1 6,67 - 0,00 1 6,67 2 4,44<br />
Tidak suka - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
sekali<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Susu<br />
Suka sekali 4 26,67 4 26,67 3 20,00 11 24,44<br />
Suka 4 26,67 8 53,33 4 26,67 16 35,56<br />
Biasa 4 26,67 2 13,33 7 46,67 13 28,89<br />
Tidak suka 3 20,00 1 6,67 1 6,67 5 11,11<br />
Tidak suka - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
sekali<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: datd primer (2010)<br />
Alasan memilih pangan hewani<br />
Contoh di lokasi penelitian memiliki alasan <strong>untuk</strong> mengkonsumsi pangan<br />
hewani termasuk ikan karena rasanya lebih enak dengan persentase 47,67%.<br />
Sebagian besar contoh mengungkapkan bahwa alasan lainnya dalam mengkonsumsi<br />
pangan hewani tersebut adalah mudah diperoleh (40,00%). Contoh di semua lokasi<br />
penelitian (desa kulwaru, desa sogan dan desa karangwuni) tidak ada yang<br />
menjawab mengkonsumsi pangan hewani karena alas an lebih terhormat. Menurut<br />
contoh, daging lebih enak rasanya bila dibandingkan dengan ikan (Tabel 14).<br />
~<br />
26
Tabel20. Alasan yang diberikan contoh dalam memilih pangan hewani di lokasi<br />
penelitian, 2010<br />
Alasan memilih<br />
pangan hewani<br />
yang disukai<br />
Oesa<br />
Kulwaru<br />
Desa Sagan Desa Karangwuni Total<br />
n 96 n 96 n 96 n 96<br />
Rasanya lebih enak 6 40,00 5 33,33 10 66,67 21 46,67<br />
- 0,00 1 6,67 3 20,00 4 8,89<br />
Sudah terbiasa dari<br />
kecil<br />
Lebih terhormat - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Mudah diperoleh 12 80,00 3 20,00 3 20,00 18 40,00<br />
Harganya<br />
6 40,00 4 26,67 1 6,67 11 24,44<br />
terjangkau<br />
Lainnya - 0,00 1 6,67 4 26,67 5 11,11<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Penentu pang an hewani yang dikonsumsi<br />
Sebagian besar contoh (48,89%) di lokasi penelitian menyatakan bahwa istri<br />
sebagai ibu rumah tanggalah yang menentukan jenis pangan hewani yang akan<br />
dikonsumsi keluarga sebagai menu makan sehari-hari. Selanjutnya berturut-turut<br />
adalah suami (24,44%) dan anak, orang tua ataupun orang lain yang tinggal dalam<br />
rumah tangga masing-masing sebesar 8,89% turut berperan dalam menentukan<br />
jenis pangan hewani yang akan dikonsumsi keluarga. Secara lengkap data dan<br />
informasi mengenai penentu pangan hewani yang dikonsumsi contoh di lokasi<br />
penelitian dapat dilihat pad a Tabel 21.<br />
Tabel21. Penentu pangan hewani yang dikonsumsi contoh di lokasi penelitian,<br />
2010<br />
Penentu jenis<br />
pangan<br />
Desa Kulwaru Desa Sagan Desa Karangwuni Total<br />
hewani yang<br />
dikonsumsi<br />
n % n % n % n %<br />
Suami 4 26,67 3 20,00 4 26,67 11 24,44<br />
Istri 8 53,33 5 33,33 9 60,00 22 48,89<br />
Anak 2 13,33 2 13,33 - 0,00 4 8,89<br />
Orangtua - 0,00 2 13,33 2 13,33 4 8,89<br />
Lainnya 1 6,67 3 20,00 - 0,00 4 8,89<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Frekuensi mengkonsumsi ikan<br />
Frekuensi mengkonsumsi ikan pada contoh digolongkan menjadi lima<br />
kategori berdasarkan Suhardjo (1989) . Pada Tabel 22 dapat dilihat bahwa frekuensi<br />
mengkonsumsi ikan pada contoh di desa Kulwaru (93,33%) dan desa Karangwuni<br />
(40,00%) adalah 1-2 kali seminggu. Yang mengkonsumsi ikan sebanyak 4-6 kali<br />
seminggu sebnyak 6,67% di desa Sogan dan 46,67% di desa Karangwuni. Sedangkan<br />
27
· ..<br />
yang mengkonsumsi ikan lebih dari 7 kali seminggu hampir tidak ada di semua<br />
wilayah. Sesuai dengan maraknya kampanye gemar makan ikan, maka disarankan<br />
paling tidak mengkonsumsi ikan 2 kali dalam seminggu (Dahuri 2004). Dari tabel x<br />
tersebut ternyata eontoh yang mengkonsumsi kurang dari 1 kali seminggu sebanyak<br />
6,67% di desa Kulwaru, 53,33% di desa Sogan dan 13,33% di desa Karangwuni.<br />
label 22. Frekuensi mengkonsumsi ikan eontoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Frekuensi<br />
mengkonsumsi<br />
ikan per mgg<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Tidak pernah - 0,00 6 40,00 - 0,00 6 13,33<br />
< 1x 1 6,67 8 53,33 2 13,33 11 24,44<br />
1-2 X 14 93,33 - 0,00 6 40,00 20 44,44<br />
3x - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
4-6 x - 0,00 1 6,67 7 46,67 8<br />
7x - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
lumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi ikan<br />
label 23 menunjukkan bahwa mayoritas contoh di desa kulwaru (93,33%)<br />
dan desa karangwuni (80,00%) semua anggota keluarganya menyukai ikan dan<br />
hanya sekitar 6,67% contoh di desa kulwaru dan 20,00% eontoh di desa karangwuni<br />
yang tidak semua anggota keluarganya menyukai ikan. Sedangkan di desa Sogan<br />
yang semua anggota keluarganya mengkonsumsi ikan adalah sebanyak 46,67%<br />
eontoh dan yang tidak semua anggota keluarganya mengkonsumsi ikan sebanyak<br />
-<br />
53,33% eontoh. Hal ini dikarenakan ketersediaan ikan di desa kulwaru dan<br />
karangwuni lebih banyak dan mudah diperoleh dibandingkan dengan desa sogan,<br />
karena merupakan dari pekerjaan utma kepala keluarga sebagai pembudidaya ikan<br />
dan nelayan. Alasan eontoh yang tidak semua anggota keluarganya menyukai ikan<br />
adalah tidak suka pad a bau ikan yang amis, karena tidak terbiasa dari keeil, alergi<br />
terutama pada ikan tongkol, banyak durinya terutama pada ikan bandeng.<br />
label 23. Jumlah anggota keluarga eontoh yang mengkonsumsi ikan di lokasi<br />
penelitian, 2010<br />
Jumlah anggota<br />
keluarga yang<br />
mengkonsumsi<br />
ikan<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Semua 14 93,33 7 46,67 12 80,00 33 73,33<br />
Tidak semua 1 6,67 8 53,33 3 20,00 12 26,67<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
28
·.. <br />
Ketersediaan pangan ikan<br />
Cara mendapatkan ikan<br />
Sebagian besar contoh di lokasi penelitian memperoleh ikan dengan cara<br />
membeli (62,22%). Selanjutnya berturut-turut adalah hasil budidaya sendiri<br />
(37,78%), hasil tangkapan suami (31,11%) dan pemberian dari tetangga sebesar<br />
2,22% (Tabel 24). Hal ini dikarenakan contoh di lokasi penelitian yaitu desa Kulwaru<br />
mempunyai lahan <strong>untuk</strong> melakukan budidaya ikan sendiri khususnya <strong>untuk</strong> jenis<br />
ikanlele dan gurame. Selain itu contoh di desa Karangwuni juga memang<br />
merupakan nelayan yang tinggal di wilayah dekat pantai. Kalaupun ikan itu harus<br />
diperoleh dengan cara membeli, seluruh contoh di lokasi penelitian menyatakan<br />
bahwa cara membayar tunai (TabeI25).<br />
Tabel24. Cara mendapatkan ikan contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Cara Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
mendapatkan<br />
Ikan<br />
n % n % n % n %<br />
Membeli 9 60,00 11 73,33 8 53,33 28 62,22<br />
Pemberian - 0,00 - 0,00 1 6,67 1 2,22<br />
tetangga<br />
Hasil<br />
1 6,67 - 0,00 13 86,67 14 31,11<br />
tangkapan<br />
suami<br />
Hasil budidaya 11 73,33 6 40,00 - 0,00 17 37,78<br />
sendiri<br />
Sumber: data primer (2010) <br />
Tabel 25. Cara membeli ikan contoh di lokasi penelitian, 2010 <br />
Cara membeli Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
ikan n % n % n % n %<br />
Beli tunai 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Berhutang - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Tempat membeli ikan<br />
Pada Tabel 26 dapat terlihat bahwa secara keseluruhan (100,00%) di lokasi<br />
penelitian memiliki pili han tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ikan,<br />
sebagian besar responden (53,33%) memiliki keterkaitan dengan pasar tradisional<br />
<strong>untuk</strong> memenuhi kebutuhan akan ikan, dan sebagian besar masyarakatnya berada<br />
pada Oesa Sogan (66,67%). Alasannya adalah Oesa Sogan cenderung memiliki lokasi<br />
yang lebih jauh ke TPI dibandingkan kedua desa lainnya, sehingga masyarakat lebih<br />
cenderung membeli pada pasar dibandingkan harus mendatangi TPI.<br />
29
· ..<br />
Desa Karangwuni memiliki<br />
kaitan yang kuat dengan TPI dalam rangka<br />
pemenuhan kebutuhan akan ikan (53,33%), dikarenakan profesi nelayan terpusat<br />
pada desa karangwuni dan TPI berada pada lokasi inL, sehingga responden menjadi<br />
mudah <strong>untuk</strong> mendapatkan ikan. Disisi lain, sebanyak 22,22% responden memilih<br />
pilihan lainnya, yaitu ikan yang didapatkan tidak selalu membeli tetapi bisa<br />
didapatkan dari hasil tangkapan sendiri ataupun meminta dari teman, sekedarnya<br />
<strong>untuk</strong> lauk makan.<br />
Tabel26. Tempat membeli ikan contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Tempat Desa Kulwaru Oesa Sagan pesa Karangwuni Total<br />
membeli ikan n % n % n % n %<br />
Warung makan 7 46,67 1 6,67 1 6,67 9 20,00<br />
Pasar tradisional 7 46,67 10 66,67 7 46,67 24 53,33<br />
Pedagang 5 33,33 5 33,33 1 6,67 11 24,44<br />
keliling<br />
Tempat<br />
2 13,33 1 6,67 8 53,33 11 24,44<br />
pelelangan ikan<br />
Lainnya 3 20,00 2 13,33 5 33,33 10 22,22<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
4.3.3. Stabilitas ketersediaan ikan<br />
Harga ikon yang terjangkau<br />
Harga ikan terendah (rata-rata) yang dibeli oleh responden (di tiga desa)<br />
<strong>untuk</strong> dikonsumsi adalah Rp 9.567,00. Harga ini lebih tinggi jika dibandingkan<br />
dengan Desa karangwuni dan Desa Kulwaru. Kondisi ini dikarenakan kedua desa<br />
tersebut merupakan desa penghasil ikan (darat maupun laut). Harga terendah<br />
terdapat di Desa karangwuni sebesar Rp 7.500,00, hal ini dikarenakan sebagaian<br />
besar responden memakan ikan hasil tangkapan sendirL Sebagai desa penghasil<br />
ikan laut, Desa Karangwuni memiliki sebaran harga ikan yang bervariasi dari yang<br />
murah hingga mahal. Dalam hal ini, harga ikan tertinggi terdapat di Desa<br />
Karangwuni Rp26.455 jauh diatas harga rata-rata ketiga desa. Penjelasannya adalah<br />
terkadang ikan yang dimakan merupakan ikan dengan harga mahal seperti bawal,<br />
udang. Secara rinci informasi mengenai rata-rata harga ikan yang terjangkau oleh<br />
contoh di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 27 .<br />
Tabel 27. Rata-rata harga ikan (Rp) yang terjangkau contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Harga ikan (Rp) Desa Kulwaru Desa Sagan Desa Karangwuni Rata-rata<br />
Harga terendah 8.050 13.150 7.500 9.567<br />
Harga tertinggi 17.200 21.667 26.455 21.774<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
30
· ..<br />
Pengoruh musim<br />
Pad a Tabel 28 dapat dilihat bahwa 51,11% responden<br />
ditiga desa<br />
menyatakan musim mempengaruhi dalam aktivitas konsumsi ikan dengan proporsi<br />
terbesar terdapat di Desa Karangwuni (66,67%), Desa Kulwaru (53,33%) dan Desa<br />
Sogan (33,33%).<br />
Sedangkan responden di Desa Sogan (66,67%) menyatakan<br />
musim tidak berpengaruh terhadap konsumsi ikan dikarenakan sebagian besar<br />
responden membeli ikan di pasar tradisional yang terkadang dipasok dari luar<br />
lokasi sehingga <strong>untuk</strong> musim tertentu pasokan ikan(kembung, petek) masih<br />
tersedia. Pada Desa karangwuni, sebagian besar responden (66,67%) menyatakan<br />
bahwa musim ikut berpengaruh dalam konsumsi ikan. Kondisi ini dikarenakan desa<br />
ini merupakan desa yang merupakan desa nelayan sehingga musim sangat<br />
mempengaruhi aktivitas penangkapan nelayan dan pada akhirnya mempengaruhi<br />
hasil tangkapan yang dikonsumsi.<br />
Tabel 28. Pengaruh musim terhadap konsumsi ikan contoh 2010<br />
Pengaruh Desa Kulwaru Desa Sagan Desa Karangwuni Total<br />
musim n % n % n % n %<br />
Va 8 53,33 5 33,33 10 66,67 23 51,11<br />
Tidak 7 46,67 10 66,67 5 33,33 22 48,89<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
4.3.4. Kualitas dan keamanan pangan<br />
Pengetohuon ten tong ikon<br />
Tingkat pengetahuan tentang ikan contoh dibagi dalam 3 kategori yaitu<br />
kurang (menjawab kurang dari 60% pertanyaan yang benar), sedang (menjawab<br />
60% sampai 80% pertanyaan dengan benar) dan baik (menjawab lebih dari 80%<br />
pertanyaan dengan benar) (Khomsan 2000). Berdasarkan Tabel 29 dapat dilihat<br />
bahwa ditiga desa sebagain besar responden belum mengetahui ciri-ciri ikan yang<br />
baik (48,89%) dan didominasi oleh Desa sogan sebanyak (93,33%). Hal ini<br />
dimungkinkan karena Desa Sogan merupakan desa pertanian dan tidak berinteraksi<br />
langsung dengan ikan (budidaya ikan dan penangkapan) sehingga informasi tentang<br />
ciri-ciri ikan yang baik menjadi terbatas. Lain halnya dengan responden Desa<br />
karangwuni yang masuk kategori sedang memiliki 60% pengetahuan akan ikan yang<br />
baik dan respond en Desa Sogan yang mengetahui ciri ikan yang baik sebanyak 40%.<br />
31
. ..<br />
Tabel29. Pengetahuan tentang ciri-ciri ikan contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Pengetahuan<br />
tentang ciri-ciri<br />
Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni Total<br />
ikan n % n % n % n %<br />
Baik 6 40 0 0 4 26,67 10 22,22<br />
Sedang 3 20 1 6,67 9 60 13 28,89<br />
Kurang 6 40 14 93,33 2 13,33 22 48,89<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Kerocunon ikon<br />
Pada Tabel 30 berikut ini terlihat bahwa pada Desa Sogan dan Karangwuni<br />
tidak terjadi kasus keracunan ikan. Dalam hal ini walaupun responden Desa Sogan<br />
sebagian besar tidak mengetahui cirri-ciri ikan yang baik (93,33%) pada tabel<br />
pengetahuan ikan, namun, tidak ditemukan kasus keracunan ikan. Kondisi ini<br />
dimungkinkan karena jenis ikan yang dimakan merupakan jenis-jensi ikan yang biasa<br />
dikonsumsi di masyarakat seperti ikan lele, banding, kembung dll sehingga tidak<br />
<br />
<br />
ditemukan kasus keracunan ikan. Pada desa Kulwaru terdapat responden yang<br />
pernah terjadi keracunan ikan, namun kondisi ini tidak terlalu berbahaya (tidak<br />
sampai di rawat di rumah sakit). Kondisi yang terjadi masih dalam tahap awal, yaitu<br />
alergi memakan ikan (tongkol). Berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa<br />
mayoritas responden (95,56%) tidak pernah keracunan ikan.<br />
Tabel 30. Kejadian keracunan ikan contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Keracunan Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni Total<br />
ikan n % n % n % n %<br />
Pernah 2 13,33 0 - 0 - 2 4,44<br />
Tidak pernah 13 86,67 15 100 15 100 43 95,56<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
4.3.5. Aksesibilitas<br />
Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh masyarakat terhadap<br />
suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan di sekitarnya. Jarak dari desa-desa<br />
lokasi penelitian ke kanator kecamata berkisar antara 3 - 10 km (Tabel 31). Hal ini<br />
menunjukkan bahwa akses transportasi dalam lokasi penelitia tersebut tidak terlalu<br />
jauh. Didukung dengan fasilitas dan sarana perhubungan dalam kondisi baik dan<br />
mulus sebagaimana yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan.<br />
Modal aksesibilitas tersebut mempermudah masyarakat <strong>untuk</strong> melakukan kegiatan<br />
pembelian sarana prasarana produksi maupun penjualan dan pemasaran hasilnya.<br />
32
· .. <br />
Tabel 31. Jarak dari desa ke kecamatan (km) menurut lokasi penelitian, 2008<br />
Uraian Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni<br />
Jarak desa ke<br />
kecamatan (km)<br />
3 3 10<br />
Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka (2008)<br />
4.4. Kondisi Variabel Pengembangan Usaha Pendukung Ketahanan Pangan RT Berbasis Perikanan<br />
4.4.1. Varia bel-varia bel di luar rumah tangga<br />
Tataguna lahan<br />
Untuk <strong>pengembangan</strong> perikanan banyak dilakukan masyarakat di lahan<br />
pekarangan rumah. Penggunaan lahan di lokasi penelitian diantaranya adalah tanah<br />
sawah, tanah kering, bangunan dan lain-lain (Tabel 32). Dengan sistem pengairan di<br />
lokasi penelitian seluruhnya (100%) merupakan<br />
pengairan setengah teknis (Tabel<br />
33).<br />
Tabel 32. Tata guna lahan di lokasi penelitian (ha)<br />
Jenis lahan Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni<br />
Tanah sawah 107,8 146,5 143,23<br />
Tanah kering 69,66 7,65 110,71<br />
Bangunan 56.17 89.3 258,4<br />
Hutan negara - - -<br />
Hutan rakyat - - -<br />
lainnya 18,11 7 210,01<br />
Total 251J4 250,45 143,23<br />
Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka (2008) <br />
Tabel33. Luas tanah sawah menurut jenis pengairan di lokasi penelitian (ha) <br />
Jenis pengairan Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Teknis - - -<br />
Semi teknis 107,8 146,5 140,17<br />
Sederhana - - -<br />
Tadah hujan - - 3,06<br />
Total 107,8 146,5 143,23<br />
Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka (2008)<br />
Sarana Prasarana pendukung<br />
Sarana prasarana pendukung yang ada di lokasi penelitian bervariasi dari<br />
mulai sarana prasarana produksi budidaya perikanan dan pertanian serta sarana<br />
prasarana umum seperti irigasi, transportasi (angkutan darat seperti bis, kereta api,<br />
dan lain-lain) termasuk berbagai lembaga pendukung baik keuangan, permodalan<br />
dan pemasaran. Meskipun tidak terlalu banyak namun di masing-masing wilayah<br />
sudah tersedia berbagai fasilitas tersebut (Tabel 34).<br />
33
· ...<br />
Tabel 34. Sarana prasarana pendukung di lokasi penelitian, 2010<br />
Jenis pengairan<br />
Sarpras produksi budidaya perikanan:<br />
Desa<br />
Kulwaru<br />
Desa<br />
Sogan<br />
Desa<br />
Karangwuni<br />
Penyedia saprokan di desa 15 4 3<br />
Penyedia saprokan di dalam kecamatan yang - - -<br />
sama<br />
Penyedia saprokan di dalam kabupaten yang sama - - -<br />
Penyedia saprokan di dalam propinsi yang sama - - -<br />
Sarpras produksi pertanian:<br />
Penyedia saprokan di desa 15 4 3<br />
Penyedia saprokan di dalam kecamatan yang - - -<br />
sama<br />
Penyedia saprokan di dalam kabupaten yang sama - - -<br />
Penyedia saprokan di dalam propinsi yang sama - - -<br />
Sarpras umum:<br />
Irigasi - Ada -<br />
Transportasi Ada Ada Ada<br />
Sumber energy Ada Ada Ada<br />
Lainnya: ........ - - -<br />
Lembaga keuangan:<br />
Penyedia permodalan di dalam desa 4 6 2<br />
Penyedia permodalan di dalam kecamatan 7 7 7<br />
Penyedia permodalan di dalam kabupaten 6 6 6<br />
Penyedia permodalan di dalam propinsi - - -<br />
Lembaga pembinaan:<br />
Lembaga pembinaaan di dalam desa 4 4 4<br />
Lembaga pembinaaan di dalam kecamatan 2 2 2<br />
Lembaga pembinaaan di dalam kabupaten 2 2 2<br />
Lembaga pembinaaan di dalam propinsi - - -<br />
Lembaga pemasaran:<br />
Keberadaan pedagang penampung di dalam desa 4 2 5<br />
Keberadaan pedagang penampung di dalam kec - - -<br />
Keberadaan pedagang penampung di kabupaten - - -<br />
Keberadaan pedagang penampung di dalam prop - - -<br />
Sumber: Monografl desa (2009)<br />
Klasifikasi penduduk<br />
Jumlah penduduk di Desa Kulwaru adalah 2.937 orang, di desa Sogan<br />
sebanyak 2.351 orang dan di desa Karangwuni sebanyak 2.960 orang. Kondisi<br />
kependudukan di lokasi penelitian menurut jenis kelamin dan banyaknya penduduk<br />
yang dewasa dan anak-anak dapat dilihat pada Tabel 35 berikut ini:<br />
Tabel35. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Lokasi Penelitian, 2007<br />
No Jenis Kelamin Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
1 Laki-Laki 1.431 1.173 1.498<br />
- Dewasa 1.077 888 1.136<br />
- Anak-anak 354 285 362<br />
2 Perempuan 1.506 1.178 1.462<br />
- Dewasa 1.144 288 1.102<br />
- Anak-anak 416 1.173 360<br />
Jumlah 2.937 2.351 2.960<br />
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2008<br />
34
Sebagian besar rumah tangga di lokasi penelitian adalah pada sektor<br />
pertanian. Adapun banyaknya rumah tangga menu rut sektor kegiatan utama dapat<br />
dilihat pada Tabel 36 berikut ini.<br />
Tabel36.<br />
Banyaknya rumah tangga menurut sektor kegiatan utama di lokasi<br />
penelitian, 2007<br />
No Sektor kegiatan utama Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
1 Pertanian 313 295 626<br />
2 Pertambangan - - 8<br />
3 Industri 12 12 17<br />
4 Listri k, gas da n ai r - - -<br />
5 Bangunan/konstruksi 113 35 36<br />
6 Perdaganan 54 27 56<br />
7 Angkutan 3 5 7<br />
8 Lembaga keuangan - - -<br />
9 Jasa lainnya 97 63 18<br />
lumlah 592 437 768<br />
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2008<br />
4.4.2. Variabel tingkat rumah tangga<br />
Struktur rumah tangga berdasarkan umur dan jenis kelamin<br />
Struktur anggota rumah tangga contoh di Desa Kulwaru sebagian besar<br />
berada pada kelompok umur 41 - 50 tahun (53,33%) dan sisanya pada kelompok<br />
umur ~<br />
40 tahun yaitu 46,67%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan struktur<br />
anggota rumah tangga contoh di Desa Karangwuni. Struktur rumah tangga yang lebih<br />
bervariasi terdapat pada Desa Sogan, dimana sebagian besar contoh berada pada<br />
kelompok umur 51 -<br />
60 tahun (46,67%). Selanjutnya berturut-turut berada pada<br />
kelompok umur 41- 50 tahun (33,33%), ~ 40 tahun (13,33) dan: 60 tahun (6,67%).<br />
Secara lengkap struktur rumah tangga contoh berdasarkan kelompok umur di lokasi<br />
penelitian yang mencakup 3 (tiga) desa berdasarkan dominansi pekerjaan utama<br />
masyarakatnya yaitu budidaya peri kanan, pertanian dan penangkapan ikan disajikan<br />
pada Tabel 37.<br />
Tabel 37. Karakteristik rumah tangga contoh berdasarkan kelompok umur (%), 2010<br />
Uraian<br />
~ 40<br />
tahun<br />
41- 50<br />
tahun<br />
51- 60<br />
tahun<br />
~ 61<br />
tahun<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
7 46,67 2 13,33 8 53,33 17 37,78<br />
8 53,33 5 33,33 7 46,67 20 44,44<br />
- 0,00 7 46,67 - 0,00 7 15,56<br />
- 0,00 1 6,67 - 0,00 1 2,22<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer diolah<br />
35
Struktur anggota rumah tangga contoh berdasarkan umur kepala<br />
keluarganya di Desa<br />
Kulwaru dan Karangwuni rata-rata berumur 40 tahun,<br />
sedangkan di desa sogan rata-rata berumur 51 tahun. Sementara itu struktur<br />
anggota rumah tangga contoh bila dilihat dari besaran jumlah anggota keluarga di<br />
semua wilayah adalah rata-rata 4 orang (termasuk ayah dan ibu), dengan kisaran<br />
yang bervariasi. Untuk desa Kulwaru besar anggota keluarganya berkisar antara 2 - 6<br />
orang, di desa Sogan berkisar antara 2 - 8 orang dan di desa Karangwuni berkisar<br />
antara 2 -<br />
5 orang. Secara lebih rinci struktur rumah tangga contoh berdasarkan<br />
umur rata-rata kepala keluarga dan jumlah anggota keluarganya dapat dilihat pad a<br />
Tabel38.<br />
Tabel 38. Karakteristik Rumah tangga contoh berdasarkan umur rata-rata dan<br />
jumlah anggota rumah tangga, 2010<br />
Uraian Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Umur KK (tahun)<br />
- Rata-rata 40 51 40<br />
- Kisaran 28-47 32 - 64 30 - 50<br />
Jumlah anggota keluarga (orang)<br />
- Rata-rata 4 4 4<br />
- Kisaran 2-6 2-8 2-5<br />
Sumber: data primer diolah<br />
Struktur rumah tangga berdasarkan pendidikan dan pekerjaan<br />
Dari Tabel 39 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh<br />
contoh dalam hal ini sebagai kepala keluarga adalah lulusan Sekolah Menengah Atas.<br />
Hal ini terlihat dari besaran contoh di setiap lokasi penelitian, di desa Kulwaru dan<br />
desa Sogan masing-masing sebesar 66,67% dan desa Karangwuni sebesar 40%.<br />
Bahkan di desa Kulwaru ada salah satu contoh yang lulus kuliah. Meskipun demikian<br />
di lokasi lainnya, tepatnya di desa Karangwuni terdapat 6,67% contoh yang tidak<br />
tamat Sekolah Dasar.<br />
Tabel 39. Kondisi Pendidikan SDM di lokasi penelitian, 2010<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
Uraian<br />
n % n % n % n %<br />
Tidak tam at SD - 0,00 - 0,00 1 6,67 1 2,22<br />
Tamat SD - 0,00 3 20,00 6 40,00 9 20,00<br />
Tidak tam at SMP - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Tamat SMP 4 26,67 2 13,33 2 13,33 8 17,78<br />
Tidak tamat SMA - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Tamat SMA 10 66,67 10 66,67 6 40,00 26 57,78<br />
Kuliah 1 6,67 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer diolah<br />
36
· .. <br />
Ditinjau dari pekerjaan utama contoh hampir seluruhnya sesuai dengan<br />
tipologi pekerjaan utama masyarakatnya. Desa Kulwaru yang merupakan desa<br />
berbasis budidaya perikanan, Desa Sogan merupakan desa dengan mayoritas<br />
masyarakatnya adalah petani dan desa Karangwuni adalah desa pantai sehingga<br />
pekerjaan masyarakatnya yang dominan adalah nelayan. Meskipun ada beberapa<br />
contoh yang juga berprofesi sebagai Pegawai Swasta ataupun Pegawai Negeri Sipil.<br />
Sementara itu, rata-rata contoh melakukan usaha sampingan dengan memanfaatkan<br />
lahan dan sumberdaya yang dimilikinya yaitu sebagai pembudidaya ikan, petani<br />
ataupun nelayan (TabeI40).<br />
Tabel40. Karakteristik rumah tangga contoh berdasarkan pekerjaan, 2010<br />
Uraian<br />
Pekerjaan utama<br />
KK<br />
Pembudidaya<br />
ikan<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
13 86,67 - 0,00 - 0,00 13 28,89<br />
Petani - 0,00 15 100,00 - 0,00 15 33,33<br />
Peternak - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Nelayan - 0,00 - 0,00 11 73,33 11 24,44<br />
Swasta 1 6,67 - 0,00 - 0,00 1 2,22<br />
PNS/honor 1 9,67 - 0,00 4 Z6,97 5 H,ll<br />
Lainnya - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Pekerjaan<br />
sampingan KK<br />
Pembudidaya<br />
ikan<br />
- 0,00 - 0,00 2 13,33 2 4,44<br />
Petani 13 86,67 - 0,00 14 93,33 27 60,00<br />
Peternak 11 73,33 13 86,67 - 0,00 24 53,33<br />
Nelayan - 0,00 - 0,00 4 26,67 4 8,89<br />
0,00 -<br />
Swasta - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
PNS/honor - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
Lainnya 1 6,67 - 0,00 - 0,00 1 2,22<br />
Sumber: data primer diolah<br />
Untuk mendukung kapasitas contoh dalam melakukan usaha sebagai mata<br />
pencaharian-nya, sebagian besar contoh telah sering mengikuti pelatihan yang<br />
dilaksanakan oleh institusi pemerintahan (Tabel 41). Kegiatan pelatihan tersebut<br />
meliputi kegiatan pelatihan di bidang perikanan, pertanian, peternakan ataupun<br />
bidang lainnya (TabeI42).<br />
37
· ..<br />
Tabel41. Kondisi Kewirausahaan SDM dengan mengikuti pelatihan, 2010<br />
Uraian<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Pernah 8 53,33 10 66,67 13 86,67 31 68,89<br />
Tidak pernah 7 46,67 5 33,33 2 13,33 14 31,11<br />
Total 15 100,00 15 100,00 15 100,00 45 100,00<br />
Sumber: data primer (2010) <br />
Tabel42. Kondisi Kewirausahaan SDM <strong>untuk</strong> jenis pelatihan yang diikuti, 2010 <br />
Jenis pelatihan<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Mengikuti pelatihan<br />
bidang perikanan<br />
- 0,00 - 0,00 29 19,33 29 64,44<br />
Mengikuti pelatihan<br />
bidang pertanian<br />
13 86,67 16 106,7 3 20,00 32 71,11<br />
Mengikuti pelatihan<br />
bidang peternakan<br />
2 13,33 - 0,00 - 0,00 2 4,44<br />
Mengikuti pelatihan<br />
bidang lainnya<br />
2 13,33 2 13,33 - 0,00 2 4,44<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Pemilikan asset produksi<br />
Kelengkapan peralatan rumah tangga contoh berupa barang-barang<br />
kebutuhan rumah tangga menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga contoh di desa<br />
kulwaru dan sogan memiliki televisi. Demikian pula halnya dengan kendaraan seperti<br />
motor. Bahkan ada contoh dalam satu rumah tangga yang memiliki motor lebih dari<br />
1 (satu). Secara umum, contoh sudah memiliki berbagai perlengkapan rumah tangga<br />
yang menunjukkan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara lengkap<br />
kepemilikan perlengkapan rumah tangga contoh di lokasi penelitian dapat dilihat<br />
pada Tabel 43 berikut ini.<br />
Tabel 43. Kelengkapan rumah tangga contoh di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
1. TV 15 100,00 15 100,00 13 86,67 43 95,56<br />
2. Tape recorder 12 80,00 10 66,67 5 33,33 27 60,00<br />
3. Radio 11 73,33 9 60,00 7 46,67 27 60,00<br />
4. Emas 6 40,00 8 53,33 8 53,33 22 48,89<br />
5. Motor 16 106,67 15 100,00 19 126,67 50 111,11<br />
6. DVD/VCD 9 60,00 11 73,33 8 53,33 28 62,22<br />
7. Tanah 11 73,33 10 66,67 11 73,33 32 71,11<br />
8. Motor/Mobil - - 2 13,33 - - 2 4,44<br />
9. Perahu 1 6,67 - - 5 33,33 6 13,33<br />
10. Jaring 2 13,33 1 6,67 9 60,00 12 26,67<br />
11. Mesin 13 86,67 6 40,00 15 100,00 34 75,56<br />
Sumber: data primer dlolah<br />
38
· .. <br />
Sistem Pemasaran<br />
Pada Tabel 44 sistem pemasaran usaha perikanan di lokasi penelitian dapat<br />
dilihat bahwa pad a Desa Kulwaru, sebagian besar (46,67%) harga jual ikan<br />
ditentukan oleh pedagang. Salah faktornya adalah dikarenakan desa kulwaru<br />
merupakan desa budidaya ikan sehingga harga seringkali ditentukan oleh para<br />
pengepul dan terdapat 26,67% yang dilakukan dengan kompromi (tawar menawar).<br />
Pada Desa Sogan mayoritas responden menyatakan lainnya (86,67%) hal ini<br />
dikarenakan sebagian besar responden tidak memiliki komoditas ikan <strong>untuk</strong> dijual.<br />
Sedangkan <strong>untuk</strong> Desa Karangwuni responden lainnya sebanyak (80%), hal ini<br />
dikarenakan ikan yang dijual mengikuti harga pasaran. Berdasarkan ketiga desa<br />
dapat disimpulkan bahwa 60% responden menyatakan bahwa harga jual komoditas<br />
perikanan ditentukan dengan lainnya, yaitu harga yang berlaku dipasaran dan<br />
26,67% responden yang menyatakan penentu harga juala adalah pedagang.<br />
Dalam hal penjualan hasil perikanan di ketiga desa dapat dilihat bahwa<br />
mayoritas keputusan berada ditangan suami yaitu 71,11% dan merata diseluruh<br />
desa; Kulwaru (60%), Sogan (66,67%) dan Karangwuni (86,67%). Hal ini menunjukkan<br />
bahwa suami lebih dominan dalam pengambilan keputusan menjual hasil perikanan<br />
dan dikarenakan bahwa suami merasa yang lebih mengerti harga<br />
karena<br />
bersentuhan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Demikian halnya dalam hal<br />
pembelian sarana dan prasarana perikanan terdapat 55,56% responden menyatakan<br />
bahwa suami yang berperan.<br />
Tabel 44. Sistem pemasaran usaha perikanan di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Yang menentukan harga jual sendiri<br />
1 Pedagang 7 46,67 2 13.33 3 20,00 12 26,67<br />
2 Penjual 2 13,33 - 0,00 - 0,00 2 4,44<br />
3 Kompromi 4 26,67 - 0,00 - 0,00 4 8,89<br />
4 Lainnya 2 13,33 13 86,67 12 80,00 27 60,00<br />
Yang menentukan <strong>untuk</strong> menjual hasil<br />
1 Suami 9 60,00 10 66,67 13 86,67 32 71,11<br />
2 Istri 3 20,00 2 13,33 - 0,00 5 11,11<br />
3 Suami istri 2 13,33 2 13,33 - 0,00 4 8,89<br />
4 Lainnya 1 6,67 1 6,67 2 13,33 4 8,89<br />
Yang dominan dalam pembelian<br />
1 Suami 12 80,00 - 0,00 13 86,67 25 55,56<br />
2 Istri - 0,00 - O,DO - 0,00 - 0,00<br />
3 Suami istri 1 6,67 - 0,00 - 0,00 1 2,22<br />
4 Lainya 2 13,33 15 100,00 2 13,33 19 42,22<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
39
· ..<br />
Sistem pemasaran usaha pertanian (tabel 45), <strong>untuk</strong> ketiga desa terlihat<br />
bahwa harga jual ditentukan oleh harga pasaran (48,89%) dan merata di masingmasing<br />
desa: Kulwaru (46,67%), Sogan (40,00%) dan Karangwuni (60%) sedangkan<br />
terdapat 4,44% responden (penjual) dalam hal ini petani yang menentukan harga<br />
jual. Pada usaha pertanian ini, yang menentukan menjual hasil adalah suami<br />
sebanyak 42,22% dan merata di Desa Sogan 66,67% dan Karangwuni 60,00%.<br />
Sedangkan pada desa Kulwaru yang menentukan penjualan adalah suami istri<br />
33,33% hal ini dikarenakan sering kali terdapat kebutuhan yang mendesak atau<br />
membandingkan harga yang ada sehingga terjadi diskusi diantara keduanya. Pada<br />
ketiga desa, urusan pembelian sarana pertanian, mayoritas ditentukan oleh suami<br />
(86,67%), diikuti oleh desa: Kulwaru (86,67%), Sogan (93,33%) dan Karangwuni<br />
(80%) .<br />
Tabel45. Sistem pemasaran usaha pertanian di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Yang menentukan harga jual sendiri<br />
1 Pedagang 3 20.00 4 26.67 4 26.67 11 24.44<br />
2 Penjual 2 13,33 - 0,00 - 0,00 2 4,44<br />
3 Kompromi 2 13,33 5 33,33 2 13,33 9 20,00<br />
4 Lainnya 7 46,67 6 40,00 9 60,00 22 48,89<br />
Yang menentukan <strong>untuk</strong> menjual hasil<br />
1 Suami 3 20,00 10 66,67 6 60,00 19 42,22<br />
2 Istri 3 20,00 2 13,33 3 20,00 8 17,78<br />
3 Suami istri 4 26,67 2 13,33 3 20,00 9 20,00<br />
4 Lainnya 5 33,33 1 6,67 3 20,00 9 20,00<br />
Yang dominan dalam pembelian<br />
1 Suami 13 86,67 14 93,33 12 80,00 39 86.67<br />
2 Istri - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00<br />
3 Suami istri - 0,00 - 0,00 2 13,33 2 4,44<br />
4 Lainya 2 13,33 1 6,67 1 6,67 4 8,89<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Sementara itu, sistem pemasaran usaha peternakan (TabeI46) di ketiga desa<br />
86,67% responden menyatakan bahwa harga jual ditentukan oleh lainnya , yaitu<br />
harga pasaran. Demikian halnya yang terjadi pada desa: Sogan (40,00%) dan<br />
Karangwuni (86,67%). Sedangkan responden di Desa Kulwaru menyatakan 86,67%.<br />
Hal ini dimungkinkan karena tidak terjadi kesepakatan harga sehingga lebih banyak<br />
dilakukan dengan cara kompromi. Penentu penjualan hasil peternakan pada Desa<br />
Kulwaru berimbang antara suami (33,33%), istri(33,33%) dan lainnya 33,33% (adanya<br />
kebutuhan tertentu). Sedangkan yang dominant dalam pembelian sarana<br />
peternakan di ketiga desa adalah suami 46,67%.<br />
40
·<br />
.. <br />
Tabel46. Sistem pemasaran usaha peternakan di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Oesa Karangwuni Total<br />
n % n % n % n %<br />
Yang menentukan harga jual sendiri<br />
1 Pedagang 3 20,00 4 26,67 - 0,00 7 15,56<br />
2 Penjual 3 20,00 - 0,00 - 0,00 3 6,67<br />
3 Kompromi 5 33,33 5 33,33 2 13,33 12 26,67<br />
4 Lainnya 4 26,67 6 40,00 13 86,67 23 86,67<br />
Yang menentukan <strong>untuk</strong> menjual hasil<br />
1 Suami 5 33,33 10 66,67 2 13,33 17 37,78<br />
2 Istri 5 33,33 2 13,33 - 0,00 7 15,56<br />
3 Suami istri - 0,00 2 13,33 - 0,00 2 4,44<br />
4 Lainnya 5 33,33 1 6,67 13 86,67 19 42,22<br />
Yang dominan dalam pembelian<br />
1 Suami 7 46,67 13 86,67 1 6,67 21 46,67<br />
2 Istri 1 6,67 - 0,00 - 0,00 1 2,22<br />
3 Suami istri - 0,00 1 6,67 1 6,67 2 4,44<br />
4 Lainya 7 46,67 1 6,67 13 86,67 21 46,67<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Pengeluaran rumah tangga<br />
Pengeluaran rumah tangga (makanan dan minuman) di tiga desa terlihat<br />
bahwa sebagian besar digunakan <strong>untuk</strong> pengeluaran beras, Kulwaru (46,68%), Sogan<br />
(46,86%) dan Karangwuni (50,61%). Pengeluaran rokok ditiga desa terbilang besar<br />
yaitu Kulwaru (11,58%), Sogan (12,85%) dan Karangwuni (12,23%). Untuk<br />
pengeluaran non makanan, pada desa Kulwaru<br />
dan karangwuni pengeluaran<br />
terbesar terdapat pada pemeliharaan rumah sebersa 48,73% dan 45,24%. Sedangkan<br />
pada Desa Sogan pengeluaran terbesar terdapat pada biaya hajatan/ menghadiri<br />
undangan 14,12 %. Hal ini dikarenakan pada saat itu sedang marak-makanya hajatan<br />
yang dilakukan oleh sanak famili yang berakibat membesarnya biaya non makan.<br />
Secara rinci pengeluaran contoh <strong>untuk</strong> pangan dan non-pangan dapat dilihat pada<br />
Tabel47.<br />
41
Tabel47. Pengeluaran rumah tangga di lokasi penelitian, 2010<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Uraian<br />
Rata-rata<br />
Rata-rata<br />
Rata-rata<br />
%<br />
%<br />
(Rp) (Rp) (Rp)<br />
%<br />
A. Makanan dan minuman<br />
1 Beras 663.479 46,68 499.800 46,86 958.500 50,61<br />
2 Makanan pokok lain 185.600 13,06 155.667 14,60 182.967 9,66<br />
3 Mie dan jajan selingan 38.571 2,71 14.667 1,38 15.385 0,81<br />
4 Kopi/gula/teh/susu 86.570 6,09 89.429 8,39 156.533 8,27<br />
5 Lauk pauk/sayuran 73.000 5,14 94.000 8,81 80.071 4,23<br />
6 Rokok/tembakau 164.667 11,58 137.000 12,85 231.667 12,23<br />
7 Lainnya 209.545 14,74 75.917 7,12 268.600 14,18<br />
Total 1.421.432 1.066.479 1.893.723<br />
B. Non makanan<br />
1 Bahan bakar 54.633 1,89 84.733 9,40 142.143 2,79<br />
2 Penerangan/listrik 34.933 1,21 49.400 5,48 44.867 0,88<br />
3 Kesehatan 100.214 3,48 73.667 8,17 78.667 1,54<br />
4 Transportasi 182.333 6,32 60.500 6,71 74.233 1,46<br />
5 Pendidikan 145.533 5,05 98.867 10,96 103.667 2,03<br />
6 Pakaian 167.692 5,82 46.000 5,10 314.667 6,17<br />
7 Pemeliharaan rumah 1.405.000 48,73 48.667 5,40 2.306.111 45,24<br />
8 Rekreasi 154.615 5,36 23.333 2,59 142.667 2,80<br />
9 Sosial/sumbangan 56.154 1,95 110.000 12,20 276.333 5,42<br />
10 Hajatan/selamatan 173.667 6,02 127.333 14,12 231.333 4,54<br />
11 luran/keagamaan 189.000 6,55 11.556 1,28 72.933 1,43<br />
12 Pajak 44.917 1,56 61.528 6,82 15.833 0,31<br />
13 Sabun cuci / mandi 81.462 2,83 35.067 3,89 62.900 1,23<br />
14 Lainnya 93.333 3,24 71.071 7,88 1.231.538 24,16<br />
Total 2.883.487 901.721 5.097.892<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Kondisi dan Usaha Responden<br />
Sistem Usaha Perikanan<br />
Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya ikan.<br />
Secara garis besar, perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya,<br />
baik di darat maupun di laut. Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang<br />
melakukan penangkapan terhadap hewan air dan tumbuhan air, sedangkan<br />
perikanan budidaya adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan manusia dalam<br />
membudidayakan hewan air dan tumbuhan air.<br />
Menurut Permen No 05 Tahun 2008 disebutkan bahwa usaha perikanan<br />
adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi<br />
praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pengertian sistem usaha<br />
perikanan (SUP) mengacu pada pengertian sistem usaha pertanian atau agribisnis<br />
adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perikanan. SUP ini<br />
42
· ..<br />
mempunyai 2 makna yang berbeda namun saling berhubungan, yaitu: 1) suatu sistem<br />
usaha dan 2) suatu sistem terpadu.<br />
SUP sebagai suatu sistem ekonomi adalah suatu perusahaan yang bergerak<br />
dalam bidang yang berhubugan dengan perikanan. Hal ini dicirikan dengan: 1)<br />
berorientasi pasar dimana barang/jasa yang dihasilkan disalurkan (dijual) melalui<br />
pasar dan sebagian atau seluruhnya sarana produksi yang dibutuhkan diperoleh<br />
(dibeli) dari pasar; dan 2) bersifat rasional, bertujuan <strong>untuk</strong> memperoleh manfaat<br />
(keuntungan) ekonomi yang sebesar-besarnya. Kegiatan perikanan dapat<br />
digolongkan sebagai sistem usaha perikanan jika memiliki kedua ciri tersebut. Jika<br />
kegiatan perikanan yang bertujuan <strong>untuk</strong> memenuhi kebutuhan sendiri maka tidak<br />
tergolong SUP karena tidak melalui pasar. Demikian pula halnya dengan kegiatan<br />
perikanan yang dimaksudkan sekedar hobi juga bukan termasuk SUP karena tidak<br />
<strong>untuk</strong> memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya.<br />
Bidang usaha dari sistem usaha perikanan ini meliputi: 1) usaha <strong>untuk</strong><br />
menghasilkan sarana produksi usaha perikanan (industri peralatan dan material<br />
usaha perikanan); 2) usaha perikanan; 3) usaha yang mengolah produksi usaha<br />
perikanan; dan 4) usaha perdagangan sarana produksi, produksi primer dan produksi<br />
olahan usaha perikanan. Sistem usaha perikanan ini tidak membedakan skala usaha.<br />
Usaha produksi juga termasuk SUP bahkan merupakan komponen utamanya.<br />
SUP sebagai suatu sistem terpadu merupakan satu kesatuan jaringan yang<br />
tidak terpisahkan antara 4 (em pat) komponen, yaitu: 1) jaringan perusahaan; 2)<br />
konsumen; 3) kebijakan dan kondisi perekonomian makro; dan 4) lembaga<br />
penunjang. Berikut diuraikan usaha perikanan yang dilakukan oleh respond en di<br />
lokasi penelitian.<br />
Budidaya Lele<br />
Usaha budidaya lele dimaksudkan <strong>untuk</strong> menghasilkan benih sampai<br />
berukuran tertentu dengan cara mengawinkan induk jantan dan betina pada kolamkolam<br />
khusus pemijahan. Pembenihan lele mempunyai prospek yang bagus dengan<br />
tingginya konsumsi lele serta banyaknya usaha pembesaran lele. Yang banyak<br />
dilakukan di lokasi penelitian adalah usaha pembesaran lele di kolam terpal dengan<br />
memanfaatkan lahan pekarangan. Berikut adalah analisa usaha budidaya lele di<br />
kolam terpal yang dilakukan oleh responden penelitian (TabeI48).<br />
43
· ..<br />
Tabel48. Analisis usaha budidaya IeIe di kolam terpal 8 x 4 m yang dilakukan<br />
responden di lokasi penelitian , 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya investasi<br />
Terpal ukuran 10 x 6 m 1 buah 360.000 360.000<br />
Sekam 3 m j 1 paket 10.000 10.000<br />
Siaya gali kolam 1 paket 200.000 200.000<br />
Selang 15 meter 2.500 37.500<br />
Ember karet 2 buah 10.000 20.000<br />
Gayung 1 buah 5.000 5.000<br />
lamit 1 buah 15.000 15.000<br />
Jumlah biaya investasi 747.500<br />
Biaya operasional<br />
Sibit lele size 4-6 em 3500 ekor 100 350.000<br />
Garam 1 unit 5.000 5.000<br />
Pakan <strong>untuk</strong> 2 bulan 350 kg 6.000 2.100.000<br />
Obat-obatan utk 2 bulan 1 unit 10.000 10.000<br />
Jumlah biaya bibit, pakan<br />
2.465.000<br />
dan obat-obatan<br />
b. Tenaga kerja 60 HOK 15.000 180.000<br />
Jumlah biaya tenaga kerja 180.000<br />
Jumlah biaya fA) 2.645.500<br />
Ponen (8)<br />
350 kg 10.000 3.500.000<br />
lele size 7 -12/ kg<br />
Pendapatan (8 - C) 854.500<br />
SIC 1,32<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
Budidaya Gurame<br />
Budidaya ikan gurame, mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi.<br />
Disamping rasanya yang lezat dan empuk, ikan ini pun digemari banyak orang. Sudah<br />
menjadi tradisi dalam setiap kendurian, ikan gurame selalu menjadi syarat utama<br />
hidangan. Disamping rasanya itu, perawatannya pun tidak terlalu sulit dan tidak<br />
memakan banyak biaya, sehingga banyak petani ikan yang mulai menggemari,<br />
membudidayakan ikan ini, karena harga dari setiap bibitnya yang murah dapat<br />
menghasilkan keuntungan 3 kali lipat dari harga bibit. Harga dari ikan gurame di<br />
pasaran sangat bervariasi tergantung dari bobot ikan tersebut. Berikut adalah analisa<br />
usaha budidaya gurame yang dilakukan oleh responden penelitian dengan<br />
memanfaatkan lahan pekarangan dan pakan dari hasil samping yang ada di areal<br />
sawah atau pertanian mereka (Tabel 49).<br />
44
Harga (Rp)<br />
360.000 360.000<br />
10.000 10.000<br />
200.000 200.000<br />
2.500 37.500<br />
10.000 20.000<br />
Gayung 5.000 5.000<br />
Lamit 15.000 15.000<br />
inllestasi 747.500 .<br />
1.000 IS0.000<br />
• Garam 5.000 5.000<br />
Pakan <strong>untuk</strong> 2 tahun 1 sak 200.000 200.000<br />
Obat-obatan utk 2 bulan 1 unit 50.000 50.000<br />
1umlah biaya bib it, pakan 405.000<br />
dan obat-obatan<br />
b. 60 HOK 15.000<br />
180.000<br />
---=--~--------~------~------~--------+--------------4<br />
1um/ah biaya tenaga kerja 180.000<br />
lumlah biaya (A) 585.000<br />
Panen fB} gurame 1 ekor/kg 150 25.000 3.750.000 •<br />
• Pendapatan (8 - C)<br />
3.165.000 i<br />
. SIC<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Sistem Usaha Pertanian<br />
Areal di desa-desa pantai Kulon Progo terdiri dari lahan<br />
sawah, lahan<br />
I tegalan, lahan pasir dan di beberapa desa terdapat lahan<br />
sawah surjan. Areal ....or""..'::1 sebagian besar menggunakan<br />
dan<br />
setengah teknis, kedl lainnya menggunakan sederhana atau<br />
hujan tanam dilihat 50.<br />
Tabel 50. Kalender tanam di lokasi penelitian<br />
8 9 10<br />
Sawah Padi Kedelai Padi<br />
Padi Kacang tanah Padi<br />
Padi<br />
Padi<br />
Padi<br />
• Surjan<br />
Padi<br />
Padi<br />
Padi Cabe merah merah<br />
Cabe merah<br />
Sayur<br />
Cabe merah<br />
Semangka<br />
Bawang<br />
Cabe merah<br />
Cabe merah,<br />
Kacang tanah<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
45
· ..<br />
Tabel49. Analisis usaha budidaya gurame di kolam terpal8 x 4 m yang dilakukan<br />
responden di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya investasi<br />
Terpal ukuran 10 x 6 m 1 buah 360.000 360.000<br />
Sekam 3 m 3 1 paket 10.000 10.000<br />
Biaya gali kolam 1 paket 200.000 200.000<br />
Selang 15 meter 2.500 37.500<br />
Ember karet 2 buah 10.000 20.000<br />
Gayung 1 buah 5.000 5.000<br />
Lamit 1 buah 15.000 15.000<br />
lumloh bioyo inllestosi 747.500<br />
Biaya operasional<br />
Bibit gurame 150 ekor 1.000 150.000<br />
Garam 1 unit 5.000 5.000<br />
Pakan <strong>untuk</strong> 2 tahun 1 sak 200.000 200.000<br />
Obat-obatan utk 2 bulan 1 unit 50.000 50.000<br />
lumlah biaya bibit, pakan<br />
405.000<br />
dan obat-obatan<br />
b. Tenaga kerja 60 HOK 15.000 180.000<br />
lumlah biaya tenaga kerja 180.000<br />
lumlah biaya fA) 585.000<br />
Panen (8) gurame 1 ekor/kg 150 kg 25.000 3.750.000<br />
Pendapatan (B C) 3.165.000<br />
B/C 5,41<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Sistem Usaha Pertanian<br />
Areal pertanian di desa-desa pantai kabupaten Kulon Progo terdiri dari lahan<br />
sawah, lahan kering / tegalan, lahan pasir dan di beberapa desa terdapat lahan<br />
sawah surjan. Areal persawahan sebagian besar telah menggunakan irigasi teknis dan<br />
setengah teknis, sebagian kecil lainnya menggunakan irigasi sederhana atau tadah<br />
hujan dengan kalender tanam dapat dilihat pada Tabel 50.<br />
Tabel 50. Kalender tanam di lokasi penelitian<br />
Lahan<br />
Bulan<br />
11 I 12 I 1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10<br />
Sawah Padi Kedelai Padi<br />
Padi Kacang tanah Padi<br />
Padi Kacang hijau merah (abe merah<br />
Padi Jagung (abe merah<br />
Padi Bawang merah (abe merah<br />
Surjan Bawang merah (abe merah, Sayur (abe merah<br />
Padi Padi Padi<br />
Padi Bawang merah (abe merah (abe merah<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Semangka (abe merah Sayur<br />
Melon (abe merah Semangka<br />
Bawang merah<br />
(abe merah<br />
(abe merah,<br />
Kacang tanah<br />
.--<br />
45
Beberapa komoditas dominan di areal persawahan meliputi: tanaman<br />
pangan padi, kedelai, kacang tanah; tanaman hortikultura cabe merah, bawang<br />
merah, dan semangka atau melon; sedangkan <strong>untuk</strong> lahan kering / pasir adalah<br />
tanaman hortikultura cabe merah, bawang merah, dan semangka atau melon.<br />
Komoditas dominan di lahan sawah surjan meliputi padi, bawang merah, cabe<br />
merah, dan sayuran.<br />
Tanaman pangan <br />
Pad; <br />
Komoditas padi, oleh petani penggarap sawah di desa-desa pantai masih<br />
merupakan komoditi yang diunggulkan. Komoditas ini dianggap sebagai komoditas<br />
strategis sebagai penyangga kebutuhan pangan petani. Dalam jumlah sedikit, petani<br />
menjadikan komoditas ini sebagai komoditas perdagangan.<br />
Diduga karena alasan tersebut, petani kurang tertarik menggunakan benih<br />
padi unggul varietas baru; petani masih memanfaatkan benih IR-64 sebagai benih<br />
yang yang selalu ditanam dari tahun ke tahun selama beberapa tahun ini. Cara<br />
bercocok tanam umumnya dilakukan seara sederhana, benih yang ditanam masih<br />
dalam jumlah banyak (ombo/), dengan umur benih > 20 hari. Akibat hal tersebut,<br />
produktivitas tanaman padi tidak mengalami <strong>peningkatan</strong> secara signifikan meskipun<br />
telah diberi pupuk anorganik (urea) melebihi takaran yang dianjurkan.<br />
Budidaya tanaman padi di desa-desa pantai di bagian selatan Kabupaten<br />
Kulon Progo, secara alami menggantungkan air yang berasal dari sistem pengairan<br />
yang ada, baik dari saluran irigasi ataupun dari air hujan. Umumnya tanaman padi<br />
dibudidayakan hanya pada MT 1 dan MT 2.<br />
Meskipun umumnya petani lahan sawah juga memiliki ternak (sapi,<br />
domba/kambing), jarang bahkan tidak dijumpai adanya petani memanfaatkan bahan<br />
organik dari limbah kandang ternaknya. Petani umumnya tidak memiliki tenaga yang<br />
cukup <strong>untuk</strong> memanfaatkan limbah kandang ternak sebagai pupuk di lahan<br />
~ sawahnya.<br />
Pasca panen padi dilaksanakan secara sederhana; apabila petani kurang<br />
memiliki tenaga <strong>untuk</strong> mengolah, biasanya hasil tanaman ini dijual di lahan secara<br />
tebasan. Rice milling unit (RMU) keliling lebih berperan dominan dalam melayani<br />
kebutuhan petani dalam penggilingan padi. Pemanfaatan RMU keliling ini meskipun<br />
46
· ..<br />
Beberapa komoditas dominan di areal persawahan meliputi: tanaman<br />
pangan padi, kedelai, kacang tanah; tanaman hortikultura cabe merah, bawang<br />
merah, dan semangka atau melon; sedangkan <strong>untuk</strong> lahan kering / pasir adalah<br />
tanaman hortikultura cabe merah, bawang merah, dan semangka atau melon.<br />
Komoditas dominan di lahan sawah surjan meliputi padi, bawang merah, cabe<br />
merah, dan sayuran.<br />
Tanaman pangan<br />
Pad;<br />
Komoditas padi, oleh petani penggarap sawah di desa-desa pantai masih<br />
merupakan komoditi yang diunggulkan. Komoditas ini dianggap sebagai komoditas<br />
strategis sebagai penyangga kebutuhan pangan petani. Dalam jumlah sedikit, petani<br />
menjadikan komoditas ini sebagai komoditas perdagangan.<br />
Diduga karena alasan tersebut, petani kurang tertarik menggunakan benih<br />
padi unggul varietas baru; petani masih memanfaatkan benih IR-64 sebagai benih<br />
yang yang selalu ditanam dari tahun ke tahun selama beberapa tahun ini. Cara<br />
bercocok tanam umumnya dilakukan seara sederhana, benih yang ditanam masih<br />
dalam jumlah banyak (omboJ), dengan umur benih > 20 hari. Akibat hal tersebut,<br />
produktivitas tanaman padi tidak mengalami <strong>peningkatan</strong> secara signifikan meskipun<br />
telah diberi pupuk anorganik (urea) melebihi takaran yang dianjurkan.<br />
Budidaya tanaman padi di desa-desa pantai di bagian selatan Kabupaten<br />
Kulon Progo, secara alami menggantungkan air yang berasal dari sistem pengairan<br />
yang ada, baik dari saluran irigasi ataupun dari air hujan. Umumnya tanaman padi<br />
dibudidayakan hanya pada MT 1 dan MT 2.<br />
Meskipun umumnya petani lahan sawah juga memiliki ternak (sapi,<br />
domba/kambing), jarang bahkan tidak dijumpai adanya petani memanfaatkan bahan<br />
organik dari limbah kandang ternaknya. Petani umumnya tidak memiliki tenaga yang<br />
cukup <strong>untuk</strong> memanfaatkan limbah kandang ternak sebagai pupuk di lahan<br />
sawahnya.<br />
Pasca panen padi dilaksanakan secara sederhana; apabila petani kurang<br />
memiliki tenaga <strong>untuk</strong> mengolah, biasanya hasil tanaman ini dijual di lahan secara<br />
tebasan. Rice milling unit (RMU) keliling lebih berperan dominan dalam melayani<br />
kebutuhan petani dalam penggilingan padi. Pemanfaatan RMU keliling ini meskipun<br />
46
· ..<br />
hasil berasnya tidak begitu memuaskan, namun petani lebih memandangnya sebagai<br />
upaya menghemat biaya tranportasi.<br />
Limbah tanaman padi, berupa jerami padi umumnya dimanfaatkan oleh<br />
petani pemilik ternak sapi yang sebagian besar bukan harus pemilik tanaman padi<br />
yang sedang panen. Pemanfaat jerami padi umumnya petani-peternak sapi yang<br />
datang <strong>untuk</strong> mengumpulkan jerami padi setelah mereka membantu panen. Diduga,<br />
karena pemanfaat jerami tersebut bukan pemilik tanaman, sedangkan mereka<br />
mempunyai keinginan <strong>untuk</strong> dapat mengumpulkan jerami dalam jumlah banyak<br />
dengan waktu cepat, mereka kurang memperhatikan kualitas dan kuantitas produk<br />
tanaman. Hal ini juga diduga menyebabkan kehilangan waktu panen lebih banyak.<br />
Berikut adalah analisis usaha pertanian padi yang dilakukan oleh petani yang menjadi<br />
responden di lokasi penelitian (Tabel 51).<br />
Tabel 51. Analisa usaha pertanian padi (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
Biaya<br />
Uraian<br />
Volume<br />
Min Mak Mayoritas<br />
Satuan<br />
Harga<br />
(Rp)<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Benih (IR64, Ciherang) 40 90 80 Kg 5.000 400.000<br />
Jumlah biaya benih 400.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 0 Kg<br />
- urea 250 500 350 Kg 2.000 700.000<br />
- SP 36 0 100 25 Kg 2.500 62.500<br />
- NPK 50 250 200 Kg 2.250 450.000<br />
-KCI 50 250 50 Kg 3.000 150.000<br />
- ZA 25 100 50 Kg 1.400 70.000<br />
Jumlah biaya pupuk 1.432.500<br />
Pengolahan tanah<br />
(traktor)<br />
600.000<br />
Tenaga kerja<br />
- penanaman Boro<br />
Borongan 1.000.000<br />
ngan<br />
- penyiangan 20 20 HOK 25.000 500.000<br />
- panen Boro<br />
Borongan 500.000<br />
ngan<br />
Pestisida & insektisida 140.000<br />
Jumlah biaya lain 2.740.000<br />
Total biaya (A) 4.572.500<br />
Produksi (S) 5.000 6.500 5.800 Kg 2.000 11.600.000<br />
Pendapatan (S-A) 7.027.500<br />
RIC 1,54<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
47
· ..<br />
Kedelai<br />
Komoditas kedelai umumnya ditanam di lahan sawah setelah tanaman padi.<br />
Komoditas ini ditanam hanya sebagai tanaman selingan setelah tanaman padi.<br />
Umumnya petani tidak merawat secara intensif komoditi ini; benih yang ditanampun<br />
umumnya adalah benih lokal yang diperoleh dari pasar, bukan benih berlabel.<br />
Setelah benih tanaman disebarjditugal, dibiarkan tanpa perawatan, pemupukan,<br />
serta tanpa pengendalian hamajpenyakit. Bercocok tanam dengan cara tersebut,<br />
diduga menyebabkan produktivitas tanaman kurang baik. Pasca panen dilaksanakan<br />
secara sederhana; apabila petani kurang memiliki tenaga <strong>untuk</strong> mengolah, biasanya<br />
hasil tanaman ini dijual di lahan secara tebasan. Limbah tanaman kedelai (titen),<br />
umumnya dimanfaatkan sebagai pakan. Berikut adalah analisa usaha pertanian<br />
kedelai dalam setiap hektar lahan yang dimiliki oleh petani yang menjadi responden<br />
penelitian (Tabel 52).<br />
Tabel 52. Analisa usaha pertanian kedelai (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih local 50 Kg 7.500 375.000<br />
Jumlah biaya benih 375.000<br />
Pupuk<br />
Jumlah biaya pupuk 0<br />
Tenaga tanam dan perawatan 50 HOK 15.000 750.000<br />
Tenaga penylangan 20 HOK 15.000 300.000<br />
Pestisida & insektisida 250.000<br />
Jumlah biaya lain 1.300.000<br />
Total biaya (A) 1.675.000<br />
Produksi (B) 750 Kg 6.500 4.875.000<br />
Pendapatan (B-A) 3.200.000<br />
RIc 1,91<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Kacanq tanah<br />
Budidaya tanaman kacang tanah umumnya dilakukan oleh petani di lahan<br />
kering/lahan pasir, sedikit dibudidayakan di lahan sawah. Umumnya dalam budidaya<br />
kacang tanah digunakan benih lokal, dikelola secara sederhana. Budidaya kacang<br />
tanah di lahan pasir, umumnya petani melaksanakan secara tumpang sari dengan<br />
tanaman cabe merah atau bawang merah, atau memanfaatkan lahan sisa di bawah<br />
tegakan tanaman kelapa. Budidaya kacang tanah di lahan pasir ini, dinilai merupakan<br />
48
,. .. <br />
upaya petani <strong>untuk</strong> meningkatkan produktivitas lahan. Di beberapa wilayah di desa<br />
pantai termasuk desa Karangwuni, kacang tanah dibudidayakan di lahan sawah<br />
setelah tanaman padi pada MT ke 2. Budidaya kacang tanah di lokasi ini, umumnya<br />
dilakukan dengan cara lebih intensif. Produk kacang tanah umumnya dipasarkan ke<br />
pedagang pengumpul dalam bentuk kacang glondong, jarang petani menjualnya<br />
dalam ose karena petani tidak memiliki alat pemipil. Berikut adalah analisa usaha<br />
yang dilakukan oleh petani yang menjadi responden di lokasi penelitian (Tabel 53).<br />
Tabel 53. Analisa usaha pertanian kacang tanah (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih SO Kg 10.000 500.000<br />
Jumlah biaya benih 500.000<br />
Pupuk<br />
Jumlah biaya pupuk 0<br />
Tenaga tanam dan perawatan 30 HOK 15.000 450.000<br />
Pestisida & Insektisida 0<br />
Jumlah biaya lain 450.000<br />
Total biaya (A) 950.000<br />
Produksi (B) 600 Kg 6.500 3.900.000<br />
Pendapatan (B-A) 2.950.000<br />
RIC 3,11<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
laqunq<br />
Budidaya jagung di lahan pasir, hanya dilakukan sebatas pemanfaatan lahan<br />
di sekitar petak-petak lahan yang diusahakan. Dalam budidaya jagung ini, petani lebih<br />
mengharapkan tanaman ini sebagai wind barrier dan lim bah tanaman (tebon)<br />
daripada produk jagung yang diperoleh. Tanaman jagung dikelola secara sederhana;<br />
digunakan benih lokal, pupuk diberikan seadanya bergantung pada pupuk yang<br />
disediakan <strong>untuk</strong> tanaman pokok yang diusahakan. Beberapa tahun terakhir, di lahan<br />
sawah dan sawah surjan, dikenalkan budidaya jagung hibrida. Introduksi varietas<br />
tanaman baru tersebut, petani di beberapa desa terutama di desa-desa di bagian<br />
barat telah merespon secara posistif, terutama <strong>untuk</strong> ditanaman di bagian atas<br />
sawah surjan. Berikut adalah analisa usaha pertanian jagung yang dilakukan oleh<br />
petani yang menjadi responden di lokasi penelitian (Tabel 54).<br />
49
Tabel 54. Analisa usaha pertanian jagung (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
<br />
Biaya<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Benih 50 Kg 4.000 200.000<br />
Jumlah biaya benih 200.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 2 Colt 130.000 260.000<br />
- urea 125 Kg 2.000 250.000<br />
- NPK 200 Kg 2.250 450.000<br />
-ZA 125 Kg 1.400 175.000<br />
Jumlah biaya pupuk 1.135.000<br />
Tenaga tanam dan perawatan 20 HOK 15.000 300.000<br />
Perawatan dan pengairan 4 HOK 15.000 60.000<br />
Pestisida & insektisida 0<br />
Panen sid pengeringan 2.500.000<br />
Jumlah biaya lain 2.860.000<br />
Total biaya (A) 4.195.000<br />
Produksi (8) 5.500 Kg 1.500 8.250.000<br />
Pendapatan (B-A) 4.055.000<br />
RIC 0,97<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Tanaman hortikultura<br />
Lahan sawah yang ada di bagian utara desa-desa pantai lebih mudah terairi<br />
daripada lahan sawah yang berada di bagian selatan. Usahatani di lahan sawah di<br />
bagian utara desa, dapat dilakukan dengan pola tanam padi-padi-palawija,<br />
--<br />
sedangkan <strong>untuk</strong> lahan sawah di bagian selatan, <strong>untuk</strong> menerapkan pola tanam<br />
tersebut, masih membutuhkan tambahan input berupa tambahan air. Air tersebut<br />
tidak cukup apabila diperoleh hanya dari air pengairan teknis yang ada; sehingga<br />
petani umumnya mengambil air tanah yang dimanfaatkan <strong>untuk</strong> menyiram tanaman<br />
yang diambil dengan bantuan pompa air.<br />
Petani penggarap lahan pasir secara umum telah menyadari bahwa<br />
pengelolaan tanaman di lahan pasir membutuhkan biaya tinggi, terutama yang<br />
menyangkut biaya pengairan dan pemupukan. Dengan dasar itulah maka dalam<br />
memanfaatkan lahan pasir yang ada dengan usahatani tanaman yang bernilai<br />
ekonomis tinggi; yaitu tanaman hortikultura semangka, melon, cabe merah, bawang<br />
merah, atau kadang-kadang diselingi tanaman pangan kacang tanah.<br />
Pada awal penerapan program pola tanam, palawija yang dibudidayakan di<br />
desa-desa pantai adalah jagung dan kedelai. Sesuai dengan perkembangan waktu<br />
dan pasar, petani mulai ke arah budidaya hortikultura yang dianggap lebih<br />
50
· ..<br />
menguntungkan. Mengingat kesulitan air dan kebutuhan akan pupuk serta bahan<br />
bakar yang digunakan <strong>untuk</strong> pengairan, petani lebih memilih komoditi yang lebih<br />
bernilai ekonomis, lebih menguntungkan, yang dimulai dengan budidaya tanaman<br />
semangka kemudian diikuti tanaman melon, cabe merah dan mulai dua tahun<br />
terakhir, yaitu tahun 2005 petani mengembangkan tanaman bawang merah.<br />
-<br />
Pengembangan usahatani di pasir di desa-desa pantai Kabupaten Kulon<br />
Progo yang luasnya lebih dari 1400 ha, menghadapi kendala kondisi lahan marginal<br />
yang kurang subur, sehingga diperlukan masukan <strong>tekno</strong>logi pengolahan yang tepat<br />
dan tambahan bahan organik <strong>untuk</strong> memperbaiki tekstur tanah. Air irigasi terutama<br />
waktu musim kemarau masih menjadi faktor pembatas di lahan pantai. Kebutuhan<br />
input tinggi yang berupa bahan organik, air irigasi dan wind barrier, kawasan pantai<br />
ini dapat disesuaikan dengan komoditi yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu tanaman<br />
hortikultura.<br />
Guna mencukupi kebutuhan air <strong>untuk</strong> tanaman, mulai tahun 1993 - 1996<br />
petani aktif menggali sumber air dengan menggali sumur-sumur ladang, yang<br />
selanjutnya air dari sumur tersebut ditampung di dalam bak-bak penampungan<br />
melalui pipa-pipa penghubung dengan sistem bejana berhubungan, <strong>untuk</strong><br />
memudahkan distribusi air ke lokasi tanaman. Sistem pengairan tersebut, umumnya<br />
oleh petani disebut sebagai sumur renteng, artinya sumur yang bersambung. Adanya<br />
sumur renteng tersebut, memungkinkan petani melakukan budidaya tanaman di<br />
lahan pasir meskipun sa at musim kemarau. Kebutuhan air pertanian yang dicukupi<br />
dengan adanya sumur renteng, yang pada dasarnya juga membutuhkan bahan bakar<br />
minyak, memaksa petani <strong>untuk</strong> berperilaku arif dalam usahataninya, antara lain<br />
<strong>untuk</strong> memilih komoditi yang bernilai ekonomis tinggi. Komoditi yang yang dipilih<br />
tersebut pada awalnya adalah semangka, melon dan cabe merah.<br />
Usahatani tanaman semangka, melon dan cabe merah dirasakan mulai<br />
menimbulkan tantangan-tantangan yang semakin besar. Disamping hama dan<br />
penyakit tanaman yang selalu mengganggu ketiga komoditas tanaman tersebut,<br />
harga produk usahatani ini semakin tidak dapat dikendalikan oleh petani. Petani<br />
mulai mencari kemungkinan <strong>untuk</strong> melakukan diversifikasi tanaman, anatara lain<br />
dengan budidaya bawang merah.<br />
Wind barrier biasa dimanfaatkan petani lahan pasir di desa-desa pantai<br />
Kabupaten Kulon Progo <strong>untuk</strong> melindungi tanaman usahataniya dari terpaan angin<br />
laut yang bertiup cukup kencang. Wind barrier tersebut umumnya berupa pagar<br />
pembatas yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Kondisi lingkungan yang berupa<br />
51
· ..<br />
angin, panas dan hujan, menyebabkan wind barrier ini tidak awet, cepat rusak dan<br />
bentuknya jelek.<br />
Kondisi wind barrier yang lapuk dan berbentuk kurang baik tersebut<br />
berakibat mengganggu kenyamanan lingkungan terutama di beberapa lokasi di desadesa<br />
pantai juga menjadi lokasi wisata pantai (Karangsewu, Bugel, Glagah, Congot).<br />
Penanaman tanaman semusim yang mampu mengatasi terpaan angin sebagai wind<br />
barrier dan sekaligus mampu menambah penghasilan petani, misalnya tanaman<br />
wijen telah diteliti dan berhasil baik.<br />
Cabemerah<br />
Cabe merah merupakan komoditas paling dominan di desa-desa pantai<br />
Kabupaten Kulon Progo. Hampir sepanjang tahun komoditas hortikultura ini<br />
dibudidayakan oleh petani di lahan pasir. Budidaya tanaman cabe telah dilaksanakan<br />
secara intensif baik dalam pemeliharaan secara umum, pengairan, pemupukan,<br />
pengendalian hama/penyakit tanaman, maupun pada panen dan di beberapa desa<br />
termasuk cara pemasarannya. Usahatani cabe merah secara intensif tersebut<br />
membutuhkan modal yang cukup besar. Modal usahatani <strong>untuk</strong> keperluan tersebut,<br />
umumnya didukung oleh lembaga keuangan yang ada, baik berupa lembaga<br />
perbankan atau lembaga-Iembaga bantuan permodalan lain yang telah tersedia di<br />
desa yang bersangkutan.<br />
Umumnya petani mengusahakan benih tanaman cage berupa benih berlabel<br />
yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Air yang digunakan dalam pengairan<br />
cabe merah, diusahakan dengan mesin pompa air yang dialirkan dengan sumur<br />
renteng dan pipa-pipa paralon/slang plastik. Penyiraman dilaksanakan secara intensif<br />
1- 3 kali sehari bergantung kepada cuaca dan umur tanaman. Pemupukan umumnya<br />
dilaksanakan dengan baik; cenderung memberikan dosis pupuk anorganik yang lebih<br />
banyak. Penggunaan bahan organik (meskipun belum berupa pupuk organik) tidak<br />
dapat lepas dalam budidaya tanaman ini di lahan pasir.<br />
Bahan organik yang digunakan umumnya berupa Iimbah kandang sapi,<br />
kambing/domba yang berasal dari ternak miliknya sendiri, atau diperoleh dari lain<br />
desa bahkan dari luar wilayah kabupaten. Limbah kandang ayam petelur, ayam<br />
pedaging, dan burung puyuh juga dimanfaatkan oleh petani hortikultura di lahan<br />
pasir, terutama oleh petani yang berdekatan dengan usaha peternakan unggas<br />
tersebut. Penggunaan bahan organik yang belum terolah menjadi pupuk organik<br />
itulah yang diduga menyebabkan terjadi polusi bau dan populasi lalat yang berlebih.<br />
52
.:.Ia<br />
· ..<br />
Panen produk cabe merah umumnya dilaksanakan setiap lima hari (sepasar)<br />
sejak cabe mulai dapat dipetik hasilnya sampai tanaman tidak produktif. Sebagian<br />
besar tenaga kerja panen cabe merah berupa tenaga upahan yang berupa tenaga<br />
kerja lokal desa; beberapa desa telah menggunakan tenaga kerja dari luar desa<br />
bahkan kadang-kadang dari luar wilayah kecamatan bahkan dari luar wilayah<br />
kabupaten. Di beberapa desa tertentu, kadang-kadang dijumpai tenaga kerja lebo tan<br />
<strong>untuk</strong> panen cabe merah.<br />
Pemasaran produk umumnya dilaksanakan melalui pasar lelang yang telah<br />
dibangun oleh kelompok tani di desa yang bersangkutan; bagi kelompok tani yang<br />
belum memiliki pasar lelang, penjualan dilaksanakan ke pasar lelang di luar kelompok<br />
tani/desa. Sebagian kecil produk cabe oleh petani dijual ke pedagang pengumpul<br />
loka!. Perbedaan sistem pemasaran terse but adalah dalam cara pembayaran yang<br />
diterima petani. Pembayaran atas produk yang dijual secara lelang diberikan secara<br />
cash, sedangkan apabila dijual ke pedagang pengumpul pembayarannya dilakukan 3<br />
4 hari kemudian. Berikut adalah analisa usaha pertanian cabe merah yang dilakukan<br />
oleh petani yang menjadi responden di lokasi penelitian (label 55).<br />
label 55. Analisa usaha pertanian cabe merah (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Volume<br />
Min Mak Mayoritas<br />
Satuan<br />
Harga<br />
(Rp)<br />
Jumlah<br />
(Rp)<br />
Biaya<br />
Benih (Lado, Volcano, TM 99, 15 25 20 sachet 100.000 2.000.000<br />
Helix)<br />
Jumlah biaya benih 2.000.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 30.000 Kg 200 6.000.000<br />
- urea 0 0 0 Kg 2.000 0<br />
- SP 36 100 300 200 Kg 2.500 500.000<br />
- NPK 300 600 400 Kg 2.250 900.000<br />
- KCI 350 500 400 Kg 3.000 1.200.000<br />
- ZA 300 600 500 Kg 1.400 700.000<br />
Jumlah biaya pupuk 9.300.000<br />
Pengolahan tanah (traktor) 600.000<br />
BBM <strong>untuk</strong> penyiraman (3 Itr<br />
840 liter 6.000 5.040.000<br />
/lx siram, 2x/hr slm 140 hr)<br />
Tenaga kerja<br />
- panen (18 orang, 20x petik) 360 HOK 30.000 10.800.000<br />
Pestisida & insektisida 2.572.000<br />
Jumlah biaya lain 19.012.000<br />
Total biaya (A) 30.312.000<br />
Produksi (8) 7.500 15.000 10.700 Kg 10.000 107.000.000<br />
Pendapatan (B-A) 76.688.000<br />
Ric 2,53<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
53
Semanqka dan melon<br />
Tanaman semangka dan melon telah dibudidayakan secara intensif terutama<br />
di lahan pasir; dalam jumlah sedikit di lahan sawah. Benih yang digunakan dalam<br />
budidaya tanaman ini merupakan benih hibrida yang diperoleh dari kios/took<br />
pertanian.<br />
Kendala utama dalam melakukan budidaya tanaman semangka dan melon di<br />
lahan pasir, adalah air dan bahan organik. Untuk mengatasi kebutuhan air, petani<br />
telah memiliki sumur renteng. Pompa air dibutuhkan dalam sistem pengairan ini.<br />
Pupuk organik yang berasal dari Iimbah kandang ternak, mutlak dibutuhkan dalam<br />
budidaya tanaman di lahan pasir. Di sekitar kawasan lahan pantai, banyak dilakukan<br />
usaha pemeliharaan ayam potong. Limbah kandang ternak inilah yang dimanfaatkan<br />
oleh petani sebagai pupuk. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Iimbah<br />
kandang yang dapat diperoleh dari kandang-kandang ayam potong yang ada di desa<br />
tidak mencukupi kebutuhan petani semangka tersebut, sehingga harus didatangkan<br />
dari luar desa, akibatnya tumbuhlah "bisnis" pengumpulan limbah kandang ayam.<br />
Hal tersebut menyebabkan mahalnya bahan organik tersebut yang disebabkan antara<br />
lain oleh biaya transport.<br />
Tahapan dalam budidaya tanaman semangka adalah pengolahan tanah,<br />
persemaian, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama penyakit dan<br />
panen. Selama budidaya tanaman semangka dilakukan penyiraman 1 - 2 kali setiap<br />
hari bergantung umur tanaman. Petani menggunakan pupuk kandang baik yang<br />
berasal dari ternaknya sendiri maupun membeli pada tetangga bahkan ada yang<br />
mendatangkan dari luar desa. Selain menggunakan pupuk kandang petani juga<br />
menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk dasar.<br />
Lahan pasir seluas 0,4 ha hasil produksi semangka rata-rata sebanyak 12 ton.<br />
Produksi tersebut dihasilkan dari tiga kali tanam. Harga jual semangka sangat<br />
tergantung kepada permintaan pasar, dan ditemukan oleh pengepul. Harga tersebut<br />
bervariasi bergantung juga kepada sedikit banyaknya persediaan barang. Kondisi<br />
terakhir, harga semangka di tingkat petani dipatok sebesar Rp 1.000 / kg.<br />
Dalam berusahatani semangka di lahan pasir memerlukan input yang sangat<br />
tinggi, sementara harga jual semangka di tingkat petani sangat rendah, <strong>untuk</strong> itu<br />
perlu dicari terobosan <strong>untuk</strong> mendongkrak harga semangka agar petani memperoleh<br />
keuntungan yang wajar. Salah satu cara <strong>untuk</strong> mendongkrak harga semangka adalah<br />
dengan memasarkan produk tersebut pada konsumen kelas menengah ke atas yang<br />
berani membayar dengan harga tinggi.<br />
54
Keadaan usahatani di lahan pasir, akan lebih parah, dengan adanya<br />
hama/penyakit tanaman yang tidak dapat diatasi oleh petani. Gangguan tersebut<br />
umumnya berupa penyakit layu tanaman sejak tanaman berumur 25 hari. Keadaan<br />
ini, menyebabkan petani saat ini lebih tertarik <strong>untuk</strong> melakukan budidaya semangka<br />
daripada melon; karena modal <strong>untuk</strong> budidaya melon lebih banyak dibandingkan<br />
semangka, dan melon lebih rentan penyakit / hama tanaman. Berikut adalah analisa<br />
usaha pertanian semangka atau melon yang dilakukan oleh petani yang menjadi<br />
responden di lokasi penelitian (Tabel 56).<br />
Tabel 56. Analisa usaha pertanian semangka/melon (ha) di lokasi penelitian, 2010<br />
-,'<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih 15 sachet 32.000 480.000<br />
Jumlah biaya benih 480.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 10.000 Kg 200 2.000.000<br />
- SP 36 125 Kg 2.500 312 .500<br />
- NPK 80 Kg 2.250 180.000<br />
-ZA 150 Kg 1.400 210.000<br />
Jumlah biaya pupuk 2.702.500<br />
Pengolahan tanah (traktor) 600.000<br />
BBM <strong>untuk</strong> penyiraman (3<br />
240 Liter 6.000 1.440.000<br />
Itr/1x siram, 2xx sehari selama<br />
40 hari)<br />
Pestisida & insektisida 800.000<br />
Jumlah biaya lain 2.840.000<br />
Total biaya (A) 6.022.500<br />
Produksi (8) 20.000 Kg 800 16.000.000<br />
Pendapatan (S-A) 9.977.500<br />
RIC 1,66<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
Sebagai tanaman selingan, baik di lahan sawah, lahan pasir maupun lahan<br />
surjan, kadang-kadang petani membudidayakan tanaman sayur: kacang panjang,<br />
kangkung cabut, dan caisim . Kacang panjang atau caisim biasanya ditanam bersamasama<br />
tanaman cabe merah; sedangkan kangkung cabut ditanaman secara<br />
monokultur. Kadang-kadang dijumpai caisim ditanam secara monokultur. Budidaya<br />
tanaman sayur ini telah dilakukan secara intensif; benih yang digunakan umumnya<br />
benih berlabel yang diadakan dari toko/kios pertanian. Budidaya tanaman sayur<br />
umumnya dimanfaatkan oleh petani <strong>untuk</strong> maksud diversifikasi tanaman,<br />
55
meningkatkan produktivitas lahan, serta menambah pendapatan keluarga. Berikut<br />
adalah analisa usaha yang dilakukan oleh responden di lokasi penelitian <strong>untuk</strong><br />
komoditi sayuran seperti kacang panjang (Tabel 57), caisim (Tabel 58), kacang tanah<br />
lokal (TabeI59), dan jagung lokal (Tabel 60).<br />
Tabel57. Analisa usaha pertanian sayuran kacang panjang {hal di lokasi penelitian,<br />
2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih 12 sachet 12.000 144.000<br />
Jumlah biaya benih 144.000<br />
Pupuk<br />
- urea 200 Kg 2.000 400.000<br />
Jumlah biaya pupuk 400.500<br />
Pengolahan tanah (traktor) 600.000<br />
Tenaga tanam dan perawatan 50 HOK 15.000 750.000<br />
Tenaga kerja panen 216 HOK 15.000 3.240.000<br />
Pestisida & insektisida 2.172.500 ;<br />
Jumlah blaya lain 6.762.500<br />
Total biaya (A) 7.306.500<br />
Produksi (8) 10.800 Kg 2.000 21.600.000<br />
Pendapatan (8-A) 14.293.500<br />
RIC 1,96<br />
Sumber: data prtmer (2010)<br />
Tabel 58. Analisa usaha pertanian sayuran caisim {hal di lokasi penelitian, 2010<br />
--<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih 16 sachet 6.000 96.000<br />
Jumlah biaya benih 96.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 3 Colt 130.000 390.000<br />
- urea 200 Kg 2.000 400.000<br />
Jumlah biaya pupuk 790.000<br />
Pengolahan tanah (traktor) 250.000<br />
Tenaga tanam dan perawatan 30 HOK 15.000 450.000<br />
Tenaga kerja panen 10 HOK 15.000 150.000<br />
Pestisida & insektisida 725.000<br />
Jumlah biaya lain 1.575.000<br />
Total biaya (A) 2.461.000<br />
Produksi (8) 8.000 Kg 750 6.000.000<br />
Pendapatan (8-A) 3.539.000<br />
RIC 1,44<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
56
Tabel59. Analisa usaha pertanian kacang tanah lakal (ha) di lakasi penelitian, 2010<br />
Biaya<br />
Benih<br />
Uraian<br />
Jumlah biaya benih<br />
Pupuk<br />
Jumlah biaya pupuk<br />
Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
50 Kg 10.000<br />
500.000<br />
500.000<br />
0<br />
Tenaga tanam dan perawatan 30 HOK 15.000 450.000<br />
Pestisida & insektisida 0<br />
Jumlah biaya lain 450.000<br />
Total biaya (A) 950.000<br />
Produksi (8) 600 Kg 6.500 3.900.000<br />
Pendapatan (B-A) 2.950.000<br />
RIC 3,11<br />
Sumber: data primer (2010) <br />
Tabel 60. Analisa usaha pertanian jagung lakal (ha) di lakasi penelitian <br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya<br />
Benih lokal 50 Kg 4.000 200.000<br />
Jumlah biaya benih 200.000<br />
Pupuk<br />
- pupuk kandang 2 Colt 130.000 260.000<br />
- urea 125 Kg 2.000 250.000<br />
- NPK 200 Kg 2.250 450.000<br />
- ZA 125 Kg 1.400 175.000<br />
Jumlah biaya pupuk 1.135.500<br />
Tenaga tanam dan perawatan 20 HOK 15.000 300.000<br />
Tenaga kerja perawatan dan 4 HOK 15.000 60.000<br />
pengairan<br />
Tenaga kerja panen dan 2.500.000<br />
pengeringan<br />
Pestisida & insektisida<br />
Jumlah biaya lain 2.860.000<br />
Total biaya (A) 4.195.000<br />
Produksi (8) 5.500 Kg 1.500 8.250.000<br />
a<br />
Pendapatan (8-A) 4.055.000<br />
RIC 0,97<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
57
Tanaman perkebunan<br />
Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan dominan di desa-desa<br />
pantai di wilayah bagian selatan kabupaten Kulon Progo; terutama di bagian wilayah<br />
tegalan dan pekarangan. Kelapa yang dibudidayakan di lahan pasir, umumnya kurang<br />
produktif, kecuali apabila di bawah tegakan batang kelapa dibudidayakan tanaman<br />
semusim, baik tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya.<br />
Secara umum, tanaman kelapa yang dibudidayakan di tegalan dan<br />
pekarangan berupa tanaman lokal, dikelola secara ekstensif. Meskipun demikian,<br />
petani pemilik tanaman kelapa merasa memperoleh tambahan penghasilan yang<br />
cukup baik. Rata-rata populasi tanaman sebanyak 155 batang/ha, dengan produksi 5<br />
6 butir kelapa/batang/35 hari; harga kelapa rata-rata Rp 25OO/butir.<br />
Sistem Usaha Peternakan<br />
Populasi ternak di wilayah pantai Kulon Progo yang cukup tinggi; sapi potong<br />
(+450 ekor, yang dimiliki oleh 150 orang), itik (+ 10.000 ekor, yang dipelihara oleh 65<br />
orang), ayam ras broiler (+ 10.200.000 ekor / tahun, yang dikelola oleh 45 orang),<br />
serta ternak domba dengan jumlah kepemilikan + 10-15 ekor/petani, dinilai cukup<br />
potensial <strong>untuk</strong> dikembangkan sebagai usahatani terpadu ternak - tanaman. Limbah<br />
kandang ternak-ternak tersebut potensial digunakan sebagai sumber bahan organik<br />
<strong>untuk</strong> memelihara kesuburan tanah pasir guna mendukung produktivitas usahatani.<br />
SapiPotonq<br />
Sistem pembibitan ternak sapi potong dilakukan secara individu yang berada<br />
di pemukiman penduduk. Petani dalam pengelolaan ternak sapi potong sebagai<br />
kegiatan sambilan <strong>untuk</strong> menambah pendapatan keluarga dan tabungan hidup <strong>untuk</strong><br />
memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat mendesak selain pekerjaan pokok di<br />
sektor pertanian. Tingkat kepemilikan ternak 2 - 4 ekor/peternak. Jenis sapi potong<br />
yang dipelihara terdiri dari keturunan Peranakan Simental, Peranakan Ongole (PO),<br />
dan Limosin.<br />
Pengembangan ternak sapi potong di tingkat petani di desa-desa pantai<br />
Kabupaten Kulon Progo belum optimal. Peternak secara umum memberikan limbah<br />
pertanian terutama jerami padi sebagai pakan utama. Sistem pemberian pakan<br />
secara tradisional tidak mampu meningkatkan bobot badan ternak sapi potong<br />
...'<br />
secara maksimal (0,390 kg/hari). Pengembangan usaha perbibitan ternak sapi potong<br />
dalam sistem reproduksi menunjukkan bahwa banyak ditemukan sapi betina induk<br />
58<br />
"
maupun sapi dara yang dikawinkan berkali-kali tidak bunting. Hal ini akan berakibat<br />
selang waktu beranak semakin panjang sehingga dalam sistem budidaya perbibitan<br />
sapi potong tidak efisien karena faktor waktu menyebabkan biaya pakan dan<br />
inseminasi akan bertambah dan jarak kelahiran (calving interval) pedet sekitar<br />
panjang (18 bulan).<br />
Petani telah biasa memanfaatkan limbah kandang sapi potong <strong>untuk</strong><br />
dimanfaatkan sebagai penyubur lahan pertanian di kawasan pasir pantai, tidak <strong>untuk</strong><br />
di lahan sawah. Pada saat musim tanam terutama tanaman hortikultura, petani<br />
pemilik sapi mengangkut limbah kandangnya ke lahan usahanya, secara langsung<br />
tanpa diolah terlebih dahulu. Penggunaan bahan organik dengan cara itu, diduga<br />
berakibat tersebarnya bau dan meningkatnya populasi lalat di wilayah pantai,<br />
disamping menyebabkan tingginya pertumbuhan gulma di lahan usaha pertanian. Oi<br />
seluruh desa-desa pantai Kabupaten (kecuali di Oesa Banaran), tidak dijumpai adanya<br />
unit usaha pengolahan pupuk organik dari limbah kandang ternak.<br />
Berdasarkan data populasi ternak, limbah kandang yang tersedia tidak<br />
mencukupi kebutuhan petani lahan pasir akan bahan organik. Kenyataan tersebut<br />
menyebabkan petani lahan pasir berusaha mendatangkan bahan organik berupa<br />
limbah kandang dari wilayah lain, misalnya dari daerah Kabupaten Bantul.<br />
Tabel 61.<br />
Biaya investasi<br />
Analisa usaha penggemukkan sapi potong (10 ekor, 3 bulan) yang<br />
dilakukan responden di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Bibit 10 ekor 4.500.000 45 .000.000<br />
lumlah biaya investasi 45 .000.000<br />
Biaya operasional<br />
a. Pakan dan obat-obatan<br />
Hijauan<br />
Konsentrat<br />
10 ekor x<br />
25 kg x<br />
90 hari<br />
10 ekor x<br />
3 kg x 90<br />
hari<br />
kg 35 787.500<br />
kg 2.500 6.750.000<br />
Obat-obatan 10 paket 50.000 500.000<br />
lumlah biaya pakan dan<br />
8.037.500<br />
obat-obatan<br />
b. Tenaga kerja 100 HOK 15.000 1.500.000<br />
lumlah biaya tenaga kerja 1.500.000<br />
lumJah biaya (A) 54.537.500<br />
Produksi (pertambahan berat 10 ekor x kg 22.000 138.600.000<br />
bad an) (B)<br />
0,7 kg x<br />
90 hari<br />
Keuntungan (B A) 84.062.500<br />
B/C =(8 - A) I A 1,54<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
59
Domba<br />
Usaha budidaya ternak domba berkembang dengan baik di desa-desa pantai<br />
Kabupaten Kulon Progo. Peternak memanfaatkan waktu luang <strong>untuk</strong> memelihara<br />
domba. Ternak dipelihara seeara ekstensif, sore hingga pagi dikandangkan,<br />
sedangkan pada waktu pagi sampai sore hari, ternak tersebut digembalakan. Jumlah<br />
kepemilikan ternak domba eukup tinggi, + 10 - 15 ekor/petani bahkan di beberapa<br />
desa ditemukan kepemilikan ternak sampai 20 - 40 ekor/petani. Petani dalam<br />
memelihara domba mayoritas dengan melibatkan ibu rumah tangga, sehingga aspek<br />
gender dalam pengelolaan usaha sangat mendukung.<br />
Sistem budidaya masih bersifat tradisional, tanpa memperhitungkan aspek<br />
ekonomi; walaupun tingkat kepemilikan ternak eukup tinggi, namun pengelolaan<br />
sangat sederhana. Ternak digembalakan di lahan-Iahan kosong/bera, sehingga<br />
keeukupan pakan <strong>untuk</strong> produksi sangat kurang. Dengan usaha yang tradisional ini<br />
sering muneul serangan berbagai maeam penyakit, sehingga mortalitas baik pada<br />
anak maupun ternak dewasa eukup tinggi. Hal terse but juga mengakibatkan tingkat<br />
produktivitas ternak masih rendah; selang beranak eukup lama yaitu sampai 300 hari,<br />
sedangkan bobot yang dieapai pada sa at sapih kurang dari 10 kg.<br />
Usaha pemeliharaan domba di<br />
kawasan desa-desa pantai ini dinilai<br />
mempunyai peluang yang eukup baik, mengingat rata-rata pasar/konsumen<br />
menyenangi rasa daging domba yang dipelihara dengan eara ekstensif tersebut.<br />
Konsumen menganggap bahwa daging domba yang dipelihara di daerah pantai<br />
mempunyai daging yang lebih enak dan relatif lebih lunak. Peluang lainnya dalam<br />
pemeliharaan domba di wilayah pantai ini adalah hanya memanfaatkan tenaga luang<br />
petani/wanita tani, sehingga modal yang dibutuhkan relatif keeil.<br />
Petani pemelihara domba umumnya tidak memiliki posisi tawar yang eukup<br />
baik, karena umumnya petani menjual ternaknya saat membutuhkan uang <strong>untuk</strong><br />
keperluan rumahtangganya atau kebutuhan yang mendesak dalam meneukupi modal<br />
tanam. Peranan pedagang perantara (pedagang lokal) sangat dominan dalam<br />
tataniaga domba di wilayah ini. Petani pemilik ternak domba selalu memanfaatkan<br />
limbah kandang ternaknya sebagai bahan organik di lahan pertaniannya,<br />
-<br />
sebagaimana petani pemilik sapi potong.<br />
60
Tabel 62. Analisa usaha domba (40 ekor, 2 tahun) yang dilakukan responden di<br />
lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) lumlah (Rp)<br />
Biaya investasi<br />
Bibit/induk 40 ekor 800.000 32.000.000<br />
lumlah biaya investasi 32.000.000<br />
Blaya operaslonal<br />
a. Pakan dan obat-obatan<br />
Hijauan (40 ekor x 4 kg x 30 115.200 kg 35 4.032.000<br />
hari x 24 bulan)<br />
Obat-obatan 40 paket 12.500 500.000<br />
Jumloh bioyo pokon don<br />
4.532.000<br />
obat-obatan<br />
b. Tenaga kerja/ penggembala 720 HOK 15.000 10.800.000<br />
Jumlah biaya tenaga kerja 10.800.000<br />
Jumlah biaya (A) 15.332.000<br />
Produksi anak (8)<br />
180 ekor anak 100.000 18.000.000<br />
(40 ekor xl,S anak x 3 partus)<br />
Mortalitas 5% (C) 900.000<br />
Pendapatan (B C) 17.100.000<br />
B/c 1,12<br />
Sumber: data primer (2010) <br />
Keterangan : domba digembalakan <br />
Ayam Kampunq<br />
Pemeliharaan ayam kampung berkembang cukup baik di desa-desa pantai<br />
Kabupaten Kulon Progo, khususnya di wilayah pasir pantai. Melalui usaha<br />
pemeliharaan ayam kampung, selain peternak memperoleh keuntungan berupa<br />
selisih harga jual ayam dengan biaya produksi, peternak juga mempero\eh limbah<br />
kandang berupa kotoran ayam dan sisa-sisa pakan, <strong>untuk</strong> dimanfaatkan sebagai<br />
pupuk <strong>untuk</strong> tanaman. Kotoran ayam tersebut juga merupakan keuntungan<br />
tambahan apabila dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan.<br />
Persoalan yang sering muncul dengan adanya usaha pemeliharaan ayam<br />
kampung ini adalah munculnya populasi lalat dan timbulnya bau tak sedap, yang<br />
-<br />
di lantai/di bawah kandang, menimbulkan bau, dan merupakan media<br />
dianggap mengganggu kondisi lingkungan. Kotoran ayam yang biasanya menumpuk<br />
-<br />
-<br />
berkembangnya populasi lalat. Setelah waktu pemeliharaan ayam berakhir, dan<br />
ayam telah terjual, kotoran ternak tersebut biasanya di manfaatkan oleh petani<br />
sebagai pupuk tanaman .<br />
Kotoran ayam tersebut diangkut dari kandang dibawa ke lahan lokasi<br />
budidaya tanaman. Keadaan tersebut menyebabkan tersebarnya bau dan populasi<br />
lalat tidak hanya di sekitar kandang ayam, tetapi juga di lahan budidaya tanaman.<br />
61
Secara umum, wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, selain<br />
dimanfaatkan oleh petani dalam mengembangkan usahataninya, Pemerintah<br />
Kabupaten juga telah menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah wisata yang<br />
dinilai cukup potensial. Penggunaan limbah kandang ternak dengan cara yang salah,<br />
telah berakibat terganggunya obyek wisata pantai dengan populasi lalat yang tinggi<br />
dan bau kotoran ternak yang menyengat pada kawasan wisata pantai.<br />
-<br />
Tabel63. Analisa usaha ayam kampung yang dilakukan responden di lokasi<br />
penelitian , 2010<br />
Uraian Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)<br />
Biaya investasi<br />
Bibit/induk:<br />
Ayam kampung betina 100 Ekor 15.000 1.500.000<br />
Ayam kampung jantan 10 Ekor 25.000 250.000<br />
lumlah biaya investasi 1.750.000<br />
Biaya operasional<br />
Pakan (110 ekor x 0,120 kg x<br />
180 hr)<br />
2.376 Kg 2.500 5.940.000<br />
lumlah biaya pakan 5.940.000<br />
b. Tenaga kerja 180 HOK 15.000 2.700.000<br />
lumlah biaya tenaga kerja 2.700.000<br />
lumlah biaya (A) 8.640.000<br />
Produksl telur<br />
5.400 Butir 1.000 5.400.000<br />
(30 butir x 180 hr)<br />
Produksi daging<br />
60 Ekor 70.000 4.200.000<br />
(10 ekor x 6 bin)<br />
Produksi (8) 9.600.000<br />
Mortalitas 5% (C) 480.000<br />
Pendapatan (B - C) 9.120.000<br />
B/C 1,05<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Sistem Permodalan<br />
Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha (Suratiyah, 2006),<br />
demikian pula halnya usaha yang dilakukan oleh responden di lokasi penelitian.<br />
Sistem permodalan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengamati<br />
berbagai peluang unit-unit usaha dalam melakukan <strong>pengembangan</strong> usaha dengan<br />
dukungan sumber keuangan yang ada. Besarnya kebutuhan modal dalam melakukan<br />
usaha bervariasi, tergantung pada jenis dan skala usahanya .<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Pada Desa Kulwaru, 13 responden (86,66 %) menyatakan bahwa <strong>untuk</strong><br />
memenuhi kekurangan modal melakukan pinjaman kepada simpan pinjam di<br />
kelompok. Pada Desa Sogan, hanya terdapat 1 responden (6,67 %) responden<br />
melakukan pinjaman kepada bank. Sedangkan pada desa karangwuni, berimbangan<br />
62
antara responden yang meminjam melalui bank atau simpan pinjam kelompok<br />
sebanyak 26,67 % (4 responden).<br />
Cara pembayaran yang dilakukan 12 (dua bel as) responden di Desa Kulwaru<br />
-<br />
(80%) adalah membayar dengan eara menyieil dengan uang tiap bulan dan terdapat 3<br />
responden (40%) melakukan pembayaran hutang sehabis panen (yarnen). Pada Desa<br />
Karangwuni, 9 responden (60%) menyatakan melakukan pembayaran dengan eara<br />
mencicil. Berdasarkan wawancara dengan responden, tidak ditemukan responden<br />
yang memiliki hubungan dengan pelepas uang (100%). Responden pad a Desa<br />
Kulwaru dan Desa Karangwuni menyatakan seluruh responden (100%) menyatakan<br />
pernah mengalami kekurangan uang. Sedangkan pada desa Sogan menyatakan<br />
bahwa 11 responden (73,33%) menyatakan tidak pernah kekurangan modal.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Tabel 64. Sistem permodalan di lokasi penelitian, 2010<br />
Uraian<br />
Desa Kulwaru Desa Sagan Desa Karangwuni<br />
Jumlah % Jml % Jml %<br />
A. Dapat memenuhi modal<br />
1 Ya 1 6,67 14 93,33 6 40,00<br />
2 Tidak 14 93,33 1 6,67 9 60,00<br />
B. Cara memenuhi kekurangan modal<br />
1 Meneari pinjaman ke 2 13,33 1 6,67 4 26,67<br />
bank<br />
2 Meneari pinjaman ke<br />
koperasi<br />
6 40,00<br />
°<br />
0,00 1 6,67<br />
3 Meneari pinjaman ke<br />
saudara<br />
1 6,67<br />
°<br />
0,00 2 13,33<br />
4 Menear; pinjaman ke<br />
0,00 0<br />
pedagang °<br />
0,00 0 0,00<br />
5 Simpan Pinjam 13 86,67<br />
Kelompok<br />
°<br />
0,00 4 26,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
C. ° °<br />
6 Lainnya<br />
Cara membayar pinjaman °<br />
0,00<br />
1 Kontan dengan uang<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2 Kontan dengan natura<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3 Yarnen: uang ° 3 20<br />
0,00<br />
0,00<br />
4 Yarnen: natura 0 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5 Mengangsur 12 80 ° 1 6,67 ° 9 60,00<br />
6 Lainnya 0 0,00 0 0,00 1 6,67<br />
D. Pelepas uang di desa<br />
1 Ya<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2 Tidak 15 ° 100,00 15 ° 100,00 15 ° 100,00<br />
E. Pernah mengalami kekurangan modal<br />
1 Ya 15 100,00 4 26,67 15 100,00<br />
2 Tidak<br />
0,00 11 73,33<br />
0,00<br />
F. Saat ini kekurangan modal<br />
°<br />
1 Ya 14 93,33 1 6,67 9 60,00<br />
2 Tidak 1 6,67 14 93,33 6 40,00<br />
Sumber: data pnmer (2010)<br />
°<br />
63
Pemerintah, melalui beberapa bank milik pemrintah, seperti BRI, BNI dan<br />
Bank Mandiri, sebenarnya telah berupaua menyediakan berbagai jenis kredit yang<br />
dapat dimanfaatkan para pelaku usaha di lokasi penelitian. Beberapa jenis kredit<br />
seperti Kupedes, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kelayakan usaha, dan<br />
kredit ketahanan pangan telah disediakan oleh bank-bank pemerintah <strong>untuk</strong><br />
melayani kredit pada sektor pertanian, peri kanan, peternakan dan perkebunan<br />
(Effendi dan Oktariza, 2006). Namun, hanya sedikit para pelaku usaha perikanan yang<br />
memanfaatkan kredir-kredit tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak<br />
pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, yang<br />
tidak mempunyai jaminan ketika akan mengajukan kredit ke bank.<br />
Kebutuhan Konsumsi Ikon, Produksi Loka/, Pasokan dari Luar don De/isit Konsumsi<br />
Berikut adalah perhitungan tentang kebutuhan ikan konsumsi, produksi<br />
perikanan lokal, pasokan ikan dan defisit konsumsi yang disajikan pada Tabel 65<br />
-<br />
Tabel<br />
sampai 68.<br />
65. Total Produksi Ikan (ton) di Desa Sampel Tahun 2009<br />
Produksi Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Ikan laut 0 0 262,864<br />
Ikan Darat 50,887 42,377 24,462<br />
Total 50,887 42,377 287,326<br />
Sumber: Data Penkanan dan Kelautan Kecamatan Wates (P3D-Pertkanan) dan Profile TPI TanJung<br />
Adikarya<br />
Tabel 66. Pasokan Ikan Konsumsi dari Luar Desa<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
64<br />
Rincian Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Konsumsi makan ikan/kapita Kabupaten Kulonprogo tahun 2008= 12,95 kg<br />
Berdasarkan jumlah<br />
2.937 orang 2.351 orang 2.960 orang<br />
penduduk BPS 2008<br />
(orang)<br />
Perhitungan jumlah<br />
konsumsi ikan (kg)<br />
12,95 x 2.937 orang<br />
= 38.034,15<br />
12,95 x 2.351 orang<br />
= 30.445,45 kg<br />
12,95 x 2.960 orang<br />
= 38.332 kg<br />
Perhitungan produksi<br />
ikan - konsumsi (kg)<br />
50.887 - 38.034,15<br />
= 12.852,85<br />
42.377 - 30.445,45<br />
= 11.931,55<br />
287 .326 - 38.332<br />
= 248.994<br />
Kesimpulan<br />
tidak memasok ikan<br />
dari luar desa<br />
tidak memasok ikan<br />
dari luar desa<br />
tidak memasok ikan<br />
dari luar desa<br />
Jika menggunakan(asumsi per kapita 38,67 kg /thn/jumlah penduduk)<br />
Perhitungan produksi<br />
ikan - konsumsi<br />
Kesimpulan<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
50.887(kg)-<br />
113.573,8 kg<br />
= (-62.686,8)<br />
Memasok ikan<br />
sebanyak 62.686,8<br />
kg/tahun dari luar<br />
desa<br />
42.377(kg)<br />
90.913,17 kg<br />
=(-48.536,2)<br />
Memasok ikan<br />
sebanyak 48.536,2<br />
kg/tahun dari luar<br />
desa<br />
287.326 (kg) <br />
114.463,2 kg<br />
=172.863<br />
masih mampu<br />
memenuhi<br />
kebutuhan
Tabel 67. Kebutuhan konsumsi ikal, <strong>untuk</strong> target memenuhi 38,67 kg /thn/kapita<br />
Rincian Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni<br />
Berdasarkan jumlah<br />
anggota (15 KK)<br />
60 orang =2320,2<br />
kg/thn/kapita<br />
62 orang =2397,54<br />
kg/thn/kapita<br />
53 orang = 2049,5<br />
kg/thn/kapita<br />
Berdasarkan jumlah 2.937 orang 2.351 orang 2.960 orang<br />
penduduk BPS 2008<br />
Kebutuhan ikan 113.573,8 kg/thn 90.913,17 kg/thn 114.463,2 kg/thn<br />
konsumsi<br />
Sumber: data primer (2010) <br />
Tabel 68. Defisit kebutuhan konsumsi <strong>untuk</strong> target 38,67 kg /thn/kapita <br />
,<br />
Rincian Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni<br />
Target kebutuhan 113.573,8 90.913,17 114.463,2<br />
Produksi local 50,887 42,377 287,326<br />
Pasokan dari luar 0 0 0<br />
Total ketersediaan 50,887 42,377 287,326<br />
Defisit 62.686,8 48.536,2 0<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Berdasarkan data-data sebagaimana terangkum Tabel 65 sid 68, dapat<br />
disimpulkan bahwa adanya peluang <strong>untuk</strong> memproduksi ikan <strong>untuk</strong> memenuhi defisi<br />
pasokan konsumsi ikan. Apabila diasumsikan 20 persen Kepala Keluarga dapat<br />
dimobilisir <strong>untuk</strong> melakukan usaha budidaya, maka jumlah KK <strong>untuk</strong> Desa<br />
Karangwuni, Desa Sogan dan Desa Kulwaru yang dapat berpartisipasi dalam program<br />
budidaya tersebut adalah masing-masing 118, 86 dan 152 KK. Namun demikian, dari<br />
ketiga desa tersebut, Desa Karangwuni telah mencukupi kebutuhan dan memasarkan<br />
surplusnya ke wilayah lain. Dengan demikian, hanya dua desa, yaitu Sogan dan<br />
Kulwaru yang memungkinkan <strong>untuk</strong> <strong>pengembangan</strong> budidaya dengan kapasitas<br />
masing 564 kg/kk/tahun dan 531 kg/kk/tahun. Kapasitas tersebut kurang lebih setara<br />
dengan 220% dari skala subsisten.<br />
Tenaga kerja keluarga dalam usaha<br />
Tenaga kerja dalam usaha yang dilakukan oleh responden memiliki<br />
karakteristik yang berbeda-beda. TIdak hanya di sektor perikanan tetapi juga di<br />
sektor pertania. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tohir (1983) bahwa<br />
karakteristik tenaga kerja dalam usaha tani diantaranya adalah: 1) keperiuan akan<br />
tenaga kerja dalam usahatani tidak kontinyu dan tidak merata; 2) penyerapan tenaga<br />
kerja dalam usaha tani sangat terbatas; 3) tidak mudah distandarkan, dirasionalkan<br />
dan dispesialisasikan; dan 4) beraneka ragam coraknya dan kadang kala tidak dapat<br />
dipisahkan satu sama lain.<br />
65
,. .. <br />
<br />
lumlah keluarga yang bekerja offfarm<br />
Ruang lingkup kegiatan usaha yang dilakukan oleh responden di lokasi<br />
penelitian, baik itu perikanan dan pertanian, tidak hanya melakukan usaha produksi<br />
saja (on farm), tetapi juga mencakup kegiatan off farm, seperti pengolahan,<br />
pemasaran (sebagai pedagang pengumpul), dan faktor pendukung usaha lainnya<br />
(Tabel 69).<br />
Tabel 69. Jumlah keluarga yang bekerja off farm di lokasi penelitian<br />
Rincian<br />
Jumlah KK<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Pengolah 1<br />
- -<br />
Pedagang pengumpul 0 1<br />
2<br />
Lainnya 2 2<br />
-<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Pada Tabel 69 terlihat bahwa di Desa Kulwaru terdapat 1 KK yang memiliki<br />
usaha pengolahan off farm berupa usaha telur asin. Pada Desa karangwuni terdapat<br />
2KK yang terlibat dalam usaha off farm berupa usaha bakul ikan. Sedangkan di Desa<br />
Sogan hanya terdapat 1 KK yang memiliki usaha off farm berupa pedagang ayam.<br />
Untuk pekerjaan off farm lainya adalah jasa pengolahan lahan menggunakan traktor,<br />
dimana pad a Desa Kulwaru terdapat 1 KK dan Desa Sogan terdapat 2 KK, di 1 KK<br />
memiliki usaha pengadan pakan dan pupuk di Desa Kulwaru.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
.<br />
-'<br />
:<br />
!<br />
lumlah keluarga yang bekerja non farm<br />
Kegiatan non farm yang dapat diidentifikasi di lokasi penelitian adalah<br />
pegawai negeri, usaha industri, buruh industri, usaha/pekerja jasa lain, pedagang,<br />
tukang bangunan dan aparat desa (Tabel 70).<br />
Tabel 70. Jumlah keluarga yang bekerja non farm di lokasi penelitian<br />
Uraian<br />
Jumlah KK<br />
Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Pegawai negeri 1 1 -<br />
Seniman - - -<br />
Usaha industry 1 - -<br />
Buruh idustri - 1 -<br />
Usaha/pekerja jasa lain 4 2 -<br />
Dagang 1 2 1<br />
Tukang bangunan 2 - -<br />
Aparat desa - 3 -<br />
Buruh bangunan - - -<br />
Jasa transportasi - - -<br />
Lainnya - - -<br />
Sumber: Badan Pusat Statlstlk (2008)<br />
-<br />
66
~<br />
-<br />
Pada responden Desa Kulwaru terdapat 1 KK yang bekerja sebagai pegawai<br />
negeri (petugas kebersihan SMP), 1 KK bekerja di usaha industri (sales motor),<br />
bekerja disektor swasta dan sejenisnya sebanyak 4 KK, mempunyai warung 1 KK dan<br />
menjadi tukang bangunan sebanyak 2 KK. Pada responden Desa Sogan terdapat 3 KK<br />
yang bekerja sebagai aparat pemerintah desa, 1KK sebagai aparat pegawai negeri ,<br />
memiliki warung rumahan 2 KK dan bekerja sebagai pegawai toko dan sejenisnya.<br />
Pada Desa Karangwuni sangat sedikit variasi responden yang bekerja di sector non<br />
farm, hanya terdapat 1 KK yang memiliki usaha sampingan berupa warung.<br />
Rataan pendapatan offfarm per tahun<br />
Rataan pendapatan off farm yang dilakukan oleh responden di lokasi<br />
penelitian berkisar antara Rp 2.160.000 sampai Rp 22.200.000. Secara rinci, pada<br />
Tabel 71 terlihat bahwa pengolah hanya terdapat pada Desa Kulwaru dengan<br />
pendapatan sebanyak 30.000.000 per tahun, Untuk pedagang pengumpul, pendapatan di<br />
-<br />
Desa Sogan (Rp 5.400.000) lebih tinggi jika dibandingkan dengan Desa Karangwuni (Rp<br />
2.160.000). Untuk lainnya, di Desa Kulwaru memiliki pendapatan terbesar Rp 22.200.000 dan<br />
di Desa Sogan sebesar Rp 4.000.000.<br />
Tabel71. Rataan pendapatan offfarm (Rp 000) per tahun di lokasi penelitian<br />
Uraian Oesa Kulwaru Oesa Sogan Oesa Karangwuni<br />
Pengolah 30.000.000 - -<br />
Pedagang pengumpul - 5.400.000 2.160.000<br />
Lainnya 22.200.000 4.000.000 -<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Rataan pendapatan non farm<br />
Rataan pendapatan non farm yang dilakukan oleh responden di lokasi<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~ I<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~<br />
~)<br />
penelitian berkisar antara Rp 3.600.000 sampai Rp 43.200.000 (Tabel 72).<br />
Tabel 72. Rataan pendapatan non farm (Rp 000) per tahun di lokasi penelitian<br />
Uraian Desa Kulwaru Desa Sogan Desa Karangwuni<br />
Pegawai negeri 18.000.000 36.000.000 -<br />
Seniman - - -<br />
Usaha industry 9.600.000 - -<br />
Buruh idustri - 8.400.000 -<br />
Usaha/pekerja jasa lain 43.200.000 21.600.000 -<br />
Dagang 26.400.000 10.800.000<br />
Tukang banguan 14.400.000 - -<br />
Aparat desa - 32.400.000 -<br />
Buruh bangunan - - -<br />
Jasa transportasi - - -<br />
Lainnya - - -<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
3.600.000<br />
67<br />
~
I<br />
<br />
· .. <br />
--<br />
-<br />
Pada Tabel 72 terlihat bahwa rataan pendapatan non farm per tahun <strong>untuk</strong><br />
Desa Kulwaru <strong>untuk</strong> pegawai negeri sebesar Rp 18.000.000 dan Desa Sogan sebesar<br />
Rp 36.000.000 dan di Desa Karangwuni tidak ditemukan responden yang berasal dari<br />
pns. Adanya perbedaan nilai tersebut dikarenakan perbedaan golongan dan<br />
tunjangan. Untuk mata pencaharian usaha industri hanya ditemukan di Desa Kulwaru<br />
vatu sebagai sales penjualan motor, sedangkan <strong>untuk</strong> kedua desa (Sogan dan<br />
Karangwuni) tidak ditemukan. Untuk mata pencaharian yang bergerak sebagai buruh<br />
hanya terdapat di Desa Sogan dengan rataan pendapatan pertahun sebesar Rp<br />
8.400.000. Untuk mata pencaharian usaha /pekerja jasa lainnya hanya terdapat di<br />
Desa Kulwaru dan Sogan, di Desa Karangwuni tidak ditemukan.<br />
Mata pencaharian dagang ditemukan disemua desa dengan rataan<br />
pendapatan di Desa Kulwaru sebesar Rp 26.400.000, Sogan Rp 10.800.000 dan<br />
Karangwuni Rp3.6oo.000, adanya perbedaan nilai disebabkan perbedaan jenis usaha<br />
dan besarnya nilai penjualan. Jenis usaha di Desa Kulwaru adalah penjualan gadagada<br />
yang sudah memiliki omset sebanyak 80 piring perhari dengan harga jual Rp<br />
4500 per porsi. Sedangkan jenis usaha di Desa Sogan dan Karang wuni berupa<br />
warung rumahan. Mata pencarian tukang bangunan hanya ditemukan pad a<br />
responden di Desa Kulwaru dengan rataan pendapatan Rp 14.400.000 <strong>untuk</strong> 2 KK.<br />
Rataan pendapatan dengan pencaharian sebagai aparat desa sebesar Rp 32.400.000<br />
<strong>untuk</strong> 3KK dan hanya di temukan di Desa Sogan, sedangkan <strong>untuk</strong> mata pencarian<br />
sebagai seniman, buruh bangunan , jasa transportasi<br />
tidak ditemukan pada<br />
responden di ketiga desa.<br />
4.4.3. Sintesa<br />
Dari pemaparan data-data dan analisis sebagaimana dipaparkan pada Bab 4.3.1<br />
s/d 4.3.6, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait kondisi ketahanan pangan<br />
rumah tangga di lokasi penelitian dan peluang serta tantangan yang ada <strong>untuk</strong><br />
meningkatkan kondisi tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kondisi ketahanan<br />
pangan di ketiga lokasi kasus kurang baik, namun demikian hasil analisis juga<br />
menunjukkan bahwa dari sudut pandang persepsi dan preferensi masyarakat,<br />
<strong>peningkatan</strong> kunsumsi pangan berkualitas ternyata cukup prospektif. Kurang baiknya<br />
kondisi pangan yang ada terutama terkait dengan ketersediaan yang kurang dan pengaruh<br />
musim, terutama di desa-desa yang lebih jauh dari pantai. Tingkat kesejahteraan yang<br />
cukup tinggi (ketiga desa kasus tidak termasuk kategori miskin), tidak cukup <strong>untuk</strong><br />
mendongkrak kondisi pangan karena factor ketersediaan yang relatif lemah.<br />
68
I<br />
~<br />
Situasi di atas menyiratkan perlunya meningkatkan aspek ketersediaan pangan<br />
dan lebih memperkuat lagi aspek akses ekonomis, yang terkait dengan pendapatan di<br />
wilayah-wilayah lokasi kasus tersebut. Berdasar paparan data dan analisis pada Bab 4.4.1<br />
sid 4.4.6, dapat disimpulkan bahwa perikanan, khususnya perikanan budidaya berpotensi<br />
<strong>untuk</strong> dikembangkan <strong>untuk</strong> mendukung <strong>peningkatan</strong> aspek ketersediaan dan akses<br />
tersebut di atas. Secara umum, variable-variabel rumah tangga maupun variabel-variabel<br />
non-rumah tangga, kesemuanya mendukung potensi yang ada tersebut.<br />
Dari sisi teknis, variabel rumah tangga yang paling mendukung <strong>pengembangan</strong><br />
ketahanan pangan berbasis perikanan adalah ketersediaan lahan-Iahan pekarangan<br />
rumah tangga. Sementara itu, variabel yang relative lemah dan perlu dijadikan fokues<br />
perhatian adalah terbatasnya keterampilan dan pengetahuan budidaya di dua di antara<br />
tiga desa kasus. Di antara variabel-variabel di luar rumah tangga, ketersediaan saranaprasarana<br />
pendukung (sarana prasarana budidaya, lembaga keuangan, lembaga<br />
pembinaan, dan lembaga pemasaran) di tingkat desa merupakan variabel-variabel utama<br />
-<br />
yang dapat dikategorikan berkondisi kuat, sementara itu, ketimpangan antar desa dalam<br />
hal kemampuan penyediaan sarpras dapat dikategorikan lemah dan perlu mendapatkan<br />
perhatian yang lebih besar.<br />
Dari sisi <strong>sosial</strong>, variabel rumah tangga yang paling mendukung <strong>pengembangan</strong><br />
ketahanan pangan berbasis perikanan adalah tingginya prosentase penduduk usia<br />
produktif, pendidikan (mayoritas tamat SMA),. Sementara itu, variabel yang relatif lemah<br />
dan perlu perhatian adalah sruktur pengeluaran rumah tangga yang cenderung masih<br />
didominasi oleh unsur pengeluaran pangan. Di ketiga lokasi kasus, terdapat variabel di<br />
luar rumah tangga yang bersifat sangat positif, yaitu adanya kultur masyarakat yang<br />
dipengaruhi oleh usaha berbasis pertanian dan di ketiga lokasi kasus tersebut tidak<br />
ditemukan variable social yang secara signifikan dianggap sebagai kelemahan mendasar.<br />
~ Data-data mengenai potensi ekonomi yang ada dan keberadaan kelembagaan<br />
~ kelembagaan pendukung, disimpulkan adanya peluang <strong>untuk</strong> mengembangkan klaster<br />
b; usaha tingkat desa yang ditopang oleh unit-unit usaha tingkat rumah tangga. Berdasarkan<br />
~ pada analisa finansial yang dilakukan terhadap berbagai usaha masyarakat yang telah<br />
i!.) :<br />
J. berkembang sejauh ini, diperkirakan bahwa usaha-usaha budidaya dapat dikembangkan<br />
~<br />
~ akses<br />
~<br />
<strong>untuk</strong> memasok kebutuhan pangan rumah tangga berbasis perikanan, dengan<br />
menyisakan sebagian hasilnya <strong>untuk</strong> tujuan <strong>peningkatan</strong> pendapatan <strong>untuk</strong> meningkatkan<br />
ekonomis terhadap bahan konsumsi lainnya. Menimbang peluang pasar yang<br />
(projeksi kebutuhan ikan, pasokan local yang ada dan pasokan yang tersedia dari luar<br />
~<br />
69<br />
~
· .. <br />
(Table 65 sid 68), surplus produksi dapat diperkenankan <strong>untuk</strong> mencapai 220 persen dari<br />
kebutuhan konsumsi rumah tangga .<br />
Berdasarkan hasil identifikasi faktor luar maupun dalam rumah tangga tersebut di<br />
atas, <strong>desain</strong> <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan secara secara ringkas dapat diformulasikan<br />
secara deskriptif pada Tabel73 sebagai berikut:<br />
Tabel 73. Identifikasi <strong>desain</strong> <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan di lokasi penelitian<br />
-<br />
Struktur<br />
Jenis usaha<br />
Faktor<br />
Keterangan<br />
Sistem usaha berbasis perikanan yang dikelola dalam<br />
kelompok produksi berbasis desa dan pemasaran berbasis<br />
kecamatan<br />
Budidaya perikanan di pekarangan rumah tangga<br />
Komoditas pilihan Lele, gurame<br />
Pelaku inti<br />
Kepala rumah tangga<br />
Skala usaha<br />
220 % dari skala subsisten<br />
Kelembagaan Kelembagaan informal yang difasilitasi oleh lembaga<br />
pembina tingkat desa<br />
Rentang koordinasi<br />
Kecamatan<br />
Intervensi utama - Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan budaya,<br />
subsidi pengadaan saprokan<br />
- Perbaikan sarana prasarana<br />
Sumber: data primer (2010)<br />
Usaha-usaha budidaya tingkat rumah tangga tersebut, sebagaimana digambarkan dalam<br />
analisis usaha, diperkirakan dapat membawa dampak ganda, yaitu <strong>peningkatan</strong><br />
pendapatan, <strong>peningkatan</strong> ketersediaan sumber protein hewani, dan <strong>peningkatan</strong> daya<br />
beli bahan pangan.<br />
- terutama<br />
4.4.4. Analisis terhadap <strong>desain</strong><br />
Secara politis, <strong>desain</strong> terse but di atas diperkirakan mempunyai nilai positif. Hal ini<br />
terkait dengan program yang dicanangkan oleh Kabupaten Kulon Progo, yang<br />
menempatkan permasalahan pemenuhan pangan di dalam salah satu prioritas utamanya.<br />
Sementara itu, pemilihan sektor perikanan sebagai basis dalam <strong>desain</strong> ini juga dapat<br />
diasumsikan akan mendapatkan dukungan politis yang kuat. Indikasi yang mengarah pada<br />
dukungan besar terse but tercermin dari respon pemerintah setempat terhadap kajian ini<br />
dan dengan telah adanya pencanangan minapolitan oleh Bupati Kulon Progo pada<br />
pertengahan tahun ini.<br />
Secara teknis maupun <strong>sosial</strong>, introduksi usaha budidaya kepada masyarakat di<br />
wilayah Kabupaten Kulon Progo juga diperkirakan tidak akan menghadapi permasalahan<br />
berarti. Sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya, kondisi social kemasyarakatan<br />
70
· .. <br />
di Kulon Progo sangat memungkinkan <strong>untuk</strong> <strong>pengembangan</strong> usaha-usaha berbasis<br />
perikanan, termasuk perikanan budidaya. Kultur pertanian (dan juga perikanan di<br />
beberapa lokasi) akan memungkinkan pengenalan usaha perikanan berjalan tanpa<br />
kesulitan berarti. Namun demikian, sebagaimana dibahas dalam bagian terdahulu,<br />
bebrapa hal teknis maupun social yang merupakan tantangan cukup signifikan, termasuk<br />
di dalamnya masalah penyiapan dana <strong>untuk</strong> <strong>pengembangan</strong> keterampilan dan<br />
pengetahuan budidaya serta <strong>untuk</strong> memperbaiki ketimpangan antar desa dalam hal<br />
kondisi sarana prasarana.<br />
4.5. Aplikasi dan Kelemahan Desain<br />
Dari sudut pandang pilihan struktur, bentuk usaha, jenis komoditas dan hal-hal<br />
<br />
spesifik lain, aplikasi <strong>desain</strong> ini akan terbatas pada wilayah di sekitar lokasi-Iokasi kasus dalam<br />
. --<br />
penelitian. Hal ini karena penentuan struktur, bentuk dan komoditas tersebut didasarkan<br />
atas pembacaan variable-variabel yang spesifik lokasi. Di lokasi lain, dengan kondisi va ria bel<br />
yang berbeda, akan diperoleh hasil yang berbeda.<br />
Namun demikian, kerangka penyusunan <strong>desain</strong> tersebut dapat diaplikasikan secara<br />
umum pada kasus-kasus berbeda di tempat-tempat yang lain . Mengacu pada komponen<br />
penopang ketahanan pangan, yang mencakup ketersediaan, akses, keamanan pangan dan<br />
distribusi, kerangka penyusunan <strong>desain</strong> dalam penelitian ini telah mencakup hal-hal yang<br />
diperlukan <strong>untuk</strong> mengakomodasikan informasi-informasi yang diperlukan <strong>untuk</strong> melakukan<br />
pembahasan atau anal isis terkait komponen-komponen penopang ketahanan pangan.<br />
Dengan demikian, generalisasi dari aplikasi pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian<br />
ini dapat dipertanggungjawabkan.<br />
Terlepas dari kelebihan tersebut di atas, penggunaan kerangka pendekatan dan hasil<br />
penelitian ini, terdapat kelemahan yang harus dicermati oleh pengguna dari kerangka<br />
maupun hasil penelitian ini. Kelemahan tersebut terkait dengan tidak dilakukannya<br />
pendekatan yang bersifat dinamis atau memasukkan penyesuaian prediksi dinamika tersebut<br />
kedalam variabel-variabel yang dijadikan dasarnya. Solusi yang dapat ditawarkan melalui<br />
laporan ini <strong>untuk</strong> mengurangi kelemahan terse but adalah melakukan koreksi terhadap <strong>desain</strong><br />
~ akhir, yaitu dengan merevisi komponen <strong>desain</strong> yang bersifat kuantitatif, misalnya yang terkait<br />
dengan skala usaha.<br />
71
~<br />
· ..<br />
4.6. Perspektif Kebijakan<br />
Desain <strong>peningkatan</strong> ketahanan pangan melaui <strong>pengembangan</strong> usaha berbasis<br />
perikanan ini sangat sejalan dengan filosofi maupun tujuan dari kebijakan nasional tentang<br />
minapolitan, yang menyangkut <strong>peningkatan</strong> produksi dan pensejahteraan masyarakat.<br />
Program minapolitan merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang<br />
mengacu pada konsep <strong>pengembangan</strong> kawasan, yang diterapkan di berbagai lokasi di seluruh<br />
wilayah Indonesia. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang termasuk dalam SK<br />
Menteri no 32/2009 tentang penetapan lokasi minapolitan. Dalam konsep minapolitan<br />
' "::J<br />
tersebut, dua sistem utama yang menjadi targetnya adalah sistem usaha dan sistem<br />
permukiman, dimana masalah pangan / konsumsi merupakan salah satu elemen utamanya.<br />
Pengembangan sistem ketahanan pangan sebagaimana dikaji melalui penelitian ini<br />
jelas mendukung pelaksanaan program minapolitan. Pengembangan usaha<br />
berbasis<br />
perikanan sangat sesuai dengan penanganan sistem usaha didalam minapolitan; unit-unit<br />
usaha rumah tangga yang diusulkan melalui penelitian ini dapat dijadikan penopang kuat<br />
bagi keberadaan wilayah-wilayah pendukung bagi lokasi minapolisnya. Sementara itu,<br />
sasaran <strong>peningkatan</strong> konsumsi selaras dengan sasaran perbaikan sistem permukiman.<br />
,<br />
-"<br />
72
. .. <br />
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN<br />
5.1. Kesimpulan<br />
Terdapat peluang <strong>untuk</strong> mengembangkan unit-unit usaha berbasis perikanan yang<br />
dikelola terkait dengan <strong>pengembangan</strong> minapolitan. Penelitian ini mengusulkan sebuah<br />
<strong>desain</strong> <strong>untuk</strong> merealisasikan peluang tersebut. Desain tersebut, pada intinya merupakan<br />
kerangka kerja <strong>pengembangan</strong> system usaha seperti tersebut di atas, yang terbangun atas<br />
sejumlah elemen penting< dari sisi teknis maupun social. Elemen penting tersebut adalah<br />
struktur, jenis usaha, komoditas pilihan, skala usaha, kelembagaan, rentang koordinasi, dan<br />
bentuk intervensi utama.<br />
Desain tersebut juga menyangkut arahan <strong>untuk</strong> mengintegrasikan <strong>pengembangan</strong><br />
unit-unit usaha tersebut kedalam program minapolitan, dimana unit-unit usaha tersebut<br />
diusulkan <strong>untuk</strong> djadikan penopang wilayah hinterland, yang akan diintegrasikan dengan<br />
sebuaah minapolis tertentu. Desain itu, di sisi lain dasain tersebut secara khusus juga<br />
dirancang <strong>untuk</strong> membidik target tertentu dalam pembangunan peri kanan, yaitu<br />
<strong>peningkatan</strong> konsumsi ikan dan pengurangan kebocoran ekonomi di masyarakat pedesaan.<br />
5.2. Implikasi Kebijakan (Butir-Butir Kebijakan)<br />
• Perlu tindak lanjut oleh pemerintah daerah dalam rangka mengimplementasikan <strong>desain</strong><br />
tersebut dalam kebijakan pembangunan di daerah, termasuk kebijakan penganggarannya.<br />
• Perlu <strong>sosial</strong>isasi tentang gagasan sebagaimana dihasilkan oleh penelitian ini.<br />
5.3. Perkiraan Dampak<br />
Apabila <strong>desain</strong> hasil penelitian ini dapat diacu dan diimplementasikan oleh pengambil<br />
kebijakan, maka diperkirakan target pemenuhan konsumsi ikan masyarakat sebesar 38.67 %<br />
dapat dicapai, dan kesempatan masyarakat <strong>untuk</strong> meningkatkan pendapatan dalam rangka<br />
mendapatkan akses ekonomi yang lebih besar terhadap sumber-sumber pangan esensiallain<br />
dapat direalisasikan. Karena dengan mengoptimalkan usaha perikanan, tidak saja memberi<br />
peluang dalam menciptakan tenaga kerja, namun lebih dari itu adalah membuat masyarakat<br />
~ mudah <strong>untuk</strong> mendapatkan makanan sehat seperti ikan.<br />
73
DAFTAR PUSTAKA <br />
Adrianto Land N Aziz. 2006. Valuing The Social-Ecological Interactions in Coastal Zone<br />
Management: A Lesson Learned from The Case Of Economic Valuation of Mangrove<br />
Ecosystem in Barru Sub-District, South Sulawesi Province. Seminar in Social-Ecological<br />
System Analysis. ZMT, Bremen University. Bremen, 12 June 2006.<br />
Anonymous. 2009". Report of February 2009 Regional Consultation on International Fisheries<br />
Related Issues. SEAFOEC unpublished doc.<br />
Anonymous. 2009 b • Rumusan Akhir Rekomendasi Untuk Presiden terkait Pengembangan Program<br />
Ketahanan Pangan. Seminar Nasional Peringatan Hari Pangan Sedunia XXIX, Jakarta 1<br />
Oktober 2009.<br />
Anonimous. 2009'. Data Monografi Oesa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.<br />
Yogyakarta.<br />
Anonimous. 2010". Profil Kelompok Usaha Bersama KUB "Ngudi Rejeki" Oalam Rangka Penilaian<br />
Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2010. Oesa Karangwuni Kecamatan Wates<br />
Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta.<br />
Anonimous. 2010 b • Profil Tokoh Nelayan Teladan Oalam Rangka Penilaian Penghargaan Adibakti<br />
Mina Bahari Tahun 2010. Oesa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.<br />
Yogyakarta.<br />
Anonimous. 2010'. Profil TPI PPI "Tanjung Adikarta" Oalam Rangka Penilaian Penghargaan<br />
Adibakti Mina Bahari Tahun 2010. Oesa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon<br />
Progo. Yogyakarta .<br />
Anderies JM, MA Janssen and E Ostrom. 2004. A Framework to Analyze The Robustness of Social<br />
Ecological Systems from An Institutional Perspective. Ecology and Society 9 (1), 18 [online]<br />
Atmodjo, H Syarief, 0 Sukandar dan M Latifah. 1995. Laporan Studi Identifikasi Oearah Rawan<br />
Pangan. Proyek Pengembangan Oiversifikasi Pangan dan Gizi. Oepartemen Pertanian -<br />
Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.<br />
Aziz. 1990. Agriculture for The 1990'5. Development Center Studies OECO Paris. Oalam Berita<br />
Pangan Vol. I No. 1 Hal. 22.<br />
Badan Pusat Statistik. 2003. 01 Yogyakarta Oalam Angka 2002. Badan Pusat Statistik Propinsi 01<br />
Yogyakarta . Yogyakarta.<br />
Badan Pusat Statistik. 2010. Kulon Progo Oalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten<br />
Kulon Progo. Yogyakarta .<br />
Badan Pusat Statistik. 2008. Kecamatan Wates Oalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik<br />
Kabupaten Kolon Progo. Yogyakarta .<br />
. Berkes F and C Folke. 1998. Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and<br />
Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge University Press. Cambridge.<br />
Camelia LS, Retnaningsih dan Roosita K. 2002. Konsumsi Ikan dan Faktor Yang Mempengaruhinya<br />
Pada Remaja di SMUN 9 Bandung. Media Gizi dan Keluarga, Juli 20002, XXVI (1): 106-113.<br />
Carpenter SR and C Folke. 2006. Ecology for Transformation. Trends in Ecology and Evolution 21<br />
(6): 309 - 315.<br />
74
... "<br />
Dahuri R. 2004. Peran Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam Mewujudkan Ketahanan<br />
Pangan dan Gizi. Makalah disajikan dalam Prosiding WNPG VIII. Jakarta: LlPI.<br />
Darseno. 2010. Buku Pintar Budidaya dan Bisnis Lele. PT AgroMedia Pustaka. Jakarta.<br />
Departemen Pertanian Republik Indonesia. 1996. Undang-Undang No. 7 tentang Pangan.<br />
Departemen Pertanian. Jakarta.<br />
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 2001. Profil Kecamatan Sogan:<br />
Data Pokok Perikanan dan Kelautan. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten<br />
Kulon Progo, Yogyakarta.<br />
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 2009. Profil Kecamatan Wates:<br />
Data Pokok Perikanan dan Kelautan. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten<br />
Kulon Progo, Yogyakarta.<br />
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 2009. Data Statistik Perikanan<br />
Tangkap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan<br />
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.<br />
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 2009. Data Statistik Perikanan<br />
Budidaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan<br />
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 2010. Laporan Akuntabilitas<br />
Instansi Pemerintan (LAKIP). Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon<br />
Progo, Yogyakarta.<br />
Effendi I dan W Oktariza. 2006. Manajemen Agribisnis Perikanan. Penebar Swadaya. Jakarta.<br />
FAO. 1997. Implication of Economic Policy for Food Security. Training Materials for Agricultural<br />
Planning 30, Rome.<br />
Hardinsyah. 1996. Management and Determinant of Food Diversity: Implication for Indonesian's<br />
Food and Nutrition Policy. Disertasi Doktor. Faculty of Medicine, University of Queensland.<br />
Australia.<br />
Hardinsyah dan Suhardjo. 1987. Ekonomi Gizi. Diktat Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya<br />
Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.<br />
Hardinsyah dan D Martianto. 1992. Gizi Terapan. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan<br />
Gizi.<br />
Hardinsyah dan D Briawan. 1994. Penilaian dan Perencanaan Konsumsi Pangan. Diktat Jurusan<br />
Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.<br />
Hardinsyah. 1996. Status Kerja Ibu dan Pendapatan dalam Hubungannya dengan Mutu Makanan<br />
Keluarga di daerah Perkotaan. Media Gizi dan Keluarga. Tahun XX No. 2 Desember 1996.<br />
Hal. 86.<br />
Hardinsyah. 1997. Mutu Konsumsi Pangan Penduduk yang Mempunyai Pola Konsumsi Pangan<br />
Pokok Beragam di Indonesia (Makalah disajikan dalam Seminar Gizi) . PAU UGM.<br />
Yogyakarta. 28-29 Juni 1997.<br />
Hardinsyah, D Briawan, S Madanijah, eM Dwiriani, SM Atmodjo dan Y Heryatno. 1998. Kajian<br />
Kelembagaan <strong>untuk</strong> Pemantauan Ketahanan Pangan. Kerjasama PUsat Kebijakan Pangan<br />
dan Gizi, Institut Pertanian Bogor dengan Unicef dan Biro Perencanaan, Departemen<br />
Pertanian. Jakarta.<br />
Hardinsyah dan V Tambunan. 2004. Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, dan Serat<br />
Makanan. WNPG VIII. Jakarta: LlPI.<br />
75
Hasan I. 1995. Aku Cinta Makanan Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan.<br />
Pengarahan Kursus penyegar Ilmu Gizi dan Kongres Nasional PERSAGI X. 21- 23 November.<br />
Bandung.<br />
Khomsan A. 2000. Teknik Pengukuran Pengetahuan GizL Diktat Jurusan Gizi Masyarakat dan<br />
Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.<br />
Maryanto E. 2008. Evaluasi Kinerja Program Pertanian Rumah Tangga. Laporan Teknis Yayasan<br />
Bina Bangun Desa.<br />
Purnomo AH. 2009. Pangan dari Ikan: Kondisi Sekarang dan Prediksi Kedepan. Seminar Nasional<br />
Peringatan Hari Pangan Sedunia XXIX, Jakarta 1 Oktober 2009.<br />
Reutlinger S. 1987. Food Security and Poverty in Developing Countries. In: Gitinger et 01. (Eds.)<br />
Food Policy Published for The World Bank. The Johns Hopkins University Press, Baltimore<br />
and London.<br />
Sawit MH dan MAriani. 1997. Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah Seminar Pra<br />
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. 26 - 27 Juni. Jakarta.<br />
Simatupang P. 1999. Towards Sustainable Food Security: The Needs for A New Paradigm.<br />
International Seminar Agricultural Sector Duriirection. 17 - 18 Februari 1999. Centre for<br />
Agro-Socio Economics Research, AARD.<br />
Suhardjo. 1989. Sosio Budaya Gizi. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi.<br />
Suhardjo, U Harper, BJ Deaton dan JA Driskel. 1988. Pangan, Gizi dan Pertanian. Jakarta:<br />
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<br />
Suhardjo, Riyadi H. 1993. Pola Konsumsi Ikan di Indonesia. Risalah Widya Karya Nasional Pangan<br />
dan Gizi V. Jakarta: LlPI.<br />
Soemarwoto 0.1994. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta.<br />
Soetrisno I. 1996. Beberapa Catatan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah<br />
Tangga Indonesia. Laporan Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga . Departemen<br />
Pertanian RI- UNICEF.<br />
Soetrisno N. 1995. Ketahanan Pangan. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Serpong<br />
17 - 20 Februari. LlPI. Jakarta.<br />
Suratiyah K. 2006. IImu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta.<br />
Susanto D. 1996. Aspek Pengetahuan dan Sosio Budaya dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah<br />
Tangga. Laporan Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Departemen Pertanian RI <br />
UNICEF.<br />
Syarief H, Hardinsyah dan Atmojo. 1999. Membenahi Konsep Ketahanan Pangan Indonesia. Dalam<br />
A.R. Thaha, Hardinsyah, A. Ala (ed), Pembangunan Gizi dan Pangan dari Perspektif<br />
Kemandirian Lokal (hal. 51- 71). Pergizi Pangan dan CRESCENT. Bogor.<br />
Tohir KA. 1983. Seuntai Pengetahuan tentang Usahatani Indonesia. Bagian Satu. PT Bina Aksara.<br />
Jakarta.<br />
76