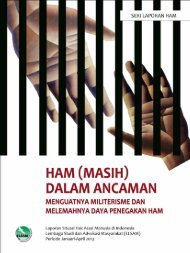mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam
mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam
mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Seri Bahan Bacaan Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X<br />
Tahun 2005<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
MEKANISME DOMESTIK UNTUK MENGADILI<br />
PELANGGARAN HAM BERAT<br />
MELALUI SISTEM PENGADILAN<br />
ATAS DASAR UU No. 26 Tahun 2000<br />
Prof. Dr. Muladi, S.H.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat<br />
Jl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510<br />
Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519<br />
Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
1. Pengantar<br />
Bagian Pertama<br />
KERANGKA KONSEPTUAL DAN ASAS-ASAS<br />
Setiap negara memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya dan berhak menentukan suatu sistem hukum<br />
nasional yang menentukan berlakunya hukum nasional atas dasar jurisdiksi substansi (ratione materiae),<br />
jurisdiksi temporal (ratione temporis), ratione territorial (ratione loci) dan jurisdiksi personal (ratione personae).<br />
Namun demikian terdapat perkembangan yang menarik berkaitan dengan proses pengadilan terhadap<br />
<strong>pelanggaran</strong> HAM berat (gross/serious violation of human rights) yang dianggap kejahatan yang sangat berat<br />
yang melanggar kepentingan yang dilindungi hukum internasional (delicta juris gentium) dan merupakan<br />
musuh semua umat manusia (hostis humani generis) serta merupakan kepentingan, tugas dan kewajiban<br />
seluruh negara <strong>untuk</strong> menegakkan hukum (responsibility to all state/erga omnes). Pelanggaran HAM berat<br />
telah mencederai nurani warga seluruh negara di dunia.<br />
Atas dasar pemikiran di atas, proses pengadilan terhadap <strong>pelanggaran</strong> HAM berat seperti kejahatan perang<br />
(war crimes), genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dalam<br />
sejarah mengalami perkembangan yang sangat bervariasi. Di samping pengadilan nasional (misalnya<br />
Indonesia atas dasar UU No. 26 Tahun 2000), berkembang pula pengadilan supranasional ( mis. IMT<br />
Nuremberg, IMTFE di Tokyo, ICTR, ICTY dan ICC) dan perpaduan antara pengadilan nasional dan<br />
internasional (Hybrid Model) seperti yang berkembang di Sierra Leonne, Kamboja dan Timor Timur.<br />
Perkembangan lain yang menarik adalah praktek penerapan jurisdiksi universal (universal jurisdiction) oleh<br />
negara-negara tertentu di mana nasionalitas terdakwa atau para korban, atau tempat di mana kejahatan<br />
dilakukan tidak menentukan di mana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan., sehingga pengadilan<br />
setiap negara dapat <strong>mengadili</strong>nya.<br />
2. Pengadilan Nasional Sebagai ‘ The Forum of First Resort ‘<br />
Sebelum membahas pengadilan HAM Indonesia, sebaiknya dipa<strong>ham</strong>i terlebih dahulu tentang hakekat,<br />
asas dan praktek pengadilan nasional dalam konteks hukum internasional. Sekalipun proses peradilan<br />
internasional telah banyak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana secara individual (individual<br />
criminal responsibility) terhadap pelbagai pelanggar HAM berat (kejahatan perang, genosida dan kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan), namun sistem hukum nasional tetap merupakan pilihan utama (primary fora)<br />
<strong>untuk</strong> menegakkan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara <strong>untuk</strong><br />
menegakkan prinsip supremasi hukum. Pertimbangan lain adalah kedekatannya dengan tempat, suasana<br />
dan iklim pada saat kejahatan terjadi, dan kedekatannya dengan pelaku serta korban. Tribunal ad hoc<br />
internasional (mis. ICTY dan ICTR) sekalipun menggunakan istilah ‘primacy’ terhadap pengadilan nasional<br />
(Art. 9.2 ICTY Statute : ’The International Tribunal shall have primacy over national court’), pada dasarnya tetap<br />
memberikan kesempatan <strong>mengadili</strong> terlebih dahulu kepada sistem pengadilan nasional. Istilah yang<br />
digunakan dalam Preamble ICC lebih jelas yakni ‘complementary’ (ICC…... shall be complementary to national<br />
criminal jurisdiction).<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
3. Asas-asas Umum Sebagai Landasan Jurisdiksi<br />
Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat menerapkan<br />
jurisdiksi atas semua kejahatan tanpa mempedulikan di mana kejahatan tersebut terjadi. Jurisdiksi nasional<br />
tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional maupun asas-asas<br />
hukum internasional.<br />
Pada dasarnya<br />
tersebut :<br />
terdapat ketentuan hukum internasional yang mengakui 5 (lima) landasan jurisdiksi<br />
a. Asas teritorialitas (the territorial principle) yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur dan<br />
menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya<br />
dilakukan di wilayah teritorialnya. Asas ini di beberapa negara mengalami perluasan , yaitu hukum<br />
pidana nasional diberlakukan juga apabila suatu bagian elemen utama dari akibat (substantial effect)<br />
kejahatan terjadi di negara tersebut (the effect principle);<br />
b. Asas nasionalitas (the nationality principle) yang mengatur bahwa setiap negara dapat menerapkan<br />
jurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya, tanpa menghiraukan<br />
tempat dilakukannya perbuatan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas, kepentingan, status dan hubungan<br />
warganegaranya. Ada negara yang membatasi berlakunya asas ini <strong>untuk</strong> tindak pidana tertentu yaitu<br />
kejahatan berat, tetapi banyak juga yang menerapkannya <strong>untuk</strong> semua kejahatan tanpa memperhatikan<br />
di mana kejahatan dilakukan;<br />
c. Asas perlindungan (the protective principle) yang mengatur bahwa perbuatan yang bersifat extraterritorial<br />
yang dilakukan oleh warganegaranya akan menimbulkan bahaya baik aktual maupun<br />
potensial terhadap kepentingan penting negara, biasanya berkaitan dengan keamanan nasional atau<br />
integritas dan beberapa fungsi penting dari negara. Termasuk di sini espionage, pemalsuan uang dan<br />
sumpah palsu di depan pejabat konsuler;<br />
d. Asas personalitas pasif (the passive personality principle). Asas ini menegaskan jurisdiksi negara <strong>untuk</strong><br />
diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar teritori negara oleh seorang bukan warganegara,<br />
di mana korban perbuatan tersebut adalah warganegara negara tersebut. Biasanya hal ini diterapkan<br />
terhadap teroris dan pelaku serangan terorganisasi yang lain terhadap warganegara dengan alasan<br />
kewarganegaraannya; tidak jarang digunakan <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> individu yang melakukan kejahatan<br />
yang diatur hukum nasional yang dilakukan di luar negeri, termasuk <strong>pelanggaran</strong> HAM;<br />
e. Asas universalitas (the universality principle) yang sangat penting <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> <strong>pelanggaran</strong> HAM<br />
berat dan kejahatan-kejahatan lain yang diakui oleh masyarakat negara-negara sebagai kejahatan yang<br />
menarik perhatian internasional seperti pembajakan di laut dan di udara serta mungkin terorisme dan<br />
perdagangan budak. Asas ini memungkinkan suatu negara <strong>untuk</strong> menerapkan jurisdiksi terhadap<br />
pelaku kejahatan tertentu yang sangat berat dan berbahaya terhadap umat manusia, tanpa<br />
memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya (nexus) dengan kejahatan, pelaku atau korban.<br />
Dalam hal ini setiap negara dianggap mempunyai kepentingan <strong>untuk</strong> menerapkan jurisdiksi ini atas<br />
kejahatan seperti pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan,<br />
penyiksaan, sabotase dan genosida. Pengalaman menunjukkan bahwa dasar hukum - apakah traktat<br />
atau kebiasaan - bervariasi dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Apabila kejahatan tersebut<br />
berkaitan dengan suatu ‘erga omnes obligation’ atau suatu ‘jus cogens norm’ (peremptory norms) maka<br />
alasan setiap negara <strong>untuk</strong> menerapkan jurisdiksinya lebih kuat. Namun demikian apabila negara yang<br />
memiliki territorial memang berkehendak (willing) dan mampu (able) <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong>, negara lain pada<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 2
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
umumnya menangguhkannya. Perjanjian (treaty) yang mengijinkan (permit) negara <strong>untuk</strong> menerapkan<br />
hukum atas dasar jurisdiksi universal termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Penyiksaan<br />
(Torture Convention) 1984. Kemudian yang mewajibkan (require) adalah 1956 Slavery Convention dan<br />
Apartheid Convention. Apabila tidak diatur dalam treaty, maka yang berlaku adalah hukum kebiasaan<br />
internasional. Dalam hal ini sifatnya mengijinkan (permissive) dan tidak memerintahkan (mandatory).<br />
(‘States may, but are not required’). Saat ini dalam beberapa hal diterapkan kewajiban negara <strong>untuk</strong><br />
mengekstradisikan atau menuntut pelaku (aut dedere aut judicare).<br />
4. Pelbagai Variasi yang Terjadi<br />
Sekalipun baik treaties maupun hukum kebiasaan internasional telah mempertimbangkan bahwa<br />
pengadilan nasional/<strong>domestik</strong> merupakan ‘primary arena’ <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> atas dasar pertanggungjawaban<br />
individual, namun ternyata bahwa variasi yang luas dirumuskan dalam pelbagai perjanjian internasional<br />
dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Ada yang mengharuskan tetapi ada juga yang hanya<br />
mengijinkan.<br />
Contoh pertama adalah masalah genosida (genocide). Sekalipun Genocide Convention bermaksud memikirkan<br />
keberadaan pengadilan internasional <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> genosida, <strong>ham</strong>pir semua negara peserta<br />
mengantisipasi bahwa pengadilan nasional merupakan ‘the primary fora’. Sehubungan dengan itu, Article VI<br />
mewajibkan (requires) para pihak <strong>untuk</strong> memidana perbuatan genosida yang dilakukan dalam teritorinya.<br />
Dalam hal ini ‘extra-territorial jurisdiction’ tidak memperoleh penegasan. Kemungkinan penerapan jurisdiksi<br />
territorial didasarkan atas asas nasionalitas dan asas personalitas pasif.<br />
Bisa dicatat bahwa sekalipun dalam konvensi tidak secara tegas diatur tentang ‘universal jurisdiction’ (extraterritorial<br />
jurisdiction), namun atas dasar ‘customary international law’ hal ini terjadi atas dasar ‘erga omnes<br />
nature of the ban on genocide’. Contohnya adalah ‘Eichmann and Demanjuk cases’, yang menegaskan<br />
penerapan jurisdiksi universal terhadap genosida.<br />
Contoh kedua berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Pelbagai<br />
Tribunal internasional yang dibentuk setelah PD II <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> kejahatan perang dan kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan (IMT dan IMTFE) acap kali mendasarkan pada asas jurisdiksi universal. Namun<br />
demikian dalam beberapa pengadilan yang digelar juga mendasarkan pada asas territorial dan asas<br />
nasionalitas. Sebagaimana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan juga tunduk pada jurisdiksi<br />
universal. Sehubungan dengan kejahatan perang (war crimes), setiap negara boleh <strong>mengadili</strong> <strong>pelanggaran</strong><br />
berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa dan Protocol I; Konvensi mewajibkan setiap negara <strong>untuk</strong><br />
menetapkan sanksi pidana yang efektif (to provide effective penal sanctions) kepada setiap orang yang<br />
melakukan ‘grave breaches’, menemukan pelakunya dan menuntut atau mengekstradisikannya.<br />
Sampai dengan tahun 1990-an, tidak nampak adanya penuntutan terhadap kejahatan perang atas dasar<br />
instrumen ini murni atas dasar asas universalitas. Terhadap <strong>pelanggaran</strong> terhadap bagian lain Konvensi<br />
dan Protokol, termasuk ‘Common Article 3 ‘ atau Protocol II, nampaknya tidak ada perintah atau kewajiban<br />
penuntutan atau ekstradisi, atau ketentuan tentang jurisdiksi universal. Meskipun demikian, hukum<br />
kebiasaan cenderung mengakui jurisdiksi universal atas jangkauan yang lebih luas dari kejahatan perang<br />
daripada yang masuk kategori ‘grave breaches’ dari Konvensi dan Protocol I. Sebagai contoh adalah<br />
Konvensi The Haque 1954 tentang ‘The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict’,<br />
mewajibkan negara-negara <strong>untuk</strong> mengambil segenap langkah-langkah yang diperlukan <strong>untuk</strong> menuntut<br />
dan menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi disiplin terhadap siapa saja, apapun kewarganegaraannya yang<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 3
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
melakukan atau memerintahkan terjadinya <strong>pelanggaran</strong> terhadap konvensi. Hal ini (jurisdiksi universal)<br />
bersifat perintah (mandatory), sekalipun konvensi tidak memuat ketentuan pidana yang lain.<br />
Contoh yang lain adalah ketentuan yang berkaitan dengan ‘Slavery and Forced Labour’. Di bawah Slavery<br />
Convention (1956), negara-negara peserta harus melakukan kriminalisasi terhadap perbudakan dan<br />
perdagangan budak, tanpa mempertimbangkan dimana perbuatan terjadi. Bahkan, ‘slave trade’ harus<br />
dipidana seberat-beratnya. Dalam hal ini tidak jelas apakah hukum kebiasaan internasional mewajibkan<br />
semua negara <strong>untuk</strong> menerapkan jurisdiksi universal terhadap perbudakan, sekalipun mengenai<br />
perbudakan paling tidak negara-negara mengaturnya secara ‘permissive’ atas dasar hukum kebiasaan<br />
internasional. Sepanjang mengenai kerja paksa (forced labour), Konvensi 1930 mewajibkan negara-negara<br />
<strong>untuk</strong> memidananya sebagai tindak pidana, sedang ‘Convention on Forced Prostitution’ mewajibkan negaranegara<br />
<strong>untuk</strong> memidana setiap orang yang berperan serta, namun tidak memuat kewajiban <strong>untuk</strong><br />
melakukan ekstradisi.<br />
Contoh selanjutnya adalah berkaitan dengan penyiksaan (torture). Konvensi tentang Penyiksaan secara jelas<br />
mewajibkan negara-negara <strong>untuk</strong> menjamin agar penyiksaan, percobaan <strong>untuk</strong> melakukannya dan<br />
penyertaan (complicity) <strong>untuk</strong> melakukan penyiksaan merupakan tindak pidana (dikriminalisasikan) dan<br />
memidananya secara patut sesuai dengan beratnya.<br />
Selanjutnya negara-negara wajib mengatur <strong>untuk</strong> memidana penyiksaan yang terjadi di wilayah<br />
teritorinya, oleh warganegaranya, dan apabila dipandang perlu, terhadap warganegaranya (korban), juga<br />
segala keadaan yang lain di mana negara tersebut memilih <strong>untuk</strong> tidak mengekstradisikan si pelaku.<br />
Melebihi ketentuan konvensi, hukum kebiasaan internasional mengijinkan negara-negara <strong>untuk</strong><br />
menerapkan jurisdiksi universal terhadap penyiksaan.<br />
Contoh berikutnya mengenai ‘Apartheid’. Konvensi Apartheid mengijinkan bahkan memerintahkan negaranegara<br />
peserta <strong>untuk</strong> menentukan dan menerapkan kriminalisasi yang dilakukan dimana pun juga<br />
(committed anywhere). Tribunal internasional juga dipertimbangkan dan mewajibkan negara-negara <strong>untuk</strong><br />
mengekstradisikan pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada.<br />
Contoh terakhir berkaitan dengan kejahatan Penghilangan Paksa (Forced Disappearances). Terlepas dari<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan asas jurisdiksi dalam hal ini juga mengalami perkembangan. Pada tahun<br />
1992, Resolusi Sidang Umum PBB menyerukan kepada negara-negara anggota <strong>untuk</strong><br />
mengkriminalisasikan ‘apartheid’ sebagai kejahatan berat dan mewajibkan negara-negara <strong>untuk</strong><br />
mengekstradisikannya atau menuntut pelakunya, dan menyerukan pengaturan daluwarsa yang panjang.<br />
5. Relevansinya dengan Hukum Nasional<br />
Negara-negara peserta konvensi mempunyai kewajiban <strong>untuk</strong> mengkriminalisasikan dan memidana<br />
kejahatan-kejahatan tertentu dalam hukum pidana nasionalnya sebagai pelaksanaan kewajiban tersebut.<br />
Bentuk lain adalah bahwa sistem hukum nasional atau <strong>domestik</strong> mengijinkan <strong>untuk</strong> secara langsung di<br />
bawah hukum internasional. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, sebenarnya merupakan<br />
<strong>pelanggaran</strong> terhadap komitmen internasional. Namun demikian akibat dari bervariasinya kewajibankewajiban<br />
atas dasar konvensi internasional (treaty-based duties) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,<br />
maka jangkauan (coverage) hukum nasional atau hukum <strong>domestik</strong> yang mengaturnya juga bervariasi dari<br />
kejahatan yang satu ke kejahatan lainnya.<br />
Sebagai contoh adalah sepanjang berkaitan dengan ‘genocide’, hukum nasional/<strong>domestik</strong> membatasi<br />
pengaturannya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam wilayahnya (state’s soil),<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
sedangkan mengenai penyiksaan (torture), jangkauannya diperluas meliputi perbuatan-perbuatan yang<br />
dilakukan di mana saja (acts committed anywhere). Di lain pihak, ada juga negara-negara yang dalam hukum<br />
nasionalnya mengatur sesuatu yang melebihi kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Mereka<br />
mengijinkan penuntutan atas dasar asas universalitas, walaupun konvensi internasional yang relevan<br />
hanya mewajibkan penuntutan atas dasar asas teritorialitas. Dalam hal ini ada kemungkinan negara<br />
tertentu memidana perbuatan tertentu, padahal konvensi internasional yang relevan tidak mewajibkan<br />
pemidanaan.<br />
Ruang lingkup pengaturan kewajiban internasional dalam hukum <strong>domestik</strong> , baik secara lengkap, tidak<br />
lengkap atau melebihi apa yang diwajibkan, merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dalam<br />
rangka melakukan penuntutan, sesuai dengan pelbagai variasi kewajiban yang digariskan baik dalam<br />
konvensi maupun hukum <strong>domestik</strong>. Dalam kriminalisasi juga terdapat variasi, dimana ada negara yang<br />
sepenuhnya mengikuti konsepsi hukum internasional dalam mendefinisikan kejahatan (definition of crime in<br />
toto), sementara yang lain berusaha <strong>untuk</strong> mendefinisikannya sendiri sesuai dengan keutuhan nasionalnya.<br />
Di samping itu ada juga negara yang hanya memanfaatkan hukum pidana yang ada yang mengatur<br />
‘common crimes’ seperti pembunuhan (murder) atau penganiayaan (battery) <strong>untuk</strong> memproses pelanggar<br />
HAM. Catatan : Larangan <strong>untuk</strong> menerapkan ketentuan ‘ordinary crimes’ terhadap <strong>pelanggaran</strong> HAM berat,<br />
sehingga mengakibatkan pengecualian terhadap asas ‘ne bis in idem’ antara lain terdapat dalam Statuta ICTY<br />
Article 19. 2 (a).<br />
6. Pengalaman Beberapa Negara<br />
Sampai tahun 1990-an penuntutan para pelanggar hukum HAM internasional melalui pengadilan nasional<br />
jarang dilakukan. Praktek yang dilakukan negara-negara Sekutu setelah PD II, begitu juga yang kemudian<br />
dilakukan oleh Perancis, Australia, Canada, UK, dan Croatia merupakan perkecualian. Sampai tahun 1980-<br />
an bisa disebut apa yang terjadi di Yunani (Greek) yang <strong>mengadili</strong> anggota-anggota junta militer menyusul<br />
keruntuhannya tahun 1974.<br />
Sepanjang mengenai genosida, di samping kasus Eichmann di Israel tahun 1960-an, hanya ada sedikit<br />
penuntutan setelah PD II. Di Equatorial Guinea pemerintah <strong>mengadili</strong> mantan diktator atas tuduhan<br />
genosida dan kejahatan lain. Demikian juga yang terjadi di Kamboja, di mana Pemerintah atas bantuan<br />
Vietnam berusaha <strong>mengadili</strong> Pol Pot Pemimpin Khmer Merah dan Ieng Sari secara in absentia atas genosida<br />
tahun 1979. Pengadilan ini boleh dikatakan kurang memadai karena nuansa politik yang besar dan kurang<br />
dipenuhinya prinsip ‘due process’ dalam pelaksanannya. Mengenai kejahatan perang (war crimes)<br />
pengadilan <strong>domestik</strong> frekuensinya lebih tinggi atas dasar ketentuan <strong>domestik</strong> yang mengatur peradilan<br />
militer, sekalipun boleh dikatakan sebagian besar kejahatan perang tidak diadili semenjak berlakunya<br />
Konvensi Jenewa 1949. Yang dipublikasikan secara luas antara lain yang terjadi di Amerika Serikat yaitu<br />
kasus Calley dalam perang Vietnam.<br />
Perkembangan selanjutnya bisa dicatat apa yang terjadi di Latvia pada tahun 1996 yang <strong>mengadili</strong> pejabatpejabat<br />
di era Soviet; kemudian di Guatemala tahun 1980-an yang memproses genosida para mantan<br />
pemimpin militer; selanjutnya tahun 1990-an Hungaria memproses pembunuhan-pembunuhan selama<br />
pemberontakan tahun 1956. Demikian pula yang terjadi di Argentina pada tahun 1999, di Jerman setelah<br />
reunifikasi pada tahun 1990 dan di Ethiopia pada tahun 1991. Indonesia mencatat adanya pengadilan<br />
militer terhadap 24 tentara di Aceh, di samping Pengadilan HAM <strong>untuk</strong> Timor Timur dan Tanjung Priok.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
7. Proses Penuntutan oleh Pengadilan Nasional Negara Lain<br />
Pengadilan hukum pidana oleh suatu negara di luar tempat dimana <strong>pelanggaran</strong> HAM berat terjadi juga<br />
merupakan salah satu opsi. Negara yang berusaha <strong>mengadili</strong> kejahatan yang dilakukan di luar negeri<br />
dapat menerapkan jurisdiksi atas dasar nasionalitas pelaku atau nasionalitas korban. Apabila negara<br />
tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan tersebut, asas yang digunakan adalah asas universalitas<br />
dengan memberlakukan jurisdiksi universal.<br />
Dalam hal ini negara yang bersangkutan harus membuat ketentuan hukum pidana yang mengijinkan<br />
penuntutan atas perbuatan extra-territorial atau mengijinkan penuntutan langsung atas dasar hukum<br />
internasional.<br />
Dalam kerangka ini seharusnya kejahatan internasional yang dilakukan di luar negeri mungkin dituntut<br />
atas dasar ketentuan khusus yang diumumkan bahwa negara tersebut mentaati kewajiban hukum<br />
internasional. Bisa juga konvensi internasional itu sendiri menentukan bahwa negara tersebut menetapkan<br />
hukum yang mengatur tentang perbuatan extra-territorial. Contohnya adalah Konvensi Penyiksaan 1984<br />
mewajibkan negara-negara <strong>untuk</strong> mengatur ketentuan yang mengijinkan penuntutan terhadap penyiksaan<br />
yang dilakukan di luar batas negara. Demikian pula dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol I. Dalam<br />
kedua hal ini negara-negara harus memiliki suatu perundang-undangan yang diperlukan <strong>untuk</strong><br />
mengkriminalisasikan ‘grave breaches’ tanpa memperhatikan tempat di mana perbuatan dilakukan.<br />
Beberapa negara perundang-undangannya mengatur mengenai perbuatan extra-territorial sekalipun<br />
konvensi yang relevan tidak mewajibkan penalisasi perbuatan tersebut. Contohnya adalah AS dan Perancis<br />
yang mengatur genosida atas dasar asas nasionalitas dan Perancis atas dasar asas nasionalitas dan<br />
personalitas pasif, di samping asas teritorialitas yang ditentukan dalam Konvensi.<br />
Beberapa negara juga mengatur kejahatan internasional di samping yang ditentukan dalam Konvensi.<br />
Belgia, Spanyol, Swedia dan AS dalam mengatur kejahatan perang mencakup kejahatan-kejahatan lain di<br />
luar ‘grave breaches’. Konvensi Jenewa termasuk <strong>pelanggaran</strong> Protocol II. Pengaturan tentang genosida di<br />
Perancis tahun 1992 mencakup pula tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan di Canada yang<br />
mengatur tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mengijinkan penuntutan<br />
terhadap seorang asing atas perbuatannya di luar Canada terhadap orang asing lain. Syaratnya adalah atas<br />
dasar kehadirannya di Canada .<br />
Praktek di pelbagai negara menunjukkan bahwa sampai pertengahan 1990-an terungkap bahwa ada<br />
kecenderungan negara-negara tidak menghendaki (unwillingness) <strong>untuk</strong> memidana pelaku kekejaman yang<br />
dilakukan di luar negeri, lebih-lebih bilamana kejahatan tidak dilakukan oleh atau diarahkan kepada<br />
warganegaranya. Perkembangan yang menarik terjadi setelah ICTR dan ICTY digelar, dalam hal mana<br />
sejumlah negara Eropa mulai menuntut pelaku kejahatan yang berada dalam wilayahnya, atas dasar<br />
ketentuan <strong>domestik</strong> yang melaksanakan Konvensi Jenewa atau Konvensi lain.<br />
Tersangka dalam konflik Yugoslavia dapat dituntut di Belanda, Jerman dan Denmark serta Austria dan<br />
Swiss. Demikian pula tersangka kasus Rwanda yang dapat dituntut di Swiss, Perancis dan Belgia. Demikian<br />
pula yang terjadi di Spanyol dan negara lain, yang menerapkan asas jurisdiksi universal <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong><br />
mantan-mantan pejabat di Chili, Argentina dan Guatemala dalam rezim militer tahun 1970 dan 1980-an<br />
seperti Jendral Augusto Pinochet. Januari tahun 2000 Senegal <strong>mengadili</strong> diktator Chad Hissene Habre yang<br />
diasingkan ke Senegal sejak 1990.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 6
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah hukum pidana di beberapa negara mengatur kemungkinan<br />
pemidanaan secara extra-territorial terhadap kejahatan biasa. Contohnya Perancis. Bagi warganegara<br />
Perancis berlaku <strong>untuk</strong> semua kejahatan yang dipidana di Perancis dan <strong>untuk</strong> orang asing terbatas pada<br />
kejahatan melawan negara Perancis. Amerika menerapkan prinsip extra-territorial pada orang asing yang<br />
melakukan terorisme. KUHP Swedia memungkinkan diadilinya warganegara Swedia dan orang asing yang<br />
tinggal di Swedia atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri dengan syarat perbuatan tersebut<br />
merupakan tindak pidana di tempat tersebut termasuk kejahatan menurut hukum internasional.<br />
8. Kesimpulan<br />
a. Pengadilan nasional merupakan ‘the primary forum’ <strong>untuk</strong> <strong>mengadili</strong> para pelanggar HAM berat.<br />
Pengadilan di mana kejahatan dilakukan sangat praktis mengingat (1) keterkaitan dengan masyarakat<br />
setempat, sehingga memiliki effek ‘deterrent’; (2) memudahkan mencari bukti-bukti, saksi-saksi dan para<br />
pelaku; (3) tidak mahal dan lebih mudah dilaksanakan;<br />
b. Kendala terhadap pengadilan nasional biasanya berkaitan dengan (1) disfungsionalisasi pengadilan<br />
karena sebab-sebab tertentu; (2) <strong>pelanggaran</strong> HAM biasanya berkaitan dengan kebijakan negara ;<br />
c. Pengadilan nasional hanya akan efektif apabila (1) dilakukan secara ‘fair and effective’; (2) keberadaan<br />
hukum materiil dan hukum formil yang memadai; (3) penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara<br />
terlatih dengan baik; (4) keberadaan infrastruktur sistem peradilan pidana yang memadai; dan (5)<br />
keberadaan budaya yang menghormati ‘fairness’ dan ‘impartiality’ dari proses peradilan dan hak-hak<br />
pelaku;<br />
d. Eksistensi dari Tribunal internasional, ‘mixed tribunals’ dan penerapan jurisdiksi universal sekalipun<br />
penting <strong>untuk</strong> memicu digelarnya pengadilan nasional sebaiknya hanya dilakukan apabila pengadilan<br />
nasional manunjukkan gejala ‘unwilling and unable’, sehingga peranannya bersifat komplementer<br />
terhadap pengadilan nasional.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 7
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Bagian Kedua<br />
CATATAN TERHADAP PENGADILAN HAM NASIONAL<br />
1. Keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak terlepas dari perkembangan<br />
Pengadilan HAM internasional baik yang bersifat ad hoc (yang berlaku di Nuremberg, Tokyo, Rwanda<br />
dan bekas Yugoslavia) maupun yang bersifat permanen (Statuta Roma 1998 tentang the International<br />
Criminal Court). Dalam hal ini dapat dikaji :<br />
(a) Bentuk peradilan ad hoc tersebut pada Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang berlaku <strong>untuk</strong> locus dan<br />
tempos delicti tertentu mengacu pada bentuk pengadilan internasional ad hoc, yang antara lain<br />
memungkinkan berlakunya prinsip retroaktivitas (sip. hal ini masih perlu diperdebatkan);<br />
(b) Perumusan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam<br />
Pasal 7 s/d Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sesuai dengan penjelasannya disesuaikan dengan “Rome<br />
Statute of International Criminal Court “ Pasal 6 dan Pasal 7 (genocide and crimes against humanity);<br />
(c) Beberapa norma yang diatur juga sama dengan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, seperti<br />
perkecualian yurisdiksi terhadap mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana<br />
dilakukan (exclusion of jurisdiction over persons under eighteen);<br />
(d) Perlindungan korban dan saksi serta kewajiban <strong>untuk</strong> membayar kompensasi, restitusi dan<br />
melakukan rehabilitasi terhadap korban atau ahli warisnya (sip. pelaksanaannya menunggu PP);<br />
(e) Sistem ‘individual responsibility’ yang digunakan;<br />
(f) Pengaturan tentang ‘Responsibility of commanders and other superiors’;<br />
(g) Tidak berlakunya asas daluwarsa bagi tindak pidana di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM (nonapplicability<br />
of statute of limitations).<br />
2. UU No. 26 Tahun 2000 masih mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain :<br />
(a) UU No. 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis<br />
tindak pidana (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) yang diatur dalam UU No. 26<br />
Tahun 2000 dengan Statuta Roma (genocide and crimes against humanity). Hal ini disebabkan karena<br />
UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur sekaligus tentang penyesuaian unsur-unsur tindak pidana<br />
(Elements of Crimes) yang sesuai dengan Art. 9 Statuta Roma, diharapkan dapat membantu<br />
Pengadilan <strong>untuk</strong> menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana di atas;<br />
(b) UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur ketentuan yang sangat penting bagi pelaksanan proses<br />
peradilan yang merdeka dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Art. 70 dan Art. 71 yang<br />
mengatur ‘Offenses against the administration of justice’ dan ‘Sanctions for misconduct before the court’;<br />
(c) Sekalipun di dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan<br />
lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara <strong>pelanggaran</strong> HAM yang berat dilakukan<br />
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, namun mengingat kekhususannya sebagai<br />
‘extraordinary crimes’, dalam hal-hal tertentu perlu antisipasi pengaturan hukum acara khusus. Hal<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 8
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
ini sesuai dengan Art. 51 Statuta Roma yang menegaskan pentingnya ‘Rules of procedure and<br />
Evidence’ yang merupakan instrumen <strong>untuk</strong> menerapkan Statuta;<br />
(d) Pengaturan tentang perlindungan korban dan saksi serta kompensasi, restitusi dan proses<br />
rehabilitasinya. Hal ini sangat penting karena seringkali berkaitan dengan hukum acara (misalnya<br />
saja kemungkinan dilakukannya ‘in camera proceedings’ atau presentasi, pembuktian melalui sarana<br />
elektronik).<br />
3. Pengadilan HAM (baik yang bersifat ad hoc maupun permanen) mempunyai semangat (spirit) yang<br />
sama, baik yang bersifat umum (general spirit) maupun yang bersifat khusus (specific spirit). Secara<br />
umum keberadaan pengadilan HAM tersebut berusaha mengamankan penghormatan terhadap HAM<br />
dan kebebasan dasar (human rights and fundamental freedom); sedangkan secara khusus keberadaan<br />
pengadilan HAM mengandung pelbagai semangat sebagai berikut :<br />
(a) Berupaya <strong>untuk</strong> menciptakan keadilan bagi semuanya (to achieve justice for all);<br />
(b) Mengakhiri praktek ‘impunity’, yaitu sikap mengabaikan tanpa memberi hukuman bagi para<br />
pelanggar HAM berat tanpa perkecualian. Di sinilah urgensi berlakunya ’the principle of individual<br />
criminal responsibility/accountability’;<br />
(c) Untuk membantu mengakhiri konflik yang terjadi sebagai awal mula kekerasan dan kekejaman;<br />
(d) Khusus pengadilan HAM permanen (bukan yang bersifat ad hoc) bertujuan <strong>untuk</strong> memperbaiki<br />
kekurangan atau kelemahan (deficiencies) dari pengadilan ad hoc, yang mencerminkan terjadinya<br />
‘selective justice’;<br />
(e) Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa datang.<br />
4. Bagi Indonesia mendemonstrasikan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2000 secara sungguh-sungguh<br />
(genuinely) sangat penting <strong>untuk</strong> membuktikan pada dunia luar (PBB), bahwa kita berkehendak (willing)<br />
dan mampu (able) <strong>mengadili</strong> <strong>pelanggaran</strong> HAM berat yang terjadi. Tidak mustahil Dewan Keamanan<br />
PBB membentuk Tribunal internasional ad hoc nantinya bilamana :<br />
(a) Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan <strong>untuk</strong> melindungi<br />
(shielding) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana;<br />
(b) Terjadi keterlambatan proses pengadilan yang alasannya tidak dapat dibenarkan (unjustified delay);<br />
(c) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (independently) dan tidak memihak (impartially).<br />
Inilah yang dinamakan pengadilan pura-pura (s<strong>ham</strong> proceeding) yang bahkan dapat<br />
mengesampingkan asas ‘ne bis in idem’. Dalam pelbagai Statuta Tribunal Internasional ad hoc bahkan<br />
ada ketentuan bahwa Tribunal Internasional dapat <strong>mengadili</strong> kembali, bilamana pengadilan<br />
nasional <strong>mengadili</strong> si pelaku atas dasar kejahatan biasa (ordinary crimes). Apabila butir a, b, c<br />
tersebut merupakan parameter <strong>untuk</strong> menentukan ‘unwllingness’ maka ukuran ’inability’ dalam<br />
kasus-kasus tertentu terjadi apabila pengadilan mempertimbangkan bahwa telah terjadi kegagalan<br />
secara menyeluruh atau substansial atau ketidaksediaan sistem pengadilan nasional <strong>untuk</strong><br />
menemukan tersangka atau bukti-bukti atau sama sekali tidak mampu <strong>untuk</strong> menyelenggarakan<br />
proses peradilan (collapsed). Kedudukan pengadilan internasional jelas lebih tinggi daripada<br />
pengadilan nasional. Pengadilan (Tribunal ad hoc menggunakan istilah “primacy”, sedangkan ICC<br />
menggunakan istilah yang lebih sopan yaitu ‘complementary’. Sebenarnya dalam hal ini ‘the national<br />
courts have primary jurusdiction to try the accused’.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 9
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
5. Dalam hal berlakunya asas retroaktif yang dianggap bertentangan dengan asas legalitas (nullum<br />
delictum nulla poena sine lege) merupakan hal yang ‘debatable’. Alasan yang tertera dalam Penjelasan<br />
Umum UU No. 26 Tahun 2000 atas dasar Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 (“Dalam menjalankan hak dan<br />
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang<br />
dengan semata-mata <strong>untuk</strong> menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang<br />
lain dan <strong>untuk</strong> memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,<br />
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”), tidak sepenuhnya tepat, sebab<br />
perkecualian yang nampaknya didasarkan atas Pasal 29 Piagam HAM PBB tersebut hanya berlaku<br />
<strong>untuk</strong> ‘derogable rights’. Padahal hak <strong>untuk</strong> tidak diadili dengan peraturan yang berlaku surut adalah<br />
‘non-derogable rights’. Atas dasar ‘international customary law’, alasan yang dapat digunakan adalah :<br />
(a) Atas dasar ‘the principle of justice’. Artinya ‘impunity’ terhadap pelaku <strong>pelanggaran</strong> HAM berat akan<br />
dirasakan lebih tidak adil dibandingkan dengan tidak menerapkan asas legalitas, yang juga<br />
ditujukan <strong>untuk</strong> menciptakan kepastian hukum dan keadilan; dan<br />
(b) Dalam hal ini tidak ada persoalan asas legalitas, sebab tidak ada perundang-undangan yang baru.<br />
Yang terjadi adalah penerapan hukum kebiasaan internasional (international customary law) dalam<br />
peradilan ad hoc dengan locus dan tempos delicti tertentu yang sudah dikenal dalam praktek hukum<br />
internasional (Nuremberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia). Dalam hal ini berlaku asas ‘nullum delictum<br />
nulla poena sine iure’.<br />
6. Pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) disebut sebagai ‘extraordinary crimes’ sebab<br />
perbuatan yang keji dan kejam tersebut dapat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock<br />
the conscience of humanity) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (a threat to<br />
international peace and security). Apalagi bilamana dilakukan secara ‘sistematic or widespread” and<br />
‘flagrant’. Di dalam Art. 1 Statuta Roma kejahatan tersebut dinamakan ‘the most serious crimes of<br />
international concern’, yang penanganannya membutuhkan bantuan internasional.<br />
7. Beberapa catatan tambahan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) :<br />
(a) Kejahatan terhadap kemanusiaan sudah bersifat ‘sui generis’/autonomous/self-contained category/new<br />
category of crime’, dalam arti tidak ada kaitannya dengan kejahatan perang (war crimes). Pengaturan<br />
ICC merupakan puncak dari perkembangan hukum kebiasaan internasional (customary international<br />
law);<br />
(b) Dalam perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebelum kata<br />
’penduduk sipil’ (civilian population) ada kata “any” (any civilian population). Hal ini mengandung arti<br />
bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan terhadap mereka yang mempunyai<br />
nasionalitas seperti pelaku atau mereka yang ‘stateless’ atau mereka yang mempunyai nasionalitas<br />
berbeda. Pengertian ‘civilian’ harus diartikan luas termasuk pasien di rumah sakit baik orang sipil<br />
atau pejuang yang telah meletakkan senjata;<br />
(c) Sekalipun istilah ‘population’ menunjuk pada kejahatan kolektif (crime in collective nature) dan<br />
mengecualikan apa yang disebut ‘single or isolated or random acts’, namun seorang individu yang<br />
melakukan suatu kejahatan dengan korban tunggal (single victim) dapat dipersalahkan melakukan<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan apabila perbuatannya merupakan bagian dari ‘cruel and barbarous<br />
political system‘ atau apabila perbuatan tersebut ‘is the product of a political system based on terror or<br />
persecution’. Istilah ‘widepread’ menunjuk pada sejumlah korban sedangkan ‘systematic’<br />
mengindikasikan adanya bentuk rencana yang terpola atau metodis dan jelas (a pattern or<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
methodical plan is evident). Sistematik mengandung arti juga sebagai perbuatan yang merupakan<br />
kelanjutan dari sebuah rencana atau kebijakan yang dipertimbangkan sebelumnya (preconceived).<br />
Dan seringkali juga ‘organized’. Jadi bukan perbuatan ‘random’, tetapi perbuatan yang bisa<br />
menghasilkan perbuatan berlanjut atau ulangan. Selanjutnya istilah ‘widespread’ atau ‘large scale’<br />
mengandung arti bahwa perbuatan tersebut ditujukan ke arah sejumlah korban yang banyak (a<br />
multiplicity of victims). Jadi bukan ‘isolated act’ karena kemauan sendiri pelaku dengan satu korban.<br />
‘Policy‘ tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat disimpulkan di lapangan. Policy bisa<br />
dari negara yang pelaksanaannya harus melalui lembaga, personil, sumber-sumber daya negara,<br />
tetapi bisa juga ‘policy’ dari ‘non-state actors’ berupa entitas yang de facto menguasai suatu wilayah<br />
atau kelompok teroris atau organisasi;<br />
(d) Di samping perlindungan terhadap korban dan saksi, perlu diperhatikan pula perlindungan<br />
terhadap tersangka dan terdakwa (rights of persons during investigation and rights of the accused);<br />
(e) Apabila berkenaan dengan ‘Applicable Law’ ICC di samping menggunakan Statuta Roma beserta<br />
Elements of Crime dan Rule of Procedure and Evidence dapat juga menggunakan traktat dan ‘principles<br />
and rules of international law’ dan hukum nasional, maka tidak mustahil Pengadilan HAM juga<br />
memperhatikan sumber-sumber hukum internasional.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 11
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
1. Pengantar<br />
Bagian Ketiga<br />
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN<br />
Perkembangan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan sangat menarik <strong>untuk</strong> diikuti. Hal ini sangat<br />
relevan dalam rangka implementasi UU No. 20 Tahun 2000, karena dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan<br />
bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome<br />
Statute of International Criminal Court”. Dengan demikian pelbagai logika dan spirit hukum dan perundangundangan<br />
yang terkait atas dasar Statuta Roma harus dipa<strong>ham</strong>i.<br />
Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) pertama kali digunakan pada tahun 1915<br />
pada saat terjadi kasus “massacres of Turkey’s Armenian population”. Tuntutan atas dasar genosida gagal<br />
dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat “retroactive criminal legislation”.<br />
Istilah ini muncul kembali pada tahun 1945 sebagai salah satu kategori kejahatan yang berada di bawah<br />
yurisdiksi Tribunal Nuremberg (di samping ‘war crimes’ dan ‘crimes against peace’). Sekalipun penentangan<br />
atas dasar larangan retroaktivitas muncul kembali, tetapi Tribunal Nuremberg berhasil meredamnya atas<br />
dasar “the principle of justice” dalam rangka <strong>mengadili</strong> penjahat perang Nazi.<br />
Hanya saja muncul pema<strong>ham</strong>an bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan<br />
mensyaratkan (nexus) hubungan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan perang (war crimes).<br />
Bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap merupakan kembar siam (Siamese twin) dari kejahatan<br />
perang.<br />
Hal ini bisa terjadi karena Tribunal Nuremberg merupakan “war crimes trials”. Pendekatan ini sangat<br />
membatasi proses pemidanaan terhadap <strong>pelanggaran</strong> HAM berat, sebab dalam kenyataannya kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan dapat dilakukan di masa damai (committed during peacetime).<br />
Setelah itu Sidang Umum PBB berusaha merumuskan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan<br />
yang berat dan keji seperti genosida sebagai kejahatan mandiri yang dapat dilakukan baik di masa damai<br />
atau perang atas dasar hukum kebiasaan internasional (international customary law).<br />
2. Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan<br />
Secara umum unsur-unsur kejahatan mencakup unsur obyektif (criminal act, actus reus) berupa adanya<br />
perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya<br />
alasan pembenar, dan unsur subyektif (criminal responsibility, mens rea) yang mencakup unsur kesalahan<br />
dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan<br />
serta tidak adanya alasan pemaaf.<br />
Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lain terdapat prinsip<br />
umum bahwa unsur-unsur kejahatan (the elements of crime) terdiri atas :<br />
(1) Unsur material yang berfokus pada perbuatan (conduct), akibat (consequences) dan keadaan-keadaan<br />
(circumstances) yang menyertai perbuatan;<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
(2) Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (intent), pengetahuan (knowledge) atau keduanya.<br />
Sesuai dengan Art. 30 yang mengatur “mental element”, maka ada kesengajaan (intent) apabila<br />
sehubungan dengan perbuatan (conduct) tersebut si pelaku berniat <strong>untuk</strong> melakukan/turut serta dalam<br />
perbuatan tersebut dan berkaitan dengan akibatnya (consequences), si pelaku berniat <strong>untuk</strong><br />
menimbulkan akibat tersebut atau sadar (aware) bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam<br />
kaitannya dengan perbuatan tersebut. Sedangkan “knowledge” diartikan sebagai kesadaran (awareness)<br />
bahwa suatu keadaan terjadi atau akibat pada umumnya akan timbul sebagai akibat kejadian<br />
tersebut. Tahu (know) dan mengetahui (knowingly) harus ditafsirkan dalam kerangka tersebut.<br />
Yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan kemanusiaan adalah dua elemen terakhir dari<br />
setiap kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggambarkan konteks dalam hal mana perbuatan terjadi.<br />
Dua elemen tersebut adalah :<br />
(a) Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread) dan<br />
sistematik (systematic) ditujukan pada penduduk sipil; dan<br />
(b) Keharusan adanya pengetahuan (with knowledge) pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan<br />
bagian dari atau dimaksudkan <strong>untuk</strong> menjadi bagian serangan yang meluas atau sistematik terhadap<br />
penduduk sipil.<br />
Catatan : Kata “systematic” berasal dari suku kata “system”, definisi kerja (working definition). Sistem selalu<br />
mengandung konotasi sebagai berikut :<br />
(1) Purposive behavior - the system is objective oriented;<br />
(2) Wholism - the whole is more than the sum of all the parts;<br />
(3) Openness - the system interacts with a larger system, namely its environment;<br />
(4) Transformation - the working of the parts creates something of value;<br />
(5) Interrelatedness - the various parts must fit together;<br />
(6) Control mechanism - there is a unifying force that holds the system together.<br />
3. Hal-hal yang Harus Dicermati<br />
Eliminasi secara tegas hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan konflik bersenjata (armed<br />
conflict) dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB pada saat merumuskan Statuta Tribunal Internasional <strong>untuk</strong><br />
Rwanda (ICTR) dan selanjutnya diakui pula oleh Majelis Banding dari International Criminal Tribunal for<br />
Former Yugoslavia (ICTY) dalam suatu kasus (Tadic jurisdictional decision).<br />
Perkembangan ini dilembagakan oleh Statuta Roma 1998. Art. 7 diawali dengan paragraf yang menyatakan<br />
“For the purpose of this Statute, “crimes against humanity” means any of the following act when committed as part of<br />
a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with the knowledge of the attack”.<br />
Pengertian “attack” tersurat dan tersirat pada Art. 7. 2 (a) yang menyatakan bahwa “the term of attack is<br />
defined as ‘a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any<br />
civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack’.” Dengan<br />
demikian secara implisit dapat disimpulkan bahwa serangan tersebut tidak memerlukan karakter sebagai<br />
suatu serangan militer (military attack). Selanjutnya dari kata ‘organizational policy’ dapat disimpulkan pula<br />
bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan oleh “non-state actors”.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 13
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Selanjutnya adanya persyaratan bagi pelaku yang harus memiliki “knowledge of the attack”, harus diartikan<br />
sebagai kesengajaan khusus (specific intent). Misalnya, seseorang yang turut serta melakukan kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (murder), tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan<br />
bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread) atau sistematis (systematic) terhadap penduduk sipil<br />
dapat dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan, tetapi tidak dalam kerangka kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan. Tetapi perlu pula ditegaskan di sini bahwa <strong>untuk</strong> dapat dipidana karena melakukan<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak disyaratkan bahwa si pelaku (perpetrator) telah mengetahui seluruh<br />
karakteristik dari serangan atau rincian pasti (precise details) dari perencanaan atau ‘policy’ dari negara atau<br />
organisasi tersebut.<br />
Persyaratan yang berkaitan dengan alasan/sebab (‘motive’) kejahatan, sekalipun tidak tercantum dalam<br />
definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini tetap relevan sebagai indikator kesalahan (indicator of<br />
guilt), di samping <strong>untuk</strong> menentukan sanksi pidana yang tepat atau proporsional.<br />
Catatan : Pada Art. 7. 1 (h) kejahatan penganiayaan (‘persecution’) terhadap suatu kelompok tertentu atau<br />
perkumpulan, dicantumkan motif berupa perbedaan pa<strong>ham</strong> politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,<br />
jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum<br />
internasional.<br />
Jenis-jenis kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan terus meningkat dan<br />
berkembang mulai dari Tribunal Nuremberg sampai dengan 11 kejahatan sebagaimana diatur dalam<br />
Statuta Roma 1998. Hal yang cukup menarik adalah jenis kejahatan yang dirumuskan secara terbuka pada<br />
Art.7. 1 (k), yakni “other inhuman acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury<br />
to body or to mental or physical health”. Kiranya hal ini memerlukan kejelasan lebih lanjut demi kepastian<br />
hukum (dalam kerangka ‘lex certa’ principle).<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 14
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Bagian Keempat<br />
GENOCIDE<br />
Istilah “genocide” diciptakan pada tahun 1944 oleh Raphael Lewkin dalam bukunya tentang Kejahatan Nazi<br />
selama pendudukan di Eropa yang berjudul “Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of<br />
Government, Proposals for Redress”. Dia berpendapat bahwa perjanjian internasional yang selama dua perang<br />
dunia yang ditujukan <strong>untuk</strong> melindungi minoritas dalam kehidupan nasional mempunyai kelemahan,<br />
antara lain kegagalan <strong>untuk</strong> menuntut kejahatan terhadap kelompok (crimes against groups).<br />
Istilah “genocide” diterima setelah beberapa tahun oleh jaksa (bukan hakim) di Nuremberg, dan pada tahun<br />
1946 dinyatakan sebagai kejahatan internasional (international crime) oleh Sidang Umum PBB. Bahkan oleh<br />
MU diputuskan <strong>untuk</strong> diproses sebagai rancangan traktat tentang Genosida. Pada saat itu dipertimbangkan<br />
<strong>untuk</strong> mendefinisikan genosida sebagai kejahatan yang terpisah dan berbeda dari kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan (crimes against humanity). Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kekejaman (atrocities)<br />
yang mempunyai jangkauan yang lebih luas, di samping keterbatasannya yang harus terkait dengan konflik<br />
bersenjata internasional (catatan : perkembangan kemudian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan pada akhirnya juga menjadi delik yang berdiri sendiri terlepas dari kejahatan perang atau<br />
“delictum sui generis”).<br />
Apa yang akan ditonjolkan oleh MU PBB adalah bahwa genosida merupakan kekejaman yang dapat pula<br />
terjadi di masa damai. Akan nampak kemudian bahwa usaha membedakan ini justru akan membatasi<br />
unsur-unsur delik baik yang bersifat unsur mental maupun unsur material. Hal ini akan terlihat dalam<br />
“Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, 9 Desember 1948, yang sering disebut<br />
sebagai inti dari pelbagai traktat tentang HAM (quintessential human rights treaty).<br />
Saat ini perbedaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak begitu penting sebab definisi<br />
tentang kejahatan terhadap kemanusiaan terus berkembang dan pada akhirnya juga mencakup segala<br />
kekejaman yang dapat dilakukan baik di masa damai atau masa perang. Genosida dipandang sebagai<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempunyai unsur pemberatan (aggravated). Tribunal Internasional<br />
<strong>untuk</strong> Rwanda menyebutnya sebagai “the crime of crimes”. Tidak mengherankan apabila hal ini<br />
mengakibatkan disebutnya “the crime of genocide” sebagai kejahatan pertama dalam Statuta Roma yang<br />
menjadi jurisdiksi ICC (International Criminal Court) tanpa adanya kontroversi. Perumusan ini sebenarnya<br />
mengambil dari Article II Konvensi tahun 1948.<br />
Article 6 dari Statuta Roma tentang ICC dan Article II Genocide Convention 1948 mendefinisikan “genocide”<br />
sebagai 5 (lima) perbuatan tertentu atau khusus (specific acts) yang dilakukan dengan maksud <strong>untuk</strong><br />
memusnahkan (intent to destroy) suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau agama. Lima perbuatan<br />
tersebut adalah :<br />
- Pembunuhan anggota-anggota kelompok;<br />
- Mengakibatkan penderitaan berat baik terhadap badan atau mental;<br />
- Menerapkan kondisi terhadap kelompok yang diperkirakan dapat memusnahkan kelompok;<br />
- Mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan<br />
- Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 15
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Seringkali dikatakan bahwa perbedaan antara genosida dan kejahatan-kejahatan lain adalah apa yang<br />
dikategorikan sebagai “dolus specialis” atau kesengajaan khusus (special intent).<br />
(Catatan : 3 kejahatan yang dirumuskan dalam Statuta Roma mengandung perbuatan pembunuhan (killing<br />
or murder)).<br />
Apa yang memisahkan antara genosida dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (war<br />
crimes) adalah bahwa genosida harus dilakukan dengan kesengajaan khusus (specific intent) <strong>untuk</strong><br />
memusnahkan seluruhnya atau sebagian kelompok di atas.<br />
Kesengajaan khusus ini mempunyai beberapa komponen. Pelaku harus bertujuan <strong>untuk</strong> memusnahkan<br />
kelompok tersebut. Dalam perdebatan yang terjadi sebelum Genocide Convention diadopsi, jenis<br />
pemusnahan diindikasikan mengandung 3 kategori kemungkinan : fisik, biologis dan kultural. Genosida<br />
kultural merupakan hal yang tersulit di antara ketiga kategori, sebab dapat diinterpretasikan meliputi pula<br />
penindasan (suppression) terhadap bahasa nasional atau ukuran yang lain.<br />
Hal ini akhirnya dikeluarkan dari konvensi. Namun demikian pelbagai saran mengusulkan agar saat ini<br />
ketiga bentuk pemusnahan (fisik, biologis dan kultural) tersebut bisa diterima sebagai konstruksi progresif.<br />
Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa genosida kultural (cultural genocide) terbukti merupakan indikator<br />
penting dari “physical genocide”.<br />
Definisi genosida tidak memuat secara formal persyaratan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan<br />
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik atau sebagai bagian dari perencanaan yang umum atau<br />
terorganisasi <strong>untuk</strong> memusnahkan kelompok sebagaimana ditentukan bagi kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan. Namun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan karakteristik tersirat (implicit characteristic)<br />
dari kejahatan genosida. Walaupun demikian harus diakui adanya praktek yang dinamakan “lone genocidal<br />
maniac” (Jelesic Case, Former Yugoslavia).<br />
Dokumen tentang elemen Kejahatan ICC mensyaratkan bahwa perbuatan genosida terjadi dalam konteks<br />
sebuah bentuk nyata atau “manifest pattern” dari perbuatan yang serupa ditujukan terhadap kelompok<br />
atau merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan pemusnahan. Kata-kata seluruhnya atau sebagian<br />
mengindikasikan dimensi kuantitatif yang signifikan. Kesengajaan <strong>untuk</strong> membunuh hanya sedikit anggota<br />
kelompok bukan merupakan genosida. “Part”, it must be “substantial part”. Tetapi sekali lagi harus dicatat<br />
bahwa yang penting adalah bukan jumlah aktual dari korban, tetapi kesengajaan dari pelaku <strong>untuk</strong><br />
memusnahkan sejumlah besar anggota kelompok. Semakin besar korban semakin logis kesimpulan tentang<br />
adanya kesengajaan <strong>untuk</strong> melakukan pemusnahan tersebut (seluruhnya atau sebagian).<br />
Ukuran kelompok atas dasar ikatan politik dan sosial ditolak pada tahun 1948, begitu pula dalam ICC,<br />
sebab keempat kategori kelompok tersebut pada kejahatan genosida mengacu pada minoritas etnis dan<br />
nasional sebagaimana diatur dalam hukum atau dokumen HAM yang juga terkesan menghindari definisi<br />
yang tepat. Kata-kata “as such” merupakan kompromi bahwa di samping “intentional element” terdapat juga<br />
“motive”. Motif antara lain bisa berupa kecemburuan, kebencian atau kerakusan. Hal ini sebenarnya<br />
mempersulit pembuktian, sehingga banyak ditolak adanya penafsiran definisi.<br />
Unsur “mens rea” (mental element) bersifat membatasi 5 perbuatan tersebut di atas, sehingga perbuatan<br />
yang saat ini dikenal sebagai “ethnic cleansing” cenderung dipidana atas dasar kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 16
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Pembunuhan (killing) merupakan inti dari definisi dan perbuatan terpenting genosida. Hal ini sinonim<br />
dengan “murder” atau “homicide” atau menyebabkan kematian. Selanjutnya mengenai jenis genosida kedua<br />
(mengakibatkan penderitaan berat baik terhadap badan atau mental, contohnya adalah perkosaan dan<br />
penyiksaan , kekerasan seksual atau perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang<br />
lain. Jenis ketiga contohnya adalah menyuruh pergi dengan paksa (force marches) orang-orang Armenia di<br />
Turki pada tahun 1915. Khusus mengenai bentuk kelima terdapat syarat bahwa anak-anak yang<br />
dipindahkan atau ditransfer berumur di bawah 18 tahun dan si pelaku tahu atau seharusnya harus tahu<br />
bahwa yang bersangkutan berusia di bawah 18 tahun.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 17
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Bagian Kelima<br />
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN<br />
(CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMMANDERS)<br />
1. Pendahuluan<br />
Pertanggungjawaban komando saat ini sangat relevan <strong>untuk</strong> dibahas karena hal-hal sebagai berikut :<br />
a. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan nonmiliter<br />
yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (other superiors), terhadap <strong>pelanggaran</strong> HAM berat<br />
yang dilakukan bawahannya (subordinates);<br />
b. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga<br />
bisa terjadi di masa damai;<br />
c. Di lingkungan militer, pertanggungjawaban komando berkaitan dengan “sacred trust”, yang<br />
mengandung baik tanggung jawab juridis maupun tanggung jawab moral yang tidak ada<br />
bandingannya dengan posisi pimpinan lainnya;<br />
d. Apabila pertanggungan jawab komando yang bersifat langsung (direct command responsibility) yang<br />
berlaku umum telah diatur dalam hukum pidana dalam kerangka Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP<br />
(penyertaan tindak pidana), maka konsep pertanggungjawaban komando yang tidak langsung (indirect<br />
command responsibility) dalam bentuk “participation by omission” yang berlaku secara khusus dalam<br />
<strong>pelanggaran</strong> HAM yang berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang bersumber dari<br />
hukum kebiasaan internasional ternyata telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang<br />
bersifat umum, apabila yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum <strong>untuk</strong> berbuat;<br />
e. Bagi Indonesia persoalan pertanggungjawaban komando dalam kerangka “individual responsibility”<br />
sangat penting sehubungan dicantumkannya lembaga hukum ini dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000<br />
tentang Pengadilan HAM, yang mengadopsi perumusan Article 28 Statuta Roma Tahun 1998 dan<br />
berlaku dalam kerangka kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi<br />
jurisdiksi Pengadilan HAM;<br />
Diskusi tentang doktrin pertanggungjawaban komando (the doctrine of command responsibility or superior<br />
responsibility rule), khususnya dalam hukum pidana akan selalu menarik, mengingat perkembangannya<br />
yang penuh perdebatan dalam hukum internasional maupun polemik yang berkembang dalam hukum<br />
nasional. Sekalipun maknanya tidak sesederhana sebagai “military commanders are responsible for the acts of<br />
their subordinates”, sebenarnya hal ini bukan sebagai suatu hal yang baru. Pada kira-kira tahun 500 BC, Sun<br />
Tzu menulis dalam “The Art of War” bahwa :<br />
“When troops flee, are insubordinate, distressed, collapse in disorder, or are routed, it is the fault of the<br />
general. None of these disorders can be attributed to natural causes.”<br />
Napoleon Bonaparte menegaskan dalam hal ini dengan mengatakan bahwa : ”There are no bad regiments; they<br />
are only bad colonels”. Begitu pula King Charles VII of Orleans yang mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa<br />
komandan militer dapat dipertanggungjawabkan, bilamana di dalam komandonya telah terjadi kejahatan<br />
terhadap penduduk sipil, tidak peduli apakah komandan militer tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan<br />
kejahatan.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 18
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Hugo Grotius dalam bukunya yang legendaries “De Jure Belli Ac Pacis” (1615) menegaskan eksistensi doktrin<br />
tersebut. Beliau menyatakan : “We must accept the principle that he who knows of a crime, and is able and bound to<br />
prevent it and fails to do so, himself commits a crime”. Dalam periode yang sama (1621) King Gustavus Adolphus<br />
dari Swedia mengumumkan “Articles of Military Lawwes to be Observed in the Warres”. Di situ beliau<br />
menyatakan bahwa “No Colonel or Captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does,<br />
shall be punished according to the discretion of the Judges...”.<br />
Di Amerika Serikat, “The Article of War” yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1775 mengatur bahwa :<br />
“Every Officer commanding, in quarters, or in a march, shall keep good order, and to the utmost of his<br />
power, redress all such abuses or disorders which may be committed by any Officer or Soldiers under<br />
his command; if upon complaint made to him of Officers or Soldiers beating or otherwise ill-treating<br />
any person, or committing any kind of riots to the disquieting of the inhabitants of this continent, he, the<br />
said commander, who shall refuse or omit to see Justice done to this offender or offenders, and<br />
reparation made to the party or parties injured, as soon as the offender’s wages shall enable him or<br />
them, upon due proof thereof, be punished, as ordered by General Court Martial, in such manner as if<br />
he himself had committed the crimes or disorders complained of”.<br />
Pada tahun 1863, Amerika Serikat mengumumkan “The Instructions for Government of Armies of the US in the<br />
Field” yang kemudian terkenal sebagai “Lieber Code”. Prof. Albert Lieber adalah seorang Profesor dari<br />
Columbia University yang berperan menyusun ketentuan tersebut. Art. 71 menegaskan :<br />
“Whoever intentionally inflicts additional wounds on an enemy already wholly disabled, or kills such<br />
an enemy, or who orders or encourages soldiers to do so, shall suffer death, if duly convicted, whether<br />
he belongs to the Army of the US, or in an enemy captured after having committed his misdeed.”<br />
Pada akhir abad ke-19 (1895), dalam tulisannya “Military Law and Precedents”, Winthrop menulis :<br />
“It is indeed the chief duty of the commander of the army of occupation to maintain order and the<br />
public safety, as far as practicable without oppression of the population, and as if the district were a part<br />
of the domain of his own nation. All officers or soldiers offending against the rule of immunity of noncombatans<br />
or private persons in war forfeit their right to be treated as belligerents, and together with<br />
civilians similarly offending, become liable to the severest penalties as violators of the laws of war”.<br />
Dalam hukum internasional yang bersifat konvensional yang mengatur perilaku konflik bersenjata, Art. 1<br />
dari Konvensi Den Haag 1907 (mengatur tentang alat dan cara berperang) yang kemudian diatur pula<br />
dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Additional 1977 (mengatur tentang perlindungan terhadap<br />
korban perang), dirumuskan kondisi dalam hal mana kombatan harus menghormati hak-hak hukum dari<br />
negara yang berperang. Ditentukan pula syarat adanya tentara yang “commanded by a person responsible for<br />
his subordinates”. Persyaratan ini menegaskan tanggung jawab komando secara terperinci. Hal semacam ini<br />
juga muncul dalam laporan “Commission of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties” (1919)<br />
setelah PD I, Treaty of Versaiiles dan sebagainya.<br />
Masalah tanggung jawab komando menjadi sangat aktual seusai PD II dengan diadilinya para penjahat<br />
Perang Dunia II melalui Pengadilan Militer Internasional seperti di Nuremberg (IMT) maupun di Timur<br />
Jauh (IMTFE) yang antara lain <strong>mengadili</strong> Jendral Tomoyuki Yamashita, di samping pengadilan pelbagai<br />
negara atas dasar Control Council Law No. 10 yang <strong>mengadili</strong> para penjahat perang seperti di Canada, Israel,<br />
Amerika Serikat, Perancis dan sebagainya, yang banyak mengembangkan hukum kebiasaan internasional.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 19
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Masalah “command responsibility” menjadi menghangat kembali (burning issue) sehubungan dengan<br />
pengaturannya dalam “Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda” (1994) dan “Statute of the<br />
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” (1993) serta “Rome Statute of the International Criminal<br />
Court” (1998).<br />
Dalam kerangka pengaturan tentang “Individual Criminal Responsibility” Art. 7 Statuta ICTY menegaskan :<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the<br />
planning, preparation or execution of a crime referred to in the art. 2 to 5 of the present Statute, shall<br />
be individually responsible for the crime.<br />
The official position of any accused person, whether as Head of State or Government official, shall not<br />
relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.<br />
The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a<br />
subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know<br />
that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the<br />
necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.<br />
The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of superior shall not<br />
relieve him of criminal responsibility but may be considered in mitigation of punishment if the<br />
International Tribunal determines that justice requires.<br />
Hal yang sama juga diatur dalam Art. 6 ICTR.<br />
Hal yang lebih lengkap dan agak berbeda dengan dua Statuta di atas tersurat dan tersirat dalam Article 28<br />
Statuta Roma tentang International Criminal Court. Art. 28 tersebut menentukan sebagai berikut :<br />
a. A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally<br />
responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her<br />
effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or<br />
her failure to exercise control properly over such forces, where :<br />
(i)<br />
(ii)<br />
That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time,<br />
should have known that the forces are committing or about to commit such crimes; and<br />
That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within<br />
his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent<br />
authorities for investigation and prosecution.<br />
b. With respect to superior and subordinate relationship not described in paragraph (a), a superior shall be<br />
criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under<br />
his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly<br />
over such subordinate, where :<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that<br />
the subordinates were committing or about to commit such crimes;<br />
The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the<br />
superior; and<br />
The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to<br />
prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for<br />
investigation and prosecution. “<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 20
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Catatan : Kejahatan yang berada di bawah jurisdiksi ICC adalah : “the crime of genocide, crimes<br />
against humanity, war crimes, and the crime of aggression”.<br />
Ketentuan tersebut diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 42<br />
dinyatakan bahwa :<br />
a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat<br />
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM,<br />
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau<br />
berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan<br />
akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :<br />
b. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya<br />
mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan <strong>pelanggaran</strong> hak<br />
asasi manusia yang berat; dan<br />
c. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam<br />
ruang lingkup kekuasaannya <strong>untuk</strong> mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau<br />
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang <strong>untuk</strong> dilakukan penyelidikan, penyidikan,<br />
dan penuntutan.<br />
d. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap<br />
<strong>pelanggaran</strong> hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah<br />
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian<br />
terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :<br />
e. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan<br />
bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan <strong>pelanggaran</strong> hak asasi manusia yang<br />
berat; dan<br />
f. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup<br />
kewenangannya <strong>untuk</strong> mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya<br />
kepada pejabat yang berwenang <strong>untuk</strong> dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<br />
Dalam hal ini dapat diidentifikasikan beberapa elemen utama dari pertanggungjawaban komando yaitu :<br />
(1) Adanya hubungan antara bawahan-atasan;<br />
(2) Atasan mengetahui atau beralasan <strong>untuk</strong> mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang<br />
dilakukan kejahatan; dan<br />
(3) Atasan gagal <strong>untuk</strong> mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan <strong>untuk</strong> mencegah atau<br />
menghentikan tindak pidana atau berupaya <strong>untuk</strong> menghukum pelaku. Hubungan atasan-bawahan<br />
bisa de jure, de facto atau kombinasi antara keduanya.<br />
Jendral Arne Willy Dahl (Hakim dari Norwegia) (2001) memberikan basis filosofi dari tanggungjawab<br />
komandan, bahwa kagagalan komandan <strong>untuk</strong> mengendalikan anak buahnya berkaitan erat dengan nama<br />
baik dan reputasi serta kehormatan pasukannya atau bahkan dari negaranya serta berkaitan dengan<br />
keprihatinan mendalam dari semua orang yang memiliki kehendak baik.<br />
Hal ini juga berkaitan erat dengan kodrat organisasi militer sendiri yang membedakan antara kesatuan<br />
militer yang sah dan sekumpulan individu dalam bentuk pasukan liar atau gerilyawan (franc-tireurs).<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 21
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Di dalam “The US Army Field Manual” antara lain disebutkan bahwa : “Command is a specific and legal position<br />
unique to the military. It is where the buck stops... Command is a sacred trust. The legal and moral responsibilities of<br />
commanders exceed those of any other leader of similar position and authority”.<br />
2. Karakter Juridis<br />
Doktrin bahwa para komandan militer dan orang-orang lain yang menduduki posisi dan kewenangan<br />
yang lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan<br />
hukum dari anak buahnya sudah dimantapkan dalam norma hukum kebiasaan dan perjanjian hukum<br />
internasional.<br />
Melihat pelbagai perumusan di atas nampak bahwa, pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari<br />
“actus reus”, baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai<br />
“direct command responsibility”) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (“culpable omissions”,<br />
“indirect command responsibility” atau “command responsibility strictu sensu”). Dengan demikian seorang<br />
komandan atau superior tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena “ordering,<br />
instigating, planning, aiding or abetting” tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena<br />
kegagalan <strong>untuk</strong> mengambil tindakan-tindakan <strong>untuk</strong> mencegah atau menghentikan atau berusaha<br />
menghukum perbuatan melawan hukum bawahan.<br />
Perbedaan antara kedua tipe pertanggungjawaban terletak pada kenyataan bahwa dalam hal perbuatan<br />
positif para komandan, hal ini mengikuti apa yang dinamakan “principles of accomplice liability” dalam<br />
kerangka teori penyertaan (complicity, deelneming), sedangkan yang kedua berkaitan dengan apa yang<br />
dinamakan “The principle responsibility for omissions” yang bisa terjadi apabila terdapat suatu kewajiban<br />
hukum <strong>untuk</strong> berbuat (legal obligation to act). Sehubungan dengan hal ini Art. 87 dari Protocol Additional to the<br />
Geneva Conventions of August 1949 menyatakan bahwa :<br />
“International law imposes an affirmative duty on superiors to prevent persons under their control from<br />
committing violations of international humanitarian law, and it is ultimately this duty that provides the<br />
basis for, and defines the contours of, the imputed criminal responsibility under Art 7 (3) of the Statute”.<br />
Doktrin modern tentang “command responsibility” boleh dikatakan berakar dari Konvensi Den Haag 1907.<br />
Baru pada tahun 1919 (Preliminary Peace Conference), “Commission on the Responsibility of the Authors of the War<br />
and on Enforcement of Penalties” merekomendasikan pembentukan suatu tribunal yang dapat menuntut dan<br />
memidana mereka yang :<br />
“Ordered, or with knowledge thereof and with power to intervene, abstained from preventing or taking<br />
measures to prevent, putting an end to or repressing violations of the laws or customs of war.”<br />
Baru setelah PD II doktrin pertanggungjawaban komando yang bersifat “culpable ommisions” (failure to act)<br />
memperoleh pengakuan dalam konteks internasional. Di Perancis (1944) masuk kategori “tolerated the<br />
criminal acts of their subordinates” dalam “The Suppression of War Crimes”. Selanjutnya Chinese Law (1946) yang<br />
mengatur “The Trial of War Criminals”, hal ini dikategorikan sebagai ”Persons who have not fulfilled their duty<br />
to prevent crimes from being committed by their subordinates shall be treated as the accomplices of such war<br />
criminals”.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 22
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Prof. Bassiouni mengidentifikasi bahwa : “failure to act depends on knowledge and opportunity to act” :<br />
(1) In the prevention of the criminal act;<br />
(2) Subsequent to the act if the superior failed to supervise, discover and take remedial action as needed<br />
under the circumstances; and<br />
(3) Prosecute and if found guilty, punish the violator.<br />
Beberapa Pedoman Konseptual dan Empiris<br />
a. The bottom-line for criminal liability is blameworthiness. Menurut Prof. Nico Keijzer, yang banyak<br />
mengkaji pandangan Grotius, dalam hal ini terdapat 3 kondisi pertanggungjawaban pidana komandan<br />
atas perbuatan bawahannya :<br />
1. Seseorang mempunyai “control” atas orang lain;<br />
2. Seseorang hanya bertanggung jawab karena tidak melakukan pencegahan kejahatan yang<br />
diketahuinya (knowledge); dan<br />
3. Seseorang tidak hanya harus tahu, tetapi juga harus mampu <strong>untuk</strong> mencegah (able to prevent);<br />
dengan demikian “military subordination is a comprehensive but not conclusive factor in fixing criminal<br />
responsibility”. Dalam perang modern, banyak langkah-langkah desentralisasi komando, sehingga<br />
kemungkinan komander tingkat tinggi tidak dapat selalu memperoleh informasi lengkap dan detail<br />
dari operasi militer. Contohnya adalah Presiden Amerika sebagai “Commander in Chief” sulit<br />
dijadikan obyek dari “theory of subordination”. Dalam hal ini harus terbukti bahwa ia mengetahui<br />
atau dapat dikaitkan dengan kejahatan baik atas dasar “participation” atau persetujuan diam-diam<br />
(criminal acquiescene); (The High Command Case); Dalam Art. 87 Protocol Additional I ada istilah<br />
“commensurate with their level of responsibility”;<br />
b. Berlakunya doktrin atau pendekatan “Strict Liability” (liability without mens rea). Hal ini muncul dalam<br />
Peradilan Yamashita, di mana jaksa sulit membuktikan bahwa Jendral Yamashita telah memerintahkan<br />
kekejaman terhadap penduduk Filipina dan para tawanan orang-orang Amerika dalam pendudukan<br />
Jepang. Namun Yamashita sebagai “Commanding General” bala tentara Jepang di Filipina sekaligus<br />
sebagai gubernur militer, harus tahu (must have known) atas terjadinya kekejaman yang meluas<br />
(widespread) dan berskala besar (enormity), seperti perkosaan, pembunuhan, pembunuhan massal,<br />
perusakan harta benda yang meluas baik dalam konteks waktu maupun wilayah. Kejadian tersebut<br />
tidak bersifat sporadis dan dalam banyak kasus justru dihadiri dan diawasi oleh perwira-perwira<br />
Jepang. Sebagai komandan seharusnya melakukan kontrol efektif, karena kondisi tertentu. Pemikiran<br />
rasional menyimpulkan telah terjadinya perencanaan sengaja; Yamashita didakwa telah melakukan<br />
“unlawfully disregarded and failed to discharge his duty as commander to control the operations of the members of<br />
his command, permitting them to commit brutal atrocities and other high crimes”;<br />
c. The commanding general of occupied territory has the duty and responsibility for maintaining peace<br />
and order, and the prevention of crime. He cannot ignore obvious facts and plead ignorance as a<br />
defence; (The High Command Case);<br />
d. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari satu kejahatan perang dari kesatuan di<br />
bawah komando dan kehadiran seorang perwira atau “non commission officer” pada saat atau sebelum<br />
kejahatan terjadi sangat menentukan pertanggungjawaban komander; Meyer dipidana karena anak<br />
buahnya telah melakukan pembunuhan terhadap tahanan (Kasus Kurt Meyer di Canadian Military Court);<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 23
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
e. Komandan tidak harus melihat sendiri terjadinya kekejaman (has actual knowledge); cukup apabila dia<br />
mengetahui bahwa bawahannya sedang dalam proses melakukan kejahatan atau telah melakukan<br />
kejahatan dan yang bersangkutan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan atau beralasan<br />
<strong>untuk</strong> menjamin ditaatinya hukum perang atau memidana para pelaku ; (Kasus My Lai /Song My). Hal<br />
ini sesuai pula dengan Art. 86 para. 2 Protocol Additional I;<br />
f. “Position of Responsibility” bisa juga berkaitan dengan “Civilian Authorities”. Dalam Rwanda ad hoc<br />
Tribunal, seorang direktur pabrik telah dituntut dan dipidana karena tidak melakukan tindakan<br />
campur tangan dan pencegahan kejahatan genosida yang dilakukan bawahannya di luar jam kerja;<br />
g. Pertanggungjawaban komando tidak hanya diterapkan terhadap “Formal Commanders”, tetapi juga<br />
terhadap orang-orang yang memperoleh suatu posisi informal dalam hal mana dia bisa menggunakan<br />
kekuasaaannya sebagai seorang komandan. Hal ini bisa terjadi dalam perang saudara (civil war). Dalam<br />
Tribunal ad hoc Former Yugoslavia, seorang yang bertindak sebagai komandan penjara (camp) di<br />
Bosnia/Herzegowina sekalipun secara formal tidak pernah ditunjuk dalam jabatan tersebut, tetapi de<br />
facto dia adalah komandan (de facto commander), yang tidak melakukan pencegahan pembunuhanpembunuhan<br />
dan penyiksaan yang dilakukan oleh para penjaga penjara;<br />
h. Atas dasar “case law” dari kedua ad hoc Tribunal dan juga Art. 28 Statuta Roma tentang ICC,<br />
“Effective Control” secara umum ditafsirkan sebagai suatu kondisi di mana atasan secara sungguhsungguh<br />
mampu menggunakan kekuasaannya bilamana dia menginginkannya. Dengan demikian<br />
istilah tersebut menunjuk kepada “material ability” <strong>untuk</strong> mencegah dan menahan tindak pidana.<br />
Apakah seseorang berada dalam posisi <strong>untuk</strong> mengontrol atau tidak akan tergantung pada apakah<br />
seseorang mempunyai kekuasaan <strong>untuk</strong> mengeluarkan perintah yang mengikat bawahannya dan<br />
<strong>untuk</strong> mencegah atau menghukum setiap pelaku tindak pidana yang mungkin dilakukan. Dengan<br />
demikian “control” harus diartikan sebagai sambungan atau akibat komando (sequel of command).<br />
Perkecualian bisa terjadi apabila komandan tidak mempunyai kontrol efektif. Hal ini bisa terjadi apabila<br />
komunikasi sama sekali terputus atau karena sesuatu alasan tidak mungkin dilakukan. Contoh lain<br />
adalah apabila terjadi suatu pemberontakan (mutiny). Dalam keadaan darurat/bahaya (sipil, militer<br />
atau perang), kontrol tidak harus berasal dari komando militer, tetapi juga bisa berasal dari orang yang<br />
berwenang, misalnya pimpinan politik atau pejabat pemerintah. Tingkatan komando dan kontrol<br />
bervariasi. Bisa operasional, taktis, administratif, eksekutif dalam teritori di bawah kontrol atasan.<br />
Tanggung jawab atasan akan banyak tergantung pada derajat kontrol dan cara pelaksanaannya;<br />
i. Seorang Staf sekalipun memiliki pengaruh besar, belum tentu mampu mencegah kejahatan. Sebagai<br />
contoh adalah kasus yang diadili Trial C<strong>ham</strong>ber ICTY. Seseorang bertindak sebagai “co-ordinator of<br />
logistic support” tetapi tidak dalam posisi sebagai “superior authority” terhadap pelaku kejahatan,<br />
sehingga dibebaskan. Kasus lain yang menarik dalam hal ini adalah apa yang terjadi dalam Tokyo<br />
Tribunal (IMTFE) yang <strong>mengadili</strong> Letjen Akira Muto, yang bebas dalam kasus Rape of Nanking, karena<br />
kedudukannya sebagai seorang perwira staf dari Jendral Iwane Matsui. Muto kemudian dipromosikan<br />
menjadi Chief of Staff Jendral Yamashita di Filipina. Dalam kasus kekejaman di Filipina, Muto tidak<br />
bebas dari pertanggungjawaban komander (shares responsibility) karena dia dalam posisi yang dapat<br />
mempengaruhi kebijakan (in a position to influence policy);<br />
j. Istilah “Cognitive Element” mencakup tiga derajat kesadaran :<br />
1. Actually knew;<br />
2. Deliberately took the risk that this would happen, if not knowing it ; dan<br />
3. He should have known that such crimes were about to occur”.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 24
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Yang pertama mengandung pengertian “he must have known”. Contohnya adalah kasus Yamashita<br />
di mana kejahatan jumlahnya sangat besar (so numerous). Contoh lain adalah Kasus ICTY tentang<br />
pembunuhan di camp penjara. Dalam hal ini ada perbedaan antara perumusan ICTR dan ICTY di<br />
satu fihak yang menggunakan istilah “had reason to know” dan Statuta ICC di lain fihak yang<br />
menggunakan istilah “owing to the circumstances at the time, “should have known” that the forces were<br />
committing or about to commit such crimes”.<br />
Dalam hal ini Trial C<strong>ham</strong>ber menentukan bahwa “had reason to know” berlaku dan atasan<br />
bertanggung jawab apabila informasi sudah diberikan kepadanya, yang menempatkan dia dalam<br />
posisi “deliberately taken the risk that the crimes might occur”.<br />
Istilah “should have known “dalam Statuta ICC berkaitan dengan standar komander yang selalu<br />
mempunyai kewajiban <strong>untuk</strong> selalu memiliki informasi tentang kinerja anak buahnya. Dua kriteria<br />
“deliberately taking a risk” dan “the should have known test” terdapat dalam Statuta Roma Art. 28.<br />
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara “military superiors” dan “non military superiors”. “Non<br />
military superiors” tidak akan bertanggung jawab secara pidana sehubungan dengan kejahatan yang<br />
dilakukan bawahannya, kecuali mereka “consciously disregarded information” yang jelas-jelas<br />
diberikan, bahwa bawahannya melakukan tindak pidana. Dalam hal terdakwa “a military superiors”,<br />
berlaku syarat “owing the circumstances at the time, he should have known that the forces were committing<br />
or about to commit such crimes”. Dalam hal ini seorang komandan militer dapat dituntut karena<br />
“negligence (should have known)”, sedangkan <strong>untuk</strong> superior sipil harus menggunakan standar yang<br />
lebih tinggi, yaitu dia harus memiliki pengetahuan aktual atau konstruktif bahwa kejahatan sedang<br />
dilakukan.<br />
k. Dalam kerangka elemen operasional, terkait suatu persyaratan bahwa atasan dapat<br />
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas kegagalannya <strong>untuk</strong> campur tangan mencegah atau<br />
menghentikan kejahatan. Dalam kasus ICTY yang menyangkut pembunuhan di camp penjara, memang<br />
bisa dibuktikan bahwa komandan penjara (Mucic) telah mengeluarkan perintah bahwa tidak<br />
seorangpun boleh disiksa, namun dia alpa <strong>untuk</strong> melakukan “checking” apakah perintahnya dipatuhi.<br />
Harus dicatat bahwa hal ini tetap ada batasnya (within his material possibility);<br />
l. Untuk mengukur apakah seorang komander telah “failed in his duty” <strong>untuk</strong> mengambil langkah-langkah<br />
yang patut dan tepat guna mencegah, menghentikan atau menghukum pelaku tindak pidana, yang<br />
dijadikan ukuran adalah apakah seseorang telah bertindak sesuai dengan seorang “reasonable person”<br />
dalam posisinya sebagai komander. Contohnya adalah seorang komander dalam tentara El Salvador<br />
yang telah dianggap berpartisipasi membunuh petugas gereja Amerika, karena gagal memenuhi<br />
kewajibannya seperti tersebut di atas. Sebagai komander ia “should have known” apa yang harus<br />
dilakukan terhadap para petugas gereja dan aktivis;<br />
m. Ruang lingkup tanggung jawab individual yang mencakup pula Head(s) of State or Government atau<br />
Responsible Government Official(s) di dalam Art 7(2) mengindikasikan bahwa penerapannya jauh lebih luas<br />
daripada sekedar komander militer dan bisa mencakup pimpinan politik dan atasan sipil lainnya<br />
sebagai atasan yang berwenang. Semua di bawah “doctrine in certain circumstances”. Contohnya adalah<br />
apa yang terjadi pada IMTFE yang <strong>mengadili</strong> kasus “rape of Nanking”. Dalam hal ini yang dipidana<br />
tidak hanya Jendral Iwane Matsui, tetapi juga Menteri Luar Negeri Jepang Koki Hirota yang dianggap<br />
gagal menjalankan tugasnya <strong>untuk</strong> mengambil langkah-langkah <strong>untuk</strong> mengamankan dan mencegah<br />
<strong>pelanggaran</strong> terhadap hukum perang, padahal yang bersangkutan telah memperoleh laporan tentang<br />
kekejaman yang terjadi, waktu tentara Jepang memasuki Nanking. Pengadilan menyatakan bahwa “his<br />
inaction amounted to criminal negligence”. Demikian pula terhadap Perdana Menteri Hideki Tojo dan<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 25
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu karena dianggap melakukan “omissions to prevent or punish the<br />
criminal acts” dari tentara Jepang;<br />
n. Atas dasar pengalaman dua tribunal ad hoc, dalam hal ketiadaan bukti-bukti langsung tentang<br />
pengetahuan superior tentang kejahatan yang dilakukan bawahan, pengetahuan tersebut tidak boleh<br />
diperkirakan, tetapi harus dikaitkan dengan bukti-bukti tidak langsung (circumstantial evidence) berupa<br />
pengetahuan tertentu seperti : “the number of illegal acts; the type of illegal acts; the scope of illegal acts; the<br />
time during which the illegal acts occurred; the number and type of troops involved; the logistics involved, if any;<br />
the geographical locations of the acts; the widespread occurance of the acts; the tactical tempo of operations; the<br />
modus operandi of similar illegal acts; the officers and staff involved; the locations of the commander at the time.”;<br />
o. Hubungan sebab akibat (causation) antara “commander’s or superior’s omission” dengan kejahatan yang<br />
terjadi tidak perlu dibuktikan sebagai unsur terpisah dari pertanggungjawaban komando. Hal ini<br />
dianggap sudah melekat (inherent) dalam persyaratan atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dan<br />
kegagalan atasan <strong>untuk</strong> mengambil tindakan dalam rangka kekuasaannya <strong>untuk</strong> mencegah. Namun<br />
demikian harus difa<strong>ham</strong>i bahwa pertanggungjawaban komando baru bisa dilakukan apabila telah<br />
dibuktikan telah terjadinya “core or principal crimes”, baik dalam bentuk kejahatan perang, kejahatan<br />
genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal “core crimes” ini, sepanjang mengenai<br />
elemen material (actus reus) dan elemen mental (mens rea) perlu dikaji ketentuan yang berlaku secara<br />
universal (misalnya apa yang diatur dalam dokumen “the Elements of Crimes”, Statuta Roma tentang<br />
ICC, 1998). Sekalipun demikian pema<strong>ham</strong>an mengenai syarat pemidanaan yang berlaku dalam hukum<br />
nasional akan sangat membantu, baik yang berkaitan dengan unsur perbuatan maupun unsur<br />
kesalahan;<br />
p. Bilamana persyaratan “actus reus” (elemen material) telah diuraikan dalam bagian II makalah ini, maka<br />
prasyarat “mens rea” (elemen mental) nampak dari hal-hal sebagai berikut :<br />
1. Actual knowledge established through direct evidence; or<br />
2. Actual knowledge established through circumstancial evidence, with a presumption of knowledge<br />
where the crimes of subordinates are a matter of public notoriety, are numerous, occur over a<br />
prolonged period, or in a wide geographical area; or<br />
3. Wanton disregard of, or failure to obtain information of a general nature within the reasonable<br />
access of a commander indicating the likelihood of actual or prospective criminal conduct on the<br />
part of his subordinates.<br />
3. Beberapa Kesimpulan<br />
a. Istilah komando dan pengendalian yang efektif serta patut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<br />
1. Power to intervene (to prevent, to put an end and to repress);<br />
2. Ada hubungan bawahan-atasan (commander and forces under his or her effective command and control).<br />
Perkecualian bisa terjadi dalam keadaan bahaya (keadaan darurat sipil, darurat militer atau<br />
keadaan perang) di mana peranan militer dan sipil “combined” (contoh apabila terjadi pemberlakuan<br />
UU No. 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya);<br />
3. Power to supervise, to discover and take remedial action;<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 26
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
4. Setiap saat komandan mampu menggunakan kekuasaannya bilamana menginginkannya (material<br />
ability);<br />
5. Kontrol efektif merupakan bagian atau sambungan komando (sequel of command);<br />
6. Seorang staf bisa turut bertanggung jawab (shares responsibility) apabila “in a position to influence<br />
policy”;<br />
7. Komandan mempunyai kekuasaan <strong>untuk</strong> mengeluarkan perintah yang mengikat bawahannya;<br />
8. Mengandung “affirmative duty” baik secara moral maupun hukum;<br />
9. Hubungan bawahan-atasan (subordination) bersifat komprehensif, tetapi bukan merupakan faktor<br />
konklusif <strong>untuk</strong> menentukan pertanggungjawaban pidana. Komander hanya bertanggung jawab<br />
terhadap tindak pidana yang diketahuinya (must have known) atau atas dasar keadaan saat itu<br />
seharusnya mengetahui (should have known) (either knew or, owing to the circumstances at the time,<br />
should have known that the forces were committing or about to commit such crimes). Dalam hal ini<br />
dibedakan antara “direct evidence” dan “circumstancial evidence”. Bagi atasan di lingkungan nonmiliter<br />
berlaku persyaratan yang lebih tinggi yaitu “had reason to know” yang mengandung makna<br />
“deliberately took the risk that this would happen, if not knowing it”. Misalnya dalam bentuk dengan<br />
sadar mengabaikan informasi (consciously disregarded information);<br />
10. Dalam kompleksitas organisasi militer dan non-militer dengan pelbagai sistem pendelegasian<br />
komando dan wewenang, maka pertanggungjawaban pidana akan banyak ditentukan oleh teori<br />
kesalahan;<br />
b. Tanggung jawab komando mengandung dua aspek :<br />
1. Bersifat langsung (direct command responsibility) dalam bentuk “crime by commission” dalam bentuk<br />
penganjuran (instigating, uitlokking), perencanaaan (planning) atau memberikan perintah (ordering).<br />
Dalam hal ini bisa terjadi apa yang dinamakan penganjuran yang gagal (163 bis KUHP) karena<br />
yang digerakkan tidak mau atau tidak sampai melakukan tindak pidana; dan<br />
2. Bersifat tidak langsung (indirect command responsibility) dalam bentuk “failure to act” atau “criminal<br />
participation by omission” (culpable omission). Ada pula yang menyebut sebagai pembiaran (tolerated<br />
the criminal act of their subordinates). Dalam hal ini kejahatan harus terjadi dan tidak berlaku Pasal 163<br />
bis KUHP;<br />
c. Dalam kaitannya dengan UU No. 26 Tahun 2000, “indirect command responsibility” hanya bisa terjadi<br />
apabila telah dibuktikan melalui keputusan hakim yang berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde)<br />
bahwa ada pelaku (perpetrator) atau pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya<br />
yang efektif yang telah melakukan tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM<br />
(genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan). Dalam kasus yang ekstrim misalnya pelaku<br />
melarikan diri atau meninggal dunia, paling tidak dengan alat-alat bukti yang ada terdapat dugaan<br />
kuat telah terjadi tindak pidana tersebut;<br />
d. Tanggungjawab komando juga berlaku dalam kerangka hubungan hierarkhis di lingkungan non<br />
militer, yaitu hubungan antara atasan (superiors) dan bawahan (subordinates). Hanya saja ada<br />
persyaratan yang lebih tinggi yaitu atasan tersebut telah melakukan “consciously disregarded information”<br />
yang mengindikasikan bahwa bawahan sedang atau telah melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku<br />
doktrin “had reason to know” sehingga atasan berada dalam posisi “deliberately taken the risk that the crimes<br />
might occur”.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 27
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
Bagian Keenam<br />
PENUTUP<br />
Indonesia telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam merumuskan kejahatan<br />
yang termasuk jurisdiksinya tegas-tegas dinyatakan telah mengikuti Statuta Roma Tahun 1998. Hanya<br />
sayangnya dua dokumen lainnya yang melekat tidak pernah dibahas yaitu dokumen tentang “Elements of<br />
Crimes” dan dokumen tentang “Rules of Procedures and Evidence”. Juga sangat disayangkan tidak<br />
dimasukkannya ketentuan ICC tentang kejahatan perang (war crimes) dalam jurisdiksi Pengadilan HAM. Di<br />
samping itu pelbagai rumusan lain dalam Pengadilan HAM juga mengadopsi apa yang diatur oleh ICC.<br />
Contohnya adalah Pasal 42 yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Komando.<br />
Sebagai suatu norma yang baru kita harus mengkaji baik secara teoritik konseptual maupun empiris apa<br />
yang telah terjadi dalam praktek hukum internasional yang cenderung sudah menjadi hukum kebiasaan<br />
internasional.<br />
Dalam beberapa hal seperti pertanggungjawaban komando, sebenarnya pelbagai diskusi di atas sepanjang<br />
bersifat langsung (direct command responsibility) masalahnya dapat ditempatkan dalam kerangka hukum<br />
nasional yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), sekalipun<br />
terdapat hal yang relatif baru yaitu “crimes by omission” atau “culpable omission” atau ‘indirect command<br />
responsibility’. Dikatakan ‘relatif’ baru, karena secara konseptual kejahatan omisionis juga dikenal seperti<br />
<strong>pelanggaran</strong> berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 berupa pembunuhan dengan sengaja dengan cara tidak<br />
memberikan bantuan makanan atau kesehatan atau melalaikan hak POW <strong>untuk</strong> diadili secara adil. Dalam<br />
kerangka ini dipertimbangkan betapa pentingnya studi perbandingan hukum antar negara.<br />
Dalam hal ini pula Prof. Nico Keijzer (Hakim Agung Belanda) menyatakan bahwa pelbagai uraian di atas<br />
tidak hanya terbatas pada kejahatan perang (war crimes), tetapi harus dilihat sebagai salah satu bentuk<br />
“criminal participation” atau “participation by omission” dan dapat berkaitan dengan delik-delik yang lain<br />
secara umum.<br />
“The American Model Penal Code” (Section 2.06(3)) menentukan bahwa “ a person is an accomplice of<br />
another in the commission of a criminal offence, inter alia, if he , having a legal duty to prevent the<br />
commission of the offence, fails to make proper effort to do so”.<br />
Dalam Paragraph 13 KUHP Jerman yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang<br />
mengabaikan <strong>untuk</strong> mencegah kejahatan agar tidak terjadi, padahal yang bersangkutan mempunyai<br />
kewajiban hukum <strong>untuk</strong> melakukannya. “Participation by omission” juga dikenal dalam yurisprudensi (case<br />
law) Belanda sebagai landasan pertanggungjawaban pidana.<br />
Mengenai jurisdiksi materi kiranya dapat diusulkan amandemen terhadap UU No. 26 Tahun 2000, agar juga<br />
memasukkan juga Kejahatan Perang (War Crimes) di dalamnya sebagaimana ICC, mengingat kejahatan<br />
perang tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga bisa diterapkan terhadap<br />
konflik bersenjata internal. Perumusan yang diambil dari ICC (seperti juga perumusan genosida dan<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan) cukup memadai, mengingat perumusannya yang komprehensif.<br />
Sebagai rekomendasi lain dapat dikemukakan agar antar negara terjadi harmonisasi hukum mengenai<br />
“military codes” dan “rule of engagement” (semacam British Manual of Military Law atau the US Army Field<br />
Manual), mengingat telah terbentuknya ICC yang bersifat permanen dan dimungkinkannya dibentuknya<br />
peradilan pidana ad hoc oleh Dewan Keamanan PBB yang secara komplementer dapat mengambil alih<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 28
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
fungsi peradilan pidana nasional apabila diidentifikasikan telah terjadi “s<strong>ham</strong> proceeding” dan fakta bahwa<br />
Pemerintah Indonesia ‘unwilling’ dan “unable” menggelar pengadilan HAM dengan standar internasional<br />
(misalnya hanya menerapkan ordinary crimes).<br />
Penerapan ‘universal jurisdiction’ oleh negara-negara tertentu terhadap Indonesia, hendaknya dilakukan<br />
dengan menghormati kedaulatan nasional Indonesia, di samping memperhatikan prinsip-prinsip hukum<br />
internasional dan prinsip-prinsip hukum universal.<br />
Jakarta, 20 Januari 2004<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 29
Kursus HAM <strong>untuk</strong> Pengacara X, 2005<br />
Bahan Bacaan<br />
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
Bassiouni, M. Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Martinus Nijhof Publishers,<br />
London, 1992.<br />
Heinz, Wolfgang S, and Fruhling, Hugo, Determinants of Gross Human Rights Violations by State and Statesponsored<br />
Actors in Brazil, Uruguay, Cile, and Argentina, 1960-1990, International Studies in Human<br />
Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1999.<br />
International Council on Human Rights Policy, Hard Cases : bringing human rights violators to justice abroad,<br />
a guide to universal jurisdiction, New York, 1999.<br />
Jorgensen, Nina H.B., The Responsibility of States for International Crimes, Oxford University Press,<br />
London, 2000.<br />
Komnas HAM, Laporan Lokakarya Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Jakarta, 2002.<br />
Kittichaisaree, Kriangsak, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2001.<br />
Klip, Andre and Sluiter, Goran, Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals (ICTY 1993-<br />
1998), Hart Publisher, Vienna, 1999.<br />
Muladi, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.<br />
Robertson QC, Geoffrey, Crimes Against Humanity, The Struggle for Global Justice, Penguin Books, 2000.<br />
Ratner, Steven R and Abrams, Jason S, Accountability for Human Rights Atrocities in International<br />
Law, Beyond the Nuremberg Legacy, Oxford University Press, Oxford (Second Edition), Oxford, 2001.<br />
Steiner, Henry J, and Alston Philip, International Human Rights in Context, Law Politics Morals, Clarendon<br />
Press Oxford, 1996.<br />
Schabas, William A, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001.<br />
Von Hebel, Herman A.M. et.al, Reflection on the International Criminal Court, TMC Asser Press, The Haque,<br />
1999.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 30