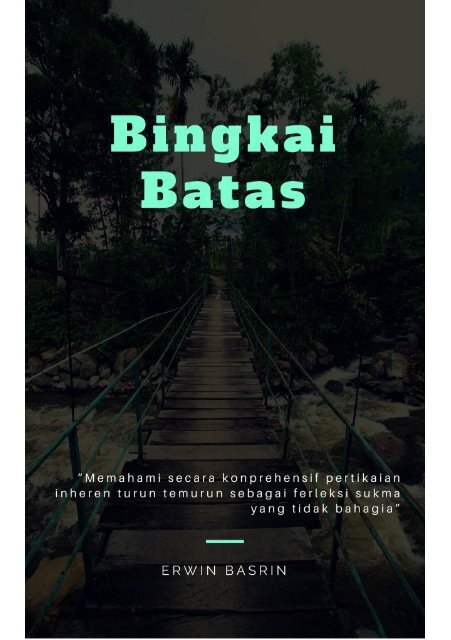Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BINGKAI BATAS<br />
“Memahami secara konprehensif pertikaian inheren turun<br />
temurun sebagai ferleksi sukma yang tidak bahagia”<br />
Erwin Basrin<br />
1
2
<strong>Bingkai</strong> <strong>Batas</strong><br />
By Erwin Basrin<br />
All rights reserved<br />
Ilustrasi sampul oleh Bdikar Anumtiko<br />
Editing oleh Javas Titon Nararya<br />
Diterbitkan pertama kali oleh<br />
Akar Foundation 2018<br />
Hak cipta dilindungi oleh<br />
Tuhan Yang Maha Esa<br />
3
1<br />
Liburan naik kelas tahun ini aku ajak anakku<br />
pulang kampung. Liburan tempat nenek mereka. Kami<br />
naik sepeda motor yang baru saja satu bulan lunas<br />
angsurannya. Motor ini kami beli tiga tahun lalu. Untung<br />
saja hujan tidak turun hari ini. Kami butuh lima jam<br />
perjalanan untuk sampai di kampungku. Jam tiga sore<br />
kami sampai di rumahku. Ibuku senang sekali. Itu<br />
pertanda rumah mereka akan ramai. Dia peluk cucunya<br />
yang kecil. Aku tahu itu pelukan rindu. Sudah sepuluh<br />
bulan dia tidak ketemu cucunya. Setelah aku turunkan tas<br />
dan bawaan kami, aku parkirkan motorku di depan<br />
rumah tetangga. Mamak Modon lewat. Seperti biasa dia<br />
selalu meyapaku dan menyalamiku ketika aku pulang.<br />
Sekedar basa basi menanyakan kenapa pulang, lalu minta<br />
rokok. Tetapi dari tatapannya ketika melihat dan<br />
menyapaku. Aku tahu, itu mengingatkan masa kecil dia<br />
bersama bapakku.<br />
Mamak Modon. Semua orang kampung<br />
memanggilnya dengan Mamak, Paman. Dia masih ada<br />
4
hubungan keluarga denganku. Dan, dia juga teman<br />
sekolah bapakku. Dia suka tersenyum dan tertawa<br />
sendiri, hobi mengupil, sedikit bisa berbahasa Inggris.<br />
Tidak mau dikasihani. Dia pekerja berat. Dan, tetap awet<br />
muda meski umurnya sudah lima puluh lima tahun.<br />
Tetapi, dia tidaklah normal. Dia mengalami gangguan<br />
jiwa. Ketika dia menjadi pelajar di Sekolah Rakyat atau<br />
SD. Mamak Modon dasarnya anak pintar secara<br />
intelektual. Kemudian di tuduh mencuri. Padahal, dia<br />
bukanlah pelakunya. Gegar otaknya karena di pukul atau<br />
disiksa. Pukulan mengenai kepala bagian belakangnya,<br />
akibatnya syaraf nomal otak dan psikologisnya<br />
terganggu. Ganguan jiwanya permanen.<br />
Setiap melihat dan ketemu dia. Aku selalu berpikir<br />
mungkin benar, penguasa atau aparat atau Polisi yang<br />
menuduh dia mencuri termasuk kaum mendustakan<br />
agama sebab mereka bukan saja menghardik anak yatim,<br />
melainkan juga menjatuhkan hukuman yang salah dan<br />
berlebihan.<br />
Dan hukuman itu mengakhiri segalanya secara<br />
teragis.<br />
5
Seorang warga pada suatu hari melaporkan<br />
kehilangan seekor ayam jantan. Modon, seorang bocah<br />
perantauan untuk menuntut ilmu, karena dikampungnya<br />
belum ada sekolah yang lebih layak. Lima belas tahun<br />
usianya, dan tak berayah. Kedapatan sedang membopong<br />
seekor ayam jantan pula. Ayam itu baru didapatinya dari<br />
keluarganya. Dari pamannya. Dari desa lain yang jauh<br />
dari tempat tinggalnya. Ayam itu untuk di jual. Hasilnya<br />
untuk membantu cicilan sewa rumah yang sudah<br />
menunggak tiga bulan.<br />
Tapi apa boleh buat. Modon kecil ditangkap dan<br />
dihukum.<br />
Pak Polisi merendamnya semalam suntuk di sungai<br />
yang mengalir melintasi dekat rumah sewa itu.<br />
Paginya.<br />
Ketika ditarik ke atas. Modon kecil menggigil,<br />
wajahnya pucat.<br />
Bibirnya kebiru-biruan.<br />
Ia sejak hari itu jatuh sakit, panas tubuhnya<br />
semakin tinggi. Dan dimalam hari, selama seminggu<br />
sakit, ia sering mengigau.<br />
6
“Dari igauannya orang-orang yang menjaganya<br />
mendengar Modon berkata bahwa ia tidak mau diajak<br />
pergi jika tidak bersama Polisi yang menangkapnya.” Itu<br />
cerita Bapakku mengenang. Karena tempat tinggal<br />
bapakku tidaklah jauh dari tempat tinggal Mamak<br />
Modon. Mereka menyewa kamar masing-masing. Mereka<br />
anak-anak kampung yang dikirim oleh orang tuanya<br />
untuk menuntut ilmu di kota.<br />
Orang-orang mulai cemas melihat gelagat Modon.<br />
Tapi Pak Polisi yang menangkap Modon, dikenal<br />
pemberani. Memiliki ilmu-ilmu “lahir batin” dan besar<br />
pengaruhnya bagi warga setempat, Cuma berkomentar<br />
pendek dan entang.<br />
“Modon itu Cuma takut di penjara, kecuali bersama<br />
saya,” katanya.<br />
Jawaban itu agak masuk akal. Orang-orang<br />
kemudian punya alasan untuk menenangkan diri. Begitu<br />
juga perasaan Sitiraha. Ibu janda, ibu kandung Modon<br />
yang murung. Dan baru datang dari kampung setelah tiga<br />
hari Modon ditangkap.<br />
7
Tidak ada orang yang berani melawan Pak Polisi,<br />
orang takut kepadanya bukan karena kewibawaannya<br />
melainkan karena dia agak kejam.<br />
Dan Mak Sitiraha, tentu saja lebih tidak berdaya<br />
lagi biarpun harga diri dan rasa keadilannya seperti<br />
dicabik-cabik oleh lelaki perkasa yang kebetulan saja<br />
sedang berkuasa disana.<br />
Di hari kedua dia datang ke kota. Ia pernah datang<br />
sendiri ke rumah Polisi, agar “berkenan” menenangkan<br />
jiwa Modon yang selalu gelisah dan ketakutan dimalam<br />
hari. Tetapi sekali lagi dia menjawab dengan enak, tanpa<br />
beban, bahwa Modon Cuma takut dibawa ke Penjara.<br />
Memang bukan perkara takut dibawa ke Penjara itu<br />
rupanya. Soalnya, Modon keesokkan harinya mulai<br />
linglung dan terganggu jiwanya. Mak Sitiraha kelihatan<br />
sangat terpukul sebab Modon satu-satunya gantungan<br />
hidup masa depannya. Meskipun begitu ia tampak pasrah<br />
ketika empat lelaki dari kampung ingin membawanya<br />
pulang ke kampung dan merencanakan untuk memasung<br />
anaknya di emperan rumahnya yang sangat sederhana.<br />
8
Tak ada yang tampak istimewa dalam iring-iringan<br />
yang mengantar Modon pulang kampung, tetapi<br />
kegemparan terjadi.<br />
Modon kecil itu, tiba-tiba tak bisa diangkat dari<br />
tempat duduknya ke mobil yang akan membawanya<br />
pulang ke kampung. Empat orang yang memikulnya tadi<br />
diduga lelah. Dan orang lain dengan tenaga segar, yang<br />
biasa mengangkat potongan pohon kelapa untuk<br />
digergaji, mengantikan mereka. Tapi aneh, mereka tak<br />
berdaya mengangkat tubuh Modon. Kenang Bapakku.<br />
Secara spontan. Orang-orang menoleh Pak Polisi<br />
yang juga hadir disana, orang kuat yang memiliki<br />
“Kesaktian”, ia mengerti. Ia diminta membantu. Dan<br />
setelah penuh dengan keyakinan menyuruh orang lain<br />
menyingkir. Pak Polisi memang mampu membopong<br />
sendirian Modon. Tak seorangpun tahu sebabnya, Pak<br />
Polisi tersungkur ketika tubuh kecil modon berada di<br />
kuris belakang mobil.<br />
Napasnya sejenak kelihatan tersenggal-sengal.<br />
Kemudian tubuhnya lunglai.<br />
Pak Polisi tak lagi bernapas.<br />
9
Orang-orang mengerti sekarang bahwa, Modon<br />
benar tak mau diajak pergi jika tidak bersama Pak Polisi.<br />
Ketika direndam didalam Sungai, bocah itu boleh jadi<br />
diam-diam menuntut keadilan. Dan keadilan itu alangkah<br />
cepat datangnya.<br />
“Tuhan memang tidak pernah tidur.” Kata<br />
Bapakku.<br />
“Ada rokok?” kata si Modon. Ketika aku menaikan<br />
tangga rumah ibuku. Kuberikan rokokku yang hanya<br />
tersisa lima batang. Dia kemudian pergi sambil senyumsenyum<br />
sendiri. Tetapi, kali ini penampilannya rapi.<br />
Dengan kaos oblong warna putih, jaket jean. Celana jean<br />
dengan ikat pinggang yang ketat dan tinggi, sebelah kiri<br />
dilipat setinggi lutut sehingga tampaklah kaos kakinya<br />
yang beda warna dan dia memakai sepatu karet warna<br />
hitam yang biasa dia pakai untuk ke kebun.<br />
Setelah duduk sebentar. Aku kemudian membantu<br />
istriku mengeluarkan baju-baju dari tas dan<br />
menyimpannya di dalam lemari kayu. Lemari yang biasa<br />
aku pakai ketika kecil dulu untuk menyiman buku-buku<br />
pelajaran sekolahku.<br />
10
Aku menemukan sebuah buku yang sampai saat ini<br />
masih tersimpan dengan baik. Buku itu digunakan ibuku<br />
sebagai alas baju. Buku tulis tipis bersampul warna<br />
hitam. Begitu aku buka dihalaman pertama bertulis<br />
“barang siapa menanam mengetam”.<br />
Pak Abdulah atau Pak Ib, guru yang paling sering<br />
menjewer kupingku ketika itu menterjemahkan “barang<br />
siapa rajin belajar, maka ia akan menikmati nilai-nilai<br />
yang baik diraportnya”. Kita tentu saja boleh memberi<br />
interpretasi. Pribahasa itu bahkan juga berlaku tak cuma<br />
dalam kehidupan pribadi. “barang siapa menanam<br />
mengetam” itu melekat dibenakku. Ia selalu menjadi<br />
penerjemah bagi berbagai peristiwa, ia menerangi sudutsudut<br />
yang gelap.<br />
Diruang tamu aku mulai mendengar keributan.<br />
Suara tawa anakku dengan cumbuan nenek dan kakeknya<br />
yang rindu. Aku keluar lalu duduk dekat Bapakku. Ini<br />
kursi rotan yang sama ketika dulu aku kecil, aku sering<br />
ikut obrolan bapakku. Obrolan dengan Wak Odon, Wak<br />
Salim. Dan obrolan bapakku dengan empat orang<br />
tamunya yang datang dari Jakarta, meminta bapakku<br />
menghitung debit arus sungai untuk dibangun PLTA.<br />
11
Dan, untung saja tidak jadi. Padahal ketika mereka<br />
berdiskusi aku duduk disamping bapakku seperti<br />
penterjemah Presiden Soeharto.<br />
“Pak Polisi memang sudah menanam bibit<br />
kesewenangan,” Kata Bapakku tiba-tiba. Sepertinya dia<br />
tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Bukan karena dia<br />
sakti tetapi dia tahu aku barusan ketemu dengan Mamak<br />
Modon.<br />
“Ia tidak pernah gentar kepada orang, karena<br />
dikanan kirinya orang-orang serba tunduk.”<br />
“Mungkin ia lupa bahwa ketika ia berurusan tidak<br />
hanya dengan orang. Ia lupa ada kekuatan lain yang<br />
tersembunyi dibalik hidup kita.” Lanjut bapakku.<br />
“Sekarang ini kesewenangan-kesewenangan serupa<br />
merebak kemana-mana.” Jawabku ingatan jadi kemanamana<br />
tapi tidak tahu apa yang aku ingatkan.<br />
“Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Polisi<br />
kepada Mamak Modon merupakan bentuk dari imbasan<br />
wajar dari ketidakadilan maupun kesewenangan orangorang<br />
yang lebih besar, lebih berkuasa, di pusat-pusat<br />
kekuasaan di kota.” Lanjutku.<br />
12
“Jangan-jangan Pak Polisi tersebut seperti laku<br />
seorang bocah, Cuma meniru-niru tokoh yang<br />
dianggapnya layak ditiru. Jangan-jangan Pak Polisi itu<br />
sadar, bahwa jika ia sendiri kedapatan salah, atau<br />
dicurigai salah, akan mungkin pula akan menjadi korban<br />
buat melindungi pihak lain yang lebih penting, lebih<br />
berkuasa.” Bapakku tersenyum. Dia tahu anak yang<br />
duduk disamping dia sudah menjadi bapak. Tidak lagi<br />
anak kecil yang selalu menyimak pembicaraan, lalu di<br />
suruh jadi tukang pijat betis sebagai imbalan mengikuti<br />
obrolan orang-orang tua.<br />
“Ia.”<br />
“Ini penyakit yang menjangkiti kita, baik secara<br />
individu maupun secara kolektif.”<br />
“Kita kehilangan Jiwa.”<br />
“Jiwa ini kemudian terwujud tidak hanya melalui<br />
tindakan, karakter, kepribadian tetapi juga tewujud di<br />
dalam struktur sosial, budaya, pola kepemimpinan dan<br />
mempengaruhi sudut pandang kita.” Katanya dengan<br />
bijak sambil mengulung rokok tembakau daun nipah<br />
kesukannya sejak 35 tahun lalu. Tembakau ini tidak<br />
13
membuat dia terserang kangker, sesak napas dan<br />
gangguan lain.<br />
“Kita sering merasa benar dengan kecenderungan<br />
menonjol dan aktif untuk menyalahkan orang lain dan<br />
mencari kambing hitam.” Jawabku<br />
“Kecenderungan menyalahkan adalah prilaku<br />
defensif yang mengantikan renungan dan intropeksi jujur<br />
atas kehidupan, yang sesungguhnya merupakan landasan<br />
yang paling diperlukan untuk mencari bimbingan saat<br />
kita salah langkah atau salah arah,”<br />
“Kontradiksi-kontradiksi kita banyak nilai<br />
negatifnya,” kataku sambil mengulung daun nipah. Aku<br />
belum terbiasa dengan tembakau hasil olahan petani<br />
kampungku yang jadi langanan bapakku. tembakaunya<br />
berserakan ketika aku menggulungnya dengan daun<br />
nipah.<br />
Kecenderungan menyalahkan. Kata-kata bapakku<br />
ini seperti tidak pernah aku dengar dari obrolan yang<br />
dilakukan di kursi dan ruangan ini ketika aku masih kecil<br />
dulu. Ada yang berubah. Bergeser.<br />
Saat ini. Kita tidak hanya kehilangan dan<br />
mengalami ganguan jiwa. Kontradiksi kita mengarah<br />
14
pada kecenderungan egois, picik dan pendengki.<br />
Kecenderungan ini mengerogoti hati dan jiwa kita. Tetapi<br />
anehnya kita semakin mengantungkan diri kepada sifat<br />
ini. Dorongan ini terwujud dari hasrat, namun sekaligus<br />
penolakan diri, menciptakan perasaan frustasi dan sifat<br />
obsesif.<br />
“Jiwa, karakter dan tindakan.” Kata-kata ini<br />
membuat aku trauma. Dan aku ingat kata-kata ibu tentang<br />
moralitas yang dia ajarkan kepadaku ketika aku masih<br />
kecil dan ketahuan berbohong karena di suruh menjaga<br />
sawah dari hama burung dan aku malah asik ngobrol<br />
dengan Wak Wahit, kakak ibuku.<br />
Aku jadi ingat dengan kata-katanya. Tingkat<br />
kebohongan itu biasanya ditentukan dari hasil proses<br />
pendifinisian mereka mengenai diri mereka sendiri. Dari<br />
kombinasi gagasan bawaan dan pengaruh kental budaya<br />
dan lingkungan tempat tumbuh, hasilnya adalah kita<br />
memiliki keyakinan tentang sifat dasar termasuk<br />
kebohongan. Keyakinan itu masuk ketingkat sangat<br />
dalam pada sistem psikosomatis kita, pikiran dan otak<br />
kita, sistem syaraf, sistem endoktrin bahkan dalam darah<br />
dan otot kita. Jadi kita bertindak, berbicara dan berpikir<br />
15
atas dasar keyakinan kita tadi. Dan kebohongan itu<br />
adalah buat dari jiwa yang tersesat.<br />
Terbayang-bayang senyum Mamak Modon, Ayam<br />
dan Pak Polisi. Aku bukan Pak Polisi.<br />
Jadi. Demi Allah, aku tidak tahu motif tindakannya.<br />
Bisa saja berbagai kemungkinan tadi separuhnya<br />
benar. Artinya, ketidakadilan Pak Polisi bisa saja Cuma<br />
bagian dari ketidakadilan dalam struktur hidup sosial kita<br />
secara keseluruhan.<br />
Meskipun begitu, tak seorang waras pun bisa<br />
menerima dengan rasa dingin perlakuan Pak Polisi pada<br />
Modon. Demi rasa keadilan yang terkoyak dan solidaritas<br />
pada Modon, kita wajib menuntut agar hal yang sama tak<br />
mudah terulang.<br />
Benar bahwa, ibarat kanker, sikap semacam itu<br />
mudah menyebar kemana-mana.<br />
Benar hal itu ibarat kanker ganas, tapi kita wajib<br />
yakin bahwa penyakit, betapapun ganasnya, pasti ada<br />
obatnya.<br />
“Kita membunuh jiwa kita sendiri,”<br />
“Kita dibutakan akan sifat dirinya sendiri.” Katakata<br />
ini muncul dari orang yang mirip diriku yang duduk<br />
16
di sudut ruang belakang pintu rumahku. Mirip dengan<br />
ujudku ketika masih anak-anak dulu.<br />
“Padahal mengenal dan memahami diri adalah<br />
syarat dasar untuk bisa menuntaskan permasalahan kita<br />
yang telah tupang tindih.” Dia menghilang bersama<br />
sapuan asap rokok bapakku.<br />
Ibuku mengendong cucunya, anak bungsuku. Lalu<br />
datang. Dia tidak keluar dari dapur. Tersenyum dan<br />
membawa tampan, di atasnya tersaji tape dari beras ketan<br />
yang dibungkusi daun kemiri.<br />
“Begitu aku dapat kabar kalian akan pulang, aku<br />
langsung buat tape dari beras ketan.” Katanya.<br />
Bau beraroma alkoholnya yang keluar dari tetesan<br />
bungkusan tape mengigatkanku pada sosok Nenek Pia.<br />
Kata ibuku dia masih rutin membuat tape dan sering<br />
menanyakan kabar diriku.<br />
Mamak Modon datang dan muncul lagi, kali ini dia<br />
senyum-senyum sambil mengeluarkan asap rokoknya<br />
dari hidung. Anak bungsuku senang. Dan, memberikan<br />
dia dua bungkus tape buatan neneknya. Dia lalu duduk di<br />
kursi dekat pintu menikmati tape lalu pergi tanpa pamit.<br />
17
Dan, kami berebut menikmati tape. Dengan melupakan<br />
semua pernik jiwa.<br />
18
2<br />
Sore dan tempat favorit kami adalah sungai. Mandi<br />
di sungai. Ritual mandi di sungai ini kami lakukan setiap<br />
kali kami pulang kampung. Sungai di mana dulu ari-ariku<br />
dihanyut. Sungai dimana bayi-bayi yang baru dilahirkan<br />
diritualkan disini. Sungai dimana aku sering mengawani<br />
bapakku mencari ikan dengan jala, dengan sumpit, jaring<br />
dan kail. Dan, di sungai ini aku membantu mencatat debit<br />
dan kecepatan arus untuk pembangunan Pembangkit<br />
Listrik dan untungnya tidak jadi.<br />
Ada sejarah adat yang melekat di sungai ini. Itu<br />
diceritakan oleh nenekku. Seorang putri dihayutkan pakai<br />
rakit dari bambu oleh saudara laki-lakinya. Putri<br />
Serindang Bulan. Kemudian lahirlah adat Beleket. Sistem<br />
kawin jujur untuk Perempuan. Perempuan dipindahkan<br />
haknya dari keluarga patrilinial kepada pihak suaminya.<br />
Dalam system adat di Kampungku, patrilineal berarti<br />
mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah.<br />
Ini konsep kesimbangan hak, bukan kesetaraan hak<br />
perempuan. Tujuan dari system perkawinan ini untuk<br />
19
mencapai keseimbangan dalam clan yang sering juga<br />
disebut kerabat luas atau keluarga besar. Maka<br />
perkawinan merupakan bagian dari pembentuk sistem<br />
sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang<br />
sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik<br />
melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu<br />
(matrilineal). Dan tentu saja dilakukan atas nama<br />
penghormatan dan cinta perempuan kepada saudara lakilakinya.<br />
Kami harus berjalan jauh untuk sampai di sungai<br />
ini. Dulu ketika aku masih kecil. Penduduk mengunakan<br />
sungai untuk mandi, cuci dan kakus. Dan di sana dulu<br />
ada mesin kincir untuk menumbuk padi. Jadi, jalannya<br />
terawat dan ramai sekali. Untuk sampai di sungai kita<br />
mesti melewati terowongan yang di gali kakekku. Kini.<br />
Jalannya jarang sekali digunakan kecuali oleh orangorang<br />
tua yang masih setia dengan sungai, setia dengan<br />
kebiasaan atau sekedar keterikatan mengingatkan memori<br />
kolektif mereka. Namun semakin hari jumlahnya semakin<br />
sedikit.<br />
Air sungai ini semakin kecil, tetapi tidak ada yang<br />
berubah, agregatnya masih seperti dahulu. Batu-batunya<br />
20
tetap berdiri kokoh, Airnya masih jernih, sejernih ketika<br />
dulu aku sering mandi dan menyelam ketika bulan<br />
ramadhan. Menyelam sambil minum air. Dan itu<br />
membantu sekali menahan haus ketika kita berpuasa.<br />
Sekali menyelam setara dengan seteguk air<br />
Anak bungsuku belajar berenang dan dia tampak<br />
kegirangan, dia ajarkan oleh kakek dan kakak sepupunya.<br />
Aku duduk di sebuah batu yang dulu sering aku gunakan<br />
untuk berdiri, aku berdiri tegak seperti berdiri di puncak<br />
dunia yang berdekatan dengan surya. Dari batu inilah aku<br />
melocat ke dalam air, berenang sampai menggigil,<br />
menggigil dalam kehangatan kebahagiaan bersama<br />
kawan sebayaku.<br />
Aku duduk dengan anak tertuaku. Bdikar.<br />
“Lihatlah Nak, dan pahamilah sungai yang<br />
mengalir ini,”<br />
“Kau akan tahu dan mengerti akan rahasia<br />
kehidupan yang kaya didalamnya.” Pikiranku melayang<br />
ketika dulu pernah jadi saksi ritual membersihkan sungai.<br />
Aku duduk di samping sang Dukun. Dan jangan sesekali<br />
berkirim surat melalui sungai, demikian pesan tua-tuan<br />
kampung setelah asap kemenyan menghilang.<br />
21
“Oh, begitu,” Kata Bdikar, kakinya bergerak-gerak<br />
seperti bersiap untuk terjun ke sungai dari tempat kami<br />
duduk.<br />
“Kau akan melihat betapa kedalamannya bermainmain<br />
beribu mutiara gemerlapan, udara yang segar<br />
berenang di permukaannya dan kebiruan cahaya langit<br />
yang berkaca kepadanya.”<br />
“Belajarlah dari dia, cintai dia, maka akan<br />
terbukalah bagimu berjuta rahasia.” Bdikar mulai buka<br />
bajunya, sepertinya tidak dia dengar dan perhatikan apa<br />
yang barusan aku bicarakan. Dia meloncat seperti kodok.<br />
Menyelam lalu berenang. Adiknya tertawa kegirangan<br />
melihat gaya renang abangnya.<br />
Aku kemudian menatap aliran sungai. Dulu aku<br />
sering berlomba menyeberanginya bersama-sama teman<br />
sebayaku. Yang kalah dan hanyut akan mendarat di<br />
lokasi khusus yang difungsikan untuk kakus terbuka.<br />
Orang yang buang hajat disana, duduk mencangkung dan<br />
menutupi mukanya dengan sarung, tampaklah knalpot<br />
yang membuang kotoran padat berwarna kekuningan.<br />
Ternyata kemaluan itu ada di muka dan kepala. Kata<br />
temanku Bambang.<br />
22
“Buktinya mereka menutup muka.” Sambungnya.<br />
“Dan kehilangan muka adalah ungkapan yang biasa<br />
digunakan untuk rasa malu, makanya muka harus<br />
ditutup.” Ia menguatkan argumenya.<br />
Setelah membuang hajad barulah mereka mandi.<br />
Mengunakan arang yang haluskan untuk mengosok gigi.<br />
Dan, dengan batu yang di gosok di betis dan tangan untuk<br />
menghilangkan daki.<br />
Aliran sungai ini masih bening dan berarus deras.<br />
Suara jeram arus ini memicu hatiku seakan terbuka dan<br />
memahami sebuah makna. Karena, Rahasia sungai ini<br />
adalah rahasia perjalanan hidupku. Arus dan sungai ini<br />
tetap berada seperti dahulu. Kenangku. Senantiasa disana,<br />
arusnya seperti merindukan sesuatu dalam perjalanannya,<br />
namun justru dalam kerinduannya itu ia menjadi selalu<br />
baru.<br />
Lamunanku berhenti, ketika ada tepukan di bahuku.<br />
Itu Bambang, dia sepupu jauhku dan teman sekolah,<br />
teman sebangku dan teman mencuri buku-buku<br />
diperpustakaan. Karena perpustakaanya selalu terkunci.<br />
Maka mencurilah satu-satunya cara untuk melihat deretan<br />
23
huruf dan angka yang tertulis didalam buku yang<br />
sebagian sudah rapuh dimakan rayap.<br />
“Buku itu untuk dibaca bukan untuk disimpan di<br />
lemari kemudian jadi makanan rayap,” itu pembelaanya<br />
kalau kami ketahuan oleh Guru Kepala Sekolah. Dan, dia<br />
yang selalu di depan dan pertama kami merasakan<br />
mendaratnya telapak tangan Guru Kepala Sekolah kami.<br />
Biasanya dia selalu menoleh kebelakang. Antrian<br />
selanjutnya adalah aku. Dia selalu meyeringai seperti<br />
kesakitan dengan mulut komat-kamit. Katanya dia sedang<br />
melapaskan ajian tahan pukul yang dia pelajari dari<br />
kakeknya untuk menetralisir rasa sakit. Ajian tahan<br />
pukulah yang membuat wajah putihnya memerah lalu<br />
muncul jejak telapak tangan. Sekarang dia menjadi<br />
seorang pegawai Negeri sipil dan bertugas di<br />
Kampungku. Anaknya pendiam. Diam-diam nakal tetapi<br />
pandai sekali merangkai kata lalu menjadikan bait-bait<br />
puisi.<br />
“Apa yang kau lihat?” Tanya dia lalu duduk<br />
disampingku. Bdikar tersenyum dengan Waknya, dan<br />
kepalanya menghilang masuk kedalam air. Bambang tahu<br />
aku pulang dan mandi ke sungai dari ibuku. Ketika dia<br />
24
lewat depan rumah, ibuku bilang aku sedang mandi di<br />
sungai dengan anak-anakku. Lalu dia menyusul. Kami<br />
selalu ketemu kalau aku pulang kampung. Kami punya<br />
kenangan di sungai ini, selain kenangan ketika berurusan<br />
dengan Perpustakaan sekolah. Dialah yang mengajariku<br />
pertama kali menyelam sambil minum air ketika kami<br />
sama-sama berpuasa. Awalnya dia tidak mau mengaku<br />
ketika aku tanyakan kenapa setiap dia menyelam<br />
gelembung udara selalu muncul.<br />
“Tidakkah dari sungai ini kau mengerti akan suatu<br />
rahasia, bahwa sebenarnya waktu itu tidak ada dalam<br />
kehidupanmu?” tanya Bambang.<br />
“Sungai itu ada dimana-mana dan sama. Ia sama di<br />
mata airnya, sama di muaranya, airnya tetap sama meski<br />
ia mengarugi air terjun, terjepit di sela-sela bukit dan<br />
pengunungan. Ia sama dalam amarahnya ketika<br />
mengamuk menjadi air bah. Sama seperti dalam<br />
keramahannya ketika bernyanyi menjadi sungai kecil.”<br />
Kami terdiam.<br />
Dia menunjukan arus deras tempat kami sering<br />
berlomba-lomba menyeberanginya. Dia selalu saja kalah,<br />
beberapa kali aku bantu dia menyeberang dengan<br />
25
menarik tangannya. Aku di untungkan dengan<br />
pengetahuanku menghitung kekuatan lalu debit arus yang<br />
diajari bapakku. Jangan sesekali menyeberang sungai<br />
dimulai dengan kaki kanan. Kemungkian hanyut semakin<br />
besar, ini pelajaran pertama bapakku. Pelajaran ini<br />
membuat aku tahu di titik di mana aku memulai berenang<br />
menyeberangi arus. Pernah suatu kali, kami berlomba<br />
lalu aku tarik tangannya, celananya lepas karena arus<br />
terlalu kuat dan ikatan celananya longgar. Dia lepaskan<br />
pegangan tangannya membiarkan hanyut lalu mengejar<br />
celananya yang hanyut dan mendarat di sebuah batu<br />
tempat orang-orang duduk dan menutup mukanya dengan<br />
sarung.<br />
Bambang selalu lemah di hitung-hitungan. Dia kuat<br />
di pelajaran sejarah, bahasa dan pencinta buku dan cerita<br />
roman. Dialah yang menceritakanku tentang kisahnya<br />
Qais dan Laila. Dia gambarkannya dalam bait puisi; Aku<br />
berseru pada singgasana langit, berilah kami kebahagiaan<br />
dalam cinta. Singkaplah tirai derita yang selalu<br />
membelenggu kalbu. Bagaimana mungkin aku tidak gila,<br />
bila melihat gadis bermata indah yang wajahnya bak<br />
26
mentari pagi bersinar cerah. Menggapai balik bukit,<br />
memecah kegelapan malam.<br />
“Sama seperti dalam kesedihannya ketika ia<br />
merintih menjadi hujan gerimis rintik-rintik,” Jawabku<br />
bak berbalas pantun. Beginilah kebiasaan kami<br />
berkomunikasi sejak dahulu. Kami selalu mengunakan<br />
kata-kata berkias. Aku memaksa diri mengikutinya.<br />
Seperti terjun Balanda. Selalu saja dia yang membetulkan<br />
redaksi dan susunan kata-kataku yang salah. Dan sejak<br />
dulu aku selalu seperti anak yang baru bisa belajar bicara.<br />
Dia gurunya.<br />
“Pahamkah kau sekarang dengan arti masa lalu dan<br />
masa depanmu. Kau tetap sama”<br />
“Tapi hendaklah kesamaamu selalu membuahkan<br />
kerinduan. Supaya hidupmu selalu baru. Kerinduan itulah<br />
yang membuatmu tak pernah muda, tak pernah tua,”<br />
“Itulah hakekat waktu dan dalam waktu itulah<br />
hidupmu berada.” Dia mulai bijak dan aku sengaja<br />
biarkan dia sendiri yang menjawab pertanyaan<br />
sebelumnya bahwa sebenarnya waktu itu tidak ada dalam<br />
kehidupan? Karena aku tahu dia semakin banyak belajar.<br />
Sejak dulu dia hampir tidak pernah meninggalkan<br />
27
kampung. Kami sering ikut menikmati obrolan tua-tua<br />
kampung. Dia selalu diam, tidak berani berkomentar.<br />
Setelah itu barulah kami mempraktekkan dan<br />
mendiskusikan obrolan tua-tua kampung.<br />
Kata-katanya tentang waktu dan hidup<br />
mengingatkanku pada mimpi tahun lalu. Mimpi ketika<br />
aku berada di suatu tempat yang tidak mengenal katakata<br />
siang dan malam. Dalam mimpiku aku merasa<br />
mengengam bulan dan matahari. Gelap dan terang<br />
sekaligus. Tapi tiba-tiba mencuat sebuah cahaya,<br />
mengulung menjadi awan yang berarak gemerlapgemerlap<br />
di iringi suara musik pada bidadari. Entah dari<br />
mana asalnya.<br />
Aku ceritakan dengannya tentang mimpiku. Aku<br />
tahu. Sejak dulu dia juga sering meraba-raba tentang<br />
masa depan. Dia sering berlagak bak peramal. Seakanakan<br />
dirinya Nostradamus. Meski setiap ramalannya<br />
selalu meleset dan tidak tepat. Sama ketika dia<br />
menyebarangi arus. Hitunganya selalu saja meleset.<br />
Tiba-tiba Bdikar datang, lalu bersalaman dengan<br />
Bambang. Belum ada tanda-tanda dia kedinginan, dia<br />
ambil ancang-ancang lalu meloncat terjun dari batu<br />
28
dimana kami duduk. Kali ini jaraknya semakin jauh di<br />
banding loncatan pertamanya. Kami tersenyum. Itu<br />
mengingatkan kami ketika kecil dulu.<br />
“Kau selalu saja kalah jauh ketika kita lomba locat<br />
dari batu ini.” Kenangku. Dia tersenyum sambil menoleh<br />
ke arah hilir dimana dulu sering difungsikan orang-orang<br />
untuk buang hajad.<br />
“Waktu yang meyediakan ruang kebahagian dan<br />
penderitaan sekaligus,” Jawab dia dengan kata-kata yang<br />
bersayap.<br />
“Jangan terkejut, cahaya. Seperti dalam mimpimu<br />
itu adalah penunjuk dalam hatimu.” Di bersemangat.<br />
“Maka jangan ikuti aku”<br />
“Ikuti hatimu.” Kali ini dia benar. Kami tertawa<br />
ketika aku ceritakan betapa dia sering salah mendarat<br />
ketika menyeberang arus dan sejak itu aku mesti<br />
mempertimbangkan untuk mengikuti setiap sarannya.<br />
“Kebijaksanaan terembunyi di dalam hatimu, sama<br />
seperti malam yang bersayap terang. Seperti kehidupan<br />
bersayapkan kematian.” Dia seperti tahu betapa aku<br />
sering meratapi hatiku yang sering mengalir kelemahan<br />
29
erupa penderitaan dan kesengsaraan. Aku perantau dan<br />
tidak bawa bekal apapun dalam perkelanaanku.<br />
Pernah suatu kali aku mulai hilang harapan.<br />
Kehilangan harapan karena ada banyak<br />
ketidakadilan yang aku lihat dalam struktur sosial,<br />
budaya, pola kepemimpinan dan mempengaruhi sudut<br />
pandangku. Ekpektasiku. Tapi aku tidak bisa berbuat apaapa.<br />
Kecenderungan menyalahkan, yang aku saksikan<br />
adalah prilaku defensif yang mengantikan renungan dan<br />
intropeksi jujur atas kehidupan, yang sesungguhnya<br />
merupakan landasan yang paling diperlukan untuk<br />
mencari bimbingan saat kita salah langkah atau salah<br />
arah.<br />
“Kini buatlah hatimu menjadi keindahan,” Katanya.<br />
Kali ini seperti Kakak yang menasehati adik yang mulai<br />
putus asah.<br />
“Karena kaindahan itulah milik rahasiamu.<br />
Keindahan itu tak dapat kau pelajari lebih daripada<br />
kebenaran”<br />
“Keindahan yang bagaimana?” Tanyaku.<br />
“Keindahan itu adalah keseimbangan,<br />
keseimbangan antara kebahagian dan penderitaan, antara<br />
30
kegembiraan dan kedukaan. Antara harapan dan<br />
kenyataan,” kata-kata ini sering juga aku dengan dari Pak<br />
Salim Senawar. Bambang adalah anaknya. Anak<br />
Sulungnya.<br />
“Dan justru dalam keseimbangan itulah kebahagian<br />
dan penderitaan lenyap, harapan dan kenyataan<br />
menghilang.” Dia membujuk. Tetapi kalimat ini belum<br />
aku mengerti. Aku lebih fokus melihat kedua putraku<br />
berenang.<br />
“Keindahan yang dibalut dengan cinta.” Jawabku<br />
pura-pura mengerti. Aku mulai tertantang dengan katakata<br />
yang berkias. Sepertinya dia mulai menantangku.<br />
“Air sungai ini bisa hilang kesegarannya bila tiba di<br />
muara, tetapi cinta mereka hidup dari pagi sampai<br />
malam”<br />
“Lihatlah!” Kataku<br />
“Maski telah berganti, tidak ada lagi Mesin kincir<br />
untuk menumbuk padi, tidak ada lagi orang-orang duduk<br />
dengan menutup kepala di tepian sungai. Fungsinya<br />
sudah dipindahkan keruangan yang orang modern sebut<br />
WC. Tak ada lagi para gadis dan ibu-ibu mencuci beras<br />
dalam baki. Tetapi keindahan sungai ini sangup membuat<br />
31
dunia kembali kepada masa mudanya yang tak bercela.”<br />
Lanjutku.<br />
“Ia.”<br />
“Karena cinta menuntun arusnya melewati jalan<br />
sempit, cinta juga menjerumuskan mereka ke dalam<br />
juruang-jurang dalam, tetapi cinta juga mengangkat<br />
mereka ke puncak gunung. Dan cinta juga menyeret<br />
mereka masuk ke dalam pondok yang hampir rubuh jika<br />
dilihat dari luar,”<br />
“Begitulah kawan,”<br />
“Dalam cinta kebahagian dan penderitaan itu<br />
bersatu, lebur menjadi kehidupan,” Kata Bambang.<br />
Kami tertawa. Sungai ini bukan hanya mampu<br />
mengingatkan ingatan kolektif kami, sungai ini menjadi<br />
saksi dalam diam perjalaan hidup kami, hidup orangorang<br />
kampung, perjalanan budaya. Sungai ini juga<br />
mengajari kami siapa yang pernah berpikir, makin<br />
kencang badai melanda makin jauh swagaloka<br />
ditinggalkan.<br />
Seperti biasa. Kami mandi dengan basahan, dengan<br />
kain penutup aurat kami. Kami bukan anak-anak lagi.<br />
Aku tantang dia berenang menantang arus sampai<br />
32
kesebarang. Arusnya tidaklah sekuat dan sebesar ketika<br />
kami masih kecil dulu. Anakku tertawa memberi<br />
semangat. Pada hitungan ketiga kami sama-sama<br />
meloncat. Kali ini aku yang tidak bisa sampai ke<br />
seberang.<br />
Dan aku hanyut. Untungnya tempat aku merapat<br />
tidak lagi di gunakan untuk buang hajad. Bambang<br />
tertawa. Dia tetap menungguku di sebarang. Lalu aku<br />
ulangi lagi kali ini dengan ancang-ancang. Meloncat<br />
dengan diawali kaki sebelah kiri aku meloncat. Dia<br />
tangkap tangganku dan kami sama-sama akhirnya di<br />
seberang arus. Kami duduk di atas batu cadas tempat<br />
tumbukan arus. Dari atas cadas ini tampaklah batu besar<br />
ditengah arus yang biasa digunakan untuk berbagai ritual<br />
yang berhubungan dengan sungai.<br />
Aku melihat ada badan halus yang berkeliaran di<br />
atas batu tempat ritual itu. Memakai pakaian serba halus<br />
dengan renda-renda putih. Menyala dalam terang yang<br />
sangat halus pula. Berpendar seperti kunang-kunang<br />
senja, hanya mereka seperti tidak berdaya. Lalu berlahan<br />
berubah ujud, ujud hati. Hati yang tidak berdaya di bawa<br />
himpitan tangan-tangan nafsu kedurhakaan. Bambang<br />
33
meloncat. Cipratan air meyadarkan lamunanku. Aku<br />
meloncat dan menyelam aku tersandung batu, air sungai<br />
mulai keruh, pertanda airnya akan naik karena hutan<br />
dihulunya mulai bsanyak yang berubah fungsi.<br />
Ini tanda dan peringatan, sungai menyampaikan<br />
sesuatu atas dasar cinta. Sungai masih bersahabat seperti<br />
dulu. Semoga saja tidak ada yang berkirim surat ke<br />
sungai dan membuat dia murka, karena nyanyian<br />
kemurkaannya adalah badai yang mengerikan. Aku tahu<br />
dihulunya hutan semakin menurun kwalitasnya karena<br />
keterdesakan kebutuhan warga kampungku. Tapi<br />
gelombang hidup pun harus mengayun, menuntun setiap<br />
doa dan mimpi manusia yang masih memiliki cinta dan<br />
gairah pada kehidupan. Cinta jua yang akan menuntun<br />
arusnya melewati jalan sempit, cinta juga menjerumuskan<br />
mereka ke dalam juruang-jurang dalam, tetapi cinta juga<br />
mengangkat mereka ke puncak gunung.<br />
Kami kemudian berhenti mandi dan pulang kembali<br />
ke rumah. Tidak ada obrolan sepanjang jalan pulang.<br />
Jalan mendaki. Dengkul gemetaran dan nafas kami<br />
seperti berpacu seperti arus sungai yang mengalir menuju<br />
muara.<br />
34
Sampai di rumah, ibuku sudah menyiapkan pisang<br />
goreng, pisang yang baru diambilnya dikebun ketika<br />
kami mandi ke sungai.<br />
35
3<br />
Melengkapi liburan. Kami ikut menemani ibuku ke<br />
sawah. Padinya mulai menguning. Sawah ibuku berada di<br />
wilayah desa tetangga. Untuk sampai disawah kami<br />
berjalan kaki. Sepanjang perjalanan kami ketemu orangorang<br />
kampung, bersalaman dan mereka selalu<br />
menanyakan “kapan pulang?”, “pulang bersama<br />
keluarga?”. Itu Cuma basa-basi. Pertanyaan itu selalu di<br />
tutup dengan “sering-seringlah pulang”. Kata terakhir ini<br />
adalah kata-kata hati yang di lisankan oleh mulut. Aku<br />
tahu dari cara pengungkapan dan intonasi suara mereka.<br />
Di ujung kampung kami melewati Gedung Sekolah<br />
Dasar. Di gedung sekolah inilah aku diajarkan<br />
pengetetahuan dasar. Tidak ada yang berubah dari bentuk<br />
fisik gedungnya, kecuali pagar dan warna cat.<br />
“Ini sekolah bapak dulu ya?” tanya Bdikar, ketika<br />
kami melewati depan pintu masuk gedung sekolah.<br />
“Iya.”<br />
“Di sinilah dulu aku sekolah.” Kenangku sambil<br />
melihat-lihat dari luar posisi ruang perpustakaan yang<br />
dulu sering aku bawa buku-bukunya tanpa pengetahuan<br />
36
guru. Ruang itu sekarang telah berubah menjadi ruang<br />
belajar.<br />
“Nak, ruang itu.” Aku menunjukan salah satu<br />
ruangan yang berada di sudut yang tempak dari luar.<br />
“Itu ruangan ketika aku duduk kelas satu.”<br />
Terangku sambil melihat ibuku yang berjalan di<br />
belakangku. dan pikiranku melayang jauh ketika dulu<br />
pertama kali aku masuk ke kompleks sekolah SD Inpres<br />
ini.<br />
“Aku diantarkan oleh ibukku.” Terangku ke Bdikar.<br />
“Kami berjalan kaki bersama beberapa anak<br />
lainnya yang juga diantar oleh ibu mereka.”<br />
“Ketika itu aku berjalan di belakang ibuku dengan<br />
sangat mantap,” Lanjutku sambil senyum-senyum, aku<br />
masih ingat dengan detail ketika aku pertama kali<br />
memakai seragamku. Seragam merah putih baru,<br />
seragam hasil jahitan perantau minang yang tinggal<br />
dikampungku. Dangan teman-teman sekelas yang<br />
semuanya adalah anak tertua dikeluargannya, Kami<br />
disuruh berbaris dan kemudian masuk ke dalam ruangan.<br />
Di satukan dalam satu ruang kelas. Seorang guru tegak di<br />
depan pintu. Kami menyalami, tapi tidak mencium<br />
37
tangannya. Begitu duduk dengan tangan bersilang dan<br />
bertumpu di papan meja, nyanyian lagu Indonesia<br />
Rayapun berkumandang. Tentu saja kami belum hafal<br />
lagu ini, mistar papan berbahan dasar dari kayu dia<br />
ketuk-ketukan ke papan tulis. Itu memudahkan untuk<br />
menyimak mengikuti intonasi dan resonansi yang keluar<br />
dari mulut Guru yang karismatik itu.<br />
Aku menoleh ke dinding sebelah kananku. Ibuku<br />
masih berada di luar, mengintip melalui celah-celak<br />
jendela yang hanya di tutupi dengan kawat besi. Dia<br />
masih mengendong adikku. Mengendong dengan kain<br />
gendongan bermotif bunga berwarna merah. Kain khas<br />
gendongan bayi yang biasa digunakan di kampungku.<br />
Kain yang sudah pudar warnanya. Kain itu juga yang<br />
digunakannya dulu ketika aku masih bayi. Aku melirik<br />
ibuku karena ada perasaan takut ketika berada di ruangan<br />
kelas ini. Mungkin ini adalah ruang pijakan pertamaku<br />
mengenal dunia yang lebih luas. Aku tentu saja punya<br />
cita-cita tapi aku tidak tahu seperti apa masa depan.<br />
Ketika dia bantu pasang baju seragamku, sebelum<br />
berangkat tadi pagi. Ibuku bilang bahwa dunia ini keras<br />
dan kejam. Pendidikan adalah bekal untuk tidak<br />
38
menjadikan kita predatisme. Jadi predator maupun jadi<br />
mangsa. Tentu saja aku takut.<br />
“Pendidikan akan memandu kamu menuju cita-cita<br />
dan mengenal lebih baik masa depan.” Pesan singkat<br />
ibuku. Dia buru-buru ingin cepat segera sampai di<br />
Sekolah. Ini juga pengalaman pertama dia<br />
menyekolahkan anaknya.<br />
Tegak didepan kelas dengan wajah wibawa namun<br />
pengasih adalah Bapak Abdulah. Biasa pangil dengan<br />
sebutan Bapak Ib, dia guru tua tanpa sertifikasi, dia<br />
menjadi guru sejak pertama sekolah ada di kampungku.<br />
Dari dulu, yang diajarinnya tidak hanya soal penguatan<br />
kognitif, mengajari dan menuntun murid-muridnya untuk<br />
memperoleh pengetahuan melalui aktivitas mengingat,<br />
menganalisis, memahami, membayangkan dan berbahasa.<br />
Dia membekalkan muridnya dengan kemampuan afektif<br />
sebuah sikap tentang kepedulian yang berbasis<br />
pengetahuan.<br />
“Dia membantu membentuk watak perilaku,<br />
perasaan, sikap, emosi dan nilai.” Kenangku ke Bdikar.<br />
Dia tersenyum sambil mengulum permen yang baru di<br />
belinya di sebuah warung depan sekolah.<br />
39
“Seseorang dapat diramalkan perubahannya bila<br />
seseorang telah memiliki kekuasaan dan penguasaan<br />
kognitif.” Dia meyakinkan sekaligus memberikan<br />
motivasi kepada kami.<br />
Aku ingat. Disuatu pagi setelah upacara bendera,<br />
dia pernah bilang bahwa huruf A, B, C bukanlah sebuah<br />
deretan huruf tanpa makna, ada makna yang luas dan<br />
dalam yang terkandung didalamnya. Lalu, dia<br />
menganalogikan tentang gelas, Sambang dan gerigik<br />
(tempat air dari bambu) dan ember. Media ini bukan<br />
hanya media tapi ada substansi yang terkandung<br />
didalamnya yaitu tempat menampung air. Tentu kami<br />
tidak mengerti apa yang dibicarakannya.<br />
Sama seperti fungsi tempat menampung air. Maka<br />
pendidikan yang salah satunya mempelajari huruf/teks<br />
yang membentuk kata, kalimat dan paragrap.<br />
“Semakin besar dan dalam kita memehami media<br />
belajar maka semakin banyaklah yang bisa ditampung.”<br />
Kata Pak Ib. Karena, semakin banyaklah pengetahuan<br />
yang akan tersedot didalamnya. Kita sudah punya tempat<br />
menampung yang kapasitasnya besar sekali. Namanya<br />
otak. Kata John von Naeumann memperkirakan kapasitas<br />
40
otak manusia adalah 35 exabyte atau sekitar 1 milyar giga<br />
dan terdiri dari 100 juta sel saraf neuron.<br />
Dia mulai memancing otak kami berpikir tentang<br />
pembacaan teks yang didalamnya ada konstruksi sosial.<br />
Huruf yang membentuk teks dan setiap teks ini tidak<br />
boleh mengacu pada makna final. Karena, katanya teks<br />
hadir sebagai jejak yang bisa dirunut pembentukannya<br />
dalam sejarah. Itu yang selalu dia katakan kepada kami,<br />
tentu kami tidak paham maksudnya. Yang kami tahu,<br />
kami harus belajar, belajar dan belajar. Belajar membaca<br />
dan belajar menulis.<br />
Dari metode pengajaran yang diterapkannya. Aku<br />
mulai paham bagaimana mempedulikan diri terhadap<br />
pendidikan. Metodelogi psikomotorik yang diajarkan itu<br />
membekas dalam diri kami. Ketelitian misalnya<br />
merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan<br />
kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar<br />
dengan kontrol yang lebih baik dan kesalahan yang lebih<br />
sedikit. Begitu juga dengan perangkaian.<br />
“Kami berlahan mampu merangkai suatu rangkaian<br />
gerakan dengan membuat urutan tepat, atau konsistensi<br />
41
internal antara gerakan-gerakan yang berbeda.” Ceritaku<br />
kepada Bdikar.<br />
Metode ini. salah satunya membuat kami merasa<br />
mencintai dan penduli terhadap huruf-huruf yang ditulis<br />
dengan kapur di papan berwarna hitam. Setelah penuh<br />
tulisan harus segera dihapus dan angka dan huruf itu<br />
berterbangan bersama debu putih memaksa kami<br />
menyimpan berbagai tulisan dalam memori kognitif<br />
kami. Kami kekurangan alat-alat tulis. Buku dan pensil.<br />
Kami harus sehemat mungkin mengunakan lembaran<br />
buku. Untuk satu tahun ajaran. Kami punya hanya satu<br />
buku tulis. Semua pelajaran ada di dalamnya. Untuk<br />
menulis di ujung pensil selalu kami balutkan dengan<br />
karet gelang, fungsinya sebagai penghapus. Menghapus<br />
tulian yang tidak perlu. Kondisi serba kekurangan ini<br />
memaksa kami melibatkan dalam berproses<br />
emansipatoris, bersama-sama mengembangkan diri,<br />
berbagi hafalan lalu menjadi akumulasi pengetahuan.<br />
Kami terbiasa dengan berbagi hafalan dan<br />
pengetahuan. Kalau aku hanya hafal bahwa Jawa Barat<br />
itu berada di Pulau Jawa, lalu teman sebangku menghafal<br />
ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah Bandung, setelah di<br />
42
akumulasi, menjadi kalimat utuhnya adalah Jawa Barat<br />
adalah salah satu Propinsi di Pulau Jawa dan nama Ibu<br />
Kotanya adalah Bandung. Menarik sekali proses berbagi<br />
pengetahuan, proses saling belajar yang diajarkannya.<br />
“Apakah dulu ada PS?” Bdikar menyela. Aku tahu<br />
maksudnya playstation, tempat ngumpulnya anak-anak<br />
kota setelah pulang sekolah.<br />
“Belum ada”<br />
“Ketika itu di Desa kami hanya ada 1 buah<br />
televisi.” Jawabku.<br />
“Tipi desa.” Bdikar tertawa ketika aku sebut tipi.<br />
Televisi milik desa. Televisi ini hanya di hidupkan dari<br />
jam 19.00-21.30 oleh Kepala Desa. Posisinya di rumah<br />
Kepala Desa dan diletakkan di tempat yang agak tinggi.<br />
Kami berjejeran di halaman kediaman Kepala Desa yang<br />
kami sebut Ginde. Kami selalu membawa dan memakai<br />
sarung ketika menonton televisi ini. Fungsinya untuk<br />
menghangatkan tubuh dan menghindar dari gigitan<br />
nyamuk.<br />
“Pasti Bapak tidak tahu dengan Ratchet dan Clank<br />
3. Game, Dead to Rights” kata Bdikar mengejek.<br />
43
“Yang aku ingat, ketika itu bulan September.”<br />
Jawabku. Tepat jam 21.00 ada gambar hitam putih dunia<br />
yang berputar. Kemudian ada tulisan Dunia Dalam Berita<br />
dan ucapan selamat malam dari penyiarnya, Laki-laki<br />
berambut ikal. Berita tentang Pembantaian Sabra dan<br />
Shatila. Pembataian ini terjadi pada September 1982 di<br />
Beirut Lebanon yang saat itu diduduki oleh Israeal,<br />
dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas<br />
para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra<br />
dan Shatila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di<br />
bawah komando Elie Hobeika yang belakangan menjadi<br />
anggota parlemen Lebanon. Aku takut, marah, ketika<br />
menonton berita ini, seperti ada keberanian di dadaku.<br />
Predatisme telah terjadi.<br />
“Kan sama dengan Disgaea, Hour of Darkness,”<br />
kataku tidak mau kalah dengan anakku. Game ini yang<br />
diperankan Laharl anak Raja Krichevskoy yang arogan<br />
untuk membuktikan bahwa ia adalah penguasa terkuat di<br />
Netherworld setelah ayahnya meninggal.<br />
Televisi yang hanya satu-satunya ini menjadi alat<br />
konsolidasi dan soliditas di kampung. Kami menikmati<br />
aroma daki dan keringat ketika berdesakan untuk<br />
44
mendapatkan posisi strategis untuk bisa menonton<br />
televisi. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua<br />
menikmati tabung ajaib berukuran 14 inch ini. Televisi<br />
ini juga jadi wadah interaksi dan berbagi informasi bagi<br />
tua-tua kampung.<br />
“Mereka membicarakan sesuatu yang telah mereka<br />
tonton, terutama berita-berita dunia yang sudah<br />
disampaikan oleh penyiar berambut ikal itu.”<br />
“Itu sama dengan kalian yang suka cerita tentang<br />
jagoan kalian di PS itu.” Kataku ke Bdikar.<br />
Setelah televisi dimatikan. Penonton bubar, orangorang<br />
tua saling berkunjung. Mereka mengobrol banyak<br />
hal sebelum mereka pulan dan tidur. Dikampung mereka<br />
menyebutnya “becelomok”. Mengobrol tentang berbagai<br />
hal. Di mulai dari obrolan tentang pekerjaan,<br />
perkembangan kampung, tentang ilmu kanuragaan,<br />
tentang aji-ajian dan biasanya diakhiri dengan kajian<br />
tasawuf yang mereka sebut dengan Kaji Dalam.<br />
“Obrolan ini bisa sampai malam.” Kataku. Bahkan<br />
ada yang sampai ayam berkokok, sampai subuh. Untuk<br />
belajar tentang kajian dalam ini, sang murid rela berjalan<br />
jauh hanya untuk bertandang dan menemui sang Guru.<br />
45
Bahkan mereka dengan suka rela membantu pekerjaan<br />
yang sedang guru kerjakan, misalnya menebang hutan<br />
dan membersihkan kebun dan sawah. Itu semua<br />
dilakukan agar bisa belajar.<br />
Aku tidak suka membuka pelajaran sekolah ketika<br />
di rumah. Aku lebih suka duduk dan kemudian ikut<br />
hanyut di obrolan tua-tua kampung. Sesekali ketika<br />
mereka sibuk berinteraksi dan berdiskusi, aku yang<br />
paling kecil dan belum tahu apa-apa sering diminta untuk<br />
mengungkapkan pendapat. Kadang-kadang mereka<br />
tertawa lalu membenarkan pendapat yang aku<br />
kemukakan, pendapat yang keluar dari tema obrolan<br />
mereka.<br />
Ketika masuk sesi tentang ilmu kanuragan/ilmu<br />
batin. Aku suka mencuri-curi dengar. Aku rela menjadi<br />
tukang pijit atau tukang pembuat kopi. Butuh kerja keras<br />
untuk menghidangkan kopi. Aku harus ke dapur dan<br />
menghidupkan api dengan pokok kayu. Kalau kayunya<br />
basah dan belum kering, merahlah mata. Kita harus lama<br />
meniup agar bara menjadi api. Dan rasa pedih dimata itu<br />
akan terbalas ketika ada imbalan. Imbalan pengetahuan<br />
Kaji Dalam.<br />
46
Beberapa dari mereka dengan suka rela<br />
menurunkan ilmu dan jampi-jampi, aku diharuskan<br />
menghafalkan jampi-jampi tersebut tetapi tidak boleh di<br />
catat. Itu di sela-sela Kaji Dalam. Ada satu jampi yang<br />
masih aku hafal sampai saat ini, mereka bilang jampi<br />
pelet. Tentu saja aku senang menghafalnya. Setelah hafal<br />
di luar kepala, akupun merapalkannya dekat nenek yang<br />
biasa aku sebut dengan Sebei. Akulah satu-satunya cucu<br />
kesayangannya diantara tujuh puluh enam orang cucunya.<br />
Dia tertawa, lalu dia bilang itu jampi untuk memotong<br />
pusat bayi. Aku tersipu malu dan jengkel karena dikibuli<br />
oleh tua-tua kampung. Bdikar tertawa mendengar<br />
ceritaku.<br />
“Tapi demikianlah caranya mereka melestarikan<br />
dan menurunkan ilmu. Beberapa kali jampi-jampi ini<br />
dimodifikasi menjadi sepeti nyanyian. Ternyata itu<br />
strategi agar cepat diingat dan dihafal.” Bdikar mulai<br />
berkeringat karena matahari semakin meninggi. Lalu, aku<br />
berikan dia topi untuk menutupi kepalanya.<br />
“Suatu hari aku pernah ikut diminta oleh mereka<br />
menyelesaikan kasus adat.” Kataku sambil membenarkan<br />
letak topi di kepalanya.<br />
47
“Kasus apa.”<br />
“Seperti Game Special Enquity itu ya.” Dia suka<br />
sekali memainkan game Game Special Enquity.<br />
“Kasus pencemaran sungai.” Jawabku.<br />
“Tiba-tiba ikan di sungai tempat biasanya kami<br />
mandi dan bersenda gurau itu banyak yang mati. Bisanya,<br />
ikan-ikan tersebut hanya boleh diambil dengan pancing,<br />
jala dan alat-alat tradisional. Sungai menjadi memutih<br />
dan bau menyengat bangkai ikan. Lalu masyarakat<br />
seperti panen, sebagian mengambil ikan-ikan yang besarbesar<br />
dan masih segar, sebagian diam saja karena takut<br />
dengan racun yang membunuh dan terkandung didalam<br />
tubuh ikan.”<br />
“Ini akibat pencemaran yang disengaja?” Potong<br />
Bdikar.<br />
“Ia.”<br />
“Dari aromanya ini Racun Endrin kata salah<br />
seorang tetua kampung ketika itu,” Aku masih ingat betul<br />
dengan tetua yang duduk bersarung dipingir sungai ketika<br />
meneliti ikan yang mati. Ketika waktu SMP aku baru<br />
tahu bahwa Racun Endrin ditumpahkan di sungai. Racun<br />
48
ini termasuk dalam golongan Rodentisida untuk<br />
membasmi tikus.<br />
“Racun berwarna putih ini tidak larut dan terurai di<br />
dalam air, sehingga sepanjang aliran sungai akan teracuni<br />
oleh racun ini.” Kataku seperti agen NYPD dalam Game<br />
Special Enquity.<br />
“Tua-tua kampung berkumpul, dan tidak ada yang<br />
bisa dijadikan tersangka pada kasus ini.” Bdikar<br />
tersenyum, seperti senyum melecehkan agen NYPD<br />
gagal memecahkan kasus.<br />
“Racun Endrin ini punya daya rusak luar biasa,<br />
berbeda dengan Tuba alam dari jenis-jenis tumbuhan<br />
yang biasa digunakan untuk meracun ikan.”<br />
“Tuba?” tanya Bdikar.<br />
“Tuba itu Racun alami yang di ambil dari sejenis<br />
tanaman” Terangku. Tuba yang biasa digunakan adalah<br />
dari jenis Derris elliptica Bth anggota suku Fabaceae<br />
(Leguminosae) yang memiliki kandungan rotenona<br />
(rotenone), sejenis racun kuat untuk ikan dan serangga<br />
(insektisida) tapi cepat larut dan terurai dalam air,<br />
interval pengaruhnya tidak lama dan panjang.<br />
“Tapikan merusak juga?”<br />
49
“Tuba tidak membunuh semua jenis ikan.”<br />
Jawabku.<br />
Pada proses peradilan adat. Terjadi dialog dan<br />
debat di antara tetua kampung, akhirnya mereka<br />
bersepakat memutuskan bahwa kasus ini tersangkanya<br />
adalah semua warga desa. Semua warga desa wajib turut<br />
membayar denda untuk memulihkan keseimbangan<br />
sosiologis. Masyarakat sudah saling curiga.<br />
Keseimbangan alam juga terganggu, maka harus segera<br />
dipulihkan, kata Tetua. Mereka sepakat akan<br />
mengadakan ritual adat. Diadakanlah “kedurai”. Ritual<br />
adat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada<br />
penguasa gaib dan penjaga sungai. Permohonan maaf<br />
karena telah bersalah dan lalai kepada makluk yang<br />
terdapat disepanjang sungai.<br />
“Kelestarian sungai ini menjadi penting bagi warga<br />
kampung.”<br />
“Sore nanti berenang lagi ya pak!”<br />
“Kalau cepat pulang dari sawah kita berenang lagi.”<br />
Jawabku.<br />
Kami mengangap bahwa Sungai seperti aliran<br />
darah dalam tubuh manusia, sungai tersebut sebagai saksi<br />
50
perjalan panjang sebuah peradaban, sungai ini menjadi<br />
sumber utama pengerak dan sumber hidup ekosistem<br />
yang berada pada daerah hamparan daerah alirannya.<br />
Ceritaku betapa pentingnya sungai.<br />
“Dan, sungai tempat berenang.” Potong Bdikar<br />
sambil tersenyum.<br />
Kalau sungai ini tergangu maka terganggulah hidup<br />
warganya. Orang kampung menyebut mencemari sungai<br />
dengan ungkapan “berkirim surat ke laut”, dan<br />
mempercayai bahwa polutan yang dibawa oleh sungai itu<br />
akan bermuara di pusaran laut atau posok laut.<br />
“Pusaran laut.?” Tanya Bdikar.<br />
”Meskipun belum pernah melihat, mereka percaya<br />
pusaran laut ini membentuk maelstorm, memicu<br />
terbentuknya pusaran air yang besar dengan<br />
downdraft yang sangat kuat.”<br />
“Pada pusaran ini mereka mempercayai sebagai<br />
tempat berkumpulnya induk penyakit. Ketika “surat”<br />
yang dikirim lewat sungai itu diterima, surat itu pasti<br />
berbalas dan balasannya berupa penyakit.<br />
“Oh,”<br />
51
“Maka Kedurai itu menjadi penting sebagai sebagai<br />
bentuk dan pengakuan kesalahan berkirim surat.”<br />
“Bapak diminta membantu menyiapkan kebutuhan<br />
ritual.” Terangku.<br />
Ritual Kudurai dilaksanakan diatas batu besar<br />
ditengah arus yang mengalir. Aku duduk di samping<br />
kanan Dukun (orang yang dianggap bisa berkomunikasi<br />
dengan alam dan gaib). Aku mendengar dengan jelas<br />
jampi-jampi yang dirapalkannya sambil membakar<br />
kemenyan di dupa yang disiapkan ibu-ibu dikampung.<br />
Kemenyan di bakar di atas dupa dan asap mengepul<br />
berbau pengap. Ada nuansa mistis yang sangat kuat<br />
ketika itu, seakan-akan jari pada dedemit dan para dewa<br />
membelai tubuh kami. Aku merasakan bulu-bulu<br />
ditubuhku mulai tegak. Aku merinding.<br />
Begitu asap kemenyan menari di udara. Beras<br />
kuning yang diwarnai dengan kunyit di taburi ke sungai.<br />
Komat-kamit mulut Dukun merapalkan “hai sepanjang<br />
hidung, hai sepajang hidung, hai sepanjang hidung, dio<br />
uku madep kumu, kumu do tekadeak temungau biyoa,<br />
kemuaso biyoa, temungau tang aai, kumu kulo do jemago<br />
lot ngen ai tang aai, uku medeu kumu bae ngami, asep<br />
52
kemenyenku melayang, belas kemunik uku mamua, awei<br />
o kulu adat bahasoku ngenkumu, dio ade iben ngen<br />
rokok, awei o kulu pembuk pangen kumu berupo sabai,<br />
baso uku menok kedeu kumu yo, uku lok madea keturuak,<br />
baso bilai yo bilai baik bulen betuweak................”. setiap<br />
helaan napas, beras kuningpun di taburi di sungai.<br />
Kedurai selesai. Wajah kami kembali berseri.<br />
Anehnya, tidak ada lagi rasa kecurigaan diantara kami.<br />
Kami telah mengakui dan menanggung kesalahan yang<br />
hanya dilakukan oleh satu orang secara bersama-sama.<br />
Sebelum pulang si Dukun bilang ke kami.<br />
“Permintaan maaf telah diterima secara bersyarat.” Surat<br />
akan berbalas ketika kami mengulang kesalahan yang<br />
sama.<br />
Si Dukun dan tetua kembali ke kampung dan kami<br />
masih bermain-main dan mandi disungai. Kami berenang<br />
sampai dingin menggigil. Setelah merasa dingin kamipun<br />
menghangatkan badan dan berjemur dengan<br />
menempelkan badan kami pada batu-batu panas karena<br />
terik matahari.<br />
53
Sambil berjemur memeluk batu, aku dan kawankawan<br />
seumuran mulai mendekontruksi proses Ritual<br />
akibat “berkirim Surat ke laut”.<br />
“Lalu, kami tahu maksudnya,”<br />
“Apa?”<br />
“Rapalan mantera itu seperti teks yang hadir<br />
sebagai jejak yang bisa dirunut pembentukannya dalam<br />
sejarah.” Jawabku. Teks ini hadir dan berkembang seiring<br />
perkembangan budaya, berjalan menuju kesempurnaan<br />
melalui dialog yang orang awam tidak akan tahu<br />
maksudnya. Rapalan ini seperti berkamuflase, dinamis<br />
dan bermetamorfosis menuju keseimbangan, dan pada<br />
titik ini, rapalan ini akan menjadi bagian dari sebuah<br />
peradaban. Terangku. Pasti Bdikar tidak mengerti apa<br />
yang sedang aku jelaskan.<br />
“Setelah mandi kami berjemur seperti anak<br />
biawak.” Bdikar tertawa. Terlalu lama berjemur kulit<br />
kami biasanya menghitam lalu mengelupas. Setelah<br />
badan hangat kami kemudian terjun lagi ke sungai.<br />
Ceritaku.<br />
54
Tidak terasa kami berjalan sampai disebuah tebing.<br />
Dari atas tebing ini tampahlah hamparan sawah yang<br />
menguning.<br />
“Itu sawah nenekmu” kataku.<br />
Seharian kami bercengkrama, keliling sawah,<br />
memancing, makan, duduk menikmati sepoi sangin dan<br />
aroma padi. Sore ini kami tidak jadi berenang. Bdikar dan<br />
adiknya keasikan mandi di pancuran dari bambu yang<br />
dibuat oleh kakeknya.<br />
55
4<br />
Aku dibangunkan pagi-pagi oleh Ibuku, dan itu<br />
pagi sekali. Dia suruh aku sholat subuh. Kedua anakku<br />
masih meringkuk kedinginan. Istriku sudah bangun dan<br />
bersiap-siap sholat subuh. Kami sholat berjamaah yang di<br />
imami oleh Bapakku. Setelah sholat aku ke dapur.<br />
Minum kopi dan menghangatkan badan di tungku dan<br />
menunggu pisang yang berenang berubah warna menjadi<br />
kuning kemerah-merahan yang di goreng istriku.<br />
Pikiranku melayang aku inggat ketika kecil dulu.<br />
Ketika kokok pertama ayam jantan, ketika aku<br />
meringkuk dengan lutut menempel di dagu di gulung<br />
selimut lusuh dan robek. Selimutku tariknya. Hawa<br />
dingin kembali menusuk-nusuk sampai sum-sum. Aku<br />
disuruh mandi, cukup lama aku duduk dekat ember<br />
penampung air, duduk sambil berhayal mentransfer<br />
energi panas ke dalam wadah air. Berharap ketika air<br />
tersebut nempel dikulit tidak mengeluarkan uap asap<br />
akibat reaksi kulit ketika bertemu dengan dinginnya air.<br />
Di kampungku ketika itu, minyak goreng saja beku, harus<br />
diiris pakai pisau kalau mau digunakan untuk mengoreng.<br />
56
Dinginnya luar biasa, belum ada pengaruh rumah kaca<br />
dan pemanasan global. Semuanya masih berjalan normal.<br />
Keteraturan cuaca dan keteraturan musim berjalan pada<br />
sistem alami dan tunduk pada skema alam.<br />
“Cepat mandi, kita mesti cepat nanti tidak kebagian<br />
tempat sholatnya.” bahasa perintah Ibuku ini membuat<br />
gagal transfer energi panas ke dalam ember tempat<br />
menampung air. Dan benar saja ketika guyuran air<br />
membasahi tubuhku, uap asappun keluar, aku seperti<br />
kena malaria stadium empat, gemetar kedinginan, lutut<br />
tidak bisa tegak lurus dan gigi atas dan bawahku saling<br />
bertabrakan. Pagi itu adalah hari Lebaran/idul fitri 1402<br />
H, lebaran di tahun 1982. Kami menyebutnya bilai rayo<br />
atau hari lebaran.<br />
Bersama ibu dan bapakku kami berangkat ke<br />
Masjid yang tidak jauh dari rumah, aku duduk samping<br />
Bapakku. Berdua berbagi sejadah. Masjid ini kata ibuku<br />
adalah cenderamata dari Ayahnya, masjid permanen<br />
pertama di kampungku ini dibangun oleh tangan<br />
Kakekku. Ayah dari ibuku. Maka setiap pulang dari<br />
masjid, terutama setelah sholat idul fitri atau lebaran, Ibu<br />
dan nenekku pasti menangis sedih, dan itu berlangsung<br />
57
lama. Aku tahu dia pasti rindu dengan ayahnya. Masjid<br />
kenangan ini mampu mengugah ingatan kolektif keluarga<br />
kami terhadap kakek yang kini sudah tiada.<br />
Pulang sholat. Kampung masih berkabut, tapi<br />
udaranya segar dan dingin, dinginnya seperti nempel<br />
dikulit dan menusuk-nusuk ke tulang. Lalu, kami<br />
hangatkan tubuh dengan kue tanpa pengawet buatan<br />
ibuku. Sambil menikmati kerenyahan kue, telinggaku<br />
juga menikmati tangisan rindu ibuku pada Ayahnya. Air<br />
mata itu obat. Obat mereduksi rindu. Dia rindu dengan<br />
ayahnya yang telah tiada dan itu bisa lama kalau ada<br />
saudaranya yang lain datang ke rumah. Jadilah ritual<br />
menagis. Sampai aku hapal nada dan cara mereka<br />
menagis. Biasanya tangisan itu akan berhenti ketika<br />
Kakak tertua Ibuku datang. Dia pemimpin tertinggi<br />
dikeluarga kami. Dialah presentatif Kakekku di keluarga<br />
patrilinial kami. Aku punya tradisi, biasannya ketika dia<br />
datang. Langsung aku pijit betisnya. Karena pasti ada<br />
kejutan-kejutan yang akan keluar dari mulutnya, mulut<br />
yang hapal habis isi Al Quran. Kedatangannya juga akan<br />
meredakan tangisan komunal yang aku hapal di luar<br />
kepala pemiliknya<br />
58
“Kita tidak mungkin menentukan secara mutlak<br />
momen kematian, karena fisiologi membuktikan bahwa<br />
kematian bukanlah sesuatu fenomena yang langsung dan<br />
sejenak, tapi suatu proses yang berlangsung lama,”<br />
Katanya membuka obrolan dan aku menganguk tanda<br />
tidak mengerti dan dia tersenyum kemudian sambil<br />
merebahkan kepalanya setalah memakan makanan yang<br />
sudah disiapkan ibuku.<br />
“Begini, setiap makluk hidup itu adalah momen<br />
yang sama atau berbeda,”<br />
“Nah,”<br />
“Dalam setiap momen kematian misalnya, ketika<br />
sel-sel tubuh itu sendiri mengalami kematian maka pada<br />
momen yang lain membangun sendiri yang baru.”<br />
Lanjutnya. Dan. Akupun tambah tidak mengerti, umurku<br />
baru 6 tahun ketika itu, masih kelas 2 SD dan belum<br />
lancar baca tulis.<br />
Sambil menyengir dan memijit betisnya, aku lihat<br />
dia mulai tertidur, lalu pikiraku melayang. Aku membuat<br />
tafsir bebas. Sesuka hatiku. Mungkin ini bentuk dari<br />
patah tubuh hilang berganti yang sering aku dengar dari<br />
celoteh tetua kampung kalau mereka sedang berkumpul.<br />
59
Mereka juga beranggap bahwa setiap makluk hidup<br />
adalah dirinya sendiri namun juga sesuatu yang lain dari<br />
dirinya.<br />
Jadi Kakekku boleh saja meninggal. Dia tetap<br />
bagian dari kami, tapi kami tetap harus hidup. Lalu,<br />
merefleksi apa yang telah dia lakukan, kemudian berbuat<br />
dan merancang untuk perkembangan berkesinambungan.<br />
Tentu kami harus lebih baik dari beliau dan menjadikan<br />
kebaikan ajaran dan jejaknya sebagai alas pijakan kami.<br />
Imajinasiku mulai berdialektika.<br />
“Itu masa lalu, kemudian masa kini lalu masa<br />
depan, kesemuanya adalah proses pembentukan sejarah.”<br />
jawab teman imajiku yang keluar tiba-tiba dari dalam<br />
sarung yang aku pakai lalu menghilang.<br />
Pada lebaran tahun itu, tidak ada baju baru yang<br />
dibelikan ibuku seperti anak-anak lainnya. Bagiku harihari<br />
itu berjalan sangat alami, alami dalam<br />
kesederhanaan. Tidak perlu yang baru. Yang penting<br />
tangisan mereda. Sepertinya kedatangan kakak tertua<br />
ibuku mampu secara simbolik mengantikan kehadiran<br />
Ayahnya. Buktinya, tidak ada lagi bunyi tangisan.<br />
60
Semua saudara dari keluarga ibuku sudah<br />
berkumpul. Di Dalam tradisi. Setiap keluarga harus<br />
mempunyai rumah tua. Tempat pulang. Rumah ibuku,<br />
rumah peninggalan Kakekku. Disepakati sebagai “Rumah<br />
Tua”. Rumah tempat pulang dan berkumpul keluarga<br />
besar kami. Keluarga besar yang dihitung atas akumulasi<br />
lima generasi di atas kakekku, beserta keturunannya. Jadi<br />
aku tidak perlu capek-capek berkunjung kerumah saudara<br />
kami kalau lebaran untuk maaf-maafan, cukup tunggu<br />
dan duduk-duduk dirumah, lalu mereka yang akan datang<br />
dengan sendirinya. Aku menikmati dan kebagian berkah<br />
dari fungsi “rumah tua” ini.<br />
Dan belum lagi kalau dihitung, aku satu-satunya<br />
anggota kelurga yang disayangi dalam keluarga besar ini.<br />
Di sayang karena berpenyakitan, aku sejak lahir sampai<br />
umur sepuluh tahunan aku selalu diserang oleh berbagai<br />
penyakit dan selalu jenisnya bergantian, sumber penyakit<br />
terlalu dekat dengan tubuhku, penyebab utamanya pasti<br />
karena kurangnya asupan dan suplai gizi.<br />
Setelah semuanya berkumpul, ibu dan para<br />
saudaranya menyiapkan makanan untuk syukuran. Kami<br />
menyebutnya Beduo, berdoa yang diakhiri dengan makan<br />
61
ersama. Ini bentuk pesta makan setelah satu bulan<br />
berpuasa. Setelah pesta dan doa makan, tradisi<br />
selanjutnya mengunjungi makam tua yang terletak di<br />
ujung desa. Makam ini dipercayai sebagai makam leluhur<br />
yang melahirkan tradisi adat dan agama di Kampungku.<br />
Semua warga kampung berkumpul di makam ini. Ada<br />
yang hanya berdoa, membaca yasin, membayar nazar<br />
bahkan mengucapkan tekat, niat dan keinginan. Bisanya<br />
mereka berjanji akan membangun kuburan, memasang<br />
atap, memotong kambing dan macam-macam ketika<br />
keinginan mereka terkabul.<br />
Jaraknya cukup jauh untuk sampai ke makam ini.<br />
makam ini berada di ujung desa, dia atas jurang. Dalam<br />
perjalanan ke Makam untuk bersiarah. Aku berhayal.<br />
Penghuni Kubua Penungea (nama kompleks kuburan)<br />
pasti dimasa hidupnya telah banyak meninggalkan jejak<br />
entitas. Sesuatu yang sungguh ada. Diketahui dan jadi<br />
acuan karena mengandung ajaran mungkin saja sangat<br />
ideologis. Buktinya ada eksistensi fisik yang reflektif<br />
sehingga kami anak keturunannya bisa memamahi<br />
sejarah kami. Dan bersimpul di makamnya.<br />
62
“Ada pohon sejarah yang sukses dengan fondasi<br />
akar yang kuat, batang yang menjulang dan ranting yang<br />
merindang serta buah sejarah yang bisa dinikmati<br />
sepanjang musim. Lalu ada pohon sejarah yang rapuh,<br />
akar yang tercabut dari bumi, akhirnya mudah runtuh<br />
dan rubuh.” kata ibuku yang tiba-tiba berjalan<br />
disampingku. Dia membawa tikar, buku yasin dan teko<br />
tempat air.<br />
Antrian panjang sekali di makam tua ini, setelah<br />
bedoa dan tabur bunga. Keluarga besar kami ke komplek<br />
pemakaman kakekku. Keluarga besar kami duduk rapi<br />
mengelilingi kuburan kakekku yang sepertinya sudah<br />
mulai di kramatkan. Belum ada kesepakatan menjadikan<br />
Makam kakekku sebagai Makam Tua. Sepertinya,<br />
mungkin karena wibawa yang besar dalam memimpin<br />
keluarga besarnya menuju pemahaman realitas inderawi.<br />
Sebuah kemampuan memahami dunia luar dari manusia.<br />
Dia dihormati waktu hidup dan matinya.<br />
Menurut cerita dari tua-tua kampung yang pernah<br />
belajar dengan beliau. Kakekku ketika masih hidup<br />
semangat sekali mengajari orang-orang kampung Ilmu<br />
Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Thariqah ini<br />
63
merupakan perpaduan dari dua buah tarekat besar,<br />
yaitu Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah<br />
yang didirikan oleh seorang Sufi Syaikh besar Masjid Al-<br />
Haram di Makkah al-Mukarramah bernama Syaikh<br />
Ahmad Khatib Ibn Abd.Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. inti<br />
pokok ajarannya adalah sama-sama menekankan<br />
pentingnya syari'at dan menentang faham Wihdatul<br />
Wujud, menuntun pada kesempurnaan suluk, adab (etika),<br />
dzikir, dan murakabah. Secara sederhana mengajarkan<br />
survive material untuk tetap hidup sehingga mampu<br />
membentuk kesalehan sosial dan kesalehan individu<br />
berjalan secara pararel.<br />
Sepulangnya dari kuburan, aku sempat bermainmain<br />
dengan teman-teman sekampung yang berbanga<br />
dengan baju barunya, ada perasaan minder ketika itu.<br />
Cuma aku yang tidak memakai baju baru. Tapi tidak apaapa.<br />
Bukankah sehari setelah lebaran baju itupun jadi<br />
barang usang. Kemudian, menjadi bagian dari masa lalu.<br />
Bagian dari sejarah.<br />
“Ini realitas historis,”<br />
“Realitas yang berubah.” Aku menghibur diri<br />
sendiri.<br />
64
Oleh karena itu, konsepsi kita terhadap sejarah<br />
haruslah bermula dan berdasar pada realita yang utuh,<br />
seperti setiap makluk hidup adalah dirinya sendiri namun<br />
juga sesuatu yang lain dari dirinya, kata-kata yang selalu<br />
diucapkan para tetua dikampungku berfilosofi.<br />
Tentu saja kemudian konsepsi kita tidak boleh<br />
fragmentatif yang memisahkan objek dan subjek,<br />
mengisolasi gerak dalam diam, memutuskan rangkaian<br />
sebab dan akibat, sejauh mana kita melihat realitas,<br />
sejauh itu pula konsepsi kita terbangun, ini adalah<br />
substansi dari ritual Mulang Apei. Ritual pulang. Pulang<br />
kerumah Tua. Mengunjungi makam leluhur. Mulang<br />
Apei, bukan hanya aktivitas kembali ketempat leluhur,<br />
bukan aktivitas secara priodik mengenang sejarah.<br />
Mempelajari artepak-artepak dan jejak leluhur, bukan<br />
pula prosesi metaforis.<br />
“Tetapi, mengajarkan pengungkapan konsepsi<br />
sejarah, konsepsi tentang sejarah panjang dari peradaban<br />
masyarakat manusia.” Kata ibuku ketika menjelang<br />
malam hari. Aku duduk disamping ibuku ketika dia<br />
sedang menyiapkan makan kami dari sisa Syukuran/Doa<br />
siang tadi.<br />
65
“Keluarga yang berkumpul dan menangis-nagis<br />
siang tadi sesungguhnya sedang mengingat sejarah<br />
identitas mereka, mereka sedang melaksanakan kaidahkaidah<br />
formal tradisi.”<br />
“Itulah bentuk peradaban,” Katanya<br />
Peradaban ini menyisihkan dialektika dan kondisi<br />
historis masyarakat lain sebelum kita.<br />
“Jadi nak,” katanya lembut.<br />
“wujud sosial kita yang bisa kita pahami dari<br />
Mulang Apei ini hanya bisa dipahami secara realistis<br />
sebagai individu di suatu masyarakat, tidak ada individu<br />
yang berdiri sendiri di luar kumpulannya.”<br />
“Jadi tujuan masyarakat manusia kapan pun dan<br />
dimanapun adalah hidup, yakni melestarikan hidup dalam<br />
hubungan alamiah dan hubungan sosialnya.” Otakku<br />
belum bisa pahami kata-kata ibuku ini, tapi hatiku<br />
berbunga karena yakin dia pasti pintar seperti Abang<br />
tertuanya, yang selalu aku pijit betisnya setiap ketemu.<br />
Lamunanku berhenti ketika istriku tersenyum<br />
sambil memindahkan pisang goreng dari kuali yang ke<br />
piring, aku menggigitnya. Pisang ini terlalu panas dan<br />
keluar lagi dari mulutku.<br />
66
67
5<br />
Mata hari mulai meninggi. Masuk melalui celahcelah<br />
papan dapur rumah ibuku. Sepiring penuh goreng<br />
pisang sudah berpindah ke perutku. Ibu datang dengan<br />
membawa beberapa ruas bambu muda. Dia ambil dari<br />
rumah tetangga. Gerigik. Demikian sebutan untuk Bambu<br />
muda kalau di fungsikan sebagai tempat air.<br />
“Kita akan masak sambal.” Kata ibuku. Bahanbahan<br />
sudah disiapkan oleh ibuku. Mereka memasukan<br />
semua bahan-bahan ke dalam bambu lalu ditegakkan di<br />
tungku dekat api yang menyala-nyala.<br />
“Bambu ini kalau untuk kentongan, namanya<br />
Ke’tuk” Kataku sambil membenarkan pokok kopi yang<br />
mulai padam apinya.<br />
“Dulu, ketika kecil cita-citamu jadi Pak Sahak”<br />
Kata ibuku tersenyum. Pak Sahak sudah meninggal. Dua<br />
dia bertugas sebagai tukang ke’tuk. Menyampaikan berita<br />
untuk warga kampung. Senyum ibuku mengingatkanku,<br />
mengingat memori yang masih tersusun dengan rapi di<br />
memori di thalamus, dalam ruang otak yang berfungsi<br />
sebagai tempat penerimaan sensor data dan sinyal-sinyal<br />
68
motorik. Memori ini tersusun dengan rapi secara setelah<br />
melalui proses selektif dan subjektif atas pengalaman<br />
masa lalu. Tahun dimana dulu pertama kalinya aku<br />
masuk Sekolah, Sekolah Dasar Inpres. Sekolah ini di<br />
bangun oleh Orde Baru untuk mendukung program wajib<br />
belajar. Merupakan program pembangunan Sekolah<br />
Dasar (SD) di daerah-daerah terpencil. Tujuannya<br />
memperluas kesempatan siswa untuk mendapatkan<br />
pendidikan, mempermudah akses menuju sekolah bagi<br />
siswa yang tinggal di daerah pelosok, memaksimalkan<br />
potensi siswa cerdas. Infrasrukturnya untuk mendukung<br />
program aksarawan fungsional. Program belajar<br />
membaca, menulis dan keterampilan lainnya.<br />
Semua pengalaman, tentang pengalaman masa<br />
pertumbuhan dan perkembanganku disebuah<br />
perkampungan tua dan dingin. Pengalaman itulah yang<br />
berproses dalam ruang lobus temporan ketika kenangan<br />
itu berhubungan dengan bahasa. Bahasa ibu, dan yang<br />
berhubungan dengan ingatan. Ingatanku.<br />
“Belajarlah yang baik, karena masa depan adalah<br />
milik kamu, kamu akan jadi apa saja nantinya dan itu<br />
tergantung dengan apa yang terjadi sekarang, jangan<br />
69
terputus dengan akar meskipun kau sejajar dengan<br />
bintang nantinya.” Kata-kata ini kuat sekali sehingga<br />
terkonsolidasi dalam lobus parietal, dan lobus occipital.<br />
Tempat yang berfungsi sebagai lembaga sensor data pada<br />
otak membantu kita mencerna antara penglihatan dan<br />
persepsi. Aku ingat banyak hal. Tentang batu tempat<br />
ritual, kemenyan, kuburan tua, kain untuk mengendong<br />
adikku. Dan bambu yang dibuat khusus untuk fingsi<br />
ket’uk atau kentongan. Alat andalan di kampungku dulu<br />
untuk menyampaikan sesuatu selain beduk menandakan<br />
buka puasa.<br />
Ke’tuk adalah alat yang masih detail aku ingat baik<br />
bentuk, panjang, besar dan bunyi ketika dipukul. Benda<br />
ini adalah alat yang mampu mensugesti orang sekampung<br />
untuk berkumpul lalu memperhatikan kata-kata yang<br />
keluar setelah ketukan ketiga. Ke’tuk ini terbuat dari satu<br />
ruas bambu yang tengahnya dibuat lobang kemudian<br />
dipukul. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan<br />
Kentongan. Kentongan atau Ke’tuk ini adalah alat<br />
komunikasi, alat konsolidasi sekaligus berperan sebagai<br />
intruksi.<br />
70
Tuk...tuk...tuk...waktu itu habis sholat magrib,<br />
waktu paling efektif untuk menyampaikan informasi,<br />
masyarakat biasanya istirahat dan ada di rumah masingmasing,<br />
lalu aku berlari keluar, karena biasanya Pak<br />
Sahak pasti lewat depan rumah kami untuk<br />
menyampaikan informasi tentang apa saja. Setelah<br />
ketukan tiga kali, suaranya melengking dan<br />
menyampaikan pengumuman “dio periteak kundei<br />
Ginde, bulen adep ite harus tu’un bumai sesamo, api do<br />
lok mok pupuk neak koperasi harus lunas bayar pajak<br />
kileak, amen ati bayar pajak mako akan ade petugas<br />
kemnek tu’un umeak temagiak pajak kumu dau yo” (Ini<br />
perintah Kepala Desa bulan depan sudah boleh turun<br />
sawah, siapa saja yang mau beli pupuk di koperasi<br />
syaratnya harus lunas pajak, kalau belum lunas pajak<br />
maka akan ada petugas yang akan turun naik rumah<br />
untuk menagih tagihan pajak). Aku menirukan Pak<br />
Sahak. Ibuku tersenyum.<br />
“Kau ternyata masih ingat dengan Pak Sahak” Kata<br />
ibuku. Wajahnya berseri.<br />
Pak Sahak, biasa dipangil Pak Sahril, kerena anak<br />
tertuanya adalah Sahrir. Dialah yang bertugas keliling<br />
71
kampung, tidak ada yang bisa mengantikan dia, kecil<br />
tubuhnya tapi lincah, intonasi suaranya lantang, bak<br />
orator ulung, setiap dia menyampaikan pesan, layaknya<br />
sedang di depan massa ribuan orang, anehnya semua<br />
orang diam. Karena dia tidak pernah mau menyampaikan<br />
pesan untuk kedua kalinya, kecuali menyawab<br />
pertanyaan-pertanyaan yang sipatnya teknis.<br />
Ketika itu, aku baru kelas satu SD, maka ketika<br />
ditanya apa cita-citaku. Dengan meyakinkan jawabanku<br />
ingin menjadi “Pak Sahak”. Penyampai berita, tentu saja<br />
seperti Pak Sahak, konten berita mudah dicerna dan<br />
dipahami, setiap kata-kata di turuti, sedikit sekali ruang<br />
diskusi. Seperti demokrasi terpimpin saja. Aku sering<br />
ikut dia berkeliling kampung untuk menyebarkan berita,<br />
kata-katanya jujur dan tidak hiper-realitas, tidak<br />
menciptakan kepalsuan bersatu dengan keaslian, tidak<br />
menciptakan fakta bersimpang siur dengan rekayasa, dan<br />
dusta bersenyawa dengan kebenaran.<br />
Pernah suatu sore, Aku sedang membantu ibuku<br />
menumbuk Padi di samping rumahnya yang sedehana,<br />
lalu adu duduk di teras rumahnya. Ketika itu Pak Sahak<br />
72
sedang membersihkan alat komunikasi andalannya, alat<br />
ini biasanya digantung di depan pintu utama rumahnya.<br />
“Wak, kapan mulainya kita mengunakan alat ini?”<br />
tanyaku.<br />
“Bukan kita nak, Tapi Manusia.” Jawabnya sambil<br />
membenarkan ikatan sarungnya lalu duduk di kursi papan<br />
Sambil menghisap rokok yang terbuat dari daun Nipah<br />
dengan tembakau yang ditanamnya sendiri.<br />
“Sebelum mengenal tulisan, zaman ini disebut<br />
dengan Pra-Aksara, atau zaman palaeolithikum dan<br />
Mesolithikum, manusia ketika itu hidupnya berpindahpindah<br />
lalu untuk memberikan informasi mereka<br />
membuat petroglif atau lukisan dan coretan di dinding<br />
gua, permukaan batu. Gambar lukisan ini biasanya<br />
menceritakan tentang pengalaman dan harapan atas<br />
kehidupan mereka.” Dia mulai bercerita. Aku tertarik,<br />
karena dia memang pencerita yang ulung.<br />
Lalu, dia melanjutkan kembali ceritanya, namun<br />
tidak berapi-api seperti ketika dia menyampaikan<br />
informasi dengan kentongannya.<br />
“Setelah mereka membentuk desa-desa kecil,<br />
mereka perlu melakukan komunikasi satu sama lain yang<br />
73
lebih tinggi intensitasnya. Mereka sudah saling megenal<br />
dan memiliki ikatan emosional satu sama lain. Dan pada<br />
zaman logamlah komunikasi ini semakin insten, zaman<br />
ini telah tersusun golongan masyarakat dengan<br />
kemunculan golongan undagi atau kelompok yang<br />
memiliki keahlian menciptakan barang. Pembagian kerja<br />
mulai teratur. Mereka butuh alat komunikasi dalam<br />
menjalankan sistem transaksi.” Penjelasannya berhenti.<br />
Istrinya yang sering mengurut perutku kalau aku<br />
sedang sakit itu keluar membawa pisang yang sudah<br />
digoreng, dari aromanya, goreng pisang ini pasti di<br />
goreng dengan minyak buah Kepahiang.<br />
Dia melanjutkan ceritanya.<br />
“Sekitar abad ke-2 SM.” Katanya. Banyak yang<br />
mengunakan kuda untuk mengirim pesan, misalnya di<br />
Mesir dan Cina, lalu mereka membangun stasiun<br />
pengirim pesan, sebagian ada yang mengunakan sinyal<br />
api dari stasiun tersebut. Dan Bangsa Romawilah yang<br />
berjasa mengembangkan jasa pos mereka menyebutnya<br />
Cursus Publicus yang nantinya diwarisi oleh Kekaisaran<br />
Bysantium. Fungsi Cursus Publicus ini untuk<br />
mengirimkan pesan, surat resmi dan pajak antar wilayah.<br />
74
Mereka juga tercatat sebagai penguna pertama Heliograf,<br />
cermin untuk mengirimkan pesan. Cermin ini<br />
mengunakan pantulan dari sinar matahari. Aku<br />
mengangguk sambil menelan goreng pisang suguhan<br />
istrinya Pak Sahak, sambil terkagum-kagum dengan<br />
pengetahuannya tentang pekerjaan swadaya yang<br />
digelutinya. Swadaya, karena dia tidak pernah dibayar<br />
atas pekerjaanya sebagai penyampai pesan itu.<br />
“Ke’tuk.” Lanjut Pak Sahak, adalah alat<br />
komunikasi yang dikembangan sejak abat ke-2 SM<br />
namun masih efektif digunakan sampai saat ini.<br />
“Ini sungguh suatu bentuk keajaiban alat<br />
komunikasi.”<br />
“Perkembangannya tidak banyak,” Sambung Pak<br />
Sahak.<br />
Beberapa perubahan hanya pada ritme ketukan,<br />
ketukan ini kemudian menjadi sugesti, ketukan<br />
menyampaikan informasi, tentu berbeda dengan ketukan<br />
ketika adanya bencana, dan lain-lain. Dia mengajariku<br />
soal kode bunyi.<br />
“Kenapa Ke’tuk ini bisa bikin orang tersugesti dan<br />
bertahan sampai saat ini? Karena konten berita yang<br />
75
disampaikan jujur dan tidak hiper-realitas, tidak<br />
menciptakan kepalsuan bersatu dengan keaslian, tidak<br />
menciptakan fakta bersimpang siur dengan rekayasa, dan<br />
dusta bersenyawa dengan kebenaran.” Kata-kata terakhir<br />
ini diucakannya dengan menaikan intonasi suaranya.<br />
Nanti. Aku berhayal. Di Kampungku tidak ada lagi<br />
Pak Sahak, atau generasi penerus Pak Sahak. Alat<br />
komunikasi pasti berkembangan. Akhir abad ke-20 wajah<br />
dunia berubah, itu yang aku dengar obrolan tua-tua<br />
kampung. Perubahan ini dibentuk oleh riuh rendah<br />
citraan elektronik (televisi, film, game, virtual reality,<br />
foto digital, internet).<br />
Perkembangan teknologi digital ini pasti tidak<br />
mampu mensugesti seperti kata Pak Sahak. Tetapi telah<br />
membawa fantasi manusia menembus batas, menciptakan<br />
ruang-ruang tiga dimensi berikut obyek-obyek di<br />
dalamnya, sampai pada tahap di mana realitas visual telah<br />
dilampaui dengan manipulasi pencitraan visual, sehingga<br />
seolah manusia melangkah dari dunia nyata menuju dunia<br />
fantasi, dunia maya yang tampak nyata.<br />
Permasalahannya pasti menjadi semakin rumit<br />
ketika komunikasi ini menjadi sangat massal, kerumitan<br />
76
ini bertambah ketika dihadapkan pada realita bahwa<br />
perkembangan teknologi tersebut membawa pula dampak<br />
negatif. Itu terjadi pada saat teknologi memuaskan<br />
hasrat/nafsu manusia, memberikan pesona ekstasi, maka<br />
nilai-nilai moral seakan rontok satu per satu. Karena<br />
komunikasi ini menciptakan sejarah simulacra, sejarah<br />
imitasi, reproduksi persoalan makna, orisinalitas dan<br />
identitas.<br />
“Ke’tuk,” aku peluk ke’tuk yang sudah dibersihkan<br />
oleh Pak Sahak sebelum dia gantung di atas tangga<br />
beranda rumahnya. Pasti benda ini nantinya berganti<br />
dengan nilai guna komoditas dan nilai imperatif sebuah<br />
produksi. Pun berganti digantikan oleh model, kode,<br />
tontonan dan hiperrealisme “simulasi”.<br />
Perubahan ini sudah pasti membuat semua orang<br />
terjebak dalam permainan simulacra yang tidak<br />
berhubungan dengan "realitas eksternal". Akhirnya<br />
kitapun hidup di dunia simulacra, dunia yang dipenuhi<br />
citra atau penanda.<br />
“Ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan<br />
simulasi.”<br />
77
“Tidak nyata, dan tidak asli. Dimana<br />
masyarakatnya sudah sirna dan digantikan oleh massa.”<br />
“Massa yang tidak mempunyai predikat, atribut,<br />
kualitas maupun reference.”<br />
“Pendeknya, massa tidak mempunyai realitas<br />
sosiologikal.”<br />
Ah, nanti ketika aku sudah besar pastilah aku<br />
merindukan duduk diteras rumah Pak Sahak. Kemudian<br />
mengikuti dia ketika keliling Kampung buat<br />
menyampaikan berita.<br />
Api terlalu besar, sambal dalam bambu meloncatloncat<br />
tumpah. Aku buru-buru menarik beberapa pokok<br />
batang kopi dan api mengecil.<br />
“Ingat Pak Sahak?” tanya ibuku.<br />
“Bukan, aku ingat dengan istrinya yang suka<br />
mengurut perutku dulu.” Kataku berbohong. Aku<br />
menciptakan kepalsuan bersatu dengan rekayasa, dan<br />
bersenyawa dengan dusta.<br />
Tapi ibuku tahu aku berbohong.<br />
78
6<br />
Hari minggu, seperti biasa aku harus bangun cepat<br />
pagi ini, kebiasaan menemani ibuku menyiapkan<br />
santapan pagi untuk kami sekeluarga membuat aku<br />
terbiasa bangun cepat. Ibuku hanya punya dua anak lakilaki,<br />
kondisi inilah yang mendidik kami untuk terlibat<br />
membantu pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh anak<br />
perempuan, mengiris bawang, mengiling cabe dan<br />
menanak nasi adalah bagian tugas rutin dan menjadi<br />
salah satu keahlianku. Selain makan dan duduk<br />
bermalasan dekat tungku menemani ibuku memasak.<br />
Tidak pedulilah aku dengan dinginnya pagi, bagiku<br />
menemani ibu pagi-pagi adalah kebangaaan, kebangaan<br />
seorang anak laki-laki tertua dikeluarga kecil kami. Dan<br />
aku tahu ada banyak ekspektasi yang dibebankan<br />
dipundakku nantinya. Dan, yang paling penting bagiku,<br />
ibuku adalah segala-galanya, dia pertama bagiku, guru<br />
pertamaku, cinta pertama dan tidak akan pernah<br />
tergantikan oleh apa dan siapapun.<br />
79
“Dapur ini dulu tinggi. Kami punya kandang itik di<br />
bawahnya.” Bdikar duduk di samping neneknya.<br />
Menemani nenek dan ibunya memasak.<br />
“Setelah ruang dapur ini di renovasi, dapur ini<br />
direndahkan posisinya oleh Kakekmu,” Kata ibuku ke<br />
anakku, Bdikar. Bapakmu suka sekali menemani ketika<br />
aku masak pagi-pagi, sesekali dia juga membantu.<br />
“Setelah cuci muka, tugasnya memungut telur itik”<br />
posisi kandangnya tepat di tempat kita duduk sekarang<br />
ini. Kenang ibuku.<br />
Dulu, aku harus merangkak melalui pintu seukuran<br />
tubuhku, lalu memungut beberapa telur dan<br />
mengeluarkan beberapa ekor itik, begitu itik-itik ini<br />
keluar, pada wajan yang terbuat dari bambu aku harus<br />
memberi itik-itik ini makan. Ada perasaan aneh ketika<br />
aku melihat itik-itik ini makan. Perasaan itu, perasaaan<br />
senang, mungkin ini bentuk terima kasihku atas telurtelur<br />
yang dikeluarkannya. Setelah memastikan semua<br />
itik-itik mendapat jatah makan, aku naik ke ruang dapur<br />
sambil membawa beberapa butir telur, dan pagi ini aku<br />
berhasil mengumpulkan sebelas bitur dari dua puluh satu<br />
80
ekor itik, artinya ada delapan ekor yang tidak berproduksi<br />
pagi ini, karena dua ekor lainnya adalah pejantan.<br />
“Bapakmu tahu betul ciri-ciri itik pejantan.”<br />
Katanya.<br />
“Ekor dan bulu yang jantan cenderung menekuk ke<br />
atas, intonasi suaranya relatif lebih pelan dibanding yang<br />
betina, lalu ketika berjalan ia selalu di depan.” Kata ibuku<br />
dan Bdikar tertawa senang.<br />
“Dulu,” kataku lalu duduk sambil peluk Bdikar.<br />
“Ibuku lalu menyimpan telur-telur ini dalam bakul<br />
hasil anyaman yang dibuatnya beberapa bulan<br />
sebelumnya,” aku pegang tangan ibuku. Tangan yang<br />
mulai keriput.<br />
“Tangan inilah dulu yang membersihkan sarang<br />
laba-laba yang menempel di kepalaku.” Kenangku. Dan<br />
membenarkan posisi duduk di bangku tepat dipingir<br />
tungku, menghangatkan tubuh, ini kebiasaanku sambil<br />
menemani ibuku dulu kalau sedang memasak.<br />
Aku menikmati hangatnya tungku yang bersumber<br />
dari proses pembakaran kayu bakar dari pokok kopi.<br />
Dulu batang kopi ini aku yang membantu bawa dari<br />
kebun setelah ibuku potong menjadi beberapa bagian.<br />
81
“Nak.” Kata ibuku sambil mengangkat wadah<br />
tempat air yang sudah mendidih, lalu mengantikannya<br />
dengan periuk nasi yang sudah menghitam pekat karena<br />
meng-arangnya asap. Dia lalu membuatkan segelas teh<br />
hangat untukku. Dan masih terniang-niang kata-kata ini<br />
ditelinggaku.<br />
“Nanti tidak ada lagi periuk, tidak ada lagi kerak,<br />
tidak ada lagi gerigik (tempat air dari bambu) semua<br />
bahasa untuk menyebutkan periuk, kerak, gerigik akan<br />
hilang dan beberapa berganti seiring berkembangnya<br />
kebudayaan dan teknologi.” kata ibuku.<br />
Selain sebagai anak laki-laki yang menemani<br />
ibunya memasak, obrolan-obrolan seperti inilah yang aku<br />
suka. Karena ada banyak kalimat yang akan keluar dari<br />
mulut bijak ibuku. Aku mengangap ini adalah sekolah<br />
pertamaku.<br />
“Bukankahkah kita punya sistem batutun bak jale,<br />
Mak.?” Jawabku.<br />
Aku tahu dari ibuku batutun bak jale ini adalah<br />
sistem bertutur yang mengacu pada induk kata lalu<br />
dipecahkan menjadi beberapa anak kata dan terbentuklah<br />
kalimat, selebihnya aku tidak tahu secara detail.<br />
82
“Ia, selain itu kita punya ketibeak baso.” Jawab<br />
ibuku.<br />
Ketibeak baso ini cara menyampaikan bahasa yang<br />
mengacu pada objek, ruang dan waktu, sehingga bahasa<br />
mampu mengartikulasi verbalitas pikiran. Sambung<br />
ibuku sambil menambah dan menyilangkan kayu bakar<br />
pada tungku, itu membuat asap semakin menjadi dan<br />
apinya semakin mengecil, pertanda aku harus meniup<br />
tungku ini untuk menyalakan apinya. Tanpa diperintah,<br />
akupun meniupkan api dengan alat bantu dari bambu<br />
yang terbuka kedua ruasnya. Tipuan pada ujung akan<br />
mengkonsentrasi keluaran tiupan dan kosentrasi oksigen<br />
di ujung yang lain, lalu terjadilah reaksi radikal bebas<br />
secara berantai dan ini sangat membantu proses<br />
percepatan pembakaran dan menyalanya api.<br />
“Apa maksudnya Mak.? Ketibeak baso yang<br />
mampu mengartikulasi verbalitas ini?” tanyaku sambil<br />
menggosok-gosok mata yang pedih akibat asap, ketika<br />
aku tiup tunggu, asap berhambutan karena angin pagi<br />
yang lewat dari sela-sela dinding, asappun tertuju pada<br />
muka dan mataku.<br />
83
“Maksudnya begini Nak.” Ibuku berhenti dia lalu<br />
mengusap mataku yang mengeluarkan air karena asap<br />
dengan telapak tangannya. Aneh, telapak tangannya<br />
dingin tepatnya adem, dan terasa nyaman sekali. Dan, itu<br />
langsung meredakan pedih mataku akibat asap. Aku tahu,<br />
itu telapak tangan iklas dan penuh kasih sayang. Bukan<br />
telapak tanggannya yang menempel di mataku, tetapi<br />
hatinya. Hati yang penuh kasih dan cinta tak terbatas.<br />
“Pertama,” sambung ibuku.<br />
“Bahasa itu berasal dari teori kata kerja dan<br />
proposisi. Bahasa bukanlah bermula dari ekspresi tetapi<br />
dari suatu uraian pikiran, kata yang keluar dari mulut<br />
manusia dapat dikenali merupakan elemen dari sebuah<br />
bangunan uraian atau proposisi.” Akupun binggung.<br />
Lalu ibuku memberikan contoh.<br />
“Misalnya, bila ada orang yang mengatakan<br />
‘Tidak’ dalam teori ini, itu bukan berarti langsung bisa<br />
dipahamai sebagai suatu penolakan, tapi kata ‘tidak’<br />
harus diletakan dahulu dalam keseluruhan proposisi,<br />
karena ia merupakan bagian dari semisal pikiran,” Aku<br />
masih tetap binggung, ibuku tahu aku binggung, aku<br />
tidak mengeluarkan kata-kata meski mulutku terbuka.<br />
84
Tidak ada penjelasan lanjut dari ibuku. Lalu aku mulai<br />
berpikir dan berdialektika, ‘aku tidak bisa berpikir’<br />
bukankan ‘tidak” pada kalimat itu bukan berarti<br />
penolakan untuk berpikir.? Atau aku tidak bisa<br />
mendengar, dan ‘tidak’ pada kata mendengar bukan<br />
berarti aku menolak untuk mendengar.?<br />
“Kedua.” Lanjutnya.<br />
Dan itu membuyarkan dialog imajinatifku yang<br />
mencoba-coba menganalisa teori pertama dari ibuku.<br />
“Bahasa itu tentang artikulasi, pada posisi ini<br />
bahasa menyatakan bahwa betapapun murninya,<br />
sederhana atau arkeisnya sebuah bunyi, bunyi tersebut<br />
pasti mempresentasikan artikulasi dan intonasi tertentu,<br />
yang mempresentasikan pikiran di balik bunyi itu.”<br />
“atau sederhananya,”<br />
“Tidak ada sesuatu bunyi bebaspun yang tidak<br />
mendenomisasikan sebuah nama tertentu.” Mulutkupun<br />
semakin melebar, ibuku terlalu cepat menjelaskannya.<br />
“Misalnya tangisan.” ibuku mulai menganalogi, dia<br />
tahu kebingunganku akan memicu masuknya beberapa<br />
ekor lalat ke mulutku nantinya.<br />
85
“Setiap tangisan mengartikulasi pikiran di balik<br />
bunyi, ada tangisan takut, tangisan kesakitan bahkan<br />
tangisan sedih, intonasinya pasti berbeda. Bunyi ini<br />
berasal dari kontak dental yang diakibatkan kekokohan<br />
gigi yang sejalan dengan bibir yang senantiasa bergerak<br />
fleksibel yang menghasilkan intonasi berkesan nyaring,<br />
berisik dan kuat, ini mengartikulasikan pikiran mengenai<br />
fenomena keriuhan maupun kelembutan.” Dan, aku<br />
masih saja belum mengerti.<br />
Malah pikiranku tertuju pada 2 ekor itik jantan,<br />
betapa berdaulat, tepatnya, betapa nikmatnya ia diantara<br />
19 ekor itik betina, bukankah ia tidak perlu proses bahasa<br />
dan komunikasi yang berbelit untuk merayu para<br />
betinanya. Cukup mengeluarkan suara serak-serak nakal<br />
atau cukup mengerakkan sayap dan ekor proses<br />
pembuatan telurpun jadi.<br />
“Ketiga.” Dan itu membuyarkan lamunanku pada<br />
itik pejantan itu.<br />
“Bagaimana bahasa kemudian bertindak sebagai<br />
sebuah instrumen petunjuk, pada asal mulanya tidak<br />
bermula dari ekspresi atau gerak alamiah, tapi dari<br />
kemampuan untuk menganalisa tanda. Pada posisi ini,<br />
86
ahasa adalah alat untuk memberi nama. Ia berangkat<br />
dari kemampuan membaca, menerima dan<br />
mengekspresikan tanda sebagai sebuah substitusi<br />
pikiran.” Kali ini ibuku menjelaskannya lebih cepat dan<br />
itu dilakukannya sambil menggaduk nasi yang mulai<br />
mendidih, aroma yang keluar dari uap yang berasal dari<br />
air nasi yang kental berwarna putih itu, membuat perut<br />
semakin lapar. Lagi-lagi pikiranku tertuju pada dua ekor<br />
itik pejantan.<br />
“Bahasa pada posisi ini, melengkapi gerak-gerak<br />
dan isyarat-isyarat alami untuk menunjukan sesuatu yang<br />
diucapkan oleh badan seperti gerak menudingkan jari ke<br />
arah benda yang dituju” sambung ibuku.<br />
Dia tetap saja menjelaskan secara rinci meskipun<br />
dia tahu betapa aku tidak mengerti penjelasannya yang<br />
sangat membingungkan itu, padahal dia tahu anak yang<br />
diajaknya berbicara itu baru kelas tiga SD.<br />
“Nah, ini yang terakhir.” kata ibuku.<br />
Nasipun mulai mengering, dia mulai menyiakan<br />
irisan cabe, bawang, dan enam biji telur itik. Dan, yang<br />
ini aku tahu, perpaduan antara bawang, cabe, minyak dan<br />
beberapa butir telur pasti keluarannya adalah sambal<br />
87
goreng telur itik. Sambal ini adalah simbol sekaligus<br />
pertanda menunjukan waktu makan pagi semakin dekat.<br />
“Teori ini menjelaskan persoalan persebaran<br />
bahasa, atau derivasi. Pada posisi ini, mobilitas dan<br />
perkembangan bahasa tidak ditentukan oleh dimensi<br />
waktu, tetapi bahasa ditemukan oleh dimensi ruang.<br />
Faktor lokus ruang membuat antar bahasa satu dengan<br />
bahasa lain memiliki kebiasan atau cara yang berbedabeda<br />
dibanding perjalanan waktu bahasa itu sendiri.”<br />
“Dari empat teori bahasa ini, selain membentuk<br />
hubungan fungsional yang sejajar secara otomatis juga<br />
membentuk hubungan fungsional yang diagonal.” Jelas<br />
ibuku dan aku semakin tidak mengerti dengan penjelasan<br />
ibuku ini.<br />
Sungguh aku tidak kosentrasi dan mengikuti<br />
penjelasan rinci ibuku ini, pikiranku berada di atara<br />
sambal goreng telur itik dan posisi strategis dua ekor itik<br />
pejantan diantara sembilan belas betinanya.<br />
Nasipun matang, lalu periuk berganti posisi dengan<br />
kuali. Ibuku menuangkan minyak goreng yang beku<br />
karena dingin. Lalu bawang daun berenang diantara<br />
merahnya warna cabe giling. Bawangpun layu di atas<br />
88
minyak yang mencair dan panas. Lalu, berenang seperti<br />
itik ketika ketemu kolam dan layu seperti pejantan telah<br />
menunaikan tugasnya untuk betina.<br />
Aku kagum dengan ibuku ditengah kebingunganku<br />
atas penjelasanya. Dia seperti filsuf, terlibat di dalam<br />
aktivitas praktis, aktivitas praktis secara implisit berisi<br />
konsep tentang dunianya, dunia bahasa selain<br />
kemampuan praktisnya memasak, dan sekaligus<br />
menyiapkan makanan bagi kami.<br />
Bahasa ibu. Dan bukankah bahasa ibu adalah<br />
bahasa pengantar pertama bagi kita, bahasa untuk<br />
komunikasi yang titik kosentrasinya adalah posistif, lalu<br />
dipakai untuk memahami realitas sosial, digunakan selalu<br />
untuk mengartikulasi praktek sosial budaya, dan bahasa<br />
kemudian mampu mengambarkan pencapaian<br />
kebudayaan bukan hanya sekedar alat komunikasi satu<br />
pihak dengan pihak lainnya.<br />
Penggunaan bahasa dalam praktek budaya secara<br />
umum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat dialogis,<br />
artinya bahasa tertentu atau formasi diskursifnya<br />
menentukan apa yang mungkin dikatakan pada topik<br />
tertentu. Formasi diskursif terdiri dari peraturan yang<br />
89
tidak tertulis yang berusaha mengatur apa yang dapat<br />
ditulis, dipikir dan dilakukan pada dan untuk hal-hal<br />
tertentu. Itu semuanya bermula dari mulut ibu, mulut<br />
yang senantiasa mengeluarkan kata-kata bijak, sayang,<br />
cinta, lafaz doa dan mulut yang selalu menempel<br />
dikening menjelang tidurku.<br />
Kami duduk berbaris di meja makan, dulu kami<br />
hanya berempat setelah nenekku meninggal. Sekarang<br />
bertambang tiga orang, dua orang anaku dan istriku. Nasi<br />
telah berpindah dari priuk ke piring. Tidak ada telur itik<br />
berwarna merah menyala, Ibuku tersenyum. Dan dia<br />
duduk disamping bapakku yang sudah berganti baju<br />
untuk siap-siap ke sawah.<br />
90
7<br />
Di dekat lemari piring masih ada sisa beberapa<br />
potongan bambu muda sisa ibuku memasak sambal<br />
kemaren. Ada sepuluh batang lagi. Kami bergotong<br />
royong memasak lemang. Kedua anakku asik membantu<br />
memasukan beras yang sudah dicampur dengan kelapa<br />
dan pisang. Yang sudah selesai aku tegakkan dekat api<br />
bertumpu pada kayu yang aku pasang melintang rendah<br />
seperti tiang gawang.<br />
“Dulu orang Belanda binggung cara memasak<br />
lemang ini,” ceritaku bercanda. Dan itu benar karena<br />
tidak ada budaya memasak Lemang di Belanda.<br />
“Dari mana Bapak tahu.” Tanya Titon anak<br />
bungsuku.<br />
“Dari Sejarah” jawab Bdikar<br />
“Iya, dari sejarah,” Jawabku. Dulu. Kenangku<br />
Sepulang sekolah aku bergegas mengantikan baju<br />
seragam pramukaku yang sudah lusuh, hari ini hari sabtu.<br />
Dan, tadi disekolah kami belajar tentang pelajaran<br />
sejarah. Tepatnya mata Pelajaran Sejarah Perjuangan<br />
Bangsa (PSPB). Setelah seragam sekolahku berganti<br />
91
dengan pakaian “kotor”, pakaian ini pakaian khusus,<br />
kotor dan tambalan ada di mana-mana. Biasanya dipakai<br />
kalau ke kebun atau kesawah. Siang ini aku kebagian<br />
menjaga hama burung dan tikus yang mulai sering<br />
menyerang sawah kami yang sebentar lagi akan panen.<br />
Aku harus buru-buru kesawah selain sudah ditunggu oleh<br />
ibuku, dan tentu aku harus makan siang di sawah hari ini.<br />
Sore ini juga aku ditugasi membantu Wakku, dia kakak<br />
ibuku namanya Dulaha. Kami biasa panggil dia Wok<br />
Odon. Sore ini dia akan membuat ritual untuk mengusir<br />
hama tikus disawah kami. Namanya “betikeun”, setelah<br />
ritual ini dilaksanakan, kata ibuku, jika ada tikus yang<br />
nekat masuk kesawah maka tikus-tikus itu akan mati<br />
dengan badan yang membengkak.<br />
Ritual “betikeun” ini sering dilakukan ketika padi<br />
mulai memunculkan butiran buahnya, ketika itulah air<br />
sawah mulai dikurangi dan tikus punya kesempatan untuk<br />
memotong batang-batang padi. Tidak banyak orang yang<br />
bisa melaksanakan ritual ini. Hanya orang-orang terpilih.<br />
Orang-orang turun waris. Begitu juga dengan jenis dan<br />
sistem pengelolaan padi. Hanya padi lokal yang dikelola<br />
92
dengan pola tradisional saja yang bisa dilaksanakan ritual<br />
ini.<br />
Wak Odon adalah salah satu orang turun waris<br />
sebagai pelafas jambi ritual “betikeun”. Selain punya<br />
kemampuan kanuragan, ilmu-ilmu kampung yang<br />
bernuansa mistis. Wakku ini didik oleh pendidikan<br />
Belanda dan Jepang. Tentu bahasa Belanda dan<br />
Jepangnya bagus sekali, dan pengetahuannya juga sudah<br />
pasti luas sekali. Sehingga. Kemudian, dia pernah<br />
menjadi Asisten peneliti M.A Jaspan, seorang<br />
anstropologi dari Australia dan pernah juga menjadi<br />
pimpinan desa ketika masa kritis pemberontakan PRRI,<br />
dan anaknya pernah ditembak oleh Gerombolan PRRI<br />
dan mati dipelukan istrinya.<br />
Menjelang magrib dia baru tiba di sawah kami.<br />
Lalu, ritualpun dimulai. Aku duduk disampingnya,<br />
didepan kami ada tujuh batang benik dari beras ketan<br />
hitam dan paha ayam kampung panggang yang sudah<br />
disiapkan oleh ibuku. Benik adalah nasi yang dimasak<br />
dalam bambu, di Sumatera dikenal dengan Lemang.<br />
Mataku melotot dan fokus ke batang-batang lemang dan<br />
paha ayam panggang yang mengeluarkan minyak dan<br />
93
warna merah, air liurku mencair, mulai menetes keluar<br />
lewat kiri mulutku. Sementara Wakku merapalkan<br />
mantera-mantera yang tidak aku mengerti, setelah selesai<br />
ritual, aku diajak Wakku mengelilingi sawah, bibirnya<br />
gemetar pertanda dia masih melapaskan mantera. Aku<br />
berjalan dibelakangnya. Pikirankku masih tertuju ke<br />
batang lemang dan paha ayam.<br />
Setelah selesai mengelilingi sawah kami, dia pamit<br />
pulang dan akupun langsung berlari menuju titik ritual<br />
pertama, ada sesuatu yang harus aku ambil dan<br />
selamatkan.<br />
“Pasti Lemang dan paha ayam panggang.” Potong<br />
Bdikar.<br />
“Ia,”<br />
Setelah sholat magrib, Aku, ibu dan adikku pulang<br />
ke rumah. Bapakku masih bertugas menjaga sawah<br />
malam ini. Malam berikutnya tidak perlu di tunggu lagi<br />
pesan Wakku. Ceritaku sambil membolak balik lemang<br />
di batang bambu yang mulai hangus.<br />
“Setelah habis sholat isya.” Lanjutku. Wakku<br />
datang bertandang ke rumah kami. Rumah adik<br />
perempuannya. Yang sebenarnya adalah rumah ibunya.<br />
94
Ibuku adalah bungsu dari sepuluh orang saudaranya, dan<br />
aku tahu betul kakak-kakaknya sangat menyangi ibuku.<br />
Malam ini Wakku datang dengan syal sulaman warna<br />
biru yang selalu menempel di lehernya, berbaju sapari<br />
warna biru muda, sarung kotak-kota dan peci hitam.<br />
Garis wajahnya tegas, bersih, berwibawa dan<br />
kharismanya memancarkan aura yang sangat kuat sekali.<br />
Tangan kecilku tiba-tiba langsung menyambar betisnya.<br />
Aku memulai ritual pijatan di betis kirinya, dia tersenyum<br />
sambil memegang kepalaku. Dia tahu sebagai ‘‘barter”<br />
atau sebutlah upah memijat betisnya, dia harus bercerita.<br />
Semakin panjang cerita maka semakin lamalah durasi<br />
pijatanku.<br />
“Win, tadi disekolah balajar apa?”. Belajar Sejarah,<br />
jawabku cepat.<br />
Biasanya ini pertanda cerita akan dimulai. Dia<br />
tersenyum, telinggaku sepertinya bergerak dan lobangnya<br />
membesar. Dia merepon dengan mengubah posisi<br />
duduknya.<br />
“Tadi kata guru kami, Indonesia dijajah selama 350<br />
tahun”. Aku mulai memancing ceritanya.<br />
95
Dan itu lama sekali kita menjadi bangsa terjajah<br />
yang terbelakang, kemudian bermental inlender, lanjutku.<br />
Wajahnya tidak berubah, menandakan kematangan<br />
emosional.<br />
“Kita tidaklah minderwardheid, minder atau tidak<br />
percaya diri” katanya bijak. Dari hasil penelitian yang<br />
lebih teliti, Belanda baru dapat mengkonsolidasi<br />
kekuasaanya atas Nusantara dan efektif menguasai<br />
Nusantara cuma 70 tahun, catatannya apabila Aceh dan<br />
Bali baru ditaklukkan di abat ke 20. Dia mulai<br />
melanjutkan cerita. Seperti biasa, jawabannya selalu<br />
memancing pertanyaan-pertanyaan baru dariku.<br />
“Aku lebih percaya di angka 350 tahun”, pijitankku<br />
semakin kuat.<br />
“Nyatanya, entitas bangsa nusantara kita<br />
mengalami kehancuran berlahan-lahan menjadi<br />
berkeping-keping, menyebabkan kehancuran moral dan<br />
mental, serta tidak adannya konsolidasi kebangsaan<br />
sebagai satu bangsa yang merdeka, kalau hanya 70 tahun<br />
tidak seperti ini kejadiannya”. Lanjutku.<br />
Dia terdiam, aku senang, tiba-tiba dia melepaskan<br />
peci dan minum kopi buatan ibuku. Di belakangku,<br />
96
sambil menjahit dan memasang lambang Pramuka di<br />
bajuku, ibuku melirik dan menahan senyum. Jawaban<br />
panjangku pasti mampu mengangkat ingatan kolektif<br />
Wakku yang hidup dan mengalami masa jajajah maupun<br />
pergolakan setelah Indonesia Merdeka.<br />
“Belanda pertama kali datang ke Maluku dengan<br />
maksud memonopoli pasar rempah-rempah dan<br />
setelahnya mencari pangkalan tetap, yang kemudian<br />
ditemukannya di Batavia. Setelah perang melawan<br />
Kerajaan Mataram, Belanda menguasai konsesi di<br />
Priangan dan Semarang. Kejadian ini memperlemah<br />
posisi Mataram”. Lobang telingaku semakin membesar.<br />
“Di tahun 1705 VOC memperoleh daerah<br />
perniagaan Cirebon dan Madura, baru di Tahun 1743<br />
memperolah seluruh pantai Utara Mataram, lalu tahun<br />
1755 Kerajaan Mataram ini diserahkan kepada VOC,<br />
perusahan kongsi dagang Belanda. Pada priode ini<br />
kekuasaan politik Belanda dimulai”. Dia melanjutkan<br />
dengan rinci dan lebih detail dibandingkan Guru<br />
Sejarahku di Sekolah tadi.<br />
“Lah, kenapa Belanda berubah dari kongsi dagang<br />
ke kongsi Politik?”. Tanyaku.<br />
97
Mata kami saling bertatapan, dan aku menunduk,<br />
tidak sanggup lama-lama menatap sorotan matanya yang<br />
tajam.<br />
“Pada dasarnya, tidak ada yang berubah. Setelah<br />
diadakannya berbagai kebijakan agraria guna menguasai<br />
produk pertanian bagi pasar dunia yang dilaksanakan<br />
sejak abad ke 18 lewat kerja rodi dan penanaman paksa.<br />
Lalu, bentuk kongsi dagang VOC dianggap tidak lagi<br />
efisien dan produktivitas penanaman paksa mulai<br />
dipertanyakan”. Lanjutnya, tapi kali ini dia akhiri dengan<br />
senyuman.<br />
Dan, akupun tambah bersemangat memijat<br />
betisnya. Sepertinya barter kami malam ini, barter pijatan<br />
dengan cerita mulai saling menguntungkan.<br />
“Oleh karenanya”. Di berhenti untuk menyulutkan<br />
rokok Nipahnya.<br />
“Sejak tahun 1800 dimulailah di Jawa satu negara<br />
kolonial modern Hindia Belanda, yang dasar-dasarnya<br />
dimulai sejak Gubernur Jendral Dendels. Dan, pada masa<br />
Raffles di perkenalkan sewa tanah individual yang<br />
mencerminkan liberalisme Inggris, sehingga sejak saat itu<br />
dimulai seterusnya titik berat ekonomi kolonial kepada<br />
98
pertanian, dan bukan lagi perdagangan, sebagaimana<br />
strategi awal VOC”. Kalimat ini keluar dari mulutnya<br />
bersamaan dengan asap rokok yang membuat dadaku<br />
sesak, aku terbatuk kecil dan lobang hidungkupun mulai<br />
mengecil, ini bentuk respon alamiah pertahanan tubuh<br />
ketika ada serangan dari luar. Tapi, dia tidak peduli<br />
dengan keberatan tubuhku dengan asap rokok yang<br />
tembakaunya ditaman sendiri oleh dia.<br />
Sepertinya dia memaksa tubuhku beradaptasi<br />
dengan serangan asap rokoknya.<br />
“Meskipun demikian elemen-elemen merkatilisme<br />
masih kuat di Belanda, karena itulah didirikan badan<br />
usaha baru. Namanya NHK (Nederlandche Handel<br />
Maatschappij) pada tahun1824.” Bahasa Belandanya<br />
menyebutkan kepanjangan NHK sangat Fasih. Aku<br />
terkagum-kagum penguasaan Bahasa Belandanya.<br />
“Maskapai ini sebagian besar sahamnya masih di<br />
kuasai oleh Raja Belanda untuk mengusahakan berbagai<br />
komoditi pertanian.” Lanjutnya, asap rokoknya semakin<br />
tebal saja.<br />
“Di tahun 1830 dimulai kembali sistem tanam<br />
paksa di bawah Van Den Bosch dengan pemaksaaan<br />
99
untuk menanam tanaman ekspor, yang merupakan bentuk<br />
penghisapan surplus pertanian paling efektif”. Lanjut dia<br />
semangat.<br />
“Dengan riwayat tadi, riwayat kolonialismeimprealisme.”<br />
Dia tersenyum ketika mendengar aku<br />
menyebutkan istilah kolonialisme-imprealisme. Dalam<br />
hatiku mungkin dia kagum anak kelas lima SD bisa<br />
menyebutkan istilah kolonialisme-imprealisme. Tetapi,<br />
cuma itu yang aku dengar dan ingat dari penjelasan guru<br />
Sejarah di Sekolahku tadi.<br />
“Proses tersebut telah merusak semua pencapaian<br />
masyarakat yang ada sebelumnya, semuanya telah<br />
ditaklukkan untuk tunduk dan hanya mengikuti perintah<br />
dari pemerintahan seberang lautan, pertanian kemudian<br />
menjadi subsistens, karena semuanya disedot keluar<br />
untuk pemerintahan Belanda”. Lanjutku bersemangat.<br />
Kata-kata sedot sebenarnya untuk Wakku, untuk<br />
sedotan batang rokoknya yang mulai menganggu<br />
pernapasanku. Pesanku sampai, dia lalu mematikan<br />
rokoknya. Tetapi masih ada tiga batang rokok nipah yang<br />
sudah disiapkannya dan pasti akan ada sedotan lagi yang<br />
100
akan mengeluarkan asap tebal yang bisa buat sesak<br />
dadaku yang sedang mengalami pertumbuhan.<br />
“Pada tahun 1870, Undang-undang tanah Agraria<br />
diberlakukan, dan dimulainya sistem perkebunan besar,<br />
petani dipaksakan untuk menyewa tanahnya kepada<br />
perusahaan-perusahaan perkebunan swasta besar,<br />
sementara petaninya tinggal menjadi kuli upahan.<br />
Akibatnya terjadi peningkatan produksi dan berakibat<br />
pula terjadinya depresi yang hasilnya memunculkan<br />
kosentrasi kapital pada perusahaan besar.” Dia mulai<br />
memprovokasiku.<br />
“Kolonialisme telah merubah Indonesia menjadi<br />
keadaaan yang sekarang ini, yaitu timbulnya masalahmasalah<br />
paska-kolonial yang rumit dan kompleks,<br />
bukankan struktur agraria pra-kolonialisme berupa<br />
kuatnya sistem perhambaan feodal dan lembaga bagi<br />
hasil”. Aku tiba-tiba memotong penjelasannya.<br />
“Ia.” Jawabnya sambil menjulurkan kakinya<br />
sebelah kanan, setelah tangan kecilku merayap padat di<br />
betis kirinya.<br />
“Pada masa penjajajahn Belanda, guna melayani<br />
sistem tanam paksa dihidupkan kembali komunalisme<br />
101
desa. Sistem tanam paksa ini sistem yang unik, yaitu<br />
mengkombinasikan dipertahankannya kekuasaan feodal<br />
dengan kepentingan kolonialisme dari luar.” Lanjutnya.<br />
Suaranya kemudian diturunkan.<br />
“Hasilnya adalah memadukan cara produksi yang<br />
komunal dan feodal, petani mendapatkan tanah, statusnya<br />
sebagai petani hamba yang menyerahkan tenaga kerjanya<br />
untuk tanaman komoditas yang diharuskan oleh<br />
Pemerintah sebagai ganti pembayaran pajak. Bersamaan<br />
dengan itu kelas tuan tanah diperlemah”. Suaranya<br />
mengeluarkan intonasi sedih, berbanding terbalik dengan<br />
intonasinya ketika membaca mantera sore tadi di sawah<br />
ibuku.<br />
“Padahal”. Lanjutnya sambil menghidupkan rokok<br />
daunnya, asapnyapun memenuhi rongga mulutnya.<br />
“Pada abad ke 15 di Jepang, feodalisme matang<br />
disempurnakan oleh dinasti Shogun Tokugawa yang<br />
berkuasa stabil selama 270 tahun. Setelahnya<br />
ditransformasikan ke dalam pemerintahan borjuasi di<br />
bawah restorasi Meiji”. Ah, dia mulai memecahkan<br />
kosentrasiku.<br />
102
“Dan, akhirnya dinasti terakhir Shogun Tokugawa,<br />
Yoshinobu akhirnya disingkirkan oleh para samurai<br />
muda, yang merasa kecewa dengan konsesi-konsesi yang<br />
diberikan pemerintah Tokugawa kepada pihak asing.<br />
Peristiwa ini kemudian kita kenal dengan istilah restorasi<br />
itu.” Lanjutnya.<br />
“Setalah kita Merdeka, kondisi dan hubungan sosial<br />
dari sisa-sisa feodal dan kolonial yang lama tetap<br />
berlangsung, sehingga Pemerintah Indonesia yang baru<br />
kesulitan untuk bisa menerapkan suatu rencana besar<br />
pembangunan yang jelas dalam memecahkan warisan<br />
struktur tersebut.” Ternyata dia ajak pikiranku untuk<br />
membandingkan kondisi Jepang dengan Indonesia.<br />
Aku terdiam, aku kesulitan menghubungkan<br />
kondisi di Jepang dengan alur sejarah yang terjadi di<br />
Negaraku, Indonesia. Atau Wakku sengaja mengalihkan<br />
perhatianku supaya durasi pijatan semakin lama.<br />
“Lalu, apa yang terjadi di Indonesia, ketika kita<br />
awal Merdeka,”<br />
“Adakah restorasi?” Tanyaku menghubunghubungkan.<br />
103
Restorasi dengan kemerdekaan meskipun aku<br />
sendiri tidak paham maksud pertanyaanku. Dia ternyata<br />
berhasil memanjangkan durasi pijatanku.<br />
“Kondisinya begini, para tuan kolonial lama,<br />
condong kepada dekolonisasi politik tetapi bukan<br />
ekonom, karena itu mereka bersiap-siap berfungsi<br />
melalui kelompok-kelompok nasionalis yang pantas dan<br />
moderat, komprador neo-imprealisme dan neokolonialisme<br />
yang setelah pemindahan kekuasaan<br />
berhadapan dengan para nasionalis radikal dan komunis<br />
serta kelompok lain yang mengajurkan dekolonisasi<br />
total”. Dia mencoba menjelaskan meski dia tahu aku pasti<br />
tidak mengerti maksud dari penjelasanya.<br />
“Tiba-tiba diluar rumah ada suara ribut.”<br />
“Suara gentongan.” Ceritaku.<br />
“Suara apa.” Tanya Bdikar<br />
“Suara Gentongan,” Jawabku.<br />
Dari ketukannya, biasanya akan ada pengumuman.<br />
Aku langsung meloncat keluar rumah. Aku melepaskan<br />
diri dari semburan asap rokok dan memulihkan pegalnya<br />
tanganku setalah merayap pada di kedua betis Wakku.<br />
104
“Tuk..tuk..tuk..tuk.” Aku pukul batang-batang<br />
lemang menirukan bunyi pukulan pada bambu yang<br />
menjadi alat gentongan.<br />
Setelah ketukan itu berhenti Pak Sahak yang di<br />
tugasi menyampaikan pengumuman. Suaranya keras<br />
melengking “Besok akan dilaksanakan sensus penduduk<br />
naik rumah turun rumah, gunanya untuk pendataan<br />
kelayakan mendapatkan bantuan pendanaan program<br />
bimbingan masyarakat atau BIMAS. Pemerintah akan<br />
membantu peningkatan usaha pertanian sebagai basis<br />
ekonomi rakyat, jadi besok jangan ada yang pergi ke<br />
sawah atau ke kebun demi suksesnya Sensus ini.<br />
Demikian pengumuman ini disampaikan.”<br />
Biasanya aku ikut mengawal Pak Sahak keliling<br />
desa menyampaikan pengumuman ini. Karena Wakku<br />
masih ada di rumah kami, jadi setelah mendengarkan<br />
penguman ini aku kembali duduk di samping Wakku.<br />
Ceritaku.<br />
“Sudah saatnya perencanaan pembangunan itu<br />
beralih dari ekonomi neo-liberal kepada perekonomian<br />
yang heterodoks atau non-mainstream.”<br />
“Ini sangat penting,”<br />
105
“Karena neo-liberal atau ekonomi pasar<br />
menyebabkan tidak adanya pilihan-pilihan pembangunan<br />
yang beragam dan tidak adanya ruang publik yang<br />
berbeda dengan mekanisme pasar. Pertumbuhan ekonomi<br />
yang berkualitas hanya bisa terjadi jika kebijakan<br />
ekonomi mementingkan kepentingan rakyat.” Lanjutnya<br />
tiba-tiba. Akupun mengangguk-angguk tidak mengerti.<br />
Dia kemudian pamit pulang ke ibuku. Dua batang<br />
rokoknya tertinggal, aku berlari kedapur.<br />
Ada aroma sesuatu yang hangus. Dua batang<br />
Lemang menghitam.<br />
“Apinya terlalu besar.” Kata ibuku. Lemang yang<br />
hangus ini kamu buka. Jadilah dua batang ini berpindah<br />
habis ke perut ku dan kedua anakku.<br />
106
8<br />
Hari ini ibuku membersihkan rumah. Aku ikut<br />
membantu. Semua barang-barang yang tidak terpakai dia<br />
masukan ke kamar kecil, kamar kecil ini dulu aku pakai<br />
untuk tempat tidurku. Sekarang berubah fungsi menjadi<br />
gudang. Aku membantu menyusun barang-barang yang<br />
berserakan. Buku-bukuku ketika SD masih tersusun rapi<br />
tapi warnannya mulai pudar dimakan usia.<br />
Ketika aku merapikan buku-buku ini, ada photo<br />
yang jatuh dari lipatannya. Pas photo hitam putih<br />
berukuran 4 x 3. Ukuran pas photo yang biasa di<br />
tempelkan di buku raport. Aku masih ingat ini photonya<br />
Dewa. Wanita teman sekelasku. Wanita yang sempat<br />
singgah dihatiku. Cinta pertama, membuatku seperti<br />
cintanya bunga pada harum aroma, seperti cintanya<br />
matahari atas cahaya dan penyempurnaannya. Seperti<br />
harapan rembulan pada cerahnya malam.<br />
Aku mabuk.<br />
Pernah di suatu malam.<br />
Malam Senen, belum begitu malam sebenarnya.<br />
Malam gelap setelah hutan badai.<br />
107
Jam dinding yang di belikan ibuku di pasar desa,<br />
desa tetangga itu menunjukan jam 22.28. Belakangan ini<br />
pikiranku tidak bisa fokus. Aku mulai takut apakah ini<br />
akibat pengaruh ketika aku kesetanan melahap lemang<br />
dan paha ayam, kesetanan makan seperti para dedemit<br />
penunggu mantera ritual betikeun pengusir tikus.<br />
Atau. Bisa jadi aku terserang kesapo atau kena<br />
teguran makluk halus seperti yang dipercayai oleh<br />
banyak orang di kampungku. Mereka masih sangat<br />
percaya secara gaib, padi dan tikus dikendalikan peri<br />
perempuan. Tanda-tanda terserang kesapo ini biasanya<br />
dimulai dengan demam dan suhu tubuh semakin panas.<br />
Beberapa kali aku raba. Suhu tubuhku normal.<br />
Aku cenderung suka menyendiri dan imajinasiku<br />
semakin liar. Terutama dengan sosok yang berlainan<br />
jenis. Aku tidak tahu dengan apa yang terjadi pada dada<br />
sebelah kiriku. Seperti ada yang sedang bergejolak. Apa<br />
lagi ketika aku ketemu dengan teman sekolahku.<br />
Namanya Dewa. Dia teman sekelas dan masih ada<br />
hubungan keluarga denganku jika di hitung dari garis<br />
keluarga bapakku.<br />
108
Di sekolah. Posisi duduknya berada di depan<br />
bangkuku. Dan ketika dia menoleh ke belakang, pantulan<br />
matanya, kalau kami saling bertatapan membuat dadaku<br />
bergetar. Sulit sekali dijelaskan getaran ini. Dan.<br />
membuat Aku malu sendiri. Getaran ini menganggu,<br />
apalagi ketika malam mulai larut. Aku seperti terserang<br />
jampi pelet seburuk tulang. Pelet yang akan<br />
mempengaruhi dan mengendalikan jiwa seseorang.<br />
Legendanya. Seseorang yang kena ajian pelet jenis ini,<br />
bahkan ketika sudah meninggalpun. Rohnya akan<br />
gentayangan mencari dengan cinta orang yang<br />
melepaskan ajian pelet ini. dan, malam ini aku tidak bisa<br />
pejamkan mataku.<br />
Dan. Malam ini. Udara terasa dingin menusuk<br />
sampai sum-sum tulang. Aku meringkuk dalam kain<br />
sarung petak-petak pemberian bapakku. Tiba-tiba saja<br />
terdengar ada suara ketukan di jendela teras rumahku<br />
yang sudah retak dan berdebu kacanya. Tetapi anehnya<br />
tak ada siapa-siapa. Daun jendela tiba-tiba saja terbuka,<br />
di belakangnya sosok buruk rupa dengan suara serak dan<br />
bernada resah menyapa, lalu dia menyebutkan namaku.<br />
109
Bulu-bulu di tengkukku berdiri seperti ada yang meniup<br />
berlahan-lahan dari belakang.<br />
“Denawa..!” dan itu bukanlah namaku.<br />
Kuberanikan diri buka pintu kayu jendela, lalu<br />
sosok buruk rupa itu menghilang dan hanya<br />
meninggalkan bayang-bayang hitam, dan sayup-sayup<br />
terdengar nama, Dewa...!<br />
Ada arak-arakan pelan di depan beranda rumahku,<br />
kutatap, lalu senyap ada barisan nisan pusara jiwa di luar<br />
jendela. Aku ketakutan tapi penasaran.<br />
Komat-kamit mulutku membaca ayat-ayat pengusir<br />
setan yang diajari ibuku, sambil kusapa embun pada<br />
kelopak mawar yang merambat di pagar rumah, tetapi<br />
embun itu begitu culas padaku. Seakan mau memberiku<br />
badai yang akan mengguncangkan jiwa.<br />
“Denawa” suara itu lantang datang dari pintu<br />
rumahku disertai dengan ketukan beberapa kali.<br />
Suara perempuan yang selalu hadir dalam<br />
thalamus, ruang otak tempat sensor data dan sinyal-sinyal<br />
motorik. Dan itu jelas sekali suara Dewa.<br />
Dia, perempuan yang aku kenal beberapa tahun<br />
lalu, aku ingat betul ketika dia dengan teman-temannya<br />
110
membantu ibu-ibu menyiapkan ritual cuci kampung.<br />
Ritula yang kami sebut kedurai agung. Itu ritual tahunan<br />
untuk mengusir pengaruh jahat dikampungku.<br />
Setelah peristiwa itu lama Dewa menghilang, tentu<br />
aku mulai melupakan Dewa. Tidak lama kemudian aku<br />
baru tahu, Dewa menghilang karena kecelakaan,<br />
setenggah tulang yag ada di badannya remuk. Dia jatuh<br />
dari jembatan ketika liburan kenaikan kelas. Ketika dia<br />
ikut membantu ibunya di kebun yang jauh dari kampung.<br />
Tali yang terbuat dari kawat sebelah kanan bawah<br />
jembatan putus. Posisi Dewa berada pas di perempat<br />
jembatan dan sedang membawa perbekalan keluargannya<br />
selama berada di kebun. Dia jatuh menimpa tumpukan<br />
batu sungai. Cuma itu yang aku tahu. Tahu dari ceritacerita<br />
yang beredar dikampung.<br />
Pagi itu, dengan di antar ibunya, Dewa muncul di<br />
sekolahku. Tidak ada yang berubah, dia berdiri tegak<br />
tetapi di tompang dua tongkat ditubuhnya, matanya tetap<br />
tajam, cantik. Mata kami saling berpandangan. Sorot<br />
mata bulat yang bisa membuat dadaku bergetar.<br />
Setelah jam istirahat. Kakiku bergerak sendiri<br />
menemui Dewa yang sedang bersandar di diding kelas<br />
111
kami yang retak, dan sudah mulai tampak bilah-bilah<br />
bambu pengikat semennya. Kami bercerita banyak<br />
tentang kejadian ketika dia jatuh dan beberapa rencana<br />
aktivitas yang menjadi ambisinya. Dia ingin jadi perawat<br />
dan guru mengaji. Setelah itu dia selalu datang sekolah<br />
dan tak kami sia-siakan waktu bersama.<br />
Kami banyak cerita, cerita tentang perempuan,<br />
tentang desa, tentang batu, tentang novel-novel yang ada<br />
di perpustakaan sekolah kami. Tetapi tetap saja selalu ada<br />
getar ketika mata kami bertatapan.<br />
Malam ini. Dia datang menemuiku, buru-buru aku<br />
buka pintu. Dewa, dengan dua tongkat penumpuh<br />
badannya, Dewa tegak di depan pintu, matanya merah<br />
seperti habis menangis. Seperti kebiasaanku, aku usap<br />
kepala dan rambutnya, lalu aku papah dia masuk dan<br />
kami duduk di kursi rotan reot peninggalan kakekku.<br />
Dan, Dewa Duduk bersandar pada sebuah bantalan<br />
berwarna merah di ruang tamu rumahku. Bantalan yang<br />
di jahit oleh tangan ibuku.<br />
Hubungan di antara kami terjalin seperti kisah yang<br />
diceritakan tanpa naskah, hanya menjalani rasa,<br />
menuruti kata hati dan naluri, tanpa terikat janji. Kami<br />
112
sedang mengalami dialektis emosi dalam berhubungan,<br />
saling mempengaruhi menuju kedewasaan yang berujung<br />
pada keutuhan keperibadian.<br />
“Ini proses bercinta kami.” Kata Dewa<br />
“Untuk menghindari mu, ternyata sembunyi saja<br />
tidak cukup letih jika terus berkejar-kejaran seperti ini”<br />
lanjutnya dan laluku peluk dia dalam-dalam.<br />
“Itu karena kita menyamarkan luka masing-masing<br />
lalu saling menutupi kesedihan, menutupi realitas dan<br />
mimpi,” Jawabku. Dan dengan beberapa puisi yang tak<br />
pernah dibukukan, sebab yang kita yakini, puisi itu<br />
takkan pernah mati dan selalu menjadi spasi dalam<br />
iringan setiap kata-kata” Intonasi dan hatikupun bergetar.<br />
“Kita,” lanjutku. Berhenti sebentar untuk<br />
mengontrol getaran suaraku<br />
“Kita, harus menentukan alternatif yang harus<br />
diambil, regresi atau progresi, untuk kembali ke<br />
eksistensi pola bercinta. Ini kebiasaanku berteori ketika<br />
berbicara dan berdiskusi dengan Dewa. Kami satu tim<br />
cerdas cermat di SD kami. Dan beberapa kali memenangi<br />
cerdas cermt di tingkat Kecamatan. Dia jago hapalan dan<br />
aku menguasai pelajaran hutungan.<br />
113
“Ketika kita kembali ketitik awal sudah pasti<br />
mengelami penderitaan, dan kalau di lanjutkan pasti<br />
menakutkan sekaligus menyakitkan. Ketakutan dan<br />
keragu-raguan bukanlah pilihan bijak pada posisi ini”<br />
terangku.<br />
“Aku” jawab Dewa, dan dia semakin tengelam<br />
dalam pelukkanku.<br />
Aku cuma butuh cinta, cinta yang berwujud<br />
penyatuan disaat aku sedang mempertahankan<br />
keterpisahan yang memungkinkan perwujudan dari<br />
aktifitas batin secara penuh.<br />
“Karena ketika adanya kamu, realitas cinta<br />
membuat eksistensi individuku meningkat, dan aku<br />
meraskan pengalaman mistis dari gairah penyatuan kita,”<br />
Lanjut Dewa, nada suaranya juga gemetar.<br />
“Cinta antara kita harus mulai dari titik orientasi<br />
produktif” jawabku dan ku cium kening Dewa, ciuman<br />
buat menenangkannya.<br />
“Orientasi produktif ini harus bersentuhan dengan<br />
realitas penalaran, itu akan membuat kita lebih kuat dan<br />
bahagia. Maka konsef penghargaan, keberanian, kesetian<br />
114
dan nilai-nilai estetis haruslah menjadi bagian simbolik<br />
dari cinta kita.” Lanjutku.<br />
“Aku tahu, tapi pada titik ekstrim, bukankah cinta<br />
itu pembebasan dari dorongan insting murni? lalu dia<br />
bisa menjadi bentuk sublimasi dan di sisi lain<br />
kepemilikan yang dilakukan oleh dorongan dan<br />
mengarah pada pengrusakan diri?” jawab Dewa.<br />
“Pengrusakan diri?” tanyaku.<br />
Begini, akupun berdialektika secara sederhana,<br />
cinta itu hidup, dia tidak semata-mata tentang inti,<br />
melainkan soal arus. Dia seperti bunga, seperti sungai<br />
yang tidak pernah berhenti mengalir, bunga, sejak kuncup<br />
mungil yang muncul diantara dedaunan, batang tumbuh<br />
berlahan, lalu muncul kelopak berwarna putih dari<br />
kehijauan kuncupnya, hingga menjadi bunga yang bulat,<br />
putih, dan ceriah yang membuka dan menutup melalui<br />
beberapa fajar, beberapa senja. Bunga itu bertahta<br />
anggun, lalu berlahan keriput dan menghilang secara<br />
mistrius, tidak ada titik, tidak ada jedah, hanya ada arus<br />
kecil yang mengalir tanpa henti. Begitulah cinta. Tiada<br />
berujung.<br />
115
“Maka cinta diantara kita harus banyak<br />
menghasilkan bunga mekar yang harum” Terangku.<br />
Lalu akupun melanjutkan<br />
“Karena Cinta pada dasarnya bukanlah kekuatan<br />
emosional, tetapi kekuatan ontologis, ia inti kehidupan,<br />
lebih tepatnya penyatuan dinamis atas sesuatu yang<br />
tercerai-berai.” Lanjutku lalu diam<br />
Aku diam menunggu jawaban Dewa, tidak ada<br />
tanda-tanda dia menjawab, biasanya setiap argumenku<br />
aku selalu memancing daya kritisnya, biasanya aku<br />
menikmati kepenasaran Dewa. Dewa sedang diam dan<br />
berpikir, tentu aku tahu apa yang sedang dipikirkannya,<br />
bukankah beberapa hari lalu dia berbicara tentang batas<br />
senja.<br />
“Pada akhirnya kita harus sepakat, bahwa<br />
hubungan ‘kita’ dibatasi senja. Kita harus sepakat bahwa<br />
bercinta seperti ini sudah sangat cukup mengurangi<br />
dahaga”. Demikian yang dia bilang padaku di suatu<br />
siang.<br />
Lama kami saling diam, lalu, ada genangan<br />
dimatanya, kusapu tetesan yang keluar dari matanya<br />
dengan jempol sebelah kananku. Wajah kami semakin<br />
116
mendekat, Dewa pejamkan matanya, setelah beberapa<br />
saat bibir kami menyatu, ada gerakan aneh pada lidah<br />
kami, gerakan ahamkara, gerakan yang menuntun kami<br />
menuju ketentraman jiwa, jiwa kami melayang tanpa<br />
ingat kepentingan pribadi kami, kami melebur dalam<br />
sensasi magis.<br />
Peleburan dan pergumulan kami terhenti ketika<br />
tanganku menyentuh paha kanannya yang belum pulih<br />
akibat kecelakaan. Dewa kesakitan. Lama kami saling<br />
diam dan berpandangan. Dan, akupun menyalakan rokok,<br />
rokok daun nipah Bapakku. Tentu Dewa tidak suka<br />
dengan asap rokok, bukan karena polusi tapi karena<br />
kesehatanku.<br />
Ciuman itu ternyata mampu membuat peleburan<br />
cara berpikir antara kami, kami mulai membangun peta<br />
realitas-sadarnya, respon-respon emosi dalam rentang<br />
yang luas melekat pada apa yang kami rasa dan pikirkan,<br />
mungkin saja ini merupakan variabel dari keyakinan, dan<br />
karena itulah yang memicu emosi pada setiap gerakan<br />
ahamkara pada lidah kami.<br />
“Emosi tidak hanya membantu kita<br />
mempertahankan keyakinan, keyakinan bahwa kita<br />
117
mencintai, mencintai dengan memberi” Aku mulai<br />
membuka pembicaraan lagi.<br />
“Tetapi juga membela kita dari keyakinankeyakinan<br />
lain yang mengancam keyakinan kita, caranya<br />
dengan mencari konsistensi dan pertalian dari apa yang<br />
kita yakini.” Tambahku, sambil memeluk dan mendekap<br />
Dewa di pangkuanku<br />
“Ia, keyakinan terkadang selalu berubah, bahwa<br />
otak kita terus menerus membayangkan dan<br />
menghasilkan perspektif alternatif tentang realita,<br />
kelenturan ini boleh jadi adaptasi pikirian terhadap situasi<br />
baru dan tak lazim, seperti hubungan kita” Jawab Dewa,<br />
sambil membenarkan kancing bajunya.<br />
“Perspektif alternatif, tentu saja lahir dari<br />
interpretasi cara kita berpikir, produknya adalah<br />
keyakinan” tambahku.<br />
Aku tahu Dewa belum mengerti maksudku.<br />
“Jadi begini” jelasku kembai berdialegtika, seperti<br />
musik yang merupakan interpretasi saraf atas bunyi,<br />
warna adalah interpretasi atas cahaya, mata dan sistim<br />
visual membantu membedakan berbagai frekwensi<br />
cahaya, kita tidak melihat frekwensi melainkan cahaya<br />
118
sebagai konsef. Merah, hitan, putih adalah kesepakatan<br />
atas konsef yang membentuk realita. Sama dengan<br />
matematika, meskipun dia ilmu pasti tapi sesungguhnya<br />
matematika adalah ilmu tentang kesepakatan, dan<br />
penjumlahan terjadi jika hanya jika kita sepakat<br />
mengunakan sistem bilangan desimal/persepuluhan.<br />
“Poinnya begini, bahwa mencintai tidak boleh<br />
tunduk pada variabel konsef misalnya norma tabu apa<br />
lagi batas senja, mencintai adalah mencintai, cinta adalah<br />
soal eksistensi manusia, soal apa yang kita yakini. Cinta<br />
yang demikian tentu saja tidak boleh resesif estatik,<br />
resesif pada lokus lalu menekan ekspresi lokus lain.”<br />
Sampai disini aku diam, aku merelakan menampar pipiku<br />
sendiri.<br />
“Maafkan aku, Dewa”, bujukku.<br />
Aku mulai sadar. Aku tahu selama ini aku<br />
cenderung resesif bahkan terlalu agresif, aku selalu saja<br />
mulai dari diriku, kepentingan egoku. Tak pernah aku<br />
berpikir yang titik pijaknya adalah kamu. Benar bahwa<br />
pribadi yang mementingkan dirinya sendiri tidak mampu<br />
mencintai orang lain, namun juga tidak mampu mencintai<br />
dirinya sendiri.<br />
119
Sementara bukankah kamu pernah bilang padaku<br />
“Aku mencari dan memburu agar tahu, aku ingin belajar<br />
tentang hal yang menjadi ketertarikan mu....Dan jika<br />
nanti aku telah menemukan diriku jatuh cinta, maka, aku<br />
tidak tahu untuk apa.” Lanjutku.<br />
Di luar hujan mulai turun, ku peluk Dewa, tak ku<br />
biarkan dia pulang meninggalkanku malam ini, malam ini<br />
senja tak lagi menjadi membatas. Pada kursi reot<br />
bersandaran bantal berwarna merah itu, Dewa tidur<br />
dipangkuanku.<br />
Aku tetap duduk menjaga tidurnya sambil berbisik<br />
“Biarlah hanya kita yang paham rasa, aku mengembara<br />
dalam dirimu, terima kasih tuhan Engkau telah mengirim<br />
Dewa untukku, karena pada dirinyalah letak<br />
penyempurna kisah.”<br />
Hujan sepertinya berhenti, lalu terdengar azan<br />
subuh dari Masjid seberang jembatan, aku terbangun dari<br />
tidurku, tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada pintu<br />
yang belum di tutup dan tidak ada Dewa dipangkuanku.<br />
Bantal berwarna merah yang menjadi sandaran kursi itu<br />
basah oleh air mataku. Air mata dari permulaan getaran-<br />
120
getaran yang memisahkan kekasih dari ruang dan matra<br />
lalu membawa mereka pada ilham dan impian.<br />
Aku simpan kembali photo hitam putih ini dalam<br />
lipatan buku dengan hati-hati seperti menyimpan mimpi.<br />
Mimpi untuk memuaskan atau pemenuhan hasrat (wish<br />
fulfillment) atas dorongan akumumulasi insting alamiah<br />
yang tersumbat dan dibatasi senja. Senja yang memakan<br />
banyak waktu, ketika yang di harap hanya tergerus<br />
semu. Dan aku masih memakai seragam merah putih<br />
jahitan ibuku.<br />
Aku tersenyum. “Merayaplah” kataku dalam hati.<br />
Merayap diantara hatiku. Tiuplah seruling cintamu agar<br />
hari-hariku melagu rindu.<br />
Aku penasaran.<br />
Aku buka kembali lipatan buku.<br />
“Tetapi kita terlampau asing untuk senja,” kataku<br />
sambil melihat detail photo.<br />
Marilah sejenak kita duduk di tepian danau, pada<br />
batu yang disusun tahun lalu oleh tangan kekar para<br />
buruh. Dan lihatlah, senja mati menelikung biduk-biduk,<br />
berpendar-pendar, berpacu dengan kabut dan badai laut<br />
121
senjapun tampak malam. Kembali imajinasiku terganggu.<br />
Aku seperti dirasuki.<br />
Mungkinkah ini bentuk peristiwa perubahan<br />
biologis yang terjadi pada makhluk hidup? berupa<br />
perubahan ukuran yang bersifat ireversibel (tidak berubah<br />
kembali ke asal). Ada perubahan ukuran yang terjadi<br />
pada pertumbuhan. Perubahan ukuran volume, tinggi,<br />
masa, dan mungkin aku sudah berada di gerbang<br />
pubertas.<br />
Aku semakin suka berhayal.<br />
Dengarkanlah Dewaku.<br />
“Suatu hari di sepi ini kau akan percaya cinta itu<br />
seperti mata pisau tidak hanya memukau tetapi<br />
menganiaya.”<br />
Maka jika pura-pura tidaklah akan jadi apa-apa.<br />
Bukankah pada jelang senja sore itu, ketika kau datang<br />
bersama ibumu, kau berdiri depan pintu dengan<br />
tongkatmu dan akupun terharu.<br />
“Kita seperti mengikuti garis jodoh, aku bahkan<br />
lebih suka menyebutnya garis hidup.” Aku memaksa.<br />
Pertemuan itu seperti cermin yang sama-sama kita<br />
cari terselip dan tertinggal entah dimana, tiba-tiba kita<br />
122
sudah saling berhadapan, saling berseru tentang laba-laba<br />
yang membangun sarang di mata kita masing-masing.<br />
Tetapi kenapa kita terlalu cepat membuang wajah.?<br />
Lalu, hari-hari berikutnya diam-diam kita saling<br />
meneliti kembali, kita temukan entah berapa banyak debu<br />
menutupi pori-pori kulit kita. Debu di tubuhmu dan juga<br />
ditubuhku bertutur tentang jalan panjang, penuh kelok<br />
dan curam. Tapi kita tetap tertawa sekaligus bersedih<br />
laksana magma dan luap bara. Pada debu di tubuh, angin<br />
dan gerimis pagi sampai siang itu sempat mengusapnya,<br />
namun malam menyempurnakan kelabunya kitapun cepat<br />
menutup tubuh.<br />
“Dan, jika pada penyempurnaan malam aku<br />
melupakan jatuh cinta, berarti aku telah lupa cara<br />
menjatuhkan airmata.” Itu ucap janjiku ketika aku antar<br />
kau pulang lewat gang.<br />
“Gang penanda waktu senja, waktu pemisahan<br />
dua hati yang harusnya tetap bersatu dalam bercinta,”<br />
itu katamu.<br />
Tahukah kau, Gang itu membuatku pada<br />
penghujung malam sering terbangun dari tidur lelap,<br />
bayangmu, senyummu bahkan tatapan gelisah menari-<br />
123
nari tepat diatas kepalaku. Pada udara basah yang turun<br />
bersama embun menjelang pagi, kenangan-kenangan<br />
yang lahir lewat mimpi, tarian wajahmu dipelupuk mata<br />
menjelang jaga malamku seringkali ikut tumpah dan<br />
rindupun terpuruk, dan menjadi kenangan mengetuk.<br />
Saat fajar aku menyatu dengan angin, ada asa<br />
menyeruak lewat mentari yang malu-malu dari balik<br />
hijau dan birunya gunung. Aku tertawa sendiri lalu<br />
menyatu, menyeru mengumumkan datangnya terang.<br />
Pagipun basah, burung pipit terbang mencari sarangnya<br />
yang hilang dengan gelisah. Rindupun kembali<br />
menghangatkan dan aku bersemangat, dan<br />
menikmatinya berulang-ulang dengan segenap<br />
perasaan.<br />
Pernah suatu hari, kau kirim aku tulisan meski<br />
kita sedang berhadapan, ku lihat sejenak ada semburan<br />
tetesan madu keluar dari bibir meronamu, lalu aku baca<br />
pesan yang kau tulis “apa begini cara kerja sesuatu yang<br />
engkau sebut cinta. Engkau bertemu seseorang, lalu kita<br />
perlahan-lahan merasa nyaman berada disekitarnya. Jika<br />
dia dekat, engkau akan merasa utuh, dan terbelah ketika<br />
dia menjauh.” Kalimat itu cukup membuat aku terbang,<br />
124
kalimat itu agung bersemayam bak ayat-ayat pembunuh<br />
sepi. Lalu, mengalirlah kata-kataku di sungaimu,<br />
berenang dan berkecipak jadi angsa-angsa yang riang<br />
bersaksi bagi laut yang redup.<br />
Senjapun datang lagi, Dewa.! Di tengah senja<br />
semua arloji kuhancurkan, agar pelukan tak mengenal<br />
kata pulang. Tapi, kemudian terbanglah kau menjauh<br />
bersama sayap rindu yang bukan aku, biarkan aku di<br />
sini menuliskanmu dalam puisi sendu. Duduk aku<br />
sendiri pada meja yang patah kaki. Dan, telah juga<br />
kugambar sayap di punggung agar rindu terbang<br />
mencari panggung. Di cintamu semoga semua berujung.<br />
Dalam hati penuh harap janganlah kau jadikan<br />
selendangku layang-layang bertaruh pada angin dan<br />
benang gelasan. Kini kau sudah terbangkan<br />
selendangku untuk mengubah warna langit<br />
menjauhkannya dari burung-burng terbang rendah yang<br />
melenggangkan tiap helai rambutku, rambut yang<br />
melukai mata angin kemudian mengintai hitam peta di<br />
tubuhku.<br />
Tentu saja aku tidak boleh terlalu<br />
berpengharapan, tapi kau mungkin mengenang<br />
125
lambaian tangan dan pesan-pesan agar berkabar setelah<br />
sampai tujuan. Adakah kau siap siaga mengintai debar<br />
jiwaku dan selalu berhasrat menghukumku. Kenapa kau<br />
menemuiku bagai cahaya yang melesat seketika alam di<br />
sekitar padam.<br />
Hayalanku berhenti ketika teriakan ibuku. Minyak<br />
lampu kaleng yang jarang sekali digunakan itu tumpah.<br />
Aku keluar kamar dengan badan penuh keringat. Aku<br />
kepanasan.<br />
126
9<br />
Rumah tua ini menyimpan banyak kenangan masa<br />
kecilku dulu. Pernah suatu hari, hari menjelang bulan<br />
Puasa, bulan ramadhan. Suasana kampung sepi, pagi-pagi<br />
tidak seperti biasanya. Tidak ada asap yang mengepul<br />
dari tungku dan kayu pokok kopi. Tidak ada bau<br />
gemercik minyak panas dan tidak ada bau kerak hangus.<br />
Aku sengaja tidak berhitung berapa hari menjelang<br />
Puasa. Karena bisanya ada yang sudah mulai, ada yang<br />
belum bahkan mundur jadwalnya tergantung pilihan<br />
mazhab atau keyakinan yang semakin hari semakin<br />
banyak sekali tafsir mazhab atau keyakinan. Awal bulan<br />
puasa ditandai oleh bulan naik atau bulan turun, yang<br />
dipelajari secara turun-temurun.<br />
Di kampung, ada beragam masyarap jika mengikuti<br />
ajaran yang berkembang. Ada Naqsyabandiyah,<br />
Muhamadiyah, Nahdatul Ulama dan banyak lainnya.<br />
Perbedaan ini semakin tajam saja jika memasuki bulan<br />
ramadhan atau idul fitri. Tetapi yang terjadi di<br />
kampungku. Hanya adat yang bisa mengikat dan<br />
menumpulkan tajamnya perbedaan keyakinan ini.<br />
127
Bahkan ada yang sengaja satu bulan penuh tidak<br />
menunaikan ibadah wajib yang disyaratkan dalam rukun<br />
Islam ini. Tentu alasannya macam-macam. Aku tidak<br />
akan bercerita tentang puasa di bulan ramadhan, bisa jadi<br />
pilihanku nantinya tidak mengikuti mazhab apapun<br />
dalam menjalankan kewajiban atau bisa jadi aku<br />
membebaskan diri dari kewajiban ini.<br />
Menjelang Ramadhan kali ini, bulan sya’ban. Bulan<br />
kedelapan dalam penangalan Hijriyah. Aku mulai<br />
membaca buku pada pertengahan Syah’ban. Buku<br />
kisahnya Layla dan Majnun. Majnun adalah sebuah lilin<br />
yang perlahan membakar habis dirinya dengan api hasrat<br />
di hadapan gadis itu. Keindahan Layla bak taman bunga<br />
mawar. Majnun bagaikan menara api yang menyala<br />
dengan kerinduan. Layla menebarkan benih-benih cinta.<br />
Majnun menyiraminya dengan air matanya. Layla dan<br />
Majnun adalah kisah cinta dari negeri Timur yang cukup<br />
termasyhur. Sebuah kisah tentang cinta sejati yang<br />
menjelma menjadi kekuatan yang tak ada habisnya. Qays<br />
mencintai Layla dengan segenap jiwanya.<br />
Meski rasa cinta itu terhalang, ia menolak untuk<br />
menyerah. Kekuatannya bahkan memelihara rasa cinta<br />
128
itu. Ia berjalan tak tentu arah sambil mendendangkan<br />
lagu-lagu cintanya, menitikkan air-mata kesedihannya.<br />
Orang-orang yang berpapasan dengannya meneriakkan<br />
namanya, si “Majnun” (si “Orang gila”).<br />
Ini buku pertama yang di belikan oleh Bapakku.<br />
Dia beli di toko buku bekas di kota Curup ketika<br />
mengantar sepupunya beli televisi hitam putih 14 inch.<br />
Setelah membaca buku ini dengan serius. Ada<br />
dialog yang terjadi dalam diriku. Dialog ini semakin liar.<br />
Bahkan sangat terpengaruh dengan Dewa, dengan Senja.<br />
Terpengaruh dengan perubahan biologis anak laki-laki<br />
yang bersifat ireversibel.<br />
“Nah, sekarang mari kita mulai dengan Cinta dan<br />
Sex.” Aku berbicara dengan diriku sendiri. Dan itu terjadi<br />
di hari ke 3 dimana aku menjalankan ibadah puasa.<br />
Cinta yang menyasar tapi dalam arti luas dan sex<br />
yang sempit. Cinta, kata para psikolog dan para pujanga<br />
tempatnya bersemayamnya dihati posisinya di bawah<br />
diafragma, di sebelah kanan rongga perut dengan massa<br />
yang lebih besar pada sisi kanan dan memanjang sedikit<br />
lebih ke kiri dari garis tengah. Dengan kata lain, jika<br />
Anda meraba dengan hati-hati tepat di bawah arkus kosta<br />
129
kanan Anda (di bawah tulang rusuk kanan). Tapi anehnya<br />
kita sering merasa sakitnya tuh di sini (di dada sebelah<br />
kiri). Aku menjelaskan pada diriku sendiri. Dan lalu aku<br />
menjelaskan ke seseoarang yang berada di kursi rotan.<br />
Dia mirip dengan diriku. Matanya terlihat merah tapi<br />
tidak bertanduk.<br />
Cinta bisa saja melompat dari pijakan apa saja dan<br />
pada akhirnya capaiannya adalah kenyamanan,<br />
kedamaian. Kenyamanan ini abstrak tapi bisa di buat<br />
indikatornya. Bisa jadi indikatornya muncul dari mata,<br />
maksudnya tatapan mata, tatapan yang bersinar, lisan<br />
yang manis dan lembut, bahkan bau badan. Pokoknya<br />
ketika sampai pada rasa nyaman, rasa ini akan<br />
mempengaruhi indera lain dengan rentang waktu yang<br />
lama bahkan ada yang cuma numpang lewat hanya<br />
sebentar. Naluri anak tertuaku muncul. Suka memaksa<br />
kehendak. Teman imajinasiku terlihat seperti menganguk.<br />
“Lalu, Sex. Sex yang berhubungan dengan kelamin.<br />
Sex ini dia bisa saja menyasar lain jenis maupun yang<br />
sejenis. Capaian terjauhnya adalah kepuasan, dan rentan<br />
waktunya hanya sebentar tapi bisa bekali-kali.” Aku<br />
130
mulai nakal dan keluar tabu adat. Dan teman imajinasiku<br />
mulai tersenyum tapi tidak lebar dan terbahak-bahak.<br />
Lalu, apa hubungannya cinta dan sex.? Aku mulai<br />
bingung dengan pertanyaan ini, lalu mencari jawaban.<br />
“Begini.” Seperti ada yang berbisik. Masingmasing<br />
orang tentu berbeda dalam melihat cinta dan sex<br />
ini, dan sangat mungkin tergantung dengan pemahaman,<br />
kepentingan, pengetahuan bahkan pengalaman soal cinta<br />
dan sex. Semakin berpengalaman biasanya semakin<br />
canggihlah jawabannya. Kata teman imajinasiku sambil<br />
mengeserkan kursinya.<br />
“Cinta dan sex ini satu mata rantai yang tidak<br />
terpisahkan.” Aku berkesimpulan kawan imajinasiku ini<br />
punya pengalaman dan sekaligus rakus soal cinta dan sex,<br />
dalam satu kesempatan dia mau dapat kepuasan dan<br />
kenyamanan sekaligus.<br />
Padahal menurutku yang belum berpengalaman ini.<br />
“Cinta seperti katabolisme atau respirasi,<br />
merupakan proses pemecahan dan melepaskan sejumlah<br />
energi (reaksi eksergonik).” Aku mulai berteori. Energi<br />
yang lepas tersebut digunakan untuk membentuk<br />
adenosin trifosfat (ATP), yang merupakan sumber energi<br />
131
untuk seluruh aktivitas kehidupan yang positif. Sehingga<br />
cinta ini pada prinsipnya sama seperti katabolisme<br />
merupakan reaksi reduksi-oksidasi (redoks), karena itu<br />
dalam reaksi tersebut diperlukan akseptor elektron. Mari<br />
kemudian kita sebut dengan sex gunanya seperti dalam<br />
reaksi kimia hanya untuk menerima elektron dari reaksi<br />
oksidasi organik. Aku mulai memaksa lagi.<br />
“Ini kalau cinta setara antar lain jenis atau sejenis.”<br />
Tanya teman imajinasiku. Dia mulai memaksa.<br />
“Lalu mari kita perluas sebaran capaian cinta.” Aku<br />
tidak mau kalah. Cinta sesama tapi bukan sejenis. Cinta<br />
persahabatan, cinta dengan ibu, cinta dengan pekerjaan.<br />
Kata ibuku cinta antara dia dengan anaknya, itu aku.<br />
Cinta itu tak bersyarat seperti putik jadi buah dan rela<br />
jatuhkan dirinya pada tangan rapuh, tangan retak, tangan<br />
yang rela menampung hidup pahit.<br />
Cinta itu bukan romantisme kolektif, tapi<br />
penyerahan, penderitaan bahkan pengorbanan, untuk<br />
sikap, untuk pilihan, untuk senyum bahkan untuk sedih<br />
yang berurai air mata. Ini seperti paradoks. Cinta tak<br />
bersayarat bukan cinta yang megejar kenyamanan. Pada<br />
posisi ini cinta setara (antar lawan jenis maupun sejenis)<br />
132
terlalu sempit apalagi ada pariabel sex, mungkin dengan<br />
momen puasa cinta seperti ini bisa dikoreksi. Jelasku.<br />
Karena berpuasa bisa jadi salah satu tujuannya adalah<br />
pengorbanan untuk cinta, cinta akan kawajiban umat<br />
teradap keyakinannya.<br />
Ah, aku mulai binggung sendiri menjelaskan soal<br />
ini, karena keterbatasan pengalamanku soal cinta dan sex.<br />
Jadi aku harus berhenti untuk berdialog.<br />
“Tapi begini saja, dalam perjalananya. Bisa jadi<br />
kita sudah mendapatkan kenyamanan dan kepuasan atau<br />
kita dalam proses menuju dua hal tersebut, baiknya buat<br />
komitmen atau tetaplah pada komitmen yang sudah<br />
terlajur dibuat. Dan, bisa jadi kita akan ketemu dengan<br />
cinta yang penyerahan, cinta tak bersyarat walau diiringi<br />
dengan urai air mata, karena disitulah kita akan<br />
menemukan cinta yang sesunguhnya.” Aku mulai<br />
berkesimpulan dan teman imajinasiku tersenyum<br />
mengejek.<br />
Aku menjadi ingat kata Rubi’ah Al-Adawiyah. Dia<br />
bilang bahwa jarak antara orang yang mencintai dan<br />
dicintai tidak ada internal atau jarak, cinta itu ungkapan<br />
kerinduan dan gambaran perasaan yang terdalam. Siapa<br />
133
yang mengenalinya pasti akan merasakannya.<br />
“Tuhanku,” dia berdoa. Jika ibadahku untuk surgamu<br />
jauhkan surga itu dariku, jika sembah sujudku karena<br />
takut pada-Mu bara dan nyalakan api nerakamu bakarlah<br />
jasadku. Jadi sanggupkan kita bilang jika yang ingin aku<br />
capai dalam cintaku adalah kenyamanan maka<br />
buatkanlah hatiku terbakar cemburu dan menderita?<br />
Karena dalam prosesnya akan ada perasaan sedih ketika<br />
dimabuk cinta, hati mengelepar menahan rindu, terputus<br />
lalu nyambung teradang ketemu surga dan tak jarang<br />
ketemu neraka. Cinta itu seperti pertarungan yang tidak<br />
berpantai kata Kata Rubi’ah Al-Adawiyah.<br />
Ku tendang kursi yang berada di sudut ruang itu,<br />
dan teman imajinasiku melompat lalu berlari lewat celah<br />
kayu jendela. Mendengar suara kursi roboh, ibu datang<br />
sambil membawa baki rendaman beras. Lalu memintaku<br />
untuk menjadikannya tepung, sore nanti akan dia olah<br />
jadi pembuka puasa kami.<br />
134
10<br />
Nenek Pia berkunjung ke rumah kami. Dia tahu aku<br />
pulang kampung. Katanya dia rindu dan malam tadi dia<br />
mengaku ketemu denganku, ketemu dalam mimpi. Dia<br />
sudah enam tahun tidak ketemu denganku. Kami<br />
mengobrol di dapur ibuku. Fisiknya masih terlihat masih<br />
sehat di usianya yang sepuh. Tidak tuli, gigi-giginya<br />
masih utuh, matanya masih awas. Dulu dia pembuat tape<br />
terbaik dikampungku. Aku adalah langganan dan<br />
penyuka tape buatannya. Setalah ngobrol, dia pamit<br />
pulang. Dia mesti ke kebun di ujung desa. Dia panen<br />
cabe dan terong. Aku janji sore akan ajak anak-anakku<br />
berkunjung ke kebunnya.<br />
Melihat punggungnya aku ingat puluhan tahun lalu.<br />
Setelah pulang Sholat Jumat di Masjid yang satu-satunya<br />
ada di Kampungku. Rumah kami kedatangan tamu.<br />
Mereka datang dari Jakarta. Sengaja ketemu dengan<br />
Bapakku. Mereka empat orang. Katanya mereka akan<br />
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan<br />
mengunakan aliran Sungai yang mengalir deras di<br />
135
kampungku. Dan katanya sebelumnya ada teman mereka<br />
yang juga datang menemui Bapakku. Aku masih inggat,<br />
itu beberapa tahun lalu. Dua diantarnya berpenampilan<br />
rapi dan kulitnya putih bersih. Kontras dengan kulit kami<br />
yang dekil dan ada peninggalan jejak-jejak penyakit kulit.<br />
Dua agak hitam tapi bersih. Mereka mengobrol di<br />
beranda rumah kami. Dan aku duduk seperti penterjemah<br />
disamping Bapakku.<br />
Bapakku tidak terlalu bersemangat untuk meminta<br />
mereka menginap dirumah, selain tidak ada kamar tamu,<br />
dipan, kasur, kamar mandi dan WC. Untuk kebutuhan<br />
MCK biasanya kami hajadkan di sungai kecil yang kami<br />
sebut dengan Uneu. terletaknya 500 meter dari rumah<br />
kami. Bapakku, dan harus aku akui jika di bandingkan<br />
dengan empat tamunya sama sekali tidak mencerminkan<br />
gempita era industrialisasi, globalisasi seperti yang aku<br />
dengar-dengan di televisi umum milik desa itu. Pada<br />
akhirnya mereka mereka tidak menginap di Kampungku,<br />
sesudah Bapakku biarkan obrolan berkepanjangan tanpa<br />
ada tanda-tanda mempersiakan mereka menginap.<br />
Tengah asik kami mengobrol, tentang potensi<br />
PLTA, tentang perubahan debit arus, tentang hutan di<br />
136
hulu Sungai tentang persiapan awal feasibility study. Itu<br />
yang aku dengar dari pembicaraan mereka. Aku tentu<br />
tidak malu. Bapakku mampu mengimbangi obrolan ini.<br />
tiba-tiba datang Nenek Pia yang mungil tubuhnya dan<br />
amat keriput wajahnya, dia sering mengurut perutku<br />
kalau aku sakit atau demam. Dia datang menemui<br />
Bapakku. Dia menawarkan bungkusan-bungkusan tape<br />
beras di bungkus dengan sejenis daun. Makanan<br />
kesukaanku. Bapakku langsung membeli. Itu bukan<br />
karena sok terharu oleh semangat hidup orang Nenek Pia<br />
yang telah ditinggalkan oleh Suaminya 18 tahun lalu, tapi<br />
karena tape beras buatannya memang enak sekali<br />
rasanya, entah bumbu apa selain ragi<br />
yang dicampurkannya ketika meramu tape, tapi rasa<br />
enaknya terutama berasal dari keperibadian dan<br />
keiklasannya.<br />
Tapi, ternyata uang di saku bapakku, cuma ada<br />
hanya enam ribu rupiah. Aku mengintip ketika dia<br />
membuka dompet dan menghitung lembaran uang yang<br />
tersedia di dompetnya. Itu hasil dia mengangut semen<br />
untuk irigasi yang sedang dibangun di kampungku.<br />
137
Padahal untuk tamu yang datang sebanyak ini<br />
setidaknya perlu dua bungkus dan sebunghkusnya<br />
seharga lima ribu rupiah. Maka seorang tamu dari Jakarta<br />
langsung berinisiatif mengeluarkan sepuluh ribu rupiah<br />
dan langsung di berikan ke Nenek ini enam belas ribu<br />
rupiah untuk dua bungkus. Tiba-tiba Nenek itu kemudian<br />
mengembalikan satu lembar ribuan dan selanjutnya<br />
mengembalikan yang lima ribuan, “Aduh ini<br />
bagaimana?” protesnya. “ambil dua bungkus kok<br />
uangnya enambelas ribu rupiah!”<br />
“Loh, Nek Bapak ini memang sengaja memberikan<br />
semua ini kepada nenek.” Aku coba menjelaskan.<br />
Aku tahu dia cukup akrab dan sayang padaku.<br />
Kemudian tiba-tiba wajah nenek menyala, sorot matanya<br />
meluncurkan anak panah kewajah kami.<br />
“Jangan merendahkan kami orang kecil.” Katanya<br />
keras sambil pergi membawa baki dari anyaman bambu<br />
sisa tape yang belum laku.<br />
Kami semua terkesima untuk beberapa lama, shock<br />
rasanya, bahkan tamu Bapakku yang datang dari Jakarta<br />
itu tersiam dan gelisah sangat lama. Kami merasa<br />
138
terpukul sangat keras oleh sesuatu, tetapi pikiran kami<br />
tidak cukup sigap untuk menguraikan apa gerangan itu.<br />
“Kenapa dia begitu tersinggung dan agak marah?”<br />
celetuk salah seorang dari mereka yang berbaju merah<br />
kotak-kotak.<br />
“Aku yang bersalah sok mau amal.” Jawabku<br />
namun terbata. Padahal maksudku mau pamer ke Nenek<br />
bawa ada teman bapakku yang datang dari Jakarta dan<br />
mereka kaum berduit dan akan punya proyek besar.<br />
Proyek pembangunan PLTA di Kampungku.<br />
Sedang asik-asiknya mereka mengobrol ibu datang<br />
dan menawari mereka makan. Ibuku tahu tidak ada<br />
rumah makan di kampungku. Mereka makan dengan lauk<br />
apa adanya. Setelah itu mereka pamit dan meninggalkan<br />
tugas untuk Bapakku yang sudah mereka obrolkan<br />
sebelum makan. Tugas itu mengukur debit arus sungai.<br />
Dari obrolan singkat itu Bapakku mencatat meteode yang<br />
digunakan adalah metode Equal Discharge Increment<br />
(EDI) dan Equal Width Increment (EWI). Metode Equal<br />
Discharge Increment dilakukan dengan cara membagi<br />
debit pengukuran menjadi bagian yang sama sejumlah<br />
sampel yang akan diambil. Itu petunjuknya. Lalu.<br />
139
Metode Equal Width Increment dilakukan dengan cara<br />
membagi lebar penampang sungai menjadi beberapa<br />
bagian yang sama tergantung dari jumlah sampel yang<br />
akan diambil. Vertikal pengambilan sampel terletak pada<br />
tengah-tengah dari bagian penampang tempat<br />
pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel dapat<br />
dilakukan dengan metode point sample dan depth<br />
integrated. Lamanya waktu pengambilan ditentukan<br />
berdasarkan kecepatan aliran. Ada dua buah alat yang<br />
mereka tinggalkan. Namanya Flowatch FL-03. Tidak ada<br />
pertanyaan dari Bapakku pertanda dia sudah tahu<br />
mengunakan alat ini.<br />
Seminggu setelah mereka datang. Aku selalu<br />
menemani Bapakku mengukur arus Sungai yang ada di<br />
Kampungku. Setiap hari dilakukan selama dua kali. Pagi<br />
dan sore. Sore itu aku yang selalu bertugas membawa<br />
buku dan mencatat hasil perhitungan Bapkku. Di jalan<br />
menuju Sungai, kami berpas-pasan dengan Nenek Pia.<br />
Dia dari habis menumbuk beras menjadikanya tepung di<br />
mesin kincir kayu yang ada disungai. Dia terbungkukbungkum<br />
memikul keranjang yang berisi tepung beras.<br />
Keranjang yang sama ketika dia datang menjual tape<br />
140
minggu lalu. Dia tersenyum padaku. Dan aku seperti<br />
ditampar.<br />
Aku duduk ditepian sungai dan bapakku sibuk<br />
dengan alat ukurnya. Aku belum bisa melupakan<br />
peristiwa minggu lalu.<br />
Jelas ada sesuatu yang menganjal hatiku.<br />
Senyum Nenek Pia.<br />
Dan aku merasa sangat bersalah.<br />
Bersalah dengan sikap dan psikologis kelas, sok<br />
priyai, borjuasi, kelas atas dan sok kaya. Memandang<br />
kebawah dan menganggap Nenek Pia yang tua dan janda<br />
itu orang rendahan yang bisa di hina dengan pemberian<br />
beberapa ribu rupiah. Aku yang merasa jadi aristokrat<br />
karena di datangi tamu dari Jakarta dan merasa bahwa<br />
Nenek ini orang kecil yang akan berbahagia dan<br />
menyembah-yembah karena kita beri kemurahan amal.<br />
Aku tidak bisa memendam rasa. Sampai di rumah<br />
ibuku sedang sibuk meramu tape. Begitu dia tahu kami<br />
masuk ruangan dapur, dia bertanya “ada bawa gula.”<br />
Bapakku langsung jawab “ada” pertanyaan dan jawaban<br />
ini menandakan tape yang dibuat akan manis. Aku duduk<br />
disampingnya. Lalu bercerita tentang Nenek Pia. Dengan<br />
141
senyum dia kemudian menjelaskan bahwa manusia hanya<br />
memperoleh sebatas yang dikerjakannya, manusia tak<br />
berhak menerima upah yang berlebih, apalagi merampok<br />
kelebihan itu, entah melalui kecurangan politik<br />
perekonomian, melalui monopili, nepotism atas<br />
pembocoran system-sistem.<br />
“Hanya maling dan pengemis yang melakukan itu,”<br />
Kata ibuku sambil membungkus Tape dengan daun<br />
kemiri.<br />
Aku mulai berpikir apakah nilai semacam ini<br />
mengakar secara alamiah dalam hati nurani keperibadian<br />
sang Nenek Pia. Ataukah ini sekedar peristiwa normal<br />
tentang kemandirian manusia. Dalam hatiku. Seandainya<br />
Nenek setua itu datang mengemis, kami pasti<br />
memberikannya uang meskipun sekedar ratusan atau<br />
ribuan, tetapi tampaknya ia sama sekali tak punya mental<br />
pengemis, ia baru merasa sah untuk hidup jika atas hasil<br />
keringatnya sendiri dan atau serupiah pun ia tidak<br />
bersedia menerima lebih dari takaran hasil kerjanya.<br />
Aku jadi berhayal kalau kita menjaul beras seharga<br />
seratus ribu rupiah untuk tiga kaleng beras lantas orang<br />
membelinya dengan dua ratus ribu rupiah, akankah tidak<br />
142
kita terima uang itu? Kita bahkan akan menerima uang<br />
seratus ribu rupiah tanpa tukar jasa pun dari kita.<br />
Bahkah. Dari cerita orang-orang kampung ketika<br />
pulang lebaran, orang-orang modern di kota-kota besar<br />
suka sekali mengemis-ngemis, menjilat-jilat, menyogoknyogok.<br />
Bahkan katanya. Lebih dari itu. Mereka<br />
merampok, merampas, merebut tidak hanya ratusan ribu<br />
bahkan juta-an, miliaran, beribu hektar tanah,<br />
bersamudra-samudra hak dan kedaulatan orang banyak.<br />
“Seandainya kita bekerja tanpa gaji, kita akan<br />
protes, dan seandainya kita digaji tanpa kerja, pasti kita<br />
terima. Sebab, yang kita cari uang, bukan kerja.” Kata<br />
mereka di suatu ketika. Dan aku membayangkan betapa<br />
keras dan kejamnya Jakarta dan kota-kota besar.<br />
Bayangan itu semakin menjadi ketika aku menonton film<br />
Kejamnya Ibu Titi Tidak Sekejam Ibu Kota. Film yang di<br />
produksi di tahun 1981 yang diperankan oleh Ateng dan<br />
Ishak yang menceritakan betapa menderita keduanya di<br />
Jakarta.<br />
“Itulah Nenek tua renta, orang tua dan kuno yang<br />
tidak berpendidikan, wajah keriput dan pakaian kumuh<br />
yang tidak tersentuh dengan gegap-gempita<br />
143
pembangunan, moderinisasi, perkembangan ekonomi<br />
Negara, kemerdekaan dari penjajah, inovasi pemikiran<br />
ultramodern, kecangihan teknologi, serta omong besar<br />
dari Pemilu ke Pemilu. Maka belajarlah cara dan<br />
bagaimana dia hidup.” Pesan Bapakku. Dia pasti Bela<br />
karena Nenek Pia itu adalah saudara dekat Bapaknya.<br />
“Nenek ini bekerja, namun tidak memperbudak<br />
dirinya pada orientasi keuntungan sebesar-besarnya,”<br />
Tambah Bapakku sambil memeriksa catatan arus sungai<br />
yang aku catat tadi. Ada nada marah. Sepertinya ada<br />
catatan yang salah aku tulis.<br />
“Nenek Pia berjualan tetapi tidak kapitalistik, dia<br />
mencari nafkah tapi tahu memerangi keserakahan. Tapi<br />
kemudian orang-orang yang nyaring berpidato tentang<br />
kemandirian dan kehormatan sebagai anak bangsa,<br />
mereka jugalah yang menceramahi mereka tentang<br />
profesionalisme dan progresivitas manusia industrialis.”<br />
Dia melanjutkan. Intonasinya tetap sama kemudian dia<br />
meninggalkan kami di ruang dapur dan aku Cuma bisa<br />
terdiam. Kata-katanya menyerang sanubariku yang sudah<br />
mulai gemar membaca buku hasil curian dari ruang<br />
perpustakaan sekolahku.<br />
144
Aku merenung.<br />
Bukankah kita jua yang memompa kepala besar<br />
kita dengan cara memandang mereka. Kitalah yang,<br />
dengan kebobrokan keperibadian kita, dengan<br />
keterpecahan mentalitas kita, dengan mental pengemis<br />
dan penindas kita, menguburkan mereka dalam timbunan<br />
kata-kata angkuh yang penuh estetika dan daya intelek,<br />
serta yang membingungkan diri kita sendiri. Kita jugalah<br />
yang berusaha melupa-lupakan fenomena kecemerlangan<br />
manusia-manusia semacam itu sambil mengangkat bahu<br />
dan berkata<br />
“Ah, romantic!”<br />
Nenek Pia ini pasti tidak tergolong berjasa atas<br />
negeri dan bangsa ini, sehingga tidak menagih apa-apa<br />
buat nasibnya, tidak meminta perkebunan, bukit, atau<br />
saham-saham, tetapi mungkin itu yang membuatnya<br />
mandiri, bekerja keras dan menjaga kehormatannya<br />
sebagai manusia hingga buram senja hari tuanya. Itu pula<br />
yang tampaknya membuat sang Nenek tetap kuat. Tidak<br />
tuli telinganya, tidak rabun matanya dan tidak sakit<br />
pinggangnya.<br />
145
11<br />
Aliran Sungai Hulu Ketahun ini selain dugunakan<br />
untuk kebutuhan MCK dan Pengairan areal persawahan.<br />
Juga digunakan untuk Pembangkit Lintrik Tenaga Air<br />
(PLTA). Potensinya luar biasa. Makanya Bapakku dulu<br />
diminta untuk mengukur Debit Sungai. Rencananya akan<br />
di bangun satu lagi Pembangkit dan akan merendam<br />
empat perkampungan dan ratusan hektar areal<br />
persawahan. Akan ada ganti rugi. Itu desas-desus yang<br />
aku dengar. Padahal masyarakat di hulu Sungai ini sangat<br />
tergantung sekali dengan Sungai ini. Sungai ini adalah<br />
identitas bagi mereka. Simbol-simbol adat dan<br />
kepercayaan mistik. Kepercayaan ini muaranya adalah<br />
sungai.<br />
Sebagai komunitas adat. Masyarakat kampungku<br />
beranggapan bahwa ada kekuatan lain diluar kekuatan<br />
manusia yang dimanifestasikan kedalam bentuk<br />
kepercayaan terhadap penguasan alam yang tampak dan<br />
penguasan alam yang gaib, kepercayaan ini seakan-akan<br />
melekat dengan erat dengan kehidupan warganya.<br />
146
Di suatu pagi pernah aku antar dan kawani<br />
Bapakku mengukur debit arus sungai. Pagi Jumat. Dan<br />
aku tidak masuk sekolah karena kelender menunjukan<br />
hari besar Agama Islam.<br />
“Hari tanggal merah.”<br />
“Hari libur nasional.” Ceritaku ke pada Bdikar<br />
ketika mengantar dia berenang. Meskipun berada di hulu<br />
sungai dan terisolasi, kampungku juga mengalami<br />
akulturasi budaya. Warna akulturasi ini kontras sekali<br />
dengan pengaruh masuknya kebudayaan islam.<br />
Tambahku.<br />
“Salah satu aplikasi dari system kearifan local<br />
dimana kepercayaan gaib ini melekat dalam system<br />
budaya dapat dilihat dari proses awal kelahiran seorang<br />
bayi.”. Ritual ini disebut dengan ‘mbin cupik moi<br />
muneau’. Jelasku. Ritual dimana bayi yang baru lahir<br />
dibawa ke tempat pemandian umum.<br />
“Ritual ini untuk memperkenalkan bagi bayi<br />
kepada alam dan makluk yang dipercayai sebagai<br />
penunggu air (semat medek ilia, dung/ular, ke’it, gulung<br />
kasua, kebeu biyoa, sebei beleket).” Kata Bapakku ketika<br />
aku mengantar dia menghidung debit air.<br />
147
Aku merinding mendengar nama-nama penunggu<br />
gaib ini. Informasi yang sering aku dengar jenis-jenis<br />
makluk penunggu air dipercayai bisa membawa bahaya<br />
dan bencana bagi manusia.<br />
“Ritual ini bentuk permohonan agar si bayi ketika<br />
dewasa bisa selamat ketika dia punya dengan urusan air.”<br />
Jelas Bapakku. Ketika kami duduk sambil menghitung<br />
debit air. Lalu aku tanyakan apakah aku juga ketika bayi<br />
dilakukan juga ritual ini. Dan cerita Bapakku membuat<br />
kutakut. Belum tahu sampai kapan aku berhenti<br />
membantu dia mengukur debit arus sungai ini. tentu ritual<br />
ini menjadi garansi keselamatanku selama berada di<br />
sungai<br />
“Ada beberapa proses yang harus dipersiapkan<br />
dalam melaksanakan ritual,” Kata Bapakku. Sepertinya<br />
dia akan menceritakan pengalaman dia ketika aku bayi<br />
dulu.<br />
“Apa saja Bak,?” Tanyaku<br />
Pertama keluarga yang akan melaksanakan ritual<br />
ini harus mengadakan rembuk keluarga (basen asuak<br />
basuak, basen sesanok) untuk membicarakan keperluan<br />
yang harus dipersiapkan dan berbagi pekerjaan dalam<br />
148
pelaksanaan ritual. Setelah itu dilakukanlah Berasan<br />
Kutai (basen kutai) untuk menjadikan ritual/hajatan<br />
keluarga tetapi menjadi ritual komunitas. Jelas Bapakku,<br />
sambil menampakkan angka-angka di Flowatch dan aku<br />
mencatat.<br />
Isi basen kutai menyepakati: kesepakatan hari<br />
mendirikan kemujung (tempat dilaksanakannnya jamuan,<br />
mendirikan kemujung ini dilakukan secara gotong<br />
royong) juga dengan penyiapan bahan material untuk<br />
seperti bamboo, akar-akaran dan kayu, serta keperluan<br />
untuk bahan makanan utamanya rempah-rempah<br />
dilakukan gotong royong. penetapan hari pelaksanaan<br />
ritual.<br />
“Pemotongan seekor kambing adalah syarat agama<br />
yang di sebut aqiqah yang dilakukan dalam ritual adat.”<br />
Tambah Bapakku.<br />
Seperti dukun saja Bapakku kemudian menjelaskan<br />
beberapa bahan keperluan untuk ritual tersebut<br />
diantaranya sekapur sirih (iben meson, iben mateak),<br />
rokok yang terbuat dari daun nipah, bahan percikan (guik<br />
minyok), dupa kemenyan, kain warna hitam, mangkok<br />
putih yang diisi dengan daun tertentu (setabea), sapu lidi<br />
149
yang terbuat dari lidi kelapa hijau yang diikat dengan<br />
benang tiga warna yang disertai dengan beberapa sejenis<br />
daun yang dipercayai sebagai penangkal dari gangguan<br />
makluk gaib serta tikar yang terbuat dari daun pandan.<br />
Selain bahan-bahan tersebut juga dipersiapkan<br />
seberapa bahan lain yang akan digunakan ketika<br />
memandikan sang bayi antara lain kemiri, kunyit, pisau<br />
ada juga yang pakai keris, duit logam, bara api dari<br />
kayu/putung opoi, sembilan jenis bunga, jeruk<br />
nipis/lemeo langgia, air tangis tepok, sejenis alu/kelicung<br />
dan wadah tempat memandikan bayi/reseng.<br />
“Bahan-bahan makanan juga dipersiapkan.<br />
biasanya kue-kue local rejang (bajik, lemang/benik, Kue<br />
Apam/sabai, ta buruk dan serawo yang terbuat dari beras<br />
ketan yang dibumbui dengan kelapa yang dicampur<br />
dengan gula aren.” Katanya. Dan perutku berbunyi ketika<br />
mendengar jenis-jenis makanan ini. dari pagi belum<br />
sarapan.<br />
Pembagian peran dilakukan secara rinci kata<br />
bapakku. Dukun laki-laki biasanya membawa lidi kelapa<br />
hijau yang sudah diikat dengan kain warna hitam. Ada<br />
yang membawa dupa. Dan dukun bayi perempuan<br />
150
memandikan bayi, bayi digendong oleh seorang anak<br />
(bayi laki-laki dibawa oleh laki-laki dan begitu juga kalau<br />
bayinya perempuan di bawa oleh anak perempuan),<br />
bujang dan gadis memakai baju adat juga ikut<br />
mengantarkan bayi, ulubalang membawa tombak, pedang<br />
dan keris, kedua orang tua dan beberapa tua-tua<br />
komunitas/desa serta anak-anak biasanya ramai ikut<br />
dalam ritual mengantarkan sang bayi ketempat<br />
pemandian. Jelas Bapakku. dan aku berbungga-bungga<br />
bukankah aku dulu ketika bayi di arak oleh orang<br />
sekampung lalu dimandikan di sungai yang sekarang aku<br />
hitung arus debitnya.<br />
Begitu sampai di tempat pemandian si dukun<br />
menyiapkan bahan-bahan lalu membakar kemenyan di<br />
dupa yang telah disiapkan. Si dukun berkomunikasi<br />
dengan penguasa gaib dan arwah para leluhur untuk<br />
meminta izin pelaksanaan ritual memandikan bayi.<br />
“Sama seperti proses Kedurai ya,” Tanyaku<br />
“Ia.” Jawab bapakku lalu diam, sepertinya dia<br />
mengingatkan atau menghapal sesuatu. Mulutnya komat<br />
kamit jelas bukan di tujukan kepadaku.<br />
151
Kemudian melapaskan seperti puji-pujian dengan<br />
nada aneh.<br />
“Hai sepanjang hidung, hai sepajang hidung, hai<br />
sepanjang hidung, dio uku madep kumu, kumu do<br />
tekadeak temungau biyoa, kemuaso biyoa, temungau tang<br />
aai, kumu kulo do jemago lot ngen ai tang aai, uku medeu<br />
kumu bae ngami, asep kemenyenku melayang, belas<br />
kemunik uku mamua, awei o kulu adat bahasoku<br />
ngenkumu, dio ade iben ngen rokok, awei o kulu pembuk<br />
pangen kumu berupo sabai, baso uku menok kedeu kumu<br />
yo, uku lok madea keturuak, baso bilai yo bilai baik<br />
bulen betuweak, keme mi’ing anok keme di betegen<br />
….(nama bayi) moi muneun, penan dik kenuaso kumu,<br />
ujud maksud keme mbin si moi muneun yo, dio keme<br />
melei namen made keturuak magea kumu dik tekadeak<br />
penguaso biyoa, kemuaso lubuk, dik temungau lubuk,<br />
temungau tebing, waei o kuo magea kumu do temungau<br />
kiyeu, keme teko magea kumu yo, lok minget supeak<br />
semanyo janjai setio kumu mena’o, amen keme melei<br />
pemuk pangen kumu mako kumu coa buliak, keniayo<br />
magea umat manusio, neak bilai yo keme magiak pemuk<br />
pangen kumu kiro ne kumu dapet temimo ngen kumu<br />
152
temimo pembuk pangen yo mako kumu, coa buliak<br />
kemniayo magea anok keme do betegen…… (nama<br />
bayi), amen kiro ne si telonok waktaumendai tulung<br />
kumu mbiding ne, amensi tendem tulung kumu cemungas<br />
ne, amen si ade saleak pemiling, saleak pengenea,<br />
mneakkumu tema’ok senapo si, mbeak kulo kumu<br />
temawe. Dio ba kecek do perlu uku semapei, dio uku<br />
magiak pembuk kumu.” Aku merinding mendengarkan<br />
puji-pujian ini. Lalu dia menjelaskan arti kata-kata apa<br />
yang di lapaskan ini. Dan menjelaskan dia dulu belajar<br />
dari Kakeknya tapi dia belum dibolehkan untuk<br />
melaksanakan ritual.<br />
“Nah,” dia melanjutkan penjelasannya.<br />
Setelah dukun melapaskan pujia-pujian ini kue<br />
apam/sabai di lemparkan ke arah air dan lidi dari kelapa<br />
hijau ditancapkan di pingir air. Bayi dimandikan di dalam<br />
wadah tempat memandikan bayi yang diisi dengan air<br />
dicampurkan dengan sembilan macam bunga dan bara<br />
api, dan duit logam. Bayi dimandikan oleh dukun bayi<br />
perempuan. Ketika inilah banyak jampi dan mantera di<br />
baca dan di sugesti menjadi pelindung sayang bayi.<br />
153
“Setelah dimandikan sang bayi diperciki dengan<br />
setepung setawar, sebelum pulang dari tempat pemadian<br />
semua bahan yang dibawa ditinggalkan di tempat<br />
pemandian. Begitu sampai dirumah. Ketika akan menaiki<br />
tangga rumah, ibu sang bayi diwajibkan untuk melangkah<br />
atau melewati sabut kelapa yang telah dibakar,” Lanjut<br />
Bapakku.<br />
Begitu sampai didalam rumah. Ibu sang bayipun<br />
diwajibkan mencuci tangan dukun perempuan dengan air<br />
yang telah dipersiapakan dalam wadah mangkuk<br />
berwarna putih dan memberikan sabun, duit, kain<br />
(keracok matea) sebagai ujud ucapan terima kasih<br />
terhadap dukun perempuan dan begitu juga terhadap<br />
dukun laki-laki yang telah membantu proses kelahiran<br />
sampai proses dimana bagi dibawa ke luar rumah/mbin<br />
moi muneun.<br />
Ritual ini berakhir ketika dukun mengendong bayi<br />
sambil mengucapkan “Bismillah hirahman nirrahim,<br />
aluhumma sali allla muhamad wa alai muhammat<br />
(sebanayak 3 kali) dio cupik keme, coa si gering keno<br />
panes, coa telep kenu ujen, cupik keme teko ne kundei<br />
awing-awang, cupik keme teko ne kundei tebo lekat sapei<br />
154
ulen penuak hu…..cupik keme”. Berakhirlah ritual adat<br />
kemudian dilanjutkan dengan ritual agama. Jelas<br />
Bapakku.<br />
“Oh, itu seperti adat memulai dan agama<br />
mengahiri,” Tanyaku sok tahu.<br />
“Ia,”<br />
“Jamuan kutai?”<br />
“Memotong rambut bayi yang diiringi oleh lapas<br />
shalawatan oleh tokoh-tokoh agama, itukan?” Tanyaku<br />
lagi.<br />
“Dan kali ini aku tahu.” Lanjutku.<br />
Aku sering diminta untuk mengendong bayi yang<br />
akan di cukur rambutnya. Anak tetangga dan anak-anak<br />
ponakanku. Proses ini sering juga disebut dengan parsanji<br />
atau marhaban perpaduan antara adat dan agama.<br />
Biasanya si bayi digendong oleh seorang anak. Ada<br />
gunting yang akan digunakan untuk memotong rambut<br />
bayi dicelup kedalam kelapa muda hijau yang telah<br />
dihiasi sebelumnya yang disertai dengan wewangian.<br />
Bayi dibawa keliling mengikuti barisan orangorang<br />
yang melapaskan persanji/marhaban. Ketika<br />
memotong rambut bayi beberapa tua-tua desa/komunitas<br />
155
iasanya mengucapkan jampi-jampi dan doa-doa untuk<br />
keselamatan sang bayi. Setelah semua orang-orang yang<br />
hadir memotong rambu sang bayi maka mulailah<br />
dilaksanakan acara jamuan atau makan-makan. Ritual<br />
biasanya diakhir juga dengan membongkar kemujung<br />
secara gotong royong membongkar kemujung.<br />
“Dulu cerita Nenek aku juga dimandikan di sungai<br />
ya pak?” tanya Bdikar.<br />
“Ia” Jawabku. Aku jadi ingat ketika membawanya<br />
Cuma dengan memakai motor. Umurnya belum 30 hari<br />
ketika itu. Mata besarnya melotot ketika ibuku menyiram<br />
dia dengan air rendaman keris. Tapi dia tidak menangis<br />
meski kedinginan.<br />
“Kenapa ketika dimandikan, sedingin apapun air<br />
yang digunakan bayi tidak akan menangis,” Tanyanya<br />
menyelidik. Dia tahu, diceritakan ibuku. Neneknya.<br />
“Tidak tahu,”<br />
“Mungkin tubuhnya diselimuti oleh kekuatan gaib”<br />
Jawabku seadanya.<br />
“Katanya Nenek, kalau bayi dilakukan ritual dia<br />
akan terhindar dari banyak penyakit,?”<br />
156
“Tidak adanya hubungan penyakit, kalau berprilaku<br />
kotor penyakit akan mendekat.”<br />
“Penyakit itu berhubungan dengan prilaku”<br />
“Oh” dia terdiam.<br />
“Dulu, ketika aku bayi,”<br />
“Juga di ritualkan, bahkan ari-ariku dihayutkan<br />
olehku atas perintah dukun” ceritaku ke Bdikar<br />
“Kenapa dihanyutkan?” tanyanya.<br />
“Hibahkan bulat-bulat,” Bdikar binggung.<br />
“Yakinlah,”<br />
“Mereka akan menjaga mu.”<br />
“Tetapi tetap jaga sikap.” Jawab kusingkat sambil<br />
mengajari Bdikar berenang menyeberangi sungai.<br />
Tiba-tiba aku lincah sekali berenang. Padahal hari<br />
ini hari terakhir kami di kampung. Besok pagi kami akan<br />
pulang ke rumah kami. Pulang dengan motor yang sama<br />
ketika dulu aku bawa Bdikar yang belum berumur 30<br />
hari.<br />
157
12<br />
Waktu telah berjalan seperti meloncat. Meski<br />
waktu berjalan ada kenangan yang masih tersisa tentang<br />
kampungku yang beberapa hari lalu kami kunjungi.<br />
Pulang. Tidak hanya mengingak kembali suatu yang<br />
pernah terjadi tetapi bisa kita lihat perkembangannya<br />
ketika waktu meloncat-loncat. Kampungku semakin<br />
ramai, semakin padat, semakin terang dan semakin<br />
tergerus kearifan yang dulu menompang hidup<br />
masyarakatnya.<br />
Aku sesekali pulang. Itu hanya untuk menemui Ibu<br />
dan Bapakku. Kalau aku pulang tidaklah sendiri lagi.<br />
Tetapi bersama rombongan. Anak-anakku dan cucu-cucu<br />
ibuku. Anak tertuaku Bdikar, ketika umur berumur 20<br />
hari adalah perjalan pertama dia mengunjungi kampung<br />
leluhurnya. Dia, tidak sakit dan menangis ketika dalam<br />
perjalanan selama 5 jam. Dia seperti menunggu-nunggu<br />
sejak dalam kandungan untuk di ritualkan oleh<br />
Kakeknya. Bapakku. Ritual membawa bayi ke air. Bdikar<br />
di mandikan dengan air sungai rendaman keris<br />
158
peninggalan leluhurku. Ini ritual terakhir yang aku<br />
saksikan.<br />
Ada mantera yang dirafalkan di tubuhnya oleh tuatua<br />
kampung ketika dia selesai di mandikan di sungai.<br />
Bdikar tumbuh beriring-iringan dengan pergeseran<br />
budaya kampung. Dia suka membaca, punya bakat<br />
menjadi orator, keras kepala dan suka sekali berdiskusi,<br />
mendengar dan pencerita yang baik.<br />
Sedang asik-asiknya Bdikar dengan ibunya belajar<br />
tentang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), tiba-tiba listrik<br />
mati dan Bdikar sepertinya kegirangan karena lepas dari<br />
cengkeraman ibunya, karena setiap belajar, maka volume<br />
suara ibunya selalu tinggi dan melengking. Udara malam<br />
ini panas, karena kipas angin tidak bisa dihidupkan dan<br />
kamipun pindah ke teras rumah. Teras rumah adalah<br />
bagian favorit dari rumah kami. Dengan hanya diterangi<br />
lilin, kami tidur-tiduran di sela koleksi bunga yang belum<br />
lengkap jenisnya, ada beberapa sansivera, bromelia dan<br />
antorium yang sudah dirawat sejak 3 tahun lalu.<br />
Kopipun datang tapi tidak ada goreng pisang,<br />
sepertinya lengkap sudah kebahagian ini.<br />
159
“Cerita lagi pak, tentang masa kecil bapak yang<br />
sederhana itu.” Minta Bdikar.<br />
Mendengar permintaan Bdikar, Titon adiknya<br />
mulai mendekat, dia senang sekali kalau aku cerita<br />
tentang apa saja.<br />
“Dulu, yang mengajari bapak membaca namanya<br />
Bapak Abdullah.” Ujarku memulai bercerita.<br />
“Dia masih ada hubungan keluarga dengan Bapak,<br />
cara dia mengajari murud-muridnya membaca tidaklah<br />
dengan mengenal huruf tetapi lebih dari itu, dia mulai<br />
dengan penguatan kognitif lalu afektif kemudian<br />
psikomotorik tapi dilakukannya dengan pelan-pelan.”<br />
Jelasku dengan cepat.<br />
“Bapak mestinya pakai bahasa yang sederhana saja<br />
biar mereka mengerti.” potong ibunya.<br />
“Jadi begini caranya mengajari kami nak,” Akupun<br />
menjelaskannya secara sederhana dengan analogi. Dia<br />
seperti memperkenalkan kami kepada Sungai kemudian<br />
menyuruh kami berenang keseberangnya, dimulai dengan<br />
memperkenalkan sungai dan beberapa elemenya sampai<br />
kami bisa menginggati bahwa itu sungai, lalu berinisiatif<br />
mau berenang kemudian berpikir bagaimana caranya agar<br />
160
isa berenang. Setelah ada inisiatif, kami diajarkan agar<br />
bisa beradaptasi dengan sungai, dengan temperatur, pola<br />
arus dan setelah kami bisa beradaptasi maka kami mulai<br />
berenang.<br />
“Oh, begitu caranya.” kata Bdikar. Dari caranya<br />
menjawab saya tahu dia pasti belum mengerti dengan<br />
analogi yang aku sampaikan itu.<br />
“Sebelum berangkat sekolah, Bapak biasanya<br />
dikasih sarapan nasi goreng, nasi yang disangrai hanya<br />
dengan mengunakan minyak kepahiang atau minyak<br />
kelapa.” Aku mengalihkan isue biar tidak menambah<br />
binggung anak-anakku dengan metode pendidikan kami<br />
dulu dikampung.<br />
“Berangkat ke Sekolah, Bapak tidak pernah dikasih<br />
uang jajan oleh Nenekmu.” Karena memang tidak ada<br />
duitnya. Bapak ingat betul, ketika pertama kali masuk<br />
sekolah, seragam bapak dibelikan dan di jahit oleh<br />
penjahit Minang tetangga kami. Dan, itu setelah<br />
Kakekmu mendapat upah angkut semen untuk bagunan<br />
irigasi yang sedang dibangun ketika itu. Ceritaku<br />
Tetapi sesekali kalau hari Senen, baru dikasih Jajan<br />
sebesar Rp. 100, karena hari senen itu hari pasar desa,<br />
161
yang lokasi pasarnya berdekatan dengan sekolah kami.<br />
Sesekali kalau lagi istirahat dengan modal Rp. 100 itu,<br />
bisa jadi Rp.500 atau Rp 1.000, duit jajan itu Bapak<br />
gunakan untuk taruhan judi, namanya “Dadu Kuncang”.<br />
Bapak paham betul angka apa yang akan keluar, itu<br />
tergantung dengan cara mengoyangkan penutupnya,<br />
kecenderungan angka kelipatan tiga yang keluar biasanya<br />
besar.<br />
Bapak selalu menang dalam permainan ini,<br />
biasanya dapat Rp.500 atau lebih, Rp. 100nya bapak<br />
tabung, dan sisanya bapak teraktir teman-teman bapak<br />
yang tidak dapat jatah jajan dari orang tuanya. Selain<br />
main Dadu, kebiasaan buruk Bapak ketika itu membawa<br />
buku-buku dari perpustakaan sekolah pulang kerumah<br />
dan tidak pernah bapak kembalikan.<br />
Pernah suatu hari bapak ketahuan tidak<br />
mengembalikan buku-buku tersebut, tetapi Kepala<br />
Sekolah kami tidak berani marah, karena Bapak menjadi<br />
salah satu perwakilan dari SD untuk ikut cerdas cermat di<br />
tingkat Kecamatan, alasan bapak buku-buku itu akan<br />
dibaca untuk bahan cerdas cermat. Tapi beberapa kali<br />
162
ketahuan, berbekaslah telapak tangan guru Kepala<br />
Sekolah di pipi Bapak.<br />
“Bdikar juga suka main tarik benang disekolah<br />
pak.” Ini kebiasannya Bdikar ketika mendengarkan<br />
cerita, dia juga terpancing untuk cerita juga tentang tema<br />
yang sama.<br />
“Bapak. Satu kelas dengan Bdikar itu ada teman<br />
Bdikar, Ibunya sudah meningal dan bapaknya menikah<br />
lagi, dia sekarang dititip di panti asuhan, aku setiap hari<br />
kasih dia Rp.1.000 rupiah untuk jajannya, kasian dia<br />
pak.” sambung Bdikar.<br />
“Ia baguslah kalau begitu, tapi jangan keseringan<br />
ya, nanti dia tergantung dengan Bdikar, kalau sesekali<br />
tidak apa-apa.” Kata ibunya yang selalu menonjolkan<br />
naluri pengelolaan keuangan berbasis cosh in dan ketat<br />
pada cosh flow kalau menyangkut tentang keuangan, dan<br />
bisa detail sekali. Dulu dia kuliah di Jurusan Akuntansi<br />
dan sekarang sebagai kepala dan mengatur sistem<br />
keuangan di rumah tangga kami yang pendapatannya<br />
tidak menentu.<br />
Akupun melanjutkan cerita. Begitu pulang sekolah<br />
biasanya Bapak biasa bantu Nenekmu di sawah atau ke<br />
163
Kebun, kalau tidak ke kebun atau kesawah, Bapak sering<br />
juga upahan bersama kawan-kawan jadi kuli angkut<br />
pasir, itupun kalau ada tetangga yang bangun rumah<br />
biasanya dapat Rp.300-Rp.500, pasirnya diambil dari<br />
sungai dekat kampung. Begitu sore datang, kami<br />
biasanya main bola, dulu ada lapangan bola, setelah<br />
lapangan itu dijadikan Sekolah SMP kami sering main<br />
bola di sawah yang berada di sekitar kampung.<br />
Begitu malam datang kami belajar membaca<br />
Alquran, tetapi Bapak lebih sering dan lebih suka belajar<br />
silat atau mendengar beberapa orang tua-tua berdiskusi<br />
tentang banyak hal dibanding belajar membaca Alquran.<br />
Aku sering mendengar cerita tentang ilmu yang berbau<br />
jampi-jampi, tentang makna dan perkembangan<br />
kehidupan. Aku suka dengan cara mereka berfalsafah.<br />
Dari obrolan mereka, aku tahu walaupun mereka<br />
tidak sekolah, mereka bijak sekali melihat penomena<br />
yang ada, visioner dan yang paling penting aku<br />
dibolehkan ikut dalam obrolan bersama dan mereka<br />
sesekali mendengarkan pendapatku. Mereka egaliter.<br />
Sekarang aku tahu bahwa ruang bagi anak-anak untuk<br />
terlibat bicara itulah wujud dari demokrasi yang sering<br />
164
dibicarakan itu. Kalau sudah tengah malam obrolan<br />
biasanya tentang tentang agama, mereka menyebutnya<br />
“Kajian Dalam”, kajian pengenalan atas Tuhan dimulai<br />
dari pengenalan tentang diri kita.<br />
“Sesi inilah yang paling bapak suka,” Lanjutku.<br />
Sering Bapak dengar tentang sifat 20 dan kata berdirinya<br />
Zat pada Sifat. Metode kongnitif, afektif dan<br />
psikomotorik yang diajarkan di Sekolah ternyata<br />
membantu Bapak bisa memahami obrolan mereka.<br />
“Sifat 20 itu apa.?” Tanya Bdikar<br />
“Sifat Allah”<br />
“Misalnya Sifat Allah itu adalah Ruh bagi<br />
manusia.” Ruh itu ditiupkan melalui ubun-ubun kepada<br />
qalbi manusia, semasih ia dalam kandungan rahim ibu.<br />
Jelasku.<br />
“Lalu?”<br />
“Dari jantung itulah kehidupan Ruh itu dipompakan<br />
keseluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh<br />
darah/vessel, maka gerak tubuh itu adalah gerak ruh<br />
dengan kendali hati.”<br />
“Baik kendali hati, baiklah gerak ruh yang zahir<br />
kepada jasad (raga).”<br />
165
Begitulah sebaliknya. Itulah sebabnya antara<br />
Syariát dengan Hakikat tidak boleh terpisah dan<br />
Thareqatlah yang mengaturnya., dan barangsiapa<br />
menceraikan antara keduanya, maka terbakarlah dirinya.<br />
Ketika itu tinggallah segala Rabithah (penuntun). Jelasku<br />
menirukan tua-tua kampung ketika itu. Bdikar dan<br />
adiknya mengganguk-angguk kepalanya.<br />
Karena siring ikut obrolan tetua kampung, mereka<br />
sering tanya apa cita-cita Bapak? maka Bapak jawab,<br />
cita-citanya mau menjadi tukang “ketuk” atau tukang<br />
menyampaikan informasi kepada Publik.<br />
“Dulu Nak. Di kampung Bapak ada Bapak Ishak<br />
namanya, dia sudah tua sekali waktu itu, dia bertugas<br />
menyampaikan pengumuman atau informasi apa saja<br />
keliling kampung, dia selalu membawa kentongan dari<br />
bambu, dipukulnya beberapa kali dan orang-orangpun<br />
berkumpul, begitu orang berkumpul, barulah dia<br />
sampaikan pengumuman dan informasi, misalnya<br />
informasi harus bayar pajak, turun sawah, pembagian<br />
pupuk. Pembagian pupuk ini bagian dari program<br />
Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dari Pemerintahan<br />
Soeharto, katanya program ini akan membuat Indonesia<br />
166
menjadi Negara Surplus Beras, tetapi kenyataannya<br />
secara berlahan program ini menghilangkan varietas padi<br />
lokal yang tidak perlu pupuk, dan nyatanya sampai<br />
sekarang petani dikampung sangat tergantung akan<br />
pupuk.” Ceritaku panjang sambil membayangkan mulut<br />
tipis dan lengkingan suara Pak Ishak idolaku masih kecil<br />
dulu.<br />
“Ia, Bapak pernah ceritakan itu ketika di rumah<br />
Nenek waktu kita pulang dua bulan lalu” potong Bdikar.<br />
Setelah Program BIMAS, tiba-tiba di Kampung<br />
Bapak masuk Program Reboisasi atau penghijauan,<br />
masyarakat diberikan bibit kayu, Kakekmu ikut juga<br />
mendapakan jatah bibit ini. Setelah bibit itu ditanam<br />
dikebun-kebun masyarakat, kemudian ada aparat<br />
melakukan pengukuran dan pematokan. Mereka tidak<br />
pernah menyampaikan informasi untuk apa beberapa<br />
kawasan itu diikur atau diberi batas. Mereka tidak seperti<br />
Bapak Ishak yang sangat informatif itu.<br />
Baru setelah pengukuran, kawasan tersebut<br />
dijadikan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Aku<br />
tahu tujuannya ketika mendengar obrolan mereka di<br />
167
pertemuan di Rumah Kepala Desa. Ketika ketika Bapak<br />
di minta jadi tukang buat kopi.<br />
“Mereka akan menjadikan kawasan itu menjadi<br />
kawasan yang dilindungi”<br />
“Dilindungi?”<br />
“Sekarang kawasan itu jadi Taman Nasional, Hutan<br />
Lindung, Cagar Alam” Jelasku.<br />
“Baguslah kan hutan tidak rusak?”<br />
“Ia, tapi sebagian bukan hutan, ada sawah, kebun,<br />
petalangan masyarakat”<br />
“Memangnya tidak boleh memanfaatkan ya pak?”<br />
“Tidak boleh ada aktivitas ekonomi”<br />
“Kenapa?”<br />
“Karena hutan bisa rusak”<br />
“Tapikan orang butuh untuk hidup”<br />
Aku terdiam, pertanyaannya tidak bisa aku jawab.<br />
Untung tiba-tiba lampu hidup, dan kami berlari menuju<br />
depan televisi untuk menunaikan ritual neorotik, ritual<br />
kaum perkotaan, begitu televisi dihidupkan muncul<br />
tayangan yang tidak berbobot, reality show yang<br />
menampilkan lagu dan goyangan Kereta Malam dan<br />
168
Oplosan ternyata Anak Bungsuku yang baru 4 tahun<br />
hapal dengan lagu dan goyangannya.<br />
169
13<br />
“Nak.” ceritaku dimulai ketika kami duduk di teras<br />
rumah kami yang belum selesai dibangun sejak 6 tahun<br />
lalu. Malam menjelang munculnya bulan membentuk<br />
sabit setelah hujan turun yang Cuma membasahi bunga<br />
tanah. Ada sisa-sisa hujan tersisa di ujung kelopak bunga<br />
bromelia dalam pot semen berwarna hitam.<br />
“Bapak itu dilahirkan disebuah perkampungan.<br />
Perkampungan itu perkampungan tua dan tua sekali.”<br />
“Aku tahu tapi tidak tahu itu kampung tua” Jawab<br />
Bdikar<br />
Menurut sejarah. Lanjutku, perkampungan ini<br />
sudah berdiri sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya dan<br />
Majapahit. Nama perkampungan itu diambil dari nama<br />
batang Tongkat pendiri kampung itu, kanon legendanya<br />
dia itu seorang ayah yang menjelma menjadi anak. Dia<br />
bertapa bersama istrinya untuk mengenapkan anaknya<br />
menjadi tujuh orang. Mereka bertapa dalam sangkar<br />
ayam. Keduanya menghilang. Kami menyebutnya raib.<br />
Dan tiba-tida dalam sangkar ayam itu ada bayi laki-laki<br />
170
yang panjang kukunya. Dia manusia keturunan para dewa<br />
yang turun dari Istana Makedum Rajo Diwo, itulah<br />
leluhur kalian nak.” Aku memulai ceritaku.<br />
Kampung ini berada di lereng bukit barisan yang<br />
memanjang membelah Sumatera, para sejarawan<br />
menyebutnya dataran tinggi dan berada di titik tengah<br />
Pulau Sumatera. Udaranya dingin dan segar,<br />
pemandagannya hijau, kampungnya asri dipenuhi rumahrumah<br />
tinggi dari papan. Papan yang disusun berdiri<br />
tegak. Dibawah rumah tersusun rapi pokok kayu untuk<br />
bahan bakar.<br />
“Disanalah dulu Bapak dilahirkan,”<br />
Kata Kakekmu. aku dilahirkan hari Selasa tanggal<br />
12 Juli, tanggal itu mengingatkan dia pada Thariq bin<br />
Ziyat yang berhasil memasuki Spanyol sekaligus<br />
perkembangan politik dan tindakan sepihak oleh Fretilin<br />
yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Timur<br />
Timor. Yang, sekarang benar-benar Merdeka dan jadi<br />
Negara Demokratik Timur Leste.<br />
Tangisan pertama Bapak, melengking di sebuah<br />
kamar pengap yang sering kita tiduri ketika kita pulang<br />
ke rumah nenekmu. Itu pertarungan hidup mati nenekmu.<br />
171
Kakekmulah yang mengumandangkan azan di kedua<br />
telinggaku. Kelahiran Bapak mengobati duka yang<br />
dialami nenekmu, dua tahun sebelumnya dia juga<br />
melahirkan anak yang hanya sempat berumur 3 bulan<br />
kemudian dipangil Tuhan. Tidak ada yang tahu apa<br />
penyebab kematiannya, ketika itu belum ada dokter atau<br />
bidan yang bisa mendeteksi penyebab kematiannya. Saat<br />
itu hanya ada dukun dan jampi-jampi. Tidak ada susu,<br />
aku dibesarkan dengan air nasi. Air nasi yang mendidih<br />
ditampung ibuku ketika dia menanak nasi diatas tungku<br />
dengan pokok kayu kopi.<br />
“Hidup kami disana berjalan dengan sederhana dan<br />
bahkan sangat sederhana sekali.” Ceritaku sambil melihat<br />
bulan muncul melalui celah daun batang sawo yang<br />
pertama kali aku taman ketika membeli tanah yang<br />
kemudian diatasnya berdiri setengah kokoh rumah kami.<br />
Mereka pasti tidak bisa bayangkan kesederhanaan itu.<br />
Mataku berlinang ada perasaan rindu pada Ayahku yang<br />
tidak lagi kekar ototnya, badanya mulai kurus dan<br />
keriput, rambutnya semakin putih dan sering sakitsakitan.<br />
Lalu, selintas ada bayangan senyum karismatik,<br />
dan bau harum peluhnya ketika mengendong aku yang<br />
172
selalu sakit-sakitan ketika kecil. Lamunan rindu itu<br />
buyar. Dengan agresor dan keingintahuannya, Bdikar<br />
anak tertua kami yang sekarang baru 8 tahun memotong<br />
lamunanku,<br />
“Sederhana seperti apa maksudnya pak.?” Tanya<br />
dia.<br />
“Sederhana sekali nak.” jawabku sambil<br />
membenarkan letak kepala Adiknya yang mulai miring<br />
dibantal berwarna merah kesayangannya. Dia tidurtiduran<br />
di teras rumah kami. Kata kakekmu, ari-ari Bapak<br />
dihanyutkan di Sungai, sungai yang menjadi saksi sejarah<br />
perjalan kebudayaan sekaligus berfungsi sebagai denyut<br />
utama kehidupan warga di sana. Katanya itu simbol<br />
supaya ketika Bapak besar nanti bisa seperti Thariq bin<br />
Ziyat, bisa menjadi penerus garis wali lalu melakukan<br />
invansi kebudayaan. Sepertinya, bapak itu sengaja jiwa<br />
dan raganya di hibahkan. Itu simbol kenapa ari-ari itu<br />
hanyut tidak dikuburkan seperti anak-anak lainnya.<br />
Ketika mulai besar, tidak ada injeksi imunisasi<br />
BCG, Polio, DPT, Hepatitis B dan Campak yang wajib<br />
diberikan kepada setiap Bayi. Tidak satu selpun tubuh<br />
Bapak di berikan vaksin. Ritual adatlah yang menjadi<br />
173
ganti imunisasi. Bapak lalu diperkenalkan kepada alam<br />
melalui ritual Mbin Cupik moi Munen. Membawa bayi ke<br />
Air adalah ritual yang wajib dilakukan setiap bayi lahir<br />
dan berumur 40 hari, bagi masyarakat modern umur 40<br />
hari sudah wajib di kasih asupan imunisasi. Bapak<br />
dicelup dan dimandikan di Sungai, tepat pada umur 40<br />
hari, ini mengingatkan pada kelahiran Achilles anaknya<br />
Peleus dan Thetis yang dicelupkan oleh ibunya ke sungai<br />
Styx agar menjadi Immortal.<br />
Bayi Bapak yang masih merah diserahkan kepada<br />
alam dan gaib melalui proses ritual, itu dipercayai untuk<br />
menjaga kesehatan, kebugaran dalam masa pertumbuhan.<br />
Tapi, tidak ada ritual melumuri tubuh bayi dengan<br />
Ambrosia, dan dibaringkan di atas api. Bapak hanya<br />
dipandu dengan jampi-jampi yang dilapaskan oleh para<br />
Dukun dan tetua kampung. Boleh jadi, jampi-jampi ini<br />
adalah doa yang dipanjatkan kepada sang Penguasa Alam<br />
melalui karomah para arwah leluhur. Kami percaya doadoa<br />
dan jampi-jampi ini merupakan imunisasi dan<br />
vaksinasi yang akan mengalir dalam denyut darah yang<br />
kemudian mengakumulasi di bawah permukaan kulit<br />
kami, lalu berfungsi seperti selaput Vernix Caceosa<br />
174
sepanjang hayat hidup kami, tetua kampung<br />
menyebutnya sebagai Kerajat Tu’un atau pakaian lahir<br />
yang berfungsi menangkal bahaya dari 8 penjuru dan<br />
menjaga dari kami dari 4 waktu dan pintu sial keturunan.<br />
Selama masa pertumbuhan, tidak ada susu bayi,<br />
tidak ada makan buatan siap saji yang padat nutrisi dan<br />
gizi. Asupan-asupan yang masuk ke tubuh Bapak adalah<br />
makakan yang dibuat dan dimasak oleh tengan lembut<br />
Nenekmu. Nenekmu tidak perlu membeli telur, beras,<br />
ikan, daging dan minyak sebagian bahan untuk<br />
mengelolanya menjadi makanan yang siap kami makan.<br />
Kami punya beberapa ekor itik dan ayam kampung yang<br />
tiap pagi tinggal masuk ke kandang lalu mengumpulkan<br />
telurnya, kami punya lumbung beras yang tiap tahun<br />
selalu surplus, kami menyebutnya dengan Poi Usang,<br />
untuk menjadikan beras kami cukup numpang di ‘kincir<br />
alu’ yang digerakkan oleh air, berasnya pasti bagus dan<br />
masih banyak bekatulnya.<br />
“Nak,”<br />
“Bekatul itu adalah lapisan yang ada di beras,<br />
terdiri dari lapisan aleuron dan perikarp yang kaya gizi<br />
175
aik, katanya bagus untuk mencegah diabetes dan<br />
hipertensi.” Lanjutku.<br />
“Berarti beras sekarang tidak ada bekatulnya ya<br />
pak.? Makanya banyak penderita diabetes dan<br />
hipertensi?” Potong Bdikar seperti biasanya.<br />
“Tidak begitu juga nak,” jawabku, kan ada banyak<br />
sebab lainya, misalnya makanan yang kadar gulanya<br />
tinggi maka secara tidak langsung akan meningkatkan<br />
kadar hormon angiotensi 2 yang akan mengakibatkan<br />
terjadinya hipertensi. Jelas saya seadanya saja.<br />
Dulu, kalau mau makan ikan, tinggal ke kolam<br />
yang ada disawah atau malam-malam sebentar saja bapak<br />
dengan kakekmu ke sungai, dengan peralatan seadanya<br />
kami bisa dapat ikan untuk 3-4 hari. Ibuku atau nenekmu<br />
itu, kalau sedang tidak ada pekerjaan di kebun atau<br />
sawah, dia rajin sekali membuat minyak goreng dari buah<br />
Kepayang (Pangium Edule, tumbuhan berbentuk pohon),<br />
atau sesekali ‘menanak’ kelapa, minyak ini non kolestrol<br />
dan nikmat sekali jika nenekmu memasak nasi goreng<br />
atau mengoreng pisang di setiap pagi buat kami sarapan.<br />
Setelah besar, setiap hari kalau tidak mandi di<br />
sungai, kami mandi di pemandian umum, bisa lama kalau<br />
176
mandi, selain airnya masih sangat segar dan bersih,<br />
sambilan mandi kami bisa bercerita atau mendengarkan<br />
cerita para ibu-ibu dan orang tua tentang banyak hal yang<br />
terjadi di kampung. Mereka itu sangat akrab sekali, tidak<br />
ada kecurigaan antar mereka dan kalau ada masalah atau<br />
pekerjaan, semuanya dikerjakan secara kolektif, semua<br />
ikut membantu.<br />
“Kami sering disebut orang udik”<br />
“Penunggu hulu air,”<br />
“Kenapa?” Tanya Bdikar<br />
Karena kami gagap dengan kemajuan. Kemajuan<br />
yang sebagian besarnya bisa jadi sebagai perusak struktur<br />
sosial dan budaya yang telah dibangun ratusan tahun<br />
lamanya oleh leluhur kami. Pernah sesekali ada mobil<br />
pejabat yang masuk ke kampung, seperti semut<br />
mengerubungi gula kemudian kami berebut memegang<br />
mobil pejabat sampai dimarahi oleh tetua kampung,<br />
mungkin karena malu oleh tingkah kami, setelah itu<br />
kamipun terkaget-kaget ternyata asap yang keluar dari<br />
lubang belakang mobil itu bisa membuat batuk, sesak<br />
napas dan membuat pedih mata.<br />
177
Dulu tidak ada listrik di kampung kami, untuk<br />
penerangan cukup mengunakan lampu minyak, kemudian<br />
dipadamkan kalau sudah mau tidur. Kami diajari untuk<br />
tidak takut gelap. Makanya kami terbiasa untuk tidak<br />
mengutuk kegelapan. Kami diuntungkan dengan belum<br />
adanya listrik ini, karena medan elektromagnetik bisa<br />
berdampak terhadap kesehatan jika terjadi pemajanan<br />
dengan intensitas yang sangat tinggi. Kondisi ini tidak<br />
berdampak pada DNA, RNA, dan sintesis protein,<br />
proliferasi sel, respon imun serta transduksi signal<br />
membran. Efek ini membuktikan bahwa pada tingkat<br />
pajanan yang tinggi akan terjadi gangguan dan pada sisi<br />
fisiologis dapat mempegaruhi beberapa fungsi seperti<br />
fungsi reproduksi, kardiovaskular, saraf, hematopoetik,<br />
endokrin, mutagenesis, sistem imun.<br />
“Banyak sekalikan akibatnya bagi kesehatan<br />
tubuh?” Jelasku meniru guru Biologiku ketika duduk di<br />
Kelas 2 SMP.<br />
Di dalam tubuh makhluk hidup, dalam tubuh kita<br />
sebenarnya terdapat medan listrik endogen yang<br />
mempunyai peranan kompleks dalam mengontrol<br />
mekanisme fisiologis tubuh, seperti aktivitas saraf otot,<br />
178
sekresi kelenjar, fungsi membran sel, perkembangan dan<br />
pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Aku menjelaskan.<br />
Kalau kami sedikit takut gelap cukup nyalan lampu<br />
minyak, lalu kemudian matikan. Lampu minyak inilah<br />
yang membantu kami ketika malam, waktu untuk belajar.<br />
Belajar pelajaran yang kami dapatkan dari Sekolah SD<br />
satu-satunya yang ada di Desa kami. Kami menyebutnya<br />
sekolah 24 jam. Karena bisa bertanya apapun dan<br />
dimanapun dengan guru kami untuk sesuatu yang perlu<br />
ditahu atau tanyakan.<br />
Loh, kenapa Bdikar yang biasanya suka bertanya<br />
kok diam.? Ternyata keduanya sudah pulas tidur sambil<br />
memeluk bantal guling berwarna merah yang dijahit oleh<br />
tangan ibunya tadi siang.<br />
179
14<br />
Malam itu kami harus berebut nonton televisi yang<br />
cuma satu-satunya yang kami miliki, ada beberapa siaran<br />
yang serempak ditayangkan dan masing-masing kami<br />
berbeda hobinya, anak-anak lebih suka nonton film<br />
kartun, aku suka dengan acara dialog para praktisi hukum<br />
dan ibunya suka dengan acara ajang pencarian bakat.<br />
Kami ribut dan masing-masing tentu saja tidak ada yang<br />
rela mengalah, sialnya waktu jedah iklan masing-masing<br />
stasiun ini serempak pula.<br />
Akhirnya suara kami kalah, kami menyerah pada<br />
satu-satunya suara perempuan yang ada diantara kami,<br />
bukan kalah karena jumlah suara tapi kalah dengan<br />
lengkingan vokal ibunya, lalu kami meringkuk tanda<br />
kalah. Celakanya lagi kami tidak boleh kemana-maka<br />
harus tetap didepan televisi, menemani perempuan yang<br />
melenging suaranya itu.<br />
“Dulu ketika masih di kampung, baru kelas 4 SD<br />
kami barulah bisa nonton televisi, dan itu satu-satunya<br />
milik Kepala Desa.” Akupun mulai bercerita dengan dua<br />
putraku, dan istrikupun diam sambil menahan senyum<br />
180
sebagai tanda kemenangan. Televisinya hanya<br />
dihidupkan malam hari, itupun sampai selesai Dunia<br />
Dalam Berita, dari Dunia Dalam Berita itulah bapak<br />
kemudian tahu kita ini berada di Negara yang namanya<br />
Indonesia, Negara kita ini luas sekali bahkan di beberapa<br />
tempat ada pergerakan yang pengacaukan keamanan,<br />
mereka tidak puas dengan sistem bernegara kita.<br />
“Irian Jaya itu nama Politik untuk Papua, Irian itu<br />
singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland.”<br />
kata Bak Wo yang pensiunan Tantara ketika aku duduk<br />
diatas pangkuannya sambil nonton berita tentang Papua.<br />
“Nak,”<br />
Kalau nonton Televisi, Bapak duduknya selalu<br />
dibarisan belakang, kadang-kadang dipangku oleh orang<br />
yang lebih besar fisiknya. Acara yang paling tinggi rating<br />
dan paling banyak pengemarnya adalah acara Kelompok<br />
Pencapir, acara “cerdas cermat” bagi Petani, pada acara<br />
ini sering hadir Presiden kita, namanya Soeharto, dia<br />
senang sekali tersenyum yang ditemani oleh isterinya.<br />
Dia juga sering hadir di acara-acara multi nasional,<br />
katanya Negara kita itu tergabung dalam OPEC sebagai<br />
Negara produsen minyak, anggota Persatuan Bangsa-<br />
181
Bangsa (PBB), PBB ini konsorsium Negara-negara<br />
Merdeka, disana ada Rusia, China, Jerman dan lain-lain.<br />
“Dulu sudah ada Listrik Pak.?” Tanya Bdikar.<br />
“Belum ada nak,” Jawabku.<br />
Televisi ketika itu pakai Accu, makanya hidup<br />
cuma 2-3 jam saja, sekitar 8 bulan setelah itu ada orang<br />
kampung yang bisa menghasilkan listrik dari mesin<br />
pengilingan padi, listriknya hanya dialiri ke rumah-rumah<br />
orang kaya, Cuma mereka yang mampu beli alat-alat<br />
instalasi. Listriknya menyala dari jam 18.00- 23.00. Dan<br />
rumah Nenekmu masih tetap pakai lampu minyak, karena<br />
Kakekmu tidak cukup duit beli alat instalasi listriknya.<br />
“Lalu, setelah listrik swadaya ini menyala, selain<br />
Rumah Kepala Desa, ada 1 keluarga lagi yang beli<br />
televisi, mereka keluarga terhormat dan orang kaya di<br />
kampung, Bapak ikut gotong royong ketika pasang tiang<br />
Antena yang tingginya lebih dari 30 meter, kalau layar<br />
televisinya banyak “semut” tiang antenanya lalu diputarputar,<br />
eh.. televisinya menyala, tenyata setelah Aneka Ria<br />
Sapari, ada Eliyas Pical yang lagi lawan Ju Do Chun,<br />
Eliyas Pical ini petinju kebangaan Kakekmu nak.” Bdikar<br />
dan Titon tersenyum tersipu-sipu mendengar ceritaku.<br />
182
Bapak masih ingat, ketika listrik swadaya ini<br />
menyala, ketika itu musim panen padi. Di kampung<br />
musim panen padi ini disebut dengan musim Mengetem<br />
ada banyak pantangan ketika musim panen ini, Padi<br />
hanya bisa dipanen dengan alat yang namanya Tuwei atau<br />
Ani-Ani, papan yang diberikan pisau di ujungnya<br />
kemudian dijepit di antara jari tengah dan telunjuk.<br />
Tidak boleh pakai Arit, karena itu dipercayai akan<br />
menyakitkan dewi padi. Padi dengan tangkai yang sudah<br />
dipanen selanjutnya sipimpan dalam Tuwoa, Tuwoa ini<br />
rumah-rumah kecil yang terbuat dari bambu yang<br />
fungsinya sebagai lumbung padi, padi-padi ini tidak<br />
boleh dijual hanya untuk dikonsumsi selama 1 tahun,<br />
karena panennya hanya setahun sekali. Anehnya,<br />
meskipun hanya panen setahun sekali, padi-padi ini<br />
selalu surplus makanya ketika itu Kampung Bapak sering<br />
disebut dengan daerah penghasil padi atau daerah<br />
lumbung padi.<br />
Sepuluh bulan setelah panen, Ada teman Kakekmu<br />
dari Kota berkunjung ke rumah, katanya dia teman<br />
sekelas Kakekmu ketika SMP di Kota Curup, dia bekerja<br />
di Perusahaan Negara Pembangkit Listrik Negara (PLN),<br />
183
mereka saling bercerita tetang kisah-kisah susah ketika<br />
masih Sekolah, dan yang Bapak dengar Kampung Bapak<br />
akan di pasang tiang Listrik, tidak detail informasi yang<br />
bapak dapat karena waktu itu Bapak lagi bantu Nenekmu<br />
buat bubuk kopi dengan Alu. Baru sebulan setelah itu,<br />
ada beberapa mobil truk membawa tiang dari besi<br />
panjangnya sekitar 4 meter, tiang ini kemudian ditegakan<br />
dengan jarak masing 60 meter oleh orang-orang dari kota,<br />
setelah semua tiang tegak baru Bapak tahu, tiang ini<br />
namanya Tiang Listrik. Butuh waktu 7 bulan setelah<br />
tiang ini ditegakkan, instalasinya baru dipasang, tiang ini<br />
sering digunakan oleh Bapak dengan teman-taman untuk<br />
lomba memanjati tiang ini, dan kalau bulan puasa tiang<br />
ini ternyata efektif mengantikan beduk untuk<br />
membangunkan warga untuk Makan Sahur dan Buka<br />
Puasa.<br />
“Instalasipun dipasang.”<br />
“Dan listrikpun menyala.”<br />
“Rumah Kakekmu juga di aliri listrik,”<br />
Bayarannya tidak terlalu mahal, ada kopensasi dari<br />
teman kakekmu yang bekerja di PLN itu. Pertama-tama<br />
tentu saja kami gagap dengan listrik ini, mata kami harus<br />
184
eradaptasi dengan cahaya dari lampu pijar yang<br />
warnanya kuning dan membuat sakit kepala.<br />
Kampung bapakpun semakin semarak, kami mulai<br />
menikmati kemajuan teknologi penerangan ini.<br />
“Jam mengaji dan belajar kami mulai berkurang,<br />
kalau tidak keluyuran malam-malam, kami pasti keasikan<br />
nonton televisi di rumah-rumah tetangga.”<br />
“Ada yang jual kerbau untuk beli televisi, beli<br />
kulkas, beli kipas angin padahal udara sangat dingin di<br />
kampung ketika itu, karena dinginnya minyak gorengpun<br />
beku.”<br />
Masyarakatpun mulai mengkonsumsi barangbarang<br />
yang tidak menjadi kebutuhannya, obrolan dan<br />
gaya merekapun mengikuti acara di televisi itu, kalau<br />
sedang ada turnamen Bulu Tangkis, semua<br />
membicarakan Icuk Sugiarto, Lim Swie King, lalu<br />
merekapun mulai menyukai Elvie Sukaesih, Masyur S.<br />
Kalau sedang di Unen tepat pemandian umum, mereka<br />
lebih lama dari biasanya karena mereka saling bercerita<br />
tentang idolanya. Sedang asiknya bercerita. Eh, tiba-tiba<br />
ibunya mengantikan Chanel Televisi yang menyiarkan<br />
Goyangan Caesar dan goyangan oplosan, iniah acara<br />
185
yang paling netral yang bisa kami tonton bersama-sama,<br />
dan sayapun berhenti bercerita.<br />
186
15<br />
Malam ini, makan malam kami agak lambat, karena<br />
memang tidak ada yang harus di masak. Malam ini<br />
sepertinya kebalikan dari malam sebelumnya dimana ada<br />
4 menu yang tersedia di meja makan, perpaduan antara<br />
komoditas lokal dan impor. Ada tempoyak, bahan<br />
utamanya adalah durian dan lemea, bahan dari frementasi<br />
bambu muda atau rebung, dua menu ini adalah menu<br />
kesukaan saya. Ada ayam goreng yang dibeli dari rumah<br />
makan cepat saji, tentu saja ini menu impor, semua<br />
berbahan impor atau setidaknya punya lisensi berbasis<br />
impor walaupun sebagian besarnya berbahan lokal. Ini<br />
menu kesukaan anak-anak kami. Aku tidak menemukan<br />
dimana sisi nikmat menu ini, Aku hanya tahu penetrasi<br />
kapitalisme melalui makanan ini sudah sampai di meja<br />
makan kami yang sudah mulai dimakan rayap.<br />
Karena lapar, akhirnya si pemegang otoritas<br />
logistik dapur di rumah kami, istriku memasak nasi<br />
dengan sambal terasi, perpaduan antara terasi yang<br />
dibakar, lalu tomat dan ada juga cabe. Sambalnya cukup<br />
187
pedas, membuat keringat keluar dari kening dan ubunubun.<br />
“Diam, jangan banyak komentar, nikmati saja<br />
pedasnya, pedas cabe itu bisa buat badan sehat dan kuat.”<br />
kata istriku sambil menyiapkan minuman dari kulkas.<br />
Tentu kami tidak berani komentar atas masakannya.<br />
Habis makan, pedasnya masih menempel di lidah,<br />
lalu sambil duduk di teras sambil menghisap rokok. Aku<br />
mulai cerita dengan dua anakku yang keduanya keluar<br />
dengan tidak berbaju dengan muka memerah karena<br />
kepedasan.<br />
“Bapak dari kecil memang tidak biasa makan<br />
pedas, karena sejak kecil bapak ini sakit-sakitan nak.”<br />
Aku mulai membuka cerita.<br />
Kalau makan makanan yang pedas perut bapak<br />
langsung bereaksi, lalu bergemuruh, ketika perut mulai<br />
bergemuruh maka harus segera berangkat ke Unen,<br />
tempatnya sekitar 800 meter dari rumah. Unen multi<br />
fungsi, perpaduan antara tenpat untuk mandi, cuci dan<br />
kakus. Dengan tiga fungsi ini, maka mandi dan cuci<br />
berada di hulu dan kakus di bagian hilirnya. Nah, untuk<br />
fungsi kakus ini biasanya ada dua buah batu yang<br />
188
fungsinya sebagai tempat bertumpuhnya kaki ketika kita<br />
jongkok, dan batu-batu ini berderet rapi, sehingga kalau<br />
lagi buang air besar, kami berderet secara rapi, seperti<br />
WC deret yang berjejer panjang. Dulu, bapak tidak malu<br />
walau harus buang hajad di depan umum, mungkin kami<br />
sadar bahwa ini manusiawi, ini hukum alam yang harus<br />
ditunaikan segera, jadi kenapa harus malu.<br />
“Nak, Unen ini bentuk dari aplikasi pemanfaatan<br />
ruang komunal.” Lalu Bdikar tanya apa maksudnya<br />
ruang komunal ini.<br />
“Komunal itu apa?”<br />
Aku lalu menjelaskan secara sederhana ruang<br />
komunal. Ruang umum, yang dimiliki oleh siapa saja dan<br />
diperuntukan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas<br />
penggunanya. Dalam pemanfaatan ruang milik umum ini,<br />
etika, tata tertib disepakati secara bersama, biasanya<br />
kalau dalam bentuk aturan, maka aturannya tidak ditulis,<br />
aturanya tidak rinci, hanya memuat garis-garis besarnya<br />
saja tapi anehnya aturan ini sangat efektif dan tidak ada<br />
yang berani untuk melanggarnya.<br />
“Unen ini bertahan sampai kami SMP,” terangku.<br />
189
Awalnya ada pembangunan WC Umum yang<br />
modelnya berbeda dengan Unen, WC umum ini<br />
bentuknya bangunan permanen yang oleh Pemerintahan<br />
Desa. Kata Kepala Desa waktu itu Bangunan WC ini<br />
untuk meminalisir penyakit yang ditimbulkan oleh<br />
kotoran manusia, jadi kotoran manusia yang baunya tidak<br />
sedap dan bentuknya tidak menarik ini harus disimpan di<br />
dalam lubang yang disebut dengan septic tank. Padahal<br />
Kepala Desa ini sampai umurnya 67 tahun ketika itu<br />
selalu mengunakan Unen ini untuk kebutuhan<br />
pembuangan kotorannya, dan tidak ada penyakit yang<br />
ditularkannya.<br />
Setelah pembangunan WC umum ini, ada<br />
perubahan secara berlahan yang kami rasakan, awalnya<br />
semua dilakukan secara bersama-sama di ruang publik,<br />
lalu berlahan masuk kedalam ruang-ruang privat, ruangruang<br />
yang sifatnya sangat pribadi. Tetapi ada benarnya<br />
juga Kepala Desa kami, dulu kalau lewat hilir Unen ini<br />
biasanya kita mesti tutup hidup, karena aromanya luar<br />
biasa, setelah ada Pembangunan WC umum ini,<br />
sepertinya ada yang hilang, baunya menguap entah<br />
190
kemana, tentu kemudian kami senang meskipun ada rasa<br />
kehilangan.<br />
“Oh, begitu” kata Bdikar.<br />
Sementara Adiknya tetap melotot binggung dan<br />
sepertinya mereka belum bisa bayangkan Unen ini seperti<br />
apa, bentuknya apa dan bagaimana mengunakannya.<br />
“Unen, itu seperti kamar mandi kita nak,” jelasku.<br />
Kamar mandi yang kita gunakan secara bersamasama,<br />
tapi kalau di kamar mandi kita, kita mesti antrian,<br />
nah kalau Unen ini kita gunakan bisa pada saat<br />
bersamaan. Mereka menganguk, sepertinya sedikit mulai<br />
mengerti.<br />
Sekarang, kalau kita pulang ke kampung, maka<br />
tidak kita temukan lagi Unen ini, jelas saya. Mereka<br />
mulai mengerti tentang kekerabatan dan keakraban yang<br />
lahir dari fungsi Unen ini. Dan sekarang jelasku sambil<br />
menghisap rokok dan membayangkan kondisi kampung<br />
dimana kedua orang tua saja masih disana.<br />
“Semua sudah sangat pribadi sifatnya. Ruang-ruang<br />
publik hampir terkikis oleh sistem privat ini. Tentu saja<br />
kondisi ini kemudian berdampak pada sistem sosial yang<br />
dulunya diikat dengan sistem kekerabatan mulai<br />
191
mengecil dan terjebak pada sistem pasar, sistem sosial ini<br />
kemudian bertransaksi nak.!” Lanjutku. Struktur<br />
kemasyarakatan yang mulai di eliminasi, mereka lebih<br />
percaya kepada struktur formal, ini membuat mereka<br />
seperti yang Adek pakai baju Abang. Akupun beranologi.<br />
“Oh, kebesaran pak, tidak bisa Adek lari dan kalau<br />
kena angin bisa melayang Adek pak.” Potong Titon anak<br />
Bungsuku.<br />
“Ia nak, tapi ada juga manfaatnya juga, kalau kita<br />
kebelet e’ek kan tidak perlu jauh-jauh sambil lari, kita<br />
tinggal ke WC langsung e’ek, Sungai bisa bebas dari<br />
pencemaran, tidak ada penyakit yang disebabkan dari<br />
mengkonsumsi air sungai, dulukan waktu bapak masih<br />
kecil, Bapakkan cacingan.” jawab saya pada si Bungsu,<br />
dia pun tersenyum mungkin mambayangkan bapaknya<br />
waktu kecil, badan kurus, biji mata besar melotot seakan<br />
mau meloncat keluar, perut buncit.<br />
“Sudah ceritanya.? Hari sudah malam masuklah..!”<br />
bentak ibunya, tapi intonasinya lebih lembut ketimbang<br />
ketika kami makan kepedasan tadi, sekali lagi kami harus<br />
mengalah dengan satu-satunya perempuan dirumah kami.<br />
192
16<br />
Diam-diam Bdikar mulai menunjukan<br />
pemberontakan-pemberontakan kecil, tapi aku mulai<br />
menikmati nada suaranya yang memenuhi ruangan rumah<br />
kami yang dindingnya hanya dilapisi susunan bata.<br />
Suaranya memang terdengar mengema lalu menantul.<br />
Sepertinya frekwensi resonansi berkeja dengan baik di<br />
rumah kami.<br />
“Saat ini kita mengalami ketidaksadaran kolektif,<br />
yang dibentuk oleh kesadaran masa lalu dan sebagian<br />
terbentuk atas pengalaman empiris,” Kata Bdikar pada<br />
sore hari sehabis membantu ibunya menyiram bunga.<br />
“Bapak boleh Periksa.”<br />
“Kita sudah sangat biasa dituntun dan diperintah,”<br />
“Kita kemudian tidak punya kepercayaan diri dan<br />
terus menerus butuh pengakuan dan penghargaan, oleh<br />
karena itu kita sering mencari status tanpa substansi,<br />
demontrasi-demontrasi tanpa henti yang kita anggap<br />
sebagai cerminan demokrasi, kebutuhan berbagai<br />
kelompok baik etnis maupun keagamaan untuk<br />
menonjolkan diri mereka dalam cara-cara menarik<br />
193
perhatian yang tidak selalu konstruktif, cenderung<br />
memecah belah,” dia seperti membaca sebuah tulisan tapi<br />
aku lupa buku apa.<br />
Sampai disitu aku potong omongannya yang mulai<br />
memojokkan itu.<br />
“Bukankah masih ada kelompok-kelompok<br />
intelektual, cendikia yang punya kemampuan ilmiah,<br />
rasional dan kesadaran kritis untuk keluar dari<br />
ketidaksadaran kolektif.?”<br />
“Tunggu dulu, saya akan selesaikan dulu<br />
kalimatnya,” Seperti biasa dengan sifatnya yang tidak<br />
mau dikalahkan dalam berargumentasi.<br />
”Yang terjadi kemudian secara masif kita menjadi<br />
komunitas imajiner, menjadi bangsa yang panakut tanpa<br />
jiwa besar, menjadi masyarakat yang iri dan pedengki.”<br />
“Kemudian menciptakan rasa frustasi dan obsesif<br />
karena bertahun-tahun dikontruksikan secara sosial, lalu<br />
kita terobang-ambing antara membohongi diri atau<br />
mengamuk tak terkendali.!”<br />
Bdikarpun kemudian termenung sebentar kemudian<br />
dengan gaya bicaranya yang sering mempelototi lawan<br />
194
icaranya, seperti mempelototi ayam goreng buatan<br />
ibunya.<br />
“Menjawab pertanyaan bapak tadi,” dia berhenti<br />
sejenak. Tidak seperti biasanya. Pertanyaannya standarstandar<br />
saja.<br />
“Seharusnya memang begitu, tapi juga<br />
kecenderungan banyak kaum intektual kita menjadi<br />
selebritas, yang lebih sedang muncul di televisi dan<br />
mengungkapkan pendapat mereka tentang apa saja atau<br />
mengulang-ulang apa yang telah mereka katakan.”<br />
“Tidak ada pikiran dan ide baru,” Dia berhenti tarik<br />
napas<br />
“Mereka tidak mau turut merenung dan<br />
menghasilkan pengetahuan demi terciptanya masyarakat<br />
baru, ini praktik akademik yang memalukan!” tambah<br />
dia.<br />
Sambil menghisap rokok bergambar tomur di leher,<br />
aku kemudian coba memastikan dia harus bertanggung<br />
jawab atas statemennya.<br />
“Sampai disitu aku sepakat,” aku hisab lagi rokok<br />
sampil tertawa dalam hati, ingat dialog interaktif disalah<br />
195
satu stasion televisi yang sering menghadirkan kaum<br />
intelektual, kemudian aku melanjutkan pertanyaan.<br />
“Tapi apakah kamu punya indikator lain atau paling<br />
tidak dampak ketidaksadaran kolektif yang kamu<br />
sebutkan itu.?”<br />
Sepertinya dia mulai gerah dengan pertanyaan itu.<br />
“Pertanyaan Bapak itu adalah ciri-ciri pertanyaan<br />
masyarakat yang aku jelaskan tadi, selalu merasa benar<br />
dan cenderung menonjol sekaligus memojokkan<br />
kemudian mulai menyalahkan orang lain,”<br />
“Metalitas superior-inferior merupakan dasar<br />
psikologis budaya kekerasan yang kemudian jadi<br />
sadomasokistis dan itu adalah prilaku depensif yang aku<br />
sebut diawal yang mengantikan renungan dan intropeksi<br />
jujur atas kehidupan dan kondisi yang terjadi,”<br />
“Kita ini irasional dan sebagai akibatnya sering<br />
terlalu emosional.” Aku tertawa tetapi tidak terbahakbahak,<br />
menertawakan diri sendiri. Lalu. Mulai terasa<br />
muka mulai memerah dan mulai tersingung dibuatnya.<br />
Sepertinya Bdikar tahu dan tetap saja dia<br />
menikmati ketersingunganku. ketersingunganku<br />
psikologis bawaan anak sulung yang tidak mau di atur.<br />
196
“Secara kultural, kita masih berorientasi feodal baik<br />
dalam mentalitas maupun dalam struktur sosial” tambah<br />
dia.<br />
Dia mulai menikam pertahanan terdalam yang aku<br />
miliki, kumatikan rokok kemudian menyulut batang<br />
rokok yang baru untuk menjembunyikan hasrat feodal<br />
sebagai bawaan anak sulung dan kepala patriarki<br />
keluarga kecil kami.<br />
“Kamu tidak boleh terlalu berpikir begitu, untuk<br />
memahami jiwa Indonesia kamu mesti mengerti kontek<br />
keberadaanya, kamu mestinya percaya pada gagasan<br />
anima mundi atau jiwa dunia, kita hidup pada entitas<br />
kosmik, kesatuan organisme yang memiliki jasad dan<br />
sukmanya sendiri” Aku pun berhenti. Ibunya Bdikar<br />
membawa kopi dan sambil tersenyum menyaksikan<br />
perdebatan kami. Dialah biasanya yang mampu<br />
menundukkan kami ketika kami bertengkar.<br />
“Bapak,” Lanjut Bdikar yang mulai sadar bahwa<br />
dia berhadapan dengan Bapak biologisnya.<br />
Senyuman ibunya.<br />
Dia menurunkan intonasi suaranya.<br />
197
“Tapi Bapak, filosofis itu kemudian diartikan<br />
sebagai gagasan Desa Global, Entitas Global yang<br />
diciptakan dengan serat optik dan kemudian kita<br />
dipaksanakan ditarik kedalamnya, penafsiran ini di<br />
dampingi oleh kebekuan budaya,”<br />
“Tidak ada puisi.”<br />
“Tidak ada ritual.”<br />
“Yang ada hanya ritual neurotik, makan makanan<br />
olahan, tidak ada imajinasi, tidak ada kesucian.”<br />
“Ini adalah bentuk syndrom modernisme yang<br />
ditanam dan tertaman dalam diri kita penyebab utamanya<br />
adalah rusaknya sukma, secara global kita hidup dalam<br />
priode materialisme dan konsumerisme yang ditandai<br />
hilangnya nilai-nilai dan pergeseran standar estetika.”<br />
Aku ingat Wak Odon, Wak Salim Senawar, Ibuku,<br />
Bapakku dan ingatan tentang Nenek Pia itu melekat<br />
sekali di ruang penghubung kedua telinggaku.<br />
“Oh, lalu apa yang harus dilakukan kalau begitu?”<br />
Aku coba menyelesaikan perdebatan ini.<br />
“Kita dibekali sifat tenggang rasa, tapi tidak<br />
ditanamkan sikap analitis dan kritis, keduanya harus<br />
seimbang, memilih salah satunya akan mengakibatkan<br />
198
cara berpikir yang katagoris dan reduksionis” Jawab<br />
Bdikar.<br />
Kemudian berlahan dia mulai menaikan kembali<br />
intonasi suaranya.<br />
“Indonesia sekarang ini sesungguhnya belum<br />
mencapai tarap hidup modern yang berlandaskan<br />
pendekatan intektual, rasional, terbuka, egaliter dan<br />
pluralistik namun terlanjur meningalkan tradisi lama.<br />
Maka keberanian memahami keraifan tradisi lama,<br />
kejujuran atas kajian dan kejadian sejarah, memahami<br />
secara konprehensi pertikaian inheren turun temurun<br />
sebagai refleksi sukma yang tidak bahagia dan semu yang<br />
terpecah-pecah itu kemudian kita juga perlu menyalakan<br />
kembali nasionalisme sehat dan tentu saja kita mesti<br />
berani berdamai dengan diri kita sendiri.”<br />
“Dan sejarah kita,”<br />
“Karena jika tidak kita akan terkatung-katung dan<br />
tidak pernah berkembang menjadi bangsa yang kuat.”<br />
Kata penutupnya sangat abstrak dan prematur,<br />
sepertinya dia buru karena ada 4 orang temannya<br />
menuggu ingin bermain sepeda, dia kemudian berlari<br />
keluar sambil gotong sepedanya dan membiarkan<br />
199
pikiranku jadi berantakan oleh statemennya yang pedas<br />
dan keras. Aku seperti di tampar sekeras smassnya Liem<br />
Siau Bok. Smash-smash tajamnya yang turut<br />
mengantarkan Indonesia merebut dua medali emas di<br />
arena SEA Games. Tepatnya pada SEA Games 1981 di<br />
Manila, Filipina dan SEA Games 1987 di Jakarta untuk<br />
Cabang Voly ball.<br />
Akupun terdiam sendiri dikursi reot yang belum<br />
tahu kapan aku mampu mengantikannya dan sambil<br />
berhayal; bukankah dulu pernah ada MANIFOL USDEK<br />
(Manifesto Politik; UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi,<br />
Ekonomi dan Kepribadian), sehingga berdaulat dalam<br />
politik, mandiri diekonomi dan bermartabat dalam<br />
budaya, Pancasila, ada Repelita, ada GBHN, ada<br />
Reformasi, ada Otonomi, tapi entahlah rokok habis dan<br />
kopipun sudah kering, sepertinya aku harus<br />
menyelesaikan siraman bunga yang belum diselesaikan<br />
oleh Bdikar. Kemudian mandi, rebus mie instan lalu<br />
menikmati ritual neurotik. Nonton televisi.<br />
Ah.. Bdikar ada-ada saja.<br />
200
17<br />
Pernah aku memimpin advokasi bagi komunitas<br />
adat yang ada di kampung, yang hak-haknya diabaikan.<br />
Itu 5 tahun lalu. Salah satu hak yang diabaikan itu adalah<br />
hak perempuan. Perempuan adat. Titik tekannya<br />
mengeluarkan posisi perempuan dari pusaran subordinat,<br />
diskriminasi ganda posisi perempuan. Lalu, aku bingung,<br />
apa alat yang menjadi pegangan untuk melihat proses<br />
dominasi ini. Dengan gender, feminisme, emansipasi?<br />
Dominasi ini terjadi pada ruang yang sangat lokalitas.<br />
Akupun mulai mendokumentasikan pijakan<br />
“advokasi” ini, ada feminis. Tapi tidak aku ajak Bdiar<br />
diskusi soal ini. Tamparan bak kena smassnya Liem Siau<br />
Bok masih membekas merah di pipiku.<br />
Rupanya, kata feminis ini ternyata sebuah kata<br />
yang diambil dari kalimat Perancis (féminisme) asalnya<br />
dari kata Latin (femind), dan mengalami sedikit<br />
perubahan. Dalam bahasa Inggris dan juga Jerman, kata<br />
itu mempunyai arti yang sama. Feminine (feminim)<br />
bermakna wanita atau jenis perempuan. Istilah<br />
201
Feminisme dapat digunakan untuk dua makna. Makna<br />
pertama adalah makna yang telah digunakan secara<br />
umum dan telah dikenal, yakni sebuah pemikiran dan<br />
kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki<br />
dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dan Makna<br />
kedua sangat sederhana: Sifat dan prilaku kewanitaan<br />
yang nampak pada laki-laki.<br />
Yang hampir mirip-mirip dengan feminis, ada juga<br />
gender, basisnya adalah konsep kultural yang merujuk<br />
pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan<br />
pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial<br />
budaya.<br />
Gender melihat pria dan wanita secara sexual<br />
berbeda. Begitu pula secara perilaku dan mentalitas.<br />
Namun perannya di masyarakat dapat disejajarkan<br />
dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga secara<br />
sederhana dan tafsir bebas, akupun mendifiniskan gender<br />
itu sebagai aturan atau normal perilaku yang<br />
berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem<br />
masyarakat. Karena itu, gender sering kali di identikan<br />
dengan jenis kelamin atau sex. Meski sebenarnya kedua<br />
202
jenis kata ini yaitu sex dan gender memiliki konsep yang<br />
berbeda.<br />
Selain faminisme dan gender, ada juga emansipasi,<br />
sebuah metode yang dikembangkan sejak abad ke 14.<br />
Emansipasi ini berasal dari bahasa latin “emancipatio”<br />
yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan, dan<br />
definisi sederhananya: persamaan hak dalam berbagai<br />
aspek kehidupan masyarakat, dalam ruang yang lebih<br />
kecil, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<br />
Indonesia punya tokoh yang mempopulerkan emansipasi<br />
ini, dia RA Kartini, saya tahu itu sejak Sekolah Dasar<br />
dari buku-buku perpustakaan sekolah kami yang berdebu,<br />
dan aku sering mencuri buku-buku dari perustakaan<br />
sekolah ini, karena perpustakaan ini selalu terkunci.<br />
Dari tiga acuan ini, Gender, Feminisme dan<br />
Emansipasi, lalu bagai mana memposisikan dan<br />
mendudukannya pada ruang yang sangat lokal, ruang<br />
kampung. Aku tentu saja sepakat bahwa kampungpun<br />
adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ruang<br />
global, yang selanjutnya disebut dengan global village<br />
itu, dunia yang dianalogikan sebagai sebuah kampung<br />
besar, ada koneksitas satu dengan lainnya. Nah,<br />
203
masalahnya kemudian di titik mana muaranya akan<br />
ketemu, dalam bahasa yang sok akademiknya;<br />
menemukan titik universalisme dengan relativisme<br />
budaya (cultural relativism).?<br />
Dari pada kesulitan memahami tiga hal dan dua<br />
titik binner ini, yang tentu saja sulit dan tidak aku<br />
pahami, lalu bayangan ibuku yang biasa aku sebut<br />
dengan Mak, bayangan Mak mondar-mandir dalam<br />
otakku yang volumenya dan kapasitas berpikirnya lemah<br />
dan tidak up date. Aku membayangkan feminisme,<br />
gender dan emansipasi itu dalam sosok Makku.<br />
Makku adalah wanita kampung, dia bungsu dari 13<br />
saudara diantara 10 laki-laki dan 3 orang perempuan.<br />
Karakternya kuat dia punya kharisma melebihi kakakkakaknya,<br />
perpaduan antara bapak dan ibunya.<br />
Bapaknya, itu kakekku punya karakter dan sikap yang<br />
kuat. Dia pernah dipenjara karena berbeda sikap dengan<br />
Pemerintahan Belanda, dia menolak penindasan dan<br />
melakukan konsolidasi perlawanan. Ketika<br />
pemberontakan PRRI, ketika itu kampungya di bakar, dia<br />
berada garis depan membuat dia tertembak, dan peluru<br />
yang bersarang dibetis itu dibawahnya sampai mati. Lalu<br />
204
ibunya, itu nenekku seorang wanita yang tegar, dia harus<br />
mengantikan posisi suaminya ketika masa-masa sulit,<br />
masa berjuang dan sampai suaminya berakhir di penjara<br />
Belanda, dialah yang membesarkan anak-anaknya.<br />
Makku, dan aku lupa kapan dia berbicara keras<br />
kemudian memarahiku, tidak pernah protes dengan posisi<br />
dia sebagai pendamping Bakku, itu suaminya. “Saya<br />
harus membaca 1.000 kali Surah Al-Ikhlas sebagai Mas<br />
kawin, membuat keringatku bercucuran dan itu 3 jam<br />
baru selesai” cerita Bakku.<br />
Dan itu aku pikir itu pantas untuk seorang wanita<br />
seperti ibuku. Surah Al-Ikhlas dilafaskan oleh Bakku<br />
pada tahun 1974, Surah ini cukup pendek, hanya terdiri<br />
dari 4 ayat dan intinya menegaskan bahwa tentang<br />
Keesaan Allah SWT dan menolak segala penyekutuan<br />
terhadap-Nya.<br />
Sebagai anak putri bungsu dalam keluarganya,<br />
maka dia diposisi dan memposisikan diri sebagai<br />
tumpuan dari keluarganya. Dan itu tidak hanya bagi<br />
anggota keluarganya yang ada hubungan geneologi tetapi<br />
dia menggangap bahwa semua orang bagian yang<br />
ter”esa”kan dalam pusaran dirinya, dia tumpahkan semua<br />
205
asa sayangnya, dan itu membuat dia sering dirindukan<br />
oleh angota keluarga dan orang-orang yang pernah dia<br />
beri rasa sayangnya sebagai ibu. Tidak peduli dia orang<br />
kampung atau orang kota, jelek dan genteng, miskin dan<br />
kaya, bahkan berlainan agama.<br />
Dalam kesederhanaanya, aku tahu dia punya<br />
pemehaman juga tentang penindasan terhadap kaumnya.<br />
Pernah suatu kali ketika aku kelas 3 SD itu di tahun 1984,<br />
saat itu sore hari dan aku sedang baca buku tentang RA<br />
Kartini, dia lalu duduk disampingku sambil<br />
memperhatikan gambar RA Kartini di buku, lalu dia<br />
bilang begini “Hukum dan sistem hak asasi manusia<br />
termasuk kesetaraan itu adalah sistem yang sangat<br />
maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara<br />
berfikir dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan<br />
kemudian menguntungkan laki-laki lalu melegitimasi<br />
situasi yang tidak menguntungkan perempuan.” Apa<br />
maksudnya tanyaku binggung, karena tidak ada dalam<br />
catatan dalam buku yang sedang aku baca.<br />
“Hal tersebut dilihat dari beberapa hal pertama,<br />
pendikotomian antara wilayah publik dan privat; kedua,<br />
konsepsi pelanggaran hak asasi manusia sebagai<br />
206
pelanggaran yang dilakukan oleh negara; ketiga,<br />
pendekatan kesamaan dan perbedaan yang dipakai oleh<br />
beberapa instrumen pokok hak asasi manusia; keempat,<br />
pemilahan dan prioritas hak sipil dan politik, ketimbang<br />
hak ekonomi, sosial dan budaya”. Jelas dia. Dan aku<br />
bertambah binggung ketika itu.<br />
“Sederhananya begini,” dia melanjutkan setelah<br />
melihat tatapan kosong mataku.<br />
“Pemilahan antara wilayah lingkup dan publik dan<br />
prioritas perlindungan hak pada wilayah publik sangat<br />
dilematis dalam konteks penegakan hak asasi manusia<br />
terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan.<br />
Sebab, dalam banyak pengalaman perempuan, wilayah<br />
domestik dan privat ini malah menjadi arena di mana<br />
kekerasan dan diskriminasi berlangsung sangat serius dan<br />
massif.” Dia berhenti sebentar.<br />
Dengan pelan-pelan dengan intonasi suara<br />
keibuannya dia melanjutkan “Namun, situasi kekerasan<br />
tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi<br />
manusia dan hanya dikategorikan sebagai perlakuan<br />
kriminal semata. Konsepsi pemilahan publik dan<br />
domestik pun berjalin dengan pandangan bahwa pelaku<br />
207
pelanggaran hak asasi manusia adalah negara (state<br />
actor) yang kemudian meminggirkan berbagai<br />
pengalaman perempuan. Dalam kasus “penyiksaan”<br />
(torture), misalnya, pendekatan hak asasi manusia<br />
konvensional hanya akan melihat kasus penyiksaan<br />
sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika dilakukan<br />
oleh aparat negara dan terjadi di wilayah publik.” Lalu<br />
akupun semakin binggung dan kepalaku mulai berputarputar.<br />
Penjelasan ibuku di tahun 1984 itu, menambahkan<br />
kebinguanku tentang titik universalisme dengan<br />
relativisme budaya. Awal tahun 2008, akupun pulang<br />
kampung meminta penjelasannya terkait dengan program<br />
yang sedang aku kembangkan, program Perempuan Ada.<br />
Suatu sore, kami duduk dikursi, dibawah batang pohon<br />
nangka yang aku tanam ditahun 1982 di depan teras<br />
rumah. Belum sempat aku tanyakan sama tentang<br />
perspektifnya terhadap feminisme, gender dan<br />
emansipasi. Tiba-tiba lewat Saudara sekampungnya,<br />
saudara sepupu jauh Bakku, Saya menyebutnya Mamak<br />
Lan, dia buta, kemana-mana dia dituntun oleh isteri dan<br />
anak perempuannya secara bergantian.<br />
208
“Begitulah seharusnya sebagai Perempuan”.<br />
Celetuk ibuku tiba-tiba. Tentu aku tahu maksudnya<br />
adalah istrinya Mamak Lan.<br />
“Perempuan tidak boleh lebih maju atau di depan,<br />
dan tidak boleh juga lebih mundur atau di belakang lakilaki,”<br />
lanjutnya.<br />
Dia juga bercerita tentang Istrinya Mamak Lan<br />
yang buta itu, pernah dibujuk oleh saudara-saudaranya<br />
untuk menceraikan Mamak Lan karena cacat fisik,<br />
istrinya cuma bilang “Dulu dia tidak buta, setelah kami<br />
menikahlah dia buta, maka akan saya jaga suamiku<br />
meskipun dia cacat, karena itu akan meninggikan<br />
derajatku sebagai Perempuan”. Mereka itu saling berbagi<br />
Peran, Jelas ibuku, sesekali suaminya mengerjakan tugas<br />
isterinya begitu juga sebaliknya, mereka berdua tidak<br />
mau terjebak pada prinsif maskulinitas maupun<br />
femininitas.<br />
Aku tahu, ibuku yang sudah pasti tahu tentang<br />
kegalauan anaknya ini.<br />
“Jadi pendekatan ‘kesamaan’ (sameness) dan<br />
‘perbedaan’ (differences) dalam sistem yang sangat<br />
maskulin dan patriarki itu tidak boleh dibangun dengan<br />
209
cara berfikir dunia laki-laki yang lebih memperhatikan<br />
dan kemudian menguntungkan laki-laki lalu melegitimasi<br />
situasi yang tidak menguntungkan perempuan.” Dia<br />
lanjutkan. Dan jangan memaksakan men-download<br />
universalisme lalu di instal dengan relativisme budaya<br />
(cultural relativism) karena nanti berkonflik, biarkanlah<br />
dia pada posisi binner, seperti Lan yang buta dengan<br />
istrinya.<br />
Tiba-tiba Bapakku datang membawa HPnya,<br />
katanya ada Abang Jordan Saragih yang mau dengar<br />
suara ibuku. Ternyata Abang Angkatku yang orang Batak<br />
beragama Nasrani rindu, aku tahu dari dari obrolan<br />
mereka. Abang Jordan ini pernah dapat limpahan kasih<br />
sayang ibuku, bahkan dia harus ke Gereja untuk<br />
menikahkan dia dengan istrinya. Dari Cerita Bapakku,<br />
banyak sekali anak angkatnya di luar pengetahuanku.<br />
Ah, untungya setelah 5 tahun aku mulai<br />
mengurangai advokasi soal perempuan adat ini, jadi tidak<br />
perlu mendalami soal hak Perempuan. Yang sesunguhnya<br />
sangat sederhana sekali, jika itu mau disederhanakan.<br />
210
211
18<br />
Hampir 8 tahun terakhir, sebagian besar aku<br />
habiskan untuk bersama masyarakat di Kampungkampung<br />
yang sebagian besar adalah kaum minoritas<br />
yang tidak banyak di catat dalam perjalanan sejarah<br />
bangsa ini. Ini pencarianku. Jelajah alam komunitas yang<br />
aku lakukan bak pelintas membuat aku tahu bahwa<br />
mereka adalah struktur terbesar pembentuk Negara ini<br />
namun ironisnya menjadi ‘korban’ dari kebijakan Negara<br />
atas nama pembangunan, aplikasi kebijakan dan hanya<br />
dianggap sebagai ‘penumpang’ gelap di kendaraan yang<br />
namanya Indonesia.<br />
“Kami ibarat perahu yang kehilangan dermaga.”<br />
jelas Pak Salim Senawar ketika menceritakan hak<br />
adatnya atas tanah terkoptasi.<br />
Dan. Di sisi lain dilakukan penghancuran strukturstruktur<br />
local secara struktural yang diyakini lebih<br />
mampu untuk mengatur hubungan antar sesama maupun<br />
hubungan dengan alam dan gaib yang diaplikasikan<br />
dengan nilai-nilai kearifan local dan tidak ekploitatif.<br />
212
“Koptasi ini membuat kami seperti orang-rang<br />
kalah,”<br />
“Orang-orang kalah yang terkatung-katung tidak<br />
saja dalam ketiadaan harapan, tapi bahkan dalam<br />
kepungan ancaman-ancaman.”<br />
“Sebagai orang kalah, kami tidak mencari<br />
pahlawan, melainkan sekedar haus terhadap sahabat.<br />
Kami tidak menuntut agar dipindahkan dari kekalahan ke<br />
kemenangan, tetapi setidaknya kami mempunyai sahabat<br />
dalam kekalahan.” Kata Pak Salim Bijak.<br />
Dalam hati dan pengalaman menapakku lama-lama<br />
aku menjadi tahu: ada banyak orang-orang kalah dan<br />
dikalahkan tetapi belum tahu bagaimana menjadi sabahat<br />
yang baik dalam kekalahan. Aku bahkan belum tahu di<br />
file kategori mana menyimpan kenyataan dimana ratusan<br />
pedagang, petani yang penghasilannya belum bisa<br />
mencapai kata “cukup”. Yang ruang kelola hidupnya<br />
secara paksa digusur atau dalam bahasa klisenya<br />
direlokasi atas nama pembangunan yang sesungguhnya<br />
diselimuti kepentingan ekonomi yang sangat individual<br />
kapitalistik, atau mungkin saja atas kesepakatan dan<br />
sadera atas komitmen “diam” politik. Ditolong dan<br />
213
ditemani tidak oleh orang yang digaji hidupnya dari iuran<br />
pajak dalam bentuk distribusi dari kaum yang<br />
penghasilannya belum bisa mencapai kata “cukup”,<br />
melainkan oleh orang-orang muda yang belum menentu<br />
hidupnya? Bahkan mereka ini pula yang dengan setianya<br />
bersama untuk satu napas mengapai asa “kemenangan”.<br />
“Jumlah orang-orang kalah semakin membengkak<br />
saja dari hari kehari.” Terangku<br />
“Dan jumlah itu semakin tidak terkirahkan lagi<br />
takkala kita mengetahui bahwa orang-orang yang<br />
mengalahpun.” Aku terdiam.<br />
“Bahwa orang-orang yang memperoleh<br />
kemenangan atas orang lainpun sesungguhnya adalah<br />
orang-orang kalah.” Lanjutku mulai kompromis.<br />
“Tuhan tidak memintamu untuk menang melawan<br />
orang lain. Yang diminta-Nya adalah kemenangan<br />
melawan diri sendiri.” Jawab Pak Salim yang tahu<br />
penyerahakku.<br />
Pak Salim berusaha melawan kenyataan filosofi<br />
populer yang berlaku dimana-mana. Dunia membuka<br />
lapangan kompetisi agar seseorang mengalahkan lainnya.<br />
214
Dengan kata lain: agar seseorang menjadi pemenang,<br />
sementara yang lainnya menjadi orang kalah.<br />
“Kalau begitu betapa tidak membahagiakan dunia<br />
semacam itu!”<br />
“Betapa setiap keindahan dalam kemenangan<br />
semacam itu sesungguhnya palsu! Kemenangan dan<br />
keindahankah yang didapatkan oleh seseorang Kades<br />
yang berhasil tidak memperhatikan kesejahteraan<br />
penduduknya, bahkan menguras kekayaan penduduk itu<br />
untuk perutnya sendiri?” Tanyaku Pak Salim tertawa<br />
Pikiranku melayang jauh ke tapak dimana jejakku<br />
tertinggal. Masyarakat adat Bermani, dimana wilayah<br />
kelola warganya masuk ke dalam kawasan hutan negara,<br />
hutan lindung. Oleh Negara ini kawasan-kawasan ini<br />
hanya difungsikan untuk konservasi (perlindungan,<br />
pengawetan jika mengacu pada faham konservasi alam<br />
klasik (classic nature conservation).<br />
Kebijakan yang membuka peluang masyarakat<br />
untuk terlibat didalamnya melalui sistem Hutan<br />
Kemasyarakatan (HKm) belum membawa manfaat<br />
ekonomi bagi masyarakat, belum mapu penompang<br />
kehidupan yang lebih jauh sebagai sistem pertahanan<br />
215
warganya baik secara ekonomi, sosial, bidaya dan<br />
religius.<br />
Dibagian lain komunitas adat Sungai Ipuh yang<br />
menghormati system kaum/kelembagaan adat yang<br />
dicerminkan dengan pepatah adat sutan hidayat mudik<br />
bekudo, kudo tuanku pagaruyung, lubuk adat gedung<br />
lembaga, urang tuo kepalo kaum. Hamparan wilayah<br />
adatnya kemudian berganti dengan hamparan perkebunan<br />
besar swasta, kebijakan lewat konversi hutan dalam<br />
mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit<br />
skala besar. Dalam prakteknya telah menimbulkan<br />
berbagai dampak negatif terhadap lingkungan maupun<br />
dampak sosial dan berkontribusi terhadap rusaknya<br />
tatanan struktur-struktur sosial masyarakat yang hidupnya<br />
bergantung pada pengelolaan hutan dan lahan.<br />
Perkebunan besar juga munculkan masalah sosial<br />
lainnya, dengan ekspansi perkebunan yang masif telah<br />
menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada tata<br />
cara pengusahaan sumber daya alam dimana akhirnya<br />
lahir konflik sosial.<br />
Konflik ini disebabkan oleh diklaimnya lahan hutan<br />
dan pertanian masyarakat menjadi areal perkebunan<br />
216
kelapa sawit. Perbedaan kepentingan ekonomi ini<br />
membuat negara lebih berpihak pada pengusaha dengan<br />
mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal atas hutan<br />
dan tanah yang telah mereka kelola sacara turun temurun.<br />
Mereka pun terjerat dan kemudian mereka ‘dipaksakan’<br />
untuk menjadi buruh di atas tanah mereka karena alasan<br />
bertahan hidup.<br />
Suku Tengah Kepungut salah satu sub suku dalam<br />
Sistem Adat Lembak, mereka dipaksanakan untuk<br />
meningalkan kebun-kebun garapan mereka karena di atas<br />
tanah tersebut akan dibangun Projek Tranmigrasi. Project<br />
Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan<br />
Daerah. Klaim Pemerintahan Daerah. Mereka yang<br />
dikalahkan melakukan perlawanan. Dan, berhasil<br />
menghentikan pembangunan project tersebut untuk<br />
sementara waktu.<br />
System penguasaan tanah dalam konflik ini<br />
menjelaskan hak miliki atas tanah, hak atas tanah tidak di<br />
pegang oleh satu pihak saja. Pada saat yang sama di<br />
bidang tanah yang sama, bisa saja terdapat sejumlah<br />
pihak yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut<br />
secara bersamaan tetapi dengan sifat hak yang berbeda-<br />
217
eda (bundle of rights) antar negara dan hak kepemilikan<br />
warga.<br />
Sementara landasan kebijakan pengelolaan<br />
sumberdaya alam di Indonesia adalah Undang-Undang<br />
Dasar 1945—yang sudah diamandemen empat kali—<br />
khususnya pasal 33 ayat 3 yang isinya : “Bumi, air dan<br />
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai<br />
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk<br />
kemakmuran rakyat”. Konsep “Negara menguasai bumi,<br />
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” ini<br />
dikenal sebagai konsep ‘Hak Menguasai Negara’.<br />
Dengan demikian politik sumberdaya alam di<br />
Indonesia yang diwakili pasal 33 UUD 1945 berpusat<br />
pada kekuasaan yang besar dari Negara terhadap<br />
penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya<br />
alam. Dari beberapa persoalan dari catatan kasus di atas<br />
merupakan dampak dari Hak Menguasai Negara yang<br />
menekankan pada paradigma stated based natural<br />
resources, bahwa ‘paradigma pengelolaan sumberdaya<br />
alam yang berbasis Negara cenderung memberikan<br />
kewenangan yang penuh kepada Negara untuk<br />
mengklaim, menguasai, memiliki dan mengatur<br />
218
pengelolaan sumberdaya alam, sehingga secara sistemik<br />
Negara menegasikan klaim-klaim Masyarakat Adat, local<br />
dan lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alamnya’.<br />
Paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang<br />
didominasi oleh Negara ini dibuat dengan sangat<br />
sentralistik yang disebabkan kondisi Negara yang<br />
terhegemoni atas system kapitalis dan system politik<br />
Negara yang berkembang, kondisi ini terlihat dari<br />
kebijakan yang dibuat hanya untuk berpihak dengan<br />
pemilik modal, Negara memberikan berbagai fasilitas<br />
kemudahan yang memungkinkan para pemilik modal<br />
untuk menguasai sumber-sumber daya alam untuk<br />
kepentingakn akumulasi modal dan menegasi<br />
kepentingan masyarakat adapt atau local lainnya.<br />
Eforia reformasi maupun sebelumnya ‘perlawanan’<br />
dalam menuntut hak atas milik masyarakat yang dikuasai<br />
oleh Negara tersebut telah dilakukan di berbagai tempat<br />
dengan issue yang sama dan system gerak yang berbeda,<br />
ini menunjukkan di satu sisi semakin “gilanya” tekanan<br />
struktural kapitalisme yang menyengsarakan rakyat dan<br />
di sisi lain meluasnya perlawanan dan keresahan rakyat<br />
tapi dalam formasi yang tersebar, tidak saling terhubung,<br />
219
dan cenderung tidak signifikan dalam mendorong<br />
akselerasi perubahan politik baik dalam skala lokal<br />
maupun nasional.<br />
Dimana Kaum-kaum muda yang mencoba untuk<br />
mengeliminasi ‘kekalahan’ dan mencoba mengapai asa<br />
kemenangan bersama kaum yang kalah dan dikalahkan<br />
itu.<br />
“Tidak ada orang menang, melainkan orang kalah,”<br />
ini penomena, demikian sering Pak Salim bilang.<br />
“Orang kalah.”<br />
“Orang yang dikalahkan.”<br />
“Oleh siapa?”<br />
“Oleh orang lain.” Oleh kehidupan yang tikaman<br />
pisaunya amat menyakitkan. Oleh kekuasaan yang datang<br />
dari luar dirinya.<br />
Ternyata aku masih disini, masih bersama orangorang<br />
yang dikalahkan. Menjadi sahabat baik kekalahan.<br />
220
19<br />
Hari minggu, sinar matahari mulai mengintip<br />
melalui celah-celah daun jambu dan sawo yang aku<br />
tanam sendiri. Daun-duannya berguguran akibat hujan<br />
badai malam tadi. Habis berolah pagi raga aku sapu<br />
daun-daun yang berguguran. Anak kecilku tiba-tiba<br />
datang dengan sepeda kecil kesayangannya. Begitu<br />
selesai menyapu halaman, aku di panggil istriku kopi<br />
pahit kesukaanku sudah tersaji.<br />
Ini hari pertama di bulan kedua 2015. Bulan kasih<br />
sayang, konon pada bulan ini valentine membuktikan<br />
penyerahan cintanya, cinta penyatuan dengan seseorang<br />
atau sesuatu diluar dirinya, pada saat seseorang sedang<br />
mempertahankan keterpisahan dan integritas dirinya.<br />
Seperti biasanya, di hari minggu. Hari minggu<br />
bagiku hari untuk memastikan hak ibu dari anakku<br />
sebagai perempuan terpenuhi, aku ambil kendali semua<br />
pekerjaan rutin rumahnya. Dan, dia bebas melakukan apa<br />
saja hari ini.<br />
Hari mulai meninggi, aku duduk di gerasi<br />
sederhana rumahku, sambil menikmati kopi dan rokok<br />
221
kesukaanku. Ku panggil kedua putraku. Yang bungsu ku<br />
angkat dan dia duduk dipangkuanku, sedang yang sulung<br />
duduk sebelah kiriku.<br />
“Nak.” Sambil aku matikan rokokku.<br />
Akan Bapak ceritakan tentang Nenekku.<br />
“Dia ibu dari nenekmu.” Keduanya mulai serius,<br />
karena biasanya setelah aku ceritakan sesuatu ke mereka,<br />
pastilah setelah itu mereka akan ceritakan dengan ibunya,<br />
atau dengan temannya dengan cara dan bahasa mereka.<br />
Dulu, dirumah kami hanya ada 5 orang penghuni<br />
resminya, aku dan adikku, nenek dan kakek kalian, itu<br />
ibu dan bapakku, dan nenekku, itu Poyang kalian. Ruang<br />
yang selalu menyatukan kami adalah ruang dapur, pagi<br />
hari, kami sama menghangatkan tubuh dekat tungku kayu<br />
sambil menikmati aroma yang akan kami santap pagi itu.<br />
Lalu, di sore hari kami makan malam bersama setelah<br />
sholat magrib, kami duduk melingkar dan bersila diatas<br />
tikar bambu hasil anyaman tangan keriput Nenenkku, aku<br />
selalu duduk disampingnya, dialah yang selalu<br />
menambah nasiku.<br />
Namanya Hadijah, Hajjah Hadijah. Dia<br />
mendapatkan gelar Hajjah ketika anak bungsunya<br />
222
erumur 6 tahun. Itu ibuku. Nenek kalian. Ibuku, anak<br />
yang 13 dilahirkannya. Dulu, ketika dia baru punya dua<br />
orang anak, suaminya ditahan pemerintahan Belanda<br />
karena ketahuan melakukan perencanaan dan<br />
pemberontakan. Sebelum tidur, karena aku selalu tidur<br />
dibelakang punggunya, aku sering memperhatikan garisgaris<br />
pada wajahnya, garis tegar yang menandakan dia<br />
sebagai perempuan bukan sebagai wanita. Suaminya<br />
meninggal ketika ibuku berumur 8 tahun, dan itu sungguh<br />
sangat siap dia mengendalikan keluarga besar tanpa<br />
suaminya, tanpa kakekku.<br />
Dia tumpahkan kasih sayangnya padaku, dan aku<br />
beruntung diantara 67 orang cucu-cucunya. Dari<br />
mulutnyalah aku diberitahu tentang betapa besar dan<br />
kuatnya cinta Bujang Kurung dengan Dayang Kerne,<br />
mitologi cinta yang dibatasi langit dan bumi. Cinta yang<br />
mengorbankan sebagian untuk memenuhi dan menutupi<br />
kekurangan cinta yang lain. Lalu, dia juga yang ceritakan<br />
tentang kisah romantis antara Cerlik Cerilang dengan<br />
Sinatung Natak, kekuatan cinta yang mampu<br />
menghidupkan yang mati, cinta mulo bangun, kata-kata<br />
223
penutup diakhir cerita. Cerita-cerita yang keluar dari<br />
mulutnya, adalah cerita mengugah emosi.<br />
“Dia tidaklah sekolah nak, tapi dia tahu bahwa<br />
emosi tidak hanya membantu kita mempertahankan<br />
keyakinan tetapi juga membela kita dari keyakinankeyakinan<br />
lain yang mengancam pandangan kita tentang<br />
dunia,” Ceritaku.<br />
Menurut dia konsesus menjadi bagian penting dari<br />
proses pembentukan keyakinan yang mengabungkan<br />
pengalaman perseptual, nilai-nilai emosional dan<br />
gambaran kongnitif ke dalam sesuatu yang utuh dan<br />
secara sosial diterima.” Kedua putraku serius mendengar<br />
cerita perempuan leluhur mereka.<br />
Dia tidak cerewet, tubuhnya tegak, tinggi dan<br />
berkulit putih, ada bercak-bercak merah tanda termakan<br />
usia di kulitnya. Aku selalu belajar bagaimana cara<br />
menghindari perdebatan dan pertentangan bila sistem<br />
kayakinan bertabrakan?<br />
“Di keluarga besar Suaminya, dia menjadi tiang<br />
tengah,”<br />
“Dia memposisikan sebagai poros utama.”<br />
Terangku.<br />
224
Tabrakan keyakinan dan gesekan pastilah ada.<br />
Jawabanya kemudian aku tahu perlu kerja keras untuk<br />
membangun toleransi, pada titik ini, ia membutuhkan<br />
upaya sadar terus-menerus menerapkan ideal-ideal<br />
spiritual dan humanistik.<br />
“Ini realitas historis,”<br />
“Aku tahu maksud bapak”<br />
“Apa?” tanyaku<br />
“Sebuah kemampuan memahami dunia luar dari<br />
manusia realitas yang berubah.” Jawab Bdikar.<br />
“Betul. Oleh karena itu, konsepsi kita terhadap<br />
sejarah haruslah bermula dan berdasar pada realita yang<br />
utuh,”<br />
“Seperti setiap makluk hidup adalah dirinya sendiri<br />
namun juga sesuatu yang lain dari dirinya,” Kedua<br />
anakku menganguk-anguk.<br />
Kita bisa saja mengisi celah dengan keyakinankeyakinan<br />
rumit, tetapi kebimbangan dan ketaidakpastian<br />
tetap ada. Inilah yang menarik kita semakin jauh ke<br />
dalam pencarian akan pengetahuan, makna kebenaran.<br />
“Kita terus berputar-putar karena manakala ada<br />
misteri, otak kita ditakdirkan untuk menyelajahinya.”<br />
225
Aku yakin Bdikar mulai tertarik dengan ceritaku, tetapi<br />
dari tadi dia diam saja. Tidak ada respon apa-apa.<br />
Secara logis bisa saja kita pakai sebab akibat, kita<br />
berusaha untuk menjadikannya masuk akal-memberi<br />
alasan, penyebab.<br />
“Jadi kita bisa menjelaskan sesuatu,” Bdikar<br />
terpacing<br />
“Iya,” Jawabku<br />
Kita mungkin menyebutkannnya sihir, mukjizat<br />
atau halusinasi, bergantung pada penjelasan mana yang<br />
lebih masuk akal atau memberikan kita banyak<br />
kedamaian dan harapan.<br />
“Tetapi, ketika kita tidak dapat membuat koneksi<br />
kausal ini maka kita akan merasa terasing dan<br />
menghalangi kita membedakan antara keyakinan dan<br />
kejadian imajiner dan kebetulan.” Bdikar tertawa. Dia<br />
tandang keras-keras bola adiknya. Lalu keduanya berebut<br />
bola dan berkelahi sampai ibunya datang. Jurus Auman<br />
Singa ibunya menghentikan perkelahian kedua anak lakilakiku.<br />
226
20<br />
Nak, malam ini bapak tidak di Rumah. Tapi tetap<br />
akan aku antarkan tidur kalian dengan cerita, meskipun<br />
Bapak tidak ada disana, tapi kalian tetap ada di hati<br />
Bapak. Cerita itu Bapak tulis dalam lembaran-lemaran<br />
setiap sel darah, kemudian Bapak simpan dalam bentuk<br />
narasi tanpa jeda dari rindu yang kian dalam terpatri di<br />
dada dan di sanalah kalian tidur dalam dekapan hangat<br />
dan tak biarkan kalian mengigil dingin dan panas<br />
berkeringat.<br />
“Ah, sudahlah,”<br />
“Yang penting jangan nakal,”<br />
Karena auman dan cubitan ibumu bisa sampai<br />
merah perut kalian nanti.<br />
“Oh ya,”<br />
“Apakah sekolah Abang sudah dibuka segelnya.?”<br />
Kemaren waktu Bapak antar Abang ke sekolah,<br />
dalam hati Bapak marah sekaligus kasihan, kalian belajar<br />
di emperan rumah bedengan itu. Karena gedung sekolah<br />
disegel oleh orang yang mengaku pemilik lahan,<br />
227
sementara “penguasa” disana diam saja seakan tidak ada<br />
masalah.<br />
Padahal mereka tahu mereka berkewajiban untuk<br />
memastikan hak kalian untuk mendapatkan pendidikan<br />
yang tidak hanya layak tetapi berkualitas, tapi tidak apaapa<br />
bukankah dulu mereka disumpah untuk<br />
melaksanakan perintah pelayanan itu.?<br />
“Secara hukum,”<br />
“Mungkin saja tidak bisa kita paksakan lalu<br />
menempelkan sangsi ke mereka, tapi yakinlah sangsi<br />
sosial secara pelan-pelan akan masuk ke dalam otak,<br />
jantung dan kemudian menyerang ke sel-sel pembuluh<br />
darah, lalu kutukan sosial ini secara genetik akan turun ke<br />
keturunannya sampai pada turunan yang ketujuh barulah<br />
kutukan itu netral.”<br />
SMS ibumu malam tadi buat hati Bapak senang,<br />
pemilik lahan sekolahmu itu mulai lunak hatinya<br />
kemudian membuka segel dan kalian bisa belajar<br />
kembali, tapi tetap saja “Penguasa” yang lehernya pendek<br />
itu bisa tidur nyenyak di istana yang dibangun dari pajak<br />
yang Bapak bayar seperti biasanya.<br />
“Bapak berangkat tadi Abang masih di Sekolah,”<br />
228
“Bapak naik Garuda nak,”<br />
“Ini pesawat katanya milik Negara,”<br />
Bapak beruntung duduk di baris kedua dari dinding<br />
pembatas kelas ekonomi dan bisnis, posisi duduk itu<br />
menguntungkan sekali, sehingga Bapak bisa merasakan<br />
betapa nikmatnya kalau duduk di Kelas Bisnis,<br />
bangkunya luas, pramugarinya ramah-ramah lagi.<br />
Bapak dapat bangku di tengah.<br />
Kiri kanan Bapak duduk dua orang laki-laki. Dari<br />
penampilannya, sepertinya mereka pejabat tinggi dan<br />
tentu mereka sangat sibuk. Itu terlihat dari mulai mereka<br />
duduk, masing-masing kedua tangan mereka pegang HP,<br />
dari merknya Bapak tahu harganya pasti mahal sekali,<br />
pasti harganya 50 kali lipat dari harga HP Bapak yang<br />
cuma harganya Rp. 200.000.<br />
Lalu, Bapak pura-pura tidur sambil mengintip<br />
tulisan apa yang sibuk mereka baca, ternyata isinya SMS<br />
ecek-ecek, sepertinya ada janjian tapi tidak ada<br />
hubungannya dengan pekerjaan mereka. Kalaupun ada<br />
portal berita, berkali-kali mereka buka portal dengan<br />
berita yang sama.<br />
229
“Bapak sekarang sedang ada di Kota yang dulunya<br />
disebut dengan Batavia nak.”<br />
“Suatu hari kalian juga akan sampai ke sini.”<br />
Bapak berangkat tadi tidak dimulai dari angka nol,<br />
tapi berangkat dari Minus 10. Ada banyak yang belum<br />
diselesaikan, tidak hanya tentang persoalan rumah kita.<br />
Istana kecil kita yang dipenuhi bunga ditanami ibumu,<br />
tapi bertumpuk persoalan di rumah kedua Bapak. Rumah<br />
kedua itu rumah tempat Bapak kerja nak.<br />
Ada banyak persoalan butuh diselesaikan, temanteman<br />
Bapak tadi ketika Bapak berangkat ke Bandara, di<br />
masing-masing kening mereka sepertinya ada angka III<br />
Romawi, kedua alis mereka seakan-akan bersatu. Seakanakan<br />
mereka mau melahap habis semua persoalan yang<br />
terjadi di Negeri ini, dan ini konras sekali dengan para<br />
Pejabat yang duduk disamping Bapak tadi.<br />
Hati Bapak mulai kasihan dan iba, terutama dengan<br />
satu Perempuan yang suka pakai jilbab dan jean warna<br />
merah, sepertinya dia harus berpikir keras, karena dialah<br />
yang harus mengatur segala hal agar Rumah kedua itu<br />
agar tetap seperti biasanya, meskipun pada saat yang<br />
230
sama terjadi tumpukan dan tunggakan masalah yang juga<br />
harus dia selesaikan.<br />
“Dan pagi ini dengan segaris banyangan kalian<br />
seakan melangkah dari cangkir kopi”. Kopi bapak<br />
dibautkan oleh tangan kekar teman Bapak.<br />
“Dulu kampungnya integrasi dan sekarang sudah<br />
Merdeka”<br />
Bayangan kalian pelan-pelan mencoba jauh berlari<br />
mengendap-endap bersembunyi diantara hati dan jantung<br />
yang setiap debar gumamnya akan terjaga oleh semu<br />
geletar menjalar dari paras tidur kalian yang berpendar.<br />
Dan itu tentu saja cukup buat Bapak membariskan<br />
diri kemudian membiarkan impian terus saja mengusik<br />
diri membayangkan jutaan impian yang kian berseri,<br />
impian yang akan mengisi ruang kosong yang enggan<br />
singgahi oleh Petinggi Negeri ini.<br />
“Nanti akan aku kirim cerita-cerita buat pengantar<br />
tidur kalian.” Bisikku dalam hati.<br />
231
21<br />
“Sudah tidurkah kalian disana Nak.?”<br />
“Kalau Bapak tidak di rumah siapa yang menjadi<br />
Pemimpin.?” Ini pertanyaan yang sering aku lontarkan<br />
kepada anak tertuaku.<br />
“Aku yang akan memimpin.” Jawabanmu dengan<br />
yakin.<br />
Pasti kalian tidak nakalkan, karena tidak akan ada<br />
yang bela kalian ketika bentakan dan cubitan ibumu<br />
menempel dikulit kalian. Apakah ibumu tadi cerita<br />
tentang hidup.? Dimana nanti yang kalian hadapi adalah<br />
suatu masa dimana jiwa bergejolak duka ketika<br />
pertumpahan hati tak lagi bisa bersua dan garis<br />
kehidupan haruslah tetap kalian jalani sambil meniti<br />
jejak-jejak yang mungkin saja salah tapi yakinlah semua<br />
akan berakhir indah seperti pada bagai bunga mawar<br />
mewangi yang di tanam ibumu pada teras rumah kita.<br />
Dalam doa yang selalu kami tiupkan pada ubunubun<br />
kalian adalah bahwa damai akan selalu bernaung<br />
232
pada kebahagiaan, damai itu kejujuran dan kebahagiaan<br />
itu tujuan.<br />
“Oh ya nak,” Sekarang Bapak sudah di Cirebon, di<br />
Kesepuhan Cigugur kalau secara Adminstratif sudah<br />
masuk wilayah Kuningan, di sini dingin sekali sama<br />
seperti di Kampung Nenek kalian. Masyarakatnya ramah<br />
dan setiap tuturnya halus, mereka berbahasa Sunda, saya<br />
senang disini.<br />
Mereka menghormati keberagaman, mereka satu<br />
suku, satu bahasa tapi keyakinan mereka berbeda. Bapak<br />
tidur dirumah Penduduk, mereka hanya berdua saja di<br />
sini, kami diterima dengan baik. Tuan rumah banyak<br />
bercerita tentang kehidupannya, mereka punya tiga putri<br />
semuanya sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari<br />
kampung. Mereka Nasrani nak, tapi tak apa-apa<br />
bukankah soal keyakinan adalh soal hubungan antara<br />
manusia dengan tuhannya.<br />
Ini kali pertamanya Bapak kesini, Bapak berangkat<br />
dari kota Batavia itu, kami harus kumpul di stasiun dekat<br />
Monumen yang katanya sebagian besar emas yang<br />
menghiasai monomen ini dari kampung Bapak, ini<br />
bentuk kontribusi terhadap Negara ini. Bapak berjumpa<br />
233
dengan teman-teman lama Bapak, ada yang dari Propinsi<br />
yang tiap tahun selalu saja menghasilkan kabut asap,<br />
karena penetrasi kapitalisme melalui ekploitasi<br />
perkembunan sangat masif disana. Ada juga dari<br />
Palembang, Borneo dan Selebes, mereka orang-orang<br />
hebat nak, mereka pembela rakyat sejati.<br />
Kami sama-sama menuju Cirebon memalui kereta<br />
api, Bapak tentu saja menikmati perjalanan ini,<br />
disepanjang perjalanan sawah terbentang luas, mungkin<br />
dua puluh tahun lagi, pasti sudah berubah menjadi<br />
kawasan industri yang hanya mempruduksi buruh dan<br />
kemiskinan bagi masyarakat sekitarnya. Sepanjang<br />
perjalanan yang terpikir oleh Bapak ternyata memang<br />
basis Negara kita hanya agraris dan maritim, bukan yang<br />
lain-lain, tapi kenapa ya.? Keduanya menjadi daftar<br />
terakhir yang menjadi prioritas pembangunan. Dan<br />
bukankah penjajah dulu datang ke sini hanya butuh hasil<br />
pertanian itu.?<br />
Nak, tidak sengaja karena asiknya menikmati<br />
hamparan sawah, tiba-tiba sekilas saja lirikan Bapak<br />
tertuju pada seorang perempuan berkaca mata. Memori<br />
kolektif Bapak tiba-tiba berbalik pada 10 tahun yang<br />
234
lalu, Bapak jadi ingat dengan dua orang perempuan<br />
berkaca mata yang megisi kisi-kisi hati Bapak ketika itu.<br />
Satu berjilbab dan berkacamata, tururnya lembut karena<br />
memang anak bungsu dikeluarganya, ada ada juga<br />
berkaca mata lainnya, mandiri, lincah dan tegas.<br />
Perempuan berkacamata pertama yang Bapak kenal<br />
ketika di Bis menuju kota tempat Kuliah, ketika itu<br />
Bapak tidak sehat badan dan AC mobil yang rusak, dia<br />
duduk disamping Bapak kemudian dengan bermurah hati<br />
dia berikan jaketnya untuk Bapak, kami kuliah di kota<br />
yang sama tapi tempatnya beda. Mulai saat itu ada<br />
perasaan aneh kepada dia, lalu di tingkat 5 di Gedung<br />
jalan Damar itu kami sepakat untuk saling menyatuhkan<br />
hati kami.<br />
Ada banyak waktu yang kami habiskan bersama,<br />
sampai pada akhirnya kami harus terpisah karena Bapak<br />
tidak lagi bisa melanjutkan Kuliah Bapak. Bapak ketemu<br />
dia kembali setelah 8 tahun terpisah dan umurmu ketika<br />
itu 1 tahun. Dia menangis histeris nak, lalu dia bercerita<br />
banyak tentang perjalanan hidupnya ketika kami tidak<br />
lagi bersama. Setelah manamatkan kuliahnya, dia sampai<br />
kemudian dia bekerja untuk Negara ini, dia tutup hatinya<br />
235
untuk lelaki lain sampai dia ketemu dengan seseorang<br />
yang mirip dengan Bapak dan seseorang itu telah<br />
berkeluarga, jadilah dia simpanan lelaki itu. Semuanya<br />
dia ceritakan sambil berurai air mata histeris nak, Bapak<br />
kemudian menggelus dada betapa dia mencintai Bapak.<br />
Tentu Bapak merasa bersalah. Meninggalkan hati yang<br />
mencintai dengan tulus tanpa ada rasa bersalah.<br />
Tiga tahun yang lalu, perempuan berkacamata<br />
kedua datang ke kota kita nak. Dia teman lama dan di<br />
beberapa kesempatan kami sering berdua untuk belajar<br />
menyelesaikan persoalan yang terjadi di Negeri ini. Dia<br />
datang ke kota kita. Tapi bukan untuk pekerjaan yang<br />
biasa kami lakukan, tapi dia dapat tugas dari Negara.<br />
Karena dia bekerja untuk Negara ini. Sebagai teman lama<br />
tentu saja Bapak ajak dia keliling kota kita, sampai dia<br />
pulang kembali ke Ibu kota. Dia bekerja untuk sebuah<br />
Departemen nak. Awalnya kami tidak ada apa-apa.<br />
Semuanya berjalan seperti apa adanya, sampai suatu<br />
malam, telepon Bapak berdering dan ternyata Namanya<br />
yang muncul. Dia bilang ketika itu, ada yang tertinggal di<br />
Bengkulu, dan itu hati untuk Bapak nak. Dua bulan<br />
setelah itu, Bapak berkunjung ke kotanya, kami habiskan<br />
236
indu dan hasrat kami sampai tidak ada yang tersisa. Lalu<br />
Bapak harus menjawab benyak pertanyaan dan pilihan,<br />
tentu pilihan pada akhirnya kalianlah yang Bapak pilih.<br />
Bapak tahu berkepinglah hatinya, ada banyak komitmen<br />
dan espektasi pada dia, namun tak bisa Bapak penuhi.<br />
Bapak bisa rasakan betapa sakitnya dia atas rasa itu.<br />
Tentu saja Bapak besikap, bahwa kalianlah<br />
segalanya. Selama 7 tahun bapak bangun cinta bapak<br />
dengan ibumu sebelum kemudian kami ikat cinta itu<br />
dengan pernikahan dan itu yang membuat kalian lahir,<br />
lahir dari sebuah rasa cinta. Tentu saja si kaca mata itu<br />
hanyalah jadi bagian yang menghiasi perjalanan Bapak.<br />
Sedikit saja rasa itu mampir kemudian bayangan kalian<br />
dan ibumu menghapus bayangan semu itu. Tentu saja itu<br />
bersalah ketika rasa itu tak berbalas, tapi kemudian dia<br />
kasih tahu ke Bapak bahwa dia akan melanjutkan<br />
hubungannya dengan seorang pria yang di sayangi<br />
meskipun tidak sebesar rasanya kepada Bapak.<br />
Meskipun dia hanya sebentar mampir dihati Bapak<br />
kemudian permanen di hatinya, ada pelajaran yang<br />
menarik dari perjalanan singkat kami.<br />
237
Dia pernah bilang “bahwa rasa itu tidak boleh<br />
disimpan dihati, jika seandainya rasa itu menguat maka<br />
dia harus dilisankan, meskipun kemudian menyebabkan<br />
rasa sakit dihati, itulah konsekwensi dari apa yang<br />
menjadi pilihan termasuk pilihan hati”. Sikap ini tentu<br />
saja dipengaruhi oleh pendidikan dan pergaulannya<br />
ketika dia melanjutkan pendidikannya diluar Negeri.<br />
Bapak senang dengan sikap dia yang keluar dari<br />
pakem perempuan timur yang malu-malu padahal itu<br />
munafik dan menafikan sikap yang ada dihatinya. “Nak,<br />
tapi ini jangan disampaikan ke Ibu kalian ya, nanti bisa<br />
ada perang dunia ke III”.<br />
“Tapi tidak apa-apa,” Beberapa kali pernah Bapak<br />
cerita dengan ibumu, dan dia mengerti.<br />
“Tentu saja dia mengerti nak kami 18 tahun sudah<br />
bersama, jadi tidak ada yang harus ditutupi, dan itu akan<br />
menguatkan konsolidasi dan hubungan kami.” Mataku<br />
berair dan mulai merindukan teras rumah dan bau<br />
keringat anak bungsuku.<br />
238
22<br />
“Bapak, sudah malam. Mari tidur dan cerita lagi<br />
yuk.” bujuk Titon, ketika pulang setelah sekian hari<br />
berkelana diluar.<br />
Titon. Dia putra kecilku yang masih berumur 4<br />
tahun, Akupun matikan Televisi yang sedang menyiarkan<br />
siaran yang tidak bermutu itu, kemudian bergegas ke<br />
kamar tidur. Dan seperti malam sebelumnya, posisi<br />
tidurku selalu di pingir. Karena setiap malam aku harus<br />
cerita sebagai pengantar tidur mereka. Aku mulai<br />
kehabisan bahan, aku tahu menyampaikan cerita<br />
menjelang tidur itu bagus sekali untuk anak-anak yang<br />
sedang dalam masa pertumbuhan, selain untuk relaksasi,<br />
juga berguna untuk membantu keterampilan problem<br />
solving serta mampu merangsang imajinasi, kreatifitas<br />
dan keterampian berpikir bagi anak.<br />
“Baik nak, untuk malam ini saya akan bercerita<br />
tentang Peradilan Sang Kancil” jawab saya sambil<br />
membenarkan posisi tidur untuk memastikan bahwa kami<br />
saling berinteraksi.<br />
239
Akupun memulai cerita. Pada suatu pagi, ketika itu<br />
sinar mata hari mulai mengintip dari balik dedaunan yang<br />
tumbuh rindang disepanjang spadang sungai. Seekor<br />
biawak menjemur anaknya yang baru lahir 4 hari yang<br />
lalu, dan diletakkannya di salah satu bebatuan di pinggir<br />
sungai. Induk biawak meninggalkan anaknya.<br />
Tak lama kemudian datanglah anak kijang yang<br />
meloncat-locat seperti kegirangan. Tidak sengaja diapun<br />
menginjak anak biawak yang masih berwarna kemerahmerahan.<br />
“Anak biawak itupun tewas.” Ceritaku. Mata Titon<br />
membesar. Induk biawak datang, dia sedih dan marah.<br />
Dapati anaknya sudah tewas mengenaskan, sekujur<br />
tubuhnya penuh jejak kaki anak rusa.<br />
Dia yakin bahwa yang membunuh anaknya adalah<br />
anak rusa. Dia menuntut keadilan. Pengadilan dipimpin<br />
oleh sang kancil. Visum dan indok biawak di periksa dan<br />
diminta keterangannya. Hasil dari Berita Acara<br />
Pemeriksaaan dan visum disebutkan bahwa kematian<br />
anaknya disebabkan oleh kaki anak rusa. Jejak kakinya<br />
terang di mata hukum.<br />
Lalu, digelarlah peradilan.<br />
240
Anak rusapun dipangil ke pengadilan untuk<br />
diperiksa keterangan, statusnya saksi yang akan dijadikan<br />
tersangka. Anak rusa mengakui bahwa dialah yang<br />
menginjak anak biawak.<br />
“Akulah yang menginjak anak biawak, karena<br />
waktu itu aku sedang menari karena mendengar bunyi<br />
gendang monyet.” Akui anak rusa.<br />
“Oh ternyata kamu tidak salah yang salah adalah<br />
monyet,” Kata si Kancil. Akibat monyet menabuh<br />
gendang, anak rusa menari lalu terinjak anak rusa.<br />
“Pangil monyet kesini biar kita minta<br />
pertanggungjawabannya.” Perintah si hakim. Kancil.<br />
Monyet datang ke pengadilan.<br />
“Benar kamu yang menabuhkan gendang,” tanya si<br />
hakim kepada monyet yang duduk sambil garut-garut<br />
kepala.<br />
“Benar yang mulia hakim,” jawab monyet. Waktu<br />
itu aku melihat udang mondar mandir membawa senjata<br />
lengkap dan aku pikir akan ada perang maka akupun<br />
menaguhkan gendang. Gendang perang. Lanjut monyet.<br />
“Oh, kalau begitu bukan monyet yang salah,” kata<br />
si hakim, pangil Udang biar kita dengar penjelasan<br />
241
Udang. Lanjutnya sambil mengetuk palu bahwa sidang<br />
akan dilanjutkan besok hari.<br />
Pagi-pagi Udang sudah hadir diruang pengadilan,<br />
sidangpun dilanjutkan dan diawali dengan pertanyaan si<br />
hakim.<br />
“Udang! benar kau yang mondar mandir dengan<br />
senjata lengkap beberapa hari lalu.? Sehingga monyet<br />
menabuh gendang perang, anak rusa menari, lalu terinjak<br />
anak biawak. Anak biawak itu mati, karena<br />
perbuatanmu.!”<br />
“Betul Pak Hakim, karena waktu itu aku lihat si<br />
siput mondar mandir dengan baju besinya”<br />
“Baju besi menandakan bahwa siput siap turun ke<br />
medan perang, akupun berpatroli dengan senjata<br />
lengkap”<br />
“Aku berjaga-jaga meskipun aku belum tahu siapa<br />
lawannya.”<br />
Kancil terdiam. Lalu berkesimpulan bukan udang<br />
yang salah tapi Siput.<br />
Siput di spirindik. Dia dengan suka rela pada<br />
pangilan pertama datang. Dia mengakui di pagi itu<br />
memakai baju besi. Baju perang. Dia menjelaskan<br />
242
alasannya memakai baju besi karena dia melihat setiap<br />
ikat sepat. Matanya merah seperti sedang marah, untuk<br />
mengatisipasi kemarahan ikan sepat, Siput memakai baju<br />
besi. Kancil pemutuskan siput tidak bisa di jadikan<br />
tersangka apalagi terdakwa dalam kasu ini.<br />
Keluarlah surat pemangilan untuk ikan Sepat.<br />
Ceritaku. Mata Titon mulai redup.<br />
Sepatpun datang ke pengadilan. Kancil yang<br />
bertanya “Sepat, benar pada waktu itu, matamu merah<br />
seperti orang yang sedang marah.?”<br />
“Siput ketakutan kemudian dia pakai baju besi,<br />
udang mondar mandir dengan senjata lengkap, dan<br />
monyet mengendangkan gendang perang, mendengar<br />
bunyi gendang anak rusa menari, dia terinjak anak<br />
biawak, lalu tewas!” Tanya Kancil. Intonasi<br />
pertanyaannya mengadung ancaman beratnya sangsi yang<br />
akan diberikan kepada ikan Sepat jika bersalah.<br />
Ikan sepatpun mengerti kenapa tuduhan itu<br />
ditujukan padanya. Dengan santai dia jawab.<br />
“Benar yang mulia Kancil, mataku dan mata temanteman<br />
merah karena air sungai tempat kami hidup kami<br />
243
keruh. Keruh dari hulunya akibat perbuatan Induk<br />
Biawak” jawabnya santai.<br />
“Mendengar jawaban ikan Sepat,” kancil binggung.<br />
Lalu dia pangil beberapa ahli hukum untuk meminta<br />
pertimbangan, setelah bermusyawarah, sidang vonispun<br />
dimulai.<br />
Dengan lantang kancil membaca keputusan sidang.<br />
“Mengingat dan mempertimbangakan bahwa<br />
sidang ini memperhatikan akar dari masalah yang terjadi,<br />
maka kami putusakan yang bersalah adalah Induk<br />
Biawak, karena atas perbuatan yang disengaja telah<br />
membuat air sungai keruh dan kotor, akibatnya ikan sepat<br />
merah, siput memakai baju besi dan udangpun siap<br />
berperang. Gendang perang digendangkan oleh monyet<br />
dan menarilah anak rusa dan menginjak anak biawak,”<br />
“Lalu kami memutuskan yang bersalah adalah<br />
Induk Biawak.!” Terang kancil dengan yakinnya sambil<br />
mengetuk palu sidang.<br />
Lagi-lagi anak tua kami Bdikar, sudah tertidur<br />
sebelum cerita berakhir, untung adiknya masih merem<br />
melek sambil pegang dot susunya, lalu saya padamkan<br />
lampu dan tidurlah kami.<br />
244
245
23<br />
Entah siang ini aku bosan. Obat bosan biasanya<br />
Cuma bau keringat anak kecilku dan wajah ibuku. Ibu<br />
yang dari kecil aku pangil mak. Makku jauh di kampung<br />
dan aku belum punya banyak waktu untuk<br />
menginjunginya. Aku kemudian ambil pena, tintanya<br />
berwarna biru. Lalu pada kertas buran aku mulai menulis<br />
untuk Makku.<br />
“Mak,”<br />
Aku memulai dengan kata Mak. Sampai hari ini<br />
anakmu masih tegak pada posisi dan bekerja untuk<br />
kemanusian/humanism meskipun aku kesulitan<br />
mendekontruksi makna kemanusian itu, aku cuma tahu<br />
bahwa aku hanya bekerja, jadi pekerja Mak. Takut aku<br />
sebut sebagai aktivis, karena aku dapat sesuatu dari yang<br />
aku kerjakan setidaknya ada kepuasan batin disana selain<br />
sedikit material untuk bertahan. Tapi aku tidak<br />
mengantungkan hidup dari sana. Paragraf terakhir ini aku<br />
yakinkan dia bahwa aku akan menghidupi cucunya<br />
dengan nafkah halal.<br />
246
Mak. Aku melanjutkan dengan paragraf kedua,<br />
dengan paragraf pertama tanpa coretan. Sebelum aku<br />
sampaikan lebih jauh tentang apa yang aku kerjakan dan<br />
tentu saja ada teman-temanku yang mengerjakan hal yang<br />
sama dengan motif yang berbeda. “Begini Mak,” aku<br />
bayangkan di duduk di depanku. Aku akan menjelaskan<br />
tentang apa itu humanisme atau aliran kemanusiaan itu,<br />
dari Buku-bukunya Ali Syari’ati yang aku baca. Dia<br />
menyebutkan humanisme sebagai himpunan prinsipprinsip<br />
dasar kemanusiaan yang berorientasi pada<br />
keselamatan dan kesempurnaan manusia. Dia ternyata<br />
berangkat dari sudut pandang etimologis (human atau<br />
homo = manusia dan isme = paham atau pandangan).<br />
Istilah humanisme ini merupakan terma yang hanya<br />
dikenal dalam diskursus filsafat, namun humanisme<br />
sebagai pandangan mengenai konsep dasar kemanusiaan<br />
dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti sains<br />
dan spiritualisme. Aku yakin Makku akan tertawa ketika<br />
membaca paragraf ini.<br />
“Baiklah Mak,” seakan akan aku sedang presentasi<br />
meyakinkan Makku, seperti ketika dulu aku minta jajan<br />
untuk beli lontong di sekolah. Akan Aku mulai dari sains<br />
247
dulu. Dalam diktum fisika Newton yang menyatakan<br />
”tiada fenomena yang tak dapat diukur dalam filsafat<br />
eksperimental”. Diktum ini melahirkan pandangan<br />
positivisme yang menekankan metode empirikaleksperimentatif<br />
dalam memahami realitas. Metode ini<br />
meniscayakan lahirnya paradigma reduksionismeatomistik<br />
yang menghasilkan pengerusan pada makna<br />
dan hakekat realitas. Secara sederhananya dalam tinjauan<br />
sains, memandang manusia tak lebih dari fakta empirikal<br />
(nomotetis) dan bersifat mekanistik-deterministik serta<br />
mereduksi manusia dari hal-hal non empiris, seperti nilai<br />
dan kesadaran. Konstruksi manusia dalam pandangan<br />
saintifik ini mencapai titik ekstrimnya dalam pandangan<br />
Julien O de Lametrie yang menyamakan manusia dengan<br />
mesin (L’Homme machine). Menulis paragraf ini aku<br />
berhayal jadi Bapak Abdulah Guru SD ku yang<br />
kharismatik tetapi bersarang TBC di tubuhnya.<br />
Mak. ini adalah suatu kondisi akibat<br />
perkembangan teknologi menghasilkan pergeseran<br />
mendasar dari human thought kepada thinking of machine<br />
yang mengakibatkan manusia tergeser dari pusat<br />
peradaban hingga ke “margin-margin” peradaban. Nah,<br />
248
kalau menurut Filsafat Humanisme ini mendasarkan<br />
dirinya pada akal sebagai realitas sublim pada diri<br />
manusia, sederhananya filosofis memandang manusia<br />
tidak hanya sebatas realitas material belaka yang statis<br />
dan determinis, melainkan juga sebagai realitas ideografis<br />
yang memiliki persepsidan kesadaran yang bersifat<br />
dinamis.<br />
Kalau menurut filsafat humanis ini kemudian<br />
membagi eksistensi manusia secara bidimensional, yaitu<br />
l’ etre ensoi (ada dalam diri) dan l’ etre pour soi (ada<br />
untuk diri), dengan akalnya, manusia berperan sebagai<br />
“lakus dunia” yang dapat mempersepsi, mengubah, serta<br />
memberi nilai dan makna pada dunia dan hidupnya. Jika<br />
kita menelusuri humanisme dari sudut pandang filsafat<br />
maka kita akan terbawa pada perdebatan panjang yang<br />
tiada henti mengenai nilai dan makna kehidupan<br />
manusia. Jika sains memandang manusia dari sisi<br />
matternya, filsafat memandang manusia dari sudut<br />
pandang mindnya, maka spiritualisme memandang<br />
manusia dari sudut pandang spirit (ruh)nya. Secara<br />
ontologis, spiritualisme mendasarkan pandangannya<br />
bahwa manusia selain memiliki dimensi eksoteris<br />
249
(tubuh), manusia juga memiliki sisi esoteris (ruh) yang<br />
bersifat ransenden dan Ilahiyah. Dua paragraf ini aku<br />
tulis seakan-akan Wak Wahitku yang pintar sekali<br />
mengajari tasawuf itu, mengintip di belakang telinggaku.<br />
Aku mendengar suaranya sayup-sayup.<br />
Mak. Terangku. Yang coba aku kerjakan itu<br />
berharap manusia berperan sebagai “lakus dunia” yang<br />
dapat mempersepsi, mengubah, serta memberi nilai dan<br />
makna pada dunia dan hidupnya secara aplikatif. Kami<br />
menyebutnya dengan istilah ‘Gerakan’, kadang-kadang<br />
kami lakukan dengan penekatan kasus, kadang kami juga<br />
melakukan dengan pendekatan politik tapi kami selalu<br />
kalah.<br />
Mak... ternyata wacana yang coba kami sampaikan<br />
terhegemoni secara masif oleh banyak kepentingan.<br />
Akupun menjelaskan makna Hegemoni kepada Makku.<br />
Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang<br />
dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang<br />
kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara<br />
institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan<br />
seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius<br />
250
dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial,<br />
khususnya dalam makna intelektual dan moral.<br />
“Mak. itu yang aku, anakmu baca dari<br />
pengagasanya Antonio Gramsci.” Jelasku. Untuk<br />
meyakinkan Makku akupun menjelaskan.<br />
“Atau secara sederhanya, hegemoni ini sebuah<br />
kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya<br />
mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui<br />
pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual.<br />
Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat<br />
tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas<br />
sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif<br />
mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan<br />
makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka<br />
pada struktur kekuasaan yang ada.”<br />
“Lalu apa hubungannya kemanusian dengan<br />
hegemoni ini?” Seakan-akan Makku bertanya.<br />
“Kali ini saya tidak akan berteori Mak,” Jawabku.<br />
ternyata upaya dalam menuju kemanusiaan dimana<br />
outputnya manusia itulah berperan sebagai “lakus dunia”<br />
yang dapat mempersepsi, mengubah, serta memberi nilai<br />
251
dan makna pada dunia dan hidupnya secara sukarela<br />
digerus atas banyak kepentingan.<br />
Ada kepentingan eksternal, ini untuk menyebutkan<br />
sesuatu diluar kami, dia adalah sistem globalisasi,<br />
liberalisasi dan sederet ideologi untuk mendehumanisasi<br />
yang namanya manusia, sementara dari internal kami<br />
banyak sekali kepentingan disana, jika mereka mau<br />
melakukan kerja-kerja humanisme itu mereka buat<br />
proposal. Aku tidak tahu dengan siapa saja.<br />
Sebagian lagi kami ribut-ribut ketika yang lain<br />
mendapat prioritas lebih untuk melakukan kerja-kerja<br />
humanisme ini, mereka saling klaim bahwa merekalah<br />
yang paling hebat, paling bisa menyelesaikan yang<br />
namanya humanisme tanpa menyebutkan indokatorindikator<br />
yang rinci, mereka rajin mengobral kata-kata<br />
‘pokoknya’, ‘hanya kita’, tentu saja mereka kemudian<br />
inclusif.<br />
Anehnya juga ada yang hobi nulis depan<br />
komputernya dan dijadikan status media jejaring<br />
sosialnya lantang berteriak soal humanisme tapi tetap saja<br />
tidak beranjak dari depan komputernya.<br />
252
Sejauh ini saya capek tapi tidak tahu harus berhenti<br />
kapan, dan sesadarnya hanya dua tangan dan dua kaki<br />
yang saya punya, tidak akan selesai olehku dan kami jika<br />
saja antara kami friksinya semakin tajam dan terjebak<br />
pada hegemoni oleh tangan yang tidak tampak yang nun<br />
jauh sana.<br />
Mak, aku selesaikan surat ini dulu sampai disini.<br />
Nanti akan aku tulis lagi curahan hati yang galau dan<br />
lemah ini, semoga doanya selalu tercurah untuk anakmu<br />
yang lemah ini.<br />
24<br />
Malam itu habis magrib, aku duduk di teras rumah<br />
sambil menikmati sisa senja, menikmati sulutan asap<br />
rokok dan tentu dengan segelas kopi. Bdikar anak<br />
tertuaku datang lalu duduk disampingku. “Sebei” ini<br />
untuk sebutan Neneknya, itu ibuku.<br />
253
“Kenapa Sebei tidak pernah marah, Pak?” tanyanya<br />
tiba-tiba.<br />
Aku tentu harus hati-hati menjawabnya<br />
pertanyaannya. Karena berurusan dengan ibuku, orang<br />
yang paling aku cintai sekaligus aku hormati.<br />
“Sebeimu seinggatku memang tidak pernah marah,<br />
tapi kalau Bapak buat salah sedikit saja, duduk dekat dia<br />
saja seperti kambing ketemu harimau, berat sekali kaki<br />
bapak untuk lari menjauh dari dia, meskipun tidak ada<br />
omelan yang keluar dari mulut tipisnya.” Jawabku<br />
seadanya<br />
“Nak, dulu ketika masih kecil bapak pernah buat<br />
tiga kesalahan dalam waktu yang hampir bersamaan, dia<br />
tidak marah Cuma tersenyum saja, dan sedikit kasih<br />
nasehat, setelah itu air mata bapak bercucuran” ceritaku.<br />
“Terus, kesalahan apa yang telah diperbuat<br />
bapak.?”<br />
“Dan reaksi Sebei bagaimana ketika itu,”<br />
Ini pertanyaan khas Bdikar, aku seperti di introgasi,<br />
matanya mulai fokus, mimik wajahnya mulai serius dan<br />
posisi duduknya mulai dekat ini pertanda dia sudah<br />
sangat siap mendengar cerita.<br />
254
“Dulu” aku mulai bercerita.<br />
Ketika itu umurku baru 10 tahun dan duduk di<br />
kelas 5 SD. Tepatnya di hari minggu bulan Agustus, tiga<br />
bulan menjelang musim panen padi. Waktu sedang<br />
banyaknya hama burung. Burung pipit (amandava<br />
amandava) spesies burung dari keluarga estrildidaer dari<br />
genus Amandava. Jadi, hari itu aku dapat jatah menjaga<br />
sawah. Sawah kami tidak jauh dari sawah Wakku. Wak<br />
Wahid, kakak tertua ibuku. Beliau ketika itu sedang<br />
semangatnya mengajar “Ilmu Kajian Dalam”. Kajian<br />
tasawuf Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Thariqah<br />
ini merupakan perpaduan dari dua buah tarekat besar,<br />
yaitu Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah<br />
yang didirikan oleh seorang Sufi Syaikh besar Masjid Al-<br />
Haram di Makkah al-Mukarramah bernama Syaikh<br />
Ahmad Khatib Ibn Abd.Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. inti<br />
pokok ajarannya adalah sama-sama menekankan<br />
pentingnya syari'at dan menentang faham Wihdatul<br />
Wujud, menuntun pada kesempurnaan suluk.<br />
Sebelum berangkat sambil menyiapkan bekalku<br />
untuk seharian ada tiga pesan ibuku, dia bilang begini<br />
255
“burung pipit biasanya datang menjelang sore, tepatnya<br />
menjelang Azhar nak.! Jadi jangan sampai lalai.”<br />
“Dan kalau mampir di sawah wakmu, jangan terlalu<br />
banyak tanya tentang Kajian tasawuf Thariqah Qadiriyah<br />
Naqsabandiyah, umur, otak dan pengetahuan agamamu<br />
masih dangal. Dan jangan bermain-main di anak sungai<br />
yang ada di dekat sawah karena anak sungai itu angker.!”<br />
Pesannya padat dan sangat jelas. Aku mengagguk lalu<br />
pergi kesawah.<br />
Sampai di sawah jam 9 pagi, aku lalu menyalan api<br />
dari batang pokok kayu yang sudah disiapkan ibuku<br />
beberapa hari lalu. Pagi lumayan cerah dan tidak tampak<br />
seekorpun burung yang datang. Aku mulai kepanasan. Di<br />
dinding pondok ada pancing, lalu aku menuju anak<br />
sungai yang tidak jauh dari sawah. Aku duduk di atas<br />
batang kayu yang sudah roboh, lalu mancing. Ikannya<br />
lumayan banyak, aku asik menaikan ikan mujair<br />
(oreochromis mossambicus) dari air dengan kailku. Pasti<br />
ibuku senang pikirmu, ada hasil tambahan selain laporan<br />
“pengusiran burung pipit”. Lamunanku berhenti ketika<br />
pancinganku tersangkut. Aku turun ke air, dan airnya<br />
256
terasa segar sekali. Aku mandi, dan baru sadar pesan<br />
ibuku setelah aku menggigil kedinginan.<br />
Dengan pakaian yang basah. Aku kembali ke<br />
pondok dari bambu yang dibangun dengan tangan<br />
Bapakku. Ikan hasil pancingan aku masukan ke dalam<br />
bakul, wadah dari bambu hasil ayaman ibuku. Hari mulai<br />
meninggi, tampak dari jauh Wakku sedang menunaikan<br />
Sholat Zuhur tepat di bawah pohon jambu depan<br />
pondoknya. Dia seakan-akan memangilku untuk kawan<br />
mengobrol. Pangilan itu begitu kuat masuk ke dalam<br />
alam pikiranku, wajah bersih dan senyum yang<br />
kharismatik itu menganggu sekali. Begitu dia selesai<br />
sholat, aku berlarian ke pondoknya yang memang tidak<br />
jauh dari Pondok sawah kami. Dia senang sekali ketika<br />
aku sampai di pondoknya, keluarlah ubi rebus, secara<br />
reflek aku langsung bergegas menyeduh kopi dengan<br />
gula aren.<br />
Kami duduk diteras pondoknya, angin sepoi-sepoi<br />
yang membawa aroma padi meniup wajah kami. Dia<br />
mulai cerita tentang ajaran Thariqah Qadiriyah<br />
Naqsabandiyah, karena semangat. Dia tidak sadar ketika<br />
itu umurku baru 8 tahun. Otak belakangku bagian kiri<br />
257
mulai sakit, tapi masih saja aku bertahan dengan<br />
penjelasannya. Sesekali aku bertanya di sela penjelasan<br />
untuk sesuatu yang membingungkanku. Tentu saja aku<br />
menikmati penjelasannya, kali ini sampai pada materi<br />
sifat 18 dari sifat 20 tentang berdirinya zat pada sifat.<br />
Tidak terasa sudah tiga jam berjalan. Penjelasannya<br />
berhenti. Dia harus menunaikan sholat Azhar. Aku<br />
langsung ingat pesan ibuku, bukankah menjelang Azhar<br />
pasukan Burung akan meng-agresi lalu meng-okupasi<br />
sawah kami, aku harus buat perlawanan untuk<br />
mempertahankan wilayah sawah kami.<br />
Sawah yang akan menghasilkan padi dua bulan<br />
mendatang, alat pital bagi pertahanan hidup keluarga<br />
kami. Begitu aku sampai di sawah, burung sudah<br />
berlarian tanpa aku usir. Terbang karena kekenyangan.<br />
Aku duduk di anak tangga, seperti tantara kalah perang,<br />
duduk dengan dagu yang menempel pada lutut. Aku<br />
menyesal, pertanahan hidup keluarga kami terancam<br />
untuk satu tahun kedepan. Dan terjadi dimulai dari<br />
kelalaianku menjaga pesan Ibuku, dan dilakukan secara<br />
runut dan sistematis pada hari yang sama pula.<br />
258
Menjelang Magrib aku baru pulang ke rumah,<br />
langkahku gontai dan lesu. Sampai dirumah ibu<br />
tersenyum, dia sepertinya mencium ketakutan dan<br />
kekalahanku atas agresi burung pipit, lalu dia bersihkan<br />
ikan mujair (oreochromis mossambicus) hasil<br />
pancinganku. Habis makan malam dengan lauk ikan<br />
mujair hasil pancingan dari sungai terlarang itu. Akupun<br />
belum berani untuk mengakui kesalahanku, mulutku<br />
seperti kena “tulah”. Seperti kena sepuluh bencana yang<br />
didatangkan oleh Tuhan atas bangsa Mesir. Aku tidak<br />
bisa berkata apapun seperti di jahit dengan ribuan mata<br />
pancing. Rasa bersalah itu membuat malam itu aku tidak<br />
bisa tidur.<br />
Menjelang Subuh ibuku bangun. Itu kebiasaanya<br />
yang aku tahu, selesai Sholat Subuh yang di imami oleh<br />
Bapakku, dia biasanya menyiapkan sarapan dan makan<br />
pagi buat kami sekeluarga. Aku yang biasanya paling<br />
disiplin menemani ibuku menyiapkan sarapan pagi kami.<br />
Pagi ini ada yang berbeda, bisanya hanya dengan<br />
nasi sisa sore kemaren yang disangarai hanya di campur<br />
dengan minyak jelantah dan garam. Pagi ini ada pisang<br />
yang akan di goreng. Pisang yang diberikan oleh Wakku,<br />
259
encananya memang aku yang bawa. Karena kelupaan<br />
akhirnya dia yang antar sendiri ke Ibuku. Dan, ketika dia<br />
ketemu ibuku, dia cerita banyak tentang kegiatanku di<br />
sawah sepanjang hari.<br />
“Kenapa pesan ibu di abaikan nak?” tanyanya<br />
lembut sambil memasukan pisang ke dalam kuali yang<br />
minyaknya mulai mendidih. Hatiku seperti pisang yang<br />
berenang di minyak panas. Wajahku mulai berkeringat,<br />
beban dikakiku mulai terasa berat. Akupun menjawab<br />
terbata-bata dengan sejuta alasan sambil menunjukkan<br />
senyuman yang tidak dari hati, penjelasanku kadangkadang<br />
terlalu cepat kadang terlalu lambat. Tentu, Ibuku<br />
langsung mendeteksi setiap kebohongan atas alasanalasanku.<br />
Bdikarpun tertawa mendengar ceritaku.<br />
“Tapi, bukankah dari dua hal, mancing dapat ikan<br />
dan belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itukan<br />
bagus?” Tanya Bdikar.<br />
“Ia,”<br />
“Itu positif sekali”<br />
“Dapat ikan dan dapat ilmu tapi dampaknya, sawah<br />
kami bisa gagal panen, mau makan apa kami selama satu<br />
260
tahun.” Jawabku dan air mataku belinang, bayangan<br />
ibuku sedang mengoreng pisang pagi itu masih saja<br />
melekat dipikiranku.<br />
“Nenek ngomong apa kemudian pak.?” Tanya<br />
Bdikar, sepertinya dia mulai penasaran mau mendengar<br />
apakah Neneknya pernah marah atau memang punya stok<br />
sabar yang berlimpah.<br />
“Pisang dalam pengorengannya dibolak balik.”<br />
lanjutku cerita.<br />
Begitu matang pisang dia angkat dan<br />
menghidangkannya untuk kami. Sambil membenarkan<br />
selendangnya berwarna merah dia bilang begini.<br />
“Nak, emosi-emosi negatif sulit ditutupi oleh<br />
banyak orang.” kata-katanya bersayap.<br />
Sebagian besar orang tidak begitu saja<br />
mengerakkan otot-otot tertentu yang diperlukan untuk<br />
menyembunyikan perasaan tertekan atau takut secara<br />
masuk akal. Dari senyumanmu, ibu sudah tahu bahwa<br />
kamu berbohong dan mengingkari pesanku, ibu tahu<br />
kamu berbohong sebelum Wakmu cerita kepada ibu.<br />
Gelagat ketidakjujuran atau kebocoran dapatlah ibu lihat<br />
dari perubahan ekspresi wajah, gerakan tubuh, perubahan<br />
261
pada suara, gerakan menelan ludah, tarikan napas, jedah<br />
panjang ketika mengucapkan kata-kata, selip lidah,<br />
eksperesi wajah mikro dan gerakan yang tidak disengaja.<br />
“Dari sore kemaren tanda-tanda itulah yang<br />
kemudian bercerita sehingga ibu tahu kamu telah buat<br />
salah.” Terangnya sambil membolak-balik pisang di<br />
pengorengan, penjelasannya rinci dan runut dengan suara<br />
lembut tapi berkharisma.<br />
“Jadi,” sambungnya.<br />
Tingkat kebohongan itu biasanya ditentukan dari<br />
hasil proses pendifinisian mereka mengenai diri mereka<br />
sendiri. Dari kombinasi gagasan bawaan dan pengaruh<br />
kental budaya dan lingkungan tempat tumbuh, hasilnya<br />
adalah kita memiliki keyakinan tentang sifat dasar<br />
termasuk kebohongan. Keyakinan itu masuk ketingkat<br />
sangat dalam pada sistem psikosomatis kita, pikiran dan<br />
otak kita, sistem syaraf, sistem endoktrin bahkan dalam<br />
darah dan otot kita. Jadi kita bertindak, berbicara dan<br />
berpikir atas dasar keyakinan kita tadi. Dia menjelaskan<br />
seperti dosen psikologis.<br />
“Berbohong itu nak,” lanjut ibuku.<br />
262
“Itu hanya untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan<br />
egosentris kita. Selama kita berbohong maka jangan<br />
pernah kita berharap kita bisa menbantu dan<br />
berkontribusi kepada orang lain.” Akupun belumlah lega<br />
atas rasa bersalah, tentu aku berjanji dengan diriku<br />
sendiri tidak akan mengulangi kebohongan atas<br />
ketidaktaatan atas pesan siapapun.<br />
“Mak.” Mataku berlinang, entah oleh sebab apa.<br />
“Hukumlah aku dengan hukuman apapun dan aku<br />
bersedia menerimanya” aku menyela meskipun aku<br />
sudah tahu tidak akan ada hukuman buatku.<br />
“Tidak nak.” jawabnya lembut.<br />
“Bagi ibu kalianlah segalanya.”<br />
“tetapi lain kali, belajarlah melakukan tindakan<br />
rekonsiliasi eudaemonisme. Kamu boleh dan tentu saja<br />
punya hak untuk melakukan keinginanmu mungkin itu<br />
akan bertentangan dengan kepuasan orang lain, tapi kamu<br />
harus memilih di antara keinginan yang kamu usahakan<br />
untuk dipenuhi dan berusaha mendamaikannya dengan<br />
keinginan orang lain.”<br />
263
“Pada posisi ini mungkin saja akan lahir<br />
keselarasan.” Kataya bijak, lalu berhenti sambil<br />
mengangkat pisang yang sudah matang dari pengorengan.<br />
“Pada titik ini keselarasan bisalah sebut dengan<br />
etika, yang merupakan bentuk sarana dibanding sebagai<br />
tujuan akhir.” Kata-kata ini menyentuh sekaligus<br />
mengugah hatiku.<br />
“Etika yang ibu maksud ini memiliki nilai derivatif<br />
atau instrumental ketimbang nilai intrinsik atau final,”<br />
“Secara rasional tidak dapat dibangun hanya<br />
berdasar atas apa yang “seharusnya” diinginkan<br />
melainkan atas apa yang kita inginkan” sambungnya<br />
menjelaskan sambil mendinginkan gorengan dan tentu<br />
akan diberikan untukku yang telah berbuat salah. Pisang<br />
sudah dingin, setelah kukunyah susah sekali pisang<br />
goreng ini melewati tenggorokanku.<br />
“Apakah Bapak kemudian di hukum oleh Sebei.?”<br />
Tanya Bdikar memotong ceritaku, sepertinya dia mau<br />
mendengar cerita betapa menderitanya aku ketika<br />
mendapat hukuman.<br />
Aku kembali menyulutkan rokokku yang hanya<br />
tinggal sebatang. Aku hisap dalam-dalam. Bayangan<br />
264
ibuku ketika itu masih tetap menempel di alam pikiranku.<br />
Mataku kembali berlinang entah oleh sebab apa.<br />
“Tentu saja ada hukuman dari Sebeimu untuk<br />
Bapak nak. Sampai sekarang Bapak sedang menjalankan<br />
hukuman itu.!” Jawabku.<br />
Dan Bdikar bertambang bingung.<br />
“Hukumannya adalah menemukan bentuk secara<br />
sungguh-sungguh untuk melakukan “rekonsiliasi” antara<br />
egoisme dan altruisme dan setidaknya untuk setiap apa,<br />
saja termasuk efeksi, yang sebagian besarnya haruslah<br />
dipengaruhi asumsi ini”. Jelasku.<br />
“Intinya nak, janganlah meminta atau<br />
mengharapkan kepada orang lain untuk berbuat pada kita<br />
lebih daripada yang akan kita inginkan untuk dilakukan<br />
oleh orang lain, atau terimalah orang lain hanya sebesar<br />
ekspektasi yang ingin kita berikan kepada mereka jika<br />
kita berada dalam posisi mereka.” Tambahku.<br />
“Maksudnya apa itu pak.?” Tanya Bdikar.<br />
Aku binggung dengan cara menjelaskannya kepada<br />
Bdikar, umurnya baru 10 tahun. Aku terpaksa telepon<br />
ibuku di kampung. Aura suaranya di ponselku membuat<br />
aku ingin menangis. Aku lalu cerita tentang obrolanku<br />
265
dengan Cucunya tentang kesalahanku 27 tahun lalu. Dia<br />
tertawa, dan memberi jawaban pertanyaan Cucunya.<br />
“Sebeimu tadi bilang begini nak, jika ada dua orang<br />
dan terjadi konflik, kalau memakai prinsif yang diajari<br />
Sebeimu itu. Masing-masing harus mempertimbangkan<br />
kepentingan keduanya, niscaya mereka akan secara<br />
niscaya bertindak dalam keselarasan, keselarasan ini<br />
merupakan sikap yang terdapat dalam keharmonisan,<br />
mutualisme yang meluas menjadi sentimen atau prinsip<br />
keadilan.”<br />
“Untuk itu berbuatlah adil,” Aku menirukan ibuku.<br />
“Bayangkanlah ketika kita berada pada posisi<br />
mereka. Tugas kita memberikan ruang bagi mereka untuk<br />
memperbaiki diri, memaafkan dan sekaligus<br />
memperbaiki diri kita.” Penjelasankupun berhenti.<br />
Ibunya Bdikar keluar dan memberikan perintah<br />
kepada kami bahwa waktunya makan malam tiba.<br />
Kami berlarian menuju meja makan. Menu<br />
utamanya kami malam ini adalah ikan mujair<br />
(oreochromis mossambicus) goreng. Ini persis menu<br />
makan malamku 27 tahun silam.<br />
266
Mudah-mudahan tidak ada kesalahan yang aku<br />
perbuat siang tadi.<br />
267
25<br />
Sore itu setelah seharian bacaan The Old Man and<br />
The Sea. Aku bergegas keluar menuju teras. Duduk, lalu<br />
menyulut rokok. Tidak lama kemudian lewat Pak Imam<br />
Masjid RT kami. Dia tertatih-tatih berjalan menuju<br />
Masjid. Teriakan keras azan ini memaksa dia buru-buru.<br />
Tidak peduli dia dengan kondisi kakinya yang pernah<br />
terserang struk 2 tahun lalu. Aku menjadi ingat dengan<br />
Wak Salim, Sepupu ibuku. Aku menyebutnya penjaga<br />
adat dan menguasai kearifan intelektual.<br />
Nama lengkapnya Salim Senawar, rambutnya mulai<br />
banyak yang ubanan, wajar saja umurnya sekarang<br />
sekitar 65 tahun, tetapi tatapan matanya tetap tajam,<br />
berjenggot, wajahnya bersih dan bersinar, gerak tubuhnya<br />
lentur karena memang dia ahli dan guru silat. Daya tahan<br />
tubuhnya luar biasa, tahan dia berdiskusi sampai<br />
menjelang subuh.<br />
Diskusi tentang apa saja. Apalagi kalau dilakukan<br />
dengan pola dialog, maka keluarlah dari mulutnya yang<br />
tidak bisa lepas dari rokok, tentang adat, sejarah adat,<br />
tentu sangat lengkap dan rinci dia jelaskan penomena-<br />
268
penomena adat di berbagai generasi. Begitu juga dengan<br />
diskusi tentang agama, bahkan tentang kajian “dalam”,<br />
kajian-kajian tasawuf dilahapnya habis, dia mampu<br />
mendekontruksi ayat-ayat dalam Al Quran dengan<br />
penomena-penomena bumi, mampulah dia berdikusi<br />
tentang perkembangan politik mutakhir, sangup dia<br />
keluar dari cara pandang politik mainstream, lalu dia baca<br />
persoalan politik dengan sangat jernih dan arif. Inilah<br />
gambaran Pak Salim Senawar yang berjengot yang<br />
memilih tinggal di kampung tua Topos, ketika beberapa<br />
kali aku bertandang kerumah tua tempat dia<br />
menghabiskan sisa hidupnya.<br />
“Kadang-kadang kita ini seperti daun salam saja,<br />
dibutuhkan dan dicari-cari ketika akan masak, lalu<br />
dibuang dan menjadi sampah ketika masakan tersebut<br />
matang.” Katanya memulai obrolan kami di teras<br />
rumahnya di suatu ketika. Adat hanya dibutuhkan untuk<br />
kebutuhan seremonial, masyarakatnya hanya dibutuhkan<br />
ketika pemilu, pilpres dan pemilukada lanjut Pak Salim<br />
sambil meyuguhkan kopi dengan cangkir dari alumanium<br />
yang mulai karatan.<br />
269
“Hasilnya tentu saja kekacauan sosiologis, tidak<br />
ada yang mampu mereduksi kekacauan ini selain adat<br />
yang benar-benar adat.” Lanjut dia berteori.<br />
Pak Salim menjelaskan adat sejati adalah adat<br />
peninggalan nenek moyang atau leluhur yang sering<br />
dikatakan tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang karena<br />
panas.<br />
“Intinya adalah adat yang memahat sepanjang<br />
garis, bertarah di dalam sifat, bertanam di dalam pagar,<br />
berjalan di hati jalan dan berkata dalam adat.” Terang dia.<br />
Lalu, ada adat yang diadatkan adalah adat<br />
tambahan pada sejati adat baik yang merupakan suatu<br />
peraturan dari Tuai Kutai yang merupakan hasil<br />
kesepakatan dan musyawarah dalam Kutai maupun<br />
kebiasan tertentu yang sudah menjadi adat yang teradat,<br />
seperti berbagi sama banyak, bermuka sama terang dan<br />
bertanak di dalam periuk, bersumpah bersemanyo,<br />
berjanji bersetio dan yang terpenting adalah kalah adat<br />
karena janji. Pak Salim mampu menjelaskannya secara<br />
runut.<br />
Dengan arif dia bercerita tentang kondisi kekinian,<br />
bahwa di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan<br />
270
krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis<br />
ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di banyak tempat,<br />
dia berpendapat kekuatan adat harus terus dipelihara<br />
untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya, kearifan<br />
menyelesaikan konflik dan pertikaian melalui pendekatan<br />
kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat luhur. Salah<br />
satu bentuk kearifan budaya itu berupa tradisi<br />
mempergunakan media tepung tawar dalam meresolusi<br />
konflik, katanya dengan menurunkan intonasi suaranta.<br />
Apabila ada konflik, kekerasan yang saling melukai satu<br />
sama lain, dengan menggunakan tradisi tepung tawar itu,<br />
diantara orang yang bertikai dapat saling berdamai dan<br />
akur kembali.<br />
Sambil menghisap rokok dari daun nipahnya<br />
kemudian dia menceritakan pengalamanya melakukan<br />
damai “tepung tawar”; dulu ada konflik antara pemuda<br />
desa dengan pemuda tetangga desa sebelahnya saat acara<br />
pesta pernikahan. Kedua pemuda itu sudah saling<br />
melukai walaupun belum ada yang terbunuh. Konflik<br />
antar kedua pemuda itu sudah berkembang aromanya ke<br />
arah konflik antar komunitas adat dalam satu Marga.<br />
Namun tokoh adat setempat segera berinisiatif menemui<br />
271
sang keluarga yang bertikai untuk mencari kebenaran asal<br />
usul dan penyebab pertikaian. Setelah diketemukan<br />
dengan tokoh adat dari pihak yang bersalah itu kemudian<br />
mendatangi keluarga pihak yang bertikai lainnya sambil<br />
membawa “iben/sirih” yakni sebagai alat atau sarana<br />
yang harus dibawah kepada keluarga korban atau yang<br />
tidak bersalah dalam konflik itu, di dalamnya<br />
seperangkah sirih lengkap dan sebungkus rokok.<br />
Sirih atau iben itu sebagai bentuk ungkapan<br />
penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga<br />
korban. Kalau sudah ada iben dibawa, biasanya keluarga<br />
korban merasa puas dan dihormati, lalu langsung<br />
menerima ungkapan maaf dengan lapang dada tanpa ada<br />
perasaan dendam. Usai pemberian iben, kemudian<br />
dilanjutkan dengan tradisi tepung tawar dan makan<br />
serawo atau punjung mentah, pemuda atau orang yang<br />
saling bertikai itu kemudian saling mengoleskan tepung<br />
tawar di badannya. Sesudah itu, maka kedua pemuda<br />
yang bertikai tadi sudah dianggap menjadi bagian dari<br />
saudaranya sendiri. Usai melakukan tradisi punjung<br />
mentah dan tepung tawar, konflik yang sudah makin<br />
memanas itu kemudian menjadi reda, ungkap Bapak<br />
272
Salim. Ia sendiri sebagai pemangku adat cukup sering<br />
menjadi ‘duta’ perdamaian dan melakukan tradisi lokal<br />
semacam itu.<br />
“Kalau semua konflik harus diselesaikan secara<br />
hukum, nyatanya makin repot dan cenderung<br />
menimbulkan konfliknya turunan, selain karena aparat<br />
negara lambat, butuh ongkos yang lebih dan masyarakat<br />
juga kurang puas, hasilnya jauh lebih ampuh dengan<br />
pendekatan adat atau budaya lokal, media tepung tawar<br />
ini tidak hanya berlaku bagi komunitas yang seidentitas<br />
budaya saja, tapi juga dapat dilakukan oleh orang luar<br />
yang kebetulan sedang berselisih paham atau berkonflik<br />
dengan orang adat.” lanjut Pak Salim sambil menghisap<br />
rokok daun nipah kesukaanya.<br />
“Adat itu dinamis, adat itu lahir dari kesepakatan<br />
pat sepakat lemo sempurno, empat pihak yang bersepakat<br />
dengan cara musyawarah dan menjadi sempurna ketika<br />
kesepakatan itu menjadi komitmen.” Seperti biasa dia<br />
mulai dengan statement provokatif memancing<br />
pertanyaan kritis.<br />
Makanya untuk beberapa kasus, adat bisa<br />
berkompromi dengan agama, dengan perkembangan<br />
273
umat manusia, itulah hakekatnya adat yang tidak lekang<br />
karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Kalimat ini<br />
biasa disampaikannya kepada orang-orang yang<br />
bertandang kerumahnya. Dia percaya sejak dari Masa<br />
Makedum Rajo Diwo (asal titik nol adat atau zaman mula<br />
jadi) sampai zaman milenium, adat itu akan tetap dan<br />
selalu hidup, adat akan berkelit dinamis dan pada<br />
akhirnya akan survive.<br />
Dengan komitmen yang kuat dalam menjaga adat,<br />
Pak Salim yang berjengot ini sering bersyair dan<br />
mengutip bait-bait Sambei Siyen Kutai “Ape disurat oleh<br />
aur; tiran ulung layang putiak, ado disano, tiran ulung<br />
pandai membace, layang putiak pandai menyurat, laju<br />
bepesan burung tiran ulung, amun cikundu ngadap<br />
keteluk, besok kundu sare tangungan, kundu menengah<br />
jarang balik, patah kundu hilang di ratau (apa yang<br />
tersurat pada bambu; tiran/burung hitam dan tiran putih,<br />
ada disana, burung hitam pandai membaca, burung putih<br />
pandai menulis, berpesanlah burung/tiran hitam, kalaulah<br />
pemalu menghadaplah ke sudut, tinggilah<br />
semangat/harapan besarlah tangungan, semangat<br />
setengah-setengah jaranglah pulang, patah semangat<br />
274
hilang di rantau). Inilah pedoman dan gambaran atas<br />
berkomitmen ketika kita bertekat untuk menjaga,<br />
berkomitmen dan berjuang untuk adat.<br />
“Seperti mengenggam sembilu, gengaman kita<br />
harus sekuat mungkin, kalau ragu-ragu tangan kita yang<br />
akan luka dan berdarah karenanya.” Nasehatnya kepada<br />
para pemuda yang belajar pengetahuan tentang adat<br />
dengan dia.<br />
Badanya gemetaran, lalu berkeringat kemudian<br />
urat-urat ditubuhnya berkelipan seperti digerakan oleh<br />
seribu jampi, seperti digerakan oleh arwah leluhur ketika<br />
mendengar kecurangan. Apalagi ketika dia mendengar<br />
ada pihak yang mendegradasi nilai-nilai dalam adat.<br />
“Kita”, katanya dengan meninggikan intonasi<br />
suaranya.<br />
“Janganlah seperti abung cerite lamun jauh,<br />
besaklah ikan lamun luput, ayam betabang senimar<br />
elang, ikan dipangang tingal tulang, igak berigak padi<br />
masak, igak beragam badan tue, igak bedindang biduk<br />
anyut,” inilah gambaran hidup yang sia-sia, menyiayiakan<br />
waktu, menyia-yiakan usia, hidup tidak membawa<br />
manfaat, manfaat buat dirinya dan bermanfaat untuk<br />
275
orang lain. Jelasnya dengan intonasi suara yang kuat<br />
tetapi bijak.<br />
Dia berpandangan secara konsisten dalam melihat<br />
penomena adat. Bahwa sistem sosial-budaya yang ada<br />
dalam adat menciptakan resource yang sifatnya sangat<br />
umum, yaitu makna, makna yang ditata oleh kedua<br />
subsistem fungsional sehingga bisa sampai pada level<br />
kinerja ekonomi dan politik yang diinginkan, lalu dia<br />
menyederhanakan, atas kondisi ini inputnya adalah<br />
reproduksi simbol kehidupan mengikuti logika nonfungsional.<br />
Dia sering mencontohkan norma dan hukum<br />
adat harus mengikuti standar internal tertentu, konsistensi<br />
logis dan kesatuan prosedural, pada hal adat ada di<br />
baliknya. Lalu, adat itu didistorsi, hanya simbol-simbol<br />
saja yang naik ke permukaan. Hak atas berhukum, hak<br />
berorganisasi lewat lembago adat, hak atas taneak tanai<br />
dan imbo piadan atau wilayah dan hutan di abaikan<br />
secara masif. Seringlah dia menganalogikan hukum dan<br />
lembaga adat seperti kapal yang kehilangan dermaga.<br />
“Adat dalam keadaan krisis” katanya.<br />
Hanya kekuatan objektif yang bisa menyebuhkan<br />
adat dari krisis, adat harus dibebaskan dari<br />
276
keterperangkapan krisis. Pembebasan ini menurut dia,<br />
tidak hanya bersifat memaksa dari luar, tetapi juga<br />
memaksa dari dalam adat yang menjadikannya terasing<br />
dari identitas dirinya.<br />
Cara berpikirnya runut dalam melihat dan<br />
menjelaskan penomena, mungkin ini disebut dengan<br />
kearifan intelektual. Dia tidaklah tamat sekolah dasar di<br />
zamannya.<br />
“Dari kecil saya biasa berada dibalik punggung tuatua<br />
kampung, ketika mereka bercelomok atau berdiskusi<br />
tentang makna hidup, saya sering mencuri-curi dengar<br />
dan beberapa kali dilibatkan dalam obrolan mereka.”<br />
Jelas dia dan matanyapun berlinang.<br />
Saat ini “ritual” bercelomok atau berdiskusi<br />
digantikan dengan ritual neorotik, orang lebih suka<br />
menonton televisi dibanding diskusi atas penomena yang<br />
ada. Curhat Pak Salim.<br />
Inilah akibatnya, lanjut Pak Salim “tiliklah tang<br />
desa ninik mamak disini, desa serut laman sunyi, desa<br />
digepung oleh betung, desa disindang oleh lalang, rumah<br />
berarik tiang serik satu idak tiang duduk, peratin kurang<br />
perite, sude digepung dengan ringgit, sude disindang<br />
277
dengan redai, bujang gadis kurang pengunyung.”<br />
Pemerintah kurang perintah, lalu prihatin tanpa kerja,<br />
pemerintah menikmati kepungan ringgit. Pemuda dan<br />
pemudi sibuk dengan urusannya sendiri, berharap<br />
diselamatkan dan percaya pada determinasi berbagai<br />
konstelasi bintang secara astrologis. Padahal katanya,<br />
Tuhan sudah berjanji tidak akan merubah nasib kita,<br />
sebelum kita berusaha merubahnya.<br />
Dia tentu saja prihatin, tetapi bekerja, dia juga yang<br />
mengumpulkan para pemuda di desannya. Maka saat itu<br />
lahirnya organisasi adat. Dia juga yang memperkenalkan<br />
nilai-nilai kearifan intelektual kepada para pemuda di<br />
akmpungnya. Pak Salim yang berjengot itu memulai<br />
metode pelajarannya melalui konsolidasi persepsi, lalu<br />
dia kuatkan pemahaman kongnitif, kemudian di bawa dan<br />
benturkan dua hal ini pada penomena dan konsesus sosial<br />
pada posisi inilah akan muncul bibit-bibit kearifan<br />
intelektual.<br />
“Bagi saya, semua orang itu hidup dizamannya,<br />
tidak boleh orang bermimpi atas kebesaran masa lalu,<br />
tidak boleh juga takut atas kesuraman masa depan.”<br />
Katanya bijak.<br />
278
Pilihannya cuma dua.<br />
“Rambai sayap terbang layang, pendek sayap<br />
terbang sayup.” Lanjutnya<br />
Meski mempunyai kelebihan kapasitas, tetap saja<br />
dia tidak mau menonjolkan diri, dia selalu ada di Sap<br />
kedua kalau sholat berjamaah meskipun imam Masjid<br />
berguru sama dia tentang agama. Dia selalu bicara<br />
terakhir ketika ada musyawarah adat dikampungnya.<br />
Dia “ia” kan pendapat yang benar dan lurus, lalu di<br />
patahkan secara bijak pendapat yang dianggapnya salah,<br />
diplomasinya luar biasa dalam mematahkan pendapat<br />
orang lain.<br />
“Harus seperti yang tikus tidak boleh luka, dan<br />
kucing tidak boleh malu atau seperti menarik rambut<br />
dalam tepung, rambut tidak boleh putus dan tepung tidak<br />
boleh tumpah.” Sering dia jelaskan begitu.<br />
Ini ajaran yang sangat sulit sekali di lakukan<br />
ditengah krisis identitas dan konsolidasi subjektivisme.<br />
Pak Salim yang berjenggot, dia tetap konsisten<br />
menjadi piawang (penjaga) kampung dengan kelebihan<br />
yang dimilikinya jarang ada yang berani “berhadaphadapan”<br />
dengan dia. Pernah beberapa kali dia marah,<br />
279
dia pernah mengembalikan bantuan seperangkat alat<br />
kesenian adat dari Pemerintahan Kabupaten, dia<br />
tersinggung karena sebelumnya syarat bantuan itu cukup<br />
rumit dan pelik.<br />
“Saya suruh mereka bawa kembali alat-alat<br />
kesenian yang mereka dibawa, cukup banyak ada dua<br />
truk, pertama kami sudah punya alat yang sama<br />
pengadaannya secara swadaya oleh masyarakat kampung,<br />
kedua saya tidak mau diperalat mereka.” cerita Pak Salim<br />
sambil tertawa dan tampaklah gigi-giginya yang<br />
menghitam akibat nikotin rokok. Dan bayangan Pak<br />
Salim menmbuat aku rindu pulang. Pulang ke kampung<br />
dimana darah pertamaku tumpah. Dimana ari-ariku<br />
dihanyutkan. Kampung yang membentuk tubuh dan<br />
pikiranku.<br />
280
26<br />
Hari ini ada acara wisuda di salah satu universitas<br />
yang ada di kampungku. Rame-ramelah orang dari<br />
kampung yang datang. Pak Salim Senawar salah satunya,<br />
karena yang berwisuda masih ada hubungan dengan dia.<br />
Dia pemabuk. Dia tidak datang dengan mobil bersama<br />
rombongan keluarga yang berwisuda, dia sengaja naik<br />
sepeda motor bersama kakak iparku orang Batak<br />
bermarga Sitompul.<br />
Malam ini Pak Salim Senawar datang berkunjung<br />
kerumah kami. Berbaju koko putih, celana dari sarung<br />
dan peci hitam yang mulai koyak warnanya. Kami<br />
mengobrol di ruang tamu. Tidak duduk di kursi, tapi<br />
duduk di lantai. Dia kepanasan. Cuma kami bertiga di<br />
ruang tamu. Aku, Pak Salim dan kakak Iparku orang<br />
Batak bermarga Sitompul. Di kampung kalau tidak ke<br />
kebun. Dia selalu berdua dengan Pak Salim. Pak Salim<br />
ini terhitung mertua Sitompul. Tetapi mereka sangat<br />
akrab, seperti anak dan Bapak.<br />
Pak Salim lalu menanyakan seputar aktivitasku.<br />
Perkembangan politik di kotaku, Lalu obrolan kami<br />
281
mengarah pada seputaran adat. Hukum adat. Dia juga<br />
ceritakakan padaku, yang diwisuda itu jurusan Hukum<br />
dan ketika dia menyaksikan proses wisuda, ketemu<br />
dengan salah seorang dosen hukum yang pernah lama<br />
penelitian di rumahnya.<br />
“Hukum adat itu seperti kapal yang kehilangan<br />
dermaga, tidak ada tempat untuk melempar sauh, lalu di<br />
ayun-ayun oleh gelombang.” Dia mulai memancing.<br />
“Tidak akan sampai tengelam tapi hancur dan<br />
berkeping-keping.” Katanya aku mengangguk.<br />
Padahal menurut dia, hukum adat ini hidup dan<br />
berkembang lalu di masuk kedalam denyut hidup<br />
warganya.<br />
“Hukum adat tidak hanya mampu menciptakan<br />
keseimbangan sosiologis tetapi mampu menekan<br />
persoalan horizontal maupun vertikal yang terjadi pada<br />
warganya.” Pak Salim meyakinkanku.<br />
“Karena dinamis dalam berkembang, maka hukum<br />
adat mampu mengambarkan realitas lebih akurat, mampu<br />
mengikuti perubahan-perubahan sosial, konstalasi politik<br />
dan perubahan budaya bagi warganya” Katanya seperti<br />
Dosen Fakultas Hukum.<br />
282
Sitompul nampak tersenyum-senyum. Tersenyum<br />
menyindir seakan-akan mau kasih tahu bahwa dia sudah<br />
semengerti Pak Salim tentang Hukum Adat.<br />
Aku kemudian menjadi ingat dengan Eugene<br />
Ehrlich menyebutnya sebagai Living Law (hukum yang<br />
hidup). Sebagai hukum yang hidup, itulah substansi yang<br />
digambarkan dalam filosofi, tidak lapuk karena hujan dan<br />
tidak lekang karena panas dalam hukum adat.<br />
Sama dengan Pak Salim hukum adat menurutnya,<br />
kedinamisannya terkesan akomodatif dalam prakteknya.<br />
Misalnya, sangat akomodatif dengan hukum Agama<br />
bahkan terkesan kompromis dengan hukum Negara.<br />
“Tetapi secara substansi hukum, hukum adat ini<br />
tetap tegak berdiri.”<br />
“Dinamis maksudnya bisa menerima sesuatu diluar<br />
dirinya.” Kata Sitompul ikut berpendapat. Aku tahu<br />
belakangan ini Sitompul giat belajar dan mengali sistem<br />
adat Rejang. Katanya ada kedekatan dan kesamaan<br />
dengan Budaya asalnya. Budaya Batak. Paling tidak<br />
masyarakatnya sama-sama penunggu dataran tinggi<br />
Sumatera. Bagi orang Batak terangnya. Marga sama<br />
283
seperti yang ada di Rejang. Marga atau Tarombo penting<br />
untuk di cari dan diperjelas.<br />
Pernah satu kali dia mengajari cara dan notasi<br />
kelintang untuk mengiringi tari Kejai, tarian sakral milik<br />
suku Rejang. Yang diajarinya adalah pemilik sanggar<br />
adat di kabupaten tetanganya. Cerita Pak Salim. Pemilik<br />
sanggar bingung kesenian orang Rejang dimainkan oleh<br />
orang Batak bermarga Sitompul.<br />
“Orang Batak menyadari bahwa mereka adalah<br />
Dongan-Sabutuha, mereka berasal dari rahim yang sama.<br />
Baik secara matrilinial maupun patrilinial. “<br />
“Dan hukum adat memandu pencarian ini.”<br />
Katanya.<br />
“Adat didahulukan baru kemudian agama, dan<br />
syarak bahkan hukum negara yang harus<br />
dikemudiankan.” Katanya. Kami tersenyum. Pengetahuan<br />
lumayan berkembang.<br />
“Sekarang mari kita lihat seperti apa gambaran<br />
hukum adat, dalam hal ini hukum adat Rejang, mari kita<br />
sebut sebagai hukum adat Jang, hukum yang dianggap<br />
mampu menciptakan keseimbangan sosiologis yang<br />
sifatnya Living Law atau hukum yang hidup itu.”<br />
284
Sambung Sitompul bersemangat. Lalu dengan logat<br />
Batak dia menceritakan hasil pembelajarannya dengan<br />
“penjaga adat”. Salim Senawar ini, guru sekaligus<br />
mertuanya.<br />
“Sebagai outonomous social field.” Katanya,<br />
sepertinya dia juga mulai banyak membaca buku. Tibatiba<br />
dia menyebut istilah Inggris dengan pronunciation<br />
berlogat Bapak. Masyarakat Adat Jang adalah kesatuan<br />
kekeluargaan yang timbul dari system unilateral yang<br />
kebiasaanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja<br />
dengan system garis keturunannya yang partrinial. Dari<br />
pihak laki-laki. Dan, cara perkawinannya yang eksogami,<br />
sekalipun mereka berada di mana-mana. Dia<br />
menjelaskan. Pak Salim Merem melek takut salah sebut<br />
si Batak ini.<br />
“Kesatuan kelembagan outonomous social field<br />
disebut dengan Kutai,” Katanya<br />
Sebuah kesatuan Hukum masyarakat Adat asli Jang<br />
yang berdiri sendiri, genelogis dan tempat berdiamnya<br />
jurai-Jurai atau suku-suku. Kesatuan masyarakat komunal<br />
ini diikat dengan sistem hukum, hukum ini disebut degan<br />
Hukum adat Jang dalam bahasa lokal disebut dengan<br />
285
adat beak nyoa pinang. Aku mulai kagum dengan Kakak<br />
Iparku ini. Aku ingat betul ketika dia melamar kakak<br />
perempuanku. Dia belum bisa berbahasa Rejang. Mereka<br />
berbeda keyakinan. Atas nama cinta dia kemudian dia<br />
iklas masuk ke keyakinan kami. Aku menjadi saksi<br />
pernikahannya. Dia mualaf ketika itu. Dan akulah<br />
mengantar dia ke kuburan lelulurku. Tradisi kampungku<br />
ketika menerima keluarga baru lewat ikatan perkawinan.<br />
“Adat Beak nyoa pinang?” Tanyaku.<br />
“Ia.”<br />
“Isinya memuat norma yang tumbuh dan<br />
berkembang serta dipatuhi dan mengikat masyarakat adat<br />
Jang.” Dia selalu meyebut Jang, bukan Rejang. Jang itu<br />
nama lokal argumennya.<br />
“Didalamnya mengandung nilai-nilai kekeluargaan,<br />
gotong royong, musyawarah, mufakat, kepatutan, magis,<br />
religius, arif dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap<br />
permasalahan yang timbul di batas-batas wilayah hukum<br />
adat Jang.” Dia lancar sekali menjelaskannya. Tetapi dia<br />
masih mirip dengan Pak Salim.<br />
“Jadi begini.” Kata Pak Salim memotong, dia takut<br />
sang murid keceplosan.<br />
286
“Dalam prakteknya hukum adat adat beak nyoa<br />
pinang ini dilaksanakan oleh peradilan adat jang, ini alat<br />
atau yang bertugas menjalankan mekanisme penyelesaian<br />
sengketa”.<br />
“Prakteknya harus menciptakan keseimbangan dan<br />
mendorong memberikan daya koersif kepada warga<br />
supaya mau tunduk pada aturan yang hidup dalam<br />
masyarakat tersebut.” Dia berhenti sampai karena<br />
tembakau yang di bawa dari kampung jatuh. Aku hanya<br />
menjadi pendengar dan tuan rumah yang baik. Mereka<br />
semangat sekali mengajariku.<br />
Dalam prakteknya Kelpiak Ukum Adat dipakai<br />
sebagai acuan “beracara dan berdelik”. Isinya kumpulan<br />
dokumen yang berisikan tentang tata aturan penyelesaian<br />
sengketa adat termasuk sangsi dan denda atas perkara<br />
yang terjadi di satu kesatuan wilayah hukum adat Jang.<br />
Lanjut Pak Salim bijak.<br />
“Acuan yang dimaksud benar-benar acuan, sebagai<br />
referensi dan tidak boleh menjadi bahan keputusan<br />
dalam menyelesaikan kasus.” Sitompul memotong.<br />
Eksekutor pada praktek hukum adat jang ini<br />
disebut dengan hakim adat, jenang kutai.<br />
287
“Bahkan ada yang menyebutnya majelis kutai,”<br />
Lanjut dia mulai binggung.<br />
“Mereka ini adalah perangkat peradilan adat yang<br />
teridiri dari beberapa personal yang merupakan<br />
representatif dari struktur pemerintahan adat Jang dan<br />
memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan<br />
sistem tata aturan hukum adat.”<br />
Ada pepatah adat saleak cong udi bepapet, mu’eak<br />
kakane ade beripit kakea ne coa, bepatet bekenek<br />
bejenjang tu’un,“ Potongku. Aku mulai tidak sabar<br />
mengali tentang Hukum Adat ini. Di dalam hatiku<br />
bertanya-tanya sejauh mana, hukum yang sedang kami<br />
diskusikan ini kuat jika di hadapkan dengan pihak luar.<br />
Karena sepengatahuanku praktek hukum ini mampu<br />
menciptakan keseimbangan bukan keadilan.<br />
“Itu hanya kiasan saja” Kata Pak Salim<br />
“Sebagian dari kiasan berisikan nilai-nilai sebagai<br />
pegang pakai masyarakat adat Jang untuk pemulihan<br />
kondisi keseimbangan atas perselisihan atau<br />
persengketaan atau terjadinya perkara adat di dalam<br />
wilayah hukum adat Jang.”<br />
288
Dari penjelasan Pak Salim aku bisa mengambil<br />
kesimpulan, dan tentu saja aku tidak mau aku debatkan<br />
dengan dua tamuku ini, bahwa adat, atau hukum adat itu<br />
adalah sebuah mekanisme yang lahir dari sebuah<br />
kesepakatan.<br />
“Adat itu adalah kesepakatan.” Kataku. Lalu aku<br />
mencontohkan hubungan Pak Salim dengan Sitompul ini<br />
adalah hubungan Mertua dan Menantu. Adat<br />
komunikasinya harus melereng. Tetapi karena sudah<br />
sangat dekat kemudian bersepakat komunikasinya bisa<br />
melereng, mendaki dan mendatar. Maka itulah adat<br />
mereka berdua. Dan beda lagi jika Sitompul<br />
berkomunikasi dengan mertua dia selain Pak Salim.<br />
Terangku. Sitompul sepertinya kurang yakin.<br />
“Begini”<br />
“Kata-kata selengan-lengan dendo adeba iben<br />
desaghen sebenek-benek dendo adeba bangun mayo,<br />
denda paling ringan adalah sekapur sirih dan denda<br />
paling berat adalah bangun mayo, untuk denda dan sangsi<br />
menghilangkan nyawa orang.”<br />
“Ini acuan saja, hasil akhirnya adalah kesepakatan<br />
kedua belah pihak yang bersengketa” Terangku. Sitompul<br />
289
melirik dan melerengkan tubuhnya ke arah Pak Salim.<br />
Pertanda bendera putih dan meminta dikirim bala<br />
bantuan.<br />
“Lalu, pertanyaannya apakah diluar hukum adat,<br />
bisa disebut dengan hukum adat?” Akupun memancing.<br />
“Jika hukum itu dibuat atas dasar kesepakatan<br />
bersama oleh para pihak atau paling tidak lahir dari<br />
konsensus sosial, yang tujuannya adalah mendamaikan<br />
dan membuat keseimbangan sosiologis, bolehlah itu<br />
disebut dengan hukum adat.” Kata Pak Salim. Kali ini<br />
tidak ada bala bantuan untuk Sitompul.<br />
“Karena hukum adat ini tidaklah boleh diciptakan<br />
oleh suatu badan hukum dengan tujuan memberikan<br />
keuntungan dan merugikan pihak lain.” Lanjut Pak<br />
Salim. Dari alur pikirannya dia sebenarnya sedang<br />
menjelaskan bahwa membahas pluralisme hukum.<br />
Membahas hukum yang lain, termasuk di dalamnya<br />
adalah Hukum Adat tidak lain adalah melakukan kritik<br />
terhadap positivisme hukum.<br />
“Sederhananya,” Kataku. Positivisme hukum dapat<br />
dipahami sebagai sebuah teori hukum yang menyatakan<br />
bahwa hukum adalah yang dibuat oleh penguasa.<br />
290
Positivisme hukum dikritik karena dinilai gagal mencapai<br />
tujuan hukum, yang mencakup kepastian, keadilan dan<br />
kemanfaatan.<br />
“Kepastian, belum tentu memberikan keadilan atau<br />
kemanfaatan. Ada situasi tumpang tindih. Kepastian<br />
tercapai, apakah keadilan tercapai?”<br />
“Belum tentu,” Sitompul masih diam, sepertinya<br />
pelajaran dia belum sampai tahap ini.<br />
“Abang mesti belajar lagi.” Kataku. Dia tertawa<br />
sambil mengarut kepala dan tertunduk.<br />
“Lalu,”<br />
“Marilah kita kembali ke kondisi hukum adat yang<br />
ibarat perahu,”<br />
“Layarnya semakin miring dan ombak semakin<br />
kencang.” Tanyaku. Ini bentuk pertanyaan kritis kita atas<br />
kondisi yang ada. Aku menatap Sitompul.<br />
“Apakah kemudian ramalannya perahu itu akan<br />
hancur berkeping lalu terombang-ambing oleh<br />
gelombang? Karena kita tahu bahwa pada sisi lain<br />
terdapat sentralisme hukum (hukum positif) yang secara<br />
nyata dan menyakinkan merugikan hukum adat karena<br />
291
memberikan perbandingan yang salah terhadap kondisi<br />
kedua hukum yang cenderung berhadap-hadapan ini.”<br />
“Pada hal, pada saat yang bersamaan menunjukan<br />
bahwa hukum positif ini belum mampu menciptakan<br />
keadilan bahkan tidak terlalu mengikat masyarakat<br />
modern untuk taat dan tunduk pada sistem hukum ini.”<br />
“Belum lagi jika sisi lainnya terdapat hukum lain,<br />
hukum nasional dan hukum negara.”<br />
Sebagai bagian untuk mengkontruksi “dermaga”<br />
yang sudah hancur, maka kontek penerapan hukum adat,<br />
perluasan kajian ditengah pesatnya perubahan struktur<br />
sosial dan budaya masyarakat serta penetrasi global.<br />
“Bukankah kita tahu hukum mainsteram ada hukum<br />
negara dan internasional dibuat untuk melayani<br />
kebutuhan liberalisasi pasar?” aku memprovokasi.<br />
“Kalau demikian”<br />
“Hukum adat perlu direvitalisasi kembali dalam<br />
kontek yang lebih luas,”<br />
“Rekontruksi dermaga itu penting.” Kata Pak<br />
Salim.<br />
“Lalu dari mana mulai dari mana?’ Tanya<br />
Sitompul.<br />
292
Pertanyaannya membuat kami terdiam. Ada<br />
inisiatif yang telah dibangun. Ada model kompromis<br />
dibangun. Mengangakat kayu terendam, meminjam<br />
pepatah Minang adalah pekerjaan berat.<br />
Pak Salim kecapean. Tidak mau dia tidur di kamar<br />
tidur yang telah disiapkan oleh istriku. Dia lebih suka<br />
tidur dilantai ruang tamu.<br />
Mereka berdua lalu tidur, aku matikan lampu dan<br />
ku lihat dalam wajah mereka ada kerinduan di hati<br />
mereka pada adat sebagai ibu peradaban.<br />
Meminjam Gibran. Ibu merupakan kata tersejuk<br />
yang dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Dan “Ibuku”<br />
merupakan sebutan terindah. Kata yang semerbak cinta<br />
dan impian, manis dan syahdu yang memancar dari<br />
kedalaman jiwa.<br />
Tetapi aku masih diruangan ini. Ruangan rumahku.<br />
293
27<br />
Sore kemaren, aku antar istriku belanja untuk<br />
kebutuhan bulanan. Tempat belanjanya tidak ditempat<br />
biasa, di pasar yang sampahnya berserakan dan para<br />
pedagangnya sudah pasti tidak mandi selama 3 hari. Atau<br />
di warung tetangga dimana ibu-ibu biasanya bertukar<br />
informasi negatif tentang tetangganya.<br />
Kali ini kami belanja di sebuah super market<br />
terbesar dikotaku. Aku memanfaatkannya untuk jalanjalan<br />
dengan anakku. Aku berdua dengan Bdikar. Titon<br />
ikut ibunya. Aku seperti kena syndrom gagap urban,<br />
tulang terasa ngilu dan nyeri karena ruangannya berhawa<br />
dingin buatan.<br />
Susunan pajangan barang-barang tersusun rapi,<br />
tidak ada penjaga yang bisa diajak tawar menawar. Dan<br />
disalah satu sudut, terdapat pajangan lengkap alat<br />
elektronik. Tersedia juga harga tunai, juga harga kredit<br />
atau beli dengan cicilan, kalau tidak cukup duit kita bisa<br />
cicil, pilihan waktu angsurnya beragam.<br />
“Inilah skenario transaksi pasar pada kapitalisme<br />
mutakhir, kita dibuat tidak punya pilihan untuk masuk<br />
294
skenario pasar, kemudian terjebak dalam konsumerisme<br />
lalu membuat kita gagap?” Kataku ke Bdikar dengan<br />
nada emosi karena tidak mampu beli salah satu alat<br />
elektronik ini untuk kami.<br />
Ketika antrian di kasir, ada banyak orang<br />
sepertiku, sekedar gaya-gayaan karena hanya beli 2 botol<br />
minuman mineral, ada yang serius belanja yang<br />
‘mengunungkan’ troli yang mereka dorong.<br />
Sambil bercanda istriku bilang.<br />
“Inilah konsep kritis medis menuju konsep kritis<br />
secara dramaturgis,”<br />
“Ini proses titik balik yang tidak hanya memaksa<br />
dari luar, tetapi juga memaksa dari dalam diri yang<br />
menjadikannya terasing dari identitas pribadinya,”<br />
makanya kita kemudian tergagap-gapap katanya. Aku<br />
menganguk-anguk, sambil berbisik dengan istriku.<br />
“Kita ternyata dibatasi oleh ruang dan waktu,<br />
sehingga kelangsungan eksistensi kita sangat ditentukan<br />
oleh nilai-nilai tujuan yang rentan perubahannya, dapat<br />
ditoleransi dan ditakar, kita dipaksa untuk tetap tinggal di<br />
dalam sebuah lingkungan hiperkomplek.”<br />
295
“Dipaksa dengan cara melakukan perombakan<br />
terhadap unsur-unsur sistem, nilai-nilai tujuan atau<br />
keduanya sekaligus, tidak peduli apakah sistem baru<br />
tersebut mengandung kekacauan moral atau sistem<br />
tersebut berangkat dari perpecahan-perpecahan tradisi.”<br />
Bisikku.<br />
Ketika keluar dari kasir aku seperti kuntil anak,<br />
tidak menginjak bumi dan tidak tergantung ke langit,<br />
identitasku hilang, atau ini karena pengendalian yang<br />
tidak selesai.?<br />
Karena krisis identitas.<br />
Sambil mendorong sedikit hasil belanjaan, akupun<br />
berpikir, kondisi ini seperti anomali sebuah kesadaran<br />
atas kenyataan subyektif, berhubungan secara dialektis<br />
dengan masyarakat yang dibentuk oleh proses-proses<br />
sosial, lalu seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi<br />
dan kesinambungan historis.<br />
Beberapa bungkus hasil belanjaan aku gantungkan<br />
di motor yang setia mengantar kami sekeluarga. Aku<br />
suka motor. Kami keluar dari perantaran parkir, tentu saja<br />
harus bayar meskipun kami sudah menghabiskan<br />
beberapa rupiah di tepat ini, begitu habis bayar parkir,<br />
296
aku boleh keluar. Entah tiba-tiba aku ingat dengan Carl<br />
Gustav Jung, dia mengatakan bahwa keperibadian yang<br />
menempel dalam identitas itu terdiri dari tiga sistem yang<br />
terpisah tetapi saling berintraksi satu sama lain.<br />
Sistem itu adalah aku yang ego, ketidaksadaran<br />
pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Lalu apakah ini<br />
merupakan persona atau topeng yang dipakai pribadi<br />
sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan<br />
tradisi masyarakat, tuntutan tentang arketipenya sendiri,<br />
yang kemudian menciptakan kesan tertentu pada orang<br />
lain dan seringkali ia melupakan hakikat kepribadian<br />
sesungguhnya.<br />
Tiba-tiba anakku yang duduk dipangkuanku di<br />
depan minta dibelikan makan makanan cepat saji yang<br />
pemiliknya berjengot itu.<br />
Lalu aku melirik ke kiri kanan jalan. Dimana pecal<br />
lele, sate padang, tempoyak yang merupakan produk<br />
lokal dan bagian dari identitas diri, bisikku dalam hati.<br />
“Cari apa?” tanya istriku dari belakang.<br />
“Pecal lele, sate padang, atau gorengan” Jawabku.<br />
297
“Baiknya kita ucapkan selamat datang Global<br />
Village,” aku tahu maksudnya dia mendukung untuk<br />
dibelikan makanan sepat saji itu.<br />
“Kenapa?” Tanyaku.<br />
“Kita akan menjadi sebuah kesatuan dalam desa<br />
global ini. Konsekuensinya menghilangkan bagian dari<br />
identitas kita kemudian berlahan-lahan bermimikri<br />
supaya dapat diterima dalam komunitas global itu.”<br />
Jawabnya.<br />
Begitu sampai di rumah. Hasil belanjaan yang<br />
hanya beberapa jenis itu kami tumpahkan di atas meja<br />
makan kami.<br />
“Bermimikri boleh saja tapi harus atas kesadaran.”<br />
“Iya”<br />
“Sadar yang bagaimana?” Jawab istriku singkat.<br />
“Kesadaran itu ada dua, kesadaran kelas dan<br />
kesadaran palsu” Jawabku meniru Georg Lucas yang<br />
pengikut Marxisme Hegelian itu. Aku baca pendapat<br />
mereka beberapa tahun lalu.<br />
Kesadaran kelas mengacu pada system keyakinan<br />
yang dianut oleh orang yang menduduki posisi kelas<br />
yang sama, sedangkan kesadaran palsu adalah kelas-kelas<br />
298
dalam masyarakat kapitalis umumnya tidak menyadari<br />
kepentingan kelas mereka yang sebenarnya.<br />
“Kelas yang tidak tahu diri.” Jelasku sambil<br />
tertawa.<br />
“Jadi?” Tanya dia.<br />
“Kesadaran itu merupakan kondisi dimana kita<br />
memahami situsi dan kondisi watak masyarakat dimana<br />
kita hidup,”<br />
“Kesadaran adalah basis dari segala kehidupan dan<br />
ladang dari seluruh kemungkinan.”<br />
“Hakikatnya memperluas dan melipatgandakan<br />
potensi sepenuhnya?” Tanyanya.<br />
“Dengan demikian dorongan untuk berkembang<br />
melekat dalam hakekat kehidupan,” Jawabku. Kondisi<br />
berpikir logis tentang sesuatu yang terjadi dan kemudian<br />
direspon dengan tindakan melalui metode sistematis dan<br />
terukur, ketika kita ingin menuju perubahan.<br />
“Tentu saja perubahan itu tidak datang dengan tibatiba,”<br />
“Tidak datang dengan bim salabim, ia butuh proses<br />
rasional, pematangan system dan momentum tindakan,”<br />
299
“Artinya proses menuju perubahan ini butuh proses<br />
pembongkaran menyeluruh?” Tanyanya sambil<br />
menyimpan bungkusan minyak ke dalam lemari.<br />
“Betul”<br />
“Berpikir sistematis inilah yang disebut dengan<br />
kesadaran dimana akan menempatkan diri manusia sesuai<br />
dengan apa yang diyakininya,”.<br />
Kesadaran ini diungkapkan dengan refleksi, cikal<br />
bakal gagasan dan tindakan. Ketika kesadaran itu<br />
terhambat dan terjebak pada artikulasi dan pemaknaan<br />
diri, klaim diri paling hebat terjebak pada nilai-nilai<br />
subjectivisme yang sempit maka kesadaran itu belum<br />
terkelola dengan baik, kesadaran itu masih dalam taraf<br />
dirinya. Jelasku.<br />
Secara otomatis kita tidak mampu menyadarkan<br />
pihak lain diluar kita dengan kesadaran palsu.<br />
“Etre pour soi e” Kataku sambil membuka bungkus<br />
rokok yang juag dibelikan istriku ketika di kasir tadi.<br />
“Apa itu?”<br />
“Kesadaran berjarak, kesadaran kita terhadap<br />
sesuatu menyatakan adanya perbedaan antara kita dengan<br />
300
sesuatu, kita tidak sama dengan sesuatu yang kita sadari,<br />
ada jarak antara kita dengan object yang kita lihat,”<br />
“Misalnya?” Tanya dia lagi. Aku terdiam mencari<br />
jawaban yang tepat.<br />
“Jadi begini” aku mengambil jedah untuk<br />
menjawab.<br />
“Maka prasyarat utamanya adalah distansi,<br />
penandaan pada jarak.” Karena kesadaran adalah pondasi<br />
tindakan yang mengunakan media kewaspadaan, maka<br />
kesadaran ini muncul ketika subjek berhadapan dengan<br />
realitas ruang. Jelasku. Dia tidak begitu yakin dengan<br />
jawabanku. Kebiasanku selalu menjawab pertanyaanya<br />
yang berputar-putar.<br />
“Intinya gagasan, sikap dan aksi, yang diperoleh<br />
dari interaksi subject dengan object melalui panca indera<br />
terverifikasi melalui akal rasional, harus mengacu pada<br />
struktur yang sitematis pengetahuan.”<br />
“Pengetahuan?”<br />
“Ia, karena pengetahuan akan melahirkan konsep<br />
kecerdasan dan kematangan jiwa untuk menyeimbangi<br />
kecerdasan emosional yang merupakan pondasi<br />
rasionalisme,”<br />
301
“Oh,”<br />
“Kecerdasan ini bisa bisa memotivasi kondisi jiwa<br />
agar menjadi pribadi yang matang secara social<br />
berkenaan dengan eksistensinya sebagai entitas social,”<br />
“Wujudnya dalam bentuk kemampuan merasakan,<br />
memahami dan secara efektif menerapkan daya dan<br />
kepekaan emosi” Jelasku.<br />
“Aku mulai mengerti,” Kata dia sambil<br />
menuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah<br />
diisinya kopi tanpa gula.<br />
“Sebagai sumber energy yang menyulut kretivitas<br />
yang tentu saja mengarahkan manusia ke arah yang lebih<br />
baik.” Sambungnya sambil mengaduk kopi.<br />
“Kesadaran jiwa ini menyiratkan kesediaan<br />
manusia untuk memikul amanah, beban, kepedulian yang<br />
tidak diikuti oleh komitmen terhadap sikap mendua.”<br />
Aku menarik lebih dekat gelas kopi.<br />
Sumber utama konplik jiwa ini adalah kebodohan<br />
dalam mendifinisikan makna tindakan fisiologis, hawa<br />
nafsu, keinginan buta, ambisi atau sikap yang munafik,<br />
atau penghianatan.<br />
302
Wilayah kesadaran yang harus dikuasai agar bisa<br />
melakukan perubahan yang optimal, satu-satunya untuk<br />
mengubah secara permanen dunia luar kita adalah dengan<br />
mengubah dunia dalam kita.<br />
“Kita tidak melihat dunia seperti seharusnya, kita<br />
hanya melihat dunia seperti yang kita mau lihat,”<br />
“Kita hanya akan melihat berdasarkan keyakinan<br />
bukan kanyataan.” Lanjutku sambil minum kopi.<br />
Hanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan<br />
keyakinan yang mendominasi pikiran dan hati akan<br />
membuahkan hasil, keyakinan yang utuh hasil dari proses<br />
reflektif yang panjang dan teruji dilapangan akan<br />
melahirkan sebuah karakter yang nantinya menjadi<br />
cermin bagi pergerakan perubahan.<br />
Obrolan kami terhenti ketika anakku berlari keluar<br />
mendengar pangilan mamang penjual sate yang menjadi<br />
langanannya.<br />
“Mamang kenapa lama tidak jualan?” terdengar<br />
ananku bertanya.<br />
“Mamang sakit ya?<br />
“Tidak nak, kemaren kami pulang kampung” kata<br />
Mamang sate.<br />
303
“Dua bungkus ya mang”<br />
“Iya”<br />
“Kuahnya ditambah mang”<br />
“Iya,”<br />
“Kerupuknya juga”<br />
“Berapa Mang?”<br />
“Rp. 5.000”<br />
“Boleh kurang?”<br />
Kami tersenyum. Mamang sate penjelaskan bahanbahan<br />
sate sehingga harganya Rp. 5.000. kalau kurang<br />
volume satenya akan dikurangi juga. Mereka seperti tidak<br />
berjarak, mereka sadar ruang, sadar posisi dan tidak<br />
terleminasi dari produk dan kebutuhannya.<br />
304
305
Tentang penulis<br />
Erwin Basrin adalah Pegiat isue lingkungan, kerakyatan<br />
dan penulis lepas dan penikmat sastra yang berlatar<br />
belakang Pendidikan Teknik Sipil Univerasitas Ekasakti,<br />
Padang. Pemegang mandat Direktur Eksekutif Akar<br />
Foundation sejak tahun 2014, sebuah NGOs local di<br />
Bengkulu yang bergerak pada isue Masyarakat Adat,<br />
Kehutanan dan Tata Kelola Kekayaan Alam yang<br />
Demokratis dan Berkelanjutan. Menjadi pegiat Aktif dan<br />
pendamping Perhutanan Sosial, Reforma Agraria serta<br />
isue transparansi Industri Ekstractive di Bengkulu,<br />
Pendiri Pendidikan Alternatif dan Rumah Literasi “Mata<br />
Hati”, tahun 2003-2007 menjadi Sekretaris Jenderal<br />
Aliansi Masyarakat Adat Bengkulu (AMA Bengkulu)<br />
dan Dewan Nasional Masyarakat Adat Nusantara<br />
(DAMAN) Priode 2003-2004. Dan, sampai saat ini masih<br />
menikmati hidup menjadi Petani hutan dan sesekali<br />
menikmati tanaman bunga.<br />
306
307