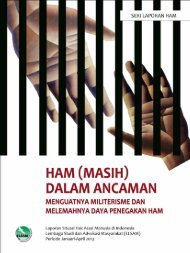2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAPORAN HAM<br />
TUTUP BUKU DENGAN<br />
“TRANSITIONAL JUSTICE”?<br />
MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-<strong>2004</strong> DAN MEMBUKA<br />
LEMBARAN BARU 2005<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />
JAKARTA, 2005
TUTUP BUKU DENGAN “TRANSITIONAL JUSTICE”?<br />
MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-<strong>2004</strong> DAN MEMBUKA LEMBARAN BARU 2005<br />
Januari 2005<br />
Tim Penulis:<br />
Ifdhal Kasim, SH<br />
Amirudin Arrahab<br />
Sentot Setyasiswanto<br />
Zaenal Abidin<br />
Diterbitkan oleh:<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (<strong>Elsam</strong>)<br />
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510<br />
Tel.: (021) 797-2662, 7919-2564<br />
Fax: (021) 7919-2519<br />
Email: elsam@nusa.or.id, advokasi@indosat.net.id<br />
Website: www.elsam.or.id
EXECUTIVE SUMMARY<br />
Laporan ini merupakan hasil pengamatan<br />
atau observasi Lembaga Studi dan<br />
Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas<br />
kewajiban negara (state obligation) dalam<br />
memajukan, melindungi, dan memenuhi hak<br />
asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih<br />
memang terbilang panjang, yakni mulai 1999<br />
hingga <strong>2004</strong>; sepanjang masa reformasi bergulir.<br />
Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa<br />
yang telah dicapai pada kurun itu, dan dari<br />
sinilah titik pijak untuk melihat prospek<br />
pemenuhan kewajiban negara pada babakan<br />
baru tahun 2005: apakah agenda penegakan hak<br />
asasi manusia yang telah dicanangkan, yakni<br />
agenda ‘transisional justice‘ sudah dicapai atau<br />
belum, apa yang perlu dilakukan selanjutnya?,<br />
atau kita telah melupakannya alias “tutup<br />
buku”?.<br />
Dalam rentang waktu sejak bergulirnya<br />
reformasi, 1999-<strong>2004</strong>, ELSAM mengamati<br />
pemenuhan kewajiban negara dalam hal<br />
pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak<br />
asasi manusia telah mengingkari konsensus<br />
‘Reformasi’, yakni mewujudkan ‘keadilan<br />
transisional’ (transitional justice). Keadilan<br />
transisional yang dimaksud di sini adalah,<br />
keberanian politik untuk sekali dan selamanya<br />
memutuskan rantai impunitas atas dasar suatu<br />
keadilan yang kontekstual yang didambakan<br />
rakyat, yaitu keadilan bagi si korban dan<br />
hukuman bagi si pelaku. Tekad politik untuk<br />
mewujudkan ‘transisional justice’ inilah yang<br />
praktisnya macet, khususnya terlihat dengan<br />
gamblang pada lembaran tahun <strong>2004</strong>. Yang<br />
terlihat cuma tindakan-tindakan setengah hati,<br />
retoris, dan berlindung di belakang tameng<br />
ketidakjelasan hukum positif yang berlaku.<br />
Hukum berubah menjadi tempat berdalih,<br />
bukannya jalan menuju keadilan.<br />
AWAL YANG MENJANJIKAN<br />
Di awal runtuhnya rezim otoriter-Soeharto<br />
(1965-1998) terlihat semangat yang besar untuk<br />
menerapkan ‘keadilan transisional’. Negara baru<br />
atau rezim transisi mencetuskan tekad politik<br />
dan komitmen untuk menyelesaikan<br />
pelanggaran berat hak asasi manusia di masa<br />
Orde Baru, dan meletakkan dasar bagi budaya<br />
penghormatan hak asasi manusia ke depan.<br />
Tekad politik dan komitmen tersebut terlihat<br />
dari, antara lain, penyelidikan pelanggaran hak<br />
asasi manusia Mei 1998, bumi-hangus Timor-<br />
Timur pasca jajak-pendapat, dan kekerasan<br />
masa DOM Aceh; amandemen konstitusi<br />
bermuatan hak asasi manusia; produksi regulasi<br />
dan ratifikasi instrumen-instrumen perlindungan<br />
hak asasi manusia; reformasi institusiinstitusi<br />
yang selama Orde Baru terlibat dalam<br />
pelanggaran hak asasi manusia (seperti polisi,<br />
intelijen negara, dan TNI); dan menghadirkan<br />
pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia,<br />
yang diharapkan dapat mencegah keberulangan<br />
pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.<br />
Pemaparan di atas kongkritnya dapat dilihat<br />
dari produksi kebijakan di sepanjang tahun<br />
1998-2000. Kita mulai dari Ketetapan MPR,<br />
yaitu mulai dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/<br />
1998 tentang Hak Asasi Manusia; TAP MPR<br />
Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar<br />
Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2000; TAP<br />
MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan<br />
Persatuan dan Kesatuan Nasional; TAP MPR<br />
iii
Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan<br />
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian<br />
Negara Republik Indonesia; serta TAP MPR<br />
Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan<br />
Polri. Pada kurun waktu ini pula MPR telah<br />
melakukan amandemen kedua UUD 1945, yang<br />
di antaranya memasukkan hak asasi manusia<br />
sebagai hak konstitusional. Secara garis besar<br />
dari ketetapan-ketetapan MPR tersebut dapat<br />
disimpulkan, yang menjadi arah (agenda)<br />
penegakan hak asasi manusia nasional di masa<br />
Reformasi saat ini adalah, (i) penyelesaian<br />
pelanggaran hak asasi manusia masa lalu;<br />
(ii)pembuatan regulasi tentang jaminan perlindungan<br />
dan penghormatan hak asasi manusia;<br />
dan (iii) reformasi institusi-institusi kehakiman<br />
(polisi, kejaksaan, dan pengadilan) dan institusi<br />
keamanan (TNI, Polri dan Intelijen Negara);<br />
dan penghukuman pelaku dan pemulihan para<br />
korban pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Di tingkat Undang-undang, selama kurun<br />
waktu tersebut, kita saksikan terbit berbagai<br />
perundangan-undangan yang menjamin perlindungan<br />
dan penghormatan hak asasi manusia.<br />
Di antaranaya UU No 39/1999 tentang Hak<br />
Asasi Manusia dan UU No 26/2000 tentang<br />
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setelah kedua<br />
UU ini Pemerintah dan DPR RI belum<br />
memproduksi regulasi lainnya. Baru di akhir<br />
masa jabatannya, Pemerintah dan DPR<br />
mengesahkan UU No 27/<strong>2004</strong> tentang Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara<br />
untuk penghapusan peraturan perundangundangan<br />
yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia, ELSAM mencatat pencabutan<br />
terhadap TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang<br />
Referendum, UU No 5 Tahun 1985 tentang Referendum,<br />
dan UU No 11/PNPS/1963 tentang<br />
Subversi; dan beberapa Keppres dan Inpres yang<br />
membatasi hak-hak masyarakat sebagai warga<br />
negara. Tetapi di lain pihak, pemerintah juga<br />
memproduksi regulasi yang mengukuhkan<br />
peraturan yang melanggar HAM di antaranya<br />
UU No 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang<br />
berkaitan dengan Keamanan Negara, yang tetap<br />
mempertahankan pelarangan terhadap<br />
penyebaran paham Marxisme/Leninisme.<br />
Ratifikasi instrumen internasional yang<br />
diagenda tidak semuanya berjalan sesuai yang<br />
dengan rencana yang tertuang dalam Rencana<br />
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)<br />
1998-2003. Hingga kini, instrumen<br />
internasional hak asasi manusia yang pokok,<br />
yakni Kovenan Hak Sipil dan Politik dan<br />
Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya<br />
belum kunjung diratifikasi. Begitu pula dengan<br />
Konvensi tentang Pencegahan dan<br />
Penghukuman Kejahatan Genosida. Yang cukup<br />
menggembirakan, tahun 1999 pemerintah dan<br />
DPR telah meratifikasi 7 konvensi pokok ILO,<br />
antara lain, Convention No. 138 Concerning<br />
Minimum Age for Admission to Employment;<br />
Convention No. 111 Concerning Discrimination<br />
in Respect of Employment and Occupation; dan<br />
Convention No. 182 Concerning The Prohibition<br />
and Immediate Aaction for The Elimination of<br />
The Worst Forms of Child Labour. Selain telah<br />
meratifikasi instrumen internasional hak asasi<br />
manusia, seperti Konvensi Anti Diskriminasi<br />
Rasial 1965, Konvensi Anti Penyiksaan, dan<br />
Konvensi Anti Perbudakan.<br />
Dalam konteks penyelesaian kasus-kasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde<br />
Baru dan saat ini, dalam periode lima tahun ini,<br />
ditunjukkan dengan melakukan penyelidikan<br />
dan mengadilinya. Seperti diketahui, negara<br />
transisi telah membentuk komite-komite<br />
penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia<br />
(KKP HAM), antara lain, KPP-HAM Timor-<br />
Timur, Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan<br />
Mei 1998, Komite Penyelidikan Tindak<br />
Kekerasan Aceh, KPP-HAM Tanjungpriok,<br />
KPP-HAM Irian Jaya/Papua, dan seterusnya.<br />
Penyelidikan kasus-kasus tersebut, di antaranya,<br />
telah pula digelar pengadilannya, yaitu Timor-<br />
Timor pasca jajak-pendapat, Tanjungpriok, dan<br />
Abepura. Selain itu telah digelar pula peradilan<br />
di luar pengadilan hak asasi manusia, yakni<br />
melalui pengadilan pidana koneksitas dan<br />
Mahkamah Militer. Kasus Teungku Bantaqiah<br />
dan kasus 27 Juli 1996 diselesaikan melalui<br />
pengadilan (pidana) koneksitas, sedangkan<br />
kasus Theys Eluay dan Kasus Trisakti<br />
diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Tetapi<br />
hasilnya jauh dari memuaskan, bahkan malah<br />
melanggengkan impunity; tidak ada<br />
penghukuman bagi pelaku dan keadilan bagi<br />
korban.<br />
iv
REGULASI TANPA DIDUKUNG<br />
PEMBENAHAN INSTITUSI<br />
Dukungan berbagai regulasi di bidang<br />
penegakan dan penghormatan hak asasi<br />
manusia tersebut, yang mencerminkan tekad<br />
politik negara transisi menerapkan ‘transitional<br />
justice’, ter nyata mandeg karena reformasi<br />
institusi-institusinya berjalan di tempat.<br />
Institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan,<br />
dan kehakiman berjalan bagaikan siput, amat<br />
lambat. Begitu pula reformasi institusi TNI dan<br />
intelijen negara, juga berjalan dengan lambat.<br />
Pembenahan institusi-institusi ini memerlukan<br />
kepemimpinan politik yang berani mengambil<br />
tindakan yang radikal, antara lain, dengan<br />
melakukan pensiunan dini terhadap mereka<br />
yang terlibat dengan berbagai kasus korupsi dan<br />
pelanggaran hak asasi di masa Orde Baru. Tetapi<br />
persis policy inilah yang tak berani diambil!<br />
Ambil contoh reformasi kehakiman.<br />
Reformasi di sektor ini telah berhasil<br />
menempatkan Mahkamah Agung sebagai<br />
puncak tertinggi kekuasaan kehakiman melalui<br />
UU No 4/<strong>2004</strong>. Tetapi sayangnya, regulasi yang<br />
berusaha mereformasi institusi tersebut tidak<br />
disertai pula dengan reformasi secara internal<br />
lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.<br />
Substansi reformasi agar lembaga ini lebih<br />
independen dan jauh dari kooptasi kekuasaan<br />
ternyata tidak sepenuhnya dijalankan, karena<br />
sebagian besar dari fungsi dan kewenangan di<br />
masa lalu masih dipertahankan. Lembaga ini<br />
gagal melakukan pembenahan ke dalam, antara<br />
lain, dengan melakukan pensiunan dini<br />
terhadap hakim-hakim yang korup dan pelaku<br />
kekerasan pengadilan di masa Orde Baru.<br />
Reformasi disektor ini nyaris seperti<br />
memasukkan anggur lama ke dalam botol baru!<br />
Inilah yang menjadi salah satu penyebab kasuskasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang<br />
diadili oleh lembaga ini gagal memberi keadilan.<br />
Reformasi kelembagaan memang sarat<br />
dengan kepentingan politik. Hingga hari ini<br />
lembaga kejaksaan belum tersentuh oleh<br />
gebrakan reformasi. Padahal lembaga ini<br />
merupakan ujung tombak penegakan hukum,<br />
tetapi lembaga ini dikoopatasi oleh kepentingan<br />
politik elit yang berkuasa di masa Orde Baru.<br />
ATAS NAMA OTONOMI DAERAH DAN<br />
KONFLIK<br />
Agenda pembangunan hak asasi manusia di<br />
tingkat nasional ternyata belum bisa<br />
diimplemetasikan oleh pemerintah daerah.<br />
Kebijakan otonomi daerah malah menyebabkan<br />
pemerintah daerah – baik itu di tingkat propinsi<br />
maupun kabupaten/kota — mengeluarkan<br />
regulasi-regulasi yang bertentangan dengan hak<br />
asasi manusia sehingga penggusuran,<br />
pengusiran secara paksa, penghancuran<br />
institusi-institusi lokal turut mewarnai<br />
rangkaian pelanggaran hak asasi manusia dalam<br />
periode 1999-<strong>2004</strong>. Di tingkat pemerintah<br />
daerah sangat minim institusi-institusi perlindungan<br />
hak asasi manusia. Malah sebaliknya<br />
pemerintah daerah berlomba untuk<br />
menguatkan institusi-institusi kekerasan seperti<br />
Satuan Tugas Polisi Pamong Praja guna<br />
mengawal dan mengamankan kebijakan yang<br />
dibuatnya. Parahnya lagi, dengan<br />
mengalaskan”sesuai prosedur” pemerintah<br />
daerah sering mengingkari praktik-praktik<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang<br />
dilakukannya.<br />
Dalam menangani Aceh, pemerintah pusat<br />
melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003<br />
menentapkan status Darurat Militer, yang menyebabkan<br />
pengerahan pasukan militer besarbesaran<br />
ke Aceh. Begitu pula dalam menangani<br />
Papua, pemerintah mengirimkan ribuan<br />
pasukan militer untuk mendukung Operasi<br />
Militer Selain Perang di sana guna menghadapi<br />
perlawanan kelompok OPM. Hal yang sama<br />
juga diterapkan dalam menangani konflik<br />
komunal di Maluku dan Poso yang<br />
berkepanjangan, lagi-lagi pemerintah<br />
menggunakan kekuatan militer. Pola-pola<br />
penyelesaian melalui cara-cara damai<br />
sebagaimana yang nampak pada awal<br />
pemerintahan transisi terbentuk lambat laun<br />
ditinggalkan.<br />
Dengan slogan “menjaga keutuhan NKRI”<br />
pejabat-pejabat tinggi militer dan sipil seolaholah<br />
menjadi matra untuk menghalalkan caracara<br />
kekerasan digunakan. Akibatnya Extrajudicial<br />
and summary killing; penangkapan dan<br />
penahanan sewenang-wenang; penyiksaan,<br />
tindakan kejam, tidak manusiawi, merendahkan<br />
martabat dan hukuman kejam; orang hilang<br />
v
dan penemuan mayat; pembatasan ruang gerak<br />
dan pencabutan hak untuk mengeluarkan<br />
pendapat masih terus terjadi.<br />
HAK-HAK PEREMPUAN: “ALAS KAKI<br />
SIANG HARI, ALAS TIDUR MALAM<br />
HARI “<br />
Sejak runtuhnya Orde Baru perlindungan<br />
dan penghormatan terhadap hak-hak<br />
perempuan tidak mengalami peningkatan yang<br />
cukup signifikan, baik di tataran legal reform<br />
maupun institusional reform. Perempuan masih<br />
dilihat dalam perspektif “alas kaki di waktu<br />
malam, alas tidur di waktu malam”; hak-hak<br />
mereka masih terpasung di bawah kekuasaan<br />
yang patriarki!<br />
Reformasi di bidang legislasi masih jauh dari<br />
apa yang diharapkan. Setidaknya baru dua<br />
produk legislasi tentang perlindungan dan<br />
pencegahan di tingkat nasional yang berhasil<br />
diproduksi dalam lima tahun terakhir, Undangundang<br />
Nomor 23 Tahun <strong>2004</strong> tentang<br />
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br />
dan Undang-undang Nomor 39 Tahun <strong>2004</strong><br />
tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan<br />
di Luar Negeri. Sehingga hingga saat ini —<br />
bersama Konvensi penghapusan segala bentuk<br />
diskriminasi terhadap perempuan yang telah<br />
diratifikasi — hanya ada tiga produk legislasi<br />
nasional tentang perlindungan dan pencegahan<br />
kejahatan terhadap perempuan. Oleh karenanya<br />
DPR dan Pemerintah dapat dikatakan mandul<br />
dalam memproduksi regulasi yang melindungi<br />
dan menghormati hak-hak perempuan. Di<br />
samping itu, pemerintah dan DPR juga tidak<br />
berdaya untuk mencabut beberapa regulasi di<br />
masa Soeharto yang diskriminatif terhadap<br />
perempuan.<br />
Lemahnya upaya-upaya peningkatan<br />
penghormatan dan perlindungan terhadap hakhak<br />
perempuan telah menimbulkan begitu<br />
banyak praktik-praktik penyiksaan dan ill-treatment<br />
terhadap perempuan. Sehingga kejahatan<br />
penyiksaan, tindakan tidak manusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
terhadap perempuan terus terjadi bahkan<br />
bersifat massif dan berskala besar. Dalam lima<br />
tahun ini masih belum ada tempat yang aman<br />
bagi perempuan, terutama di wilayah-wilayah<br />
konflik, di tempat kerja, bahkan dalam rumah<br />
tangga sekalipun.<br />
PENUTUP: TUTUP BUKU DENGAN<br />
“TRANSITIONAL JUSTICE”?<br />
Implementasi agenda penegakan hak asasi<br />
manusia, sebagai perwujudan dari agenda<br />
Reformasi, terlihat berjalan di tempat.<br />
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi<br />
manusia masa lalu (dan saat ini) dilakukan<br />
dengan selektif, hanya ditujukan bagi<br />
pelanggaran pada pertengahan 80-an hingga<br />
akhir 90-an. Itupun dengan hukuman yang jauh<br />
dari rasa keadilan, dan hanya dikenakan pada<br />
aktor lapangan sedangkan aktor pembuat<br />
kebijakan tidak tersentuh sama sekali! Selective<br />
justice begitu kentara, sehingga impunity masih<br />
dinikmati oleh pelaku yang berkedudukan<br />
tinggi. Pengadilan HAM Timtim dan Tanjung<br />
Priok menjadi bukti yang sulit dipungkiri<br />
tentang bagaimana praktik impunity tersebut<br />
terus berlanjut. Pemerintahan hasil pemilu<br />
<strong>2004</strong>, SBY-JK, terlihat tidak berani menyentuh<br />
wilayah peka ini: 100 hari program<br />
pemerintahannya hampir tidak menyentuh<br />
sama sekali ranah ini!<br />
Rentang waktu lima tahun ternyata bukan<br />
waktu yang cukup bagi Pemerintah, baik itu<br />
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,<br />
untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi<br />
hak asasi manusia. Masih banyak komitmen<br />
pemerintah yang belum dikerjakan dengan<br />
tuntas, khususnya agenda-agenda “transitional<br />
justice”. Akibatnya kondisi hak asasi manusia<br />
tidak begitu berbeda denga Orde Baru. Produksi<br />
regulasi yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia, reformasi institusi-institusi pelanggar<br />
hak asasi manusia yang setengah hati,<br />
pengadilan yang tak berdaya menghukun<br />
pelanggar hak asasi manusia, penggunaan caracara<br />
militer dalam menangani konflik, perilaku<br />
patriarki pemerintah yang merasuk ke berbagai<br />
lapisan masyarakat telah menggenapkan<br />
rangkaian kegagalan penghormatan dan perlindungan<br />
hak asasi manusia di Indonesia.<br />
Pemerintahan yang baru, SBY-JK, terlihat<br />
gamang mendekati masalah serius ini. Selama<br />
100 hari program kerjanya, pemerintahan SBY-<br />
JK tidak memiliki strategi dan visi menuntaskan<br />
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan<br />
membangun perbaikan keadaan hak asasi<br />
vi
manusia ke depan. Tidak adanya langkah yang<br />
berarti yang diambil dalam 100 hari pertama<br />
pemerintahan SBY-JK dalam penyelesaian dan<br />
penegakan hak asasi manusia, akhirnya<br />
membawa kita pada pertanyaan: pemerintah<br />
sudah menutup buku dengan “transitional justice”?<br />
REKOMENDASI:<br />
Berangkat dari pemaparan hasil pengamatan<br />
kami di atas, Lembaga Studi dan Advokasi<br />
Masyarakat (ELSAM) menawarkan langkah<br />
berikut ini, sebagai rekomendasi, yang harus<br />
dilakukan negara transisional.<br />
Khusus kepada Pemerintah Nasional, kami<br />
mendesakkan :<br />
1. Melanjutkan proses reformasi regulasi<br />
yang belum lengkap di antaranya terhadap<br />
berbagai UU yang belum dibentuk yang<br />
seharusnya menjadi bagian dari regulasi<br />
yang lain. UU tersebut diantaranya adalah<br />
UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU<br />
mengenai Kompensasi, Restitusi dan<br />
Rehabilitas, UU mengenai Ratifikasi<br />
Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, UU<br />
mengenai Ratifikasi Konvensi hak-hak<br />
Ekonomi, Sosial dan Budaya.<br />
2. Melakukan amandemen terhadap<br />
regulasi/UU yang masih banyak<br />
mempunyai kendala subtansial dan tidak<br />
sinkron dengan regulasi lainnya. UU<br />
tersebut di antaranya Kitab Undangundang<br />
Hukum Pidana, UU Hukum Acara<br />
Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang<br />
Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun<br />
2000 tentang Pengadilan HAM, Kitab<br />
Undang-Undang Hukum Pidana Militer<br />
3. Mencabut regulasi yang masih tersisa<br />
yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia terutama yang bertentang dengan<br />
Ketentuan mengenai HAM di UUD 1945.<br />
4. Lembaga-lembaga pelaksana regulasi<br />
harus melakukan reformasi internal untuk<br />
menghilangkan warisan watak orde baru<br />
sehingga reformasi regulasi yang terjadi<br />
juga diimbangi dengan perubahan internal<br />
di lembaga-lembaga tersebut.<br />
5. Mengembalikan penyelesaian persoalan<br />
sparatisme dan konflik sosial serta perang<br />
melawan terorisme melalui cara-cara<br />
damai, dan sebisa mungkin meminimalisir<br />
penggunaan kekuatan bersenjata dalam<br />
penyelesaian sparatisme dan konflik sosial<br />
serta perang melawan terorisme.<br />
6. Mempercepat proses reformasi di tubuh<br />
kepolisian.<br />
7. Mempercepat proses reformasi di tubuh<br />
TNI.<br />
8. Mempercepat proses reformasi di<br />
institusi kejaksaan<br />
9. Mempercepat proses reformasi di<br />
institusi pengadilan.<br />
Khusus kepada Pemerintah Daerah, kami<br />
mendesakkan:<br />
1. Melakukan audit terhadap regulasi<br />
daerah dengan menggunakan konstitusi<br />
dan hukum hak asasi manusia sebagai<br />
indikator audit dan selanjutnya mencabut<br />
regulasi daerah yang bertentangan dengan<br />
konstitusi dan hukum hak asasi manusia<br />
nasional<br />
2. Membuat regulasi-regulasi di tingkat<br />
daerah untuk mendorong pelaksanaan<br />
hukum hak asasi manusia nasional di<br />
tingkat daerah<br />
3. Mengembalikan fungsi Satuan Polisi<br />
Pamong Praja sebagai satuan pengaman<br />
internal.<br />
4. Menyelenggarakan training hak asasi<br />
manusia bagi aparatur pemerintahan<br />
daerah secara berkala dengan mengundang<br />
para pengajar dari kalangan akademisi dan<br />
praktisi hak asasi manusia.<br />
5. Membuka Kantor Perwakilan Komisi<br />
Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayahnya<br />
dan bekerjsama dengan Komnas HAM<br />
untuk melakukan pemantauan kondisi<br />
hak asasi manusia di daerahnya secara<br />
periodik.<br />
6. Mempublikasikan laporan kondisi hak<br />
asasi manusia daerahnya secara periodik<br />
kepada publik lokal.<br />
vii
DAFTAR ISI<br />
EXECUTIVE SUMMARY iii<br />
BAGIAN PERTAMA<br />
Pendahuluan 1 | Tujuan dan Cakupan 3 |<br />
Metode Pengumpulan dan Analisis Data 4 | Sistematika Laporan 4 |<br />
BAGIAN KEDUA<br />
Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia Periode 1999-<strong>2004</strong>: Produksi Kebijakan dan<br />
Implementasinya 6<br />
Pengantar 6 | Komitmen dan Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 7 | Implementasi Atas<br />
Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 1999-<strong>2004</strong> 8 | Kesimpulan 24 |<br />
BAGIAN KETIGA<br />
Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer:<br />
Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah Konflik 28<br />
Pengantar 28 | Menguatnya Penggunaan Regulasi Kedaruratan dan Pengerahan Kekuatan<br />
Militer oleh Negara Sepanjang 1999-<strong>2004</strong> 29 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia 33 | Respon<br />
Negara Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 38 | Kesimpulan 39 |<br />
BAGIAN KEEMPAT<br />
Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus<br />
Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia<br />
Dalam Kerangka Otonomi Daerah 41<br />
Pengantar 41 | Implementasi Otonomi Daerah di Berbagai Daerah 41 | Perlindungan dan<br />
Penegakan HAM dalam Otonomi Daerah 43 | Peristiwa-peristiwa Pengusiran Paksa Periode<br />
1999-<strong>2004</strong> 46 | Pengingkaran Pemerintah Daerah Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 47 |<br />
Pengusiran Paksa: Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah 48 |<br />
Kesimpulan 50 |<br />
BAGIAN KELIMA<br />
Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment<br />
terhadap Perempuan Periode 1999-<strong>2004</strong> 52<br />
Pengantar 52 | Upaya-upaya penegakan Hak-Hak Perempuan 53 | Akibat Buruknya<br />
Pelaksanaan Perbaikan Hak-hak Perempuan: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill Treatment<br />
terhadap Perempuan di Indonesia 54 | Pengingkaran Negara Atas Kejahatan Penyiksaan,<br />
Perlakuan Tidak Manusiawi, Merendahkan Martabat dan Hukuman Kejam Terhadap<br />
Perempuan 58 | Kesimpulan 59 |<br />
BAGIAN KEENAM<br />
Kesimpulan dan Rekomendasi 62<br />
Rekomendasi 64 | Kepada Pemerintah Nasional 64 | Kepada Pemerintah Daerah 65 | Kepada<br />
DPRD Seluruh Indonesia 65 | Rekomendasi Khusus 65 | Kepada Pemerintah Nasional 65 |<br />
Kepada TNI/POLRI 65 | Kepada Pemerintah Daerah 66 | Kepada DPR dan DPRD 66 |<br />
viii
BAGIAN PERTAMA<br />
Pendahuluan<br />
Ketika tahun <strong>2004</strong> berganti, berarti kita<br />
telah lima tahun dalam era reformasi.<br />
Meskipun telah lima tahun, penuntasan<br />
berbagai permasalahan hak asasi manusia terasa<br />
belum begitu mengembirakan. Bahkan dalam<br />
dua tahun terakhir ini, perlindungan dan<br />
pemajuan hak asasi manusia seakan kembali<br />
ketitik terendah, karena reformasi kelembagaan<br />
dan ratifikasi instrumen norma hak asasi<br />
manusia internasional belum terjadi seperti<br />
yang diharapkan. Di samping itu, upaya untuk<br />
mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi<br />
manusia terasa sangat lamban serta belum<br />
memiliki arah yang jelas. Dengan sendirinya kita<br />
kembali mengalami berulangnya pelanggaran<br />
hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa kita<br />
bedakan dengan pelangaran di era Soeharto.<br />
Situasi serba lamban itu disebabkan oleh<br />
beberapa faktor yaitu: (i) Kembali menguatnya<br />
penggunaan regulasi kedaruratan yang disertai<br />
pengerahan kekuatan militer untuk<br />
menyelesaikan tuntutan kemerdekaan atau<br />
konflik sosial di beberapa daerah; (ii) Terlalu<br />
bersandarnya agenda perbaikan ekonomi<br />
nasional kepada pemilik modal; (iii)<br />
Diabaikannya hak-hak ekosob masyararakat<br />
dalam proses desentralisasi kekuasaan; dan (iv)<br />
Masih lestarinya watak patriarki dalam birokrasi<br />
negara. Keempat faktor itu pada gilirannya<br />
membuat negara lebih berpihak kepada pemilik<br />
modal di satu sisi dan menyisihkan perempuan<br />
dari proses pengambilan keputusan politik<br />
nasional di sisi lain.<br />
Dalam era reformasi ini, agenda utama yang<br />
dituntut masyarakat, terutama korban dan<br />
keluarga korban, adalah penyelesaian kasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia pada masa<br />
Soeharto. Untuk menjawab tuntutan itu mulai<br />
diselidiki kasus kerusuhan Mei dan Penculikan<br />
aktivis pro-demokrasi, DOM Aceh dan<br />
kejahatan militer di Timor Lorosae pasca jajak<br />
pendapat. Kemudian penyelidikan berlanjut ke<br />
kasus seperti kasus penembakan mahasiswa<br />
Trisakt-Semanggi, Talangsari dan kasus-kasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia di Papua.<br />
Sayangnya, sebagian besar hasil penyelidikan<br />
itu, di dalam pengadilan tidak mendapatkan<br />
respon yang baik. Hal itu terlihat dari bebasnya<br />
para terdakwa. Bahkan tak jarang pula ada hasil<br />
penyelidikan terkatung-katung nasibnya karena<br />
berkasnya selalu bolak-balik antara Komnas<br />
HAM dan Kejaksaan Agung. Kondisi ini-lah<br />
yang menimbulkan skeptisme dari masyarakat<br />
terhadap proses reformasi institusi peradilan.<br />
Rendahnya kepercayaan itu kemudian<br />
diperburuk oleh masihnya tingginya tingkat<br />
korup di lembaga-lembaga peradilan tersebut.<br />
Selain itu lembaga peradilan juga tidak mampu<br />
mengatasi atau menolak intervensi dari pihak<br />
eksekutif, legislatif, serta institusi militer atau<br />
polisi.<br />
Sepanjang lima tahun terakhir, pemerintah<br />
— baik di tingkat pusat, propinsi, maupun<br />
kabupaten/kota — dalam membuat kebijakan<br />
baru terlihat lebih banyak mengabaikan hak<br />
asasi manusia ketimbang memberikan<br />
perangkat melindungi. Produk undang-undang<br />
yang melindungi hak asasi manusia di awal<br />
reformasi dalam perkembangannya belum<br />
menjadi acuan bagi daerah seperti provinsi dan<br />
kabupaten/kota dalam membuat kebijakan<br />
baru. Kadang kala kebijakan yang tidak respek<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
1
terhadap hak asasi manusia itu direproduksi<br />
atau diproduksi dengan alasan tingginya potensi<br />
konflik di berbagai daerah, seperti<br />
perkembangan masalah di Aceh dan Papua, atau<br />
konflik antar etnis atau bernuansa agama yang<br />
terjadi di Maluku, Poso dan Kalimantan. Alasan<br />
lain dari dikeluarkannya kebijakan yang tidak<br />
respek terhadap hak asasi manusia itu adalah<br />
perlunya jaminan keamanan untuk investasi<br />
demi perbaikan kondisi ekonomi nasional.<br />
Kebijakan yang tidak respek hak asasi manusia<br />
ini pada gilirannya mengabaikan pula hak-hak<br />
perempuan. Pengiriman besar-besaran<br />
perempuan ke manca negara sebagai TKW<br />
adalah contoh nyata dari situasi ini.<br />
Keadaan lain yang membuat perlindungan<br />
dan pemenuhan hak asasi manusia lamban<br />
adalah belum terjadinya reformasi yang<br />
signifikan dalam institusi militer, intelijen dan<br />
kepolisian. Kelambanan itu terjadi karena<br />
kurangnya dukungan dari parlemen dan<br />
departemen terkait. Semua itu terjadi karena<br />
kuatnya kepentingan personal, terutama personal<br />
yang terlibat masalah pelanggaran hak<br />
asasi manusia dalam menentukan arah dari<br />
reformasi institusi-institusi tersebut. Akibatnya<br />
upaya Komnas HAM untuk melakukan<br />
penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dan<br />
Pengadilan HAM untuk membuktikan<br />
terjadinya pelanggaran terbentur pada aturanaturan<br />
internal institusi-institusi tersebut. Di sisi<br />
lain peranan institusi keamanan dan pertahanan<br />
ini kian menjadi dominan tak kala konflik terus<br />
menerus berkembang, sementara itu para<br />
pejabat sipil dan parlemen tidak percaya diri<br />
menghadapi konflik tersebut.<br />
Peristiwa kekerasan yang terus terjadi dalam<br />
lima tahun belakangan ini telah memaksa lebih<br />
dari 3 juta penduduk meninggalkan kampung<br />
halamannya dan terpaksa hidup di kamp-kamp<br />
pengungsian dalam batas waktu yang tidak<br />
-terbatas. Setidaknya saat ini 3 juta orang korban<br />
tersebut hidup dalam kemiskinan dan sangat<br />
bergantung dengan uluran tangan pemerintah<br />
dan organisasi-organisasi kemanusiaan nasional<br />
maupun internasional. Para korban itu saat ini<br />
hidup dalam ancaman serangan busung lapar,<br />
kekurangan gizi, dan penyakit menular<br />
berbahaya lainnya. Dan celakanya, mayoritas<br />
dari korban tersebut adalah perempuan dan<br />
anak-anak.<br />
Di samping itu, dalam lima tahun ini<br />
langkah-langkah pembenahan ekonomi Indonesia<br />
patut untuk diperhatikan karena programprogram<br />
ini kerap berkontribusi terhadap<br />
berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi<br />
manusia di Indonesia. Program-program recovery<br />
ekonomi yang menitiktekankan pada<br />
pembuatan regulasi liberalisasi ekonomi Indonesia<br />
ini diketahui menjadi penyebab praktikpraktik<br />
pelanggaran dalam bentuk perampasan<br />
tanah petani dan masyarakat asli oleh<br />
perusahaan, penggusuran rumah/tempat tinggal<br />
masyarakat miskin kota, PHK, dan semakin<br />
buruknya akses penduduk atas fasilitas<br />
pendidikan dan kesehatan. Dengan<br />
mengatasnamakan memacu pertumbuhan<br />
ekonomi nasional atau daerah, pemerintah<br />
bersama-sama parlemen kemudian<br />
memberikan kekebalan kepada pemilik modal<br />
dalam bentuk jaminan modal dan pemenuhan<br />
seluruh kebutuhan-kebutuhan dari para<br />
pemodal tersebut. Praktis seluruh sektor<br />
ekonomi di pedesaan dan kota telah dikuasai<br />
oleh para pemilik modal, dan penduduk hanya<br />
menjadi pengisi tenaga kerja kasar di situs-situs<br />
ekonomi besar.<br />
Meskipun Indonesia telah meratifikasi<br />
instrumen internasional tentang hak-hak<br />
perempuan, bahkan jauh sebelum gerakan hak<br />
asasi manusia di Indonesia menguat, namun<br />
tidak membuat kondisi perempuan dengan<br />
sendirinya membaik. Laporan adanya kasuskasus<br />
penyiksaan, tindakan tidak manusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
terhadap kelompok perempuan terus<br />
meningkat hingga mengkhawatirkan banyak<br />
pihak. Peristiwa-peristiwa ini nyaris ditemukan<br />
di seluruh propinsi, tanpa melihat apakah<br />
propinsi tersebut masuk dalam kategori maju<br />
atau tidak. Para korbannya pun berasal dari<br />
semua tingkatan status sosial. Para pelaku dari<br />
kejahatan ini pun tidak melulu negara,<br />
melainkan sudah meluas hingga ke wilayah<br />
domestik. Di wilayah-wilayah konflik<br />
bersenjata, intensitas kejadiannya cukup tinggi<br />
dan sangat terkait erat dengan penggunaan<br />
strategi perang yang digunakan pihak-pihak<br />
yang bertikai. Sementara di wilayah non-konflik<br />
intensitas dari kejahatan ini juga cukup<br />
2 Bagian I
meningkat dan terkait erat dengan sejumlah<br />
langkah-langkah negara dalam memulihkan<br />
perekonomian nasional, proses desentralisasi<br />
dan kebijakan perang melawan terorisme.<br />
Kecenderungan yang semakin memburuk ini<br />
semakin diperparah dengan tidak berjalannya<br />
agenda pembangunan dan perbaikan hak-hak<br />
perempuan. Terbatasnya produksi regulasi di<br />
tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota<br />
berkaitan dengan perlindungan dan penegakan<br />
hak-hak perempuan; proses reformasi di tubuh<br />
institusi pemerintahan dan parlemen yang tetap<br />
melanggengkan sistem patriarki; serta ketiadaan<br />
institusi-institusi khusus perlindungan dan<br />
penyelidikan serta ketidakmampuan peradilan<br />
Indonesia untuk mengadili kasus-kasus<br />
kejahatan terhadap perempuan adalah sumber<br />
utama penyebab meningkatnya praktik-praktik<br />
penyiksaan, tindakan tidak manusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
terhadap perempuan di wilayah konflik, lokasi<br />
bekerja, sekolah hingga di rumah.<br />
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa<br />
komitmen nasional tentang penegakan hak asasi<br />
manusia yang dirumuskan dari pengalaman<br />
hidup sejumlah korban di masa rezim Orde<br />
Baru berkuasa tidak dengan sendirinya<br />
membuat kondisi hak asasi manusia di Indonesia<br />
membaik. Dengan pengamatan yang<br />
panjang dan mendalam ELSAM menilai perlu<br />
untuk memaparkan proses penerapan agenda<br />
pembangunan dan perbaikan hak asasi manusia<br />
nasional yang sekaligus juga mampu<br />
memaparkan problem-problem ekonomi<br />
politik yang membingkainya.<br />
TUJUAN DAN CAKUPAN<br />
Selanjutnya laporan ini bertujuan untuk :<br />
Pertama, mengevaluasi proses pelaksaanan<br />
agenda penegakan hak asasi manusia nasional,<br />
termasuk agenda penegakan hak-hak<br />
perempuan, periode 1999-<strong>2004</strong>. Kedua,<br />
mengevalusi implementasi atas sejumlah agenda<br />
penegakan hak asasi manusia nasional,<br />
termasuk agenda penegakan hak-hak<br />
perempuan yang telah berjalan. Ketiga, Sebagai<br />
bahan refleksi kepada departemen perudangudangan<br />
dan HAM, TNI, Polri, pengadilan dan<br />
kejaksaan dan sekaligus menjadi bahan pijakan<br />
pembenahan agenda penegakan hak asasi<br />
manusia ke depan. Keempat, Sebagai bahan<br />
refleksi pemerintahan propinsi dan kabupaten<br />
atas proses penerepan otonomi daerah dan<br />
sekaligus menjadi bahan masukan dalam<br />
penegakan dan pembangunan hak asasi<br />
manusia dalam pembenahan pelaksanaan<br />
otonomi daerah.<br />
Untuk itu laporan ini akan mencakup upayaupaya<br />
penerapan agenda penegakan hak asasi<br />
manusia nasional sepanjang periode 1999-<strong>2004</strong><br />
yang meliputi pembuatan dan pencabuatan<br />
regulasi yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia; proses reformasi di institusi<br />
pemerintah, termasuk institusi TNI, Polri,<br />
kehakiman dan kejaksaan. Penentuan tahun<br />
1999 sebagai periode awal pengamatan, karena<br />
sejumlah upaya penegakan hak asasi manusia,<br />
penyelidikan, pembentukan regulasi hak asasi<br />
manusia dan pengadilan atas sejumlah<br />
pelanggaran hak asasi manusia untuk<br />
pertamakalinya dilakukan di Indonesia. Di<br />
samping itu, pada tahun yang sama<br />
pemerintahan baru pengganti pemerintahan<br />
otoriter Soeharto baru saja terbentuk. Meskipun<br />
pada pertengahan 1998 ada sejumlah langkahlangkah<br />
penegakan hak asasi manusia, namun<br />
demikian langkah-langkah tersebut tidak<br />
memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat<br />
Indonesia, karena pemerintahan pada saat itu<br />
masih dipandang bagian dari pemerintahan<br />
masa lalu.<br />
Selanjutnya untuk melihat apakah upayaupaya<br />
penerapan agenda penegakan hak asasi<br />
manusia periode 1999-<strong>2004</strong> berjalan efektif di<br />
tataran praktis, laporan ini juga akan mencakup<br />
peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi<br />
manusia periode 1999-<strong>2004</strong> seperti<br />
pembunuhan sewenang-wenang, penangkapan<br />
dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan<br />
dan berbagai perlakuan kejam dan tidak<br />
manusiawi di Aceh dan Papua serta berbagai<br />
daerah lainnya, yang terkait dengan penggunaan<br />
regulasi-regulasi kekerasan.<br />
Laporan ini juga akan mencakup proses<br />
penerapan otonomi daerah yang terkait dengan<br />
penegakan dan pembangunan hak asasi<br />
manusia. Secara khusus pula, laporan ini akan<br />
mencakup berbagai peristiwa pengusiran atau<br />
penggusuran paksa terhadap penduduk urban,<br />
penduduk asli, petani dan pelarangan atas<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
3
sejumlah aktivitas mencari nafkah para<br />
penduduk di kota maupun di desa, seperti<br />
pengemudi becak, pedagang kaki lima dan para<br />
penambang dan nelayan kecil yang terkait<br />
dengan penerapan otonomi daerah.<br />
Laporan ini pun secara khusus akan<br />
mencakup berbagai upaya-upaya penerapan<br />
agenda penegakan hak-hak perempuan. Tanpa<br />
bermaksud memisahkan agenda penegakan<br />
hak-hak perempuan dengan agenda penegakan<br />
hak asasi manusia secara umum, laporan ini<br />
dengan sengaja memisahkan pembahasan<br />
agenda penegakan hak-hak perempuan agar<br />
gambaran penegakan dalam agenda ini dapat<br />
terlihat dengan jelas sehingga dapat mendorong<br />
upaya-upaya pembenahan di masa yang akan<br />
datang dengan bobot yang sama dengan agenda<br />
penegakan hak asasi manusia yang lain. Laporan<br />
ini pun akan mencakup secara khusus tentang<br />
praktik-praktik penyiksaan dan beberagai<br />
bentuk kekerasan terhadap perempuan yang<br />
dalam lima tahun ini terus meningkat, dan para<br />
pelakunya pun sudah meluas,tidak hanya<br />
datang dari para agen negara, akan tetapi juga<br />
melibatkan kelompok-kelompok non negara,<br />
seperti satuan pengaman swasta, milisi sipil,<br />
termasuk para anggota laki-laki dalam sebuah<br />
keluarga. Penggabungan kekerasan domestik<br />
dalam kategori penyiksaan, tindakan tidak<br />
manusiawi, merendahkan martabat, dan<br />
hukuman kejam karena praktik-praktik<br />
kekerasan dalam rumah tangga dilakukan<br />
berulang-ulang dan membawa akibat-akibat<br />
terhadap korban yang tidak jauh berbeda<br />
dengan praktik-praktik penyiksaan yang<br />
dilakukan oleh aparatur negara. Para pelakunya<br />
pun melakukan tindakan ini didasari atas dasar<br />
praktik diskriminasi sexual yang selama ini<br />
dijalankan oleh orde baru dan pemerintahan<br />
baru. Upaya ini juga bagian dari dukungan<br />
ELSAM terhadap kampanye atas sejumlah<br />
organisasi hak asasi manusia internasional yang<br />
sedang berupaya memasukan kasus-kasus<br />
kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian<br />
dari praktik-praktik penyiksaan, tindakan tidak<br />
manusiawi, merendahkan martabat, dan<br />
hukuman kejam. 1<br />
METODE PENGUMPULAN DAN<br />
ANALISIS DATA<br />
Informasi dan data dalam laporan ini<br />
dikumpulkan dari dokumentasi pelanggaran<br />
hak asasi manusia dan laporan-laporan hak asasi<br />
manusia ELSAM periode 1999-<strong>2004</strong>, puluhan<br />
laporan lembaga hak asasi manusia nasional dan<br />
daerah, kumpulan e-mail dan sejumlah<br />
wawancara terbatas atau tertutup dengan<br />
sejumlah pihak, baik melalui telepon maupun e-<br />
mail. Untuk membuat isi laporan ini berimbang,<br />
sejumlah informasi dan data juga diperoleh dari<br />
sejumlah dokumen pemerintah yang telah<br />
dipublikasikan secara luas. Seluruh informasi<br />
yang berhasil dikumpulkan oleh tim penulis<br />
selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk<br />
informasinya dan kemudian secara mendalam<br />
dikaji untuk mendapatkan gambaran yang<br />
komperhensif tentang proses penegakkan hak<br />
asasi manusia sepanjang 1999-<strong>2004</strong>.<br />
SISTEMATIKA LAPORAN<br />
Laporan ini disusun dalam enam bagian<br />
besar. Masing-masing bagian memiliki kaitan<br />
dan merupakan potret dari kondisi hak asasi<br />
manusia di Indonesia. Dimulai dengan bagian<br />
pertama, yang mencoba menjelaskan tentang<br />
latar belakang penulisan, cakupan, metode<br />
pengumpulan dan analisis data serta sistematika<br />
laporan. Selanjutnya pada bagian kedua<br />
memaparkan review atas komitmen penegakan<br />
hak asasi manusia nasional sekaligus bagaimana<br />
implementasinya, baik di tingkat pembuatan<br />
regulasi, reformasi institusi negara, praktikpraktik<br />
pelaksanaan perlindungan dan<br />
penghormatan di lapangan serta berbagai<br />
hambatan dalam pelaksanaannya. Bagian ketiga<br />
membahas tentang menguatnya penggunaan<br />
regulasi kedaruratan dalam operasi militer yang<br />
melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi<br />
hak asasi manusia nasional. Selanjutnya<br />
berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang terjadi semasa penerapan<br />
Otonomi Daerah, khususnya tentang praktikpraktik<br />
pengusiran paksa (forced eviction) akan<br />
dipaparkan dalam bagian keempat laporan ini.<br />
Bagian kelima laporan ini memaparkan tentang<br />
buruknya proses implementasi agenda<br />
perbaikan kondisi hak-hak asasi manusia kaum<br />
perempuan. Bagian keenam memberikan<br />
4 Bagian I
sebuah kesimpulan besar berkaitan dengan<br />
capaian agenda penegakan hak asasi manusia<br />
serta sejumlah persoalan-persoalan yang<br />
melingkarinya. Selanjutnya laporan ini ditutup<br />
dengan paparan rekomendasi umum dan<br />
khusus tentang perbaikan atas implementasi<br />
perbaikan kondisi hak asasi manusia ke depan<br />
kepada pemerintah baru.<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Salah satu organisasi hak asasi manusia internasional<br />
yang sedang berkampanye memasukkan kekerasan<br />
dalam rumah tangga ke dalam kategori penyiksaan<br />
adalah Amnesty Internationa. Kunjungi http://<br />
www.amnestyusa.org/women/violence/<br />
domesticviolence.htm<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
5
BAGIAN KEDUA<br />
Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia<br />
Periode 1999-<strong>2004</strong> : Produksi Kebijakan dan<br />
Implementasinya<br />
PENGANTAR<br />
Pemerintahan-pemerintahan pasca Orde<br />
Baru telah berkomitmen untuk<br />
melakukan penegakan hak asasi manusia<br />
di Indonesia. Dimulai dalam Sidang Istimewa<br />
MPR 1998, untuk pertamakalinya parlemen dan<br />
pemerintahan pengganti Soeharto bersamasama<br />
mencetuskan komitmennya untuk<br />
memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia.<br />
Komitmen yang dituangkan dalam<br />
sejumlah kebijakan nasional sepanjang 1998-<br />
2000 tersebut berhasil merumuskan lima agenda<br />
pokok penegakan yang meliputi: penyelidikan<br />
pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde<br />
Baru; mengamandemen konstitusi dan<br />
memproduksi regulasi perlindungan hak asasi<br />
manusia; mereformasi institusi-institusi yang<br />
terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia,<br />
membentuk mekanisme pertanggungjawaban<br />
pelanggaran hak asasi manusia, dan serta<br />
mencegah keberulangan dalam bentuk<br />
menghukum para pelaku kejahatan hak asasi<br />
manusia. Komitmen ini lahir sebagai bentuk<br />
dari pengakuan mereka atas kejahatankejahatan<br />
hak asasi manusia rezim Orde Baru<br />
yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa<br />
terhadap para korbannya selama lebih dari tiga<br />
dasawarsa. Komitmen ini lahir sebagai bentuk<br />
kesadaran baru dalam pengelolaan Negara<br />
setelah hancurnya tatanan kehidupan<br />
berdemokrasi di Indonesia selama<br />
pemerintahan otoriter.<br />
Pelantikan presiden hasil pemilu <strong>2004</strong> pada<br />
Oktober lalu, menandai agenda penegakan hak<br />
asasi manusia sudah berjalan selama lima tahun.<br />
Namun demikian, agenda penegakan hak asasi<br />
manusia tersebut belum berhasil dituntaskan.<br />
Bahkan dalam dua tahun terakhir ini,<br />
pelaksanaan agenda penegakan hak asasi<br />
manusia terus melemah dan cenderung stagnan.<br />
Ini terlihat dari tidak berjalannya sejumlah<br />
agenda penegakan penting, seperti penyelesaian<br />
kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu<br />
dan penghukuman para pelaku kejahatannya<br />
hingga akhir tahun <strong>2004</strong> ini. Di lain sisi,<br />
sejumlah agenda yang berhasil dijalankan,<br />
seperti pembuatan regulasi hak asasi manusia<br />
dan proses penyelidikan, masih jauh dari yang<br />
diharapkan oleh banyak pihak, karena<br />
banyaknya kelemahan dan keterbatasan yang<br />
pada akhirnya justru menyebabkan<br />
penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak<br />
berjalan efektif.<br />
Bagian ini akan menjelaskan tentang<br />
pelaksanaan komitmen penegakan hak asasi<br />
manusia yang dicetuskan pasca kejatuhan<br />
Soeharto Mei 1998. Selain memaparkan<br />
perjalanan pelaksanaan dari masing-masing<br />
agenda penegakan tersebut, bagian ini juga akan<br />
memberikan gambaran berkaitan dengan<br />
capaian yang telah berhasil diraih. Sejumlah<br />
agenda penegakan yang tidak berhasil<br />
dijalankan pun akan turut dipaparkan dalam<br />
bagian ini, termasuk juga problem-problem<br />
pelaksanaannya. Untuk memudahkan dalam<br />
melihat capaian keberhasilan serta kegagalannya<br />
maka pemaparan dalam bagian ini akan<br />
mencoba mengelompokkan masing-masing<br />
agenda ke dalam kategori-kategori yang antara<br />
lain: penyelidikan, legal reform, institusional reform,<br />
penghukuman, rekonsiliasi, dan<br />
pemulihan korban.<br />
6 Bagian II
KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN<br />
HAK ASASI MANUSIA<br />
Pasca tumbangnya Soeharto Mei 1998,<br />
kalangan korban dan kelompok pro-demokrasi<br />
secara terus-menerus mendesak pemerintahan<br />
pasca Soeharto agar segera menunjukkan<br />
komitmen mereka terhadap penegakan hak asasi<br />
manusia. Berpijak dari peristiwa pelanggaran<br />
masa lalu dan banyaknya institusi-institusi<br />
negara yang terlibat dalam kejahatan hak asasi<br />
manusia, kelompok korban dan publik luas<br />
mendesak pemerintah menempatkan agenda<br />
penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu<br />
agenda reformasi nasional. 1 Desakan yang terus<br />
menguat inilah yang kemudian membuat MPR<br />
mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/<br />
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.<br />
Ketetapan ini menyebutkan tentang tugas yang<br />
harus dijalankan presiden Habibie dan lembagalembaga<br />
tinggi negara serta seluruh aparatur<br />
negara untuk menghormati dan<br />
menyebarluaskan pemahaman hak asasi<br />
manusia kepada seluruh lapisan masyarakat,<br />
dan serta menugaskan presiden untuk<br />
meratifikasi instrumen internasional hak asasi<br />
manusia. 2<br />
Terbitnya ketetapan ini selanjutnya menjadi<br />
titik awal pemerintahan sementara pasca<br />
tumbangnya Soeharto untuk secara serius<br />
memasukkan komitmen penegakan hak asasi<br />
manusia ke dalam agenda reformasi nasional.<br />
Dan secara umum ketetapan ini secara efektif<br />
dijalankan oleh pemerintahan Habibie, yakni<br />
dengan membuat Rencana Aksi Nasional Hak<br />
Asasi Manusia (RAN-HAM) periode 1998-2003.<br />
RAN-HAM ini memuat agenda pembuatan<br />
regulasi hak asasi manusia di tingkat nasional,<br />
sosialisasi hak asasi manusia di tingkat institusi<br />
negara dan masyarakat; serta kewajiban<br />
pemerintah untuk meratifikasi instrumen hak<br />
asasi manusia.<br />
Pasca pemilu 1999 yang berhasil menaikkan<br />
Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI<br />
ketiga, kembali memperkuat komitmen<br />
pemerintah dalam bidang penegakan hak asasi<br />
manusia. Berpijak dari ketetapan selanjutnya,<br />
komitmen penegakan hak asasi manusia di masa<br />
Abdurrahman Wahid, terus menguat dan<br />
berhasil memproduksi berbagai produk regulasi<br />
dan sejumlah agenda di tataran praktis. Upaya<br />
Presiden Abdurrahman Wahid ini pun juga<br />
mendapat dukungan dari MPR dan DPR kala<br />
itu, yakni dalam bentuk membuat sejumlah<br />
regulasi dan ikut memperhatikan problemproblem<br />
hak asasi manusia di tanah air. Berbagai<br />
produk ini adalah diterbitkannya Ketetapan<br />
MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis<br />
Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-<br />
2000, yang mana dalam GBHN tersebut MPR<br />
meminta presiden secara konsisten menjamin<br />
kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,<br />
supremasi hukum serta menghargai hak asasi<br />
manusia. Selain itu MPR juga meminta presiden<br />
untuk melanjutkan ratifikasi sejumlah konvensi<br />
internasional, terutama yang berkaitan dengan<br />
hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan<br />
kepentingan. 3 Memasuki 2000, dukungan MPR<br />
dan DPR terhadap komitmen penegakan hak<br />
asasi manusia semakin memperkuat atas<br />
ketetapan-ketetapan tahun 1999. Dalam Sidang<br />
tahunan MPR 2000, MPR kembali<br />
mengeluarkan sejumlah ketetapan yang isinya<br />
mengarahkan negara untuk mengambil<br />
langkah-langkah kongkrit berkaitan dengan<br />
pelaksanaan atas agenda penegakan hak asasi<br />
manusia nasional. Ketetapan itu antara lain: TAP<br />
MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan<br />
Persatuan dan Kesatuan Nasional, TAP MPR<br />
Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan<br />
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian<br />
Negara Republik Indonesia dan TAP MPR<br />
Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan<br />
Polri. Ketiga ketetapan tersebut, memerintahkan<br />
presiden untuk membentuk Komisi Kebenaran<br />
dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga<br />
ekstrajudisial yang bertugas mengungkap<br />
kebenaran atas praktik penyalahgunaan<br />
kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di<br />
masa Soeharto; melaksanakan rekonsiliasi<br />
dalam perspektif kepentingan bersama sebagai<br />
bangsa; dan menghapuskan peran sospol ABRI<br />
(Dwifungsi ABRI); memisahkan institusi<br />
kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia<br />
(TNI) serta merubah konsep sistem pertahanan<br />
nasional. Bahkan pada Sidang Tahunan 2000<br />
tersebut MPR melakukan amandemen kedua<br />
UUD 1945 yang di antaranya memasukkan hak<br />
asasi manusia ke dalam Bab XA serta bidang<br />
pertahanan dan keamanan negara pada Bab XII<br />
UUD 1945. 4 Terobosan yang dilakukan MPR<br />
selama Sidang Tahunan 2000 inilah yang<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
7
kemudian menjadi dasar dan arahan penegakan<br />
hak asasi manusia nasional bagi presiden. Secara<br />
garis besar dari ketetapan-ketetapan MPR dapat<br />
disimpulkan berbagai agenda penegakan hak<br />
asasi manusia nasional, yakni: Agenda<br />
Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia<br />
masa lalu; pembuatan regulasi tentang jaminan<br />
perlindungan dan penghormatan hak asasi<br />
manusia; reformasi institusi TNI dan Polri;<br />
penghukuman dan pemulihan para korban<br />
pelanggaran hak asasi manusia. Kelima agenda<br />
besar inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah<br />
dan jajaran birokrasinya untuk melaksanakan<br />
agenda penegakan hak asasi manusia untuk<br />
periode 1999-<strong>2004</strong>.<br />
IMPLEMENTASI ATAS AGENDA<br />
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA<br />
1999-<strong>2004</strong><br />
Adanya agenda penegakan hak asasi manusia<br />
nasional tidak dengan sendirinya membuat<br />
kondisi hak asasi manusia di Indonesia berubah.<br />
Menurunnya dukungan politik DPR terhadap<br />
pelaksanaannya membuat agenda membuat<br />
titik tekan pelaksanaan dari agenda tersebut<br />
hanya berhenti pada produksi regulasi saja.<br />
Agenda-agenda penegakan penting lainnya<br />
seperti penyelidikan pelanggaran hak asasi<br />
manusia, reformasi institusi TNI/Polri,<br />
Penghukuman para pelaku pelanggaran hak<br />
asasi manusia masa lalu dan pemberian<br />
rehabilitasi para korban belum tersentuh sama<br />
sekali, sementara agenda-agenda ini menjadi<br />
indikator utama penentu keberhasilan<br />
penegakan hak asasi manusia nasional. Bahkan<br />
memasuki tahun keempat, proses pelaksanaan<br />
agenda penegakan hak asasi manusia semakin<br />
menurun dan mencapai titik terendahnya<br />
memasuki tahun kelima, ketika parlemen<br />
bersama-sama dengan pihak eksekutif, semakin<br />
menurunkan dukungannya terhadap<br />
pelaksanaan agenda penegakan hak asasi<br />
manusia dan berbalik meningkatkan<br />
pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan yang<br />
bertentangan dengan hak asasi manusia.<br />
Akibatnya banyak sekali agenda penegakan yang<br />
terbengkalai dan kembali menciptakan<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang tak kalah<br />
hebatnya ketika di masa pemerintahan<br />
Soeharto. Untuk selanjutnya paparan di bawah<br />
akan menjelaskan proses pelaksanaan dari<br />
masing-masing agenda penegakan hak asasi<br />
8 Bagian II
manusia nasional periode 1999-<strong>2004</strong>.<br />
1. Penyelidikan kasus-kasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia masa<br />
lalu<br />
Terungkapnya berbagai tindak kejahatan hak<br />
asasi manusia pasca tumbangnya Soeharto<br />
berlanjut dengan munculnya tuntutan<br />
penyelidikan atas kejahatan-kejahatan tersebut<br />
di berbagai daerah. Dengan menyuarakan apa<br />
yang pernah mereka alami, kelompok korban<br />
menuturkan praktik-praktik pelanggaran hak<br />
asasi manusia di masa orde baru ke publik.<br />
Proses kesaksian inilah yang kemudian<br />
melahirkan gerakan untuk menyelidiki berbagai<br />
kejahatan hak asasi manusia di tanah air<br />
menguat di berbagai kota. Desakan penyelidikan<br />
yang semakin menguat inilah yang akhirnya<br />
membuat pemerintahan sementara pengganti<br />
Soeharto terpaksa melakukan penyelidikan atas<br />
sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.<br />
Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998<br />
adalah kasus pertama yang diselidiki oleh<br />
pemerintahan Habibie. Dimulai dengan<br />
membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta<br />
(TGPF) 5 , 23 Juli 1998, Habibie mengikuti<br />
keinginan sebagai besar penduduk Indonesia<br />
untuk menyelidiki berbagai dugaan tindak<br />
pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa<br />
tersebut. Dengan mandat menyelidiki penyebab<br />
kerusuhaan dan berbagai tindak perkosaaan dan<br />
serangan seksual terhadap perempuanperempuan<br />
etnis Cina di berbagai kota, TGPF<br />
bekerja kurang lebih tiga bulan terhitung Juli<br />
1998.<br />
TGPF kemudian menyimpulkan adanya<br />
tindak kejahatan hak asasi manusia dalam<br />
peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, serta<br />
menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah satu<br />
kerusuhan yang terencana dan sistematis. 6 Atas<br />
hasil kesimpulannya tersebut, TGPF<br />
merekomendasikan kepada presiden untuk<br />
segera mengambil langkah-langkah<br />
penyelidikan, dan langkah-langkah yuridis<br />
terhadap para pelaku kejahatannya, melakukan<br />
rehabilitasi dan pemberian kompensasi<br />
terhadap para korbannya. 7 Namun demikian,<br />
perlu dicatat bahwa hasil penyelidikan TGPF<br />
hingga saat ini belum digunakan pemerintah<br />
untuk dijadikan bahan awal ke tahap<br />
penyidikan. Sejumlah rekomendasi pun belum<br />
dilaksanakan hingga saat ini.<br />
Kasus kedua yang diselidiki oleh pemerintah<br />
adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia<br />
selama penerapan Daerah Operasi Militer<br />
(DOM) di Aceh dan pembunuhan Teungku<br />
Bantaqiah dan para santrinya, 23 Juli 1999.<br />
Terbongkarnya tindak kejahatan hak asasi<br />
manusia dan kejahatan perkosaan terhadap<br />
perempuan-perempuan Aceh selama penerapan<br />
DOM pertengahan 1998, melahirkan desakan<br />
penyelidikan atas kasus-kasus tersebut menguat<br />
di kalangan penduduk Aceh.<br />
Desakan inilah yang kemudian membuat<br />
Habibie mengeluarkan Keppres Nomor 88<br />
Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi<br />
Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di<br />
Aceh. Melalui Keppres tersebut Habibie<br />
memberikan mandat kepada komisi tersebut<br />
untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang berlangsung di Aceh selama<br />
penerapan DOM dan sekaligus menyelidiki<br />
Kasus penembakan dan Pembunuhan Teungku<br />
Bantaqiah dan pengikutnya di Beutong Ateh,<br />
Kabupaten Aceh Barat pada tangal 23 Juli 1999.<br />
Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa telah<br />
terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia<br />
pada masa penerapan DOM dan peristiwa<br />
penyerbuan militer ke pondok pesantren<br />
Teungku Bantaqiah. Atas dasar temuan tersebut<br />
Komisi memberikan rekomendasi kepada<br />
presiden agar segera meningkatkan status<br />
penyelidikan ke tahap penyidikan dan<br />
pengadilan. Sayangnya, rekomendasi yang<br />
dijalankan pemerintah hanya menggelar<br />
pengadilan kasus Teungku Bantaqiah dan<br />
penyiksaan sejumlah orang di kantor KNPI<br />
Banda Aceh.<br />
Peristiwa bumi hangus di Timor Timor pada<br />
masa Jajak Pendapat Pertengahan 1999, kembali<br />
memaksa pemerintah untuk membentuk tim<br />
penyelidikan atas dugaan kejahatan hak asasi<br />
manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia<br />
dengan bantuan kelompok-kelompok milisi<br />
bentukannya. Desakan yang kali ini tidak hanya<br />
datang dari dalam negeri, namun juga datang<br />
dari luar negeri, membuat pemerintah Habibie<br />
cukup tertekan dengan desakan tersebut.<br />
Akhirnya dengan menggunakan Undangundang<br />
Nomor 39 Tahun 1999 dan Perpu<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
9
Nomor 1 Tahun 1999, Komnas HAM<br />
membentuk tim penyelidikan untuk merespon<br />
tuntutan dari masyarakat luas tersebut. Dengan<br />
nama Komisi Penyelidik Peritiwa Pelanggaran<br />
Hak Asasi Manusia untuk Kasus Timor Timor<br />
(KPP-HAM Timor Timor) 8 , proses penyelidikan<br />
kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor<br />
Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai<br />
dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan<br />
Oktober 1999 yang mengesahkan hasil jajak<br />
pendapat mulai dijalankan.<br />
Penyelidikan meliputi pembuktian kejahatan<br />
genosida, pembunuhan massal, penganiayaan,<br />
pemindahan paksa, kekerasan terhadap<br />
perempuan dan anak-anak serta politik bumi<br />
hangus dan serta keterlibatan aparatur negara<br />
dan atau badan-badan lain dalam peristiwaperistiwa<br />
tersebut. Tim ini bekerja selama lima<br />
bulan, terhitung sejak September 1999. Dari<br />
hasil penyelidikan, KPP berkesimpulan bahwa<br />
telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia<br />
berat, dengan kategori kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan. Dan selanjutnya KPP juga<br />
memberikan 13 rekomendasi kepada<br />
pemerintah yang beberapa di antaranya adalah<br />
menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan;<br />
mengadili para pelaku secepat mungkin;<br />
merehabilitasi dan memberikan kompensasi<br />
kepada para korban. 9 Sayangnya, rekomendasi<br />
yang dijalankan hanya rekomendasi<br />
pembentukan pengadilan ad-hoc saja, dan itu<br />
pun baru dijalankan dua tahun setelah KPP<br />
HAM Timor Timor menyelesaikan kerjanya.<br />
Disahkannya Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi<br />
Manusia, membuat intensitas penyelidikan<br />
pelanggaran hak asasi manusia masa lalu oleh<br />
Komnas HAM terus meningkat. Berbagai<br />
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa<br />
lalu dan pasca 1999 pun satu demi satu mulai<br />
dilakukan. Diawali dengan pembentukan<br />
Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan<br />
Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, Komnas<br />
HAM kembali menjalankan tugasnya<br />
menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi<br />
manusia berat pada kasus tersebut. Dibentuk<br />
melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor<br />
002/Komnas HAM/III/2000 tanggal 8 Maret<br />
10 Bagian II
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
11
2000 dan kemudian disempurnakan melalui SK<br />
Ketua Komnas HAM Nomor 003/Komnas<br />
HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, KPP<br />
HAM kasus Tanjung Priok memiliki mandat<br />
menyelidiki sejumlah dugaan kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan dalam peristiwa<br />
pembantaian warga Tanjung Priok pada tahun<br />
1984. Dukungan yang luar biasa yang datang<br />
dari berbagai elemen masyarakat, membuat tim<br />
ini cukup leluasa untuk mengumpulkan<br />
sejumlah bukti-bukti, baik dari korban maupun<br />
keterangan dari sejumlah para perwira militer.<br />
Dukungan yang luar biasa inilah yang membuat<br />
KPP-HAM Tanjung Priok berhasil<br />
membuktikan adanya tindak kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan berikut menyerahkan<br />
daftar nama para para tersangkanya. Selanjutnya<br />
KPP HAM Tanjung Priok mengeluarkan<br />
beberapa rekomendasi yang salah satunya<br />
adalah meminta kepada presiden untuk segera<br />
membentuk pengadilan HAM ad hoc. 10 Namun<br />
seperti hasil rekomendasi KPP HAM lainnya,<br />
rekomendasi KPP HAM Tanjung priok ini,<br />
hanya rekomendasi pembentukan pengadilan<br />
saja yang dijalankan pemerintah.<br />
Sukses Komnas HAM dalam penyelidikan<br />
kasus Timor Timor dan Tanjung Priok tidak<br />
terulang kembali ketika menyelidiki kasus<br />
Trisakti-Semanggi I dan II (TSS) pertengahan<br />
2001. Keputusan politik DPR yang menyatakan<br />
bahwa ketiga kasus tersebut bukanlah peristiwa<br />
pelanggaran berat hak asasi manusia membuat<br />
para pelaku menolak untuk dimintai keterangan<br />
oleh Tim penyelidik yang dibentuk melalui<br />
Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/<br />
Komnas HAM/VII/2000 tanggal 27 Agustus<br />
2001. Akibatnya kinerja dari KPP HAM TSS ini<br />
menjadi sangat terbatas, sehingga sulit untuk<br />
mengakses dokumen-dokumen milik militer<br />
dan polisi. Sekalipun terjadi penolakan dari para<br />
pelaku, dengan mengumpulkan keterangan dari<br />
para korbannya akhirnya KPP HAM TSS<br />
berhasil membuktikan pelanggaran berat hak<br />
asasi manusia, dalam peristiwa penembakan<br />
mahasiswa di Kampus Trisakti dan Atmajaya.<br />
Namun kesimpulan ini kembali tidak<br />
berpengaruh apa-apa karena Kejaksaan Agung<br />
menolak untuk menindaklanjuti hasil<br />
penyelidikan Komnas HAM ke tingkat<br />
penyidikan dengan alasan berpijak pada<br />
statemen DPR tersebut.<br />
Penurunan dukungan politik terhadap Tim<br />
penyelidik kasus TSS, juga berimbas pada upaya<br />
Komnas HAM dalam penyelidikan kasus<br />
kerusuhan Mei 1998. Tim ad hoc Penyelidikan<br />
Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk<br />
melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor<br />
10.a/Komnas HAM/III/2003 tanggal 06 Maret<br />
2003, terbata-bata dalam melaksanakan<br />
tugasnya menyelidiki kasus pelanggaran berat<br />
hak asasi manusia dalam peristiwa kerusuhan<br />
13-15 Mei 1998. beberapa kesulitan mendasar<br />
adalah mendatangkan para perwira militer dan<br />
polisi yang diduga mengetahui latarbelakang<br />
peristiwa 13-15 Mei 1998 untuk dimintai<br />
keterangan serta mengakses dokumen milik<br />
militer dan polisi kala itu. Hingga laporan ini<br />
disusun tidak ada informasi lebih lanjut tentang<br />
hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Tim<br />
ad-hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei<br />
1998.<br />
Di samping menggunakan mekanisme pertanggungjawaban<br />
hak asasi manusia nasional,<br />
beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia<br />
di masa Soeharto juga diselidiki dengan<br />
mekanisme penyelidikan koneksitas atau<br />
mekanisme penyelidikan internal di institusi<br />
12 Bagian II
militer/Polri. Beberapa kasus itu antara lain<br />
adalah kasus Penyerangan kantor PDI pada 27<br />
Juli 1996, kasus pembunuhan Theis Hiyo Eluay,<br />
kasus penculikan aktivis-aktivis pro-demokrasi<br />
oleh Kopassus dan kasus penembakan<br />
mahasiswa Trisakti oleh satuan Brimob.<br />
Pasca reformasi, desakan pengusutan kembali<br />
kasus 27 Juli 1996 kembali menguat. Menyikapi<br />
desakan ini presiden Abdurrahman Wahid,<br />
menugaskan Mabes Polri untuk melakukan<br />
penyelidikan atas kasus ini. 11 Bekerja dengan<br />
cukup efektif dan cepat, Mabes Polri<br />
berkesimpulan telah terjadi tindak kriminal atas<br />
peristiwa ini. Kesimpulan ini didapat setelah<br />
melakukan pemeriksaan atas 106 saksi, dari<br />
kalangan sipil maupun militer. Polri juga<br />
menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam<br />
peristiwa tersebut. Namun demikian muncul<br />
kendala politis, kemudian Polri melakukan gelar<br />
perkara di Komisi I dan II DPR untuk mengatasi<br />
hambatan politis dan teknis yang dihadapinya.<br />
Selanjutnya hasil dari gelar perkara, Komisi I<br />
dan II DPR bertemu dengan Panglima TNI<br />
Widodo AS, Kapolri Rusdihardjo, Menhan<br />
Juwono Sudarsono, dan Menteri Kehakiman<br />
Yusril Ihza Mahendra untuk mencari jalan<br />
keluar atas kesulitan yang dihadapi Mabes Polri.<br />
Dari pertemuan tersebut diputuskan agar<br />
dibentuk Tim Penyidikan Koneksitas kasus 27<br />
Juli 1996 yang terdiri dari Puspom TNI dan<br />
Mabes Polri. 12 Tim ini sendiri dipimpin<br />
langsung oleh Komandan Korps Reserse<br />
(Dankorserse) Polri Inspektur Jenderal<br />
Chaeruddin Ismail dan Danpuspom Mayjend<br />
TNI Djasri Marin bertindak sebagai wakil. Tim<br />
ini mulai bekerja pada tanggal 19 Juli 2000<br />
dengan mengulang memeriksa saksi-saksi yang<br />
telah dilakukan Polri. 13<br />
Sayangnya, Tim Koneksitas bekerja sangat<br />
lamban dibandingkan dengan saat kasus<br />
ditangani Mabes Polri. Ini terlihat dari proses<br />
penyidikan yang baru selesai akhir 2001.<br />
Kelambatan proses penyidikan semakin<br />
diperparah ketika berkali-kali pihak Kejaksaan<br />
Agung mengembalikan berkas penyidikan<br />
dengan berbagai alasan. Hingga saat ini belum<br />
ada pengadilan independen yang digelar untuk<br />
mengadili para pelaku utama dalam kasus 27<br />
Juli 1996.<br />
Selain melakukan penyelidikan atas sejumlah<br />
pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu,<br />
upaya penyelidikan juga dilakukan terhadap<br />
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang<br />
terjadi pada periode 1999-2003. Berbagai kasus<br />
yang pernah diselidiki adalah, kasus pelanggaran<br />
hak asasi manusia di Papua/Irian Jaya, yang<br />
dibentuk melalui SK Ketua Komnas HAM No<br />
020/Komnas HAM/II/2001 tanggal 5 Februari<br />
2001, dengan nama tim penyelidik Komisi<br />
Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian<br />
Jaya. Selanjutnya adalah Tim Penyelidikan<br />
Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena,<br />
KPP-HAM kasus Bumi Flora Aceh, dan KPP<br />
HAM kasus kerusuhan Maluku dan Sampit.<br />
Dari berbagai kasus tersebut baru penyelidikan<br />
kasus Abepura saja yang telah dilimpahkan ke<br />
pengadilan, sementara kasus yang lain masih<br />
menumpuk di Kejaksaan Agung atau<br />
rekomendasinya tidak ditemukan indikasi<br />
pelanggaran berat hak asasi manusia.<br />
Di samping itu, satu kasus pelanggaran hak<br />
asasi manusia berat lain yang diselidiki tanpa<br />
menggunakan Undang-undang Nomor 39<br />
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 2000 adalah kasus pembunuhan Theis<br />
Hiyo Eluay, ketua Presidium Dewan Adat Papua,<br />
tahun 2002. Kasus ini diselesaikan melalui<br />
Komisi Penyelidik Nasional (KPN). Melalui<br />
Keppres Nomor 10 Tahun 2002, presiden<br />
menunjuk Koesparmono Irsan sebagai ketua<br />
KPN dengan sepuluh anggota lainnya yang<br />
terdiri dari Danpuspom TNI, dan unsur<br />
kepolisian serta tokoh-tokoh Papua. 14 Dari hasil<br />
penyelidikannya terungkap bahwa Theis Hiyo<br />
Eluay terbunuh akibat operasi intelejen yang<br />
digelar oleh Satuan Wirabuana dari Kopassus.<br />
Selanjutnya kasus ini disidangkan di pengadilan<br />
militer Surabaya. Tidak diketahui persis hukum<br />
yang dijatuhkan kepada para tersangkanya.<br />
Namun proses penyelidikan ini membuat kasus<br />
ini menjadi kasus pembunuhan biasa dan bukan<br />
kejahatan hak asasi manusia.<br />
2. Pembaharuan hukum dalam bidang<br />
hak asasi manusia<br />
Agenda pembaharuan hukum dalam bidang<br />
hak asasi manusia terdiri dari tiga bagian. Bagian<br />
pertama adalah mengamandemen sejumlah<br />
produk hukum nasional yang bertentangan<br />
dengan hak asasi manusia, kedua memproduksi<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
13
hukum hak asasi manusia dan ketiga adalah<br />
meratifikasi instrumen hak asasi manusia<br />
internasional. Sepanjang 1999-<strong>2004</strong><br />
pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan<br />
banyak pihak. Parlemen dan eksekutif terlihat<br />
sangat tidak produktif dan lamban. Bahkan dari<br />
beberapa regulasi hak asasi manusia baru, secara<br />
substansi sangat lemah dan kabur. Berikut ini<br />
capaian dari pelaksanaan agenda pembaharuan<br />
hukum dalam bidang hak asasi manusia:<br />
a. Produksi Regulasi Hak Asasi Manusia<br />
Implementasi agenda produksi regulasi hak<br />
asasi manusia dimulai dengan pengesahan<br />
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang<br />
Hak Asasi Manusia. 15 Kemudian pasca terjadinya<br />
pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur<br />
September 1999, pemerintah Abdurrahman<br />
Wahid kembali memproduksi regulasi hak asasi<br />
manusia yakni Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi<br />
Manusia. Sebelum undang-undang ini<br />
disahkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid<br />
juga pernah membuat satu Peraturan<br />
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor<br />
1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi<br />
Manusia. 16 Selanjutnya Undang-undang Nomor<br />
26 Tahun 2000 ini mengatur secara spesifik<br />
tentang yurisdiksi atas pengadilan HAM yaitu<br />
untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan<br />
kejahatan genosida. Rumusan tentang kejahatan<br />
genosida mendekati perumusan dalam Konvensi<br />
Anti Genosida sedangkan rumusan mengenai<br />
kejahatan kemanusiaan dalam undang-undang<br />
ini secara tegas mengacu pada Statuta Roma<br />
1998. Namun rumusan jenis kejahatan dalam<br />
undang-undang ini banyak mengandung<br />
kelemahan dan multi interpretatif karena tidak<br />
memasukkan elements of crimes yang akan<br />
menjadi landasan untuk menginterpretasikan<br />
pasal-pasal tersebut. Kritikan lainnya adalah<br />
tidak dimasukkannya kejahatan perang (war<br />
crimes) dalam yurisdiksi pengadilan HAM. 17<br />
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini juga<br />
memberikan pengaturan tentang perlindungan<br />
saksi dan korban dan pengaturan tentang<br />
jaminan reparasi kepada korban pelanggaran<br />
HAM yang berat serta ahli warisnya. Jaminan<br />
reparasi ini berupa adanya hak korban untuk<br />
mendapatkan kompensasi, restitusi dan<br />
rehabilitasi. Ketentuan secara lengkap untuk<br />
mengenai tata cara perlindungan saksi dan<br />
korban serta kompensasi, restitusi dan<br />
rehabilitasi kemudian dituangkan dalam<br />
Keppres Nomor 2 Tahun 2002 dan Keppres<br />
Nomor 3 Tahun 2002. 18<br />
Pasca penerbitan Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 2000, DPR selanjutnya tidak pernah<br />
membuat atau mengesahkan produk regulasi<br />
hak asasi manusia. Dan sebaliknya, DPR dan<br />
presiden secara bersama-sama banyak terlibat<br />
dalam pembuatan regulasi dan kebijakan yang<br />
bertentangan dengan hak asasi manusia. Baru di<br />
akhir masa kerjanya, DPR kembali<br />
memproduksi regulasi dalam bidang hak asasi<br />
manusia yakni mengesahkan Undang-undang<br />
Nomor 27 Tahun <strong>2004</strong> tentang Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi. 19 Undang-undang<br />
ini disahkan karena merupakan mandat yang<br />
diberikan MPR kepada presiden melalui TAP<br />
MPR Nomor V/MPR/2000 dan Undangundang<br />
Nomor 26 Tahun 2000. Undangundang<br />
ini sendiri mengatur tentang proses<br />
pencarian kebenaran pelanggaran HAM yang<br />
berat masa lalu melalui mekanisme extrajudicial.<br />
Dengan mandat mengungkap kebenaran<br />
atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia<br />
masa lalu, Komisi ini diharapkan mampu<br />
mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi<br />
manusia di masa lalu, termasuk juga<br />
mengungkap kejahatan-kejahatan rezim yang<br />
sengaja digelapkan dan tidak mampu<br />
diungkapkan di pengadilan. Undang-undang<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga<br />
mengatur tentang mekanisme kompensasi,<br />
restitusi dan rehabilitasi kepada korban dan juga<br />
permohonan amesti kepada pelaku. Persoalan<br />
amnesti inilah yang menjadi sasaran kritik dari<br />
berbagai pihak karena dianggap<br />
menguntungkan pelaku terlebih nasib korban<br />
akan reparasi kepada dirinya digantungkan<br />
kepada ada atau tidaknya amnesti kepada<br />
pelaku.<br />
b. Penghapusan Peraturan yang<br />
Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia<br />
Periode 1999-<strong>2004</strong> terdapat beberapa<br />
peraturan yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia dihapuskan tetapi jumlahnya tidak<br />
begitu banyak. Peraturan-peraturan tersebut<br />
14 Bagian II
adalah beberapa peraturan yang dibuat untuk<br />
melarang sebuah aktivitas tertentu ataupun<br />
ketentuan yang biasa digunakan untuk menjerat<br />
aktivitas politik misalnya undang-undang<br />
Subversi. Tercatat hanya dua undang-undang<br />
dan beberapa keppres yang mengatur tentang<br />
pencabutan regulasi yang bertentangan dengan<br />
HAM. Pencabutan pertama adalah pencabutan<br />
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985<br />
tentang Referendum dengan Undang-undang<br />
Nomor 6 Tahun 1999. Undang-undang tentang<br />
referendum ini dicabut karena dalam UUD 1945<br />
tidak ada ketentuan mengenai referendum dan<br />
telah ditentukan bahwa prosedur perubahan<br />
UUD telah ditentukan dalam UUD 1945. Di<br />
samping itu juga dijelaskan bahwa dengan<br />
dicabutnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1983<br />
tentang Referendum maka undang-undang<br />
yang mengatur tentang referendum ini juga<br />
harus dicabut. 20 Peraturan lainnya bahkan<br />
masih melanggengkan aturan-aturan yang<br />
melanggar HAM, terutama jika menyangkut<br />
kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota<br />
partai terlarang. Undang-undang Nomor 12<br />
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum misalnya<br />
masih melarang adanya pihak-pihak yang<br />
terlibat dalam partai terlarang untuk<br />
mendapatkan haknya sebagaimana warga<br />
negara yang lainnya. Tetapi undang-undang di<br />
atas dalam satu pasalnya yang melanggar HAM<br />
dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi setelah<br />
ada judicial review atas pasal tersebut. 21 Selain<br />
itu, undang-undang penting masa rezim lama<br />
yang akhirnya dihapus adalah Undang-undang<br />
Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan<br />
Kegiatan Subversi. Undang-undang Nomor 11/<br />
PNPS/1963 yang selama ini sering digunakan<br />
untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap<br />
berseberangan dengan pemerintah telah<br />
dihapuskan dengan Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 1999. Namun demikian pencabutan<br />
undang-undang ini kemudian dilanjutkan<br />
dengan undang-undang sejenis yang kembali<br />
menimbulkan protes dari banyak pihak. Akibat<br />
dari ini penundaan undang-undang sejenis ini<br />
menyebabkan Undang-undang Nomor 11/<br />
PNPS/1963 kembali digunakan oleh<br />
pemerintah sebagai pegangan. Penetapan Status<br />
Darurat Sipil di Maluku Juni 2000 dan Status<br />
Darurat Militer di Aceh Mei 2003, adalah bukti<br />
masih dipergunakannya Undang-undang<br />
Nomor11/PNPS/1963 di Indonesia. Terdapat<br />
satu undang-undang yang seharusnya bisa<br />
menjadi regulasi yang berfungsi untuk<br />
menghapus peraturan yang bertentangan<br />
dengan hak asasi manusia. Namun demikian,<br />
undang-undang belakangan justru<br />
meneguhkan peraturan yang melanggaran<br />
HAM. Undang-undang ini adalah Undangundang<br />
27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab<br />
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang<br />
Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap<br />
Keamanan Negara. Undang-undang ini masih<br />
mengatur tentang pelarangan penyebaran<br />
paham Marxisme dan Leninisme dan<br />
menambah beberapa hal yang termasuk<br />
kejahatan terhadap keamanan negara.<br />
Peraturan lainnya selama tahun 1999-<strong>2004</strong><br />
yang merupakan regulasi yang menghapuskan<br />
peraturan yang bertentangan dengan HAM<br />
diatur dalam beberapa keputusan presiden.<br />
Keppres-keppres ini pada umumnya mencabut<br />
berbagai pelarangan atas aktivitas-aktivitas<br />
tertentu. Keppres itu adalah Keppres Nomor 6<br />
Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi<br />
Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama,<br />
Kepercayaan dan Adat Istiadat China, Keppres<br />
Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan<br />
Keppres Nomor 16 Tahun 1990 Tentang<br />
Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri RI,<br />
Keppres Nomor 69 Tahun 2000tentang<br />
Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962<br />
tentang Larangan Adanya Organisasi Liga<br />
Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society,<br />
Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia),<br />
Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical<br />
Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan<br />
Organisasi Baha’i.<br />
c. Ratifikasi Hukum HAM Internasional<br />
Selama periode 1999 –<strong>2004</strong>, Indonesia telah<br />
meratifikasi salah satu konvensi penting yaitu<br />
Internasional Convention on the Elimination of<br />
All Forms of Racial Discrimination 1965<br />
(Konvensi International tentang Penghapusan<br />
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965).<br />
Konvensi ini disahkan dengan Undang-undang<br />
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan<br />
internasional Convention on the Elimination of<br />
All Forms of Racial Discrimination 1965. Secara<br />
umum konvensi ini berisi tentang penolakan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
15
terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala<br />
bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh<br />
pemerintah dan sebagian masyarakat,<br />
penghentian propaganda supremasi ras atau<br />
warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang<br />
harus diambil oleh negara-negara dalam<br />
penghapusan diskriminasi rasial.<br />
Program ratifikasi berbagai instrumen<br />
internasional penting lainnya tampaknya belum<br />
berhasil dilaksanakan terutama untuk konvensi<br />
hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi,<br />
sosial dan budaya. RAN-HAM periode 1998–<br />
2003 telah memprioritaskan beberapa<br />
instrumen yang akan diratifikasi yaitu Konvensi<br />
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik<br />
(konvensi sipol) beserta protokolnya; Konvensi<br />
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<br />
(konvensi ekosob); dan juga Konvensi<br />
Penghentian Perdagangan Manusia pada tahun<br />
2002, sedangkan tahun 2003 adalah Konvensi<br />
Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan<br />
Genosida; Konvensi Perbudakan; dan Konvensi<br />
Internasional Perlindungan Semua Pekerja<br />
Migran dan Anggota Keluarganya.<br />
Implementasi dari program RAN-HAM<br />
tentang ratifikasi ini adalah terhadap konvensi<br />
hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi<br />
sosial budaya akan dilakukan persiapan<br />
ratifikasi mulai tahun <strong>2004</strong> sesuai dengan RAN-<br />
HAM <strong>2004</strong>-2009. 22 Konvensi mengenai<br />
Penghentian Perdagangan Manusia, pemerintah<br />
mengeluarkan kebijakan mengenai trafficking<br />
dengan Keppres Nomor 88 tentang Rencana<br />
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking)<br />
Perempuan dan Anak.<br />
Konvensi Tentang Pencegahan dan<br />
Penghukuman Kejahatan Genosida sampai saat<br />
ini belum diratifikasi padahal sudah ada rencana<br />
untuk meratifikasi konvensi ini sejak tahun 2000<br />
dan pada perbaikan RAN-HAM periode 1998-<br />
2003 konvensi ini masih tetap menjadi prioritas.<br />
Terhadap Konvensi Perbudakan, Indonesia telah<br />
meratifikasi Konvensi Perbudakan ini dengan<br />
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang<br />
Pengesahan Konvensi International Labour Organization<br />
(ILO) Nomor 105 mengenai<br />
Penghapusan Kerja Paksa. Selain adanya<br />
ratifikasi Konvensi Anti Perbudakan, pada tahun<br />
2003 dikeluarkan produk perundang-undangan<br />
tentang ketenagakerjaan dengan Undangundang<br />
Nomor 13 Tahun 2003 tentang<br />
Ketenagakerjaan yang menjamin dilarangnya<br />
praktik perbudakan di Indonesia.<br />
Meski belum merativikasi konvensi<br />
internasional perlindungan semua perkerja<br />
migran dan anggota keluarganya sampai saat ini<br />
pemerintah belum melakukan ratifikasi tetapi<br />
pada tahun <strong>2004</strong> ini pemerintah telah<br />
mengeluarkan Undang-undang Nomor 39<br />
Tahun <strong>2004</strong> tentang Perlindungan Penempatan<br />
TKI di Luar Negeri/tentang Buruh Migran,<br />
namun undang-undang ini malah justru<br />
mengatur tentang tata organisasi penempatan<br />
buruh migran dan belum menyentuh aspekaspek<br />
perlindungan terhadap buruh migran.<br />
Selain berbagai macam konvensi yang<br />
diagendakan dalam RAN-HAM, pemerintah<br />
Indonesia juga telah melakukan pengesahan<br />
terhadap berbagai konvensi lainnya terutama<br />
adalah konvensi-konvensi dari ILO. Konvensikonvensi<br />
tersebut adalah Convention No. 138<br />
Concerning Minimum Age for Admission to Employment<br />
(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum<br />
Untuk Diperbolehkan Bekerja), Convention<br />
No. 111 Concerning Discrimination in Respect<br />
of Employment and Occupation (Konvensi<br />
ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan<br />
dan Jabatan) dan Convention No. 182 Concerning<br />
The Prohibition and Immediate Action for The<br />
Elimination of The Worst Forms of Child Labour<br />
(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan<br />
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk<br />
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 23<br />
3. Reformasi Institus TNI, Polri,<br />
Kejaksaan, dan Pengadilan<br />
Salah satu mandat dari agenda penegakan<br />
hak asasi manusia adalah reformasi institusi<br />
TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.<br />
Masuknya agenda ini merupakan pengamatan<br />
mendalam atas keterlibatan institusi-insitusi ini<br />
dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi<br />
manusia karena telah terkooptasi oleh<br />
kekuasaan Soeharto. 24 Atas dasar itu juga agenda<br />
reformasi ini dimulai menjadi tiga tahap besar,<br />
yakni mencakup pembuatan regulasi untuk<br />
membenahi wewenang, tugas dan hirarki<br />
komando, pembenahan struktur organisasi<br />
termasuk di sini menertibkan unit usaha milik<br />
militer dan Polri, dan penguatan atau<br />
16 Bagian II
pembenahan mekanisme pertanggungjawaban<br />
kriminal di institusi-institusi tersebut. 25<br />
a. Kepolisian, Militer dan Intelejen<br />
Lahirnya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000<br />
dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah<br />
menjadi landasan proses reformasi di tubuh TNI<br />
dan Polri. Dimulai dengan mengeluarkan<br />
sejumlah kebijakan dalam bentuk Keppres,<br />
pemerintahan Habibie dan Abdurrahman<br />
Wahid memulai reformasi di dua institusi ini<br />
dengan melakukan pemisahan antara TNI dan<br />
Polri. Keppres pemisahan ini kemudian<br />
diarahkan untuk ditingkatkan ke dalam bentuk<br />
undang-undang pada masa Abdurrahman<br />
Wahid. Namun karena kepemimpinan Wahid<br />
berhasil ditumbangkan oleh parlemen upaya ini<br />
pun terhenti. Naiknya Megawati menjadi<br />
presiden menggantikan Abdurrahman Wahid,<br />
kemudian lahir insiatif untuk melanjutkan<br />
proses reformasi di dua institusi tersebut.<br />
Namun demikian, begitu kuatnya penolakan<br />
kedua institusi tersebut untuk memberikan<br />
kepada sipil kewenangan merumuskan arah<br />
reformasi di dua institusi tersebut, membuat<br />
proses pembuatan undang-undang untuk kedua<br />
institusi ini berjalan lama dan masih<br />
mempertahankan nilai-nilai lama yang tentunya<br />
membahayakan proses demokratisasi dan hak<br />
asasi manusia di Indonesia. Akhirnya memasuki<br />
tahun 2002, Undang-undang Nomor 2 Tahun<br />
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<br />
26 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun<br />
2002 27 disahkan. Pasca pengesahannya,<br />
selanjutnya pemerintah menerbitkan beberapa<br />
peraturan lainnya yang berkaitan dengan<br />
institusi kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah<br />
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian<br />
Anggota Kepolisian Negara RI, Peraturan<br />
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang<br />
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara<br />
RI dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun<br />
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional<br />
Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian<br />
Negara RI. 28 Sayangnya proses pembuatan<br />
regulasi untuk TNI dan Polri tidak dilanjutkan<br />
dengan pembuatan regulasi untuk institusi<br />
intelejen. Institusi yang pada masa Soeharto juga<br />
kerap terlibat dalam pelanggaran hak asasi<br />
manusia ini, hingga saat ini belum memiliki<br />
undang-undang karena draft Rancangan<br />
Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh<br />
pemerintah masih mempertahankan cara-cara<br />
lama. Di samping itu, pasca penerbitan Undangundang<br />
Nomor 3 Tahun 2003, juga tidak<br />
dilanjutkan dengan menerbitkan undangundang<br />
tentang TNI sebagai konsekuensi<br />
perubahan yang harus dijalankan oleh institusi<br />
karena penerbitan undang-undang tersebut.<br />
Tanpa alasan yang jelas, pembuatan regulasi ini<br />
tertunda-tunda selama dua tahun. Setelah<br />
saling tarik-menarik antara TNI dengan politisi<br />
sipil yang mengkritisi sejumlah pasal-pasal<br />
bermasalah dalam draft RUU TNI, Undangundang<br />
Nomor 34 Tahun <strong>2004</strong> tentang Tentara<br />
Nasional Indonesia (TNI) diterbitkan. Dalam<br />
undang-undang ini didefinisikan secara jelas<br />
persoalan jati diri atau identitas TNI, yakni TNI<br />
sebagai tentara profesional. 29 Poin penting<br />
lainnya dari undang-undang ini adalah adanya<br />
pasal larangan bisnis oleh TNI dan hubungan<br />
antara TNI dengan otoritas sipil berkait dengan<br />
kedudukan TNI apakah berada di bawah<br />
departemen pertahanan atau langsung di bawah<br />
presiden. Sedangkan larangan bisnis oleh TNI<br />
dalam undang-undang ditegaskan bahwa<br />
penyerahan aset akan dilakukan dalam waktu<br />
lima tahun kepada pemerintah.<br />
Meskipun pencapaian di tingkat normatif<br />
untuk agenda pemisahan TNI dan Polri<br />
(dengan disahkannya undang-undang tentang<br />
TNI) telah dicapai, ternyata dalam<br />
implementasinya masih terdapat hambatanhambatan<br />
yang kembali berakibat langsung<br />
terhadap praktik-praktik pelanggaran hak asasi<br />
manusia. Di samping itu sejumlah pasal dalam<br />
regulasi tersebut, terutama khusus undangundang<br />
Pertahanan dan TNI, terdapat<br />
kelemahan-kelemahan subtansial yang masih<br />
akan mengancam hak asasi manusia<br />
penduduk. 30 Sepanjang proses pemisahan ini<br />
ternyata juga tidak mampu mengurangi<br />
keterlibatan TNI dan Polri dalam peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya,<br />
kedua Institusi masih terlibat dalam peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia. 31 Di samping itu<br />
agenda reformasi di lingkungan internal juga<br />
berjalan lambat, dan mencapai titik terendahnya<br />
memasuki <strong>2004</strong> ini. Berbeda dengan masa awalawal<br />
di mana reformasi internal dimulai dengan<br />
menghapuskan jabatan Kastaf Sospol dan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
17
kemudian melarang perwira-perwira aktif<br />
menjabat jabatan di pemerintahan. Kondisi saat<br />
ini, niatan dari institusi TNI untuk melanjutkan<br />
reformasi di lingkungan internal mulai<br />
melemah. Kesadaran awal tentang perlunya<br />
menghapuskan Komando Teritorial (KOTER),<br />
sebagai bagian dari keinginan meningkatkan<br />
profesionalitasnya, belum berjalan, dan bahkan<br />
cenderung diperkuat kembali. 32 Upaya untuk<br />
menghilangkan watak bisnis di kalangan<br />
perwiranya, nampak belum berjalan, padahal ini<br />
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34<br />
Tahun <strong>2004</strong>.<br />
Banyaknya praktik-praktik pelanggaran hak<br />
asasi manusia oleh TNI dan Polri pada periode<br />
reformasi, tidak dengan sendirinya membuat<br />
pemerintah segera membenahi mekanisme pertanggungjawaban<br />
internal dan memaksa kedua<br />
institusi tersebut tunduk pada hukum hak asasi<br />
manusia nasional yang berlaku. Pemerintahan<br />
sipil nampak lemah ketika berhadapan dengan<br />
dua institusi ini. Hingga saat ini hanya Institusi<br />
kepolisian yang melakukan proses pembenahan<br />
mekanisme internal, meskipun pembenahannya<br />
belum mampu menyeret para pelaku yang<br />
berasal dari kalangan perwira. Sementara di internal<br />
TNI dan Intelejen, undang-undang<br />
peradilan militer dan kitab undang-undang<br />
hukum pidana militer serta pengadilan militer<br />
di institusi ini belum berubah, sehingga<br />
mengakibatkan proses reformasi di tubuh TNI<br />
belum bisa sepenuhnya berjalan. Meski ada<br />
upaya penghukuman terhadap sejumlah pelaku<br />
pelanggaran hak asasi manusia, namun<br />
demikian proses ini hanya dikenakan kepada<br />
para prajurit kalangan bawah, dan lebih jauh<br />
lagi menutup mata rantai pelaku di level<br />
perwira. 33<br />
b. Reformasi di Institusi Peradilan<br />
Reformasi di institusi peradilan menjadi<br />
agenda penting untuk dilaksanakan ketika<br />
melihat dalam praktiknya pada masa lalu<br />
institusi ini menjadi alat untuk memperkuat<br />
atau hanya dijadikan alat kekuasaan. Insitusi<br />
peradilan juga menjadi dasar legitimasi<br />
penguasa masa lalu untuk membungkam atas<br />
segala aktivitas yang bersuara kritis terhadap<br />
penguasa. Gagasan awal atas proses reformasi di<br />
institusi ini adalah dengan mengemukakan<br />
gagasan peradilan satu atap di bawah<br />
Mahkamah Agung. Gagasan ini dipilih karena<br />
dipandang mampu mensterilkan segala<br />
instrumen pengadilan dari upaya-upaya<br />
kooptasi kekuasaan. Selanjutnya untuk<br />
mendukung gagasan ini maka dibuat Undangundang<br />
Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian<br />
dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 4<br />
Tahun <strong>2004</strong> tentang Kekuasaan Kehakiman 34<br />
untuk memperkuat kemandirian dan kekuasaan<br />
kehakiman. Dalam undang-undang yang<br />
disebutkan terakhir ini ditegaskan tentang<br />
prinsip-prinsip kemandirian pengadilan dan<br />
proses pengadilan yang adil dan tidak memihak<br />
dan undang-undang ini juga mengatur tentang<br />
kewenangan-kewenangan lembaga peradilan.<br />
Undang-undang yang menggantikan Undangundang<br />
Nomor 14 Tahun 1970 tentang<br />
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan<br />
Kehakiman ini juga menyatakan bahwa<br />
lingkungan peradilan umum dikeluarkan dari<br />
Departemen Kehakiman Republik Indonesia<br />
dan memindahkannya ke Mahkamah Agung<br />
Republik Indonesia dengan masa transisi paling<br />
lama 5 (lima) tahun. Dengan ketentuan ini<br />
depertemen Hukum dan HAM ini tidak lagi<br />
mempunyai kekuasaan terhadap peradilan<br />
umum. Hal ini menyebabkan intervensi<br />
pemerintah atas institusi pengadilan berkurang.<br />
Reformasi di institusi pengadilan ini juga<br />
menyentuh institusi kejaksaan dan lembaga<br />
Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 5<br />
Tahun <strong>2004</strong> tentang Perubahan Atas Undangundang<br />
Nomor 14 Tahun 1985 tentang<br />
Mahkamah Agung. Undang-undang ini<br />
mengatur tentang kedudukan Mahkamah<br />
Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,<br />
syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi<br />
hakim agung, serta beberapa subtansi yang<br />
menyangkut hukum acara, khususnya dalam<br />
melaksanakan tugas dan kewenangan dalam<br />
memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi<br />
serta dalam melakukan hak uji materiil terhadap<br />
peraturan perundang-undangan di bawah<br />
undang-undang. Pembaharuan di tubuh<br />
kejaksaan juga dilakukan dengan<br />
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16<br />
Tahun <strong>2004</strong> tentang Kejaksaan Republik Indonesia<br />
yang mengatur tentang lembaga kejaksaan<br />
termasuk berkaitan dengan tugas dan<br />
kewenangannya. Dalam undang-undang ini<br />
18 Bagian II
tugas utama Kejaksaan adalah melakukan<br />
proses penuntutan terhadap tindak pidana<br />
untuk melindungi kepentingan umum.<br />
Meskipun terjadi perubahan yang cukup<br />
maju, namun demikian proses reformasi di<br />
institusi peradilan masih sulit untuk dijalankan<br />
di tataran praktis. Berbagai persoalan<br />
pelaksanaannya seperti belum adanya upaya<br />
sinkronisasi beberapa regulasi lain yang<br />
bertabrakan dengan regulasi satu atap ini<br />
membuat regulasi baru ini sulit diterapkan<br />
sepenuhnya. Di samping itu munculnya<br />
penolakan yang kuat dari institusi-institusi yang<br />
terkena proses reformasi ini membuat proses<br />
pelaksanaannya tertunda-tunda dan dijalankan<br />
setengah hati. Persoalan lainnya adalah kapasitas<br />
hakim, jaksa yang masih terbatas untuk<br />
menjalankan tugas dan fungsi baru yang<br />
diamanatkan oleh undang-undang baru. Ini<br />
terlihat dalam proses pengadilan sepanjang<br />
tahun 1999-<strong>2004</strong> yang mana masih dipengaruhi<br />
oleh kepentingan politik serta tidak mampu<br />
melepaskan diri dari pengaruh eksekutif.<br />
Pengadilan koneksitas kasus 27 Juli 1996 yang<br />
digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<br />
merupakan contoh konkrit bagaimana<br />
pengadilan diciptakan untuk tujuan yang tidak<br />
sesuai dengan kenyataannya. Kegagalan<br />
pengadilan HAM ad hoc baik kasus Timor<br />
Timur maupun Tanjung Priok bukti lain<br />
tentang belum bebasnya institusi-institusi<br />
peradilan dari intervensi kekuasaan. Kapasitas<br />
hakim sangat lemah dalam menghadapai<br />
regulasi-regulasi yang baru. Di samping itu,<br />
Pendidikan hakim yang tidak berjalan pararel<br />
dengan perkembangan regulasi menyebabkan<br />
para hakim cenderung gagap untuk<br />
menerapkan regulasi baru, terlebih jika tidak<br />
ada petunjuk dari otoritas yang lebih tinggi<br />
(MA) tentang sebuah regulasi tertentu.<br />
Kebingunan hakim dalam menyikapi regulasi<br />
ternyata berimbas pada pemberian keadilan bagi<br />
korban. 35 Faktor lainnya adalah buruknya<br />
administrasi peradilan. Hal ini terlihat dari akses<br />
publik terhadap informasi perkembangan<br />
sebuah kasus ke pengadilan yang masih tertutup.<br />
Masalah administrasi pengadilan selama lima<br />
tahun terakhir atau paling tidak jika dilihat<br />
berdasarkan progressivitas penanganan kasus<br />
tidak ada perkembangan. Masalah-masalah<br />
yang sama selalu muncul dalam setiap<br />
penanganan perkara akibat dari lemahnya<br />
administrasi pengadilan. Jadual sidang yang<br />
tidak jelas baik mengenai waktu dan tempat,<br />
seringnya penundaan sidang, dan tidak jelasnya<br />
informasi mengenai perkembangan sebuah<br />
kasus di pengadilan adalah problem-problem<br />
klasik yang muncul akibat tidak berjalannya<br />
pembenahan administrasi pengadilan.<br />
Hal ini semakin lengkap ketika institusi<br />
Kejaksaan Agung menolak untuk mereformasi<br />
diri. Posisi Jaksa Agung yang masih berada di<br />
bawah eksekutif membuat institusi ini semakin<br />
menjauhkan diri dari upaya-upaya kemandirian<br />
kejaksaan. Di samping itu, masih kuatnya<br />
pengaruh pimpinan/atasan dalam institusi<br />
kejaksaan semakin meneguhkan bahwa lembaga<br />
ini belum mampu keluar dari watak militeristik<br />
warisan rezim lama. 36 Penanganan perkara yang<br />
harus selalu dikonsultasikan dengan atasan,<br />
bahkan dalam rencana penuntutan terhadap<br />
seorang terdakwa harus meminta persetujuan<br />
dari atasan, menyebabkan kinerja kejaksaan<br />
masih sarat dengan intervensi kekuasaan. Tidak<br />
gigihnya jaksa dalam melakukan pembuktian<br />
untuk membuktikan surat dakwaan adalah satu<br />
bukti bahwa masih adanya unsur intervensi<br />
yang besar terhadap institusi kejaksaan maupun<br />
para jaksa yang sedang bertugas. 37 Kegagalan<br />
penanganan kasus pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang berat dalam beberapa pengadilan,<br />
menunjukkan adanya sejumlah persoalan<br />
lemahnya kapasitas/kompetensi di kalangan<br />
para jaksa. Sistem rekruitmen yang buruk,<br />
pendidikan jaksa yang tidak memadai dan<br />
minimnya program peningkatan kualitas jaksa<br />
disinyalir sebagai penyebab rendahnya kualitas<br />
jaksa.<br />
c. Reformasi Departemen Kehakiman dan<br />
Hak Asasi Manusia<br />
Di samping mereformasi institusi peradilan,<br />
proses reformasi ini juga diarahkan ke<br />
Departemen Hukum dan HAM, karena<br />
departemen yang sebelumnya bernama<br />
Departemen kehakiman ini dahulunya<br />
merupakan perpanjangan tangan dari ekskutif,<br />
yakni mengatur hakim dan sampai tahap mutasi<br />
hakim yang tidak mengikuti kemauan penguasa.<br />
Atas dasar inilah kemudian sejumlah<br />
kewenangan Departemen hukum dan HAM<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
19
yang bermasalah dihapuskan. Untuk<br />
selanjutnya, lembaga ini mempunyai<br />
Kewenangan (a) Pengaturan dan pembinaan<br />
terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan<br />
kenotariatan; (b) Pengaturan dan pembinaan<br />
terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara<br />
dan barang rampasan negara, peradilan,<br />
penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia,<br />
perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan<br />
ketatanegaraan dalam bidangnya dan<br />
kewarganegaraan; (c) Peraturan dan pembinaan<br />
di bidang daktoloskopi, grasi, amnesti, abolisi,<br />
rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil;<br />
dan (d) Penerapan perlindungan, pemajuan,<br />
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.<br />
Sayangnya meskipun telah dilakukan reposisi<br />
atas kewenangan dan tugasnnya, karena<br />
keterbatasan sumber daya manusia, departemen<br />
ini lambat untuk menjalankan wewenang baru<br />
tersebut, termasuk di sini memotori pelaksanaan<br />
agenda penegakan hak asasi manusia nasional. 38<br />
4. Penghukuman: Proses Peradilan Atas<br />
Hasil Penyelidikan KPP HAM, Tim<br />
Koneksitas dan Komisi Nasional<br />
Penyelidik<br />
Selama periode 1999-<strong>2004</strong> telah digelar tiga<br />
20 Bagian II
pengadilan hak asasi manusia. Dua pengadilan<br />
yang sifatnya ad hoc dan satu pengadilan yang<br />
permanen. Pengadilan HAM ad hoc kasus<br />
pelanggaran HAM di Timor Timur dan<br />
Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok digelar<br />
berdasarkan Keppres Nomor 53 Tahun 2001<br />
yang kemudian diperbaharui oleh Keppres<br />
Nomor 96 Tahun 2001. 39 Sedangkan pengadilan<br />
HAM yang sifatnya permanen, karena<br />
peristiwanya terjadi setelah disahkannya<br />
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah<br />
pengadilan HAM untuk kasus Pelanggaran<br />
HAM yang berat di Abepura/Papua. 40 Selain itu<br />
ada juga beberapa kasus yang diadili dengan<br />
mekanisme pengadilan koneksitas maupun<br />
militer. Berikut ini uraian proses peradilan<br />
kasus-kasus.<br />
a. Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
i. Pengadilan HAM ad hoc Kasus pelanggaran<br />
HAM di Timor Timur<br />
Sejak<br />
a w a l<br />
persidangan<br />
pengadilan<br />
H A M<br />
Timortimur,<br />
pesimisme<br />
terhadap<br />
keberhasilan pengadilan muncul disebabkan<br />
surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat<br />
lemah. Jaksa penuntut umum juga ternyata<br />
hanya mengajukan terdakwa berjumlah 18 orang<br />
yang terdiri 10 orang dari militer, 4 orang<br />
dari polisi dan 4 orang dari sipil. Jumlah<br />
terdakwa yang diajukan ini jauh lebih kecil<br />
daripada rekomendasi hasil penyelidikan<br />
Komnas HAM yang juga merekomendasikan<br />
untuk mengajukan pelaku lapangan dan<br />
perwira tinggi militer. Tuntutan pidana yang<br />
diajukan oleh jaksa pada akhirnya juga tidak<br />
pernah cukup maksimal dan terkesan<br />
dipaksakan. Dalam pengadilan HAM ad hoc<br />
Timor Timur tuntutan pidana kepada para<br />
terdakwa paling tinggi 10 tahun 6 bulan sampai<br />
10 tahun dan terdapat satu terdakwa yang<br />
bahkan di tuntut bebas. Substansi tuntutan jaksa<br />
tidak begitu memuaskan dalam artian tidak<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
cukup bisa memperkuat surat dakwaan dan<br />
terkesan dibuat seadanya dan hal ini berbeda<br />
misalnya dengan pembelaan/pledooi yang<br />
diajukan oleh terdakwa dan penasehat<br />
hukumnya. Di tingkat banding, putusan<br />
terhadap kasus pelanggaran HAM di Timor<br />
Timur yang tak terpantau oleh publik ini<br />
ternyata menghasilkan putusan yang semakin<br />
meneguhkan bahwa pengadilan ini telah gagal.<br />
Dari 6 orang yang dinyatakan bersalah di tingkat<br />
pertama hanya 2 yang tetap dinyatakan bersalah<br />
yang dua-duanya dari sipil, satu terdakwa tetap<br />
dengan hukuman yang sama dan satu lagi<br />
mengalami pengurangan hukuman dari 10<br />
tahun menjadi 5 tahun. Bebasnya para terdakwa<br />
yang berasal dari militer dan kepolisian ini<br />
mengakibatkan sejumlah pertanyaan yang<br />
mengarah pada tuduhan bahwa pengadilan ini<br />
hanya akan meng-kambinghitam-kan terdakwa<br />
dari sipil.<br />
ii. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok<br />
Pengadilan HAM Tanjung Priok juga<br />
mengalami hal yang sama di mana hanya<br />
anggota militer sampai tingkat komandan<br />
Kodim dan Kapomdam yang diajukan ke<br />
pengadilan sementara hasil penyelidikan<br />
Komnas HAM merekomendasikan perwira di<br />
atas Komandan Kodim yaitu Pangdam dan<br />
Panglima ABRI. Kondisi yang sama juga terlihat<br />
dalam tuntutan terhadap para terdakwa yang<br />
diajukan oleh jaksa dalam pengadilan HAM ad<br />
hoc Tanjung Priok. Para jaksa tampak setengah<br />
hati dalam melakukan tuntutan kepada para<br />
terdakwa, perkecualian dalam pengadilan ini<br />
adalah dicantumkannya tuntutan mengenai<br />
kompensasi kepada korban dalam surat<br />
dakwaan meskipun hal ini merupakan desakan<br />
oleh korban. Pengadilan ini memberikan<br />
putusan putusan antara 3 tahun sampai dengan<br />
2 tahun terhadap 11 terdakwa yang merupakan<br />
pelaku lapangan dan 10 tahun kepada seorang<br />
terdakwa. Tidak begitu jelas bagaimana<br />
pengadilan memutuskan hukuman yang<br />
berbeda dan jauh menyimpang dari ketentuan<br />
undang-undang.<br />
iii. Pengadilan HAM untuk kasus Pelanggaran<br />
HAM yang berat di Abepura/Papua<br />
Pengadilan HAM Abepura justru lebih parah<br />
21
dengan hanya mengajukan dua terdakwa yaitu<br />
komandan Brimob dan Kapolres padahal hasil<br />
penyelidikan Komnas HAM menyebut pelaku<br />
lapangan dan Kapolda sebagai pihak yang juga<br />
bisa dimintai pertanggungjawaban. Hingga<br />
laporan ini dibuat, proses persidangan untuk<br />
kasus ini sedang berjalan, sehingga belum<br />
diketahui persis hasilnya.<br />
b. Pengadilan Koneksitas dan Pengadilan<br />
Militer<br />
Selain beberapa pengadilan HAM tersebut di<br />
atas, selama 1999-<strong>2004</strong> juga terjadi beberapa<br />
pengadilan terhadap kasus-kasus yang<br />
melibatkan aparat negara dan berindikasi kuat<br />
terjadi pelanggaran HAM yang berat. Kasuskasus<br />
ini tidak diselesaikan melalui Pengadilan<br />
HAM tetapi dengan Pengadilan Koneksitas dan<br />
Pengadilan Militer.<br />
i. Pengadilan Koneksitas Teungku Bantaqiah<br />
Kasus pembunuhan terhadap Teungku<br />
Bantaqiah dan pengikutnya dilaksanakan<br />
dengan menggunakan pengadilan koneksitas<br />
berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan<br />
Negeri Banda Aceh tanggal 14 April 2000<br />
Nomor 21/Pen.Pid/2000/PN-BNA. Digelarnya<br />
peradilan koneksitas didasarkan pada adanya<br />
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal<br />
13 April 2000 Nomor Register Perkara PDM-02/<br />
MLBH/4/2000. Dalam persidangan koneksitas<br />
yang digelar di Pengadilan Negeri Tingkat I<br />
Banda Aceh berkaitan dengan kasus<br />
penembakan terhadap Teungku Bantaqiah dan<br />
56 penduduk sipil lainnya, Jaksa Penuntut<br />
Umum mengajukan 25 orang terdakwa, 24 orang<br />
tentara dan satu orang sipil, telah dengan<br />
sengaja menghilangkan jiwa orang lain tanpa<br />
bukti-bukti yang jelas atas tuduhan kepada<br />
korban sebagai anggota GPK Aceh. Dakwaan<br />
dibuat secara berlapis yang bersifat komulatif.<br />
Artinya bahwa JPU menyusun dakwaan dari<br />
tindak pidana yang terberat berkaitan dengan<br />
penghilangan nyawa, yakni pembunuhan<br />
(moord) yang direncanakan, sampai yang<br />
teringan yakni kelalaian yang mengakibatkan<br />
kematian. Putusan Majelis Hakim menyatakan<br />
bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah<br />
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak<br />
pidana pembunuhan yang direncanakan<br />
terlebih dahulu yang dilakukan secara<br />
melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1<br />
KUHP sebagaimana didakwakan dalam<br />
dakwaan primer dan oleh karena itu dibebaskan<br />
dari dakwaan Primer. Tetapi pengadilan<br />
menyatakan para terdakwa telah terbukti<br />
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan<br />
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan<br />
secara bersama-sama, melanggar Pasal 338 jo<br />
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana<br />
didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Ke-25<br />
terdakwa dijatuhi hukuman antara 6 tahun<br />
sampai dengan 10 Tahun.<br />
ii. Pengadilan Militer Kasus Trisaksi<br />
Kasus penembakan terhadap mahasiswa<br />
Trisaksi disidangkan dalam pengadilan militer di<br />
Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Terdapat 18<br />
terdakwa di mana dua terdakwa Letnan Agus Tri<br />
Heryanto dan Letnan Pariyo disidangkan<br />
pertama kali. Para terdakwa lainnya yang<br />
diajukan dalam pengadilan adalah Komandan<br />
Kompi Brimob Polda Metro Jaya Lettu (Pol)<br />
Wandi Rustiawan, Komandan Kompi Korps<br />
Brimob Polri Lettu (pol) Sriyadi, Komandan<br />
Pleton Korps Brimob Polri Letda (Pol) Basya<br />
Radyananda dan Koordinator URC Polda Metro<br />
Jaya Letda (Pol) Achmad Hadi. Terdakwa<br />
lainnya yang disidangkan secara terpisah adalah<br />
11 terdakwa, namun 2 di antaranya tidak dapat<br />
menghadiri persidangan karena meninggal<br />
dunia dan desersi. Mahkamah Militer (Mahmil)<br />
II-08 Jakarta, sejak 18 Juni 2001 telah<br />
menyidangkan kasus penembakan mahasiswa<br />
Trisakti 12 Mei 1998. Mahmil akan mengadili 11<br />
anggota aparat keamanan dari pangkat<br />
golongan tamtama, bintara, dan perwira sebagai<br />
terdakwa, dengan saksi 35 orang dari berbagai<br />
kalangan, termasuk dari Civitas Akademika<br />
Universitas Trisakti. Akhirnya aktor-aktor di<br />
lapangan itu pun dijatuhi hukuman. Sembilan<br />
anggota Brimob dituntut hukuman antara 1,5<br />
tahun hingga 3 tahun penjara dan dipecat dari<br />
Polri.<br />
iii. Pengadilan Militer Kasus Theys Eluay<br />
Pasca penyelidikan KPN, berkas hasil<br />
penyelidikian kemudian dilimpahkan ke<br />
Makamah Militer Surabaya dengan mengajukan<br />
22 Bagian II
4 tersangka. Sidang dibagi dalam dua berkas<br />
perkara di mana berkas pertama terdiri dari<br />
Letnan Kolonel Hartomo (40), Kapten Infantri<br />
Rionardo (32), Sersan Satu Asrial (31), dan<br />
Praka Ahmad Zulfahmi (27) dan berkas kedua<br />
terdiri dari Mayor Infantri Donny Hutabarat<br />
(35), Letnan Satu Agus Soepriyanto (31), dan<br />
Sersan Satu Lauren SL (28). Ketujuh terdakwa<br />
dikenai dakwaan primer Pasal 338 KUHP<br />
tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa<br />
orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan<br />
ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 351<br />
KUHP Ayat (3) tentang penganiayaan yang<br />
berakibat matinya orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-<br />
1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun<br />
penjara. Para terdakwa pada akhirnya di vonis<br />
antara 2 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Letkol<br />
Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agoes<br />
Supriyanto dan Praka Achmad Zulfahmi di<br />
mana mereka terbukti menganiaya hingga tewas<br />
Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys<br />
Hiyo Eluay dengan pemecatan Sedangkan<br />
Rionardo dan Sertu Asrial serta Laurensius<br />
diganjar hukuman 3 tahun dan 2 tahun penjara.<br />
Ketiganya tidak dipecat, dan masih tetap dapat<br />
bertugas di lingkungan TNI-AD. Putusan ini<br />
sontak mengejutkan berbagai kalangan karena<br />
ternyata para pelaku tersebut dijatuhi hukuman<br />
yang sangat ringan dan tuntutan untuk<br />
pembentukan KPP HAM oleh Komnas HAM<br />
terhadap kasus ini semakin menguat. Pendapat<br />
berbeda justru datang dari institusi militer<br />
sendiri yang menyatakan bahwa para terdakwa<br />
ini adalah pahlawan karena membunuh<br />
pemimpin pemberontak dan hukuman itu<br />
untuk menyudutkan TNI. Bahkan Kepala Staff<br />
TNI AD menyatakan bahwa seharusnya<br />
tindakan para terhukum itu dibenarkan karena<br />
Theys secara terang-terangan berani menentang<br />
negara dengan mengibarkan bendera Papua<br />
merdeka, Bintang Kejora. 41<br />
iv. Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996<br />
Pengadilan terhadap kasus 27 Julii 1996<br />
dilakukan dengan Pengadilan Koneksitas.<br />
Pengadilan ini digelar di Pengadilan Jakarta<br />
Pusat mulai tanggal 23 Juni 2003 sampai tanggal<br />
30 Desember 2003. Para terdakwa yang diajukan<br />
ke pengadilan di dakwa dengan surat dakwaan<br />
Nomor: PDM/242/JKT.PTS/05/2003 tanggal 19<br />
Mei 2003 dengan susunan Primair Pasal 170<br />
ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1)<br />
KUHP dan lebih subsidair Pasal 406 jo Pasal 55<br />
ayat (1) ke-1 KUHP. Namun terjadi perubahan<br />
yang dilakukan JPU sehingga dalam uraian<br />
surat dakwaan yang disusun JPU, para terdakwa<br />
telah didakwa — secara bersama-sama —<br />
dengan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-<br />
1 KUHP, dan subsidair-nya Pasal 170 ayat (1)<br />
KUHP. Dengan dakwaan ini para terdakwa<br />
didakwa melakukan pengrusakan terhadap<br />
benda dan penganiayaan. Dalam berkas tersebut<br />
di antaranya terdapat enam tersangka yang<br />
diajukan, yaitu: Kolonel CZI (Purn.) Budi<br />
Purnama (mantan Dan Den Intel Kodam Jaya),<br />
Kapten Suharto (Mantan Dan BKI-C Den Intel<br />
Kodam Jaya), Muhammad Tanjung, Jonathan<br />
Marpaung Panahatan, Muhammad Ilyas alias<br />
Buyung, dan Djoni Moniaga alias Jojon. pada<br />
waktu sidang pertama (hari Senin 23 Juni 2003)<br />
— di saat JPU diperintahkan Majelis Hakim<br />
untuk menghadirkan terdakwa — ternyata<br />
salah seorang terdakwa yang bernama Djoni<br />
Moniaga telah meninggal dunia. Meninggalnya<br />
terdakwa Djoni Moniaga baru diketahui JPU<br />
tiga hari sebelum hari sidang pertama. Putusan<br />
pengadilan akhirnya hanya mampu<br />
menghukum beberapa terdakwa sedangkan<br />
yang lainnya bebas. Terdakwa I, II, III dan V<br />
berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang<br />
didakwakan dinyatakan tidak terbukti dan oleh<br />
karenanya harus dibebaskan dari semua<br />
dakwaan dan dikembalikan nama baiknya.<br />
Sedangkan untuk terdakwa IV, karena telah<br />
mengumpulkan massa untuk pengambilalihan<br />
kantor DPP PDI, melakukan pelemparan dan<br />
mengakibatkan orang dan barang rusak, maka<br />
dia dinyatakan terbukti secara sah dan<br />
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,<br />
melakukan kekerasan barang dan orang di<br />
muka umum. Selanjutnya majelis hakim<br />
menghukum Terdakwa IV dengan pidana<br />
penjara 2 bulan dan 10 hari yang dikurangi<br />
dengan penahanan yang telah dijalaninya<br />
sebelum keputusan mempunyai kekuatan tetap.<br />
5. Reparasi Korban: Hak Atas<br />
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi<br />
Hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi<br />
diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
23
2000 dalam Pasal 35 dan kemudian tata cara<br />
pelaksanaanya diatur dalam Peraturan<br />
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang<br />
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan<br />
Rehabilitasi Kepada Korban Pelanggaran HAM<br />
yang Berat. Regulasi ini memberikan jaminan<br />
bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia<br />
mendapatkan hak reparasi atas terjadinya<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang berat<br />
kepada mereka. Tiga pengadilan hak asasi<br />
manusia yang telah berjalan ternyata belum<br />
satupun yang berhasil memberikan hak-hak<br />
reparasi kepada korban dalam tahap<br />
implementasi. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung<br />
Priok yang merupakan satu-satunya pengadilan<br />
yang memberikan putusan kompensasi kepada<br />
korban belum berhasil diimplementasikan<br />
karena masih ada hambatan prosedural. Korban<br />
pelanggaran HAM Tanjung Priok akhirnya<br />
mendapatkan putusan dari majelis hakim untuk<br />
mendapatkan kompensai dalam dua putusan, di<br />
mana satu putusan hanya menyatakan bahwa<br />
korban mendapatkan kompensasi sedangkan<br />
satu putusan lainnya dengan disertai jumlah<br />
kompensasi yang akan diterima oleh para<br />
korban.<br />
Putusan kompensasi di atas dalam<br />
pelaksanaanya terhambat karena secara<br />
normatif di mana eksekusi putusan tersebut<br />
hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan<br />
pengadilan yang bersifat tetap. Artinya<br />
kompensasi akan diterima oleh korban pada saat<br />
terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat<br />
Mahkamah Agung, sebaliknya jika ternyata<br />
terdakwa dibebaskan di tingkat banding atau<br />
Mahkamah Agung maka kompensasi tersebut<br />
akan gugur. Hal ini karena konsep kompensasi<br />
kepada korban menggantungkan faktor<br />
kesalahan dari terdakwa dan bukan karena hak<br />
yang melekat terhadap setiap korban<br />
pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda dengan<br />
pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok,<br />
pengadilan HAM ad hoc Timor Timur tidak ada<br />
satupun keputusan mengenai kompensasi,<br />
restitusi maupun rehabilitasi kepada korban.<br />
Sampai putusan dibacakan tidak pernah ada<br />
tuntutan dari pihak jaksa untuk juga<br />
mengajukan permohonan kompensasi ke<br />
pengadilan untuk korban. Hakim juga bersikap<br />
sama di mana tidak pernah memperhatikan<br />
persoalan kompensasi kepada korban padahal<br />
dalam undang-undang ditegaskan mengenai<br />
hak-hak korban ini. Dalam pengadilan HAM<br />
Abepura, para korban berinisiatif mengajukan<br />
gugatan untuk permohonan ganti kerugian<br />
kepada korban melalui pengacara dan<br />
pendampingnya. Meskipun permohonan ini<br />
diterima oleh jaksa dan diajukan ke pengadilan<br />
tetapi pada akhirnya pengadilan menolak<br />
permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh<br />
korban dengan dalih tidak ada ketentuan<br />
hukumnya. Korban pada akhirnya mengajukan<br />
permohonan ganti kerugian secara sendirisendiri<br />
setalah para korban ini bersaksi di depan<br />
pengadilan.<br />
Uraian di atas menunjukkan bahwa<br />
implementasi pemulihan kepada korban belum<br />
terpenuhi karena sampai dengan saat ini tidak<br />
satupun korban yang menerima kompensasi<br />
dari negara. Meskipun telah ada putusan<br />
mengenai kompensasi kepada korban tetapi<br />
karena belenggu normatif yang tidak berpihak<br />
kepada korban dan juga sikap dari aparat<br />
penegak hukum terutama jaksa dan para hakim<br />
yang tidak menganggap kompensasi kepada<br />
korban ini sebagai sesuatu yang penting dalam<br />
proses penyelesaian pelanggaran hak asasi<br />
manusia masa lalu maka implementasi hak-hak<br />
ini akan sangat sulit diwujudkan.<br />
KESIMPULAN<br />
Keberadaan komitmen penegakan hak asasi<br />
manusia ternyata tidak dengan sendirinya<br />
membuat kondisi hak asasi manusia sepanjang<br />
lima tahun terakhir berubah. Lima agenda besar<br />
penegakan hak asasi manusia yang telah<br />
dirumuskan oleh MPR sepanjang pertengahan<br />
1998 hingga akhir 2000 ternyata hanya sebagian<br />
kecil saja yang dijalankan oleh pemerintahanpemerintahan<br />
yang pernah berkuasa sepanjang<br />
1999-<strong>2004</strong>. Berbagai upaya penyelidikan atas<br />
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang<br />
selama periode 1999-<strong>2004</strong> ini ternyata hanya<br />
diarahkan kepada peristiwa-peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi<br />
antara pertengahan 1980-an hingga<br />
pertengahan 1990-an, sementara peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada<br />
pertengahan 1965 hingga akhir 1970 hingga saat<br />
ini masih belum tersentuh. Problem lainnya<br />
adalah sasaran dari penyelidikan ini masih<br />
24 Bagian II
mengarah pada para pelaku lapangan, dan<br />
bukan pihak-pihak yang selama ini menjadi<br />
pelaku utama dari kejahatan-kejahatan hak asasi<br />
manusia. Buruknya lagi, langkah-langkah<br />
penyelidikan ini tidak diikuti dengan upayaupaya<br />
penghukuman atas para pelakunya.<br />
Tidak berbeda dengan agenda pertama,<br />
agenda reformasi di tingkat kebijakan seperti<br />
pembuatan sejumlah regulasi baru, pencabutan<br />
regulasi yang bertentangan dengan hak asasi<br />
manusia dan ratifikasi instrumen hak asasi<br />
manusia internasional, tidak dengan sendirinya<br />
memberikan payung hukum yang kuat dan<br />
efektif dalam usaha-usaha penegakan hak asasi<br />
manusia di tataran praktis. Meskipun beberapa<br />
dari regulasi-regulasi baru tersebut telah<br />
memberikan jaminan hak asasi manusia atau<br />
mendorong terbentuknya institusi peradilan<br />
yang fair demi supremasi hukum, pencabutan<br />
berbagai peraturan yang bertentangan dengan<br />
hak asas8i manusia, serta memaksa TNI dan<br />
Kepolisian, dan institusi peradilan untuk<br />
mereformasi diri, namun demikian regulasiregulasi<br />
baru tersebut tidak mampu<br />
menghadapi regulasi-regulasi anti hak asasi<br />
manusia yang cukup banyak diproduksi dan<br />
dipergunakan oleh DPR dan Pemerintah untuk<br />
menghadapi ketegangan politik dan konflik<br />
sosial. Substansi yang masih memiliki celah<br />
interpretasi yang cukup besar menyebabkan<br />
pelaksanaanya pun menjadi sangat tergantung<br />
kepada insitusi atau pimpinan dari institusi itu<br />
sendiri. Proses ratifikasi yang hanya<br />
mengutamakan ratifikasi instrumen hak asasi<br />
manusia internasional non-binding, membuat<br />
langkah-langkah ratifikasi ini tidak terlalu<br />
banyak memperkuat proses penegakan hak asasi<br />
manusia nasional selama ini. Penundaan<br />
ratifikasi konvensi hak sipil politik dan hak<br />
ekonomi sosial budaya, yang seyogyanya harus<br />
diratifikasi pada masa 1999-<strong>2004</strong>, adalah salah<br />
bukti bahwa langkah-langkah ratifikasi adalah<br />
kamuflase pemerintah terhadap rakyatnya<br />
sendiri dan dunia internasional.<br />
Banyaknya landasan untuk penegakan<br />
hukum tersebut ternyata tidak diimbangi<br />
dengan dukungan dan kesiapan yang memadai<br />
dari institusi pelaksananya sehingga menyebabkan<br />
penegakan hak asasi manusia terhambat. Di<br />
samping lemahnya subtansi isi di beberapa<br />
regulasi baru, kebuntuan proses reformasi di<br />
tingkat institusi-institusi negara menjadi faktor<br />
penghambat menurunnya pelaksanaan agenda<br />
penegakan hak asasi manusian periode 1999-<br />
<strong>2004</strong>. Substansi dari reformasi di tingkat<br />
institusi yakni merubah menjadi independen<br />
dan jauh dari kooptasi kekuasaan, ternyata tidak<br />
sepenuhnya dijalankan, karena sebagian besar<br />
dari fungsi dan kewenangan di masa lalu masih<br />
dipertahankan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan<br />
kasus-kasus pelanggaran hak asasi<br />
manusia di masa lalu belum dapat terungkap<br />
seluruhnya. Di samping itu, kegagalan<br />
pengadilan untuk menghukum para pelaku<br />
kejahatan adalah bagian dari tidak berjalannya<br />
proses reformasi di institusi-institusi negara,<br />
khususnya institusi peradilan.<br />
Akibat-akibat dari praktik-praktik semacam<br />
ini, kemudian melahirkan peristiwa pelanggaran<br />
hak asasi manusia yang baru sepanjang 1999-<br />
<strong>2004</strong> ini. Lahirnya peristiwa-peristiwa<br />
pelanggaran baru ini kemudian berimplikasi<br />
pada terganggunya agenda penegakan hak asasi<br />
manusia di masa mendatang, karena<br />
bertambahnya tumpukan kasus-kasus<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang harus<br />
diselesaikan. Sudah dipastikan lingkar impunity<br />
di Indonesia semakin menguat, dan kembali<br />
membahayakan kondisi hak asasi manusia<br />
nasional di masa mendatang.<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Agenda penegakan hak asasi manusia ini yang<br />
diminta saat gelombang demonstrasi 1998 adalah<br />
menuangkan komitmen penegakkan hak asasi<br />
manusia ke dalam legislasi nasional dan kerangka<br />
besar pelaksanaan di tataran praktis.<br />
2<br />
Lih., Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak<br />
Asasi Manusia.<br />
3<br />
lih., Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN<br />
Tahun 1999 – 2000.<br />
4<br />
Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Pasal-pasal<br />
yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam<br />
perubahan kedua UUD 1945 ini terdapat 10 pasal yang<br />
memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara<br />
(orang) baik yang mencakup hak-hak sipil politik<br />
maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni<br />
dimulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.<br />
Dalam ketentuan tersebut juga dicantumkan pasal<br />
tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah<br />
dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan<br />
pemenuhan hak asasi manusia, juga ditegaskan bahwa<br />
untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
25
sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka<br />
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan<br />
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<br />
5<br />
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan<br />
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik<br />
Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri,<br />
Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita,<br />
dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan<br />
Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Tim<br />
Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan<br />
mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa<br />
13-15 Mei 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur<br />
pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi<br />
kemasyarakatan lainnya.<br />
6<br />
TGPF berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak<br />
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan<br />
perkosaan dan serangan seksual terhadap perempuanperempuan<br />
etnis cina dalam peristiwa 13-15 Mei 1998<br />
Lih. Laporan TGPF, Bab VI tentang Kesimpulan.<br />
7<br />
Ibid., Laporan TGPF Bab VII tentang Rekomendasi<br />
8<br />
Dasar hukum KPP HAM adalah Surat Keputusan<br />
Ketua Komnas HAM No.770/TUA/1999, kemudian<br />
disempurnakan dengan Surat Keputusan No.770/TUA/<br />
X/1999, dan disempurnakan kembali dengan Surat<br />
Keputusan. No.797/TUA/X/1999 tanggal, 22 Oktober<br />
1999.<br />
9<br />
Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan<br />
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur,<br />
Jakarta 31 Januari 2000, bagian Kesimpulan dan<br />
Rekomendasi.<br />
10<br />
Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan<br />
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kasus Tanjung Priok,<br />
bagian Kesimpulan dan Rekomendasi.<br />
11<br />
Polri melakukan penyidikan sejak tanggal 22 Februari<br />
– 18 April 2000, selama penyidikan, Polri memeriksa<br />
106 orang saksi, baik dari kalangan sipil maupun<br />
militer. Lihat: Laporan Tim Kajian Komnas HAM<br />
12<br />
Pembentukan tim koneksitas ini didasari<br />
pertimbangan sebagai berikut: (i) Peristiwa 27 Juli 1996<br />
melibatkan warga sipil dan aparat keamanan; (ii) Baik<br />
Penyidik dari Polri sebagai rantai dari peradilan umum<br />
maupun penyidik Puspom TNI sebagai rantai dari<br />
Peradilan Militer sangat sulit untuk meraih<br />
kepercayaan masyarakat; (iii) Apabila ada tersangka<br />
dari Polri dan militer, kedua institusi tersebut sangat<br />
sulit untuk bertindak secara independen.<br />
13<br />
Akibat adanya kebijakan untuk menyelesaikan<br />
Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pengadilan koneksitas,<br />
maka penyidikan pun harus dilakukan oleh penyidik<br />
koneksitas. Sehingga hasil penyidikan Polri terdahulu<br />
boleh dikatakan diulang lagi.<br />
14<br />
Sebelumnya Danpuspom TNI, Djasri Marin juga telah<br />
tiba di Papua untuk memimpin Tim Invenstigasi<br />
penyelidikan pembunuhan ini dengan 12 orang<br />
anggota atas perintah Panglima TNI.<br />
15<br />
UU ini terdiri dari 10 Bab dan 105 pasal. Secara tegas<br />
UU ini menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan,<br />
penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi<br />
tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya hak-hak<br />
yang dilindungi oleh UU meliputi hak untuk hidup, hak<br />
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak<br />
mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak<br />
atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas<br />
kesejahteraan, dan hak turut serta dalam<br />
pemerintahan. Secara khusus pula UU ini mengatur<br />
tentang hak perempuan dan hak terhadap anak. UU ini<br />
juga mengatur tentang tugas Komnas HAM yang<br />
meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan,<br />
pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.<br />
Bagian khusus dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang<br />
HAM juga mengatur mengenai pengadilan HAM di<br />
mana untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat<br />
dibentuk pengadilan HAM dalam ruang lingkup<br />
pengadilan umum<br />
16<br />
Perpu ini lahir karena desakan yang kuat dari pihak<br />
Internasional tentang penggelaran pengadilan para<br />
pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur<br />
pasca Jajak Pendapat sesegera mungkin. Desakan itu<br />
melalui resolusi No. 1272 di mana Dewan Keamanan<br />
PBB mengutuk kekerasan yang terjadi di Timor-timur<br />
dan meminta semua pihak yang bertanggungjawab<br />
untuk dibawa ke Pengadilan Indoneisa melalui Menlu<br />
Alwi Shihab kemudian menyatakan bahwa mekanisme<br />
hukum nasional adalah mekanisme eksklusif untuk<br />
membawa pelaku pelanggaran HAM berat tersebut ke<br />
pengadilan.<br />
17<br />
Statuta Roma 1998 menyebutkan 4 jenis kejahatan<br />
yang termasuk kejahatan yang sangat serius yaitu: (i)<br />
kejahatan genosida, (ii) kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan, (iii) kejahatan perang; dan (iv) kejahatan<br />
agresi.<br />
18<br />
Sebagai catatan, dua Keppres ini terbit sehari<br />
sebelum sidang pertama digelar di pengadilan HAM<br />
ad hoc Jakarta Pusat.<br />
19<br />
UU KKR sidahkan pada tanggal 7 September <strong>2004</strong><br />
dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober <strong>2004</strong>.<br />
20<br />
Ketentuan tentang referendum ini dibentuk untuk<br />
memperkuat atau mempersulit adanya perubahan<br />
UUD 1945 yang pada masa rezim orde baru sangat<br />
disakralkan. Dengan adanya ketentuan tentang referendum<br />
ini maka perubahan atas UUD 1945<br />
memerlukan syarat-syarat tambahan dan akan<br />
mempersulit jika akan melakukan perubahan UUD<br />
1945.<br />
21<br />
Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011-017/<br />
PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa UU nomor 12<br />
tahun 2003 (Pasal 60 huruf G) mengenai larangan<br />
anggota organisasi terlarang menjadi anggota DPR,<br />
DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan<br />
UUD 1945 dan beberapa ketentuan mengenai hak asasi<br />
manusia.<br />
22<br />
Lihat Program Ran HAM <strong>2004</strong> –2009.<br />
23<br />
Konvensi-konvensi tersebut disahkan dengan UU<br />
No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention<br />
No. 138 concerning minimum age for admission to<br />
employment (konvensi ILO mengenai usia minimum<br />
untuk diperbolehkan bekerja) dan UU No. 21 tahun<br />
1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111<br />
concerning discrimination in respect of employment<br />
and occupation (konvensi ILO mengenai diskriminasi<br />
dalam pekerjaan dan jabatan) dan UU No. 1 Tahun 2000<br />
tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concern-<br />
26 Bagian II
ing the prohibition and immediate action for the<br />
elimination of the worst forms of child labour<br />
(Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan<br />
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk<br />
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).<br />
24<br />
Lih., bagian pertimbangan TAP MPR No. VI/MPR/2000<br />
dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, lih., juga kebijakan<br />
tentang pembenahan di Institusi Kejaksaan dan<br />
Pengadilan<br />
25<br />
Ibid.,<br />
26<br />
Dua undang-undang tersebut, mengatur tentang<br />
lembaga kepolisian termasuk kewenangan dan tugas<br />
institusi kepolisian. UU ini secara tegas menyatakan<br />
bahwa peran dan tugas Polri adalah a) memelihara<br />
keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan<br />
hukum dan c) memberikan perlindungan,<br />
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<br />
27<br />
UU tentang pertahanan negara menyebutkan<br />
tentang peran dan tugas TNI yang meiputi: 1) TNI<br />
berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan<br />
Republik Indonesia, 2) TNI bertugas melaksanakan<br />
kebijakan pertahanan untuk; a) mempertahankan<br />
kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, b)<br />
melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, c)<br />
melaksanakan operasi militer selain perang dan d) ikut<br />
serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan<br />
perdamaian regional dan internasional. Dalam UU ini,<br />
salah satu poin penting adalah bahwa otoritas militer<br />
berada dalam otoritas sipil di mana segala langkah dan<br />
tindakan (pengarahan pasukan, dsb) yang dilakukan<br />
oleh institusi militer harus dengan persetujuan dari<br />
otoritas sipil.<br />
28<br />
Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU kepolisian<br />
menyatakan bahwa seluruh anggota kepolisian tunduk<br />
pada kekuasaan peradilan umum.<br />
29<br />
Lihat pasal 2 UU TNI, tentara yang profesional yaitu<br />
tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara<br />
baik dan dijamin kesejahteraannya, tidak berpolitik<br />
praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang<br />
menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak<br />
asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum<br />
internasional yang telah diratifikasi.<br />
30<br />
dalam salah satu pasalnya masih memberikan<br />
definisi yang luas tentang ancaman yang<br />
memungkinkan TNI mengambil tindakan jika dirasakan<br />
ada ancaman yang muncul. Lihat pasal 4 UU No. 3<br />
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang<br />
menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan<br />
untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,<br />
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,<br />
dan keselamatan seganap bangsa dari segara<br />
bentuk Ancaman. Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan<br />
bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan,<br />
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang<br />
dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan<br />
wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<br />
Dengan demikian ancaman bisa datang dari dalam<br />
negeri dan ini akan merancukan antara kewenangan<br />
Polri dengan TNI.<br />
31<br />
Lihat Laporan HAM 2003, “Melemahnya Daya<br />
Penegakan HAM: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan”,<br />
ELSAM, Januari <strong>2004</strong>.<br />
32<br />
Muncul perlawanan dari kalangan perwira tinggi<br />
militer tentang upaya dari politisi sipil menghapuskan<br />
KOTER. Hal ini terlihat dalam UU No. 34 tahun<strong>2004</strong><br />
yang semakin memperkuat keberadaan KOTER.<br />
33<br />
Hingga saat ini, hanya para prajurit di bawah yang<br />
sering diajukan ke Makamah Militer. Lih.,<br />
Proses Peradilan Kasus Perkosaan Di Aceh Semasa<br />
Darurat Militer Dan Pembunuhan Theis Eluay Di Papua,<br />
di mana para pelaku yang diajukan ke pengadilan<br />
hanya para prajurit golongan bawah.<br />
34<br />
Upaya perbaikan di bidang peradilan melalui<br />
undang-undang sudah dimulai sejak adanya UU No. 35<br />
tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur bahwa<br />
kekuasaan di bidang peradilan akan sepenuhnya<br />
dijalankan oleh MA RI.<br />
35<br />
Problem sistemik pengadilan secara luas mencakup<br />
beberapa hal misalnya maraknya korupsi di<br />
lingkungan peradilan, lemahnya kualifikasi sumber<br />
daya manusia di pengadilan, rendahnya kualitas dan<br />
besarnya disparitas putusan hakim, hingga inefisiensi<br />
pengadilan secara organisasi.<br />
36<br />
Lebih jauh dapat dinilai bahwa kejaksaaan tidak<br />
mandiri secara fungsional yang disebabkan oleh: (a)<br />
kelemahan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan<br />
pengawasan jaksa; (b) lemahnya sistem rekrutmen dan<br />
pemberhentian jaksa agung; (c) kelemahan dalam<br />
manajemen kasus (adanya kewajiban rencana<br />
penuntutan); (d) tidak adanya akuntabilitas individual<br />
dalam menangani perkara; (e) budaya militeristik dan<br />
sistem komando yang diterapkan. Kelemahan<br />
eksternal yang mencolok adalah kondisi politik negara<br />
masa lalu yang otoriter. Lihat Kritik Terhadap Paket Ruu<br />
Bidang Peradilan Dan Kejaksaan, Indonesia Corruption<br />
Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional<br />
(KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk<br />
Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Kajian<br />
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS),<br />
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI),<br />
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).<br />
37<br />
Catatan ELSAM atas proses pengadilan HAM ad hoc<br />
baik Tanjung Priok mapun Timor Timur menunjukkan<br />
bahwa jaksa tampak bekerja setengah hati dalam<br />
membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa tidak cukup<br />
mampu menghadirkan barang bukti yang memadai<br />
dan lemah dalam mempertahankan argumentasi<br />
dalam surat dakwaan.<br />
38<br />
Hampir sebagian besar staf di bagian hak asasi<br />
manusia tidak memiliki latar belakang pendidikan dan<br />
pengalaman di bidang hak asasi manusia, karena<br />
sebagian dari mereka adalah berasal dari sejumlah<br />
departeman kementerian yang pada masa Gus Dur<br />
dibubarkan. Departemen-departemen itu antara lain<br />
departemen sosial, transmigrasi dan departemen<br />
penerangan.<br />
39<br />
Perubahan ini disebabkan karena perubahan locus<br />
dan tempus delicti.<br />
40<br />
Sebelumnya ada Keppres yang secara khusus untuk<br />
pengadilan HAM ad hoc, Presiden telah menerbitkan<br />
Keppres RI No. 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan<br />
Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta<br />
Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan Negeri<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
27
Makassar dan Pengadilan Negeri Medan.<br />
41<br />
Pendapat KSAD menanggapi vonis terhadap anggota<br />
Kopassus. Pendapat senada disampaikan oleh Danjen<br />
Kopassus yang mengaku sedih atas penjatuhan vonis<br />
tersebut. Koran Tempo, 24 April 2003<br />
28 Bagian II
BAGIAN KETIGA<br />
Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan<br />
Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer<br />
Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah<br />
Konflik<br />
PENGANTAR<br />
Masalah besar yang menghalangi<br />
pelaksanaan agenda penegakkan hak<br />
asasi manusia di Indonesia dalam<br />
lima tahun terakhir adalah menguatnya<br />
penggunaan regulasi keadaan darurat dan<br />
pengerahan kekuatan militer dalam penanganan<br />
persoalan sparatisme dan konflik sosial di<br />
beberapa tempat. Slogan menjaga ‘Negara<br />
Kesatuan Republik Indonesia’ dan<br />
‘menghancurkan provokator’ yang selalu<br />
disuarakan oleh para pejabat sipil dan militer<br />
ketika menyikapi persoalan sparatisme dan<br />
konflik sosial di beberapa daerah pada akhirnya<br />
membenarkan penerapan regulasi keadaan<br />
darurat dan pengerahan kekuatan militer<br />
sebagai jawaban atas tuntutan kemerdekaan di<br />
Aceh dan Papua dan penyelesaian aksi-aksi<br />
kekerasan oleh laskar-laskar bersenjata di<br />
Maluku, Poso dan Sampit.<br />
Memang di satu sisi sepenjang 1999-<strong>2004</strong><br />
pemerintah telah mengupayakan langkahlangkah<br />
penyelesaian persoalan separatisme dan<br />
konflik sosial melalui cara damai. Instruksi<br />
presiden tentang penyelesai masalah Aceh,<br />
Papua, Maluku dan Poso melalui cara-cara<br />
damai adalah langkah maju lainnya dari<br />
pemerintah. Langkah penting dan sangat<br />
menonjol adalah perjanjian penghentian<br />
permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka<br />
untuk mencari solusi penyelesaian konflik Aceh<br />
yang sudah berlangsung selama lebih dari 20<br />
tahun terakhir. Perjanjian Malino I dan II untuk<br />
mendorong penyelesain persoalan konflik antar<br />
kelompok di Maluku dan Poso secara damai<br />
adalah langkah penting yang perlu dicatat.<br />
Sejumlah langkah-langkah penyelesaian secara<br />
damai ini secara siginifikan kemudian<br />
mengurangi intensitas kekerasan di sejumlah<br />
daerah konflik dalam kurun waktu yang lama.<br />
Dan sebaliknya, ketika upaya-upaya damai<br />
terhenti, kekerasan pun meningkat dan kembali<br />
membawa penduduk sipil berada dalam tekanan<br />
militer pemerintah, tentara pemberontak, milisi<br />
sipil dan laskar-laskar bersenjata.<br />
Tapi di sisi lain penerapan regulasi<br />
kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer<br />
melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi<br />
hak asasi manusia nasional yang telah dirintis<br />
sejak tumbangnya Orde Baru. Namun demikian<br />
pembaharuan baru di bidang kebijakan ini tidak<br />
membuat negara menghentikan kejahatan<br />
pelanggaran hak asasi manusia terhadap<br />
penduduk sipil. Regulasi kedaruratan dan<br />
pengerahan kekuatan militer jelas-jelas<br />
membuat hukum hak asasi manusia nasional<br />
yang baru saja terbentuk itu tidak dapat<br />
diterapkan di daerah-daerah berkonflik.<br />
Penggelaran operasi militer di Papua dan<br />
pemberian kewenangan kepada pihak militer<br />
dan polisi untuk menyelesaikan pertikaian jelasjelas<br />
membenarkan langkah-langkah seperti<br />
membatasi ruang gerak, menghilangkan hak<br />
untuk mengeluarkan pendapat, dan<br />
membenarkan tindakan-tindakan<br />
menghilangkan nyawa orang untuk<br />
memulihkan keamanan dan ketertiban sipil.<br />
Pemberlakuan keadaan darurat militer dan<br />
pelaksanaan operasi militer di Aceh, yang<br />
merupakan operasi militer terbesar setelah<br />
invasi ke Timor Leste pada 1975, adalah<br />
semacam tanda kembali menguatnya<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
29
penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah<br />
sipil. Akibat dari itu semua kebijakan-kebijakan<br />
ini berbagai tindak pelanggaran hak asasi<br />
manusia di Indonesia dalam lima tahun<br />
terakhir. 1 Di lain pihak, kebijakan-kebijakan<br />
tersebut turut menggagalkan komitmen<br />
nasional tentang agenda penegakan hak asasi<br />
manusia di Indonesia.<br />
Bab ini berusaha menjelaskan proses<br />
menguatnya penggunaan regulasi kedaruratan<br />
dan penggunaan kekuatan bersenjata oleh<br />
negara dalam mengatasi ketegangan politik dan<br />
konflik sosial di daerah yang telah menyebabkan<br />
agenda perbaikan hak asasi manusia nasional<br />
sepanjang 1999-<strong>2004</strong> berjalan di tempat.<br />
Penggunaan regulasi kedaruratan dan<br />
penggunaan kekuatan bersenjata untuk<br />
menghadapi gejolak sosial adalah bukanlah hal<br />
baru di Indonesia. Justru sebaliknya,<br />
pengandalan kekuatan militer untuk<br />
menghadapi gerakan separatis dan konflik sosial<br />
adalah kebiasaan dari pemerintahan orde baru<br />
di mana dengan alasan memulihkan keamanan<br />
dan ketertiban, tindakan menangkap dan<br />
menahan orang tanpa batas waktu, menetapkan<br />
sensor terhadap pers, membatasi arus keluarmasuk<br />
orang di perbatasan dan mengawasi<br />
kegiatan ekonomi yang dianggap vital adalah<br />
sesuatu yang lumrah.<br />
MENGUATNYA PENGGUNAAN<br />
REGULASI KEDARURATAN DAN<br />
PENGERAHAN KEKUATAN MILITER<br />
OLEH NEGARA SEPANJANG 1999-<strong>2004</strong><br />
Kecenderungan penggunaan regulasi<br />
kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer<br />
oleh negara sebagai respon atas kemunculan<br />
gerakan separatisme dan konflik sosial dalam<br />
lima tahun belakangan ini semakin menguat.<br />
Pola-pola penyelesaian melalui cara-cara damai<br />
sebagaimana yang nampak dominan pada awalawal<br />
pemerintahan transisi terbentuk – pada era<br />
presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid –<br />
sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh<br />
pemerintah. Bahkan, tanpa didahului dengan<br />
evaluasi yang mendalam dan independen atas<br />
sejumlah langkah-langkah penyelesaian damai<br />
yang sudah mereka tempuh, pihak pemerintah<br />
selalu mengajak untuk membenarkan langkahlangkah<br />
militer yang mereka tempuh yakni<br />
dengan menyebutkan kelompok pemberontak<br />
atau pihak-pihak sipil yang bertikai telah<br />
menolak berdamai sehingga layak untuk<br />
diselesaikan melalui langkah-langkah militer.<br />
Dengan mengumandangkan slogan “Menjaga<br />
Keutuhan Kedaulatan Negara Kesatuan<br />
Republik Indonesia — (NKRI)” para pejabat<br />
militer dan sipil mengajak publik luas untuk<br />
dukungan langkah-langkah militer tersebut.<br />
Akibatnya, langkah-langkah penyelesaian damai<br />
yang sebenarnya banyak menunjukkan<br />
keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan<br />
pemberontakan dan konflik komunal, menjadi<br />
tidak popular di mata publik.<br />
1. Penanganan Tuntutan Kemerdekaan<br />
di Aceh dan Papua<br />
Pasca rezim orde baru tumbang, adalah<br />
Habibie, presiden pertama yang menggunakan<br />
regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan<br />
militer untuk menghadapi persoalan<br />
pemberontakan dan konflik sosial di Indonesia.<br />
Dimulai dengan penerbitan Keputusan Presiden<br />
(Kepres) Nomor 107 Tahun 1999 tentang<br />
Pemberlakuan Darurat Militer di Timor<br />
Lorosae, Habibie mencoba mengakhiri tindak<br />
kekerasan yang semakin meluas di Timor Timur<br />
(sekarang Republik Demokratik Timor<br />
Lorosae) pasca Jajak Pendapat Agustus 1999,<br />
dengan mengerahkan kekuatan militernya ke<br />
Timor Timur. Dengan dalih pemerintah Indonesia<br />
mendapat mandat dari PBB dan<br />
Pemerintah Portugal untuk bertanggungjawab<br />
atas keamanan di wilayah Timor Timur selama<br />
jajak pendapat berlangsung, Habibie memilih<br />
untuk memberlakukan darurat militer di<br />
wilayah tersebut. Meski telah ditetapkan dalam<br />
30 Bagian III
keadaan darurat militer, aksi-aksi kekerasan<br />
kelompok pro-integerasi terhadap penduduk<br />
sipil tidaklah berhenti. Justru sebaliknya, aksi<br />
kekerasan tersebut semakin meluas hingga<br />
membuat sebagian besar kota-kota di wilayah<br />
tersebut berubah menjadi lautan api dan juga<br />
melahirkan gelombang eksodus besar-besaran<br />
penduduk sipil ke wilayah Timor Barat. Ribuan<br />
penduduk sipil dilaporkan terbunuh dalam aksi<br />
kekerasan tersebut, dan 200 ribu lainnya dipaksa<br />
mengungsi ke daerah Timor Barat. Meski<br />
langkah ini mendapat kecaman dari dunia<br />
internasional, namun preseden ini menjadi awal<br />
penggunaan regulasi kedaruratan dan<br />
pengerahan kekuatan militer untuk<br />
menghadapi gejolak politik dan konflik sosial di<br />
berbagai daerah oleh pemerintahan selanjutnya.<br />
Di Aceh, kebuntuan pelaksanaan kesepakatan<br />
penghentian permusuhan 2 , antara Militer Indonesia<br />
dengan militer Gerakan Aceh Merdeka<br />
(GAM), menjadi dasar pemerintah Indonesia<br />
untuk memberlakukan status darurat di wilayah<br />
tersebut. Langkah perundingan yang<br />
merupakan babak baru dalam penyelesaian<br />
Aceh secara damai oleh pemerintah dalam 20<br />
tahun terakhir runtuh dalam hitungan hari<br />
karena pemerintah RI bersikeras agar GAM<br />
menerima konsep otonomi sebagai solusi<br />
tunggal penyelesaian Aceh. Akibatnya, CoHA<br />
yang selama lebih dari tiga bulan berhasil<br />
menurunkan tensi kekerasan di Aceh gagal<br />
untuk dipertahankan dan berbalik menjadi<br />
pemicu peristiwa kekerasan yang lebih besar<br />
dari sebelumnya. Runtuhnya CoHA inilah yang<br />
kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan<br />
Megawati untuk kembali memilih cara-cara<br />
militer sebagai jalan keluar penyelesaian Aceh.<br />
Diawali dengan menerbitkan Keputusan<br />
Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang<br />
Penetapan Status Darurat Militer di Aceh<br />
pertengahan Mei, selanjutnya Megawati<br />
memerintahkan pasukan (insert<br />
tabel)militernya yang sudah lebih dahulu<br />
berada di sekitar propinsi-propinsi yang<br />
bertetangga dengan propinsi Nanggroe Aceh<br />
Darurssalam untuk melakukan aksi<br />
penyerangan terhadap kantong-kantong<br />
pertahanan GAM. Untuk mendukung<br />
penyerbuan tersebut, Megawati menunjuk<br />
Panglima Komando Daerah Militer setempat<br />
sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah<br />
(PDMD), dan memberikan wewenang kepada<br />
PDMD untuk mengambil langkah-langkah<br />
pembatasan terhadap aktivitas penduduk sipil<br />
guna mendukung operasi tempur yang sedang<br />
berjalan. Sejak saat itu, aksi kekerasan terhadap<br />
penduduk sipil di Aceh kembali terjadi dalam<br />
skala yang lebih besar dari sebelumnya. 3<br />
Di Papua, meski pola penanganan Jakarta<br />
atas tuntutan kemerdekaan tidak menggunakan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
31
kerangka darurat militer, namun demikian<br />
secara prinsip tidak ada perbedaan dengan pola<br />
penanganannya terhadap Aceh. Pendekatan<br />
melalui langkah-langkah militer dalam bentuk<br />
pengiriman ribuan pasukan militer untuk<br />
mendukung penggelaran Operasi Militer Selain<br />
Perang (OMSP) adalah langkah dominan<br />
ketimbang langkah-langkah penyelesaian secara<br />
damai. 4<br />
Tuntutan kemerdekaan penduduk Papua<br />
yang lahir akibat proses integrasi tahun 1963,<br />
yang diduga keras sarat dengan manipulasi<br />
militer Indonesia, mulai menguat pasca<br />
kejatuhan Soeharto. Dengan mengusung isu-isu<br />
kekerasan dan kejahatan militer pada masa<br />
Penerapan Daerah Operasi Militer, organisasiorganisasi<br />
kemerdekaan bawah tanah kembali<br />
muncul ke permukaan dan mencoba<br />
menggalang kekuatan melancarkan aksi-aksi<br />
damai untuk menyuarakan tuntutan referendum<br />
kepada Jakarta. Menguatnya tuntutan<br />
kemerdekaan tersebut kemudian menimbulkan<br />
kecemasan di kalangan para pejabat sipil/militer,<br />
terutama para pejabat yang memiliki investasi<br />
besar di pulau terbesar di Indonesia tersebut.<br />
Kegelisahan ini mencapai puncaknya ketika<br />
Abdurrahman Wahid yang naik menggantikan<br />
presiden Habibie, menolak untuk<br />
menyelesaikan persoalan tuntutan kemerdekaan<br />
di Papua dengan cara-cara militer. Dengan<br />
mengeluarkan Keppres tentang Pemberian<br />
Otonomi Khusus, Abdurrahman Wahid dengan<br />
tegas menolak permintaan-permintaan<br />
sejumlah pejabat militer/sipil untuk<br />
menyelesaikan persoalan di Papua melalui<br />
pengerahan kekuatan militer. Selanjutnya untuk<br />
memperkuat langkah-langkahnya tersebut,<br />
Abdurrahman Wahid memerintahkan kepada<br />
para komandan polisi dan militer di Papua<br />
untuk tidak mengganggu aksi-aksi demonstrasi<br />
dan pengibaran bendera Bintang Kejora oleh<br />
organisasi-organisasi pro-kemerdekaan setiap<br />
awal Desember. Bahkan Abdurrahman Wahid<br />
tak segan-segan untuk mengecam berbagai<br />
tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer/<br />
Brimob terhadap penduduk sipil dan tak segan<br />
untuk menyetujui pembentukan tim<br />
penyelidikan atas sejumlah tindak kekerasan<br />
yang terjadi kepada Komnas HAM. 5<br />
Abdurrahman Wahid juga mengajak elit<br />
lokal papua untuk masuk dalam pemerintahan<br />
agar dapat terlibat dalam menentukan<br />
pembangunan Papua sesuai dengan adat dan<br />
kebudayaannya. Di masa Megawati pun cara<br />
penyelesaian Papua tetap memilih cara-cara<br />
damai, dan menolak desakan para pejabat<br />
militer untuk menggunakan kekuatan militer.<br />
Sayangnya, langkah-langkah penting ini tidak<br />
dapat berjalan dengan mulus karena tidak<br />
mendapat dukungan dari elit lokal yang<br />
mendapat dukungan dari pejabat militer<br />
setempat.<br />
Para pejabat militer yang berkolaborasi<br />
dengan elit sipil masih menggunakan cara-cara<br />
militer ketika menghadapi berbagai gejolak<br />
politik daerah, seperti pembatasan dan<br />
mengkriminalkan para tokoh Papua yang<br />
bersuara keras terhadap langkah-langkah<br />
pemerintah daerah. 6 Meski hingga kini belum<br />
ada penerapan darurat militer, aksi-aksi<br />
provokasi ini berhasil membuat peristiwa<br />
kekerasan di berbagai wilayah Papua meluas,<br />
dan menjadi argumen kuat militer untuk<br />
meningkatkan aktivitas pasukannya di propinsi<br />
tersebut. 7 Sejumlah pekerja hak asasi manusia di<br />
Jayapura kerap melaporkan bahwa satuansatuan<br />
khusus anti pemberontak dalam jumlah<br />
yang kecil (10-20 personel) telah memenuhi<br />
wilayah-wilayah yang diduga menjadi basis<br />
kekuatan gerakan pro merdeka. 8 Selain itu<br />
sejumlah pejabat militer dan sipil daerah<br />
dilaporkan kerap terlibat dalam pembentukan<br />
satuan-satuan milisi sipil. 9 Meski secara de jure<br />
pola penanganan Jakarta atas persoalan Papua<br />
tidak membenarkan cara-cara militer, namun<br />
bertambahnya kekuatan militer di Papua serta<br />
ketidakmampuan pemerintahan Jakarta untuk<br />
mengontrol aktivitas militer di lapangan, secara<br />
de facto dapat dikatakan bahwa pola<br />
penanganan tuntutan kemerdekaan di Papua<br />
sesunggugnya tetap memilih cara-cara<br />
pengerahan kekuatan militer.<br />
2. Penanganan Konflik Sosial<br />
Tidak berbeda dengan pola penanganan<br />
gerakan kemerdekaan, penyelesaian kekerasan<br />
komunal di beberapa daerah oleh pemerintah<br />
Jakarta selalu ditekankan pada penggunaan<br />
langkah-langkah pengerahan militer.<br />
Pemerintah Jakarta sering mengabaikan<br />
32 Bagian III
penyelesaian persoalan substansi yang menjadi<br />
penyebab terjadinya kekerasan antara<br />
komunitas yakni tuntutan penduduk lokal akan<br />
pembentukan pemerintahan daerah yang<br />
demokratis dan pembersihan praktik-praktik<br />
diskriminasi yang telah menyebabkan mereka<br />
kehilangan hak sipil, politik dan ekonomi<br />
selama puluhan tahun. Berbagai inisiatif<br />
penyelesaian secara damai pun telah mereka<br />
tinggalkan dengan alasan yang sama persis<br />
ketika menghadapi masalah pemberontakan.<br />
Konflik di Maluku dan Maluku Utara yang<br />
dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda ini,<br />
membawa dua propinsi tersebut berada dalam<br />
kontrol militer yang sangat panjang. Dimulai<br />
sejak akhir Desember 1998, kekerasan komunal<br />
terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2002.<br />
Sepanjang itu pula pola-pola penyelesaian<br />
melalui pengerahan kekuatan militer dijalankan<br />
lebih dari dua tahun. Berbagai inisiatif<br />
penyelesaian secara damai oleh pemerintah awal<br />
1999 hingga pertengahan 2000 ditinggalkan<br />
begitu saja karena gagal untuk membuat kedua<br />
kelompok tetap bertikai. Bahkan perjanjian<br />
Malino II yang digagas untuk menyelesaikan<br />
konflik tersebut pun dianulir oleh Jakarta yakni<br />
dengan mengerahkan pasukan militer ke<br />
Maluku untuk memaksa diam kelompokkelompok<br />
yang tidak setuju dengan konsep<br />
perdamaian yang ditawarkan oleh pemerintah.<br />
Dimulai dengan<br />
mengirimkan pasukan<br />
pada awal Januari 1999,<br />
kemudian berlanjut<br />
dengan menetapkan<br />
Maluku dalam keadaan<br />
Bantuan Militer<br />
(BANMIL) hingga Juni<br />
1999. Meski demikian<br />
cara-cara penyelesaian<br />
tersebut ternyata tidak<br />
membuat peristiwa<br />
kekerasan berhenti dan<br />
malah sebaliknya<br />
kekerasan justru<br />
semakin meningkat dan<br />
meluas hampir ke<br />
seluruh pulau yang<br />
masuk dalam propinsi<br />
Maluku. Strategi Jakarta<br />
memecah Maluku<br />
menjadi dua propinsi, yakni Maluku dan<br />
Maluku Utara, juga gagal meredam konflik,<br />
karena pemekaran ini ternyata hanya<br />
mengakomodir tuntutan elit politik lokal.<br />
Meluasnya kekerasan pertengahan 1999 yang<br />
kemudian menjadi pembenar atas pemekaran<br />
Korem Pattimura menjadi setingkat KODAM<br />
pun tidak juga berhasil menyelesaikan konflik<br />
secara tuntas dan justru mengantar Maluku dan<br />
Maluku Utara<br />
dalam status Darurat Sipil akibat peristiwa<br />
kekerasan pada Juni 2000 melumpuhkan<br />
pemerintahan sipil di wilayah tersebut. Melalui<br />
Keppres Nomor 88 Tahun 2000, presiden<br />
Abdurrahman Wahid menetapkan Maluku dan<br />
Maluku Utara dalam keadaan Darurat Sipil,<br />
agar langkah penghentian aksi kekerasan oleh<br />
pasukan keamanan dapat berjalan dengan<br />
efektif. Setidaknya kurang lebih tiga tahun,<br />
propinsi Maluku dan Maluku Utara dinyatakan<br />
dalam keadaan Darurat Sipil. Ribuan pasukan<br />
militer dan Brimob kemudian memenuhi desadesa<br />
di Maluku dan Maluku Utara.<br />
Tidak berbeda dengan Maluku, Peristiwa<br />
kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah tidak pernah<br />
berhenti sekalipun Jakarta telah berulang kali<br />
mengirimkan pasukan militer dan polisi ke<br />
daerah tersebut. Pola pemisahan tempat tinggal<br />
dan tembak di tempat bagi para penduduk yang<br />
mencoba menyeberang ke wilayah yang<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
33
erbeda, hanya membuat kecurigaan dua pihak<br />
yang bertikai semakin mengkristal. Operasioperasi<br />
intelejen yang digelar untuk mendeteksi<br />
pihak-pihak yang bermain dalam kekerasan pun<br />
gagal untuk mengungkap para pihak tersebut,<br />
dan justru membuat disinformasi di dua<br />
kelompok semakin meningkat dan memicu<br />
keduanya untuk saling menyerang. Berbagai<br />
upaya mengundang pihak yang bertikai oleh<br />
komandan militer tidak membuahkan<br />
perdamaian yang kekal, karena pihak yang<br />
mendamaikan tidak pernah memenuhi janji<br />
mereka kepada pihak yang bertikai, untuk<br />
mengusut provokator dari peristiwa kekerasan<br />
tersebut. Perjanjian Malino I adalah bukti di<br />
mana pihak pemerintah gagal untuk memenuhi<br />
janji mereka kepada dua pihak yang bertikai<br />
untuk mengusut siapa pihak yang harus<br />
bertanggungjawab dalam peristiwa kekerasan di<br />
wilayah Poso.<br />
Berbagai kegagalan perjanjian damai yang<br />
kembali memicu peristiwa kekerasan yang lebih<br />
besar, tidak membuat Jakarta merubah pola<br />
penyelesaian penanganan kekerasan di wilayahwilayah<br />
konflik. Pengiriman pasukan militer<br />
dan polisi terus mereka jalankan, sementara<br />
penambahan pasukan ini tidak secara signifikan<br />
menghentikan aksi-aksi kekerasan di wilayah<br />
konflik. Di Sampit dan Sambas, pengiriman<br />
pasukan militer ke dua tempat tersebut tidak<br />
membuat aksi-aksi kekerasan dan pengusiran<br />
penduduk Madura mereda. Sebaliknya aksi-aksi<br />
kekerasan tersebut semakin meningkat hingga<br />
menyebabkan puluhan ribu warga Madura<br />
eksodus ke sejumlah daerah untuk<br />
menyelamatkan diri. Keterlibatan elit politik<br />
lokal dalam mobilisasi laskar-laskar perang<br />
jarang dijadikan fokus penyelesaian kekerasan,<br />
dan sebaliknya Jakarta justru balik menyalahkan<br />
para penduduk sipil yang mengungsi karena<br />
perilaku negatif mereka di masa lalu.<br />
Pembenaran atas pelarangan penduduk untuk<br />
kembali ke wilayah asal pun mereka amini<br />
dengan dalih keadaan yang sudah kondusif akan<br />
terganggu jika para penduduk bermasalah<br />
tersebut kembali ke tempat asal mereka. Tak<br />
heran jika kemudian para pejabat daerah itu<br />
membuat sebuah syarat-syarat ketat untuk<br />
mensortir para penduduk yang akan kembali ke<br />
daerahnya, ketimbang menyelidiki para pejabat<br />
yang terlibat dalam aksi kekerasan dan<br />
pengusiran tersebut.<br />
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA<br />
Menguatnya penggunaan regulasi<br />
kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer<br />
membuat peristiwa pelanggaran hak asasi<br />
34 Bagian III
manusia semakin meningkat dan mempersulit<br />
agenda perbaikan hak asasi manusia di wilayahwilayah<br />
konflik. Regulasi kedaruratan dan<br />
pengerahan kekuatan militer membenarkan<br />
langkah-langkah pengabaikan hak-hak individu<br />
yang diakui oleh konstitusi dan hukum hak asasi<br />
manusia nasional. Peristiwa-peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik adalah penghilangan hak untuk hidup,<br />
penangkapan, penahanan sewenang-wenang,<br />
penyiksaan perlakuan tidak manusiawi dan<br />
hukuman kejam, penghilangan orang,<br />
pembatasan ruang gerak, menghilangkan hak<br />
untuk mengeluarkan pendapat, yang<br />
kesemuanya dibenarkan dalam rangka<br />
memulihkan keamanan dan ketertiban sipil. Di<br />
lain pihak, langkah-langkah Jakarta ini juga<br />
memancing kelompok pemberontak untuk<br />
terlibat dalam aksi-aksi kekerasan terhadap<br />
penduduk sipil, terutama penduduk sipil yang<br />
menjadi pendukung setia militer. Penerapan<br />
regulasi kedaruratan juga membuat upayaupaya<br />
penyelidikan oleh institusi hak asasi<br />
manusia menemui hambatan yang berarti dan<br />
sulit untuk mengetahui jumlah pasti korban<br />
pelanggaran hak asasi manusia untuk kategori<br />
ini. Berikut ini adalah sejumlah paparan fakta<br />
tentang pelanggaran hak asasi menonjol di<br />
wilayah-wilayah konflik sepanjang 1999-<strong>2004</strong>.<br />
1. Extrajudicial and Summary Killing<br />
Tindakan penghilangan nyawa penduduk<br />
sipil oleh militer dalam rangka pemulihan<br />
keamanan dan ketertiban menjadi peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang paling<br />
menonjol di Aceh, Papua, Maluku, Maluku<br />
Utara, Poso, Sambas dan Sampit. Operasi anti<br />
gerilya dan operasi pemisahan penduduk<br />
berdasarkan agama atau etnis membenarkan<br />
tindakan-tindakan brutal dari personil militer<br />
dalam bentuk pembunuhan di luar proses<br />
hukum, atau dalam istilah hak asasi manusia<br />
disebut extrajudicial killing dan summary execution.<br />
Penggunaan taktik anti gerilya dalam operasi<br />
militer di Aceh dan Papua, kerap melahirkan<br />
peristiwa pembunuhan di luar proses hukum<br />
atas orang-orang sipil yang diduga sebagai GAM<br />
ataupun OPM. Sasaran dalam taktik perang<br />
semacam ini tidak hanya gerilyawan akan tetapi<br />
juga mencakup pihak sipil. Sejumlah informasi<br />
menunjukkan adanya praktik-praktik<br />
pelanggaran kategori ini di Aceh dan Papua.<br />
Dengan pembuktian ditemukannya bendera<br />
pemberontak, memiliki peluru, tertangkap<br />
basah keluar dari hutan-hutan, lari dari sweeping<br />
militer di jalan-jalan, maupun memiliki<br />
kedekatan keluarga dengan kelompok<br />
pemberontak, cukup membuat pasukan militer<br />
dan Brimob untuk menghilangkan nyawa<br />
seseorang. 10 Di Aceh dan Papua, banyak sekali<br />
informasi tentang korban-korban pembunuhan<br />
yang sebelumnya dilaporkan dijemput oleh<br />
unit-unit intelejen di rumah, tempat bekerja dan<br />
kedai-kedai kopi. 11 Bahkan sejumlah informasi<br />
menyebutkan adanya praktik-praktik<br />
pembunuhan diluar proses hukum ini di<br />
tempat-tempat penahanan orang-orang yang<br />
dituduh anggota pemberontak.<br />
Tidak berbeda di Aceh dan Papua, dengan<br />
alasan pemulihan keamanan dan ketertiban di<br />
daerah-daerah konflik sosial, seperti Maluku,<br />
Maluku Utara, Poso, Sambas dan Sampit, militer<br />
dan Brimob kerap terlibat dalam tindak<br />
pembunuhan di luar proses pengadilan atas<br />
sejumlah penduduk sipil yang bertikai. Para<br />
pejabat militer dan polisi mengaku,<br />
penembakan brutal terhadap kerumunan<br />
penduduk di daerah-daerah perbatasan<br />
dilakukan dengan alasan menghindari aksi<br />
saling serang yang lebih besar. Dengan<br />
menuduh para korbannya “perusuh” atau<br />
“provokator” para pejabat militer/polisi<br />
mencoba membenarkan pola penanganan yang<br />
mereka ambil. Bahkan belakangan militer dan<br />
polisi menuduh pihak-pihak yang selalu kritis<br />
dengan pola penanganan penyelesaian<br />
kekerasan di wilayah konflik adalah kelompok<br />
pemberontak. Di Maluku, sejumlah orang yang<br />
tergabung dalam Forum Kedaulatan Maluku<br />
yang dalam beberapa tahun belakangan ini<br />
gencar menyuarakan kebobrokan penanganan<br />
konflik Maluku, dituding oleh militer sebagai<br />
kepanjangan tangan dari kelompok<br />
pemberontak Republik Maluku Selatan<br />
(RMS). 12 Bahkan sejumlah tokohnya ditangkap<br />
dan diadili dengan tuduhan makar.<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
35
2. Penangkapan dan Penahanan<br />
Sewenang-wenang<br />
Selain penghilangan nyawa orang, peristiwa<br />
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang<br />
juga mencuat sebagai kasus paling banyak<br />
terjadi di wilayah konflik. Pemisahan penduduk<br />
sipil dengan kelompok pemberontak serta<br />
pencarian provokator di wilayah-wilayah<br />
konflik komunal, membenarkan militer dan<br />
polisi melakukan penangkapan dan penahanan<br />
sewenang-wenang terhadap orang-orang yang<br />
dianggap memiliki kaitan dengan kelompok<br />
pemberontak maupun orang-orang yang<br />
ditengarai sebagai pemicu kerusuhan.Tindakantindakan<br />
ini dilakukan dengan mengabaikan<br />
prosedur hukum yang berlaku, seperti jarang<br />
menunjukkan identitas diri kepada keluarga<br />
para korban ketika menangkap maupun<br />
menjelaskan tempat penahanan para<br />
korbannya. Di Aceh, ribuan orang ditangkap<br />
dan ditahan tanpa prosedur hukum karena<br />
kedapatan tidak memiliki KTP Merah Putih<br />
atau karena kedapatan oleh anggota militer baru<br />
keluar dari hutan. 13 Di Papua, sejumlah orang<br />
ditangkap dan ditahan oleh pasukan militer dan<br />
Brimob karena Fam (identitas suku) mereka<br />
sama dengan orang-orang yang sedang dicari<br />
oleh pemerintah. 14 Sekalipun dalam beberapa<br />
kesempatan pemerintah mengumumkan telah<br />
melakukan penangkapan dan penahanan atas<br />
sejumlah orang, namun demikian<br />
pengumuman ini tidak disertai dengan<br />
penyebutan tempat penahanan. Bahkan dalam<br />
beberapa pihak sangat meragukan informasi<br />
tentang jumlah tahanan oleh para pejabat sipil<br />
dan militer. 15 Penerapan darurat militer di Aceh<br />
membuat kantor-kantor militer dari tingkat<br />
Koramil hingga Kodam kembali memfungsikan<br />
ruang tahanannya guna menampung orang-orang<br />
yang diduga sebagai anggota GAM.<br />
Sejumlah pihak juga menyebutkan adanya<br />
ruang tahanan di pos militer dan brimob yang<br />
kerap digunakan untuk menahan orang-orang<br />
yang diduga sebagai anggota GAM. Di Aceh,<br />
militer dan Brimob diduga telah menjadikan<br />
sejumlah rumah dan gedung-gedung<br />
pemerintah yang tidak terpakai sebagai tempat<br />
penahanan orang-orang yang ditangkap dengan<br />
tuduhan GAM. 16 Sementara di Papua, sejumlah<br />
informasi menyebutkan satuan Kopassus telah<br />
membuat sejumlah rumah-rumah kosong di<br />
sekitar kabupaten Wamena menjadi rumah<br />
tahanan orang-orang sipil yang diduga sebagai<br />
anggota OPM.<br />
3. Penyiksaan, tindakan kejam tidak<br />
manusiawi, merendahkan martabat dan<br />
hukuman kejam<br />
Kejahatan penyiksaan terhadap para tahanan<br />
oleh militer dan polisi Indonesia dalam<br />
kerangka mengorek keterangan tentang<br />
keberadaan atau kekuatan kelompok<br />
pemberontak menjadi fokus banyak pihak.<br />
Buruknya pola pengawasan internal di tubuh<br />
militer dan polisi, memungkinkan kejahatan<br />
penyiksaan terjadi di daerah-daerah konflik.<br />
Meskipun pemerintah mengelak tuduhan ini,<br />
berbagai fakta awal yang dikemukakan oleh<br />
organisasi hak asasi manusia nasional dan<br />
internasional menunjukkan indikasi kuat<br />
adanya tindak kejahatan penyiksaan di sejumlah<br />
tempat-tempat penahanan milik militer dan<br />
polisi. Fakta ini semakin menguat ketika<br />
wawancara diam-diam atas sejumlah<br />
narapidana politik Aceh yang dipindahkan ke<br />
pulau Jawa, baru-baru ini membenarkan adanya<br />
tindak kejahatan penyiksaan selama berada<br />
dalam tahanan milik militer atau polisi.<br />
Berbagai fakta juga menyebutkan adanya<br />
indikasi kuat peristiwa kejahatan penyiksaan,<br />
tindakan tidak manusiawi, merendahkan<br />
martabat dan hukuman kejam yang dilakukan<br />
oleh anggota militer dan polisi pada saat<br />
operasi-operasi penyisiran kelompok<br />
pemberontak. Di Wamena, buntut dari peristiwa<br />
penyerangan markas Komando Distrik Wamena<br />
oleh kelompok pemberontak, puluhan orang<br />
dilaporkan menjadi korban penyiksaan,<br />
perlakuan kejam, tidak manusiawi<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
dari satuan Kopasus dan Brimob, Mei 2003. 17 Di<br />
Aceh, operasi penyisiran yang digelar oleh<br />
pasukan militer di daerah Aceh Timur,<br />
berbuntut dengan tindakan tidak manusiawi<br />
atas sejumlah penduduk sipil di daerah tersebut.<br />
Di Sumatera Utara, Unit Anti Terror Brimob<br />
Binjai dilaporkan telah menyiksa 6 orang<br />
penduduk sipil yang diduga anggota jaringan<br />
terorisme. 18 Di Solo dan beberapa daerah<br />
lainnya, unit anti terror polisi juga dilaporkan<br />
36 Bagian III
telah melakukan tindak penyiksaan terhadap<br />
para tahanan tersangka peledakan bom untuk<br />
mengorek informasi tentang keberadaan<br />
jaringan tersebut. 19<br />
4. Orang Hilang dan Penemuan Mayat<br />
Kasus-kasus orang hilang di wilayah konflik<br />
juga menjadi perhatian banyak pihak khususnya<br />
sejumlah organisasi hak asasi manusia.<br />
Kejahatan penghilangan orang di daerah konflik<br />
terus meningkat tajam, terutama pasca<br />
pemberlakukan keadaan darurat maupun<br />
pengiriman-pengiriman satuan-satuan anti<br />
pemberontak di wilayah konflik. Beroperasinya<br />
satuan-satuan khusus anti pemberontak di Aceh<br />
dan Papua, diduga telah meningkatkan<br />
kejahatan penghilangan orang di Papua dan<br />
Aceh. Beberapa laporan organisasi hak asasi<br />
manusia lokal, menyebutkan adanya unit-unit<br />
militer yang bertugas menjemput orang-orang<br />
yang diduga anggota kelompok pemberontak.<br />
Di Papua, Theis Hiyo Eluay, Ketua Presidium<br />
Dewan Adat Papua, ditemukan tewas setelah<br />
beberapa hari sebelumnya dijemput di<br />
rumahnya oleh beberapa orang yang mengaku<br />
anggota kopasus. 20 Nasib serupa juga dialami<br />
oleh Wanggai, pemimpin populer Papua, 1998<br />
dan Willem Onde 2001. Di Aceh, puluhan<br />
keluarga mengaku anggota keluarganya hilang<br />
setelah sejumlah orang yang menumpangi<br />
mobil kijang berkaca gelap membawanya dari<br />
rumah. Sebagian dari orang-orang ini kemudian<br />
ditemukan tewas di areal persawahan,<br />
mengapung di sungai, bawah jembatan, tak jauh<br />
dari tempat tinggal mereka beberapa hari setelah<br />
mereka dinyatakan hilang. 21<br />
5. Pembatasan Ruang Gerak dan<br />
Pencabutan Hak Untuk Mengeluarkan<br />
Pendapat<br />
Pemberlakukan keadaan darurat,<br />
penggelaran operasi anti gerilya dan pemisahan<br />
penduduk atas dasar agama dan etnis, dengan<br />
otomatis menghilangkan hak-hak individu<br />
untuk bergerak dan mengeluarkan pendapat,<br />
seperti yang tercantum dalam konstitusi dan<br />
hukum hak asasi manusia nasional. Dengan<br />
alasan keamanan dan ketertiban, penguasa<br />
militer maupun sipil mengeluarkan sejumlah<br />
pembatasan dan pelarangan terhadap aktivitas<br />
penduduk di wilayah konflik. Strategi<br />
pemisahan antara penduduk sipil dengan<br />
kelompok pemberontak dan blokade wilayah<br />
yang dilancarkan pihak militer di Aceh dan<br />
Papua membuat penduduk lokal tidak bisa<br />
bepergian ke luar desa. Penguasa militer<br />
mengharuskan penduduk untuk mengurus<br />
surat jalan jika ingin bepergian ke luar desa, agar<br />
lolos dari pemeriksaan di setiap pos-pos militer<br />
yang mereka lalui. Aktivitas sosial penduduk,<br />
seperti penyelenggaraan pernikahan maupun<br />
acara-acara keagamaan harus mendapatkan izin<br />
dari penguasa militer atau sipil setempat, jika tak<br />
ingin acara mereka dibubarkan dan<br />
pengundangnya pun ditangkap dengan tuduhan<br />
makar. Pembatasan ini pun juga termasuk<br />
pelarangan orang luar daerah dan orang asing<br />
datang ke wilayah yang dinyatakan dalam<br />
keadaan darurat, sehingga membuat orang-orang<br />
lokal tidak bisa berhubungan dengan<br />
keluarga maupun sanak famili mereka yang<br />
tinggal di luar propinsi.<br />
Di Aceh, PDMD mengeluarkan maklumat<br />
berkaitan dengan pelarangan penyelenggaraan<br />
pertemuan publik, termasuk pengadaan training<br />
maupun workhsop-workshop, khususnya<br />
yang bertema hak asasi manusia. Di samping itu,<br />
PDMD juga melarang organisasi nonpemerintah<br />
(Ornop) internasional beroperasi di<br />
Aceh. PDMD juga membatasi keluar masuk orang<br />
ke Aceh, termasuk berlayar di perairan<br />
wilayah Aceh. Kebijakan-kebijakan ini<br />
kemudian berakibat pada semakin mengecilnya<br />
ruang gerak penduduk sipil baik dalam bidang<br />
politik, ekonomi sosial dan budaya. Seperti<br />
misal, banyak penduduk lokal yang tidak dapat<br />
mencari nafkah sehingga membuat mereka<br />
kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. 22<br />
Beberapa kegiatan training yang dilakukan oleh<br />
institusi pemerintah sipil, organisasi<br />
kepemudaan dan organisasi hak asasi<br />
manusia di Aceh juga dibubarkan karena tidak<br />
memiliki izin dari penguasa militer setempat. 23<br />
Pembatasan ini juga melebar hingga<br />
pembatasan aktivitas organisasi hak asasi<br />
manusia dan penanganan pengungsi di Aceh,<br />
terutama organisasi-organisasi internasional.<br />
Tidak berbeda dengan Aceh, praktik-praktik<br />
pembatasan terhadap aktivitas politik, ekonomi,<br />
sosial dan budaya penduduk sipil<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
37
mengakibatkan penduduk lokal harus<br />
menanggung persoalan-persoalan baru,<br />
terutama di bidang ekonomi. Pembatasanpembatasan<br />
ini dikeluarkan melalui regulasi<br />
daerah. Di seluruh Papua, aktivitas politik dan<br />
sosial penduduk lokal terganggu karena<br />
munculnya Surat Keputusan Bersama tentang<br />
Pelarangan Peringatan Hari Kematian Theis dan<br />
Penyelenggaran Hari Kemerdekaan Papua. SK<br />
tersebut dengan serta merta menjadi alat untuk<br />
membubarkan dan menangkap para peserta<br />
demonstrasi di seluruh wilayah Papua. 24 Di<br />
samping menggunakan regulasi daerah,<br />
pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan<br />
dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan<br />
ancaman yang ditujukan kepada pemimpin atau<br />
tokoh masyarakat yang tidak segaris dengan<br />
kebijakan pemerintah sipil daerah atau pejabat<br />
militer. Januari 2001, Kejaksaan Tinggi (Kejati)<br />
Papua, H Bismar Mannu SH mengeluarkan<br />
statement bahwa Theis cs terbukti melakukan<br />
makar. 25 Di Pegunungan Bintang dan Mulia,<br />
penerapan strategi militer untuk memblokade<br />
wilayah pasca penyerangan anggota militer di<br />
wilayah tersebut membuat penduduk lokal<br />
kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka<br />
karena pasokan-pasokan bahan pokok<br />
dibatasi. 26<br />
6. Kejahatan Terhadap Pekerja<br />
Kemanusiaan<br />
Menguatnya penggunaan langkah-langkah<br />
militer untuk menangani ketegangan politik dan<br />
sosial di beberapa daerah juga berakibat<br />
semakin rentannya aksi-aksi kekerasan terhadap<br />
para pekerja kemanusiaan. Kontrol militer<br />
terhadap wilayah-wilayah yang dinyatakan<br />
sebagai daerah operasi militer, membuat ruang<br />
gerak dari para pekerja kemanusiaan semakin<br />
terbatas. Para pekerja hak asasi manusia kerap<br />
dilarang untuk menjalankan kerja-kerja<br />
pemantauan peristiwa pelanggaran hak asasi<br />
manusia dengan dalih daerah tersebut<br />
merupakan daerah tertutup. Para penguasa<br />
militer setempat mengeluarkan kebijakan dalam<br />
bentuk maklumat atau memblokade yang<br />
melarang organisasi-organisasi hak asasi<br />
manusia beroperasi di wilayah tersebut.<br />
Sejumlah pekerja hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik, kerap mendapat terror dan ancaman<br />
dari orang-orang tidak dikenal yang isi dari<br />
ancaman tersebut meminta agar mereka segera<br />
berhenti melakukan pencatatan atas fakta-fakta<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik. Di samping itu, Polisi dan militer lokal<br />
kerap mengeluarkan ancaman akan menangkap<br />
38 Bagian III
sejumlah pekerja hak asasi manusia. 27<br />
Di Aceh, dengan menuduh sebagai kaki<br />
tangan pemberontak GAM, militer menangkap<br />
dan memenjarakan sejumlah pekerja hak asasi<br />
manusia. Di Papua, Blokade militer terhadap<br />
wilayah Pegunungan Mulia, pasca peristiwa<br />
pembunuhan penduduk sipil oleh orang-orang<br />
tidak dikenal, membuat sejumlah aktivis hak<br />
asasi manusia yang akan melakukan investigasi<br />
pelanggaran hak asasi manusia gagal untuk<br />
melakukan investigasi karena blokade militer<br />
yang cukup ketat. Di poso, seorang pendeta yang<br />
kerap bersuara keras tentang tindak pelanggaran<br />
hak asasi manusia terhadap penduduk sipil,<br />
kemudian ditangkap, setelah mobil yang<br />
ditumpanginya tiba-tiba ditemukan senjata api<br />
saat pasukan militer dan polisi melakukan<br />
sweeping. Di Ambon, pertengahan 2000, tiga<br />
orang pekerja hak asasi manusia ditangkap oleh<br />
anggota militer karena dituduh sebagai<br />
provokator dan kemudian selama di pos militer<br />
pekerja kemanusiaan tersebut dipukuli hingga<br />
babak belur. 28 Kriminalisasi ini menyebabkan<br />
para pekerja hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik terpaksa keluar dari wilayah-wilayah<br />
konflik agar terhindar dari ancaman tersebut.<br />
Tak heran jika kemudian peristiwa-peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah<br />
konflik sulit untuk diketahui.<br />
Di samping itu, praktik-praktik kekerasan<br />
terhadap para pekerja kemanusiaan juga tidak<br />
hanya terjadi di wilayah konflik saja. Sejumlah<br />
pekerja hak asasi manusia yang secara rutin<br />
melaporkan informasi berkaitan dengan<br />
pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah<br />
konflik pun juga turut menjadi sasaran dari<br />
tindak kekerasan dan terror dari orang-orang<br />
yang tidak dikenal. Baru-baru ini, seorang tokoh<br />
hak asasi manusia, Munir SH, dibunuh oleh orang<br />
tidak dikenal dalam perjalanan menuju<br />
Belanda untuk melanjutkan studi. Sebelumnya,<br />
Munir dikenal tokoh yang cukup berani untuk<br />
memberitakan peristiwa-peristiwa pelanggaran<br />
hak asasi manusia di wilayah konflik.<br />
RESPON NEGARA ATAS KEJAHATAN<br />
HAK ASASI MANUSIA<br />
Dalih pemberlakuaan kebijakan darurat<br />
militer/sipil di wilayah konflik menjadi tempat<br />
aman para pihak di institusi militer dan Polri<br />
yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi<br />
manusia untuk berlindung dari langkahlangkah<br />
penyelidikan pihak Komnas HAM.<br />
Seolah seperti kebal dari hukum, para perwira<br />
militer/Polri melihat langkah-langkah<br />
penanganan wilayah konflik yang mereka ambil<br />
adalah demi menjaga keutuhan NKRI, sehingga<br />
tidak patut diklaim sebagai pelaku pelanggaran<br />
hak asasi manusia. Di Aceh, penguasa darurat<br />
militer membantah hasil penyelidikan Komnas<br />
HAM dengan dalih informasi-informasi yang<br />
diperoleh tidak berimbang dan lebih berat<br />
memojokkan institusi TNI/Polri. 29 Di Papua,<br />
dengan arogan militer menyangsikan fakta-fakta<br />
penyelidikan yang dilakukan oleh organisasiorganisasi<br />
HAM dan mereka balik menuduh<br />
pihak-pihak yang mengungkap kasus-kasus orang<br />
hilang ini adalah pihak yang mencoba<br />
memperkeruh keadaan atau memojokkan<br />
institusi militer dan polisi. Selanjutnya TNI balik<br />
mengancam akan menuntut pihak-pihak yang<br />
menuduh TNI terlibat dalam peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun<br />
Papua ke pengadilan. 30 Baru-baru ini, pihak<br />
Penguasa Darurat Sipil dan Pejabat TNI di<br />
Jakarta mengancam akan menuntut balik <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> Watch (HRW) jika informasi adanya<br />
praktik-praktik penyiksaan sejumlah<br />
narapidana politik tidak terbukti. 31 . Sekalipun<br />
banyak informasi awal yang memperkuat<br />
adanya indikasi kejahatan penyiksaan, tidak<br />
membuat pemerintah Indonesia segera<br />
membentuk tim penyelidikan independen<br />
untuk menyelidikan kasus tersebut. Klaim<br />
bahwa pemerintah, terutama TNI dan Polri,<br />
telah membentuk tim penyelidik internal<br />
mereka mengelak desakan pembentukan tim<br />
independen kasus-kasus penyiksaan.<br />
Sikap arogan dari militer inilah yang<br />
kemudian membuat praktik-praktik<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik terus terjadi dan sulit untuk diungkap.<br />
Hingga saat ini minim sekali para pelaku<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil<br />
diadili. Bahkan lolosnya sejumlah perwira<br />
militer dari pengadilan HAM Ad hoc<br />
pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor,<br />
membuat para perwira yang diduga terlibat<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
Konflik, semakin berani menantang pihakpihak<br />
yang ingin memperkarakannya. Hasil<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
39
pengadilan itu pun secara tidak langsung<br />
membuat justifikasi bahwa tindak kekerasan<br />
dan brutal anggota militer/polisi di wilayah<br />
konflik adalah tindakan yang tepat dan bukan<br />
tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena<br />
tindakan itu ditujukan dalam rangka menjaga<br />
keutuhan NKRI.<br />
KESIMPULAN<br />
Penerapan regulasi kedaruratan dan<br />
pengerahan kekuatan militer untuk<br />
menyelesaikan pemberontakan dan konflik<br />
komunal adalah pilihan yang tidak tepat.<br />
Langkah-langkah seperti itu justru kembali<br />
membuka peluang kebangkitan otoriterisme<br />
kembali hidup di Indonesia. Akibat lainnya,<br />
penggunaan langkah-langkah militer untuk<br />
menyelesaikan pemberontakan dan konflik<br />
komunal justru menimbulkan pelanggaran hak<br />
asasi manusia baru, dan membuat upaya<br />
penyelesaian semakin menjauh dari akar<br />
masalahnya. Di lain pihak, penggunaan<br />
langkah-langkah militer juga membuat upayaupaya<br />
perbaikan kondisi hak asasi manusia<br />
nasional terus menurun, karena lingkar impunity<br />
yang diciptakan oleh kondisi kedaruratan<br />
itu sendiri semakin kuat dan permanen.<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Lih., Mengembalikan Penyelesaian Aceh Melalui<br />
Cara-cara Damai, Brifieng paper ELSAM, November<br />
2003.<br />
2<br />
Dikenal publik dengan sebutan CoHA.<br />
3<br />
Lih., Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan<br />
Sulit Dipertahankan?, ELSAM, Briefing Paper, Mei 2003<br />
4<br />
Lih., Memoria Pasionis, Gambaran Hak Asasi<br />
Manusia Papua Tahun 2001, Sekretarian Keadilan dan<br />
Perdamaian Keuskupan Papua, 2001; “Papua Barat:<br />
Gerakan Kemerdekaan Meraih Momentum,” Down To<br />
Earth Nr 45 Mei 2000; “Mabes TNI Kirim Pasukan Ke<br />
Papua,” www.dephan.go.id, 9 Agustus 2003<br />
5<br />
Abdurrahman Wahid selalu mendukung Komnas<br />
HAM untuk membentuk Komisi Penyelidikan<br />
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM). KPP HAM<br />
Abepura adalah salah satu bentuk kongkrit dukungan<br />
Abdurrahman Wahid terhadap upaya penyelidikan<br />
peristiwa penyerangan dan pemukulan secara brutal<br />
Brimob Papua terhadap para demonstran di Abepura 7<br />
Desember 2000.<br />
6<br />
Bentuk pengabaian ini antara lain adalah pembuatan<br />
Surat Keputusan Bersama Tentang Pelarangan<br />
Perayaan Hari Kematian Theis Eluay (11 November)<br />
dan Perayaan Kemerdekaan Papua (1 Desember)<br />
Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejati Papua dan juga<br />
penggelaran operasi intelejen liar di beberapa daerah,<br />
kasus pembunuhan Theis November 2002 oleh<br />
anggota Satgas Cendrawasih diduga tanpa<br />
sepengetahuan pemerintahan sipil Jakarta.<br />
7<br />
Meluasnya berbagai tindak kekerasan di Papua,<br />
menyebabkan aktivitas pengiriman pasukan militer<br />
dan Brimob ke Papua terus meningkat. Alasan<br />
menghentikan kerusuhan atau memperkua penjagaan<br />
di wilayah perbatasan, menjadi argumen kuat atas<br />
pengiriman-pengiriman pasukan ke Papua dalam<br />
beberapa tahun terakhir.<br />
8<br />
Wawancara ELSAM dengan Pekerja Hak Asasi<br />
Manusia Asal Papua, di Jakarta Awal Desember <strong>2004</strong>,<br />
juga Lih., Memoria Passionis di Papua, Kondisi Sosial<br />
Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2001,<br />
Sekretarian Keuskupan Papua, Jakarta 2002<br />
9<br />
Aktivitas para pejabat sipil (Walikota dan Bupati)<br />
mengorganisir pemuda untuk menjadi milisi<br />
meningkat pesat sejak pertengahan 2002 sampai<br />
sekarang. Pembentukan milisi ini mendapat dukungan<br />
kuat dari para pejabat militer dan polisi di tingkat<br />
kabupaten, seperti Komandan Kodim dan Kapolres.<br />
Sejumlah pemimpin partai atau anggota DPRD lokal<br />
juga ikut andil dalam pembentukan milisi-milisi ini.<br />
Bahkan mantan Komandan milisi Aitarak di Timor<br />
Leste, Eurico Gueteres, pernah terlihat dalam acara<br />
peresmian Front Pembela Merah Putih di Timika 12<br />
November 2003. Lih., Van Den Broek, Theo, Situasi<br />
Akhir Tahun 2003 di Papua, Refleksi, Sekretarian<br />
Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Jayapura,<br />
November 2003.<br />
10<br />
Dokumentasi kekerasan ELSAM Wilayah Aceh,<br />
Tentang Monitoring Darurat Militer, periode Mei 2003 -<br />
April <strong>2004</strong> dan Dokumentasi kekerasan ELSAM<br />
Wilayah Papua, 1999-<strong>2004</strong>.<br />
11<br />
Ibid.<br />
12<br />
The Situation in Ambon/Mallucas-<strong>Report</strong> No.343,1<br />
Agustus 2003<br />
13<br />
Op. Cit., Brifieng Paper ELSAM No 2, 2003<br />
14<br />
Lih, laporan, “Suasana Kemasyarakatan di<br />
Pegunungan Bintang,” Sekretarian Keadilan dan<br />
Perdamaian (SKP) Jayapura, Februari 2002 dan “Papua<br />
Aktual April-Juni <strong>2004</strong>, SKP; “Laporan Kekerasan di<br />
Kecamatan Ilaga Kabupaten Puncak Jayawijaya,” SKP<br />
Keuskupan Jayapura, April 2002 dan “Laporan Awal<br />
Kasus Wamena,” Koalisi LSM untuk Perlindungan dan<br />
Penegakan HAM di Papua, Jayapura 6 Mei 2003.<br />
15<br />
Lih., Perang Tersembunyi, Aceh dalam Darurat<br />
Militer, <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> Wacth <strong>Report</strong>, 2002<br />
16<br />
“PDMP siapkan penampungan sementara untuk GSA<br />
yang menyerah,” Kompas Cyber Media, 28 Juni 2003<br />
17<br />
Op. Cit., Laporan Awal Kasus Wamena.<br />
18<br />
Fact-sheet TIM Pengacara Muslim tentang kronologi<br />
penangkapan dan penyiksaan orang-orang yang<br />
diduga anggota terroris, tertanggal Februari <strong>2004</strong>.<br />
19<br />
Ibid.<br />
40 Bagian III
20<br />
“ Markas Satgas Cendrawasih Disegel Polisi Militer,”<br />
Kompas, 2 Maret 2002.<br />
21<br />
Dokumen Kekerasan ELSAM Tentang Darurat Militer<br />
di Aceh Periode Mei 2003- Mei <strong>2004</strong>.<br />
22<br />
Lih., “Perang dan Ketahanan Pangan,” Down to<br />
Earth, Nr 55 Agustus 2003.<br />
23<br />
Wawancara dengan wartawan lokal di Aceh, Juli<br />
<strong>2004</strong>.<br />
24<br />
Sepanjang 2003 dan <strong>2004</strong>, praktik-praktik kebebasan<br />
berekspresi dan berpendapat di Papua menurun<br />
drastis, tidak seperti tahun sebelumnya, karena polisi<br />
mengancam akan menangkap dan menahan bagi siapa<br />
saja yang melakukan demonstrasi di jalan. Para<br />
peserta yang tertangkap kemudian banyak yang<br />
dituduh menjadi kaki tangan OPM. Wawancara dengan<br />
pekerja hak asasi manusia asal Papua, di Jakarta,<br />
November <strong>2004</strong>.<br />
25<br />
“Memoria Passionis: Kondisi Sosial Politik dan Hak<br />
Asasi Manusia Gambaran 2001", SKP dan LSSP,<br />
Jakarta 2002., hlm 9<br />
26<br />
“Tiga Warga Kuyawage Dilaporkan Mati Kelaparan,<br />
Setelah Dinyatakan Daerah Tertutup,” Kompas, 24 Mei<br />
2003.<br />
27<br />
Puluhan pekerja kemanusiaan di Aceh, saat Darurat<br />
Militer berlangsung harus eksodus ke luar Aceh,<br />
karena nama-nama mereka disebut oleh polisi sebagai<br />
target operasi. Hal serupa juga terjadi di Papua, Maluku<br />
dan Poso. Wawancara dengan 10 orang pekerja hak<br />
asasi manusia asal Aceh Papua, Maluku dan Poso di<br />
Jakarta dan Bangkok, Desember 2003.<br />
28<br />
Wawancara dengan pekerja hak asasi manusia di<br />
Ambon, April 2000<br />
29<br />
Pangab Jenderal Sutarto dan KASAD Jenderal<br />
Rymizard Ryacudu menolak laporan Tim Pencari Fakta<br />
Komnas HAM yang diketuai oleh MM Bilah dengan<br />
alasan laporan tersebut tidak valid dan sangat<br />
memihak kelompok GAM. Lih., Wawancara Abdul<br />
Hakim Garuda Nusantara, “Komnas HAM Sudah<br />
Cukup hati-hati,” Majalah Tempo No 17/XXXII/23-29<br />
Juni 2003.<br />
30<br />
Lih., Papua Aktual April-Juni <strong>2004</strong>, SKP Keuskupan<br />
Jayapura, Juli <strong>2004</strong>., hlm 20.<br />
31<br />
Lih., “ HRW Tuding TNI Siksa Tahanan GAM,” Koran<br />
Tempo, 28 September <strong>2004</strong><br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
41
BAGIAN KEEMPAT<br />
Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi<br />
dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus<br />
Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh<br />
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di<br />
Indonesia Dalam Kerangka Otonomi Daerah<br />
PENGANTAR<br />
Banyak kalangan berharap otonomi daerah<br />
akan mendatangkan perbaikan kondisi<br />
hidup rakyat di berbagai daerah di Indonesia.<br />
Salah satunya adalah perbaikan terhadap<br />
kondisi hak asasi manusia. Namun setelah lima<br />
tahun proses otonomi itu berjalan harapan itu<br />
sepertinya kian pudar. Faktor penting yang menyebabkan<br />
belum terealisasinya perlindungan<br />
dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat itu<br />
adalah masih kuatnya kecendrungan<br />
keberpihakan penyelenggara pemerintahan<br />
terhadap kepentingan investasi atau modal.<br />
Keberpihakan penyelenggara negara di tingkat<br />
daerah terhadap kepentingan investor itu bisa<br />
dilihat dari kerapnya terjadi peristiwa<br />
penggusuran, pengabaian penyelesaian kasuskasus<br />
perampasan tanah masa lalu, penertiban<br />
pedagang informal dan penghilangan hak-hak<br />
penduduk asli untuk mengelola sumber-sumber<br />
kekayaan alamnya. Implementasi otonomi<br />
daerah yang keliru ini di sisi lain juga<br />
menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kelas<br />
bawah untuk mendapatkan akses pada<br />
pelayanan publik yang baik, seperti kesehatan,<br />
pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Gejala<br />
umum ini bisa kita temui di hampir seluruh<br />
provinsi dan kabupaten/kota saat ini.<br />
Secara umum bagian ini mencoba melihat<br />
bagaimana otonomi daerah itu<br />
dimplementasikan, terutama implikasinya<br />
terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi<br />
manusia di daerah. Selain itu juga mencoba<br />
menguraikan kemajuan-kemajuan di bidang<br />
hak asasi manusia yang telah mampu dicapai<br />
oleh implementasi otonomi daerah tersebut.<br />
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI<br />
BERBAGAI DAERAH<br />
Desentralisasi kekuasaan merupakan<br />
tuntutan utama yang disuarakan oleh kelompok<br />
pro-reformasi di daerah-daerah. Kuatnya<br />
tuntutan desentralisasi itu bertolak dari<br />
pengalaman buruk di masa lalu ketika<br />
berhadapan dengan pemerintahan yang<br />
sentralis yang memonopoli seluruh urusan<br />
daerah. Sebagai langkah awal demokratisasi<br />
penyelengaraan negara, otonomi daerah<br />
diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan<br />
pemerataan pembangunan.<br />
Gelombang tuntutan yang terus membesar<br />
bahkan disertai ancaman untuk melepaskan diri<br />
dari NKRI, pada akhirnya membuat Jakarta<br />
harus meluluskan tuntutan tersebut. Dengan<br />
mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun1999<br />
tentang Otonomi Daerah, Jakarta sepakat untuk<br />
melimpahkan sebagian besar kekuasaannya<br />
kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung<br />
UU Nomor 22 Tahun1999, Jakarta kemudian<br />
mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999<br />
tentang Perimbangan Keuangan Antara<br />
Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejumlah<br />
regulasi dalam bentuk Keppres dan Inpres juga<br />
dikeluarkan oleh Jakarta untuk menunjang<br />
implementasi Otda. Selepas UU tersebut<br />
dikeluarkan, tepatnya sejak 2000, seluruh<br />
pemerintah daerah kemudian melakukan<br />
langkah-langkah persiapan sebagai<br />
pengejawantahan atas UU tersebut yakni<br />
mengambil langkah-langkah persiapan seperti:<br />
memproduksi perda yang akan menunjang<br />
proses Otda di tingkat daerah, melakukan<br />
pemekaran wilayah-wilayah administrasi,<br />
42 Bagian IV
merumuskan ulang tugas dan kewenangan<br />
kantor wilayah, dinas dan badan usaha daerah .<br />
Pelaksanaan Otda di beberapa daerah<br />
ditandai dengan produksi Perda tentang sistem<br />
organisasi pemerintah daerah, pengaturan<br />
pengelolaan situs-situs ekonomi lokal, termasuk<br />
di sini Perda pengambilalihan sejumlah situs<br />
yang dulu dikuasai oleh pemerintah pusat, dan<br />
Perda tentang penanaman modal asing/nasional<br />
di daerah. Sejalan dengan itu pemerintah daerah<br />
pun kemudian menggencarkan penggalian<br />
potensi-potensi kekayaan alam dan nonkekayaan<br />
alam yang dapat menambah<br />
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda-perda<br />
tentang pajak dan retribusi pun kemudian<br />
membanjiri seluruh propinsi dan kabupaten di<br />
Indonesia. Belakangan perda-perda ini justru<br />
membuat ekonomi tinggi di hampir seluruh<br />
daerah. 1<br />
Selanjutnya, penerapan Otda juga ditandai<br />
dengan pemekaran atas puluhan wilayah di<br />
berbagai tempat, bahkan sejumlah propinsi<br />
turut pula memekarkan diri dengan alasan<br />
wilayahnya terlalu luas yang akan berdampak<br />
pada kegagalan dalam pemerataan<br />
pembangunan. 2 Lebih dari tiga propinsi di Indonesia<br />
yang membelah menjadi dua propinsi<br />
sebagai bagian dari proses penerapan Otda.<br />
Sementara, hampir seluruh propinsi kemudian<br />
memekarkan daerah kabupaten dan kota di<br />
wilayahnya untuk menyongsong penerapan<br />
Otda Mei 2001. Belakangan diketahui<br />
pemekaran ini hanya strategi untuk mensiasati<br />
kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari<br />
pemerintah pusat. 3 Pemekaran ini pun<br />
kemudian juga diteruskan reorganisasi atas<br />
institusi-institusi pemerintah daerah di tingkat<br />
Propinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk juga<br />
jajaran kantor wilayah, dinas-dinas pelaksana<br />
teknis yang dulu berada di bawah kendali<br />
pemerintah pusat. Langkah-langkah<br />
reorganisasi tersebut antara lain: menyusun<br />
garis hirarki dan koordinasi antara instansi<br />
daerah dan merumuskan ulang tugas dan<br />
kewenangan dari masing-masing instansi.<br />
Seiring dengan proses pelaksanan Otda<br />
tersebut, berbagai ketegangan politik dan sosial<br />
pun terjadi di daerah. Bermula dari ketegangan<br />
antara pemerintah daerah dengan Jakarta<br />
menyangkut komposisi perimbangan keuangan<br />
antara pemerintah pusat dan daerah kemudian<br />
meluas menjadi ketegangan antar elit daerah<br />
berkaitan dengan perebutan jabatan-jabatan<br />
strategis di daerah. Ketegangan-ketegangan ini<br />
tak jarang berujung pada lahirnya kekerasan<br />
massal. Isu etnis, agama, atau ras kemudian naik<br />
kepermukaan sebagai cerminan pertarungan<br />
politik antar elit daerah. Konflik di Maluku,<br />
Poso, dan Sampit semakin membesar ketika<br />
otonomi daerah diterapkan karena kelompok<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
43
elit lokal yang ikut bertikai kembali<br />
menggunakan pendukungnya untuk kembali<br />
melakukan tindak kekerasan terhadap para<br />
lawan politiknya. Berbagai informasi dari lima<br />
wilayah tersebut menunjukkan adanya indikasi<br />
kuat keterlibatan sejumlah elit politik lokal<br />
dalam memobilisasi massa untuk melakukan<br />
tindak kekerasan. 4<br />
Mei 2001, Otonomi daerah resmi dijalankan<br />
dan untuk pertama kalinya Pemerintah daerah<br />
memiliki kewenangan atas wilayahnya sendiri.<br />
Segera setelah pemberlakuan Undang-undang<br />
Nomor 22 Tahun 1999 penarikan pajak,<br />
retribusi daerah mulai dilakukan oleh<br />
pemerintah terhadap seluruh sektor di setiap<br />
daerah. kemudian untuk meningkatkan PAD,<br />
sejumlah situs-situs ekonomi pun mulai<br />
ditawarkan dan diserahkan kepada para<br />
pemodal. Pembangunan prasarana dan sarana<br />
sebagai prasyarat memacu laju investasi ke<br />
daerah pun mulai dijalankan oleh dinas-dinas<br />
teknis yang berada dalam hirarki gubernur atau<br />
bupati/walikota. Proses pelaksanaan inilah yang<br />
kemudian kembali membuat aksi kekerasan<br />
terhadap penduduk lokal kembali terulang. Di<br />
samping itu, fakta lain juga menyebutkan bahwa<br />
pelaksanaan Otonomi daerah justru menjadi<br />
menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan<br />
nepotisme baru di lingkungan pemerintahan<br />
daerah. Pejabat di DPRD, Pemerintah daerah<br />
propinsi dan kabupaten/kota, serta kantor dinas<br />
di daerah melakukan praktik-praktik korupsi<br />
atas sejumlah pendanaan proyek-proyek<br />
pembangunan dan anggaran belanja daerah<br />
maupun kegiatan-kegiatan studi banding di<br />
dalam maupun luar negeri. 5 Hingga<br />
pertengahan <strong>2004</strong> ini puluhan kasus korupsi<br />
oleh pejabat pemerintah terungkap, namun<br />
demikian hanya sedikit saja yang diusut hingga<br />
ke pengadilan.<br />
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN<br />
HAM DALAM OTONOMI DAERAH<br />
Dalam kesempatan ini Perda diaudit dengan<br />
menggunakan hukum hak asasi manusia<br />
nasional sebagai parameter termasuk sinkronisasi<br />
perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi<br />
dan hukum hak asasi manusia; memproduksi<br />
regulasi daerah yang lebih menguatkan<br />
implementasi hukum hak asasi manusia<br />
nasional; mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia<br />
Daerah; Menyelenggarakan pelatihan hak asasi<br />
manusia bagi aparatur pemda; Menyusun buku<br />
saku untuk pegawai pemerintah daerah; serta<br />
mengeluarkan laporan tentang kondisi hak asasi<br />
manusia di daerahnya, ELSAM mencoba<br />
melakukan observasi atas sejumlah langkahlangkah<br />
atas sejumlah pemerintah daerah.<br />
Dimulai dengan mengumpulkan dokumen<br />
resmi, ELSAM kemudian memperkuat analisis<br />
dokumen tersebut dengan melakukan<br />
wawancara singkat dengan organisasi hak asasi<br />
manusia di tingkat daerah.<br />
Norma hak asasi manusia internasional dan<br />
nasional mewajibkan kepada negara, untuk<br />
mengambil langkah-langkah perlindungan hak<br />
asasi manusia, baik melalui langkah-langkah<br />
legislatif maupun langkah-langkah lain yang<br />
memperkuat langkah-langkah legislatif<br />
tersebut. Istilah negara, disini adalah pemerintah<br />
nasional dan pemerintah-pemerintah daerah<br />
hingga tingkat kecamatan. Jadi jelas bahwa<br />
pemerintah daerah terikat dengan ketentuan ini.<br />
Sebagai penguasa lokal Gubernur atau Bupati<br />
semesti mengambil langkah-langkah<br />
pembuatan kebijakan di tingkat daerah serta<br />
langkah-langkah lain yang dapat memperkuat<br />
upaya-upaya penghormatan dan perlindungan<br />
terhadap hak asasi manusia.<br />
1. Perda yang Anti Hak Asasi Manusia<br />
Dalam lima tahun terakhir, produk regulasi<br />
daerah yang memperkuat implementasi hukum<br />
hak asasi manusia nasional di tingkat daerah<br />
masih terbatas. Konsentrasi terbesar atas<br />
produksi regulasi daerah lebih dititikberatkan<br />
pada bidang ekonomi dan pemekaran wilayah. 6<br />
Selain itu, upaya-upaya sinkronisasi atas<br />
sejumlah regulasi daerah dengan hukum hak<br />
asasi manusia nasional juga tidak ditemukan.<br />
Produksi regulasi daerah khusus tentang perlindungan<br />
hak-hak perempuan pun, juga tidak<br />
ditemukan di semua Pemda. Padahal kasuskasus<br />
kejahatan terhadap perempuan di<br />
berbagai daerah telah menjadi endemik. Di<br />
sejumlah daerah, produk-produk regulasi baru<br />
ini dilaporkan turut andil dalam melahirkan<br />
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Penarikan pajak dan retribusi menyebabkan<br />
penghasilan penduduk lokal mulai berkurang<br />
44 Bagian IV
karena usaha-usaha kecil mereka juga<br />
dikenakan pajak atau retribusi. Sementara<br />
pelaksanaan kebijakan memacu investasi daerah<br />
dan pembangunan sarana dan prasarana umum<br />
membuat masyarakat kembali kehilangan<br />
haknya atas tanah dan kekayaan alam yang<br />
sudah turun temurun mereka kelola. Di wilayah<br />
pedesaan atau perkampungan, sejumlah<br />
penduduk kembali melaporkan bahwa proses<br />
pemberian konsesi kehutanan, pertambangan<br />
dan perkebunan besar semakin memperkuat<br />
klaim perusahaan atas tanah maupun kekayaan<br />
alam penduduk lokal. Di perkotaan, penataan<br />
kota untuk pembangunan prasarana investasi<br />
maupaun penanganan persoalan kemacetan dan<br />
banjir, menjadi alasan kuat bagi pemerintah<br />
daerah untuk menggusur penduduk urban.<br />
Pemda kemudian memberikan tuduhan atau<br />
cap kriminal kepada penduduk urban untuk<br />
membenarkan langkah-langkah penggusuran<br />
atau pelarangan atas aktivitas penduduk. Cap itu<br />
antara lain: menduduki tanah-tanah milik<br />
BUMN atau pihak swasta, mengganggu<br />
kenyamanan pengguna jalan karena berjualan di<br />
pinggir jalan, menjadi penyebab kemacetan di<br />
jalan karena mengoperasikan kendaraan umum<br />
yang tidak ramah lingkungan serta menjadi<br />
penyebab banjir karena mendirikan rumahrumah<br />
di pinggir kali.<br />
Minimnya regulasi perlindungan hak asasi<br />
manusia ini tidak dibarengi dengan melakukan<br />
revisi atau mencabut atas sejumlah perda-perda<br />
yang bertentangan dengan hak asasi manusia di<br />
masa lalu. Sebut saja di Jakarta, regulasi daerah<br />
tentang Tata Ruang Kota dan Perda Nomor 11<br />
tahun 1988 tentang ketertiban Umum yang<br />
diproduksi pada masa rezim orde baru berkuasa<br />
hingga saat ini belum dicabut. Dan celakanya ini<br />
digunakan oleh Sutiyoso untuk kembali<br />
menggusur ribuan penduduk dan melarang<br />
pedagang kaki lima untuk beroperasi di<br />
sejumlah tempat serta digunakan untuk<br />
melarang beroperasinya becak. Di Tangerang,<br />
Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang<br />
ketertiban, keindahan, dan kebersihan (K3)<br />
Pemerintah Kota Tangerang, yang<br />
membenarkan praktik-praktik penggusuran<br />
hingga laporan ini dibuat juga dicabut. Bahkan<br />
para bupati saat ini menggunakan perda<br />
tersebut untuk menggusur ratusan pedagang di<br />
depan gerbang masuk pergudangan Bandara<br />
Mas, berjarak 200 meter dari pintu gerbang M-<br />
1 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di<br />
Kendari-Sulawesi Tenggara Gubernur hingga<br />
saat ini belum mencabut SK Gubernur Sulawesi<br />
Tenggara No 318 Tahun 2000 tentang<br />
Pembentukan Tim Penanggulangan<br />
Perambahan atau Gangguan kawasan TNRAW<br />
dan Kawasan Hutan Sekitarnya. Padahal SK ini<br />
kerap digunakan sebagai landasan tindakan<br />
pengusiran (pemindahan paksa) penduduk asli<br />
Tobu HukaEa-LaEa. Di Jawa Tengah, Perda No<br />
13 Tahun l991 tentang Ketertiban dan<br />
Keindahan Lingkungan Perkotaan, juga belum<br />
dicabut. Sementara perda ini memberikan<br />
kewenangan kepada Pemerintah kota Semarang<br />
untuk menggusur puluhan pedagang kaki lima<br />
di Jalan Sukowati. Di Sukabumi, Perda Nomor<br />
2 Tahun 1988 tentang K3, hingga saat ini belum<br />
dicabut dan menjadi pembenaran penertiban<br />
pedagang kaki lima. Dan masih banyak lagi<br />
regulasi-regulasi daerah yang bertentangan<br />
dengan hak asasi manusia namun hingga saat ini<br />
belum juga diamandemen, dan pada masa era<br />
otonomi ini justru menjadi senjata pemerintah<br />
propinsi dan kabupaten/kota untuk<br />
menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi,<br />
sosial dan budaya penduduknya sendiri dengan<br />
melancarkan praktik-praktik penggusuran<br />
paksa penduduk asli, petani, nelayan, dan<br />
komunitas urban di sebagian besar wilayah Indonesia.<br />
2. Ketiadaan Institusi perlindungan Hak<br />
asasi Manusia<br />
Reorganisasi struktur Pemerintah daerah<br />
pada masa persiapan dan pelaksanaan Otonomi<br />
daerah tidak dibarengi dengan pembangunan<br />
institusi perlindungan dan penegakan hak asasi<br />
manusia di daerah. Praktis dari pengamatan<br />
program reorganisasi struktur pemerintahan<br />
hanya berkutat pada pembenahan garis hirarki<br />
dan koordinasi antar instansi-instansi yang dulu<br />
tidak berada di bawah Pemerintah daerah.<br />
Berdasarkan pengamatan ELSAM, mayoritas<br />
propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak<br />
memiliki institusi perlindungan hak asasi<br />
manusia. Hanya dua propinsi di Indonesia yang<br />
ditemukan memiliki Kantor Perwakilan<br />
Komnas HAM, dan kantor-kantor itu pun tidak<br />
mendapatkan dukungan politik dan dana yang<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
45
cukup dari pemerintah daerahnya. Dari<br />
indikator tersebut nampak jelas bahwa<br />
reorganisasi struktur pemerintahan daerah<br />
memang tidak diorientasikan kepada upaya<br />
pembangunan dan perlindungan hak asasi<br />
manusia di daerah. Dan akibatnya, banyak<br />
korban hak asasi manusia di daerah yang diam,<br />
karena tidak mengetahui ke mana mereka harus<br />
melapor jika hak-haknya terlanggar. Ketiadan<br />
institusi perlindungan hak asasi manusia ini<br />
semakin diperburuk dengan minimnya<br />
penyelenggaraan program-program pelatihan<br />
hak asasi manusia bagi aparatur daerah.<br />
Pembuatan buku saku hak asasi manusia bagi<br />
para pegawai Pemerintah daerah pun sampai<br />
laporan ini ditulis tidak pernah ditemukan.<br />
3. Penguatan Institusi Kekerasan oleh<br />
Pemerintah Daerah<br />
Hal penting lainnya adalah pelaksanan<br />
otonomi daerah turut berkontribusi atas<br />
menguatnya satuan-satuan semi-militer, di<br />
setiap Pemerintah daerah. Adalah Satuan Polisi<br />
Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam lima<br />
tahun terakhir menjadi institusi sipil yang oleh<br />
pemerintah daerah didorong menjadi satuan<br />
semi-militer. Pasal 120 undang-undang<br />
Otonomi Daerah tentang keberadaan Satpol PP<br />
dan meningkatnya perlawanan penduduk<br />
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh<br />
Pemerintah daerah menjadi<br />
dalih pembenaran untuk<br />
membangun satuan-satuan<br />
keamanan sipil di jajaran<br />
pemerintahannya menjadi<br />
satuan-satuan semi-militer.<br />
Dengan memekarkan jumlah<br />
anggotanya, Satpol PP – dulu<br />
jumlah personilnya tidak lebih<br />
dari 40-an orang – menjadi<br />
ratusan orang pemerintah<br />
daerah mencoba membangun<br />
sebuah pasukan sipil terlatih<br />
yang bisa digunakan untuk<br />
mengamankan regulasi daerah<br />
yang mereka telurkan.<br />
Pemekaran ini pun kemudian<br />
berlanjut dengan pemberian<br />
pelatihan kemiliteran dan<br />
penanganan huru-hara kepada<br />
para personilnya dan pemberian alat-alat<br />
penanganan huru-hara seperti tameng dan<br />
pentungan dalam operasi-operasi penertiban.<br />
Dengan mengundang Polri atau TNI,<br />
pemerintah daerah meminta dua institusi<br />
kekerasan tersebut untuk memberikan pelatihan<br />
militer dan penanganan huru-hara kepada unitunit<br />
Satpol PP di jajarannnya. Bahkan di<br />
beberapa daerah, sejumlah pemerintah propinsi<br />
dan pemerintah kabupaten/kota diketahui<br />
mempersenjatai satuan-satuan Satpol PP<br />
mereka dengan senjata api dengan alasan<br />
menjaga keselamatan anggotanya dari amukan<br />
penduduk lokal dalam pelaksanaan penertiban. 7<br />
Dan sejak saat itu pula praktik-praktik<br />
penertiban oleh pemerintah daerah kerap<br />
diwarnai oleh tindakan brutal dan kejam oleh<br />
Satpol PP. 8<br />
Di samping mempergunakan Satpol PP untuk<br />
melakukan eksekusi penggusuran dan penertiban,<br />
satuan ini juga digunakan oleh pejabat daerah<br />
untuk menghadapi kritik-kritik yang dilancarkan<br />
oleh penduduk lokal maupun aksi-aksi<br />
demonstrasi para korban penggusuran atau<br />
penertiban. Di jawa Barat Satpol PP digunakan<br />
untuk menghadapi kritik-kritik aktivis prodemokrasi<br />
terhadap kebijakan atau perilaku<br />
otoriter dari para pejabat pemerintah. 9 Di Jakarta<br />
Satpol PP, Bantuan Polisi (Banpol), digunakan<br />
untuk menjadi satuan pengamanan demonstrasi<br />
46 Bagian IV
pedagang kakilima di Kantor Walikota Jakarta<br />
Pusat yang meminta pengembalian barang<br />
dagangan mereka yang digaruk Satpol PP dalam<br />
aksi penertiban sebelumnya. 10 Di Purwokerto,<br />
Satpol PP dilibatkan dalam pengamanan<br />
demonstrasi mahasiswa dan pedagang Pasar<br />
Wage. Dalam peristiwa tersebut polisi dan Satpol<br />
PP membubarkan demonstrasi dengan brutal 11 .<br />
PERISTIWA-PERISTIWA PENGUSIRAN<br />
PAKSA PERIODE 1999-<strong>2004</strong><br />
Besarnya produksi regulasi daerah mengenai<br />
pemacuan ekonomi dan pembangunan daerah<br />
serta pembenaran pembentukan satuan-satuan<br />
semi-militer oleh Pemerintah daerah<br />
selanjutnya menjadi penyebab praktik-praktik<br />
pengusiran paksa penduduk asli, petani,<br />
nelayan, dan komunitas urban di seluruh<br />
propinsi. Praktik-praktik pengusiran ini pun<br />
jarang memperhatikan norma-norma hukum<br />
hak asasi manusia nasional dan internasional.<br />
Hal ini semakin diperparah dengan tindakan<br />
brutal dan tidak manusiawi yang ditunjukkan<br />
oleh Satpol PP yang dibantu oleh Polri, TNI<br />
maupun kelompok-kelompok pengaman<br />
swasta.<br />
Dalam lima tahun terakhir, setidaknya lebih<br />
dari 100 kasus pengusiran paksa yang disertai<br />
dengan tindakan brutal terjadi di sejumlah<br />
propinsi dengan latar belakang yang berbedabeda,<br />
seperti penertiban kawasan hutang<br />
lindung, areal pemukiman kumuh dan<br />
kawasan perdagangan liar, serta penertiban<br />
sejumlah angkutan umum yang dianggap<br />
sebagai penyebab terjadinya kemacetan lalu<br />
lintas, maupun dalam rangka pemberian<br />
sumber-sumber ekonomi daerah kepada<br />
pihak swasta. Institusi-institusi dominan yang<br />
terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini selain<br />
masih melibatkan Polisi dan TNI, Satpol PP,<br />
Polisi Khusus Kehutanan atau Jagawana,<br />
Banpol dan satuan-satuan pengaman swasta.<br />
Berikut ini adalah ilustrasi sejumlah kasuskasus<br />
pengusiran paksa besar di berbagai<br />
daerah sepanjang 1999-<strong>2004</strong>.<br />
22 November <strong>2004</strong>, polisi membubarkan<br />
aksi unjuk rasa menolak uji coba<br />
pengoperasian TPST Bojong oleh penduduk<br />
Bojonggede secara paksa. Dalam peristiwa<br />
tersebut, 5 orang mengalami luka akibat<br />
tembakan polisi yang bertugas mengamankan<br />
TPST. Setelah bentrokan, polisi menyisir<br />
rumah-rumah dan menangkap 35 warga<br />
Bojong. Selain itu, dilaporkan pula 133 orang<br />
penduduk bojong hilang dalam peristiwa<br />
tersebut.<br />
Mei 2003 di Kecamatan Reok, Kabupaten<br />
Manggarai, aparat Kepolisian Manggarai<br />
dibantu oleh Brimob Polda NTT, Polsek Reok,<br />
dan Koramil Reok memaksa penduduk asli<br />
Gendang Mahima mengosongan lahan di<br />
kawasan Tanah Erpacht. Dalam aksi tersebut<br />
polisi dan militer melakukan pembakaran dua<br />
buah rumah dan tanaman miliki penduduk.<br />
Dalam peristiwa tersebut, Polisi juga dilaporkan<br />
menganiaya puluhan penduduk asli dan<br />
menangkap 73 orang penduduk asli Gendang<br />
Mahima, 56 laki-laki dan 16 perempuan,<br />
termasuk 1 orang ibu dengan bayinya yang<br />
sedang menyusui. Selanjutnya, penduduk asli<br />
yang ditangkap dipenjarakan di Rutan Kelas IIB<br />
Langgo Ruteng dengan tuduhan penjarahan.<br />
21 Juli 2003 aparat Polres Bulukumba dan<br />
didukung oleh personil Polda Sulawesi Selatan,<br />
Brimob Polwil Bone, Polres Sinjai, dan Polres<br />
Bantaeng melakukan penyerangan terhadap<br />
petani penduduk asli Kajang dan aktivis di<br />
wilayah Kabupaten Bulukumba Sulawesi<br />
Selatan. Dilaporkan 2 orang tewas dalam<br />
peristiwa tersebut sebanyak 28 orang ditangkap,<br />
serta 24 orang aktivis dan petani dimasukan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
47
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat<br />
kepolisian.<br />
26 Agustus 2003, ribuan aparat gabungan<br />
dari Polres Jakarta Barat, Banpol, Trantib, serta<br />
Linmas melakukan penggusuran terhadap<br />
rakyat miskin. di Jembatan Besi, Pelbak,<br />
Tambora, Jakarta Barat. Penggusuran ini<br />
dilakukan karena kawasan tersebut dinyatakan<br />
kawasan pemukiman liar oleh Pemerintah Kota<br />
Jakarta Barat. Dilaporkan sekitar 10.000 jiwa<br />
kehilangan tempat tinggal dalam peristiwa<br />
tersebut. Sebagai catatan bahwa aksi<br />
penggusuran di Jakarta oleh Pemerintah<br />
Propinsi DKI Jakarta sudah berlangsung sejak<br />
2001.<br />
16 Oktober 2003, puluhan polisi atas<br />
perintah Pengadilan Negeri Makassar, menyusul<br />
putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi<br />
warga Karuwisi menggusur rumah-rumah<br />
rakyat miskin di Kelurahan Karuwisi,<br />
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.<br />
Sebanyak 20 rumah dihancurkan sehingga<br />
mengakibatkan kurang lebih 100 jiwa<br />
kehilangan tempat tinggal. Pihak Harmunis<br />
sendiri sebagai pihak yang dimenangkan oleh<br />
MA dan sejak lama mendapat dukungan dari PT<br />
Haji Kalla dilaporkan sudah mencoba mengusir<br />
penduduk dari wilayah tersebut sejak 1996.<br />
November 2001, di Banten, sebanyak 49 orang<br />
petani Desa Cibaliung Kecamatan<br />
Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, ditangkap<br />
dengan tuduhan melakukan penebangan dan<br />
pencurian kayu miliki milik Perhutani.<br />
Penangkapan ini seiring dengan terjadinya<br />
penyerbuan polisi ke desa tersebut sehari<br />
sebelumnya.<br />
Tahun 2000, Di Kendari, Sulawesi Tenggara;<br />
SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 318<br />
Tahun 2000 yg isinya tentang Pembentukan Tim<br />
Penanggulangan Perambahan atau Gangguan<br />
kawasan TNRAW dan Kawasan Hutan<br />
sekitarnya, digunakan sebagai landasan<br />
tindakan pembongkaran dan penghancuran<br />
rumah-rumah masyarakat adat Tobu HukaEa-<br />
LaEa, serta upaya pengusiran (pemindahan<br />
paksa) mereka dari kampung mereka. 12 Akibat<br />
dari itu, ratusan penduduk kehilangan tempat<br />
tinggal.<br />
Juni 2000, kepolisian Barito Utara dan<br />
Brimob dengan dukungan dari pejabat<br />
Pemerintah daerah Tk II Barito Utara dan Pam<br />
swakarsa yang dibentuk oleh PT. IMK kembali<br />
memaksa penduduk Desa Tengkanong dan<br />
Permata Kecamatan Permata Intan, Kabupaten<br />
Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk<br />
meninggalkan pemukiman mereka.<br />
Penggusuran tersebut dilakukan dengan caracara<br />
brutal, di mana warga dipaksa keluar<br />
dengan todongan senjata pasukan Brimob.<br />
Dalam peristiwa tersebut, 15 orang yang<br />
menolak mengosongkan areal tersebut<br />
kemudian ditangkap dan ditahan di Mapolres<br />
Barito Utara.<br />
Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut,<br />
sejumlah hak-hak penduduk lokal seperti hak<br />
atas perumahan dan pekerjaan menjadi hilang.<br />
Diperkirakan ratusan ribu orang kehilangan<br />
tempat tinggal dan pekerjaan akibat praktikpraktik<br />
penggusuran. Selain itu, hilangnya hak<br />
atas pekerjaan dan perumahan ini berimbas<br />
pada hilangnya hak atas kesehatan dan<br />
pendidikan bagi anak-anak mereka. Di samping<br />
pelanggaran atas hak-hak tersebut, ratusan orang<br />
kehilangan hak sipil dan politiknya karena<br />
praktik penggusuran selalu diwarnai dengan<br />
tindak kekerasan.<br />
PENGINGKARAN PEMERINTAH<br />
DAERAH ATAS KEJAHATAN HAK ASASI<br />
MANUSIA<br />
Kecenderungan saat ini, pemerintah propinsi<br />
dan pemerintah kabupaten/kota kerap<br />
mengingkari keterlibatan mereka dalam<br />
pelanggaran hak asasi manusia. Dengan<br />
menyatakan bahwa kekerasan dan kejahatan hak<br />
asasi manusia tidak benar – mereka kerap<br />
48 Bagian IV
mengatakan proses penggusuran sudah sesuai<br />
dengan prosedur dan regulasi daerah – mereka<br />
balik mengecam pihak-pihak yang menuduh<br />
mereka terlibat dalam kejahatan tersebut.<br />
Bahkan tak jarang mereka mengabaikan<br />
kecaman dari pemerintah pusat atas perilaku<br />
brutal mereka dalam praktik-praktik<br />
penggusuran dan penanganan konflik agraria<br />
atau sumber kekayaan alam lainnya. Beberapa<br />
contoh kasus-kasus pengingkaran mereka ini<br />
adalah kasus pencemaran lingkungan PT<br />
Newmount Mining di Sulawesi Utara yang<br />
berakibat terlanggarnya hak atas kesehatan<br />
penduduk lokal, di mana Pemerintah Propinsi<br />
Sulawesi Utara menolak pengumuman<br />
pemerintah pusat tentang adanya pencemaran<br />
di Teluk Buyat. 13 Penolakan ini mereka lakukan<br />
dengan membuat penelitian tandingan yang<br />
melibatkan Universitas Sam Ratulangi dan Universitas<br />
Manado berikut para ahlinya. Di<br />
Sulawesi Selatan, Pemerintah daerah menolak<br />
terlibat dalam aksi kekerasan polisi terhadap<br />
penduduk lokal dalam aksi demonstrasi<br />
menuntut pengembalian tanah-tanah adat yang<br />
dibeli dengan tidak wajar oleh PT Lonsum,<br />
dengan alasan penduduklah yang melakukan<br />
aksi pengrusakan terhadap fasilitas PT Lonsum,<br />
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sehingga<br />
tepat jika dikerahkan pasukan Brimob ke<br />
wilayah tersebut. 14 Di Jakarta, pemerintah<br />
propinsi menolak jika praktik-praktik<br />
penggusuran yang mereka lakukan telah<br />
melanggar hak asasi manusia. Dengan<br />
menyebutkan bahwa pelaksanaan penggusuran<br />
adalah bagian dari upaya mengurangi jumlah<br />
penduduk di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta,<br />
Sutiyoso, menolak jika penertiban kawasan liar<br />
telah menyalahi prosedur hukum. 15<br />
PENGUSIRAN PAKSA: KEJAHATAN<br />
BERAT HAK ASASI MANUSIA OLEH<br />
PEMERINTAH DAERAH<br />
Hukum hak asasi manusia internasional<br />
dengan tegas memasukkan tindakan pengusiran<br />
paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia<br />
berat. 16 Masuknya pengusiran paksa ke dalam<br />
kategori kejahatan berat karena tindakan itu<br />
selalu identik dengan kesengajaan dengan alasan<br />
penataan kota, atau pembangunan sejumlah<br />
fasilitas bisnis besar. 17 Di samping itu akibat<br />
yang ditimbulkan tindakan ini menyebabkan<br />
akibat-akibat yang serius bagi para korbannya.<br />
Akibat-akibat itu, antara lain: hilangnya property<br />
pribadi, kelompok atau suku, menyebabkan<br />
penderitaan secara fisik karena kerap<br />
menggunakan kekerasan. Oleh karena itu<br />
dalam instrumen hak ekonomi sosial budaya<br />
dan diperkuat oleh berbagai ketentuan hukum<br />
internasional lainnya, tindakan ini dinyatakan<br />
sebagai kejahatan berat hak asasi manusia. 18<br />
Sementara itu kategori tindakan yang bisa<br />
dimasukkan dalam kejahatan ini adalah<br />
penempatan kembali, pengusiran dari suatu<br />
tempat, pemindahan ke lokasi baru,<br />
pemusnahan etnis, penertiban pemukiman<br />
penduduk atau lokasi perdangan yang dianggap<br />
liar, transmigrasi paksa dan penataan ulang<br />
wilayah sewenang-wenang. 19 Dalam beberapa<br />
kasus, pengusiran paksa dibenarkan oleh PBB,<br />
namun untuk melakukan itu ada sejumlah<br />
prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara atau<br />
non-negara ketika melakukan pengusiran<br />
paksa. 20<br />
Melihat peristiwa pengusiran penduduk oleh<br />
pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam<br />
menjalankan pembangunan di daerah<br />
menunjukkan bahwa Pemerintah daerah<br />
terlibat dalam kejahatan berat hak asasi<br />
manusia. Sejumlah peristiwa penggusuran atau<br />
pengusiran penduduk lokal dalam kerangka<br />
pembangunan pusat-pusat bisnis atau<br />
pengembalian lahan-lahan kepada perusahaan<br />
yang diberikan kuasa penguasaan dan<br />
pengelolaan jelas-jelas jauh dari ketentuanketentuan<br />
yang tercantum dalam hukum hak<br />
asasi manusia internasional. Hampir dalam<br />
praktik pengusiran di seluruh daerah, para<br />
pelakunya tidak memenuhi standar-standar<br />
hukum hak asasi manusia internasional tentang<br />
prosedur pengusiran paksa.<br />
1. Pengumuman yang Mendadak<br />
Sekalipun para pejabat di Pemerintah daerah<br />
mengaku telah mengumumkan rencana<br />
penggusuran di suatu tempat, namun hampir<br />
kebanyakan korban penggusuran selalu<br />
mengatakan sebaliknya, yakni Pemerintah<br />
daerah jarang sekali memberikan pengumuman<br />
tentang rencana pengusiran kepada publik jauhjauh<br />
hari sebelumnya. Kebanyakan penguman<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
49
itu diumumkan seminggu sebelum eksekusi.<br />
Bahkan sebagian korban mengaku bahwa surat<br />
edaran yang disebutkan pemerintah sebagai<br />
pengumuman, tidak bisa dianggap<br />
pengumuman karena lebih bernada ancaman. 21<br />
Di Jakarta, para korban penggusuran mengaku<br />
hanya diberikan waktu sekitar dua minggu oleh<br />
pemerintah untuk mengosongkan tempat<br />
tinggalnya. 22 Hal senada juga disebutkan oleh<br />
warga Penambungan, Makasar, di mana mereka<br />
mengaku tidak menerima pengumuman tertulis<br />
dari pemerintah daerah tentang rencana<br />
penggusuran kawasan pemukiman mereka. 23 Di<br />
Salatiga, para pedagang kakilima di sepanjang<br />
Jalan Sudirman-Salatiga mengaku tidak<br />
diberitahu bahwa wilayahnya akan digusur.<br />
Ketika akan berjualan di daerah tersebut, para<br />
pedagang tidak menjumpai gerobak-gerobak<br />
dagangan milik mereka. Setelah diusut, ternyata<br />
Satpol PP Pemerintah Kota Salatiga yang telah<br />
membawa gerobak dagangan milik mereka.<br />
2. Ketidakmauan Pemerintah Daerah<br />
Untuk Menggelar Debat Publik<br />
Demikian pula dengan kewajiban membuka<br />
ruang untuk memperdebatkan rencana tersebut<br />
ke publik, nyaris tidak terjadi. Pemerintah<br />
daerah selalu bersikukuh bahwa urusan<br />
penggusuran adalah urusan pemerintah dan<br />
bukan penduduk. Sehingga pendapat miring<br />
banyak pihak tentang penggusuran kerap<br />
diabaikan. Dan tak jarang pula Pemerintah<br />
daerah balik menuding pihak-pihak yang anti<br />
penggusuran sebagai provokator atau<br />
menunggangi. Di Jakarta, dalam menyikapi<br />
pendapat kritis masyarakat atas tindakan<br />
penggusuran yang dilakukannya, pemerintah<br />
DKI cenderung mengabaikannya. 24 Bahkan<br />
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan arogan<br />
menafikkan ketentuan ini dalam kasus-kasus<br />
penggusuran atas sejumlah kawasan ekonomi<br />
dan pemukiman yang dinyatakan liar. 25<br />
3. Ketidakadaan Proses Negosiasi<br />
Tidak berbeda dengan ketentuan<br />
sebelumnya, ketentuan untuk melakukan<br />
negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir<br />
hingga mencapai kesepakatan, praktis juga<br />
diabaikan. Proses negosiasi yang disebut oleh<br />
pemerintah telah dijalankan sebenarnya bukan<br />
negosiasi melainkan memaksa penduduk untuk<br />
menerima harga tanah atau dana kerohiman<br />
semau mereka. Di Jakarta, para korban gusuran<br />
mengaku bahwa tidak ada proses negosiasi, yang<br />
ada pemberitahuan warga akan diberikan dana<br />
kompensasi yang sudah ditentukan jika mau<br />
pindah. Di Bekasi, para korban mengaku bahwa<br />
mereka tidak diajak negosiasi ketika petugas dari<br />
pemerintah kota Bekasi membongkar tempat<br />
berdagang mereka. Dengan menuturkan bahwa<br />
mereka sudah membayar sewa sebesar 500 ribu<br />
rupiah per bulan mereka heran dengan tindakan<br />
pembongkaran sepihak dari Pemerintah Kota<br />
Bekasi. 26 Di Yogyakarta, meski para pedagang<br />
kakilima di kawasan Abadi, Samirono, menolak<br />
untuk digusur Pemerintah Propinsi DIY tetap<br />
melakukan penggusuran atas kawasan<br />
tersebut. 27<br />
4. Pendeknya Pemberian Tenggat Waktu<br />
Selanjutnya ketentuan untuk memberikan<br />
tenggat waktu minimal enam bulan sebelum<br />
eksekusi, secara umum tidak pernah dijalankan.<br />
Praktik-praktik pengusiran selalu terjadi dua<br />
minggu setelah pernyataan resmi dari pejabat<br />
setempat. Bahkan di beberapa tempat proses<br />
pengusiran ini terjadi ketika si pemilik sedang<br />
pulang ke desa atau tidak ada di tempat. 28 Di<br />
Jakarta Utara, warga Kampung Nelayan di<br />
bantaran Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara<br />
mengaku bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara<br />
tidak memberikan tenggat waktu yang memadai<br />
bagi mereka sebelum eksekusi penggusuran di<br />
wilayah mereka. Melalui Surat Edaran Camat<br />
Penjaringan Nomor 259/1003 yang terbit 19<br />
September 2000, dan dilanjutkan dengan surat<br />
pemberitahuan Walikota Jakarta Utara Nomor<br />
1622/077.7 tentang Pembongkaran, Pemerintah<br />
Kota Jakarta Utara memberi tenggat waktu 3 x<br />
24 Jam bagi penduduk untuk membongkar<br />
rumah-rumah mereka yang dinyatakan sebagai<br />
rumah-rumah liar. 29<br />
5. Kompensasi yang Tidak Memadai<br />
Pemberian kompensasi pun jauh dari nilai<br />
ekonomi yang berlaku saat kejadian dan tidak<br />
sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh<br />
para korban sebelumnya. 30 Di Tanjung Priok,<br />
sejumlah warga Lorong W Barat mengaku<br />
50 Bagian IV
ahwa Pemerintah daerah tidak memberikan<br />
dana kompensasi yang memadai. 31 Dengan<br />
hanya menyanggupi akan membayar uang<br />
kerohiman 500 ribu rupiah, Pemerintah Kota<br />
Jakarta Utara meminta warga untuk pindah.<br />
Bahkan untuk kasus-kasus penertiban para<br />
pedagang kakilima, hampir tidak ada<br />
kompensasi untuk mereka. Di Pulogadung,<br />
Jakarta Timur, para penduduk di wilayah<br />
tersebut mengaku hanya menerima uang 300<br />
ribu rupiah sebagai bentuk kompensasi dari<br />
Pemerintah Kota Jakarta Timur. Tak heran jika<br />
kemudian para korban ini banyak yang tidak<br />
mampu menyewa tempat tinggal baru. Bahkan<br />
dalam kasus-kasus penertiban pedagang<br />
kakilima, sebagian besar Pemerintah daerah<br />
jarang memberikan kompensasi, baik dalam<br />
bentuk uang ataupun lokasi baru.<br />
KESIMPULAN<br />
Penerapan desentralisasi daerah dalam<br />
kerangka otonomi daerah di Indonesia pada<br />
akhirnya justru melahirkan tindak kejahatan<br />
pelanggaran hak asasi manusia di tingkat<br />
daerah. Kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah<br />
tidaklah berbeda dengan apa yang pernah<br />
dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa<br />
lalu, yakni kental dengan penggunaan praktikpraktik<br />
kekerasan dalam proses pembangunan.<br />
Alasan memacu laju investasi yakni dengan<br />
mengundang investor ke daerah dan<br />
menggenjot pembangunan infrastruktur<br />
pemerintahan yang otonom kemudian menjadi<br />
tedeng aling-aling bagi pemerintah daerah untuk<br />
melakukan praktik-praktik pelanggaran hak<br />
asasi manusia di daerahnya sendiri. Otonomi<br />
daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan<br />
dan penegakan pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika<br />
membangun institusi dan struktur<br />
pemerintahan otonom. Akibat dari ini,<br />
penduduk lokal kembali harus menjadi bulanbulanan<br />
tindak kekerasan dan pelanggaran hak<br />
asasi manusia aparatur pemerintah propinsi dan<br />
kabupaten/kota.<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Lih., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Hasil Temuan<br />
Semeru, 3 April 2001.<br />
2<br />
Beberapa propinsi yang membelah diri antara lain:<br />
Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Utara, Maluku.<br />
Sementara pemekaran Kabupaten dan Kota hampir<br />
terjadi di seluruh propinsi di Indonesia.<br />
3<br />
Op.cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April<br />
2001.<br />
4<br />
Farid, Hilmar, Laporan Militerisasi di Indonesia, Juli<br />
<strong>2004</strong>, tidak diterbitkan untuk umum.<br />
5<br />
Hampir setiap propinsi pada awal-awal penerapan<br />
otonomi melakukan serangkaian studi banding ke luar<br />
negeri. Beberapa di antara mereka ini mendapatkan<br />
kritik yang luar biasa dari rakyatnya sendiri. Daerahdaerah<br />
itu antara lain, Jakarta, Kalbar, Kaltim, Riau, dan<br />
Padang.<br />
6<br />
Op.Cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April<br />
2001: Hampir 200 Perda diproduksi oleh Pemprop,<br />
lebih banyak mengatur tentang Pajak, Retribusi dan<br />
Pungutan Lain. Semua ini ditujukan agar dapat<br />
menangkap keuntungan dari seluruh potensi kekayaan<br />
lokal.<br />
7<br />
lih., “ Satpol PP Nganjuk Pegang Pistol,” Surya<br />
Online, 20 April <strong>2004</strong>; “Satpol PP Kota Palembang<br />
Dapat 15 Pistol,” Sinar Pagi, 9 Januari <strong>2004</strong>; “Diprotes<br />
Satpol PP Berpistol,” Jawapost.com, 15 Mei <strong>2004</strong>;<br />
8<br />
Dokumentasi ELSAM periode 1999-<strong>2004</strong><br />
menunjukkan hampir seluruh pemerintah daerah, baik<br />
propinsi maupun daerah, menggunakan Satpol PP<br />
dalam eksekusi-eksekusi penertiban yang sarat dengan<br />
tindakan kejam dan tidak manusiawi.<br />
9<br />
Di Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung membakar<br />
karya seni instalasi seniman Tisna Sanjaya tanpa<br />
alasan yang jelas. Karya-karya Tisna yang dibakar<br />
adalah karyat-karya yang bertema kritik sosial. Lih.<br />
“Tisna Jaya Melapor ke Polisi, Kasus Pembakaran<br />
Diselesaikan Secara Hukum,”<br />
Pikiran Rakyat Online, 11 Februari <strong>2004</strong>.<br />
10<br />
“Pedagang Kakilima Bentrok Dengan Petugas,<br />
Diduga Dimotori oleh Preman,” KCM, 19 April 2001.<br />
11<br />
“ Mahasiswa Tuntut Bupati Mundur,” Suara<br />
Merdeka, 29 Desember <strong>2004</strong><br />
12<br />
SK Gubernur tersebut menjelaskan institusi-intisusi<br />
daerah yang terlibat dalam operasi penertiban<br />
tersebut. Insitusi-institusi tersebut antara lain:<br />
Pembantu Gubernur Untuk Wilayah Kepuluan (selaku<br />
Ketua Tim), Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Bupati<br />
Buton, Bupati Kendari, Kakanwil Dephutbun Prop.<br />
Sultra, Ka. Dishut Prop. Sultra, Polisi Pamong Praja<br />
Pemerintah daerah Tk I Sultra, Brimob Polda Sultra,<br />
Polisi Hutan Janggawana TNRAW, dan Polres.<br />
13<br />
Presentasi Suara Nurani dalam pertemuan<br />
konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember <strong>2004</strong>.<br />
14<br />
Wawancara dengan aktivis Walhi, di Jakarta 2003<br />
15<br />
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memastikan, pada<br />
<strong>2004</strong> penggusuran tetap terus dilakukan. “Penduduk<br />
Jakarta sudah over capacity. Jika tidak dilakukan<br />
penertiban, akan lebih parah,” kata Sutiyoso, di Balai<br />
Kota Jakarta. Lih., “<strong>2004</strong>, Penggusuran di Jakarta Tetap<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
51
Berjalan,” Tempo Interaktif, 19 Desember <strong>2004</strong>.<br />
16<br />
Forced Eviction Violation of <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong>, Global<br />
Survey on Forced Eviction No.8, COHRE June 2002.,<br />
Hlm.8<br />
17<br />
Ibid., Dari studi kasus-kasus pengusiran paksa di<br />
dunia, hampir seluruh praktik-praktik pengusiran<br />
paksa selalu mendapat legitmasi dari otoritas lokal<br />
dalam bentuk regulasi nasional, propinsi dan<br />
kabupaten.<br />
18<br />
Beberapa Instrumen dan Resolusi PBB yang<br />
menegaskan tentang kasus-kasus pengusiran paksa<br />
adalah kejahatan berat hak asasi manusia adalah sbb:<br />
Pasal 11 ayat 1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi<br />
Sosial Budaya; Resolusi UN Commission on <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> No 73/1993 mengenai penegasan bahwa di<br />
manapun pengusiran paksa terjadi dinyatakan sebagai<br />
Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia. Sub-UN Commission<br />
on The Promotion and Protection of <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> mengenai No 9/1998 tentang Forced Eviction,<br />
dan Resolusi No 26/1998 Tentang Restitusi perumahan<br />
dan property dalam konteks pemulangan IDPs dan<br />
Pengungsi.<br />
19<br />
Leckie, Scott, When Push Come to Shove, Forced<br />
Eviction and <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong>., Habitat International<br />
Coalition, 1995, hlm. 11<br />
20<br />
Ibid. Leckie, Scott, hlm. 92-93: ketentuan yang harus<br />
dipenuhi oleh negara atau non-negara ketika<br />
melakukan pengusiran paksa adalah: rencana<br />
pengusiran harus dibuat oleh publik dan harus<br />
diperdebatkan kepada publik juga; menggunakan<br />
Negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir, Jika<br />
kesepakatan gagal dicapai pihak negara atau nonnegara<br />
harus mendorong proses negosiasi hingga<br />
mencapai kesepakatan, memberikan tenggat waktu<br />
minimal enam bulan sebelum eksekusi, memberikan<br />
kompensasi yang relevan dan memadai dan minimal<br />
sebanding dengan harta kekayaan yang ditinggalkan.<br />
21<br />
Wawancara ELSAM dengan korban gusuran di<br />
Kantor Komnas HAM Jakarta, Juli 2003<br />
22<br />
Ibid.<br />
pedagang kakilima di pelabuhan Makassar awal<br />
Desember <strong>2004</strong> terjadi ketika para pedagang sedang<br />
keluar mencari makan siang.<br />
29<br />
“Warga Kampung Nelayan Ketakutan, “ Kompas, 15<br />
Oktober 2003.<br />
30<br />
Kompensasi selama ini tidak ada dalam proses ganti<br />
rugi. Di Jakarta, para penduduk yang tinggal di<br />
kawasan yang disebut sebagai pemukiman liar oleh<br />
pemerintah daerah hanya mendapat uang kerohiman<br />
yang jumlahnya tidak akan bisa untuk mengontrak<br />
rumah baru apalagi sampai membelinya.<br />
31<br />
“Warga Lorong W Barat Tanjung Priok Tolak<br />
Penggusuran,” Tempo Interaktif, 25 November <strong>2004</strong>.<br />
23<br />
Lih., Kronologis Pembongkaran Rumah dan Aksi<br />
Warga Pannambungan-Lette, di http://<br />
uplink.urbanpoor.or.id.<br />
24<br />
Sepanjang 2001-<strong>2004</strong>, banyak sekali pengamat<br />
ekonomi, sosial dan politik yang mengkritik langkah<br />
penggusuran, namun demikian kritikan ini tidak<br />
ditindaklanjuti oleh pemprop DKI dengan menggelar<br />
dialog publik untuk mendapatkan persetujuan publik<br />
atas langkah-langkahnya.<br />
25<br />
Lih., “Pemerintah daerah Jakarta Pusat Akan Gusur<br />
Kakilima,” Tempo Interaktif, 22 November <strong>2004</strong><br />
26<br />
“Penertiban Pedagang Kakilima di Bekasi Diwarnai<br />
Ketegangan,” Kompas, 4 Mei 2002<br />
27<br />
“PKL Samirono Kembali Gelar Aksi,” Suara Merdeka,<br />
19 April <strong>2004</strong><br />
28<br />
Di Jakarta, sejumlah aksi-aksi pengusiran pada akhir<br />
2001 dan 2001 kerap terjadi ketika pemilik sedang<br />
pulang kampung untuk merayakan lebaran (hari raya<br />
besar Islam). Sementar di Makassar, pengusiran<br />
52 Bagian IV
BAGIAN KELIMA<br />
Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami:<br />
Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment<br />
terhadap Perempuan Periode 1999-<strong>2004</strong><br />
PENGANTAR<br />
Indonesia telah meratifikasi Konvensi<br />
penghapusan segela bentuk diskriminasi<br />
terhadap perempuan. Namun demikian<br />
ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat<br />
perempuan dapat menikmati atas hak-haknya<br />
yang dijamin dalam instrumen tersebut.<br />
Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan<br />
masih tetap berlangsung dan kecenderungannya<br />
sudah menjadi endemik. Kegagalan untuk<br />
menghancurkan sistem militeristik yang<br />
menjunjung tinggi kelaki-lakian sebagai sesuatu<br />
yang unggul dalam tubuh pemerintahan adalah<br />
faktor utama penyebab tindak kekerasan<br />
terhadap perempuan di Indonesia. Aparatur<br />
negara, institusi adat, dan bersama-sama<br />
keluarga melanggengkan tindak kekerasan<br />
terhadap manusia yang berjenis kelamin<br />
perempuan. Di rumah, pabrik, sekolah, rumah<br />
sakit, pasar, kantor pemerintah, dan kantor<br />
polisi sekalipun, bukanlah tempat yang aman<br />
bagi perempuan. Di mana pun ia berdiri<br />
ancaman tindak kekerasan terhadap dirinya<br />
berpeluang sangat besar, karena mereka adalah<br />
seorang perempuan.<br />
Hampir ribuan perempuan di Indonesia<br />
dilaporkan telah menjadi tindak kejahatan<br />
penyiksaan dan ill treatment. Penyiksaan ini<br />
dilakukan sebagai salah satu cara untuk<br />
mengontrol kehidupan perempuan ataupun<br />
bentuk hukuman atas kesalahan mereka atas<br />
nilai-nilai yang berkembang di keluarga atau<br />
komunitas. Di wilayah konflik, perempuan<br />
disiksa oleh militer atau kelompok pemberontak<br />
karena mereka tidak mau mendukung taktiktaktik<br />
perang dari salah satu pihak yang bertikai.<br />
Di daerah perkotaan, para pekerja rumah tangga<br />
perempuan disiksa karena ia bodoh dan tidak<br />
cakap untuk memuaskan majikannya. Sejumlah<br />
perempuan juga disiksa karena mencoba<br />
melarikan diri dari rumah-rumah<br />
penampungan calon tenaga kerja luar negeri<br />
yang sangat buruk fasilitasnya. Di pusat-pusat<br />
industri perempuan disiksa atau mendapatkan<br />
perlakuan tidak manusiawi karena mencoba<br />
menuntut hak-hak normatif mereka. Di rumahrumah,<br />
para perempuan juga disiksa karena<br />
mereka dianggap sebagai istri yang tidak patuh<br />
dan mau melayani suaminya.<br />
Pemaparan di atas adalah terkait erat dengan<br />
langkah-langkah negara dalam lima tahun<br />
terakhir ini dalam hal penanganan krisis<br />
ekonomi, menjaga NKRI, desentralisasi serta<br />
perang melawan pengangguran dan kemiskinan.<br />
Penanganan krisis ekonomi yang kemudian<br />
dilanjutkan dengan membuka peluang<br />
semudah-mudahnya bagi para investor<br />
membenarkan pemerintah untuk<br />
mempekerjakan perempuan dengan upah yang<br />
rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan<br />
pendapatan negara, baik pusat dan daerah,<br />
membenarkan negara untuk terus mengekspor<br />
perempuan ke negara-negara penerima tenaga<br />
kerja kasar dan murah seperti Arab, Malaysia,<br />
Singapura, dan Hongkong. Negara juga turut<br />
berkontribusi terhadap tindak penyiksaan<br />
terhadap perempuan di keluarga karena dengan<br />
sengaja membiarkan perilaku patriarki yang<br />
terus dianut oleh orang tua, tokoh agama dan<br />
masyarakat serta para guru di sekolah. Langkah<br />
konsolidasi territori Indonesia yang kemudian<br />
terganggu oleh pemberontakan, membenarkan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
53
negara terus melakukan Proxy Violence 1<br />
terhadap perempuan di wilayah tersebut untuk<br />
dapat membongkar jaringan pemberontak.<br />
Kelompok bersenjata dengan dalih<br />
memperjuangkan kemerdekaan, memaksa<br />
perempuan untuk menjadi pekerja seks atau<br />
memaksa mereka untuk menikahi para serdadu<br />
di wilayah konflik, agar memperoleh informasiinformasi<br />
penting berkaitan dengan kekuatan<br />
tentara pemerintah.<br />
Bagian ini akan memaparkan tentang<br />
praktik-praktik penyiksaan terhadap<br />
perempuan yang telah menjadi endemik di Indonesia.<br />
Bagian ini juga bermaksud<br />
memaparkan tentang kaitan-kaitan kebijakan<br />
negara dalam lima tahun terakhir dengan<br />
peristiwa penyiksaan dan ill treatment.<br />
UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK<br />
PEREMPUAN<br />
Tidak banyak upaya-upaya perbaikan hakhak<br />
perempuan di Indonesia dalam lima tahun<br />
terakhir, baik di legal reform, institusional reform<br />
maupun upaya-upaya penghukuman atas<br />
para pelaku kekerasan terhadap perempuan.<br />
Sebaliknya praktikpraktik<br />
kekerasan<br />
terhadap perempuan<br />
terus meningkat<br />
sejalan dengan<br />
sejumlah kebijakan<br />
yang diambil oleh<br />
negara terkait dengan<br />
agenda perbaikan<br />
ekonomi nasional,<br />
langkah-langkah<br />
penanganan wilayah<br />
konflik, maupun<br />
dalam penerapan<br />
k e b i j a k a n<br />
desentralisasi atau<br />
otonomi daerah.<br />
Langkah-langkah<br />
tersebut secara<br />
langsung atau tidak<br />
terkait erat dengan<br />
praktik-praktik<br />
kekerasan terhadap<br />
perempuan yang<br />
akan dijelaskan lebih<br />
detail dalam bagian lain dalam laporan ini.<br />
Secara umum, agenda perbaikan dan perlindungan<br />
hak-hak perempuan di level legislasi<br />
masih jauh dari yang diharapkan oleh banyak<br />
pihak. Problem-problem kekerasan terhadap<br />
perempuan yang belakangan muncul dalam<br />
skala yang massif dan meluas di tanah air tidak<br />
membuat produksi legislasi di tingkat nasional<br />
meningkat. Hal yang sama juga terjadi di daerah,<br />
ketika penerapan otonomi daerah tidak<br />
membuat parlemen lokal bersama-sama<br />
pemerintah propinsi dan kabupaten/kota<br />
terpacu untuk memproduksi regulasi khusus<br />
tentang perlindungan dan pencegahan praktikpraktik<br />
kekerasan terhadap perempuan, baik itu<br />
yang dilakukan oleh aparatur negara, kelompok<br />
pemberontak bersenjata, kelompok-kelompok<br />
bersenjata berbasis agama atau etnis maupun<br />
oleh perusahaan dan kelompok-kelompok<br />
pengaman sewaan. Akibatnya, di level nasional<br />
dan daerah hingga saat ini belum memiliki<br />
mekanisme perlindungan dan pencegahan<br />
perempuan dari praktik-praktik kekerasan.<br />
Setidaknya baru dua produk legislasi tentang<br />
perlindungan dan pencegahan di tingkat<br />
54 Bagian V
nasional yang berhasil diproduksi dalam lima<br />
tahun terakhir. Dua produk legislasi tersebut<br />
adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun <strong>2004</strong><br />
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah<br />
Tangga dan Undang-undang Nomor 39 Tahun<br />
<strong>2004</strong> tentang Perlindungan Tenaga Kerja<br />
Perempuan di Luar Negeri. Sehingga hingga saat<br />
ini hanya ada tiga produk legislasi nasional<br />
tentang perlindungan dan pencegahan<br />
kekerasan terhadap perempuan. Di samping<br />
mandul, parlemen dan pemerintah juga tidak<br />
memiliki inisiatif untuk mencabut sejumlah<br />
regulasi peninggalan Soeharto yang jelas-jelas<br />
membenarkan praktik diskriminasi terhadap<br />
perempuan dan selama ini digunakan sebagai<br />
payung<br />
pembenar oleh negara maupun non-negara<br />
untuk melakukan praktik-praktik kekerasan<br />
terhadap perempuan. 2 Berbagai produk legislasi<br />
di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/<br />
kota, belakangan juga mejadi penyebab<br />
terjadinya praktik-praktik kekerasan terhadap<br />
perempuan baru di berbagai tempat. Produkproduk<br />
ini membenarkan negara ataupun aktor<br />
non-negara tetap membenarkan praktikpraktik<br />
kekerasan dan pembatasan- pembatasan<br />
terhadap aktivitas perempuan di rumah,<br />
organisasi tingkat kampung hingga nasional,<br />
pasar maupun parlemen. Di samping itu<br />
sejumlah pemerintah propinsi dan kabupaten/<br />
kota juga memproduksi sejumlah regulasi<br />
daerah yang membenarkan praktik-praktik<br />
eksploitasi perempuan dalam bentuk legalisasi<br />
pengiriman tenaga kerja perempuan sehingga<br />
memperluas pertumbuhan perusahaanperusahaan<br />
penyalur tenaga kerja bermasalah. 3<br />
Alasan ingin mengentaskan kemiskinan yang<br />
terjadi di daerah menjadi dasar pembenaran<br />
bagi sejumlah pemerintah daerah untuk terus<br />
mengirim tenaga kerja perempuan ke luar<br />
negeri, sementara di lain pihak pemerintah<br />
daerah sendiri tidak memberikan perlindungan<br />
yang memadai atas proses pengiriman tersebut.<br />
Sementara di level institusi, praktis seluruh<br />
agenda reformasi di institusi pemerintahan<br />
tidak pernah memasukkan agenda perlindungan<br />
dan pencegahan hak-hak perempuan sebagai<br />
program prioritas. Reformasi institusi di level<br />
pemerintah dan parlemen hingga saat ini masih<br />
berkutat pada persoalan-persoalan penataan<br />
hirarki atau koordinasi antar departemen atau<br />
instansi, baik itu dalam program reformasi di<br />
tingkat insititusi nasional maupun dalam<br />
implementasi kebijakan otonomi daerah.<br />
Terlihat di tingkat nasional adalah bahwa tidak<br />
ada satupun institusi khusus yang memiliki<br />
mandat untuk melakukan penyelidikan atau<br />
monitoring terhadap kondisi perempuan di<br />
wilayah departemen, perusahaan, pusat-pusat<br />
pertokoan, pusat-pusat penampungan calon<br />
tenaga kerja maupun tempat-tempat lain yang<br />
diindikasikan menjadi tempat yang sarat dengan<br />
praktik kekerasan. Dalam hal ini, Komisi<br />
Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan atau<br />
lebih dikenal Komnas Perempuan pun hingga<br />
saat ini belum diberikan mandat yang cukup<br />
dan memadai untuk menjalankan tugasnya<br />
memantau atau menyelidiki tindak kekerasan<br />
terhadap perempuan di Indonesia. 4<br />
Sementara di level parlemen, situasinya pun<br />
tidak berbeda dengan di tubuh institusi<br />
pemerintahan. Parlemen hingga saat ini belum<br />
memiliki komisi yang secara khusus membahas<br />
persoalan-persoalan perempuan maupun<br />
kekerasan-kekerasan terhadap perempuan lain.<br />
Parlemen, baik itu di tingkat nasional maupun<br />
daerah, selalu menempatkan persoalanpersoalan<br />
perempuan di komisi-komisi yang<br />
sangat tidak berkompeten membahas<br />
persoalan-persoalan perempuan karena<br />
mayoritas dari mereka nyaris tidak mengenal<br />
atau bahkan memahami kompleksitas dari<br />
persoalan-persoalan perempuan. 5 Tak heran jika<br />
kemudian produksi regulasi di tingkat nasional<br />
dan daerah menjadi sangat terbatas, karena<br />
praktis parlemen hanya menunggu usulan dari<br />
pemerintah tanpa berfikir untuk mengambil<br />
inisiatif awal untuk memproduksi regulasi<br />
nasional tentang perlindungan hak-hak<br />
perempuan.<br />
AKIBAT BURUKNYA PELAKSANAAN<br />
PERBAIKAN HAK-HAK PEREMPUAN :<br />
KASUS-KASUS PENYIKSAAN DAN ILL<br />
TREATMENT TERHADAP PEREMPUAN<br />
DI INDONESIA<br />
Buruknya langkah-langkah perbaikan<br />
kondisi hak-hak perempuan oleh pemerintah<br />
dan parlemen, serta penerapan sejumlah<br />
kebijakan negara yang terkait dengan<br />
penyelesaian persoalan ketegangan politik/<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
55
konflik sosial, perbaikan roda<br />
ekonomi nasional, pelaksanaan<br />
desentraslisasi serta perang<br />
melawan terorisme, pada<br />
akhirnya menyebabkan<br />
kekerasan terhadap hak-hak<br />
perempuan di Indonesia.<br />
Kejahatan yang paling menonjol<br />
ditemukan dalam lima tahun<br />
terakhir ini adalah kejahatan<br />
penyiksaan, tindakan tidak<br />
manusiawi, merendahkan<br />
martabat dan hukuman kejam.<br />
Pemantauan ELSAM atas<br />
berbagai kejahatan dalam<br />
kategori ini menyebutkan bahwa<br />
hampir sebagian besar dialami<br />
oleh kelompok perempuan.<br />
Berbagai kasus ini ditemukan<br />
di wilayah konflik bersenjata, di<br />
tempat bekerja, bahkan di dalam<br />
rumah sekalipun. Bentuk dan<br />
pola kejahatannya pun beragam,<br />
yakni dari mulai berbentuk<br />
kekerasan fisik, perkosaan,<br />
serangan seksual hingga<br />
tekanan-tekanan psikologis yang<br />
berakibat timbulnya trauma<br />
yang panjang bagi para<br />
korbannya. Berbagai tujuan<br />
pelaku yang berhasil diidentifikasi adalah bagian<br />
dari cara laki-laki untuk melakukan kontrol<br />
terhadap perempuan yang terkait dengan taktik<br />
operasi pengungkapan jaringan klandestin,<br />
termasuk juga cara memperkecil dukungan<br />
terhadap kelompok pemberontak bersenjata<br />
yakni dengan menekan perempuan untuk tidak<br />
mendukung gerakan anti pemerintah; benteng<br />
pertahanan hidup dari serangan militer yang<br />
lebih besar; termasuk juga menjadikan<br />
perempuan sebagai sandera yang bisa ditukar<br />
dengan makanan atau uang atau obat-obatan;<br />
menunjukkan eksistensi majikan kepada<br />
perempuan; serta menunjukkan kekuasaan<br />
suami kepada istri. Para pelakunya pun<br />
teridentifikasi tidak hanya melibatkan institusi<br />
pemerintah melainkan juga melibatkan aktoraktor<br />
non-negara seperti kelompok<br />
pemberontak bersenjata, perusahaan, lembaga<br />
adat atau agama serta kepala atau anggota<br />
keluarga.<br />
Kesaksian Me dalam Kasus Penyiksaan yang Terkait<br />
dengan Peristiwa Wasior 2002<br />
“Saya ditangkap oleh sekelompok anggota Brimob di<br />
Serui pada pertengahan Juli 2001, bersama-sama dengan<br />
anak saya Sisera (9 tahun), A (7 tahun) dan R (6 tahun) dan<br />
suami saya. Kami sekeluarga dibawa ke Polres Serui dan<br />
dimasukkan ke ruang tahanan. Selama ditahan, saya<br />
hanya diberi makan satu kali sehari, dan minum dengan<br />
air WC, dipaksa untuk mandi setiap pkl.05.00 pagi tanpa<br />
pakaian pengganti. Selama dalam tahanan, saya juga<br />
sering diancam untuk ditembak, bahkan pernah ujung<br />
senjata diarahkan ke dalam ruang tahanan korban. Saya<br />
ditahan enam hari ditahan di Polres Serui, lalu dibawa ke<br />
Polres Manokwari. Dan ketika tiba di Polres Manokwari,<br />
saya dan anak-anak menerima informasi dari salah<br />
seorang anggota Polisi Manokwari kalau suami saya telah<br />
meninggal karena disiksa oleh Polisi/Brimob. Seminggu<br />
kemudian (setelah suami korban dimakamkan), saya<br />
kembali dibawa ke Polres Manokwari untuk kembali<br />
diperiksa. Saya disuruh mengaku terlibat dalam kasus<br />
Wondiboy. Selama diperiksa saya dibentak dan dikatakatai<br />
dengan kata-kata kotor. Selesai diperiksa saja disuruh<br />
membuka pakaian semua hingga tinggal pakai celana dan<br />
kemudian disuruh masuk ke sel. (Wawancara korban<br />
kepada pekerja kemanusiaan di Papua, pertengahan <strong>2004</strong>.<br />
Sejumlah laporan diterjemahkan kembali dalam bahasa<br />
indonesia, sehingga struktur kalimatnya tidak sama persis<br />
dengan kesaksian asli yang menggunakan bahasa daerah.)<br />
1. Operasi Anti Gerilya dan Tindak<br />
Penyiksaan atau Perlakuan Kejam<br />
Dalam penggelaran operasi anti gerilya di<br />
Papua dan Aceh diduga keras telah terjadi<br />
praktik-praktik penyiksaan dan ill treatment<br />
yang ditujukan kepada perempuan. Dugaan<br />
keras ini terkait dengan taktik perang anti gerilya<br />
yang juga menjadikan para istri dari anggota<br />
pemberontak, terutama para pemimpinnya,<br />
sebagai target operasi. Dalam Operasi penyisiran<br />
para pelaku penyerangan markas-markas<br />
militer/polisi atau pencarian tokoh-tokoh<br />
politik dan bersenjata, para istri yang berada di<br />
rumah atau di tempat keluarga kerap turut<br />
dibawa ke pos atau kantor militer terdekat untuk<br />
dimintai keterangan seputar keberadaan<br />
suaminya. Dalam proses meminta keterangan<br />
(lebih tepat disebut intrograsi) para perempuan<br />
kerap mendapat tindak penyiksaan dan<br />
perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan<br />
martabat dari para introgrator. 6 Kelompok<br />
56 Bagian V
pemberontak juga kerap menjadikan<br />
perempuan sebagai sasaran tindak penyiksaan<br />
dan perlakuan kejam tidak manusiawi.<br />
Tindakan ini mereka lakukan dengan cara<br />
menculik perempuan-perempuan yang diduga<br />
menjadi mata-mata militer Indonesia dan<br />
kemudian membawanya ke dalam hutan dengan<br />
berjalan kaki puluhan kilometer. Selama dalam<br />
perjalanan tersebut perempuan tersebut diawasi<br />
dan mendapatkan pengawalan ketika ingin<br />
membersihkan diri. Sejumlah bentakan juga<br />
kerap mereka lakukan agar para sandera<br />
perempuan tersebut takut untuk melarikan diri.<br />
Dari sejumlah informasi yang berhasil<br />
dikumpulkan. pola penyiksaan dan perlakuan<br />
tidak manusiawi dan di wilayah konflik<br />
memiliki beberapa bentuk meliputi: dipukul,<br />
ditelanjangi, dipopor dengan senjata, ditendang<br />
dengan sepatu lars, diberi makan satu kali sehari,<br />
dilarang atau dibatasi ke WC, ditodong dengan<br />
senjata, disiram dengan air dingin, diperkosa,<br />
disuruh menyaksikan rekan setahanan disiksa<br />
atau diperkosa, dibentak, dibiarkan dalam<br />
keadaan telanjang di dalam tahanan atau tempat<br />
penyekapan, ditontoni saat sedang buang air kecil<br />
dan besar, diperintahkan berjalan jauh tanpa<br />
istirahat yang cukup, dibatasi menggunakan<br />
perlengkapan kewanitaan (pembalut atau<br />
peralatan yang lain) dan tak jarang dibunuh<br />
dengan cara ditembak.<br />
Khusus untuk tindak perkosaan sebagai<br />
bagian dari tindak penyiksaan, kasus-kasus ini<br />
meningkat pesat di Aceh dan Papua. Di Aceh,<br />
Komnas HAM mengaku mendapat laporan<br />
setidaknya 100 perempuan Aceh telah menjadi<br />
korban perkosaan, oleh militer/polisi dan<br />
kelompok pemberontak. 7<br />
2 Kasus-kasus Penyiksaan, tindakan<br />
tidak manusiawi, merendahkan martabat<br />
dan hukuman kejam di Tempat Bekerja<br />
Sejak diterpa krisis ekonomi, praktis roda<br />
ekonomi nasional mengalami kemacetan yang<br />
luar biasa. Akibatnya terjadi pengangguran<br />
besar-besaran dan pertambahan jumlah orang<br />
miskin yang luar biasa. Di lain pihak programprogram<br />
pemulihan ekonomi juga turut<br />
menambah jumlah pengangguran dan angka<br />
penduduk miskin. Persoalan ini pun juga<br />
membuat sektor pertanian ikut terpuruk dan<br />
menyebabkan banyak penduduk desa<br />
kehilangan mata pencaharian. Hilangnya<br />
pekerjaan ini menyebabkan perempuanperempuan<br />
di desa kemudian memilih untuk<br />
pergi ke kota atau ke luar negeri untuk menjadi<br />
pekerja rumah tangga. Banjir pekerja rumah<br />
tangga ini kemudian menjadikan bisnis<br />
penyalur tenaga kerja meningkat.<br />
Peningkatan kemunculan bisnis ini<br />
kemudian menimbulkan persoalan baru di<br />
mana, praktik-praktik kekerasan dalam bentuk<br />
penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
terhadap pekerja rumah tangga atau pekerja<br />
kasar di perkebunan atau perusahaan besar oleh<br />
para penyalur maupun majikan meningkat<br />
pesat. Sejumlah informasi menunjukkan bahwa<br />
tindak penyiksaan dan perlakuan kejam dan<br />
tidak manusiawi terhadap perempuan juga<br />
berlangsung di lokasi tempat bekerja. Korban<br />
terbesar dari kelompok ini adalah kelompok<br />
pekerja rumah tangga, para buruh perkebunan,<br />
buruh perusahaan dan pekerja seks komersial.<br />
Tempat kejadian dari kasus-kasus semacam ini<br />
paling banyak ditemui di lokasi apartement<br />
maupun rumah-rumah mewah, perkebunan<br />
besar, perusahaan besar, dan lokasi-lokasi<br />
prostitusi di Indonesia, Singapura, Malaysia,<br />
Hongkong dan Arab Saudi. Khusus untuk di<br />
perkebunan, praktik-praktik ini disebabkan<br />
karena kebanyakan dari para pekerja tersebut<br />
adalah para pekerja yang tidak memiliki ijin<br />
bekerja dari pemerintah setempat atau over stay<br />
karena tidak bisa pulang ke kampung asal<br />
karena tidak memiliki uang cukup.<br />
Dari sejumlah<br />
kasus yang berhasil<br />
dikumpulkan dan<br />
dipelajari, tindakan<br />
ini digunakan<br />
sebagai hukuman<br />
atas kelalaian atas<br />
kesalahan dari para<br />
pekerja rumah<br />
tangga pada saat<br />
menjalankan<br />
tugasnya. Tindakan<br />
ini juga terkait<br />
dengan metode<br />
kontrol terhadap<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
57
Kumpulan Kasus-kasus Penyiksaan dan Perkosaan Para Tenaga Kerja Indonesia di<br />
Kuwait 2003.<br />
Dalam jumpa pers di Wisma Bonang, Jakarta Pusat, salah satu TKW bernama Rina<br />
Arsita menuturkan bagaimana ia diperkosa majikan dan tiga anak lelakinya.<br />
“Mulanya Adnan, anak majikan saya, menyuruh membereskan kamar,” kata Rina,<br />
“tiba-tiba saya dibekap dan diperkosa.” Gadis asal Cianjur itu tak bisa berbuat apaapa<br />
karena Adnan mengancam akan membunuh dia.<br />
Petaka berikutnya terjadi ketika Rina keluar kamar mandi. Khalid, adik Adnan,<br />
merangsek dan memerkosanya. Anak majikannya yang ketiga memaksa Rina<br />
melakukan hubungan badan ketika ia sedang memasak. Di bawah ancaman, Rina<br />
pasrah diperlakukan apa pun. Penderitaannya kian lengkap ketika beberapa hari<br />
kemudian, Rina juga dipaksa majikannya.<br />
“Bagaimana mungkin saya berontak,” kata Rina yang fasih bahasa Arab ini, “tubuh<br />
mereka besar, sedangkan saya wanita dan lemah, apalagi diancam dibunuh.”<br />
Perlakuan itu sebenarnya pernah diadukan, tapi istri majikannya malah menuduh<br />
Rina menebar fitnah. “Mana mungkin suami dan anak-anakku memerkosa<br />
pembantu?” kata majikan perempuannya seperti ditirukan Rina.<br />
Pengaduan itu justru membuat Rina disiksa. Muka dan tubuhnya dihajar dengan<br />
sandal kayu sampai ia tak sadarkan diri. Rina kemudian kabur ke kantor polisi, tapi<br />
malah dipenjara karena paspornya ditahan majikan.<br />
Derita Rina juga dialami Sumini. Gadis asal Pati, Jawa Tengah, itu justru digagahi<br />
enam polisi ketika ia kabur dari tempatnya bekerja. Nestapa itu bermula ketika<br />
Ahmad, polisi setempat, menangkap Sumini karena ia tak memiliki kartu identitas.<br />
Bukannya dibawa ke kantor polisi, Sumini malah diboyong ke bar. “Di kamar bar itu<br />
saya diperkosa bersama lima temannya,” kata Sumini sambil terisak-isak. (Koran<br />
Tempo, 9 Oktober 2003)<br />
perempuan agar takut menuntut hak-hak<br />
mereka kepada majikannya. Di beberapa kasus<br />
juga ditemukan, tindakan ini dilakukan untuk<br />
menjaga agar praktik perkosaan yang dilakukan<br />
oleh majikan laki-laki tidak dilaporkan oleh<br />
korban kepada majikan perempuan.<br />
Dari berbagai kasus yang dikumpulkan dan<br />
dipelajari, pola penyiksaan dan perlakuan kejam<br />
dan tidak manusiawi ini mencakup: diancam<br />
akan dibunuh, dipukul dengan pengempuk<br />
daging (berbentuk palu), dicabuti alis matanya,<br />
kepala dibentur-benturkan ke dinding, disetrika,<br />
diikat dengan tali, dipukul dengan bola bilyard<br />
yang dibungkus dengan kain, dikunci di dalam<br />
kamar mandi, atau diperkosa berkali-kali. Di<br />
Cianjur, Seorang PRT, disiksa oleh majikannya<br />
dengan cara, disiram dengan air panas, disetrika,<br />
dan dipukuli. 8 Pelaku juga mengancam korban<br />
jika mengadukan perbuatannya ke pada orang<br />
lain. Di Bandung, seorang perempuan disiksa<br />
oleh suaminya karena hamil. 9 Perempuan itu<br />
disiksa dengan cara dipukul dan ditendang<br />
hingga mengalami infeksi telinga, luka memar di<br />
pinggul wajah dan kepala bagian belakang. Di<br />
Bandar Lampung, seorang perempuan disiksa<br />
oleh suaminya karena meminta uang belanja. 10<br />
perempuan tersebut disiksa dengan cara<br />
dipukuli hingga mengalami memar di bagian<br />
wajah dan kepala bagian belakang.<br />
3. Kasus-kasus Penyiksaan, perlakuan<br />
tidak manusiawi, merendahkan martabat<br />
dan hukuman Kejam di Dalam Rumah<br />
Tangga.<br />
Krisis ekonomi juga berakibat pada<br />
meningkatnya tindak penyiksaan, perlakuan<br />
tidak manusiawi, merendahkan martabat dan<br />
hukuman kejam terhadap perempuan di dalam<br />
rumah tangga. Kasus-kasus yang lebih dikenal<br />
sebagai domestic violence ini meningkat pesat<br />
sejak krisis ekonomi yang semakin permanen<br />
ini. Sejumlah organisasi pembela hak<br />
perempuan mengaku bahwa informasi praktik-<br />
58 Bagian V
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya di<br />
Pontianak, September 2003<br />
Ace sudah berkeluarga dengan AS selama 6<br />
tahun. Selama enam tahun itu, ia yang<br />
memenuhi kebutuhan keluarga karena<br />
suaminya menganggur. Pada suatu saat,<br />
Ace pulang terlambat dari tempat kerjanya<br />
karena satu hal. Keterlambatan Ace itu<br />
membuat AS marah dan kemudian<br />
menyiksa Ace dengan cara ditampar,<br />
dipukul, ditendang, dipukul dengan botol,<br />
dan dicambuk. Akibat kejadian tersebut, Ace<br />
mengalami luka berat di sekujur tubuhnya.<br />
Belakangan diketahui bahwa tindakan AS<br />
tersebut bukanlah yang pertama akan tetapi<br />
sudah berlangsung selama enam tahun.<br />
Korban mengaku selama enam tahun<br />
tersebut sudah 31 kali ia disiksa suaminya.<br />
praktik kejahatan kategori ini oleh para suami<br />
meningkat pesat. Tindakan ini ditujukan oleh<br />
para suami sebagai bagian dari hukuman atas<br />
kesalahan, ketidaksukaan sikap atau pernyataan<br />
yang dilontarkan oleh istri atau anak<br />
perempuannya. Selain itu, tindakan ini juga<br />
dilakukan sebagai bagian dari cara suami<br />
mencapai kenikmatan dalam hubungan seks.<br />
Mempelajari laporan dari para korban ini<br />
didapatkan pola kekerasan dalam kejahatan ini<br />
meliputi; memukul dengan benda-benda keras<br />
atau alat pemukul, menendang, menempeleng<br />
bagian kepala, membentur-benturkan kepala ke<br />
dinding, menyundut rokok, menyayat dengan silet<br />
atau benda tajam, disiram dengan air panas atau<br />
dingin, memaksa hubungan seks melalui anus<br />
dan atau memasukkan benda-benda keras ke<br />
dalam vagina serta pembatasan atau pelarangan<br />
untuk berhubungan dengan pihak di luar rumah,<br />
mengunci istri dalam kamar. Seorang pembela<br />
hak-hak perempuan di Bali mengungkapkan<br />
tentang adanya laporan perlakuan penyiksaan<br />
oleh seorang suami kepada istrinya dalam<br />
bentuk menyundut pantat istri dengan rokok<br />
ketika berhubungan seks. 11 Di Cilandak-Jakarta,<br />
seorang perempuan dipukul, ditendang dan<br />
dibentur-benturkan kepalanya ketembok secara<br />
terus menerus jika menolak untuk<br />
berhubungan seks. 12 Seorang Ibu di Jakarta<br />
menerima tekanan psikologis yang luar biasa<br />
akibat suaminya terus menyalahkan dirinya<br />
seperti seorang penjahat karena ia dianggap<br />
tidak becus mengurus anak sehingga anak<br />
mereka terjerat persoalan narkoba. 13<br />
Praktik-praktik kejahatan ini jarang sekali<br />
terungkap karena masih dianggap sebagai<br />
wilayah domestik. Selain itu juga perlu dicatat<br />
bahwa sistem pemerintahan terendah yakni<br />
pemerintah desa juga sangat jarang terlibat<br />
untuk menindaklanjuti laporan-laporan<br />
adanya indikasi kejahatan penyiksaan dalam<br />
keluarga.<br />
PENGINGKARAN NEGARA ATAS<br />
KEJAHATAN PENYIKSAAN,<br />
PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI,<br />
MERENDAHKAN MARTABAT DAN<br />
HUKUMAN KEJAM TERHADAP<br />
PEREMPUAN<br />
Dalam tindak penyiksaan dan perlakuan<br />
kejam, merendahkan martabat dan tidak<br />
manusiawi, sikap pemerintah Indonesia masih<br />
bungkam. Mereka justru menutup-nutupi dan<br />
cenderung memblok informasi-informasi<br />
berkaitan dengan tindak kejahatan seperti ini,<br />
terutama informasi-informasi tentang tindak<br />
penyiksaan, perlakuan kejam dan tindak<br />
manusiawi di wilayah konflik yang<br />
menggunakan metode perkosaan. Laporan<br />
sejumlah Ornop tentang adanya kasus-kasus<br />
perkosaan disangkal oleh penguasa militer di<br />
Aceh dengan alasan informasi tersebut tidak<br />
valid. 14 Meski dalam kasus di Aceh Utara,<br />
pemerintah dalam hal ini TNI menggelar<br />
penyelidikan dan pengadilan atas dugaan kasus<br />
perkosaan dan serangan seksual dalam rangka<br />
mendapatkan informasi tentang keberadaan<br />
kelompok pemberontak, namun upaya-upaya<br />
ini dianggap jauh dari keadilan korban. Para<br />
pelaku tidak dijerat dengan hukum hak asasi<br />
manusia nasional melainkan dengan<br />
menggunakan hukum militer yang hingga saat<br />
ini belum mengadopsi hukum hak asasi<br />
manusia nasional dan internasional. 15 Tak heran<br />
jika kemudian hukuman yang ditimpakannya<br />
pun sangat ringan karena hukum militer sangat<br />
lemah untuk bisa menjerat para pelaku<br />
kejahatan dalam kategori ini. Sejumlah pekerja<br />
hak asasi manusia dan pembela hak-hak<br />
perempuan bahkan menilai bahwa upaya<br />
penyelidikan ini merupakan bagian dari cara<br />
pemerintah meredam protes dunia<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
59
internasional. Di lain pihak, kelompok<br />
pemberontak pun melakukan upaya-upaya<br />
pengingkaran atas kejahatan penyiksaan dan<br />
perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap<br />
perempuan-perempuan yang diduga sebagai<br />
mata-mata pemerintah. Dengan mengatakan<br />
para perempuan tersebut adalah mata-mata<br />
pemerintah, kelompok pemberontak mengelak<br />
telah memaksa para perempuan yang mereka<br />
culik untuk berjalan jauh tanpa istirahat yang<br />
cukup. 16 Di samping itu upaya lain untuk<br />
menutup-nutupi kasus-kasus semacam ini<br />
adalah dengan mengancam para pembela hakhak<br />
perempuan yang ingin mengungkap<br />
sejumlah kasus-kasus penyiksaan. Baik militer/<br />
polisi dan kelompok pemberontak, kerap<br />
mengancam para pembela hak-hak perempuan<br />
dan hak asasi manusia yang vokal<br />
mengumumkan indikasi kuat tentang praktikpraktik<br />
penyiksaan, tindakan kejam,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
yang melibatkan anggota mereka. 17<br />
Demikian pula dengan kasus-kasus serupa di<br />
wilayah non-konflik, pemerintah juga<br />
cenderung bersikap serupa. Kasus-kasus seperti<br />
ini cenderung disebut sebagai kasus-kasus<br />
kriminal biasa – istilah mereka kasus<br />
penganiayaan – sehingga penanganannya pun<br />
sangat tidak memuaskan para korban.<br />
Kecenderungan untuk menafikkan kasus-kasus<br />
ini juga terlihat yakni dengan upaya-upaya<br />
melindungi para tersangka dengan cara<br />
mementahkan kesaksian para korbannya<br />
kurang didukung dengan hasil otopsi. 18 Bahkan<br />
langkah-langkah perlindungan terhadap para<br />
korban oleh sejumlah organisasi perempuan<br />
dan hak asasi manusia pun kerap mereka kecam<br />
dengan berbagai alasan. 19 Akibatnya banyak<br />
sekali praktik-praktik pengendapan proses<br />
penyelidikan atas kejahatan ini atau pelaku lolos<br />
dari jeratan hukum karena kurang bukti atau<br />
penghukuman yang sangat minim bagi para<br />
pelaku, terjadi sepanjang lima tahun terakhir.<br />
Khusus untuk kasus-kasus penyiksaan,<br />
perlakuan kejam, tidak manusiawi<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam<br />
yang terjadi di dalam rumah tangga; upaya<br />
pemerintah untuk menutup-nutupinya masih<br />
sangat kuat seperti ketika orde baru masih<br />
berkuasa. Meski akhir <strong>2004</strong> ini parlemen<br />
mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan<br />
perempuan dari tindak kekerasan dalam<br />
rumah tangga, pandangan dominan di kalangan<br />
pejabat pemerintah bahwa kejahatan untuk<br />
kategori ini adalah bukan kekerasan melainkan<br />
upaya suami mendidik istri, masih cukup kuat.<br />
Ketakutan bahwa para suami yang melakukan<br />
kekerasan akan dihukum cukup kuat<br />
berkembang sehingga ada upaya untuk<br />
menghentikan penerapan undang-undang<br />
kekerasan dalam rumah tangga ditangguhkan.<br />
Ini terlihat dengan sikap sebagian pihak di<br />
kalangan pejabat penegak hukum yang masih<br />
menunda pemberlakuan undang-undang ini<br />
dengan alasan belum adanya peraturan<br />
pemerintah tentang pekerja sosial. Padahal<br />
menurut para pembela hak-hak perempuan<br />
alasan penundaan ini sangat tidak masuk akal<br />
mengingat peraturan pemerintah tersebut<br />
bukanlah ketentuan hukum yang dapat<br />
menghambat penerapan dari undang-undang<br />
tersebut. 20<br />
KESIMPULAN<br />
Dari pemaparan tersebut menunjukkan<br />
bahwa praktik-praktik penyiksaan, perlakuan<br />
kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat<br />
dan hukum kejam, terjadi di seluruh level<br />
kehidupan. Kuatnya faham patriarki di tubuh<br />
pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh<br />
masyarakat ke dalam relasi interaksi laki-laki<br />
dan perempuan sehari-hari, menjadi dasar<br />
pembenaran atas praktik-praktik kekerasan<br />
dalam kategori ini. Praktik-praktik kekerasan<br />
terhadap perempuan dalam penerapan darurat<br />
militer atau operasi militer kemudian diadopsi<br />
oleh para pemilik modal dalam menjalankan<br />
praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan,<br />
dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi<br />
laki-laki dan perempuan tidak seimbang,<br />
menjadi akar utama atas terjadinya praktikpraktik<br />
kejahatan penyiksaan, perlakuan tidak<br />
manusiawi, merendahkan martabat dan<br />
hukuman kejam terhadap perempuan.<br />
Kondisi ini semakin diperburuk dengan<br />
minimnya inisiatif negara untuk mengambil<br />
langkah-langkah perlindungan dan<br />
penghormatan hak-hak perempuan dalam<br />
pelaksanaan agenda reformasi nasional.<br />
Minimnya produksi regulasi serta gagalnya<br />
mereduksi watak patriarki dalam struktur<br />
60 Bagian V
pemerintahan nasional hingga di level<br />
pemerintah desa akhirnya membuat kejahatan<br />
dalam kategori ini semakin menguat hingga ke<br />
seluruh sendi kehidupan masyarakat dan<br />
kemudian menjadi tindak kejahatan yang<br />
endemik. Pada akhirnya banyak perempuan di<br />
Indonesia yang berujar “Tidak ada satu tempat<br />
aman pun bagi kami di tanah Indonesia ini.”<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Terjemahan Indonesianya adalah “kekerasan antara.”<br />
Kekerasan antara yang dimaksud di sini adalah bahwa<br />
kekerasan ini dilakukan untuk membuat para<br />
pemberontak berhenti melakukan aksi-aksi<br />
penyerangan kepada markas militer atau pasukanpasukan<br />
militer.<br />
2<br />
Lih, Widodo, Sri Wiyanti, “Pembakuan Peran dan<br />
Kebijakan-kebijakan di Indonesia,” Agustus 1998;<br />
Wilujeng Henry, SH., Habsjah, Attashendarti., Setya<br />
Wibawa, Dhevi., “Dampak Pembakuan Peran Jender<br />
Terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah<br />
di DKI Jakarta”, Januari 2002<br />
3<br />
Inserta tentang Pemda NTB yang mencoba membuat<br />
perda tentang Pengiriman TKI ke luar negeri.<br />
4<br />
Regulasi nasional pembentukan Komnas Perempuan<br />
hanya memberikan mandat kepada Komisi dalam<br />
lingkup pendidikan, penelitian dan pelaporan rutin<br />
tentang situasi hak-hak perempuan di Indonesia.<br />
Belum ada upaya dari pemerintah dan parlemen untuk<br />
melakukan evaluasi atas regulasi tersebut.<br />
5<br />
Pada periode 1999-<strong>2004</strong> kewenangan penanganan<br />
persoalan-persoalan perempuan masih berada di<br />
bawah Komisi VIII yang membidangi bidang<br />
pertambang dan energi. Penempatan ini menunjukkan<br />
bahwa persoalan perempuan memang bukan menjadi<br />
agenda besar dari kerja DPR-RI 1999-<strong>2004</strong>.<br />
6<br />
Anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo<br />
menuturkan: ada pemeriksaan terhadap kaum<br />
perempuan yang diduga sebagai Inong Balee (tentara<br />
perempuan GAM). Pemeriksaan dilakukan aparat<br />
dengan cara yang tidak simpatik, karena pemeriksaan<br />
mengharuskan yang diperiksa untuk membuka bagian<br />
dada. Pasalnya, ada kecurigaan kalau di bagian dada<br />
terdapat tanda bulan bintang. “Ada kakak beradik yang<br />
mengalami seperti itu. Bahkan ketika ibunya memohon<br />
agar membuka, juga tidak dibolehkan,” ujarnya. Lih.,<br />
“Komnas HAM Sudah Cek Ulang Kekerasan Seksual di<br />
Aceh,” Sinar Harapan, 20 Juni 2003.<br />
7<br />
Lih., “Soal Perkosaan 100 Perempuan Aceh, Komnas<br />
Selidiki, Korps TNI Membantah,” Kompas, 2 September<br />
2003.<br />
8<br />
Kumpulan Dokumentasi, Tentang Kekerasan<br />
Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di 13 Kota<br />
Besar di Indonesia Periode 2003-<strong>2004</strong>, milik Mitra<br />
Perempuan WCC, Institut Perempuan Bandung,<br />
Lentera Perempuan Purwokerto, SPEK-HAM Surakarta,<br />
WCC Jombang, KKTG Aceh, Cahaya Perempuan<br />
Bengkulu, Damar Lampung, WCC Palembang, YLBH-<br />
PIK Pontianak, Swara Parangpuan Manado, LBH-P2i<br />
Makasar, Rumah Perempuan Makasar.<br />
9<br />
Ibid.<br />
10<br />
Ibid.<br />
11<br />
Penuturan Pembela Hak-hak Perempuan dalam rapat<br />
konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember <strong>2004</strong>.<br />
12<br />
Wawancara korban dengan voulenteer Suara Ibu<br />
Peduli di Jakarta, Pertengahan 2003.<br />
13<br />
Penuturan Perempuan dalam Acara Tutur<br />
Perempuan, di Jakarta, September <strong>2004</strong>.<br />
14<br />
Pangkoops Mayjen Bambang Darmono: “Tuduhan<br />
ketujuh LSM itu tidak benar.Laporan itu tidak benar, itu<br />
hanya isu murahan. Saya tidak suka kalau hanya<br />
mengumbar isu, berdasarkan data lewat SMS yang<br />
dikirim sekelompok orang”. Menurut ia, kejadian yang<br />
menimpa gadis bernama M (16) pada malam perayaan<br />
17 Agustus itu dilakukan lima pelaku yang kesemuanya<br />
adalah warga sipil. Lih., “Komnas Cari Saksi<br />
Perkosaan,” Media Indonesia, 2 September 2003.<br />
15<br />
Prajurit Kepala Seprianus Lau Webang 3 tahun 6<br />
bulan, sedangkan Husni Dwila divonis 3 tahun, dan<br />
Awaluddin divonis 2 tahun 6 bulan. Vonis kepada<br />
masing-masing terdakwa lebih rendah 6 bulan dari<br />
tuntutan oditur militer. Majelis Hakim juga<br />
memerintahkan ketiganya untuk tetap ditahan., lih.,<br />
“Anggota TNI Pemerkosa Wanita Aceh Dihukum<br />
Penjara dan Dipecat,” Kompas, 20 Juli 2003.<br />
16<br />
Pertengahan Juni, GAM dilaporkan telah menculik<br />
dua orang istri perwira militer dengan tuduhan kedua<br />
orang tersebut menjadi mata-mata RI. Kedua<br />
perempuan tersebut kemudian dipaksa untuk berjalan<br />
jauh masuk hutan dan tinggal berpindah-pindah<br />
berbulan-bulan dengan pembatasan atas kebutuhankebutuhan<br />
kewanitaan mereka.<br />
17<br />
Para pembela hak-hak perempuan dan hak asasi<br />
manusia di Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Sampit<br />
kerap diancam orang-orang tidak kenal ketika<br />
mencoba mengumumkan indikasi kuat kasus-kasus<br />
penyiksaan, tindakan kejam, perlakuan tidak<br />
manusiawi serta hukum kejam yang dialami oleh<br />
perempuan.<br />
18<br />
Para pejabat penegak hukum kerap mementahkan<br />
kesaksian korban dengan cara melontarkan komentarkomentar<br />
yang bisa membuat publik menjadi ragu<br />
dengan kesaksian korban. Seperti dalam kasus<br />
penyiksaan Yuliasih di Jakarta oleh majikannya,<br />
September 2003, Kepala Unit Kriminal Umum Polres<br />
Jakarta Timur Ajun Komisaris Soeharto, 15 September<br />
2003 mencoba mementahkan kesaksian korban<br />
dengan mengatakan: “ Itu semua baru dugaan, karena<br />
hasil visum belum kami terima.” Lih., “Lagi PRT<br />
Disiksa Majikannya,” Kompas, 16 September 2003<br />
19<br />
Lih., “Depnaker Pertanyakan Motif Penjemputan 19<br />
TKI oleh LSM,” Tempo Interaktif, 9 Oktober 2003:<br />
Melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga<br />
Kerja Luar Negeri, pemerintah mempertanyakan motif<br />
penjemputan 19 orang TKI oleh organisasi pembela<br />
hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Dirjen<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
61
tersebut juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan<br />
oleh organisasi-organisasi tersebut menyalahi aturan<br />
pemerintah tentang penjemputan para tenaga kerja<br />
yang baru pulang dari luar negeri.<br />
20<br />
Wawancara dengan pekerja pembela hak-hak<br />
perempuan di jakarta, November -Desember <strong>2004</strong><br />
62 Bagian V
BAGIAN KEENAM<br />
Kesimpulan dan Rekomendasi<br />
Selama periode 1999 – <strong>2004</strong>, komitmen<br />
nasional penegakan HAM telah<br />
mengalami kemajuan yang signifikan.<br />
Komitemen penegakan HAM ini tercantum<br />
dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh<br />
lembaga negara dan pemerintah. Sumbersumber<br />
yang menjadi masalah terjadinya<br />
pelanggaran HAM telah menjadi komitmen<br />
untuk dibenahi. Reformasi regulasi yang<br />
menjamin tegaknya HAM telah berjalan dan<br />
secara normatif telah banyak regulasi yang<br />
memberikan perlindungan terhadap hak asasi<br />
manusia. Korban pelanggaran hak asasi manusia<br />
juga secara normatif mendapatkan jaminan<br />
untuk pemulihan kepada mereka. Korban telah<br />
dijamin oleh UU bahwa mereka berhak<br />
mendapatkan keadilan dan reparasi. Jaminan<br />
bahwa keadilan kepada korban ini akan<br />
diwujudkan adalah adanya reformasi regulasi<br />
yang memberikan perlindungan hak asasi<br />
manusia regulasi atas peradilan yang adil serta<br />
regulasi yang mengatur tentang hak-hak<br />
korban.<br />
Tersedianya regulasi yang memadai ternyata<br />
tidak serta merta membawa keadilan bagi<br />
korban, karena jajaran birokrasi, judiciary<br />
(Kehakiman), Kejaksaan, dan Polisi tidak siap<br />
untuk melaksanakan regulasi-regulasi tersebut.<br />
Disamping itu juga masih kentalnya resistensi<br />
dari institusi yang terkena imbas dari reformas<br />
regulasi tersebut. Praktis, macetnya reformasi<br />
institusi tersebut tidak ekuivalen dengan<br />
kemajuan regulasi. Hasilnya adalah tidak<br />
tuntasnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang terjadi sehingga capaian kearah<br />
keadilan dan pemulihan kepada korban gagal.<br />
Pada tingkat implementasi, ternyata proses<br />
keadilan kepada korban tidak juga beranjak<br />
naik. Pengadilan-pengadilan yang dilakukan<br />
untuk mengadili pelaku tidak lebih hanya<br />
peradilan yang “asal ada” untuk memenuhi<br />
ketentuan undang-undang atau tuntutan<br />
korban. Kebenaran tidak terungkap, pelaku<br />
dinyatakan bebas dan korban tidak<br />
mendapatkan kompensasi adalah akhir cerita<br />
yang bisa ditebak sejak awal.<br />
Lambatnya proses perbaikan hak asasi<br />
manusia di Indonesia semakin diperburuk oleh<br />
langkah-langkah pemerintahan transisi untuk<br />
menghadapi berbagai persoalan politik<br />
ekonomi menonjol dalam lima tahun terakhir.<br />
Penerapan regulasi kedaruratan dan pengerahan<br />
kekuatan militer untuk menyelesaikan berbagai<br />
persoalan pemberontakan, konflik sosial dan<br />
perang melawan terorisme adalah sebuah<br />
kemunduran dari langkah-langkah penegakan<br />
hak asasi manusia oleh pemerintah transisi.<br />
Penggunaan langkah-langkah militer dalam<br />
penyelesaian persoalan pemberontakan konflik<br />
komunal dan perang melawan terorisme justru<br />
menjadi penyebab peristiwa pelanggaran hak<br />
asasi manusia baru.<br />
Tercatat masih terdapat pelanggaran HAM<br />
yang menonjol terjadi sepanjang 1999-<strong>2004</strong><br />
yakni masih terjadinya pembunuhan kilat dan<br />
diluar proses hukum, penangkapan dan<br />
penahanan sewenang-wenang, penyiksaan,<br />
tindakan kejan dan tidak menusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukuman kejam,<br />
orang hilang pembatasan ruang gerak dan<br />
pencabutan hak untuk mengelurakan pendapat<br />
dan kejahatan-kejahatan terhadap pekerja<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
63
kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang terjadi<br />
tersebut tidak direspon oleh negara secara<br />
memadai karena tertutup oleh kepentingan<br />
untuk menjaga keutuhan negara kesatuan RI.<br />
Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak<br />
direspon atau diselesaikan secara tuntas di mana<br />
berbagai upaya penyelidikan selalu terhambat<br />
dan legitimasi untuk melakukan kekerasan<br />
adalah cara yang tepat karena tindakan ini<br />
ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI.<br />
Kondisi di atas semakin menjauhkan<br />
pemerintah terhadap akar pokok masalah dari<br />
persoalan pemberontakan, konflik sosial dan<br />
keberadaan organisasi-organisasi keagamaan<br />
garis keras di Indonesia. Langkah-langkah<br />
seperti itu hanya menghasilkan kembali<br />
terbukanya peluang kebangkitan sistem otoriter<br />
di Indonesia.<br />
Di lain pihak, proses desentralisasi kekuasaan<br />
dalam kerangka Otonomi daerah di Indonesia<br />
pada akhirnya justru membuat penduduk lokal<br />
semakin tidak percaya dengan pemerintah<br />
daerah. Tak ubahnya seperti rezim Suharto,<br />
dengan alasan memacu pertumbuhan ekonomi<br />
daerah, pemerintah daerah kembali<br />
menghadapi perlawanan penduduk lokal atas<br />
sejumlah rencana pembanguan daerah dengan<br />
cara-cara kekerasan. Implementasi otonomi<br />
daerah selanjutnya menimbulkan upaya-upaya<br />
pemerintah daerah untuk menggencarkan<br />
penggalian atas potensi kekayaan alam dan<br />
kekayaan non-alam untuk menambah<br />
pendapatan daerah. Tindakan-tindakan<br />
tersebut menimbukan ketegangan-ketegangan<br />
antara pemerintah daerah dengan pusat<br />
menyamgkut perimbangan keuangan. Konflik<br />
lainnya adalah ketegangan ditingkat elit lokal<br />
yang memperebutkan kekuasaan. Lagi-lagi<br />
masyarakat yang menjadi korban atas<br />
pertarungan politik dan kekuasaan ini. Otonomi<br />
daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan<br />
dan penegakan pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika<br />
membangun institusi dan struktur<br />
pemerintahan otonom. Dalam janga watu<br />
tersebut, muncul berbagai regulasi daerah yang<br />
anti hak asasi manusia dan makin maraknya<br />
pengusiran paksa. Pengusiran paksa dari tahun<br />
1999-<strong>2004</strong> semakin menunjukkan grafik yang<br />
meningkat. Pengusiran paksa ini dilakukan<br />
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan<br />
hukum dan di mana tidak ada cukup negosiasi<br />
antara warga dengan pemerintah dan tidak<br />
memadainya ganti rugi kepada korban.<br />
Pemerintah daerah pun terus-menerus<br />
melakukan pengingkaran atas terjadinya<br />
kejahatan hak asasi manusia ini. Akibat dari<br />
proses otonomi daerah yang tidak berjalan<br />
secara baik ini, penduduk lokal kembali harus<br />
menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan dan<br />
pelanggaran hak asasi manusia aparatur<br />
pemerintah propinsi dan kabupaten.<br />
Minimnya produksi regulasi serta kegagalan<br />
mereduksi watak patriarki dalam struktur<br />
pemerintahan nasional hingga desa akhirnya<br />
membuat kejahatan dalam kategori ini semakin<br />
menguat hingga ke seluruh sendi kehidupan<br />
masyarakat dan kemudian menjadi tindak<br />
kejahatan yang endemik. Proses upaya-upaya<br />
perbaikan perlindungan hak-hak terhadap<br />
perempuan yang terdiri atas refomasi hukum,<br />
reformasi institusi, pengungkapan kasus dan<br />
penghukuman tidak berjalan secara linear.<br />
Bahkan tidak ada satupun kompensasi, restitusi<br />
dan rehabilitasi kepada korban kekerasan<br />
terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan<br />
bahwa perlindungan terhadap hak-hak<br />
perempuan masih rendah dan akibatknya gejala<br />
kekerasan akan terus terjadi sehingga sampai<br />
saat ini bisa dikatakan tidak ada tempat aman<br />
bagi perempuan. Kuatnya faham patriarki di<br />
tubuh pemerintahan yang kemudian diadopsi<br />
oleh masyarakat ke dalam relasi interaksi lakilaki<br />
perempuan sehari-hari, menjadi dasar<br />
pembenaran atas praktik-praktik kekerasan<br />
terhadap perempuan. Praktik-praktik kejahatan<br />
terhadap perempuan dalam penerapan darurat<br />
militer atau operasi militer kemudian diadopsi<br />
oleh para pemilik modal dalam menjalankan<br />
praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan,<br />
dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi<br />
yang tidak seimbang antara laki-laki dengan<br />
perempuan, menjadi akar utama atas terjadinya<br />
praktik-praktik kejahatan penyiksaan,<br />
perlakuan tidak manusiawi, merendahkan<br />
martabat dan hukuman kejam terhadap<br />
perempuan. Kondisi ini semakin diperburuk<br />
dengan kegagalan dari negara untuk mengambil<br />
langkah-langkah perlindungan dan<br />
penghormatan hak-hak perempuan dalam<br />
proses menjalankan agenda reformasi nasional.<br />
Negara secara terus menerus melakukan<br />
64 Bagian VI
pengingkaran atas kejahatan penyiksaan,<br />
perlakuan tidak manusiawi, merendahkan<br />
martabat dan hukuman kejam terhadap<br />
perempuan. Berbagai upaya penyelidikan untuk<br />
menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap<br />
perempuan selalu menghadapi hambatan<br />
terutama jika kasus-kasus tersebut terjadi di<br />
wilayah konflik. Meskipun ada beberapa kasus<br />
kekerasan terhadap perempuan tetapi proses<br />
penghukuman terhadap para pelaku jauh dari<br />
kesan adil karena hukuman yang dijatuhkan<br />
sangat ringan. Data menunjukkan bahwa<br />
pengungkapan kasus kekerasan terhadap<br />
perempuan berada dalam skala yang tinggi<br />
namun penghukuman terhadap pelaku<br />
menempati skala yang terendah.<br />
REKOMENDASI:<br />
Kepada Pemerintah Nasional:<br />
1. Melanjutkan proses reformasi regulasi yang<br />
belum lengkap diantaranya terhadap berbagai<br />
UU yang belum dibentuk yang seharusnya<br />
menjadi bagian dari regulasi yang lain. UU<br />
tersebut diantaranya adalah UU Perlindungan<br />
Saksi dan Korban, UU mengenai Kompensasi,<br />
Restitusi dan Rehabilitas, UU mengenai<br />
Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik,<br />
UU mengenai Ratifikasi Konvensi hak-hak<br />
Ekonomi, Sosial dan Budaya.<br />
2. Melakukan amandemen terhadap regulasi/<br />
UU yang masih banyak mempunyai kendala<br />
subtansial dan tidak sinkron dengan regulasi<br />
lainnya. UU tersebut diantaranya Kitab<br />
Undang-undang Hukum Pidana, UU Hukum<br />
Acara Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang<br />
Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000<br />
tentang Pengadilan HAM, Kitab Undang-<br />
Undang Hukum Pidana Militer<br />
3. Mencabut regulasi yang masih tersisa yang<br />
bertentangan dengan HAM terutama yang<br />
bertentang dengan Ketentuan mengenai hak<br />
asasi manusia di UUD 1945.<br />
4. Lembaga-lembaga pelaksana regulasi harus<br />
melakukan reformasi internal untuk<br />
menghilangkan warisan watak orde baru<br />
sehingga reformasi regulasi yang terjadi juga<br />
diimbangi dengan perubahan internal di<br />
lembaga-lembaga tersebut.<br />
5. Mengembalikan penyelesaian persoalan<br />
sparatisme dan konflik sosial serta perang<br />
melawan terorisme melalui cara-cara damai,<br />
dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan<br />
kekuatan bersenjata dalam penyelesaian<br />
sparatisme dan konflik sosial serta perang<br />
melawan terorisme.<br />
6. Mempercepat proses reformasi di tubuh<br />
kepolisian yakni dengan membuat :<br />
a) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban<br />
internal hingga dapat<br />
menyeret para pelanggar dari kalangan<br />
perwira menengah dan atas<br />
b) Membenahi prosedur-prosedur<br />
pengamanan demonstrasi dan<br />
penggusuran, penertiban kawasan<br />
perdagangan liar dan konflik-konflik<br />
sumber kekayaan alam<br />
c) Membenahi standar-standar tentang<br />
pengerahan kekuatan Brimob dalam<br />
penanganan huru hara dan operasi-operasi<br />
penegakan hukum, termasuk di sini<br />
memperkuat mekanisme pertanggungjawaban<br />
internal di lingkungan kesatuan<br />
tersebut.<br />
d) Meningkatkan kapasitas pemahaman<br />
hak asasi manusia di kalangan anggota<br />
yang juga didukung dengan peningkatan<br />
kesejahteraan keluarga.<br />
e) Membuat buku saku hak asasi manusia<br />
bagi anggota Polri di lapangan.<br />
7. Mempercepat proses reformasi di tubuh<br />
TNI yakni dengan:<br />
a) Mempercepat proses reformasi di<br />
institusi tersebut dengan menjadikan dasar<br />
UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU Nomor<br />
34 Tahun <strong>2004</strong> sebagai kerangka acuan<br />
percepatan proses reformasi internal.<br />
b) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban<br />
internal, terutama untuk<br />
menjerat para pelaku dari kalanganj<br />
perwira menengah dan tinggi, termasuk<br />
juga membenahi administrasi peradilan di<br />
institusi peradilan militer.<br />
c) Meningkatkan pelatihan-pelatihan hak<br />
asasi secara berkala di kalangan prajurit<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
65
terutama di kalangan perwira muda.<br />
8. Mempercepat proses reformasi di institusi<br />
kejaksaan yakni dengan:<br />
a) Membuka akses kepada publik atas<br />
transparansi penanganan kasus-kasus yang<br />
selama ini tidak jelas penanganannya dan<br />
mandeg di Kejaksaan Agung.<br />
b) Membuat petanggungjawaban atau<br />
akuntabilitas dengan menjelaskan kepada<br />
publik tentang berbagai proses penuntutan<br />
yang mengalami kegagalan terutama<br />
dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang<br />
berat.<br />
c) Membuat kursus hak asasi manusia<br />
berkala bagi Jaksa.<br />
9. Mempercepat proses reformasi di institusi<br />
pengadilan yakni dengan:<br />
a) Melanjutkan proses reformasi internal<br />
lembaga pengadilan di bawah kewenangan<br />
Mahkamah Agung baik bidang<br />
administrasi pengadilan maupun<br />
peningkatan sumber daya manusianya.<br />
b) Menggelar kursus hak asasi manusia<br />
bagi hakim secara berkala.<br />
c) Membuka akses publik yang seluasluasnya<br />
atas proses peradilan.<br />
Kepada Pemerintah Daerah:<br />
1. Melakukan audit terhadap regulasi daerah<br />
dengan menggunakan konstitusi dan hukum<br />
hak asasi manusia sebagai indikator audit dan<br />
selanjutnya mencabut regulasi daerah yang<br />
bertentangan dengan konstitusi dan hukum hak<br />
asasi manusia nasional<br />
2. Membuat regulasi-regulasi di tingkat<br />
daerah untuk mendorong pelaksanaan hukum<br />
hak asasi manusia nasional di tingkat daerah<br />
3. Mengembalikan fungsi Satuan Polisi<br />
Pamong Praja sebagai satuan pengaman internal.<br />
4. Menyelenggarakan training hak asasi<br />
manusia bagi aparatur pemerintahan daerah<br />
secara berkala dengan mengundang para<br />
pengajar dari kalangan akademisi dan praktisi<br />
hak asasi manusia.<br />
5. Membuka Kantor Perwakilan Komisi<br />
Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayahnya dan<br />
bekerjsama dengan Komnas HAM untuk<br />
melakukan pemantauan kondisi hak asasi<br />
manusia di daerahnya secara periodik.<br />
6. Mempublikasikan laporan kondisi hak<br />
asasi manusia di daerahnya secara periodik<br />
kepada publik lokal.<br />
Kepada DPRD di Seluruh Indonesia:<br />
1. Membentuk Komisi hak asasi manusia,<br />
seperti yang sudah dilakukan oleh DPRD<br />
Propinsi Papua<br />
2. Mengambil insiatif pembuatan regulasiregulasi<br />
hak asasi manusia di tingkat daerah.<br />
3. Mengawasi pelaksanaan perlindungan hak<br />
asasi manusia yang dilakukan oleh kepala<br />
daerah.<br />
4. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk<br />
merumuskan kerangka pembangunan hak asasi<br />
manusia di tingkat daerah.<br />
REKOMENDASI KHUSUS<br />
Kepada Pemerintah Nasional<br />
1. Menggelar penyelidikan kasus-kasus<br />
penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi,<br />
merendahkan martabat dan hukum kejam<br />
terhadap kelompok perempuan untuk<br />
membuktikan informasi kejahatan semacam ini<br />
di berbagai daerah.<br />
2. Mempercepat proses perbaikan kondisi<br />
hak-hak perempuan, dengan mengambil<br />
langkah-langkah pembuatan kebijakan di<br />
tingkat nasional.<br />
3. Mengefektifkan fungsi Komnas Perempuan<br />
yakni dengan memberikan mandat Penyelidikan<br />
atas kasus-kasus kejahatan terhadap<br />
perempuan.<br />
Kepada TNI/POLRI:<br />
1. Mendorong penghormatan hak-hak<br />
perempuan di kalangan prajurit/anggota-nya,<br />
khususnya bagi mereka yang sedang bertugas di<br />
daerah-daerah konflik<br />
2. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk<br />
menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, perlakuan<br />
tidak manusiawi, merendahkan martabat dan<br />
66 Bagian VI
hukuman kejam terhadap perempuan yang<br />
diduga dilakukan oleh anggota TNI/Polri di<br />
daerah-daerah konflik.<br />
3. Memasukkan ketentuan perlindungan<br />
hak-hak perempuan dalam amandemen kitab<br />
undang-undang hukum pidana militer<br />
4. Menyelenggarakan pendidikan yang<br />
berkala berkaitan dengan perlindungan,<br />
penghormatan dan pemajuan hak-hak<br />
perempuan.<br />
Kepada Pemerintah Daerah:<br />
1. Mempercepat proses perbaikan kondisi<br />
hak-hak perempuan, dengan mengambil<br />
langkah-langkah pembuatan kebijakan di<br />
tingkat daerah untuk mendorong dan<br />
memperkuat pelaksanaan regulasi perlidnungan<br />
hak-hak perempuan nasional<br />
2. Mendirikan Komisi pemantuan hak-hak<br />
perempuan di tingkat daerah dan memasukan<br />
biaya operasional komisi tersebut ke dalam<br />
anggaran belanja negara/daerah.<br />
Kepada DPR dan DPRD:<br />
Membentuk komisi khusus yang bertugas<br />
merumuskan kebijakan tentang perlindungan<br />
hak-hak perempuan dan mengawasi<br />
pelaksanaan perlindungan dan penghormatan<br />
hak-hak perempuan di tingkat nasional dan<br />
daerah.<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
67